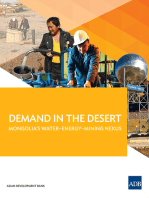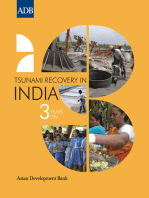Professional Documents
Culture Documents
Pemikiran Perorganisaian M, H
Pemikiran Perorganisaian M, H
Uploaded by
Rido ZulkarnainOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Pemikiran Perorganisaian M, H
Pemikiran Perorganisaian M, H
Uploaded by
Rido ZulkarnainCopyright:
Available Formats
Pengorganisasian Masyarakat Desa Mandiri Energi
Studi Kasus PLTMH di Desa Palakka, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
YANU ENDAR PRASET YO
Peneliti di Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna (B2PTTG) LIPI Email: yanu002@lipi.go.id
UMI HANIFAH
Peneliti di Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna (B2PTTG)-LIPI Email: umih002@lipi.go.id
AB STRACT Villages in Indonesia which are less fortunate geographically and economically, has always been the main target of development interventions, either through discourse lagging rural development, Independent Energy Village (DME), Independent Food Village and so forth. Developmentalism as an ideology of the entire state apparatus is then gave birth to mainstream intervention strategies based on the idiom as economic growth, productive activities, acceleration, expansion of scale and indicators of material as a marker of other progress. Thus, the development of villages through any discourse, in its essence has always positioned the local community with all the original knowledge in a position subordinate to the state. On the issue of energy needs of rural communities, it is very interesting to examine the development process DME between the complex interests (local actors vs. intervener, calculations of scientists vs. local calculation, as well as between research vs. development). This study found that lack of community organizing and political interests of different government agencies with the needs of local communities, as well as role conflict on the actors at the micro level (operators, Micro Hydro Power officials, village heads and district governments) will determine the future utilization of this Micro Hydro Power. Keywords : DME, Micro Hydro Power, Community Organizing, Palakka
72
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
PENDA HULUA N
Pada tanggal 20 Februari 2007 Pemerintah telah mencanangkan program Desa Mandiri Energi (DME). Pencanangan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan, Grobogan Jawa Tengah. DME merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan energi di kawasan perdesaan dan menjadikan kegiatan penyediaan energi sebagai titik masuk dalam pengembangan kegiatan ekonomi perdesaan. Untuk mewujudkan DME diupayakan beberapa program yang saling mendukung, seperti pemanfaatan energi setempat baik untuk listrik maupun bahan bakar dan potensi penciptaan kegiatan produktif. Di Indonesia, program ini berada di bawah payung program besar penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra). Program pembangunan semacam ini jelas bertujuan untuk pengembangan dan pertumbuhan yang bersifat ekonomi (peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas) yang menurut kalkulasi pemerintah pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Secara konseptual , DME merupakan upaya pemerintah untuk membangun desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energi (listrik dan bahan bakar) dari sumber energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat. Kriteria dari sumber daya energi setempat ini mencakup basis energi non-bahan bakar nabati (BBN) seperti mikro hidro, tenaga angin, tenaga surya, biogas dan biomassa serta yang berbasis energi bahan bakar nabati (BBN) seperti jarak pagar, kelapa, sawit, singkong, dan tebu. Kesadaran atas pentingnya penyediaan sumber energi lain selain fuel, mendorong pesatnya riset dan pengembangan berbagai energi alternatif seperti energi hidroelektrik, energi biomas, energi angin, energi surya, energi sel hidrogen, energi panas bumi, dan energi biogas yang relatif tidak mengancam ketersediaan pangan secara langsung (Pimentel & Pimentel, 2010). Target pemerintah dalam pengembangan DME sampai dengan tahun 2009 adalah sebanyak 1000 DME berbasis non-BBN dan 1000 DME berbasis BBN dengan sasaran utama adalah desa miskin, desa daerah tertinggal, desa transmigrasi, desa pesisir, desa pulau kecil, dan desa daerah perbatasan (DJLPE , 2007). Menurut Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
73
merupakan salah satu kabupaten yang masuk daerah tertinggal. Begitu juga dengan Desa Palaka, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, berdasarkan survei sosial ekonomi yang dilakukan Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna (B2PTTG) tahun 2007, desa ini termasuk dalam kategori desa miskin secara ekonomi dan infrastruktur. Sampai pada awal tahun 2007 Desa Palakka yang berada di Kecamatan Maiwa , Kabupaten Enrekang , belum teraliri listrik. Hingga akhirnya di desa ini dibangun sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 50 kW hasil kerjasama B2PTTG, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Secara teknis, unit PLTMH Palakka terdiri dari bendung, saluran penyadap, bak penenang, pipa penstok, rumah pembangkit termasuk di dalamnya turbin generator dan kontrol, serta jaringan distribusi dan instalasi ke rumah-rumah konsumen. PLTMH Palakka dapat menerangi seluruh Desa Palakka yang terdiri dari tiga dusun, 116 bangunan yang terdiri dari rumah tinggal (pemukiman) serta beberapa bangunan umum yang ada di desa itu meliputi masjid, kantor desa, puskesmas pembantu, dan SD. Sejak pertengahan tahun 2010 terjadi perubahan kebijakan pengelolaan PLTMH di Kabupaten Enrekang. Hal ini didasarkan pada dikeluarkannya Peraturan Bupati Enrekang No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Berdasarkan peraturan ini, pengelolaan PLTMH diserahkan kepada camat masingmasing wilayah dengan membentuk badan pengelola dalam bentuk Badan Usaha Desa (BUD). Padahal, sejak proses pembangunan PLTMH, kecamatan bukanlah institusi yang terlibat secara penuh. Perubahan tata kelola PLTMH dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) kepada masing-masing kecamatan ini membawa implikasi yang serius terhadap pengaturan PLTMH, khususnya terkait pembagian wewenang dan tindakan-tindakan pemecahan masalah di lapangan. Kecamatan yang tidak memahami seluk-beluk pengelolaan PLTMH ini kemudian menyerahkan tanggung jawab kepada kepala desa, sebagai kepanjangan tangan birokrasinya. Sayangnya, di level desa sendiri terjadi konflik horizontal (antar warga/pelanggan) yang bersifat laten, terutama terkait dengan penetapan pemanfaatan dan iuran PLTMH yang dirasakan pelanggan tidak adil. Pada konteks inilah penelitian ini mencoba untuk mencari akar permasalahan yang terjadi yakni dengan mendengarkan dan mempertemukan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
74
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
PLTMH, dalam hal ini adalah bupati, Distamben, camat, pemerintahan desa, dan masyarakat pelanggan PLTMH itu sendiri.
Bupati Bupati
Distamben
Distamben
Kecamatan
Kepala Desa
Kepala Desa
Pengurus PLTMH Masyarakat/ Pelanggan
Pola 1, sebelum Peraturan Bupati no 12 tahun 2010
Pengurus PLTMH/BUD Masyarakat/ Pelanggan
Pola 2, sesudah Peraturan Bupati no 12 tahun 2010
= garis instruksi pengelolaan PLTMH = garis koordinasi/konsultatif pengelolaan PLTMH Gambar 1. Perubahan Pola Pengelolaan PLTMH di Kabupaten Enrekang- Sulawesi Selatan sebelum dan sesudah Peraturan Bupati no 12 Tahun 2010 tentang pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
Pembangunan Desa Mandiri Energi (DME) ini merupakan salah satu program pembangunan nasional yang kemudian secara politik diadopsi menjadi salah satu platform utama pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Selama lima tahun (2005-2010), kabupaten ini telah berhasil membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebagai entry point DME - dari 1 unit menjadi 12 unit. Desadesa yang selama ini gelap dan terisolir, menjadi terang dan terbuka karena energi listrik yang menerangi desa itu. Akan tetapi seperti diungkap sebelumnya - proses pembangunan DME ini tidaklah semulus yang diharapkan. Pihak pembangun PLTMH memiliki harapan-harapan tertentu terhadap pemanfaatan PLTMH ini oleh masyarakat, seperti tumbuhnya usaha produktif berbasis energi PLTMH. Hal ini didasari oleh kenyataan
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
75
bahwa pada siang hari, energi listrik dari PLTMH ini tidak banyak digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, daripada energi ini terbuang begitu saja, maka menurut aktor-aktor pembangun akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk usaha ekonomi produktif , seperti penggilingan padi, penggilingan kelapa, UKM gula aren, dan pertukangan. Selain itu, dengan dibangunnya PLTMH, muncul harapan aktivitas ekonomi maupun sosial warga menjadi lebih panjang karena pada malam hari masyarakat juga dapat melakukan berbagai kegiatan dengan penerangan. Sebaliknya, pihak yang menjadi sasaran pembangunan PLTMH, yaitu masyarakat Desa Palakka, juga memiliki harapan, makna, dan respon yang berbeda sama sekali terkait dengan kehadiran listrik di desa mereka ini. Respon warga masyarakat ini umumnya bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh agen pembangun. Masyarakat cenderung menggunakan sebagian besar energi listrik yang tersedia untuk konsumsi rumah tangga dan sosial, serta hanya sedikit yang menggunakannya untuk usaha ekonomi pertukangan. Padahal, pertukangan kayu ini juga membawa kerawanan dan berbahaya dalam konteks pemeliharaan hutan yang jika terjadi penggundulan maka akan mengurangi cadangan air yang selama ini masih melimpah. Selain itu, pemanfaatan listrik untuk rumah tangga juga tidak dapat dikontrol oleh pengurus sebagai akibat melemahnya kepercayaan horisontal (antar warga) maupun vertikal (warga/pelanggan dan pemerintah desa). Akibat lanjutannya adalah konsumsi listrik pelanggan melebihi kapasitas kemampuan PLTMH, sehingga menimbulkan kerusakan teknis dan ancaman terhadap keberlanjutan PLTMH di Desa Palakka ini. Menyadari kondisi tersebut, pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah mengapa harapan pihak pembangun PLTMH dengan penerima atau pengguna listrik PLTMH bisa berbeda satu sama lain?; bagaimana konfigurasi developmentalis1 (developmentalist configuration) dalam pembangunan DME di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Palakka, Kecamatan Maiwa ini?; bagaimana pola pengorganisasian masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap keberlanjutan pengelolaan PLTMH? Penelitian ini menggunakan pendekatan riset aksi partisipatoris yang bersifat evaluatif dengan menekankan pada perspektif antropologi sosial untuk menganalisis proses dan hasil pembangunan DME PLTMH Palakka. Teknik pengambilan data primer menggunakan sensus (pencacahan) pemanfaatan energi listrik rumah tinggal, wawancara
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
76
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
mendalam, wawancara kelompok, dan observasi terlibat selama satu bulan penuh di lokasi penelitian (Juli 2010).
H A S I L E VA L UA S I T E K N I S DA N N O N -T E K N I S
Titik berangkat dalam melihat apakah pengelolaan PLTMH dalam rangka pembangunan DME ini berjalan dengan baik dan memiliki tingkat keberlanjutan yang diharapkan adalah dengan melakukan berbagai identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Identifikasi masalah ini meliputi permasalahan teknis maupun non-teknis. Momentum identifikasi masalah atau bisa juga disebut sebagai proses evaluasi ini dilakukan setelah PLTMH beroperasi di Desa Palakka selama 3 tahun. Hasil dari identifikasi masalah ini ternyata cukup mengkhawatirkan, terutama dari aspek kepedulian atau rasa memiliki yang minim dari pengurus dan pelanggan terhadap PLTMH yang telah dibangun oleh pemerintah ini. Kelemahan atau ketiadaan kontrol konsumsi listrik telah menyebabkan pemakaian energi di setiap rumah tinggal tidak seragam dan melebihi kemampuan daya dari pembangkit listrik. Rumah tinggal yang semula dijatah hanya mendapat 1A (Ampere), setelah tiga tahun menjadi berubah sama sekali. Sebagian besar rumah telah mengganti MCB di rumahnya masing-masing menjadi 2A, 4A, 6A, dan bahkan ada satu rumah yang memasang hingga 25A akibat dari ketidakpahaman pelanggan akan keterbatasan PLTMH. Penggantian MCB itu setelah ditelusuri terbukti dilakukan secara ilegal, artinya tanpa persetujuan pengurus. Pada beberapa kasus , justru operator terlibat dari penggantian MCB tersebut , yang kemudian memicu kecemburuan rumah tinggal yang lain untuk pada akhirnya berlomba menaikkan daya. Akumulasi dari berbagai permasalahan teknis dan non-teknis di atas berujung pada kerusakan pembangkit listrik. Tingginya konsumsi energi listrik ini juga dipicu oleh arus masuk barang-barang elektronik dari luar daerah dan utamanya dari Malaysia. Penduduk Enrekang, termasuk di Desa Palakka ini sebagian besar merupakan perantau ke negeri Jiran tersebut. Mereka banyak yang bekerja di perkebunan-perkebunan maupun proyek-proyek pembangunan lainnya di Malaysia. Selain itu, menurut penuturan warga Desa Palakka, banyak orang Enrekang yang sukses di negeri Jiran dan menetap di sana. Hubungan kekerabatan berdasarkan keturunan maupun kedaerahan yang sangat kuat ini, memungkinkan
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
77
arus mobilitas orang maupun barang yang keluar masuk ke desadesa terpencil di Enrekang, termasuk Desa Palakka. Begitu listrik PLTMH menerangi desa ini , maka setiap keluarga berbondongbondong dan berlomba-lomba untuk membeli lemari es, televisi , parabola, dan peralatan elektronik lainnya. Nasi yang semula dinanak menggunakan tungku atau kompor minyak, kini hampir seluruhnya berganti menggunakan rice cooker yang membutuhkan daya sangat besar. Demikian juga dengan kipas angin, tape, speaker dan barangbarang elektronik lainnya yang sebenarnya bukan kebutuhan primer masyarakat kini mulai memenuhi setiap rumah tinggal.
T a b e l 1 . H asil E valuasi M asalah T eknis dan N on - T eknis
Aspek Teknis Kerusakan pada beberapa bagian PLTMH Palakka: Kontaktor rusak, kemungkinan besar karena kelebihan beban, listrik untuk warga mati, dan harus menunggu pembelian kontaktor dari Makassar dan Jawa. Selama 6 hari listrik mati. Kebocoran pada pipa penstock karena korosi, panjang kebocoran kurang lebih 15-25 cm, jika dibiarkan kebocoran akan semakin lebar screen bak penenang hilang sebelah, mengakibatkan sampah bisa masuk dan membahayakan turbin Kondisi geografis yang berbukit-bukit dan terisolir menyebabkan sulitnya mendapatkan sinyal, sehingga komunikasi pengurus PLTMH dengan Distamben dan Kecamatan menjadi sangat terhambat dan lamban karena harus datang secara langsung untuk mengabarkan sesuatu Pemasangan MCB di rumah-rumah pelanggan dilakukan secara ilegal dan melebihi kemampuan pembangkit, sementara itu pegelola hanya diam saja. Jika dibandingkan dengan PLTMH lainnya (Tanete, Parombean, Ledan), Palakka termasuk dalam kategori kurang terkelola dan terpelihara. Aspek Non- Kepala desa tidak dapat bersikap tegas kepada warganya, sementara Teknis warga juga kurang mendengar instruksi kepala desa karena dianggap bias kepentingan warga dusunnya sendiri. Pihak kecamatan tidak memberikan perhatian yang penuh pada persoalan-persoalan yang menyangkut PLTMH karena merasa tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai dan political will Camat yang rendah Pengelola PLTMH Palakka kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya: - Ketua: tidak melakukan koordinasi, jarang mengumpulkan pengelola - Bendahara: pencatatan iuran sudah bagus, tapi tidak tepat waktu, tidak rajin menagih, sering keluar desa, dan agak sulit ditemui - Operator: sibuk merangkap kegiatan masjid dan masyarakat, kurang aktif melakukan patroli mingguan atau bulanan secara rutin, hanya sewaktuwaktu (karena medan menuju PLTMH yang cukup sulit dan melelahkan) Masyarakat sangat antusias memanfaatkan listrik tetapi sangat kurang antusias memelihara sumber energinya (PLTMH) dengan kurang mengendalikan diri/membatasi dalam pemakaian listrik di rumahnya
Tingkat konsumsi yang tinggi ini nampaknya luput diantisipasi oleh pengurus PLTMH di tingkat desa maupun di kabupaten.
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
78
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
Akibatnya, mekanisme tarif yang ditetapkan masih seragam (pukul rata) padahal konsumsi yang dipakai setiap rumah tinggal berbedabeda. Pada akhirnya desas-desus dan kontroversi mulai berkembang di tengah masyarakat/pelanggan PLTMH atas ketidakadilan yang terjadi. Khususnya dari mereka yang masih patuh untuk hanya mengonsumsi energi listrik 1A biasanya mereka tergolong warga dengan ekonomi tidak mampu atau rumah tinggal yang ditinggali oleh golongan usia lanjut tidak terima harus membayar sama dengan rumah tinggal yang mengonsumsi lebih dari 1A. Ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut ini semakin kompleks ketika terjadi pula perbedaan kontribusi dan tuntutan yang berbeda dari tiga dusun di Desa Palakka yang menikmati penerangan dari PLTMH ini. Kritik paling keras terutama datang dari Dusun Laissong yang berjarak 4 km dari PLTMH. Warga Dusun Laissong merasa tidak menikmati listrik yang sama dengan yang dirasakan oleh pelanggan dua dusun lainnya, yaitu Laballe dan Labatu yang jaraknya lebih dekat dari PLTMH. Pelanggan di Dusun Laissong mengeluh bahwa listrik yang mengalir ke dusun mereka seringkali turun tegangan sehingga redup dan bahkan tidak mampu untuk menyalakan beberapa peralatan elektronik secara bersamaan. Setelah dilakukan pengecekan secara teknis, memang ditemukan penurunan tegangan khususnya pada pukul 18.00-19.00 WITA yaitu ketika setiap rumah tinggal secara hampir bersamaan menyalakan lampu penerangan dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Bahkan setelah dilakukan pencacahan peralatan elektronik yang dimiliki, ternyata warga Dusun Laissong inilah yang justru paling banyak telah mengganti MCB mereka dengan 4A dan 6A. Penggantian sepihak ini semula mereka lakukan sebagai upaya untuk mengatasi keredupan yang dialami, padahal tindakan ini justru semakin memperburuk kondisi PLTMH yang melebihi beban pemakaian. Pada kondisi semacam ini pengurus tidak berani menegur karena peraturan tidak ditegakkan sejak awal dan cenderung membiarkan masalah ini berlarut-larut. Persoalan semacam ini tidak hanya terjadi di PLTMH Palakka saja , melainkan juga terjadi di sebagian besar PLTMH yang telah dibangun di Kabupaten Enrekang. Bahkan permasalahan yang timbul juga sangat bervariasi, mulai dari penetapan tarif yang simpang siur, konsumsi listrik yang melebihi batas, pelanggan yang tidak membayar/menunggak , kerusakan pembangkit listrik , perbaikan kerusakan yang lambat/lama, koordinasi desa dan kecamatan yang
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
79
tidak singkron, tuntutan kenaikan gaji operator, serta ketergantungan pada bahan (onderdil ) dan peralatan yang hanya bisa dibeli di Jawa. Berbagai permasalahan tersebut , sebenarnya muncul akibat dari proses pembangunan yang hanya menekankan pada aspek teknis dan melupakan aspek pengorganisasian sosial-kelembagaan masyarakat pengguna PLTMH itu sendiri. Padahal, titik penentu keberlanjutan pemanfaatan PLTMH dan itu berarti juga keberlanjutan DME ini selain dari persoalan teknis (elektrik, sipil, mesin, dan jaringan) adalah persoalan non-teknis atau sosial lainnya, seperti pengetahuan, persepsi, perilaku, manajemen hingga kesesuaian dengan kebudayaan dan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat pengguna PLTMH. Oleh karena itu, untuk menganalisis proses pembangunan DME melalui PLTMH , penulis telah memperdalam pengamatan secara komparatif pada beberapa aspek, seperti relasi antara aktor lokal dan intervener, perhitungan ilmuwan dan perhitungan masyarakat lokal, penelitian dan pembangunan, kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, konflik peran para aktor, dan terakhir adalah strategi pengorganisasian masyarakat dalam mengelola PLTMH.
R E L A SI A N TA R A A K T OR L OK A L VS INTERVENER
Terkait dengan proses pembangunan DME berbasis PLTMH , maka kita dapat memahami bahwa pemerintah melalui agen-agen pembangunannya senantiasa melihat desa-desa terpencil sebagai potret desa yang tertinggal, terbelakang sehingga patut untuk ditolong dan dibangun. Demi apa? Tentu saja demi mengejar pertumbuhan ekonomi agar desa atau kabupaten tersebut secara keseluruhan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rasionalitas semacam inilah yang kemudian mendorong relasi yang terbangun antara agen pembangun PLTMH dengan masyarakat pengguna bersifat subjekobjek , yang menolong-yang ditolong, yang maju-yang tertinggal , dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud oleh subjek pembangunan adalah bagaimana meningkatkan kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi ini tentu saja tidak dapat dicapai jikalau kebutuhan dasar masyarakat itu belum terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar tersebut meliputi air bersih, energi listrik, bahan pangan, hingga infrastruktur jalan sebagai tulang punggung mobilitas ekonomi masyarakat untuk melakukan interaksi dengan desa-desa atau kota-kota di sekitarnya.
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
80
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
Dengan demikian , intervener atau agen-agen pembangunan PLTMH akan selalu memiliki pemikiran bahwa dengan terpenuhinya energi listrik, roda pertumbuhan ekonomi masyarakat akan berputar lebih kencang. Logika sosialnya adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil itu akan menikmati kemudahan yang sama dengan masyarakat di tempat lain yang lebih dulu maju atau mengalami kemajuan. 2 Dengan menikmati kemudahan atau hal-hal yang sama, seperti penerangan lampu pada malam hari atau mereka dapat menyalakan televisi, maka arus informasi dan koneksi masyarakat dengan dunia luar akan semakin terbuka, sehingga pada akhirnya masyarakat tersebut tidak lagi terpencil atau tertinggal dari yang lainnya. Diharapkan juga terjadi adopsi beragam aktivitas ekonomi maupun teknologi dari keterbukaan informasi yang diperoleh, sehingga tumbuh aktivitas-aktivitas produktif lainnya dengan lebih cepat. Pemikiran seperti di atas, barangkali memang menjadi logika sosial yang umum di kalangan agen pembangunan. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah masyarakat setempat yang tinggal di daerah terpencil atau yang belum diterangi oleh listrik juga memiliki logika sosialnya sendiri. Mereka pada umumnya, dan khususnya di Desa Palakka, tidaklah seterpencil atau setertinggal yang dibayangkan oleh agen-agen pembangunan tersebut. Bagi mereka, kehadiran listrik PLTMH adalah berkah yang luar biasa dan mereka hayati serta nikmati layaknya sesuatu yang ditunggu-tunggu sejak lama. Namun , jauh sebelum PLTMH ini hadir, masyarakat sebenarnya telah mengadopsi berbagai teknologi sederhana yang lain, misalnya menggunakan accu setrum untuk menonton televisi, menggunakan mesin diesel untuk penerangan pada waktu-waktu tertentu (pesta), atau menggunakan kincir air dari kayu sebagai pemutar generator listrik sederhana. Meskipun berbagai peralatan tersebut memiliki banyak keterbatasan , namun hal ini hanya untuk menandakan bahwa masyarakat Desa Palakka bukanlah masyarakat yang buta dengan teknologi sama sekali. Bahkan dari sisi mobilitas sosial, perjumpaan warga desa terpencil ini dengan peradaban kota atau ekonomi pasar juga bukan menjadi sesuatu yang baru. Sudah sejak lama masyarakat Desa Palakka memiliki kebiasaan untuk merantau atau bekerja di luar daerah dan bahkan di luar negeri (TKI di Malaysia dan Arab Saudi). Setelah merantau bertahun-tahun, sebagian besar dari mereka kembali lagi ke kampung halaman dengan membawa segenap pengetahuannya tentang kehidupan dan kemajuan teknologi di luar negeri. Kehadiran PLTMH
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
81
dalam konteks desa semacam ini sebenarnya adalah mempermudah dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber energi listrik secara lebih merata dan murah dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, PLTMH juga telah menjadi saluran bagi masyarakat dan eksTKI untuk mengonsumsi berbagai kemajuan teknologi yang pernah mereka rasakan ketika berada di luar daerah atau luar negeri. Dengan kondisi semacam ini, maka kehadiran agen pembangunan PLTMH di lapangan selalu disambut dengan hangat oleh masyarakat setempat karena dianggap sebagai penolong. Meskipun relasi yang terbentuk antara agen pembangun dengan masyarakat bersifat subjekobjek, tetapi logika sosial antara agen pembangun dan masyarakat dapat bertemu satu sama lain, yaitu mereka sama-sama memiliki anggapan bahwa PLTMH nantinya akan menolong untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivitas-aktivitasnya, baik yang bersifat primer maupun tersier, ekonomi maupun hiburan. Persoalannya adalah relasi positif antara logika pembangun dan masyarakat pengguna PLTMH ini tidak kemudian sama persis dalam hal perhitungan teknis tentang cara pengelolaan, pembagian kewenangan, pembatasan-pembatasan pemakaian dan persepsi tentang kepemilikan , serta aturan main pemanfaatannya. Dari sinilah benih-benih permasalahan sebenarnya dimulai.
P E R H I T U N G A N I L M U WA N V S PERHITUNGAN LOKAL
Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa PLTMH merupakan teknologi tinggi yang seratus persen terbukti dan siap digunakan tanpa syarat. Sementara itu, agen pembangun memiliki pemahaman bahwa PLTMH merupakan teknologi yang memiliki keterbatasan dan memerlukan perawatan dan pemeliharaan periodik yang sangat kompleks dan ketat , mulai dari faktor ekologis , teknis , hingga kelembagaan pengelola PLTMH. Faktor ekologis misalnya terkait dengan ketersediaan aliran air dengan debit tertentu. Ketersediaan air ini sangat dipengaruhi faktor alam, seperti cuaca, curah hujan, cadangan air, serta faktor sosial ekonomi , seperti penebangan pohon , perambahan hutan , hingga pemanfaatan sungai, kemungkinan pencemaran, serta penumpukan sampah. Jika ketersediaan air ini tidak dapat dijamin dengan baik, maka akan sangat memengaruhi kinerja PLTMH yang sangat bergantung
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
82
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
pada kualitas aliran air. Dengan demikian, memelihara PLTMH adalah pekerjaan yang tidak sederhana karena ketergantungan dengan faktor alam dan perilaku manusia di atasnya. Dari sisi teknis, faktor pengetahuan menjadi sangat menentukan kualitas pemeliharaan PLTMH ini. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis tertentu sangat dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan PLTMH. Padahal, sumber daya manusia yang tersedia di desa terpencil seperti di Palakka ini sangat terbatas. Rata-rata hanyalah lulusan SD atau SMP, dan sedikit yang lulus SMA/ SMK, itu pun belum tentu lulusan program elektro atau mesin yang dibutuhkan sebagai kualifikasi seorang operator. Operator PLTMH adalah jantung dari pengelolaan PLTMH. Oleh karena itu, operator haruslah warga desa setempat yang memang bisa diharapkan tinggal selamanya di desa itu. Pada akhirnya, agen pembangun PLTMH harus memilih operator dari keterbatasan SDM yang tersedia. Operatoroperator PLTMH di Kabupaten Enrekang ini kemudian mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis di Bandung atau di tempat yang telah direkomendasikan oleh developer PLTMH. Jumlah operator adalah 2 orang di setiap desa. Dari sisi teknis ini sungguh dapat dibayangkan lebarnya ketimpangan pengetahuan yang harus dijembatani oleh pembangun PLTMH agar PLTMH dapat beroperasi dalam jangka panjang. Dari sisi organisasi dan kelembagaan, perlu diciptakan sebuah polapola hubungan yang bersifat horizontal (antar pelanggan) maupun vertikal (antar pelanggan dan birokrasi pemerintah) yang jelas tentang peran-peran, hak, dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masingmasing pihak dalam menunjang keberlanjutan PLTMH ini. Faktor kelembagaan pengelolaan PLTMH ini menjadi sangat krusial ketika masyarakat atau pemerintah harus menghadapi persoalan ekologis maupun teknis. Siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, mekanisme penentuan tarif seperti apa, hingga proses monitoring dan pengawasan seperti apa yang harus dijalankan agar PLTMH tetap lestari dan DME bisa terwujud? Hal ini jauh lebih sulit untuk dilakukan jika tidak oleh masyarakat setempat sendiri yang melakukannya, tentu saja dengan dorongan dari pemerintah daerah maupun agen pembangun PLTMH. Hal ini karena bagaimanapun juga, pemerintah dan agen pembangun PLTMH adalah outsider yang tidak mengerti betul seluk-beluk keseharian warga setempat. Dengan demikian , pemimpin lokal , tokoh masyarakat , tokoh agama , dan
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
83
pemuda desa memiliki peran sentral dalam menciptakan kelembagaan pengelolaan PLTMH yang solid. Kompleksitas permasalahan seperti inilah yang kurang disadari oleh masyarakat pengguna maupun oleh pemerintah daerah. Pelanggan biasanya hanya menginginkan menikmati hasil tanpa merasa harus ikut menjaga dan memelihara. Lebih-lebih dengan penetapan tarif yang tidak seberapa, pelanggan/masyarakat biasanya sudah merasa boleh untuk melakukan apa saja karena merasa sudah membayar. Sementara itu, pemimpin-pemimpin lokal setempat cenderung berpikir pragmatis dan tidak jarang malah mengambil previledge yang lebih banyak dari anggota masyarakatnya. Sementara itu, pemerintah daerah melalui kecamatan atau dinas terkait, lebih sering bertindak lamban, tidak praktis, dan sering lempar tanggung jawab antar instansi atas permasalahan di lapangan. Perbedaan perhitungan antara pembangun PLTMH biasanya berisi para ahli dan ilmuwan berbagai disiplin ilmu dengan perhitungan masyarakat lokal dan pemerintah daerah inilah yang kemudian melahirkan benturan-benturan kepentingan di lapangan yang pada ujungnya jika tidak diselesaikan akan mengancam keberlanjutan PLTMH itu sendiri.
PENELITIAN VS PEMBANGUNAN
Selain sebagai teknologi di bidang energi baru dan terbarukan ( renewable energy ) yang mampu diterapkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar listrik, PLTMH juga memiliki beragam spesifikasi dan tipe-tipe yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan selama bertahun-tahun. Proses penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D ) dalam bidang ini juga berlangsung terus-menerus menyesuaikan dengan perkembangan permasalahan yang muncul di lapangan, baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian , swasta, LSM, maupun oleh individu-individu. Sebagai teknologi tepat guna, PLTMH bukan saja dikaji secara teknis belaka, melainkan juga dikaji secara utuh dalam sebuah implementasi teknologi yang berdampak pada masyarakat, mulai dari sisi kelayakan pembangunan, pemetaan potensi geografis, hingga evaluasi dampak sosial ekonominya. Sebuah produk R&D seperti PLTMH yang kemudian dibangun dan dikembangkan dalam suatu masyarakat atau lingkungan ekologis tertentu, tentu saja harus mencapai tingkat keselarasan dan kecocokan
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
84
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
yang tinggi dengan karakteristik geografis, ekologis, maupun sosial budaya masyarakat setempat. Dalam proses pemetaan potensi kelayakan saja misalnya, diperlukan survei lokasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dapat menghasilkan perhitungan-perhitungan dan proyeksi teknis-matematis yang tepat. Misalnya saja jika peneliti menemukan titik terjunan air yang cocok untuk menggerakkan turbin pembangkit, maka tidak serta merta bisa langsung dibangun. Perlu dipertimbangkan pula berapa jauh jaraknya dari pemukiman, berapa panjang instalasi jaringan listrik yang harus dibangun, apakah mampu menerangi seluruh wilayah dusun yang ada secara adil dan merata. Jika tidak, lalu bagaimana pemecahannya? Siapa yang harus diajak untuk mengambil keputusan?, dan seterusnya. Pertimbangan-pertimbangan teknis-akademis yang ilmiah ini kemudian harus berhadapan dengan pertimbangan praktis pembangunan yang kadangkala lebih bersifat politis-pragmatis. Di sinilah permasalahan lainnya muncul. Target-target terkait jumlah DME yang demikian tinggi, tentu saja memacu proses pembangunan menjadi lebih cepat. Tuntutan politik - khususnya dari kepala daerah agar program DME ini sukses dan mendapatkan pengakuan secara politik dari pemerintah pusat maupun konstituen, membuat para agen pembangunan di bawah bekerja dengan lebih cepat. Kondisi demikian seringkali menyebabkan agen pelaksana pembangunan ini menanggalkan prinsip ketelitian, kehati-hatian, dan keberlanjutan yang merupakan prinsip dalam kajian R&D. Misalnya saja pertimbangan tentang jarak rumah pembangkit dengan pemukiman terdekat. Rekomendasi R&D yang terbaik tentu saja mensyaratkan titik terjunan air dengan jarak terdekat ke pemukinan penduduk demi memudahkan operator melakukan penanganan tertentu bila terjadi kerusakan. Akan tetapi, rekomendasi pembangunan menginginkan di titik manapun yang penting PLTMH bisa dibangun secepatnya dan listrik bisa menyala. Akibatnya, faktor psikologis jangka panjang khususnya pemikiran warga lokal atau operator seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan tersebut. Akibatnya, ketika jarak PLTMH dengan pemukiman itu lebih dari 2-3 km dan berada di tengah hutan dengan medan yang terjal, maka harus dimaklumi jika kemudian operator atau pengurus PLTMH enggan untuk melakukan patroli harian atau mingguan. Sebab, selain melelahkan secara fisik dan membahayakan keselamatan jiwanya (misalnya, harus menembus hutan untuk mematikan pembangkit karena sungai banjir atau bertemu
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
85
binatang buas) juga karena kompensasi ekonomi (gaji) operator yang tidak sebanding dengan kewajiban-kewajiban yang harus diembannya (patroli harian , mingguan , bulanan , perawatan dan perbaikan kerusakan jaringan di rumah tinggal maupun di pembangkit listrik).
K E PE N T I N G A N A PA R AT PE M E R I N TA H V S K E BU T U H A N M A SYA R A K AT LOK A L
Sebagai daerah yang masih terus membangun , pemerintah kabupaten Enrekang sangat terbuka terhadap segala bentuk proyekproyek kerjasama pembangunan, baik yang datang dari pemerintah pusat maupun dari swasta. Kondisi geografis kabupaten Enrekang sebagaimana kondisi daerah lain di Sulawesi selatan yang berbukitbukit dan memiliki jarak antar kecamatan yang sangat jauh, membuat proses pembangunan desa-desa berjalan agak lambat sebagai akibat dari medan yang demikian berat untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan atau jembatan. Oleh karena itu , berbagai proyek pembangunan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat Enrekang akan disambut dengan sangat baik, termasuk proyek pembangunan DME melalui PLTMH. Sejak pertama kali PLTMH berhasil dibangun di Desa Tanete, Kecamatan Maiwa (2005), Kabupaten Enrekang telah membangun lebih dari 10 PLTMH di desa-desa lain dengan bantuan dari berbagai pihak, seperti LIPI, Kementrian ESDM, serta Kementrian PDT. Bahkan kemudian proyek pembangunan PLTMH ini diusung secara politik menjadi program unggulan dan janji pembangunan dari pasangan bupati dan wakil bupati hingga akhirnya mampu terpilih dua kali dalam pemilihan umum kepala daerah. Oleh karena itu, bupati dan jajarannya sangat berkepentingan agar program atau janji politiknya terhadap konstituen ini dapat terwujud dengan baik di lapangan. Selain bupati sebagai kepala daerah, proyek pembangunan PLTMH ini juga merupakan debut pertama dari Distamben Kabupaten Enrekang sebagai SKPD yang baru dibentuk - yang dinilai sukses dan mampu menarik perhatian semua kalangan di birokrasi pemerintahan, eksekutif maupun legislatif. Kesuksesan PLTMH ini juga meningkatkan keberhasilan dari personal-personal yang pernah terlibat di dalam proyek ini, sehingga mendapatkan promosi atau mutasi ke bidangbidang pemerintahan lainnya yang lebih strategis, seperti mantan kepala Distamben yang kemudian menjadi kepala Bappeda, semakin
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
86
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
menguatkan eksistensi program pembangunan PLTMH sebagai cerita sukses pembangunan daerah. Pada akhirnya, tarik-menarik politik dalam wacana pembangunan PLTMH juga tidak dapat dihindarkan, seperti misalnya saling klaim keberhasilan oleh pejabat dan politisi hingga partai-partai politik yang menjanjikan akan mengalirkan listrik ke desa-desa tempat mereka menjaring konstituen. Apapun kepentingan elit politik, pejabat, ataupun birokrat lainnya terhadap program pembangunan PLTMH, tentu saja harus diabdikan terlebih dahulu bagi kepentingan masyarakat lebih luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang tepat tentang apa sebenarnya kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut. Listrik atau energi yang mandiri tentu menjadi kebutuhan dan keinginan bagi masyarakat yang tinggal di desa pedalaman atau daerah-daerah terpencil. Kehadiran teknologi PLTMH atau renewable technology lainnya memberikan jawaban untuk persoalan tersebut. Hanya saja, investasi finansial yang besar dan teknologi yang harus dikuasai oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, tidak dapat begitu saja diutarakan menjadi janji-janji politik. Hal ini karena jika janji politik itu tidak mampu diwujudkan akan menyulut kemarahan warga masyarakat yang telah dijanjikan. Untuk kasus di Desa Palakka, janji pemerintah tersebut memang pada akhirnya dapat terwujud dengan baik , meskipun dari sisi pengelolaan tidak terbentuk kelembagaan yang dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan PLTMH ini. Diberikannya penghargaan kepada PLTMH di Desa Parombean sebagai DME terbaik di Enrekang juga menjadi contoh keberhasilan pencitraan pemerintah sekaligus pengelolaan di tingkat desa yang relatif solid. Akan tetapi , di beberapa desa lainnya, pembangunan PLTMH menuai kritik keras dari masyarakat karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat , seperti listrik yang hanya menerangi sebagian dusun, pembangunan yang terbengkalai, kerusakan teknis yang lambat ditangani hingga pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sepenuhnya. Sebagai contoh pembangunan Kecamatan Mandiri Energi di Kecamatan Bungin, sampai dengan penelitian ini dilangsungkan masih menghadapi banyak kendala, baik teknis maupun pengorganisasian masyarakatnya. Oleh karena itu , mempertemukan sedekat mungkin kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat itulah sebenarnya salah satu kunci keberhasilan suatu program pembangunan, bukan hanya
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
87
soal nilai material proyeknya atau tingkat penguasaan teknologi yang diimplementasikan.
KONFLIK PERAN AKTOR-AKTOR DI T INGK AT MIK RO
Konflik peran ini terjadi dalam persoalan pengelolaan PLTMH, lebih-lebih setelah diberlakukannya peraturan Bupati No. 12 Tahun 2010 yang salah satu poin utamanya adalah memindahkan kewenangan pengelolaan PLTMH dari Distamben kepada kecamatan. Padahal, sejak awal pembangunan PLTMH di hampir semua desa, kecamatan tidak pernah terlibat secara langsung, baik dari sisi perencanaan maupun pembangunan. Begitu kewenangan pengelolaan ini dipindahkan tentu saja melekat kewenangan teknis maka pihak kecamatan hampir tidak memiliki pola dan strategi sama sekali untuk mengawal kebijakan ini. Dalam waktu bersamaan, Badan Usaha Desa (BUD) yang dimaksudkan sebagai payung hukum kelembagaan pengelolaan PLTMH belum terbentuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya dan baru disusun oleh tim yang dibentuk oleh bupati. Pemindahan kewenangan ini menjadi sesuatu yang dilematis di tengah perjalanan beberapa PLTMH yang sudah beroperasi lebih dari 2-3 tahun. Pada usia ini, PLTMH-PLTMH ini memerlukan pemeliharaan yang semakin intensif mengingat banyak peralatan yang mulai rusak dan harus diganti secara periodik. Pembiayaan untuk perbaikan teknis semacam ini tentu saja tidak ada di dalam anggaran pembangunan di kecamatan, melainkan satu-satunya sumber adalah hasil pengumpulan iuran dari masyarakat pelanggan atau bantuan langsung dari pemerintah daerah yang tidak pasti jumlah dan waktunya untuk bisa diturunkan. Sedangkan iuran pelanggan seperti sudah diungkapkan di atas, tidak ada pola kontrol dan pengawasan yang berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan persoalan pada kedisiplinan pembayaran.3 Kecamatan yang diserahi tanggung jawab baru ini kemudian menjadi kebingungan dalam mencari pola komunikasi yang tepat dengan para pengelola PLTMH yang sejak awal bergelut dengan rumitnya mengatur masyarakat desanya sendiri. Demikian juga pihak desa kepala desa dipaksa oleh peraturan baru ini untuk melaporkan dan mencari setiap pemecahan masalahnya kepada kecamatan. Setiap mereka melapor ke kecamatan tidak pernah ada tindak lanjut karena memang pihak kecamatan tidak tahu harus
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
88
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
berbuat apa kecuali melaporkan permasalahan tersebut kembali kepada Distamben. Sementara itu, Distamben yang tidak lagi memiliki kewenangan langsung untuk membantu, hanya dapat memberikan saran atau kalaupun menuntaskan permasalahan itu tidak dengan sepenuh kemampuan seperti sebelumnya. Demikian juga kepala desa, yang merasa tidak perlu melapor ke kecamatan karena merasa tidak mendapatkan apa-apa, sehingga langsung saja mereka menghubungi Distamben yang sebenarnya lebih mengerti permasalahan yang terjadi. Kepala Desa Palakka , misalnya , selalu mendapatkan keluhan dan tuntutan langsung dari para pelanggan yang tidak lain adalah masyarakatnya sendiri juga berdiri dalam pilihan peran yang serba terbatas. Misalnya untuk kasus tarif, di satu sisi ia mendukung agar tarif lebih adil dengan membedakan berdasarkan pemakaian, namun di sisi lain dia juga tinggal di Dusun Laissong, yang warga dusunnya selalu merasa dianaktirikan dalam menikmati fasilitas PLTMH karena lokasinya yang paling jauh dari rumah pembangkit. Dalam perannya sebagai kepala desa, setiap keputusannya misalnya wacana tentang pembelian trafo untuk meningkatkan tegangan ke Dusun Laissong selalu dipandang sebagai kepanjangan tangan suara warga Dusun Laissong , bukan sebagai suara keseluruhan warga desa (yang penduduknya paling banyak tinggal di Dusun Labatu). Meskipun jika dirunut secara historis, warga desa itu sebenarnya masih dalam satu ikatan kekerabatan yang kuat. Justru karena itu pula, keseganan untuk menegur langsung atau untuk melakukan kontrol penggunaan energi listrik itu menjadi lebih sulit daripada mengatur warga/pelanggan yang tidak mengenal satu sama lain. Ini pula yang dirasakan oleh operator sebagai aktor kunci dalam pengelolaan PLTMH, khususnya dari aspek teknis. Operator yang merupakan warga desa setempat menghadapi konflik peran paling krusial. Harapan masyarakat yang dibebankan kepadanya sangat tinggi, sementara kompensasi materi yang diterimanya tidak seberapa dibanding jika dia memilih bekerja di luar daerah atau menjadi TKI. Lebih-lebih operator berada dalam lingkungan yang sebenarnya masih bagian dari kerabatnya sendiri, hal ini semakin memojokkan operator pada sedikit pilihan-pilihan yang harus diambil. Misalnya saja dalam menegakkan aturan penggunaan MCB di rumah tinggal hingga pada masalah penentuan tarif posisi operator serba dilematis. Jika ia bertindak terlalu keras misalnya memberi sanksi pencabutan listrik bagi yang melanggar maka akan berdampak pada hubungan keluarga
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
89
dan kekerabatan. Namun jika operator bersifat terlalu lunak, yang terjadi adalah pelanggaran kolektif (beban berlebih) yang mengancam keberlanjutan PLTMH. Operator juga pada satu sisi terpenjara di desa itu karena jika ia meninggalkan desa untuk bekerja ke luar, selain akan mendapat kecaman dari masyarakat sebagai satu-satunya orang yang memahami teknis PLTMH ia juga menanggung beban moral terhadap warga desanya sendiri. Belum lagi ditambah dengan risiko yang harus diembannya dalam memelihara PLTMH yang biasanya terletak jauh di dalam hutan.
PE NG ORGA N ISA SI A N M A SYA R A K AT
Keteraturan dalam masyarakat akan mengalami pergeseran menjadi ketidakteraturan karena adanya perubahan-perubahan sosial (Rudito & Budimanta 2003:12). Demikian pula dengan dihadirkannya teknologi PLTMH yang membawa perubahan sosial di tengah masyarakat Desa Palakka yang terpencil, yang terlupakan dalam proses pembangunan ini adalah pengorganisasian masyarakat pengguna PLTMH. Bagaimanapun juga, keteraturan sosial dan bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat pasti berubah secara cukup revolusioner dengan hadirnya listrik. Baik dari sisi pengetahuan yang masuk, peralatan dan teknologi yang masuk juga pengaruhnya terhadap interaksi sosial di antara masyarakat. Jika tidak dibangun kelembagaan lokal yang kuat dan berbasis pada demokrasi di tingkat lokal, maka kemungkinan keberlanjutan PLTMH akan terancam. Sebagaimana dikemukakan oleh Pieterse (1998:369) bahwa perubahan terbesar dalam pola pembangunan modern saat ini adalah penekanan yang lebih kuat pada partisipasi dan demokrasi di tingkat lokal termasuk dengan mengandalkan aktor-aktor lokal. Dalam kasus pengorganisasian pengelolaan PLTMH di Desa Palakka ini, sejak dalam tahap perencanaan, pembangunan, hingga pasca pembangunan (pemanfaatan) keterlibatan masyarakat sudah memiliki permasalahan yang tidak terselesaikan secara baik, khususnya tingkat partisipasi yang berbeda dari setiap dusun. Konflik perbedaan kualitas aliran listrik antara Dusun Laissong dan dua dusun lainnya saat ini sebenarnya sudah dimulai sejak perencanaan. Dusun Laissong karena lokasinya jauh adalah yang paling tidak antusias dengan pembangunan PLTMH, termasuk dalam kontribusinya ketika kerja bakti. Kepala desa yang lama saat itu tinggal di Dusun Labatu kemudian memberikan pilihan yang sulit, yaitu jika tidak ikut kerja bakti membangun PLTMH
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
90
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
maka Dusun Laissong tidak akan diterangi oleh listrik. Akibatnya, warga Dusun Laissong bekerja dalam kondisi setengah terpaksa meskipun itu untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu, dalam pembentukan pengurus harian sebagai pengelola PLTMH di tingkat desa , dilakukan melalui penunjukkan dengan mengambil orang-orang yang memang terlibat aktif dalam proses pembangunan PLTMH dan tidak melalui mekanisme demokrasi yang sebenarnya, misalnya pemilihan melalui musyawarah dengan seluruh pelanggan. Akibatnya, orang-orang yang duduk dalam kepengurusan PLTMH didominasi oleh kerabat atau anggota keluarga tertentu saja, sehingga menimbulkan prasangka di tengah-tengah masyarakat. Pembedaan pemasangan MCB bagi pengurus dusun dan desa (mereka mendapat jatah 2A dengan tarif sama dengan 1A) yang tidak melalui kesepakatan bersama juga memicu lahirnya perasaan tidak adil di kalangan pelanggan. Akibat lebih jauh adalah masing-masing rumah tinggal berlomba untuk mengganti sendiri MCB mereka secara ilegal. Kelembagaan pengelolaan yang tidak terbentuk dengan baik seperti ini, berimplikasi pada aturan main pemanfaatan PLTMH dan pembagian kerja dalam kepengurusan yang tidak berjalan dengan semestinya. Pada kondisi seperti ini, harapan pembangun PLTMH bahwa dengan adanya listrik maka dapat terbangun usaha produktif tidak terjadi. Sekalipun modal peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun usaha produktif, seperti alat penepung dan alat-alat untuk perbengkelan kayu dan logam sudah didatangkan dalam bentuk bantuan dari pemerintah sebagai developer PLTMH. Kegagalan pengorganisasian masyarakat juga menyebabkan kegagalan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan oleh agen pembangun PLTMH.
PENUTUP
Dalam sebuah proses pembangunan, bukan hanya ide tentang kemajuan saja yang penting untuk diperhatikan , melainkan juga dimensi kompleks lainnya yang menyertai proses intervensi yang disengaja tersebut. Dimensi utama yang penting untuk dianalisis antara lain adalah agensi dan struktur dalam masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan tersebut. Artinya , penting untuk memahami keterlibatan, kepentingan, dan peran aktor-aktor lokal dalam memandang pembangunan dalam hal ini kehadiran teknologi
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
Pengorganisasian M asyarakat D esa M andiri E nergi |
91
PLTMH untuk membangun DME sekaligus perubahan struktur dan keteraturan sosial sebagai akibat dari proses pembangunan tersebut. Dengan kacamata sosio-antropologi, kasus pemanfaatan energi PLTMH di Desa Palakka merupakan contoh kompleksitas sebuah proses pembangunan, yang logika sosial (social logic) dari agen pembangunnya (developers ) seringkali tidak cocok atau tidak selaras dengan logika sosial masyarakat pengguna. Akibatnya, banyak harapan-harapan positif dari dihadirkannya PLTMH di Desa Palakka menjadi tidak terwujud dalam kenyataan. Lebih dari sekedar persoalan teknis tentang berapa kapasitas PLTMH, di mana ia harus dibangun, dan berapa biayanya, yang lebih penting dari itu ternyata adalah bagaimana mampu mengorganisasikan masyarakat.
C atatan A khir
1 A complex set of institutions. Flows and actors, for whom development constitutes a resource, a profession, a market, a stake, or a strategy (Sardan 2005:2) 2 Konsep kemajuan selalu melekat dengan model transformasi yang direncanakan (developmentalism). Menurut Nisbet (1980) kemajuan dapat didefinisikan sebagai peningkatan yang dialami manusia secara lambat, bertahap, dan berkelanjutan dari kondisi awal kultural yang lemah, kebodohan, dan kondisi tak aman ke tingkat peradaban lebih tinggi, dan kemajuan ini akan terus berlanjut hingga ke masa mendatang (Sztompka, 2008:28). Meski demikian, dunia kini lebih cenderung dikuasai oleh pemikiran tentang krisis daripada tentang kemajuan itu sendiri. 3 Sebagai contoh perhitungan di Desa Palakka adalah sebagai berikut: iuran per bulan pelanggan disamaratakan sebesar Rp. 20.000, sementara jumlah pelanggan/rumah tinggal yang harus membayar adalah 116, maka jika pelanggan disiplin membayar dalam satu bulan pengelola mampu mengumpulkan Rp. 2.320.000,-. Dkurangi gaji 2 orang operator Rp. 1.000.000,- (@Rp.500.000,-) dan gaji pengurus lain Rp. 500.000,- maka dana cadangannya tinggal Rp. 820.000, -. Dengan demikian , dalam satu tahun dana cadangannya akan terkumpul Rp. 9.840.000,-. Dana sebesar itulah yang akan digunakan untuk pemeliharaan dan pembelian peralatan PLTMH yang biasanya harganya cukup mahal.
DAF TAR PUSTAK A
Anonim. 2007. Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 50 kW sungai Laballe Dusun Laballe Desa Palaka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan. Enrekang: Dinas Pertambangan dan Energi Anonim. 2007. Panduan Pengembangan Usaha Produktif di Lokasi PLTMH: Pengkajian Usaha-Usaha Produktif yang Potensial untuk dikembangkan di Lokasi PLTMH. IMIDAP. DJLPE.
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
92
| Yanu E ndar Prasetyo & U mi H anifah
Hidayat , D.D. 2007. Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat melalui Implementasi TTG di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Laporan akhir Program Penelitian dan Pengembangan Iptek. Subang: Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI Peraturan Bupati Enrekang No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Pieterse, Jan Nederveen. 1998. My Paradigm or Yours? Alternative Development, Post-Development, Reflexive Development. Oxford: Institut of Social Studies Pike, Andy. Andres Rodriguez-Pose & John Tomaney. 2006. Local and Regional Development. New York & Canada: Routledge Pimentel, David & Marcia H Pimentel. 2010. Food, Energy & Society: Third Edition. CRC Press Rudito , Bambang & Arif Budimanta. 2003. Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development. Jakarta: ICSD Sardan, Jean Pierre Olivier de. 2005. Anthropology and Development: Understanding Contemporary Social Change. London & New York: ZED Books Sztompka, Piotr. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada
KOM U N I TA S Volu me 5 , No m o r 1 , Ju l i 2 01 1 : 7 1 - 9 2
You might also like
- Pengorganisasian Masyarakat Desa Mandiri EnergiDocument22 pagesPengorganisasian Masyarakat Desa Mandiri EnergiMary WhitneyNo ratings yet
- Electrical Energy Consumption For Rural Residences in The FutureDocument12 pagesElectrical Energy Consumption For Rural Residences in The Futureindex PubNo ratings yet
- ID Survey Potensi Pembangkit Listrik TenagaDocument10 pagesID Survey Potensi Pembangkit Listrik TenagaErry Abdul Nasir PelupessyNo ratings yet
- PR EN MENTARI PLTS Project Launch in Sumba 24 Aug 2022 1Document6 pagesPR EN MENTARI PLTS Project Launch in Sumba 24 Aug 2022 1Azri AziziNo ratings yet
- Analisis Program Listrik Pedesaan Dalam Meningkatkan Aktivitas Sosial Masyarakat Di Kecamatan Dolo Kabupaten SigiDocument7 pagesAnalisis Program Listrik Pedesaan Dalam Meningkatkan Aktivitas Sosial Masyarakat Di Kecamatan Dolo Kabupaten SigiYudi WisenoNo ratings yet
- Harnessing of Mini Scale Hydropower For Rural Electrification in NepalDocument3 pagesHarnessing of Mini Scale Hydropower For Rural Electrification in NepalSunny ShresthaNo ratings yet
- PDFDocument11 pagesPDFI WAYAN RANGGA KRISNATANo ratings yet
- Summary Orang Asli Micro Hydro ProjectDocument4 pagesSummary Orang Asli Micro Hydro ProjectalamsekitarselangorNo ratings yet
- ID Analisis Program Listrik Pedesaan DalamDocument7 pagesID Analisis Program Listrik Pedesaan DalamNur AfniNo ratings yet
- Jurnal Waduk JatigedeDocument5 pagesJurnal Waduk JatigedeSriwulanNo ratings yet
- Micro Hydro Business PlanDocument19 pagesMicro Hydro Business PlanBasnet BidurNo ratings yet
- Case Study of Prathama BankDocument5 pagesCase Study of Prathama BankmechedceNo ratings yet
- Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan Dan Percepatan Pembangunan Energi TerbarukanDocument22 pagesPembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan Dan Percepatan Pembangunan Energi TerbarukanDavin ZeansNo ratings yet
- ID Dampak Sebelum Dan Sesudah Pembangunan PDocument11 pagesID Dampak Sebelum Dan Sesudah Pembangunan PC- NergyNo ratings yet
- 340 HuesoDocument9 pages340 HuesoDyar KhanNo ratings yet
- 1 SMDocument14 pages1 SMFendi AjisNo ratings yet
- Peng Abdi AnDocument8 pagesPeng Abdi AnFisika FMIPANo ratings yet
- Pailaw para Sa Mga KatutuboDocument2 pagesPailaw para Sa Mga KatutuboSecondPmfc Bataan PnpNo ratings yet
- 1034-Article Text-5696-2-10-20210805 PDFDocument11 pages1034-Article Text-5696-2-10-20210805 PDFitha luthanNo ratings yet
- Presidency College, BangaloreDocument47 pagesPresidency College, BangaloreGowthamNo ratings yet
- The Light in WatersDocument3 pagesThe Light in WatershyuhNo ratings yet
- Rural ElectrificationDocument13 pagesRural ElectrificationdikshaNo ratings yet
- Generation of Enim Watershed Tanjung Tiga For Sustainable DevelopmentDocument6 pagesGeneration of Enim Watershed Tanjung Tiga For Sustainable DevelopmentNov Dion FuadillahNo ratings yet
- Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui UMKM Dan Koperasi Dalam Masyarakat PedesaanDocument17 pagesPenguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui UMKM Dan Koperasi Dalam Masyarakat PedesaanMuhibbullah Azfa ManikNo ratings yet
- Rural Electrification Program in Indonesia - Comparing SEHEN and SDocument14 pagesRural Electrification Program in Indonesia - Comparing SEHEN and SirenibraniNo ratings yet
- Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Institusi LokalDocument10 pagesStrategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Institusi LokalhanifNo ratings yet
- RURAL DEVELOPMENT: Economic Development N Social TransformationDocument7 pagesRURAL DEVELOPMENT: Economic Development N Social TransformationAngel SonaNo ratings yet
- Analisis (Purwanto)Document24 pagesAnalisis (Purwanto)PietasFidesNo ratings yet
- HYDROPOWER - Joshua Manuturi (2306184590)Document2 pagesHYDROPOWER - Joshua Manuturi (2306184590)Joshua SitorusNo ratings yet
- 1 SMDocument12 pages1 SMSyahrulD.LuffyNo ratings yet
- Indonesia Jump Starts Rural Electrification PlanDocument3 pagesIndonesia Jump Starts Rural Electrification PlanbradNo ratings yet
- Dividend Policy and Its Impact On Share PriceDocument12 pagesDividend Policy and Its Impact On Share PriceDestiny Tuition CentreNo ratings yet
- Renewable Energy: The Key To Achieving Sustainable Development of Rural BangladeshDocument7 pagesRenewable Energy: The Key To Achieving Sustainable Development of Rural BangladeshRafid RahmanNo ratings yet
- Profile of Under-Developed Village Designated As Conversation Village ModelDocument12 pagesProfile of Under-Developed Village Designated As Conversation Village ModelDodon YaminNo ratings yet
- GKC Oneworld Community Solar Power Plant JhansiDocument13 pagesGKC Oneworld Community Solar Power Plant JhansiSravya RatnaNo ratings yet
- CBT Desa Ponggok ApikDocument7 pagesCBT Desa Ponggok ApikAMINNo ratings yet
- Impact of Solar Energy in Rural Development in India: Tarujyoti BuragohainDocument5 pagesImpact of Solar Energy in Rural Development in India: Tarujyoti Buragohainbaashii4No ratings yet
- Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa MenurutDocument12 pagesEvaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurutvian sajaNo ratings yet
- 5501 1507005838 PDFDocument17 pages5501 1507005838 PDFDewa erlanggaNo ratings yet
- Smart VillagesDocument60 pagesSmart VillagesPriyanka ReddyNo ratings yet
- HBF BriefDocument7 pagesHBF Brief87shivaniNo ratings yet
- Admin, 73 096A-REVISI-FRANSISCA IRIANI ROESMALA DEWI Edited 1573-1580-1Document8 pagesAdmin, 73 096A-REVISI-FRANSISCA IRIANI ROESMALA DEWI Edited 1573-1580-1laris storeNo ratings yet
- JM Jap,+Olivia+MandangDocument13 pagesJM Jap,+Olivia+Mandang'aNggih PrasetyaNo ratings yet
- Master Rural Electrification of IndiaDocument11 pagesMaster Rural Electrification of IndiaShubhamNo ratings yet
- Name of The Organization: Mailing Address: Email: Visit Us: Contact Person: TelephoneDocument10 pagesName of The Organization: Mailing Address: Email: Visit Us: Contact Person: TelephoneKhatelynNo ratings yet
- A Case Study of Nabunturan Compostela VaDocument14 pagesA Case Study of Nabunturan Compostela VaArch Henry Delantar CarboNo ratings yet
- Group C Funding ProposalDocument8 pagesGroup C Funding ProposalHodo AbdilahiNo ratings yet
- Jurnal AnalisisDocument14 pagesJurnal AnalisisAquatic ZoneNo ratings yet
- Solar Will Enhance Livelihood Prospects, Improve Efficiency in Rural HouseholdsDocument3 pagesSolar Will Enhance Livelihood Prospects, Improve Efficiency in Rural HouseholdsTherasaNo ratings yet
- Jurnal Listrik 2Document12 pagesJurnal Listrik 2Dewi PNo ratings yet
- HydropowerDocument4 pagesHydropowerjoealvin bautistaNo ratings yet
- Amar Gram Amar ShaharDocument27 pagesAmar Gram Amar Shaharsajid_391100% (1)
- Reflection Report UpdatedDocument10 pagesReflection Report Updatedrabbi sodhiNo ratings yet
- Fulfilling Aspirations, Transforming Villages: A Mission ForDocument40 pagesFulfilling Aspirations, Transforming Villages: A Mission Forsss gggNo ratings yet
- SchemesDocument9 pagesSchemesSundharamoorthi SundharamNo ratings yet
- Lisa Iryani, Riska MaulizaDocument17 pagesLisa Iryani, Riska MaulizaCyntyaNo ratings yet
- Illuminating Lives: A Comprehensive Exploration of Rural ElectrificationFrom EverandIlluminating Lives: A Comprehensive Exploration of Rural ElectrificationNo ratings yet
- Demand in the Desert: Mongolia's Water-Energy-Mining NexusFrom EverandDemand in the Desert: Mongolia's Water-Energy-Mining NexusNo ratings yet
- Energy Crisis in India: A Commentary on India's Electricity SectorFrom EverandEnergy Crisis in India: A Commentary on India's Electricity SectorRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)