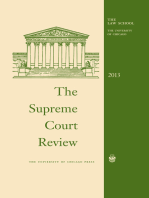Professional Documents
Culture Documents
Jurnal Habibie
Jurnal Habibie
Uploaded by
Rabi AlghazalyOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Jurnal Habibie
Jurnal Habibie
Uploaded by
Rabi AlghazalyCopyright:
Available Formats
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ...
oleh: Jawahir Thontow
54
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi
Pemerintahan BJ. Habibie dan
Abdurrahman Wahid
Jawahir Thontowi
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Abstract
This research represent research punish normatif through approach of juridis-empiris, that
is with studying regulation of yielded by law is governance of BJ. Habibie And Abdurrahman
Wahid, and also efforts performed within realizing rule of law at this reform era Result of
research indicate that big change in its bearing with straightening of law have been conducted by BJ. Habibie. That thing is in marking for example with giving of liberty of the
press guarantee, komitmen at clean governance creation (government clean and governance
good), military jurisdiction execution for the man who impinge HAM Trisakti and KKN
pemeberantasan though that thing not yet succeeded. And also also yielding of some law
and regulation product which is reformatif. In its bearing with effort uphold system of judicature and law, seen that governance of Abdurrahman enough have strong komitmen. That
thing is for example expressly place to domicile Police as enforcer punish and society
pengayom. But that way, image of[is straightening of previous law in the early reform have
shown positive symptom, is again smeared by law scandal befalling Abdurrahman One as
President at the time, in the form of releasing of Memorandum I, II And III by DPR which tip
of who is from Presidency chair
Keywords: Rule of law, reform era, Habibie, Abdul Rahman Wahid (Gus Dur)
Usaha untuk menegakkan supremasi hukum harus selalu terkait dengan dua elemen dasar
yang meliputi: Pertama, hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang mengandung nilai
moral dan sumber yang berfungsi sebagai dasar pijakan prilaku individu dan kelompok masyarakat.
Kedua, hukum dalam arti prosedur atau formal berarti sebagai ketentuan atau tata cara mengenai
bagaimana seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dapat memilih lembaga-lembaga hukum,
dimana mereka dapat menyelesaikan pertikaian secara damai dan adil.
Tegaknya supremasi hukum dalam suatu masyarakat umumnya ditentukan oleh adanya
keserasian antara substansi hukum material dengan peranan institusi hukum dalam dataran
realitas sosial. Dalam praktek, jurang pemisah antara hukum dengan material hukum formal
acapkali tidak mudah dipertemukan. Ketidaksesuaian tersebut timbul disebabkan beberapa
faktor: 1), substansi hukum tidak selalu didukung oleh aparat penegak hukum yang cukup memiliki
integritas dan komitmen yang tinggi, sehingga sekumpulan peraturan hukum yang baik akan
tetap gagal memainkan fungsi secara efektif bilamana tidak dijalankan oleh aparat penegak
hukum yang baik pula. 2) ketidaksesuaian terjadi disebabkan karena penegak hukum dalam
masyarakat tidak dibimbing atau diarahkan oleh peraturan hukum yang mengandung kepastian.
Mereka bukan saja tidak mudah merumuskan fakta-fakta hukum yang konkrit,
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
55
melainkan juga penegak hukum seringkali kehilangan acuan mengenai kepastian hukum.
Akibatnya proses penerapan hukum dapat berlangsung tetapi masyarakat tidak akan memperoleh
hasil optimal. 3) tidak ada supremasi hukum dalam suatu negara sebagai pemegang kedaulatan
hukum. Hal ini disebabkan baik peraturan hukum substantif maupun sistem penegak hukum
sama-sama tidak bisa dipergunakan. Akibatnya, tirani individu dan kolektif yang berwujud dalam
tindakan main hakim sendiri semakin subur dan berkembang dalam masyarakat. Ketiga faktor
di atas, menjadi menarik bilamana dikaitkan dengan problematika penegak hukum di Indonesia.
Usaha untuk menegakkan supremasi hukum perlu ditinjau kembali mulai dari produk hukum
Pemerintah Orde Baru hingga Era Reformasi. Secara lebih khusus, identifikasi problem
penegakan hukum tersebut mencakup beberapa aspek, baik di dalam maupun di luar peraturan
perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung terhadap ketidakberdayaan penegakan
hukum dalam masyarakat.
Usaha untuk menjelaskan ada atau tidaknya kaitan antara peraturan-peraturan hukum
dengan peranan penegak hukum dalam masyarakat akan menjadi prioritas utama dalam
penelitian ini.
Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian
Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang
penting untuk diteliti, yaitu: (1) Apakah supremasi hukum dapat direalisasikan tanpa adanya
pembaharuan-pembaharuan atas konstruksi juridis terhadap berbagai peraturan hukum?; (2)
Bagaimana hubungan antara aspek-aspek juridis-nonjuridis di dalam dan di luar hukum terhadap
ketidakberdayaan penegak hukum dalam menjalankan tugas yang mandiri?; dan (3) Usahausaha konkrit apakah yang telah dilakukan Pemerintahan Gus Dur baik secara juridis maupun
politis yang dapat mengarah pada terciptanya supremasi hukum di Indonesia?
Dari permaslahan penelitian diatas, penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu: (1)
mengidentifikasi berbagai peraturan hukum: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres
yang terkait dengan tugas dan wewenang penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara);
(2) mengklasifikasi ketentuan-ketentuan hukum, baik yang relevan maupun yang tidak, terhadap
supremasi hukum dalam era Indonesia Baru; (3) mengklasifikasi peraturan hukum dan kebijakan
pemerintah yang kotradiktif antara peranan penegak hukum yang satu dengan penegak hukum
yang lainnya; dan (4) mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum yang memberikan peluang
adanya penyimpangan dan penumpukan peranan pada satu institusi tertentu.
Kerangka Teoritis dan Juridis
Apa yang didefinisikan oleh L.A. Harts (1989) kaitan antara hukum, moral dan keadilan,
begitu jelas dalam hubungannya dengan supremasi hukum. Hukum, selain berarti peraturan
yang terdiri dari peraturan-peraturan (law of rulers), juga mengandung moralitas sehingga
bilamana hukum tidak mengartikulasikan keadilan, peraturan itu bukanlah hukum. Bagi Harts
keadilan mutlak harus menjadi bagian terpenting dari hukum unjust law is not law. Senada
dengan itu, Scholten (1999) juga menegaskan bahwa suatu peraturan hukum selain ditentukan
oleh logika alamiah, juga ketentuan hukum itu harus benar-benar mempertimbangkan keyakinan
ruhaniah masyarakat. Karena itu, kewibawaan hukum harus diartikan selain sebagai pembatasan
kekuasaan atas tindakan negara oleh hukum, juga unsur keadilan dan aspirasi ruhaniah
masyarakat mutlak perlu dalam membangun supremasi hukum.
Supremasi hukum bisa diartikan sebagai usaha mengutamakan, atau menempatkan prioritas
hukum lebih utama dari kekuasaan. Perubahan proses sosial yang mendasar ditandai oleh
adanya kewibawaan hukum menjadi syarat perubahan optimal. Revolusi material hukum,
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
56
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
terutama yang menyangkut konstitusi tampaknya menjadi ide yang tidak bisa
dikesampingkan (Miranda Risang Ayu, Kompas, 23-9-1999).
Kehendak pemerintah untuk mengangkat supremasi hukum melalui usaha memperbanyak
Undang-Undang tidak terlalu tepat, Sebuah negara yang menyediakan banyak perundangundangan tidak ada jaminan UU itu mengartikulasikan keadilan masyarakat. Oleh karena itu
penegakan supremasi hukum tidak identik dengan banyaknya undang-undang, melainkan
seberapa jauh undang-undang tersebut memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Supremasi
hukum dapat terwujud bilamana keadilan diperjuangkan melalui proses hukum yang semestinya
(due process) (Kompas, 23-9-1999).
Pada prinsipnya penegakan supremasi hukum merupakan misi the rule of law (Loeby
Loqman. Kompas, 23-9-1999). The rule of law (Inggris) atau Rechtstaats (Jerman) suatu konsep
yang dipergunakan supaya negara dan pemerintahnya, termasuk warga negara tidak melakukan
tindakan kecuali berdasarkan peraturan hukum.
Timothy OHogan di dalam The End of Law dan A.V. Docey dalam Law and The Constitution menyebutkan prinsip-prinsip utama negara hukum dalam kaitannya dengan tegaknya
supremasi hukum. Pertama, the rule of law harus diselenggarakan dalam suatu pemerintahan
yang mengutamakan hukum dan menghindarkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kedua,
the rule of law harus menempatkan kesederajatan untuk menaati peraturan hukum (equality
before the law). Ketiga, kekuasaan negara harus menerapkan cara-cara yang adil dan
terselenggaranya pembagian hak-hak dasar manusia. Keempat, penyelenggaraan peradilan
yang baik harus dilengkapi dengan alat paksa yang dapat menekan tumbuhnya absolutisme.
Kelima, adanya pembagian kekuasaan yang mengisyaratkan tidak adanya kekuasaan negara
pada suatu tangan (J. Thontowi, Jurnal Hukum No. 12 IV, 1999; 92).
Dalam realitas sosial, sebagaimana diklaim di atas terbukti bahwa supremasi hukum tidak
identik dengan banyaknya produk hukum. Kabinet Habibie mencoba melakukan reformasi dalam
bidang hukum, tidak kurang dari 69 produk undang-undang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat bersama Pemerintah. Namun, hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh IMPAK (Inisiatif
Masyarakat untuk Menegakkan Hukum) membuktikan penolakannya.
Dari 18 responden (sementara) kalangan penegak hukum formal, (Pengacara, Polisi, Jaksa
dan Hakim) menyebutkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum
dan polisi amat bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa penegak hukum telah berjalan dengan
baik, dan sebagian ada yang menyatakan kurang baik dan sangat tidak memenuhi tuntutan
(Media Indonesia, 16-9-1999).
Untuk menjelaskan adanya penyimpangan di kalangan penegak hukum dan alasan-alasan
mengapa supremasi hukum tidak bisa ditegakkan di Indonesia, perlu dipertimbangkan pemikiran
Satjipto Raharjo. Penegak hukum dan pengguna hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang
dapat menegakkan hukum untuk keadilan, tapi juga orang dapat menegakkan hukum untuk
digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Maka menegakkan hukum tidak sama
persis dengan menggunakan hukum (Satjipto Raharjo, Kompas 19-7,1999).
Kerangka pemikiran Satjipto tersebut menjadi sangat relevan terutama ketika dipergunakan
untuk melihat bagaimana pemerintah Orde Baru menggunakan hukum bagi pencapaian
kepentingan ketimbang fungsi penegak hukum untuk keadilan masyarakat. Itulah sebabnya
pakar-pakar hukum, seperti Loebby Loqman, Maria Sriwulani Sumarjono dan Sri Redjeki
menegaskan perlunya peninjauan atas seluruh UU Produk Orde Baru. Mengkaji ulang produk
legislatif Orde Baru bukanlah merupakan tugas sederhana, tetapi ini menjadi penting untuk
mengetahui mana yang bisa dan tidak bisa dipergunakan lagi.
Alasan-alasan perlunya pemajuan kembali produk-produk legislatif antara lain, Loebby
Luqman mengakui bahwa kondisi Indonesia (era reformasi) mirip saat memasuki kemerdekaan
tahun 1945. Masyarakat menilai bahwa semua yang berbau Belanda adalah jelek. Pada era
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
57
reformasi, masyarakat juga menganggap bahwa segala sesuatu yang berbau Orde Lama
atau Orde Baru, termasuk perundang-undangannya adalah buruk dan harus diganti. Hal ini
tentu tidak seluruhnya benar. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa produk Undang-Undang
Orde Lama atau Orde Baru tidak berguna lagi, diperlukan sebuah kajian (legislative Reviwe).
Pertimbangan kedua, peninjauan atas produk legislatif Orde Lama atau Orde Baru
sebenarnya terkait dengan banyaknya penyimpangan yang asasi, Sri Redjeki dengan Maria
sepakat bawha, saat ini (Orla-Orba), produk Undang-Undang cenderung tidak taat asas. Produk
undang-undang tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (tidak mengindahkan
basic ideal Hukum). Bahkan tidak jarang ditemuai perundang-undangan yang tumpang tindih
dengan peraturan lainnya, (Kompas, 11-8-1999).
Dengan demikian, untuk meninjau ada atau tidaknya peraturan hukum yang relevan dengan
penegakkan supremasi hukum di era reformasi, peninjauan terhadap produk legislatif Orba mutlak
diperlukan. Usaha tersebut secara khusus mencakup produk-produk hukum yang bertalian
dengan peran penegak hukum dalam mencapai tegaknya fungsi hukum serta terselenggaranya
keadilan masyarakat.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian ini mencakup dua
sumber, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pengambilan bahan hukum primer akan
dikaji melalui peraturan hukum, UU, perpu, dan Keppres. Sementara itu, bahan-bahan sekunder
diambil melalui telaah-telaah ahli di berbagai jurnal hokum, kemudian fakta-fakta hukum diambil
melalui beberapa media massa tertentu diantaranya Republika, Kompas, Kedaulatan Rakyat
dan Tempo.
Untuk pengolahan dan analisis data digunakan teknik analisis data secara diskriptif dengan
menggunakan teknik pengidentifikasian dan pengkategorian masalah sesuai dengan maksud
dan tujuan dari penelitian ini.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penegakan Supremasi Hukum di Awal Reformasi
Pada bagian ini ada beberapa persoalan hukum yang diasumsikan sebagai kegagalan
Pemerintan transisi B.J. Habibie. Kegagalan pemerintah transisi B.J. Habibie tersebut terutama
dalam merestrukturisasi hukum (reformasi hukum) dalam upaya penegakan supremasi hukum.
Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang berkepanjangan pada awal 1997 telah
mendorong rakyat Indonesia untuk menuntut perubahan. Terpilihnya kembali H.M. Soeharto
sebagai presiden pada periode 1998-2003 dan pembentukan Kabinet Pembangunan VII yang
penuh dengan rekayasa politik dan kolusi membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan
keapda pemerintah. Selanjutnya rakyat menuntut reformasi, tidak hanya reformasi di bidang
ekonomi yang menyebabkan krisis namun juga reformasi total. Meliputi reformasi politik, reformasi
sosial dan reformasi hukum untuk menegakkan supremasi hukum.
Untuk menguji sekaligus menjadi legitimasi bagi keinginan rakyat yang menghendaki
kepemimpinan nasional yang baru (dalam pengertian sempit kepemimpinan nasional yang bersih
dari unsur Orde Baru). Seluruh komponen bangsa yang dipelopori oleh mahasiswa menetapkan
agenda reformasi yang dalam waktu singkat harus dilaksanakan oleh pemerintah transisi, yaitu:
1) Adili Soeharto; 2) Bersihkan pemerintahd ari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 3) Cabut dwi
fungsi ABRI; 4) Percepat Pemilu; 5) Cabut lima paket Undang-Undang Politik; 6)
Amandemen Undnag-Undang Dasar 1945.
Pemerintah B.J. Habibie dituntut untuk melaksanakan agenda tersebut dalam batas waktu
yang sangat singkat. Kontroversialnya legitimasi kedudukan B.J. Habibie sebagai pengganti
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
58
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
H.M. Soeharto telah menjadi faktor sukarnya. Presiden B.J. Habibie mempertahankan
jabatannya (Pasal 8 UUD 1945). Keterkaitan B.J. Habibie dengan Orde Baru membuat B.J.
Habibie dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagiand ari sistem pemerintahan
reformasi. Hal ini dapat terlihat dari penolakan Laporan Pertanggungjawaban B.J. Habibie pada
Sidang Umum MPR Oktober 1999. Penolakan ini tentu saja mengandung konsekuensi politis
yaitu , B.J. Habibie tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon Presiden untuk periode 19992004. Penolakan B.J. Habibie sekaligus membuktikan awal dari pengaruh Partai Golkar yang
mulai menurun. Dengan demikian pencalonan B.J. Habibie oleh partai Golkar sebagai calon
Presiden tidak cukup pantas diajukan dalam Sidang Umum MPR.
Kedudukan B.J. Habibie dianggap bagian dari rezim Orde Baru dan orang dekat mantan
Presiden H.M Soeharto jelas tidak bisa diterima oleh kalangan reformis. Khususnya dalam
kaitannya dengan usaha memperbaiki sistem peradilan.
Sistem Peradilan Era Pemerintahan Transisi B.J. Habibie
Usaha melakukan peningkatan penegakan supremasi hukum tidak saja tergantung dari
para penegak hukumnya, melainkan juga dari upaya kongkrit melalui perbaikan Undang-undang.
Pertanyaannya adalah apakah usaha-usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan transisi
B.J. Habibie telah mengarah kepada perbaikan supremasi hukum.
Dalam waktu singkat, pemerintahan transisi dituntut dapat menggelar pengadilan bagi
Soeharto, karena dianggap pada saat berkuasa, Soeharto telah melakukan berbagai
penyelewengan. Diantaranya kolusi dan nepotisme (selanjutnya disebut KKN), pelanggaran
HAM dan penyalahgunaan wewenang sebagai Presiden melalui berbagai produk perundangan
(Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres dan Inpres). Misalnya Keppres tentang Mobil Nasional
yang melanggengkan praktek monopoli dan perlakuan diskriminatif terhadap satu kelompok
tertentu (dalam hal ini pemberian fasilitas khusus kepada keluarga Soeharto).
Sebelum diuraikan secara lebih jauh, apakah pemerintahan transisi B.J. Habibie berhasil
atau gagal melaksanakan agenda reformasi. Ada beberapa hal menarik yang merupakan
perubahan besar dalam rangka kehidupan berpolitik pada era B.J. Habibie. Diakui yakni
kebebasan pers yang mencerminkan kebebasan berpendapat menjadi lebih leluasa, desekralisasi
lembaga kepresidenan dengan sistem politik yang lebih terbuka dan lenturnya birokrasi
pemerintahan, merupakan terobosan yang tidak pernah dijamin bahkan tabu untuk dibicarakan
pada masa Orde Baru (Kompas, 26/11/1999). Konsep B.J. Habibie tentang pemerintahan yang
lebih terbuka merupakan bukti bahwa, pada dasarnya pemerintahan transisi telah mencoba
proses demokrasi dan berupaya mendorong percepatan reformasi. Namun kehendak reformasi
total tersebut tidak didukung oleh instrumen hukum yang diperlukan. Memang benar bahwa
pada masa pemerintahan transisi B.J. Habibie, mampu menerbitkan sekitar 67 Undang-Undang.
Namun banyaknya undang-undang tidak identik dengan jaminan terciptanya supremasi hukum.
Abdul Hakim Garuda Nusantara (Forum Keadilan Edisi No. 20, 22/8/ 1999). mengemukakan
bahwa pada dasarnya Pemerintahan transisi B.J. habibie hanya memperbanyak UndangUndang. Memproduk undang-undang, tentu saja berkaitan dengan agenda reformasi yaitu
melakukan reformasi hukum. Reformasi hukum pada dasarnya mengandung pengertian bahwa
hukum hendak diubah menjadi ideologi hukum yang berorientasi kepada keadilan dan kepastian
hukum. Ideologi hukum yang sebelumnya adalah ideologi instrumentalis yang mementingkan
kekuasaan, diubah menjadi hukum yang mengedepankan supremasi hukum.
Untuk terciptanya supremasi hukum, dimana peraturan hukum dapat menjadi instrumen
pengatur dan juga kepastian bagi masyarakat menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara diperlukan
tiga aspek yang harus dilakukan yaitu, tahap pertama, adalah pada aspek substansi hukum,
dengan perbaikan Undang-Undang. Tahap kedua adalah pada aspek struktur hukum,
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
59
yaitu dengan perbaikan pada struktur kekuasaan yang berpengaruh pada penegakan hukum.
Yang dimaksud adalah reformasi pada sistem kekuasaan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Tahap terakhir, adalah pada aspek budaya hukum, Artinya, reformasi dilakukan pada usaha
menumbuhkan nilai-0nilaiu yang memihak pada supremasi hukum. Menyelesaikan segala urusan
menurut prosedur hukum yang benar dan pasti termasuk pada penerapan persamaan di depan
hukum dan mengeliminir diskriminasi dalam bentuk apapun di hadapan hokum (Forum Keadilan
Edisi No. 20, 22/8/ 1999).
Pada dasarnya B.J. Habibie beserta Kabinet Reformasi telah memberikan reaksi yang positif
pada desakan reformasi, khususnya reformasi hukum. Namun demikian, usaha-usaha yang
dilakukan pemerintah transisi ini tidak cukup untuk memecahkan persoalan hukum yang mengakar
selama 32 tahun. Terutama masalah supremasi hukum. Secara substantif Pemerintahan transisi
B.J. Habibie telah mengundangkan beberapa produk perundang-undangan yang terkait dengan
respon atas agenda reformasi. Khususnya reformasi pada bidang politik (SI MPR, Pemilu,
Pencabutan 5 Paket Undang-Undang Politik dan pemberantasan KKN).
Jika diperhatikan secara prosedural, pemerintahan transisi B.J. Habibie pada dasarnya
telah mengambil langkah yang cukup relevan dengan merumuskan perundang-undangan politik
(sesuai pula dengan agenda reformasi). Namun, pemerintahan transisi B.J. Habibie gagal dalam
melaksanakan misi itu oleh karena terjepit pada dua kelompok besar yaitu kelompok reformis
dan kelompok Orde Baru (yang menciptakan status quo). Bahwa B.J. Habibie adalah bagian
penting dari Orde baru membuat pemerintahan transisi mandul dalam melaksanakan supremasi
hukum dan peradilan. Satu agenda penting reformasi adalah pengadilan Soeharto termasuk
yang tidak sama sekali tersentuh dalam pemerintahan transisi B.J. Habibie.
Misalnya, Pengadilan Soeharto yang terkesan diulur-ulur, padahal untuk pengusutannya
bahkan telah diamanatkan oleh Pasal 4 TAP MPR No. X/MPR/1998. Pasal ini menyebutkan bahwa
upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun, baik pejabat negara,
mantan pejabat negara, keluarga dan kroni-kroninya, termasuk mantan Presiden Soeharto ke
Pengadilan. Beberapa diantaranya ialah pertama, di tengah proses penyelidikan dan penyidikan
kasus ini, mantan Presiden Soeharto terkena stroke, serangan pertama tanggal 22 Juli 1999.
Akibatnya, secara medis Soeharto dinyatakan tidak bisa secara kooperatif dalam proses penyidikan
dan penyelidikan. Apabila kemudian kondisi tersebut dijadikan alasan oleh tim penasihat hukum
matan Presiden Soeharto (Jawa Pos, 11/1999). Kedua, batas waktu pemerintahan transisi untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan TAP MPR No. X/1998 sangat pendek. Apalagi ditambah
dengan berbagai tekanan politik dari Orde Baru.
Meskipun Undang-Undang tentang Pemberantasan KKN telah diundangkan, intervensi
kekuasaan politik ke pengadilan tetap dominan. Sikap pengadilan yang ambivalen tersebut terlihat
ketika tersadapnya pembicaraan pertelepon antara Andi M. Ghalib dengan B.J. Habibie.
Khususnya menyangkut tentang proses pengadilan Soeharto, kroni-kroni dan keluarganya.
Contohnya, pada masa pemerintahan transisi B.J. Habibie, Tomy Soeharto sempat divonis bebas
dalam kasus tukar guling Bulog dengan Goro. Kasus ini dapat dijadikan contoh, bahwa
kemandirian peradilan pada masa transisi belum terwujud. Adanya campur tangan kekuasaan,
bahkan mantan penguasa pada pengadilan kasus Tommy sekaligus menandakan bahwa
supremasi hukum belum bisa ditegakkan karena masih sangat diskriminatif. Sehingga mustahil
apabila kemudian banyak pihak berharap banyak pada pemerintahan transisi untuk mengadili
Soeharto.
Hal ini disebabkan oleh, pertama, masih kuatnya pengaruh kekuasaan Orde Baru. Kedua,
hal ini sekaligus menjadi indikasi tentang ketakutan pemerintahan transisi. Bahwa terungkapnya
kasus KKN pada masa Orde Baru juga sekaligus akan melibatkan pemerintahan transisi. Ketiga,
adanya tawar menawar politik yang memberi jaminan bahwa dengan tidak mengungkap
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
60
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
kasus-kasus tersebut secara tuntas maka ada pihak dari parpol besar mempertahankan
posisi B.J. Habibie, sebagai presiden sampai dengan 2004.
Alasan lain mengapa Kabinet Reformasi telah gagal secara positif dalam merealisasikan
agenda reformasi dalam aspek perundang0undangan tersebut. Lihat pada tabel produk
perundang-undangan pemerintahan transisi B.J. Habibie dalam bidang hukum terlampir.
Berdasarkan data di atas pemerintahan transisi B.J. habibie tidak sepenuhnya gagal dalam
merealisasikan hukum secara substantif, khususnya merumuskan berbagai produk perundangundangan.
Beberapa langkah perbaikan pada sistem peradilan sebenarnya telah dilakukan pemerintahan
transisi B.J. Habibie (sekali lagi substantif), yaitu: 1) Menyatuatapkan kekuasaan kehakiman di
bawah MA (Undang-Undang No. 35/199 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan
kehakiman); 2) Pembuktian intervensi terbalik pada kasus pemberantasan KKN (Undang-Undang
No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN); 3) Mengurangi
intervensi politik pada sistem peradilan (Undang-Undang No. 27/1999 tentang Pencabutan UndangUndang No. 11/PN 85/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi); 4) Mengeliminir
diskriminasi di hadapan hukum (Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia).
Meskipun belum ada bukti mengenai dampak positif keempat Undang-Undang terkait
peradilan upaya tersebut tetap berarti. Akan tetapi benarkah keempat Undang-Undang tersebut
sesuai dengan kehendak reformasi, ada beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai indikasi.
Dari keempat produk perundang-undangan pemerintahan transisi B.J. Habibie ini. Maka
keempat-empatnya mengandung kontroversi. hal ini disebabkan oleh masih kuatnya unsur politis
pada setiap pembentukan dan realisasi Undang-Undang tersebut di lapangan. Masih
diskriminatifnya pemberlakuan Undang-Undang tersebut pada berbagi kasus dan belum efektifnya
produk perundang-undangan tersebut di pengadilan, dengan indikator bahwa masih kuatnya
kekuasaan di luar kekuasaan yudikatif, pada proses pengadilan.
Kegagalan Pemerintahan Transisi B.J Habibie Mengadili Soeharto
Perspektif Hukum dan Politik
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hubungan antara gagalnya B.J Habibie mengadili
Soeharto dengan skandal-skandal hukum lainnya. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang
perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan hal tersebut, yaitu: (1) benarkah kegagalan ini ada
hubungannya dengan keinginan B.J Habibie untuk dicalonkan kembali sebagai presiden pada
periode 1999-2004, atau (2) apakah kegagalan ini hanya merupakan cermin ketidakberesan
kinerja kabinet reformasi, khususnya dalam penegakan supremasu hukum?
Uraian mengenai hal tersebut akan dimulai dari konstruksi hukum pidana khusus dalam hal
ini korupsi. Pada dasarnya Kabinet Reformasi telah memberikan respon positif pada tuntutan
untuk mengadili Soeharto. Hal itu dibuktikan dengan upaya merumuskan pembentukan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya, dengan menyiapkan perangkat perundang-undangan
untuk pemberantasa KKN, UU No.28 tahun 1999. Namun demikian dalam realisasinya
pemerintahan BJ Habibie terkesan lamban, mengapa demikian?
Adanya kesalahan konstruksi hukum.
Sejak awal lahirnya reformasi terdapat kesalahan konstruksi hukum terutama dalam
kaitannya dengan wewenang untuk melakukan penyidikan, seperti pada kasus tindak pidana
korupsi atau penyalahgunaan wewenang/jabatan. Hal itu ditandai dengan timbulnya konflik
kewenangan antara Kepolisian dan kejaksaan. Konflik tersebut bermula dari ketentuan KUHAP
yang menyatakan, pertama, Jaksalah yang mempunyai wewenang menjadi koordinator penyidik.
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
61
Kedua, Tim penyelidikan korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung. Ketiga, penyidikan menjadi
wewenang Polri, namun karena keterbatasannya Polri untuk menangani kasus korupsi diserahkan
kepada Kejaksaan. Payung hukum dari ketentuan tersebut adalah Inpres No.15 tahun 1983,
UU No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan, dan Keppres No.55 tahun 1991.
Dengan demikian, jelaslah bahwa penanganan kasus korupsi mengalami perubahan dari
zaman ke zaman. Namun yang jelas wewenang korupsi lebih banyak ada pada ke Jaksaan
ketimbang Kepolisian. Akibatnya intervensi kekeuasaan eksekutif dalam proses peradilan begitu
mudah. Sebab, posisi Jaksa Agung merupakan kepanjangan tangan kekuasaan eksekutif di
peradilan. Sehingga sejalan dengan itu posisi basah sebagai Jaksa Agung ini dapay disinyalir
lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan umum.
Peran dan wewenang Jaksa Agung terbukti berkaitan dengan kenyataan kepemimpinan
yang kurang profesional dalam sejarah. Pada sekitar tahun 1955 Jaksa Agung di jabat oleh R.
Soeprapto yang secara sistematis telah berupaya menegakkan kewibawaan kejaksaan, hal itu
dilakuakn dengan upaya mengedepankan wibawa hukum. Namun sikap ini dinilai penguasa
waktu itu sebagai sikap yang tidak sejalan dengan semangat revolusi. Demikian jua ketika jabatan
Jaksa Agung di ganti oleh Gatot Tanumihadjo dari MURBA sangat mendukun konsep revolusi
Bung Karno. Namun Gatot pun mengakhiri jabatannya dengan sejarah yang sama seperti ketika
R. Soeprapto diberhentikan dari jabatannya, karena membongkar kasus penyelundupan di
Tanjung Priok yang melibatkan Brigjend Ibnu Sutowo yang sangat dilindungi oleh Letjen A.H
Nasution, KSAD TNI waktu itu.
Rentetan kejadian tersebut kemudian menggugah kesadaran militer betapa strategisnya
jabatan Jaksa Agung tersebut, dan begitu berbahayanya jika dipegang oleh ahli hukum yang
idealis yang amenjadi hukum sebagai panglima. Oleh karenanya, cukup beralasan kalau pejabat
Jaksa Agung selalu berasal dari militer. Militeristik dikalangan kejaksaan tampak jelas sebagai
peluang baik untuk terciptanya penegakan hukum yang inkonsisten maupun peluang bagi
terjadinya intervensi pihak eksekutif. Perubahan mulai tampak ketika pada masa Orde baru
ketika jabatan Jaksa Agung ini dikembalikan kepada Jaksa karir, Singgih, SH. Namun hal itu,
tidak seluruhnya dilakukan, sebab umumnya Jaksa Agung Muda dibidang intelejen tetap dari
kalangan militer. Tidak lama kemudian ketika di era transisi pemerintahan BJ. Habibie jabatan
Jaksa Agung kembali dipegang oleh militer, yaitu HM. Andi Ghalib. Sehingga jabatan ini dapat
digunakan sebagai alat untuk merekayasa pengusutan dan penyidikan terhadap berbagai kasus
besar. Kasus dugaan korupsi Soeharto beserta kroni-kroninya dan berbagai skandal hukum,
seperti skandal Bank Bali tidak dapat dituntaskan.
Adanya Tekanan dari berbagai pihak
Kuatnya pengaruh mantan Presiden Soeharto kepada pemerintahan BJ. Habibie berimplikasi
besar terhadap proses penegakan supremasi hukum yang telah dirumuskan. Hal itu ditandai
dengan sulitnya membawa mantan presiden Soeharti ke Pengadilan. Realita tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, adanya tekanan dari Panglima Tinggi ABRI Wiranto terhadap
BJ. Habibie. Pengakuan ini cukup beralasan, mengingat hanya dua hari setelah Presiden
Soeharto mengundurkan diri Panglima ABRI Wiranto waktu itu dalam siaran persnya berjanji
akan melindungi Presiden Soeharto dan keluarganya. Kedua, tekanan tidak langsung dating
dari mantan penguasa Orde Baru itu sendiri. Keterikatan yang erat antara BJ Habibie dengan
Orde Baru justru membuat pemerintahan transisi menjadi gamang. Bukan saja karena Soeharto
dengan BJ Habibie mempunyai hubungan khusus melainkan mereka sama-sama terikat dengan
prinsip hutang budi. Oleh karena logikanya jika kasus korupsi yang disangkakan kepada Soeharto
dibawa ke pengadilan, maka hampir bias dipastikan separuh pejabat pemerintahan transisi akan
ikut terseret ke pengadilan, minimal sebagai
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
62
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
saksi. Demikian pula halnya penegakan hokum dibidang HAM, sama-sama tumpul, meskipun
legitimasi hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di amasa lalu melalui UU No.39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena hal itu tidak didukung oleh kemauan politik dari
pemerintah.
Jika demikian halnya, kegagalan supremasi hukum dalam pemerintahan BJ. Habibie
memang sangat komplek, selain aspek politik juga budaya untuk menjunjung tinggi kekuasaan
Soeharto sebagai mantan penguasa Orde Baru sangat mengakar, baik dalam sipil maupun
militer. Peribahasa Jawa menyebutkan Mikul duwur mendhem jero tampaknya berlaku pada
setiap usaha untuk mengungkap kasus Soeharto.
Supremasi Hukum Dalam Kabinet GusDur
Ada beberapa parameter utama dalam pembahsan mengenai penegakan supremasi hukum
pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid (GusDur). Beberapa parameter yang dimaksud
adalah (1) sejauhmana reposisi polisi sebagai penegak hukum di masyarakat telah dilakukan;
(2) bagaimana pembaharuan peradilan; (3) dan terobosan-teroban yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung. Dengan membahas sekitar masalah-maslah tersebut, akan terlihat sejauh
mana reformasi menuju supremasi hukum pada pemerintahan Abdurrahman Wahid telah
dilakukan.
Reposisi Polisi sebagai penegak hukum masyarakat
Salah agenda penegakan supremasi hukum sebagai bagian dari paket reformasi, adalah
membersihkan peradilan dari penyelewengan-penyelewengan termasuk unsur-unsur yang terkait,
seperti aparat kepolisian, Jaksa, Hakim dan Pengacara. Melihat kepolisian berada dalam unsur
peradilan, maka pelaksanaan tugas kepolisian yang bersih adalah juga termasuk usaha
penegakan hukum yang sesungguhnya.
Organisasi kepolisian secara umum mempunyai tujuan terciptanya kondisi tertib hukum
(maintaining order) dan keadilan hukum (enforcing of law) dalam semua usahanya. Kondisi dari
tujuan-tujuan itu berarti terciptanya supremasi hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Artinya
baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki kesetiaan dalam mematuhi peraturan hukum
yang berlaku. Usaha-usaha kepolisian dalam menciptakan hal tersebut sangat beraneka tajam,
sesuai dengan tuntutan keadaan dan sistem hukum disuatu negara tersebut, termasuk pula
kepolisian di Indonesia.
Tugas kepolisian Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 13 UU no. 28 Tahun 1997
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) selaku alat negara penegak hukum
memelihara serta meningkatkan tertib hukum; b) melaksanakan tugas kepolisian selaku
pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya
ketentuan perundang-undangan; c) bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan
pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara
guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat; d) membimbing masyarakat bagi
terciptanya kondisi yang menunjang usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf c; e) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam sistem peradilan, polisi adalah sebagai institusi yang bertugas mengadakan
penyidikan terhadap suatu kasus. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 UU No.28 tahun 1997
ayat (1) poin (a) yang menyatakan, bahwa diantara tugas kepolisian adalah melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan Peraturan perundang-undangan lainnya; poin (b) menyelenggrakan identifikasi kepolisian,
kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
63
kepentingan tugas kepolisian. Tugas tersebut adalah berkaitan dengan peradilan yang
disebut criminal justice system.
Sebagai bagian dari criminal justice system, maka kemandirian polisi dari intervensi pihakpihak lain yang sering merusak citra kepolisian dan menghambat tugas pokok kepolisian, adalah
hal sangat penting bagi lembaga kepolisian, dalam menentukan kebijakan sendiri sesuai
kebutuhan dan tuntutan. Dalam mrangka menuju kemandirian dan profesionalisme kerjanya,
maka polisi yang telah berpuluh tahun lamanya menjadi subordinasi TNI, maka sejak tanggal 1
Juli 1999 telah diadakan pemisahan diantara keduanya, yang cukup membawa implikasi besar
terhadap polisi dalam kelembagaannya. Mereka (Polisi) menganggap, sebagai Polisi tidak merasa
lagi adanya dualisme dengan tentara dalam menjalankan tugas, baik sebagai aparat penegak
hukum (law enforcement), penjaga ketertiban (law order maintenance), maupun termasuk di
dalamnya melakukan fungsi pembasmi kejahatan (crime fighter).
Pada era pemerintahan Gusdur telah dilakukan upaya-upaya konkrit untuk membenahi
kinerja kepolisian dengan cara melakukan reposisi dan pemecatan terhadap aparat yang
melakukan pelanggran secara serius. Serta juga upaya mempublikasikan report kinerja kepolisian
secara terbuka kepada masyarakat. Namun demikian masih terdapat sejumlah kendala dalam
proses pembenahan tersebut, antara lain: 1), masih rendahnya kualitas SDM kepolisian yang
berimplikasi pada buruknya kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga kondisi tersebut
masih belum menghilangkan stigma masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Rendahnya SDM
kepolisian itu tidak terlepas dari faktor-faktor seperti rekruitment, pendidikan dan penggajian. 2)
Pendidikan yang militeristik dalam proses membangun profesionalisme kinerja kepolisian. Dalam
ketentuan pasal 20 UU No.28 tahun 1999 tentang kepolisian NKRI dijelaskan, bahwa pembinaan
kemampuan profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Panglima.
Ini berarti pembinaan profesi tersebut tidak sepenuhnya oleh instansi Polri tapi oleh Panglima
ABRI. 3) Sistem penggajian yang masih rendah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Litbang
Kompas (30 Juni 2000) ditemukan fakta, maka seluruh Polisi yang diwawancarai tidak menutup
mata atas kemungkinan penyalahgunaan profesi oleh sesama Polisi. Kebanyakan hal tersebut
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 4) Sistem rekrutmen yang tidak menggunakan
standar yang jelas, dimana pengaruh suap dan nepostime menjadi tradisi yang menyeluruh
dalam lembaga kepolisian. 5) Faktor politik yang banyak diintervensi oleh berbagai pihak terutama
eksekutif. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya polisi masih belum bisa bersikap profesional.
6) Faktor citra masyarakat yang masih kuat menstigmatisasi polisi dengan label-label yang jelek,
sehingga mereka sering merasa dilematis dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat.
Pembaharuan peradilan tanpa perubahan sistem
Usaha menegakkan supremasi di Indonesia, adalah dimulai dengan mereformasi peradilan
sebagai ujung terakhir proses penegakan hukum. Pengertian pembaharuan sistem adalah
pembaharuan kesatuan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Misalnya, ada aturan tentang
kepengacaraan yang selama ini masih dianggap sebagai bagian luar dari sistem peradilan, dan
karena pengacara tidak termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peradilan, maka ia
harus dimasukkan sebagai salah satu dari komponen peradilan.
Terdapat beberapa pendapat yang kontroversial mengenai perlunya perubahan sistem
peradilan tersebut, yaitu: pertama, pendapat yang menyebutkan pembaharuan sistem peradilan
harus dimulai dengan membubarkan atau menghentikan seluruh Hakim-hakim yang ada selama
ini, pandangan ini dikemukankan oleh Daniel S. Lev. Kedua, pembaharuan perdailan perlu
dilakukan namun terbatas pada segi-segi tertentu saja. Misalnya, mengupayakan sistem kontrol
peradilan yang lebih terbuka, dan kemandirian Hakim lebih ditingkatkan. Ketiga,
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
64
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
pembahruan peradilan harus dilakukan secara simultan dari keseluruhan komponen sistem
yang terkait di dalamnya.
Mahkamah Agung: suatu terobosan
Mahkamah Agung adalah benteng terakhir suatu peradilan. Pada dirinya masyarakat
mengharapkan suatu keadilan. Selama ini sistem peradilan termasuk MA telah terjangkiti oleh
berbagai stigmatisasi buruk dari masyarakat yang pada intinya berpusar pada terjadinya praktek
KKN atau yang disebut mafia peradilan.
Kemudian kondisi tersebut, kemudian sebuah terobosan pembaharuan disampaikan oleh
GusDur. Menurutnya, untuk membangun lembaga yudikatif yang bersih dan berwibawa agar
perekrutan hakim agung dan penetapan ketua MA terbuka bagi orang-orang yang buka hakim
karir. Sebab, jika hal itu terbuka dilakukan terbuka untuk masyarakat luas, tapi dengan
pertimbangan integritas tinggi dan punya pengalaman penegakan hukum, maka diharapkan
perubahan di MA akan terasa oleh masyarakat. Namun demikian, para penegak hukum dari
lingkungan masing-masing perlu juga diberi peluang untuk masuk kesana melalui pemikiran
masyarakat dan seleksi yang ketat dari DPR.
Kontroversi Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kaitannya dengan supremasi
hukum Supremasi Hukum
Secara umum masyarakat memandang GusDur sebagai pendekar demokrasi yang humanis.
Akan tetapi, seringkali kebijakan yang dikeluarkannya banyak keluar dari peraturan hukum.
Kebebasan dalam berdemokrasi mulai tumbuh, tetapi kepastian hukum terabaikan. Beberapa
bukti yang dapat ditunjukkan dari hal tersebut antara lain: Pertama, praduga tak bersalah, Dalam
kaitannya dengan penyimpangan terhadap asa praduga tak bersalah ini, misalnya kasus
pemecatan dua menteri dalam kabinetnya, yaitu Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla, pada
tanggal 24 April 2000. Mereka dituduh melakukan KKN tanpa proses pembuktian yang transparan.
Meskipun sebenarnya presiden punya hak prerogatif untuk melakukan pemecatan terhadap
menterinya itu. Namun dengan menuduh dan memacatnya tanpa dasar bukti hukum yang kuat,
maka hal itu telah melanggar asa praduga tak bersalah. Karena itu tepat kiranya jika DPR
melakukan pemanggilan kepada Presiden untuk dimintai keterangan mengenai alasan-alasan
pemberhentian kedua menterinya tersebut. Dalam kasus itu seolah-olah GusDur menempatkan
dirinya sebagai Hakim.
Kedua, peradilan Soeharto Penuh Kegamangan, Salah satu tuntutan reformasi yang paling kuat adalah supaya mantan presiden Soeharto dibawa ke pengadilan terkait dengan kasuskasus KKN di masa pemerintahannya. Tuntutan tersebut menguat terutama pada masa
pemerintahan BJ Habibie dengan Jaksa Agungnya Andi M. Galib. Namun demikian, karena
pemerintahan BJ Habibie disinyalir oleh masyarakat sebagai pemerintahan Orde Baru jilid II,
maka sangat tidak mungkin membawa Soeharto ke meja peradilan terlebih Habibie sendiri menjadi
anak masnya Soeharto ketika masih menjabat presiden.
Pemerintahan reformasi mewarisi dihentikannya kasus Soeharto. Dampak negatif masih
dirasakan pada pemerintahan GusDur. Jaksa Agung yang baru, Marzuki Darusman menyadari
bahwa kredibilitas pemerintahan barunyaakan diukur dari seberapa jauh lembaganya mampu
membuat perhitungan hukum terhadap Soeharto. Karena itu, tindakan pertama yang ia lakukan
adalah membuka kembali penyidikan Soeharto untuk kasus 3 Yayasannya, Dharmais,
Supersemar da Dakab, dimana Soeharto sebagai tersangkanya. Ketiga Yayasan ini diduga
memperoleh dana dari semua BUMN dengan penyalahgunaan wewenang melalui PP No.15
tahun 1976 dan Kepmenkeu No.33 tahun 1978. Penyalurannya disinyalir hanya ke sejumlah
kroninya saja. Dengan demikian, ada penyalahgunaan keuangan negara tidak kepada seluruh
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
65
rakyat tetapi kepada beberapa orang saja, dan ini jelas melanggar ketentuan UUD 1945
khususnya Pasal 33.
Setelah melalui proses panjang, dan peradilanpun dijalankan secara spektakuler, namun
Jaksa selaku penuntut umum tidak pernah bisa mengahdirkan Soeharto di Pengadilan. Sehingga
pada putara ketiga sidang pengadilan terhadap Soeharto menetapkan bahwa kasus Soeharto
tidak bisa diadili karena tiga kali Jaksa tidak bisa menghaduirkan terdakwa.
Putusan tersebut merupakan puncak dari kekecewaan masyarakat terhadap pengadilan
Soeharto yang berlarut-larut. Bahkan tidak kurang GusDur pun mengungkapkan kekecewaannya.
Ia meminta pjs MA untuk mencari hakim yang bersih untuk menangani kasus Soeharto.
Ada beberapa hal yang perlu dicermati pada penetapan hakim tersebut. Pertama, penolakan
hakim terhadap kasus Soeharto yang terlalu cepat, dalam hal ini mestinya hakim menunda dulu
persidangan sampai Soeharto sembuh. Kedua, pencoretan kasus Soeharto seharusnya tidak
dilakukan. Sebab, dihapusnya kasus Soeharto seolah-olah kasus ini tidak pernah ada. Sebab,
mestinya kasus ini disimpan karena bisa dibuka kembali lain waktu. Ketiga, tidak hadirnya
terdakwa, mestinya hal ini dikoordinasikan dengan tim dokter yang menangani Soeharto.
Perdilan HAM Para Jenderal
Keraguan pemerintahan GusDur dalam menegakkan supremasi hukum, khususnya
peradilan juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan peradilan HAM. Secara de jure, pemerintahan
GusDur sudah mengundangkan UU no.39 tahun 2000 mengenai HAM, namun dalam
pelaksanaannya sulit menjangkau para tokoh militer yang terkena kasus HAM.
Kenyataan ini terlihat ketika aparat penegak hukum tidak mampu secara cepat membawa
kasus pelanggaran HAM ke Pengadilan. Kasus-kasus yang dianggap penting, tetapi terabaikan
pelaksanaannya, seperti pembumihangusan Timor-Timur, operasi DOM Aceh, kasus Tanjung
Priok dan kasuS Tommy Soeharto. Menurut pandangan masyarakat internasional, pihak militer
terlibat di belakang kasus tersebut. Atas dasar itu, PBB membentuk komisi penyidik CIET (Commission of Inquiry on East Timor). Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri membentuk Komisi
Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM pada tanggal 22 September 1999. Misi utama komisi ini
adalah menyelamatkan para pelaku pelanggaran HAM dari pengadilan internasional. Komisi ini
diketahui oleh Albert Hasibuan.
Setelah beberapa bulan bekerja KPP HAM ini menyerahkan hasil temuannya pada tanggal
31 Januari 2001 kepada Jaksa Agung dan CIET menyerahkannya kepada Sekjend PBB Kofi
Anan. Menurut laporannya KPP HAM menemukan keterlibatan secara langsung sejumlah petinggi
militer, para pimpinan milisi dan para Bupati dalam aksi bumi hangus tersebut. Demikian pula,
sejumlah Jenderal aktif seperti Wiranto, diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui praktek
pelanggaran HAM di Timor-Timur. Menurut catatan Forum Keadilan (13/1/2000) ada tiga puluh
nama yang disebut terlibat dalam kasus tersebut. Setidak-tidaknya kejahatan atas kemanusiaan
dimana pejabat dianggap terlibat dengan membiarkan terjadinya kejahatan kemanusiaan itu
berlangsung, dan mereka bisa diadili.
Terhadap temuan KPP HAM tersebut, kalangan DPR menolak keras. Meraka menuduh
anggota KPP HAM anti Islam, anti Habibie, tidak nasionalis, bekerja atas motif balas dendam
dan lain sebagainya (Tempo, 6/2/2000).
Kasus Aceh
Pada masa pemerintahan BJ Habibie telah dibentuk Komisi Independen pengusustan tidak
kekerasan di Aceh yang diketuai oleh Zamzam. Meskipun legitimasinya lemah, namun
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
66
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
komisi ini telah menyudahi pengusutan terhadap para pelaku kejahatan di Aceh. Tercatat
ratusan nama prajurit TNI, mulai dari Kopral sampai Kolonel di Kodam I Bukit Barisan, sebagai
tersangka. Kemudian Komisi ini berdasarkan temuannya tersebut, merekomendasikan
dibentuknya pengadilan semacam Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB).
Kontan saja rekomendasi Komisi Independen tersebut, ditentang oleh banyak piahk, sebab
MAHMILUB dipandang tidak cukup untuk menangnai kasus ini. Disamping itu, temuan ini tidak
mencantumkan orang-orang yang bertanggungjawab mengambil keputusan politik terhadap
daerah itu, tetapi terbatas pada prajurityang terlibat dilapangan saja. Padahal kejadian dilapangan
tidak terlepas dari kebijakan institusional TNI dengan berbagai bentuk operasi militernya, mulai
dari Benny Moerdany, Tri Strisno, Edy Sudrajat, Faisal Tanjung, sampai Wiranto, layak dijadikan
tersangka. Termasuk Gubernur Aceh ketika itu, Ibrahim Hasan yang menyetujui DOM di Aceh
sejak tahun 1989 hingga 1998.
Konsekuensi dari lingkaran rumit dalam proses pengungkapan dan peradilan kasus DOM
Aceh yang melibatkan unsur TNI, kemudian sangat memperlambat proses penyelesaiaannya
oleh pemerintahan reformasi. Baru satu kasus yang sudah ditindaklanjuti, yaitu kasus
pembunuhan Teungku Bantaqiyah (Kompas, 14/12/2000). Menurut temuan Komisi Independen
dalam kasus ini aparat telah memvonis mati Tengku Bantaqiyah beserta para pengikutnya, tanpa
mengindahkan asa praduga tak bersalah. TNI tidak punya cukup bukti untuk membantahnya,
bahwa korban terbunuh dalam sebuah kontak senjata, demikian keterangan para saksi.
Kasus Tanjung Priok
Kemajuan yang dicapai selama masa reformasi selain kebebasan pers dan berorganisasi,
juga diapresiasinya aspirasi keluarga korban kekerasan untuk mengajukan tuntutan. Beberapa
Tim atau organisasi yang peduli terhadap korban terbunuh mulai tumbuh, termasuk Tim yang
dibuat masyarakat muslim Tanjung Priok, yaitu Koordinator Keluarga Besar Korban Kasus (KBKK)
Tanjung Priok, yang diketuai oleh Amir Biki.
Pada masa BJ Habibie, pemerintah melalui Komnas HAM yang diketuai oleh Bahrudin
Lopa, melakukan pencarian fakta-fakta mengenai kasus Priok. Setelah menyelesaikan tugasnya
Komisi ini, kemudian merekomendasikan kepada Pemerintah agar pelaku dan penanggungjawab
pelanggaran HAM diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum. Namun sayangnya kasus ini
terkatung-terkatung dikarenakan belum ada payung hukum yang bisa menjerat para pelaku
ketika itu. Kemudian atas deskan masyarakat luas dibentuk KPP HAM yang berfungsi membantu
Komnas HAM dalam menindaklanjuti pekerjaan yang sudah dilakukan, tetapi tidak tuntas. Hal
itu disinyalir karena penangungjawab pemerintahan dan penanggungjawab peristiwa priok itu
masih berada dalam kekuasaan saat Komnas HAM melakukan penelitian.
Deskriminasi tampak dalam Tim KPP HAM tersebut, dimana mayoritas anggotanya adalah
non muslim yang jelas tidak menguntungkan bagi keluarga korban yang notabenenya adalah
muslim. Hal itu kemudian akhirnya, tidak bisa mengungkap secara adil kasus tersebut kepada
masyarakat. Sebab, pada pertengahan Juni 2000 Komnas HAM kembali mengumumkan hasil
temuannya yang menyatakan, bahwa komisi tidak menemukan bukti terjadinya pembantaian
massal dalam kasus Tanjung Priok. Alasannya aparat menembak karena terdesak , dan juga
ditegaskan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh aparat, tetapi juga oleh
masyarakat yang beringas.
Pertemuan Presiden dengan Tommy Soeharto
Pelanggaran etis dan moral yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, adalah
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
67
kasus pertemuannya dengan Tommy Soeharto yang statusnya sebagi terdakwa dalam kasus
Korupsi tukar guling tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti di Kelapa Gading.
Sehingga pada 14 Oktober 1999 terdakwa Tommy bersama Ricardo Gelael di vonis bebas
oleh Hakim. Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti dan unsur merugikan
negara tidak ada. Tidak adanya kerugian negara, sebab Bulog tidak mengajukan tuntutan perdata
atas kerugian itu (Forum Keadilan,15/10/2000).
Terhadap putusan tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Atas
permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkannya, sehingga ia membatalkan
putusan PN Jakarta Selatan sebelumnya. Putusan MA menyatakan mereka terbukti melanggar
UU No.3 tahun 1971 jo UU NO.14 tahun 1970 jo UU no.35 tahun 1979 jo UU No.8 tahun 1981
dan UU no.14 tahun 1985, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara
serta menghukum terdakwa dengan 10 juta ditambah membayar ganti rugi 35,68 miliar. Kemudian
Tommy mengajukan grasi kepada Presiden tetapi permohonan grasi tersebut ditolak oleh
Presiden. Namun belakangan Tommy melarikan diri dari sel tahanannya. Semenatar orang
mensinyalir larinya Tommy tersebut ada hubungannya dengan pertemuannya dengan Presiden
di hotel Borobudur beberapa bulan sebelumnya.
Simpulan
Pembahasan tersebut di atas telah membuktikan bahwa penegakan supremasi hukum pada
era reformasi mengalami perubahan-perubahan. Akan tetapi, perubahan ke arah penegakan
supremasi hukum, khususnya dalam bidang peradilan tersebut tidaklah sama pada masa
pemerintahan Habibie dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Karena itu, terdapat beberapa
kesimpulan yang secara faktual bisa diperbandingkan dengan masa-masa sebelumnya.
Pertama, Masyarakat mengakui bahwa perubahan besar dalam kaintannya dengan penegakan
ciri dari negara hukum telah dilakukan oleh Habibie dalam masa pemerintahan transisi. Seperti
kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendaoat. Meskipun banyak pandangan yang ekstrim
terhadap pemerintahan transisi Habibie, pemberian self-determination terhadap Timor Timur juga
merupakan bukti dari penegakan hukum yang positif dan dapat diakui oleh masyarakat
.internasional. Kebijakan melepaskan Timtim dari Indonesia membawa efek internal yang positif,
yaitu lepasnya Timtim telah meringankan beban psikologis bagi status dan citra Indonesia di dalam
masyarakat internasional.Akan tetapi, kecenderungan positif era pemerintah transisi Habibie segera
sirna oleh karena periode pemerintahan Habibie selama satu tahun delapan bulan tersebut tidak
sama sekali menyentuh program pelaksanaan enam tuntutan reformasi. Lebih rumit dari itu, pola
hubungan antara Habibie dengan mantan Presiden Suharto tampak telah menimbulkan persoalan
penegakan hukum yang amat dilematis.
Kedua, Adanya kesan Pemerintahan transisi Habibie lamban dalam merespon penegakan
hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, terkait dengan faktor esensi hukum prosedural
mengenai ambivalensi wewenang antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan
terhadap kasus korupsi. Di luar konteks hukum, nilai-nilai sosial budaya, khususnya hubungan
baik antara Soeharto dengan kroninya, termasuk Habibie memang tidak mudah diputuskan.
Hubungan sosial yang tetap relevan diperhitungkan misalnya, hubungan antara Habibie, Jaksa
Agung Andi Ghalib dan tokoh-tokoh Irama Suka (Irian Jaya, Sulawesi dan Kalimantan)
memperlihatkan fakta-fakta yang mengindikasikan adanya lingkaran setan yang saling
melumpuhkan tegaknya Peraturan hukum. Nilai budaya mengenai hutang budi (indebtedness of
gratitude) memperlihatkan pola hubungan di atas dan tidak berlebihan bilamana macetnya Proses
hukum dalam penanganan korupsi diakibatkan oleh situasi tersebut.
Ketiga, Langkah progresif yang dilakukan Pemerintahan transisi Habibie adalah mengenai
upaya untuk memperhatikan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan penegakan
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
68
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
HAM melalui UU No. 39/1999. Secara substansial masih terdapat beberapa kelemahan
mendasar, seperti persoalan impunity (Penyelesaian di luar hukum) dengan cara memaafkan,
namun jauh lebih memprihatinkan adalah Peraturan tersebut tidak bisa diimplementasikan. Pertama,
adanya kontradiksi dalam hal azas hukum seperti persoalan kadaluwarsa (retroactive). Kedua,
ketidakjelasan rumusan hukum mengenai pelaku langsung dalam pelanggaran HAM (direct actor
dan indirect actor), yang terkait dengan konsep Ignorance, Omission, Commission. Oknum pejabat
militer tidak bisa diadili bilamana ia secara tidak langsung terlibat dalam kasus kejahatan
kemanusiaan meskipun ia benar-benar mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.
Ketiga, adalah keterlibatan militer dalam berbagai penanganan dan Penyelesaian konflik masih
tetap tidak bisa ditekan sehingga korban-korban kekerasan militer, khususnya di daerah konflik
seperti Aceh, Maluku, Poso dan Irian Jaya.
Keempat, Dalam kaitannya dengan upaya menegakkan hukum dan sistem peradilan kebijakan
Politik Gus Dur mengenai sistem peradilan secara prinsipal diakui cukup komprehensif. Pertama,
secara juridis UU No. 28/1997 telah secara tegas menempatkan kedudukan Polisi sebagai penegak
hukum dan pengayom masyarakat. Namun, di dalam realisasinya tetap bermasalah. Pelanggaran
HAM, penggunaan kekerasan dalam penanganan perkara dan juga kurang gesit dalam mencegah
timbulnya berbagai peristiwa pelanggaran hukum terus berlangsung. Perlakuan diskriminatif atas
kasus-kasus hukum, terutama terkait dengan kasus korupsi dan politik, begitu juga terlanggarnya
praduga tak bersalah fakta-fakta yang tidak bisa sembunyikan pada masa pemerintahan Gus Dur.
Perubahan ke arah penegakan hukum dan peradilan yang memberikan jaminan atas kepastian
hukum di era Gus Dur ini memang menjadi akar penyebab dari timbulnya situasi yang tidak menentu
secara sosial, politik dan ekonomi, termasuk keamanan. Semakin menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap Gus Dur, bukan saja dibuktikan melalui hilangnya dukungan di DPR ketika
penentukan keluarnya Memorandum I, II dan III, melainkan karena Gus Dur mengeluarkan kebijakan
yang tidak konsisten dengan sistem hukum nasional.
Saran
Sebagaimana disimpulkan di atas terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.
Perlu diadakan penelitian mengenai berbagai faktor terkait dengan kemungkinan penegakan
supremasi hukum, khususnya mengenai peranan dan fungsi kehakiman dalam satu atap. Tindak
lajutnya, adalah selain kemungkinan perlunya diadakan amandemen atas pasal 24 UUD 1945,
juga perlu diadakan identitifikasi persoalan yang menjadi faktor penghambat terlaksananya
supremasi hukum, baik di dalam sistem hukum itu sendiri maupun aspek-aspek terkait lainnya di
luar hukum.
Pustaka Acuan
Buku Literatur
Timothy OHogan, The End of Law
A.V. Dicey, Law and The Constitution
Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta
L.A. Harts, 1989, The Concept of Law
Satjipto Rahardjo, 1982. Ilmu Hukum, Alumni, Bandung
Makalah
Salman Luthan, Kontroversi Pengeluaran dan Pencabutan SP-3, Makalah disampaikan pada
disukusi rutin, Tamir Masjid Al-Azhar, FH UII, Tanggal 12 Juli 2000
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ... oleh: Jawahir Thontow
69
Jurnal
Jurnal Hukum No. 12 Vol. IV
Media Massa
Bisnis Indonesia, 1 Juli 1999; 10 Juli 1999; 24 Juli 1999; 10 Oktober 1999
Jawa Pos, September 2000; 7 Desember 2000; 3 Februari 2001; 15 Februari 2001; 23
Januari 2001.
Kompas, 16 Januari 1999; 24 Januari 1999; 18 Februari 1999; 30 Juni 2000; 1 Juli 1999; 16
Juli 1999; 19 Juli 1999; 22 Juli 1999; 31 Juli 1999; 11 Agustus 1999; 23 Agustus 1999; 23
September 1999; 26 September 1999; 12 Oktober 1999; 13 Oktober 1999; 14 Oktober 1999; 16
Oktober 1999; 19 Oktober 1999; 18 Februari 2000; 20 November 2000; 21 November 2000; 2
Desember 2000; 3 Desember 2000; 5 Desember 2000; 9 Desember 2000; 11 Desember 2000;
14 Desember 2000; 19 Desember 2000; 4 Januari 2001; 21 Januari 2001; 22 Januari 2001; 27
Januari 2001; 3 Februari 2001; 4 Februari 2001.
Kedaulatan Rakyat, 11 Mei 2000; 2 Juli 2000; 18 Desember 2000; 20 Januari 2001; 21Januari
2001; 23 Januari 2001; 24 Januari 2001; 30 Januari 2001
Media Indonesia, 1 Juli 1999; 11 Juli 1999; 16 September 1999; 25 September 1999; 18
Oktober 1999; 25 Oktober 1999; 25 November 1999
Republika, Juni 1999; 12 Juli 1999; 30 Agustus 1999; 18 Januari 2000; 18 Februari 2000;
23 Februari 2000; 29 Februari 2000.
Forum Keadilan, Edisi No. 6 Tanggal 29 Juni 1998; Edisi No. Tanggal 4 Februari 1999;
Edisi No. 9 Tanggal 6 Juni 1999; Edisi No. 13 Tanggal 4 Juli 1999; Edisi No. 14 Tanggal 11 Juli
1999; Edisi No. 17 Tanggal 1 Agustus 1999; Edisi No. 20 Tanggal 22 Agustus 1999; Edisi No. 30
Tanggal 29 Oktober 1999; Edisi No. 32 Tanggal 14 November 1999; Edisi No. 33 Tanggal 21
November 1999
; Edisi No. 33 Tanggal 31 November 1999; Edisi No. 37 Tanggal 14 Desember 1999; Edisi
No. 17 Tanggal 30 Juli 1999; Edisi No. 18 Tanggal 8 Agustus 1999; Edisi No. 21 Tanggal 29
Agustus 1999; Edisi No. 35 Tanggal 5 Desember 1999; Edisi No. 41 Tanggal 23 Januari 2000;
Edisi No. 49 Tanggal 19 Maret 2000; Edisi No. 51 Tanggal 2 April 2000; Edisi No. 5 Tanggal 7
Mei 2000; Edisi No. 6 Tanggal 14 Mei 2000; Edisi No. 8 Tanggal 28 Mei 2000; Edisi No. 28
Tanggal 15 Oktober 2000
; Edisi No. 8 Tanggal 25 Oktober 2000; Edisi No. 30 Tanggal 12 November 2000
Gatra, 23 September 2000; Gatra, 18 November 2000
Tempo, 30 April 2000; 1 Oktober 2000; 15 Oktober 2000; 31 Oktober 2000; 20 November
2000; 26 November 2000; 3 Desember 2000; 19 Desember 2000
Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi; UU No. 13 Tahun
1961 Tentang Kepolisian; UU No. 12 Tahun 1961 Tentang Kejaksaan; UU No. 14 Tahun 1970
Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman; UU No. 14 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
TAP MPR No. III/MPR/1978 Tentang Hak Uji Materiil; TAP MPRS No. II Tahun 1960; Keppres
No. 21 Tahun 1961
Fenomena: Vol. 2 No. 1 Maret 2004
ISSN : 1693-4296
You might also like
- Legal Systems and Methods Consolidated Notes-1 1Document103 pagesLegal Systems and Methods Consolidated Notes-1 1Super TallNo ratings yet
- Administrative LawDocument135 pagesAdministrative LawDivya Jain80% (15)
- JPSP - 2022 - 215Document11 pagesJPSP - 2022 - 215maccaferriasiaNo ratings yet
- The Rule of LawDocument16 pagesThe Rule of Lawaasgor100% (2)
- Hoàng-Ngọc-Khoa 21070330 THL105703Document5 pagesHoàng-Ngọc-Khoa 21070330 THL105703Đồng HoaNo ratings yet
- 02 The Rule of Law - An OverviewDocument44 pages02 The Rule of Law - An OverviewtakesomethingNo ratings yet
- Law and Society (Essay)Document6 pagesLaw and Society (Essay)azriejohari0% (1)
- Law Enforcement in Indonesia in The Perspective of Law StatesDocument4 pagesLaw Enforcement in Indonesia in The Perspective of Law StatesIrena LorenzaNo ratings yet
- Rule of Law and Its Applicability To Democracy in NigeriaDocument64 pagesRule of Law and Its Applicability To Democracy in NigeriaSubsectionNo ratings yet
- Key Concepts and Theories 12th NCERTDocument116 pagesKey Concepts and Theories 12th NCERTSundeep Chopra0% (1)
- Judical Activism: EaningDocument5 pagesJudical Activism: EaningNaveen MeenaNo ratings yet
- Aligarh Muslim University Malappuram Centre, Kerala: Administrative LawDocument11 pagesAligarh Muslim University Malappuram Centre, Kerala: Administrative LawKunwar Ankur JadonNo ratings yet
- The Judicial Review From The Prism of The Natural LawDocument3 pagesThe Judicial Review From The Prism of The Natural LawVaishnavi singh chauhanNo ratings yet
- Your Laws Your Rights (Viky)Document4 pagesYour Laws Your Rights (Viky)ANYE 20bap1518No ratings yet
- Rule of Law 1Document11 pagesRule of Law 1Heracles PegasusNo ratings yet
- Legal Systems and Methods Consolidated Notes 2023Document116 pagesLegal Systems and Methods Consolidated Notes 2023angelkatao311100% (1)
- Rule of Law Under Indian PerspectiveDocument16 pagesRule of Law Under Indian PerspectiveAadityaVasuNo ratings yet
- 1460-Article Text-2824-1-10-20210415Document17 pages1460-Article Text-2824-1-10-20210415Elgi HIkmat SyahNo ratings yet
- Public Interest Litigation and Judicial ActivismDocument27 pagesPublic Interest Litigation and Judicial Activismellam therunchukitu kovapatravanNo ratings yet
- Reformulasi Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraDocument13 pagesReformulasi Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraIlham Endriansyah PutraNo ratings yet
- Mohammad Choiri Fakih Udin (1710412210015)Document7 pagesMohammad Choiri Fakih Udin (1710412210015)Benny SyaputraNo ratings yet
- Rule of LawDocument10 pagesRule of LawAkash Narayan100% (1)
- Due Orocess of LawDocument18 pagesDue Orocess of LawvkNo ratings yet
- Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of Stateadministrative LawDocument14 pagesJurisprudence of State Administrative Courts in The Development of Stateadministrative LawDanielFuadNo ratings yet
- Jurnal 1Document16 pagesJurnal 1Dira NabilahNo ratings yet
- Rule of LawDocument11 pagesRule of Lawsiddharth100% (1)
- Introduction and Sources of LawDocument8 pagesIntroduction and Sources of Lawaixlo50% (2)
- Administrative LawDocument36 pagesAdministrative LawtarundaburNo ratings yet
- Effectiveness of Law Enforcement in IndonesiaDocument5 pagesEffectiveness of Law Enforcement in IndonesiaAnonymous lAfk9gNPNo ratings yet
- Adrian Bedner About AdatrechtDocument1 pageAdrian Bedner About Adatrechtoheokh7481No ratings yet
- Admin GroupDocument13 pagesAdmin GroupYusuph kiswagerNo ratings yet
- Introduction To Law Session One - HANDOUT 1.2Document11 pagesIntroduction To Law Session One - HANDOUT 1.2Getahun AbebawNo ratings yet
- Assignment 1Document26 pagesAssignment 1Arzoo khanNo ratings yet
- Judicial Review in Bangladesh FinalDocument6 pagesJudicial Review in Bangladesh Finalতাসনীম নিঝুমNo ratings yet
- Introduction To Law, Morrocan CaseDocument38 pagesIntroduction To Law, Morrocan CaseOussama RaourahiNo ratings yet
- Rule of Law Assignment Rework SamuelDocument23 pagesRule of Law Assignment Rework SamuelJuliet ChisomNo ratings yet
- Doctrine of Rule of LawDocument8 pagesDoctrine of Rule of LawAkshay BhasinNo ratings yet
- Administrative Law and Its ScopeDocument3 pagesAdministrative Law and Its ScopeKashif MehmoodNo ratings yet
- Judicial Activism ProjectDocument22 pagesJudicial Activism Projectanuja167No ratings yet
- The Implementation of JuducialDocument34 pagesThe Implementation of JuducialBintang ParashtheoNo ratings yet
- Tema 9. Obedience and Civil Disobedience: 1.-Justification of The State and AuthorityDocument9 pagesTema 9. Obedience and Civil Disobedience: 1.-Justification of The State and AuthorityJTNo ratings yet
- 13 - Conclusion & SuggestionsDocument20 pages13 - Conclusion & SuggestionsANJALI NAINNo ratings yet
- PREFACEDocument107 pagesPREFACEDeepak SinghalNo ratings yet
- MEANING AND NATURE OF LAW HttpsDocument8 pagesMEANING AND NATURE OF LAW HttpsashishNo ratings yet
- K C I W P: EY Oncepts Ndian AND Estern ErspectivesDocument8 pagesK C I W P: EY Oncepts Ndian AND Estern ErspectivesVenugopal ThiruvengadamNo ratings yet
- Administrative Law: Definition, Scope, FunctionsDocument57 pagesAdministrative Law: Definition, Scope, FunctionsSyed Raza AliNo ratings yet
- T P T L: Hans KelsenDocument20 pagesT P T L: Hans KelsenzulfanNo ratings yet
- Constitutional Law NotesDocument55 pagesConstitutional Law NotesArpit Jain67% (3)
- Judicial Activism and LegislationDocument6 pagesJudicial Activism and LegislationRuchi SharmaNo ratings yet
- Jai Narain Vyas University Jodhpur: Session 2021 - 22Document7 pagesJai Narain Vyas University Jodhpur: Session 2021 - 22bhanu pratap singh rathoreNo ratings yet
- Running Head: Balance of Law and Liberty 1Document6 pagesRunning Head: Balance of Law and Liberty 1CurieNo ratings yet
- Administrative LawDocument230 pagesAdministrative LawYun YiNo ratings yet
- Legislative and Judicial Process AnswerDocument16 pagesLegislative and Judicial Process AnswerManish Kumar PandeyNo ratings yet
- 11 - Chapter 5Document54 pages11 - Chapter 5mohd mursleenNo ratings yet
- 35-Article Text-71-1-10-20210323Document40 pages35-Article Text-71-1-10-20210323Eka JanuritaNo ratings yet
- Administrative Law NotesDocument18 pagesAdministrative Law Notesjaisamada0% (2)