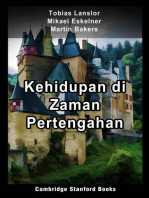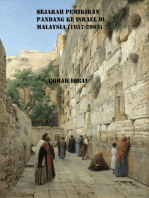Professional Documents
Culture Documents
Gerakan Islam Pra Kemerdekaan
Gerakan Islam Pra Kemerdekaan
Uploaded by
Mohammad Arif HamzahOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Gerakan Islam Pra Kemerdekaan
Gerakan Islam Pra Kemerdekaan
Uploaded by
Mohammad Arif HamzahCopyright:
Available Formats
GERAKAN ISLAM PRA-KEMERDEKAAN
Mohammad Arif Hamzah
Catur Hadi Baskhoro M.N
Afif Ghulam Irfani
Imam Bonjol dan Gerakan Paderi
Berbeda dengan dunia Maluku yang merupakan wilayah penghasil rempah-
rempah yang sumber kehidupannya berasal dari kegiatan perdagangan maritim,
Sumatra Barat merupakan wilayah pertanian yang menghasikan beberapa
komoditi yang bisa diekspor seperti emas dan kopi. Tidak seperti masyarakat
Maluku yang bercorak multietnis, mayoritas dari masyrakat Maluku adalah orang
Minangkabau. Mereka hidupa di dataran tinggi yang berlembah yang merupakan
bagian dari deretan pegunungan yang disebut dengan Bukit Barisan yang terletak
di Pulau Sumatra bagian tengah. Ada empat lembah di Bukit Barisan yang
menjadi pusat kehidupan orang Minangkabau. Keempat lembah tersebut terpisah
satu dengan lainnya oleh bukit-bukit berbatu dan masing-masing terletak di dekat
sebuah gunung berapi.1
Agama Islam mulai masuk ke Minangkabau pada abad 16. Kemampuan
kerajaan Minangkabau dalam menegakkan kekuasaanya ditunjang oleh
keberhasilannya dalam mengelola daerah-daerah penghasil emas. Daerah
penghasil utama emas di Minangkabau adalah desa-desa yang terletak di Tanah
Datar. Pada tahun 1780-an sumber-sumber emas semakin menyusut, dan ini
mengakibatkan terjadinya perubahan dalam masyarakat Minangkabau.
Menurunnya arti penting emas segera digantikan oleh sumber-sumber ekonomi
baru, yaitu kopi, garam, gambir dan tekstil. Wilayah-wilayah perdagangan
komoditi ini terutama terletak di pegunungan Agam dan Lima Puluh Kota. Daerah-
daerah ekonomi baru tersebut mengadakan hubungan dagang dengan Amerika
dan Inggris.
Kegiatan perdagangan yang berkembang di Agam menyebabkan daerah itu
menjadi pusat dari gerakan pembaharuan Islam. Pada sekitar awal abad 19,
tepatnya sekitar tahun 1803-4, gerakan pembaruan Islam yang semakin
berkembang tersebut mulai dikenal dengan sebutan gerakan Padri. Kata Padri
berasal dari sebutan “orang pidari” atau orang dari Pedir yaitu mereka yang pergi
ke Mekkah untuk naik haji melalui pelabuhan Pedir (Pidie) yang ada di Aceh.2
Suatu upaya untuk melakukan pembaharuan Islam di Minangkabau dipelopori
oleh para pedagang yang berasal dari Agam dan Lima Puluh Kota. Mereka melihat
bahwa hukum Islam yang dibawa oleh kaum pembarahu di jazirah Arab dapat
memberi perlindungan terhadap kegiatan perdagangan yang mereka lakukan.
Pada awal tahun 1803 kota Mekkah berhasil ditaklukkan oleh kaum
pembaharu Islam yang dikenal dengan sebutan kaum Wahabbi. Mereka
merupakan penganjur pembersihan Islan dari ketidakmurnian. Dalam sejarah
Islam, di masa-masa krisis sering terjadi gerakan besar kebangiktan kembali
kesadaran beragama. Gerakan ini biasanya ditandai dengan aspek politik dan
militer yang kuat serta didasarkan pada pembedaaan yang tegas. Berdasarkan
inspirasi yang diberikan oleh kaum Wahabi, para Haji yang baru pulang dari
Mekkah menyebarkan gagasan untuk melakukan pembaharuan Islam di kalangan
1 Christine Dobbin, Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847,
Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, hal. 4.
2 Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal. 311
Gerakan Politik Islam Indonesia | 1
masyarakat Minangkabau.3 Dengan menyebut dirinya sebagai kaum padri mereka
menentang perjudian, sabung ayam, penggunaan candu, minuman keras, dan
ketaatan yang lemah terhadap kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam.
Para guru agama di Minangkabau diberi gelar kehormatan “tuanku”. Gelar
kehormatan ini pula yang digunakan oleh para pimpinan kaum Padri. Salah satu
pimpinan gerakan Padri yang terkemuka adalah Tuanku Imam Bonjol (1772-
1864). Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kaum Padri di Minangkabau
mendatangkan reaksi yang keras dari kelompok masyarakat lainnya yang dipimpin
oleh para pemuka yang disebut dengan penghulu (para kepala suku dan pemimpin
adat). Para penentang gerakan Padri adalah masyarakat Minangkabau yang
mendiami wilayah Tanah Datar dan dataran-dataran rendah lainnya yang tidak
banyak terlibat dalam kegiatan perdagangan. Pertentangan yang terjadi berujung
pada konflik terbuka. Pada tahun 1815 sebagian besar keluarga kerajaan
Minangkabau yang terletak di Tanah Datar terbunuh oleh kaum Padri.
Setelah berhasil mengalahkan kekuatan penentang utamanya, gerakan
Padri mulai meluaskan pengaruhnya ke Tapanuli Selatan. Di wilayah tersebut
kaum Padri melakukan apa yang mereka sebut sebagai pemurnian agama. Di sisi
lain, ada yang beranggapan bahwa apa apa yang dilakukan oleh kaum Padri
terhadap orang Mandailing yang mendiami wilayah Tapanuli Selatan adalah
adalah agresi yang diiringi dengan penjarahan dan berbagai tindak kejahatan
lainnya.4 Kemenangan kaum Padri segera mendapat tantangan yang serius dengan
kembali berkuasanya orang-orang Belanda di Padang pada tahun 1819. Para
penghulu yang anti kaum Padri dan para anggota keluarga kerajaan yang masih
hidup segera meminta bantuan kekuatan kolonial lama tersebut.
Selama berlangsungnya Perang Jawa, Belanda tidak dapat mengerahkan
kekuatan penuh dalam menghadapi kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Imam
Bonjol. Setleah tahun 1830 perang antara Belanda melawan kaum Padri semakin
berkobar. Pintu-pintu yang menyuplai logistik bagi kaum Padri berhasil diblokade.
Blokade dilakukan Belanda dengan menutup pesisir barat dan pesisir timur
Sumatra bagian tengah yang merupakan pintu gerbang perdagangan
Minangkabau. Pada tahun 1837, basis kekuatan utama kaum Padri di Bonjol
berhasil direbut Belanda. Ketika pusat kekuatan utama kaum Padri tersebut
direbut, Tuanku Imam Bonjol berhasil melarikan diri. Tetapi pelariannya tidak
berlangsung lama, karena ia kemudian menyerah. Tuanku Imam Bonjol dihukum
dengan cara diasingkan. Pertama ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir
ke Menado, tempat di mana ia wafat pada tahun 1864.
Gerakan Purifikasi
Gerakan Paderi (1821-1838) maupungerakan “kaum putih” (gerakan Islam
mazhab Hambali atau gerakan Wahabi) diMinangkabau yang berkembang
sebelumnya (1803-1807) di bawah kepemimpinan Tuantu Nan Rentjeh, dan
kemudian tokoh-tokoh lainnya seperti Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumanik,
Tuanku Imam Bonjol (Petro Syarif), Tuantu Rao, dan lain-lain dalam konteks
gerakan keagamaan
3 Dobbin, Gejolak Ekonomi, hal. 203-204.
4 Kontroversi dari gerakan Padri yang meluaskan pengaruhnya ke wilayah Tapanuli Selatan dibahas
dalam M.O. Parlindungan, Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab
Hambali di Tanah Batak, 1816-1833, Yogyakarta: LkiS, 2006. Lihat juga Basyral Hamidi Harahap, Greget Tuanku
Rao, Jakarta: Komunitas Bambu, 2007.
Gerakan Politik Islam Indonesia | 2
maupun gerakan rakyat memang memiliki watak yang puritan. Puritanisme dalam
Islam maupun agama pada umumnya selalu dikaitkan dengan paham dan praktik
keagamaan yang ingin kembali pada agama yang dipandang atau diyakini murni
sesuai sumbernya yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi tanpa tercampur-baur
dengan apapun seperti syrik, bid’ah, dan khurafat.
Kelompok puritan sering dideskripsikan atau dikaitkan dengan istilah
fundamentalis, militan, ekstrimis, radikal, fanatik, jihadis, dan bahkan Islamis.
Pandangan puritan dalam Islam ditandai oleh ciri yang menonjol kelompok ini
yang dalam keyakinannya menganut paham absolutisme dan tak kenal kompromi
dalam beragama. Dalam banyak hal kelompok puritan cenderung menjadi puris,
yakni seseorang atau sekelompok orang yang tidak toleran terhadap berbagai
sudut pandang yang berkompetisi dan memandang realitas pluralis sebagai satu
bentuk kontaminasi atas kebenaran sejati.5
Puritanisme agama baik di Sumatra Barat maupun di sejumlah wilayah di
Indonesia pada umumnya berhadapan dengan tradisi atau adat istiadat
khususnya yang dilakukan oleh kalangan Islam tradisional atau lokal yang
dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Kecenderungan puritan sebenarnya
tidaklah tunggal tetapi terentang dari yang keras atau radikal hingga lunak atau
moderat. Sebagai contoh, lahirnya gerakan modernisme/reformisme Islam awal
abad ke-20 yang sering disebut pula sebagai gerakam “pemurnian Islam” atau
Revivalisme Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan
Islam, menurut Deliar Noer kendati keduanya sama-sama mengajak “Kembali
kepada Al-Quran dan As-Sunnah” dalam bentuk gerakan pembaruan Islam atau
Islam modern, tetapi Muhammadiyah tampak lebih moderat atau lunak sedangkan
Persatuan Islam lebih keras.6 Dalam kelompok yang sama seperti dalam
Muhammadiyah misalnya, bahkan antara satu wilayah atau daerah juga memiliki
kecenderungan puritanisme yang tidak persis sama, meskipun seluruhnya
berpedoman pada Keputusan Tarjih dalam menjalankan pokok-pokok ajaran
Islam. Disinilah rentang sikap puritanisme Islam pun memang tidaklah tunggal
tetapi plural atau beragam.
Gerakan purifikasi yang melekat dengan perjuangan Padri dan Islamisasi di
Minangkabau memiliki keterkaitan dengan paham Wahabi (Wahhabi,
Wahhabiyyah) yang memang cukup kuat di wilayah ini. Hamka mencatat bahwa
Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik adalah “pelopor paham Wahabi
menjadi gerakan Padri atau Paderi di Minangkabau, yang pulang dari Makkah
sekitar tahun 1803 atau setahun sebelumnya” (Hamka, 2008). Gerakan Wahabi
yang mengikuti paham Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792) pelopor
pembaruan (pemurnian) Islam di Arab Saudi adalah “gerakan dakwah dengan
menyeru umat mengakui dan melaksanakan ajaran keesaan Allah (tauhid), dalam
zat, sifat dan perbuatan-Nya”.
Gerakan Wahabi yang dikaitkan dengan praktik keagamaan Muhammad bin
Abd Al-Wahhab memiliki watak dan orientasi keagaman yang puritan-konservatif
dan cenderung keras dalam memberantas apa yang disebut dengan praktik
keagamaan yaitu syirk, tahayul, bid’ah, dan khurafat. Gerakan ini secara umum
sering puladikaitkan dengan Salafiyah (Salafiyyah), yakni paham orang-orang yang
mengidentifikasikan pemikiran mereka dengan pemikiran para Salaf. Gerakan ini
ingin mengembalikan agama Islam kepada sumbernya yang murni yaitu Kitab Suci
5El Fadl, Khaled Abou. 2005. SelamatkanIslam dari Muslim Puritan, Jakarta: Serambi, hal. 29
6Noer, Deliar , 1996. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1990-1942 , Jakarta, LP3ES, hal. 32
Gerakan Politik Islam Indonesia | 3
Qur’an dan Sunnah Nabi, dengan meninggalkan pertengkaran mazhab dan segala
bid’ah yang disisipkan orang ke dalamnya.7
Salafiyah sebagai aliran paham (mazhab) atau gerakan, muncul pada abad
ke-7 Hijriyah, yang dikembangkan oleh para ulama atau pengikut mazhab Hanbali
(Ahmad Ibn Hanbal), yang menghidupkan aqidah ulama Salaf dan berusaha
memerangi paham lainnya. Aliran ini dihidupkan dan dikembangkan dengan
pemikiran pembaruan oleh Syaikh al-Islam, Ibn Taimiyyah. Pada abad ke-12
pemikiran Salafiyah itu muncul dan dihidupkan kembali di jazirah Arab oleh
Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan pengikutnya kaum Wahabbi, yang
menyebarluaskan paham ini dengan berkerjasama dalam kekuasaan Ibn Saud di
jazirah Arab yang menampilkan gerakan yang sangat keras dan membangkitkan
amarah sebagian ulama.
Salafiyah memiliki karakter pemikiran antara lain, pertama, bahwa
argumentasi pemikiran Islam harus jelas diambil dari AlQuran dan Al-Hadits.
Kedua, penggunaan rasio atau akal pikiran harus sesuai dengan nash-nash yang
shahih. Ketiga, seperti dikemukakan Ibnu Taymiyyah bahwa dalam konteks
aqidah harus berdasarkan pada nash-nash saja. Nash atau teks ajaran Islam itu
bersumber dari Allah, sedangkan rasio hanya berfungsi sebagai pembenar, yakni
sebagai saksi (syahid) dan bukan sebagai penentu (hakimi), sehingga akal harus di
bawah nash ajaran serta tidak boleh berdiri sendiri sebagai dalil, yakni akal
sekadar untuk mendekatkan dengan kehendak nash ajaran. Pemikiran Salafiyah
selain mengajak kembali pada Islam generasi awal yang dipandang murni, juga
berusaha membangkitkan kembali dunia Islam dengan mengadakan pembaruan
keagamaan dan reformasi moral sebagaimana dipelopori oleh Jamaluddin
AlAfghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha, yang dikenal pula
sebagai gerakan pembaruan. Gerakan Salafiyah juga memiliki orientasi keagamaan
lainnya, yaitu mengecam praktik tarekat atau tasawuf karena dianggap
melanggengkan keterbalakangan dan mengajarkan fatalisme atau kepasrahan
hidup, serta praktik-praktik keagamaan yang mengajarkan pemujaan berlebihan
terhadap wali, kuburan, dan orang-orang yang diangap suci.
Dengan demikian, gerakan Wahabi di mana pun memang memiliki karakter
yang puritan dan cenderung keras. DiMinangkabau gerakan Padri dengan
orientasi paham Wahabi-nya boleh jadi memiliki akar kesejarahan dengan gerakan
kembali pada syariat Islam pada kurun 1784-1790 sebagaimana dipelopori oleh
Tuanku Nan Tuo dari Ampek Angkek dengan orientasi pada ortodoksi fikih
dalam rangkaian corak Islamisasi abad ke-18 di wilayah ini (Marajo, 1998).
Namun perlu dicatat, sebenarnya dalam temuan William Marsden, ketika
mengupas tentang Kerajaan Minangkabau khususnya tentang agama di Ranah
Minang, peneliti dan dokter Inggris yang tinggal selama delapan tahun di Bengkulu
(sekitar tahun 1700-1708) inimenyatakan, “sejauh observasi saya, orangorang
Melayu tidak nampak ekstrim terhadap agamanya seperti orang Islam di Barat.
7Abu Zahrah, Imam Muhammad. 1996. Aliran Politik Dan ‘Aqidah Dalam Islam, terjemahan Abd.
Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, Jakarta, Logos
Gerakan Politik Islam Indonesia | 4
Diponegoro dan Perubahan Tatanan di Jawa
Sebagai tokoh sejarah kehidupan Diponegoro terikat dalam ruang dan
waktu. Sebagai seorang pangeran yang berasal dari kesultanan Yogyakarta,
budaya Jawa dengan kental mewarnai pandangan hidup Diponegoro. Salah satu
tujan utama dari perlawanannya adalah mengembalikan tatanan budaya Jawa
seperti sebelum kekuatan kolonial masuk terlalu dalam ke kehidupan masyarakat
Jawa. Dalam pandangan Diponegoro, Jawa adalah wilayah inti Mataram, yaitu
daerah yang ada di Jawa Tengah bagian selatan. Selama kekuatan kolonial dan
kekuatan asing lainnya tidak masuk ke wilayah tersebut, menurut Diponegoro
orang Jawa akan dapat tetap mempertahankan kedaulatannya.
Meskipun sepanjang abad ke-18, kekuatan VOC secara bertahap meluas
dari Batavia ke Priangan, Banten dan Pantai Utara Jawa, namun selama kekuatan
tersebut tidak masuk ke wilayah inti Mataram bagi Diponegoro kehadirannya
masih dapat diterima. Masuknya VOC terlalu dalam ke kehidupan keraton di awal
abad 19, khususnya kesultanan Yogyakarta, telah menyebabkan Diponegoro dan
para elit keraton lainnya merasa bahwa kekuatan asing tersebut telah merusak
tatanan budaya Jawa.
Diponegoro merupakan anak jamannya. Ia hidup dalam masa peralihan
(1785-1855), yaitu ketika kekuasaan VOC di Jawa telah surut, sementara negara
kolonial Hindia Belanda yang melanjutkan kekuasaan VOC mulai tumbuh menjadi
mantap dengan diselingi oleh periode pendek pemerintahan Belanda-Prancis di
bawah Gubernur Jendral H.W. Daendels (1808-1811) dan pemerintah Inggris di
bawah Letnan Gubernur T.S. Raffles (1811-1816). Meskipun dua selingan
pendek pemerintahan Daendels dan Raffles mencakup periode yang tidak sampai
sepuluh tahun, tetapi dampaknya sangat fundamental dalam merubah tatanan
kehidupan masyarakat Jawa.
Sebagai pembawa gagasan revolusi Revolusi Perancis, Daendels melakukan
reorganisasi pemerintahan dengan memasukkan elit Jawa ke dalam sistem
administrasi kolonial dan karena itu ia telah meletakkan landasan bagi suatu
administrasi pemerintahan yang modern. Selain melakukan reorganisasi
pemerintahan Daendels juga dikenang sebagai orang yang membangun sarana
infratsruktur yang paling monumental di Jawa, yaitu jalan Anyer-Panarukan atau
Grote Postweg (Jalan Raya Pos). Sementara Raffles dalam masa kekuasaannya
menerapkan sistem pajak tanah (land rent system) untuk menggantikan sistem
pungutan wajib (verplichte leveransier) yang diterapkan pada masa VOC.
Penerapan land rend system meniru sistem pajak tanah yang diterapkan Inggris di
India, namun terbukti cukup sulit untuk diterapkan di Jawa. Penerapan sistem
pajak tanah menyebabkan meningkatnya monetisasi (penggunaan uang) di daerah
pedesaan di Jawa.8
Perubahan-perubahan besar yang menyebabkan terguncangnya tatanan
Jawa yang dikenal dengan akrab oleh Diponegoro tentu telah mendatangkan
kekecewaanyang besar terhadap dirinya. Salah satu tuntutan utama Diponegoro
yang melatar belakangi perlawananya terhadap kekuatan kolonial adalah
kembalinya tatanan Jawa seperti sebelum terjadinya reformasi Daendels pada
tahun 1808.9 Perlawanan Diponegoro terhadap kekuatanan kolonial menjadi
berbeda dengan perlawanan yang dilakukan oleh para bangsawan keraton
8 Mengenai land rent system lihat Peter Boomgaard, Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa
1795-1880, Jakarta: Djambatan dan KITLV, 2004, hal. 57-61
9 Peter Carey, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855), Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014,
hal. 90.
Gerakan Politik Islam Indonesia | 5
sebelumnya karena Diponegoro banyak memasukkan aspek Islam di dalam
perjuangannya. Kesalehan Diponegoro dan cita-citanya untuk menegakkan ajaran
agama Islam dalam masyarakat Jawa menyebabkannya mendapat dukungan yang
luas. Dukungan bagi Diponegoro bukan hanya datang dari para pendukungnya di
lingkungan keraton dan para petani, tetapi juga dari kaum santri yang berasal dari
berbagai pesantren yang ada di pedalaman Jawa.
Dalam pandangan masayarakat Jawa abad 19 Diponegoro adalah seoarang
Ratu Adil. Sebagai seorang yang dianggap sebagai Ratu Adil, Diponegoro berhasil
menyatukan berbagai elemen sosial yang berbeda di bawah cita-cita Islam Jawa.
Hilangnya sosok pemimpin yang bisa melindungi rakyat, menyebabkan
masyarakat Jawa berpaling kepada Diponegoro dan melihatnya sebagai seorang
tokoh yang bisa memandu mereka melewati masa transisi yang sulit untuk
menuju ke masa kejayaan. Pesona Diponegoro di kalangan pendukungnya terletak
pada kemampuannya untuk memberi harapan di tengah penderitaan yang
disebabkan oleh penetrasi kekuatan kolonial yang semakin dalam, terutama sejak
masa pemerintahan Daendels.
Di luar kelaziman kehidupan seorang pangeran di jamannya, sebagai putra
seorang sultan, Diponegoro justru dibesarkan di luar tembok keraton. Di bawah
asuhan neneknya yang memegang kuat ajaran agama, Diponegoro tumbuh
menjadi seorang pangeran yang relijius. Diponegoro menjadi dewasa dengan
dikelilingi oleh para ulama dan kiai sehingga ekspresi keislamannya tidak hanya
sebatas pada pelaksanaan kewajiban-kewajiban dasar Islam, tetapi lebih jauh dari
itu, ia juga mengembangkan suatu gagasan keagamaan yang cukup mendalam.
Cita-citanya untuk menjadi penata agama Islam di tanah Jawa menunjukkan
bahwa agama bagi Diponegoro tidak hanya menjadi identitas tetapi merupakan
bagian utama dari cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Jawa yang taat
kepada agama Islam. Perlawanan yang dilakukan oleh Diponegoro merupakan
sebentuk perlawanan yang melampui jamannya. Hal ini karena karena perlawanan
tersebut tidak sekedar berakar pada malsah internal di kalangan elit tradisional.
Perang Jawa menjadi suatu titik penting dalam sejarah Indonesia karena dalam
perang ini dukungan masyarakat yang luas diberikan karena Diponegoro
mempunyai empati yang mendalam terhadap penderitaan sosial ekonomi yang
dialami oleh rakyat kebanyakan. Menurut sejarawan Peter Carey, perang Jawa
menjadi sangat bermakna karena saling pengaruh yang mendalam antara derita
ekonomi dan harapan akan datangnya jaman keemasan menciptakan suatu
gerakan berwawasan sosial yang unik yang mendahului gerakan kebangsaan
Indonesia pada awal abad ke-20.10
10 Ibid., hal. 26.
Gerakan Politik Islam Indonesia | 6
SEJARAH PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
Masa baru Islam dimulai pada abad ke delapan belas yang ditandai dengan
munculnya gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab.
Tujuan gerakan ini adalah memurnikan agama Islam dari segala bentuk bid’ah.
Gerakan Wahabi ini merupakan gerakan reformisme yang bercorak lama. Gerakan
yang Wahabi ini berpengaruh kenegara yang mayoritas Islam seperti Mesir, Turki,
Iran, India dan Pakistan. Setelah Abdul Wahhab juga terdapat tokoh pembaharu
Islam seperti Jamaluddin al-Afgani, dan Muhammad Abduh. Gerakan pembaharu
yang mereka bawa juga berpengaruh di Indonesia. Dalam gerakan reformisme
sendiri memiliki beberapa kecenderungan yaitu:
1. Kecenderungan untuk mempertahankan sistem-sistem permulaan Islam
sebagai sistem yang dianggap paling benar, setelah dibersihkan dari bid’ah.
2. Berusaha membangkitkan Islam berlandaskan ajaran yang benar yang
dapat disesuaikan dengan perkembangan masa kini dalam segi agama,
kesusilaan dan kemasyarakatan.
3. Berpegang teguh pada dasar agama dan tidak menutup pada pandangan-
pandangan baru yang datangnya dari Barat.
Kencenderungan yang terakhir ini disebut dengan modernisme dalam Islam.11
Istilah modernisme ini kemudian di terjemahkan kedalam berbagai bahasa. Dalam
bahasa Arab modernisme disebut juga dengan istilah Tajdid. Sedangkan, kata
modernisme dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pembaharuan. Tujuan
pembaharuan Islam adalah membawa umat Islam kepada kemajuan.
Menurut Ahmad Jainuri, misi pembaharuan agama sesungguhnya di dasarkan
pada konsep kemerosotan keagamaan yang tak terhindarkan setelah wafatnya
Rosulullah SAW.12Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia mulai muncul pada
abad ke sembilan belas. Di antara gerakan pembaharuan Islam yang berpengaruh
di Indonesia adalah gerakan al-Irsyad.
Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Jam’iyat al-Islah wal Irsyad al-
Islamiyyah) berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Tanggal itu
mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang pertama, di
Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah Kolonial
Belanda pada 11 Agustus 1915.
Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-‘Alamah Syeikh Ahmad Surkati
Al-Anshori, seorang ulama besar Mekkah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya
Syekh Surkati datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jami’at Khair -
yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan
Arab golongan sayyid, dan berdiri pada 1905. Nama lengkapnya adalah Syeikh
Ahmad Bin Muhammad Assoorkaty Al-Anshary.
Kedatangan Ahmad Soorkatty ke Indonesia merupakan titik awal dari
sejarah latar belakang berdirinya gerakan al-Irsyad. Ahmad Soorkatty datang ke
Indonesia pada tahun 1911. Kedatangan Ahmad Soorkatty ke Indonesia
berdasarkan permohonan Jamiat Khair untuk mengajar. Al-Jamiat al-Khairiyyah
11Pijper, Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia,103-105.
12Ahmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis:Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah
Periode Awal (Surabaya: LPAM, 2002), 82
Gerakan Politik Islam Indonesia | 7
lebih dikenal dengan sebutan Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 1905. Mayoritas anggota dari Jamiat Khair adalah orang Arab
dan dari kalangan yang berada, sehingga waktu mereka banyak tercurah pada
seluruh kegiatan Jamiat Khair tanpa mengganggu mata pencaharian mereka.
Jamiat Khair mempunyai dua kegiatan yang diprioritaskan yaitu yang pertama,
pendirian dan pembinaan sekolah dasar dan yang kedua adalah pengiriman ke
Turki bagi anak-anak muda yang ingin melanjutkan belajarnya. Sekolah dasar
tersebut didirikan pada tahun 1905. Dalam sekolah ini tidak hanya diajarkan ilmu
agama saja tetapi juga ilmu pengetahuan yang lain. Seperti sejarah, ilmu
berhitung, bahasa Inggris, dan Geografi. Sekolah ini sudah terorganisir dengan
baik, hal tersebut dapat dilihat dari kurikulum yang tersusun dengan baik dan
penataan kelas yang baik pula.
Al-Irsyad adalah organisasi Islam nasional. Syarat keanggotaannya, seperti
tercantum dalam Anggaran Dasar Al-Irsyad adalah: “Warga negara Republik
Indonesia yang beragama Islam yang sudah dewasa.” Jadi tidak benar anggapan
bahwa Al-Irsyad merupakan organisasi warga keturunan Arab.Perhimpunan Al-
Irsyad mempunyai sifat khusus, yaitu Perhimpunan yang berakidah Islamiyyah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan,
pengajaran, serta social dan dakwah bertingkat nasional. (AD, ps. 1 ayat 2).
Perhimpunan ini adalah perhimpunan mandiri yang sama sekali tidak
mempunyai kaitan dengan organisasi politik apapun juga, serta tidak mengurusi
masalah-masalah politik praktis (AD, ps. 1 ayat 3).Syekh Ahmad Surkati tiba di
Indonesia bersama dua kawannya: Syeikh Muhammad Tayyib al-Maghribi dan
Syeikh Muhammad bin Abdulhamid al-Sudani. Di negeri barunya ini, Syeikh
Ahmad menyebarkan ide-ide baru dalam lingkungan masyarakat Islam Indonesia.
Syeikh Ahmad Surkati diangkat sebagai Penilik sekolah-sekolah yang dibuka
Jami’at Khair di Jakarta dan Bogor.
Berkat kepemimpinan dan bimbingan Syekh Ahmad Surkati, dalam waktu
satu tahun, sekolah-sekolah itu maju pesat. Namun Syekh Ahmad Surkati hanya
bertahan tiga tahun di Jami’at Khair karena perbedaan paham yang cukup
prinsipil dengan para penguasa Jami’at Khair, yang umumnya keturunan Arab
sayyid (alawiyin).Sekalipun Jami’at Khair tergolong organisasi yang memiliki cara
dan fasilitas moderen, namun pandangan keagamaannya, khususnya yang
menyangkut persamaan derajat, belum terserap baik. Ini nampak setelah para
pemuka Jami’at Khair dengan kerasnya menentang fatwa Syekh Ahmad tentang
kafaah (persamaan derajat).Karena tak disukai lagi, Syekh Ahmad memutuskan
mundur dari Jami’at Khair, pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Dan di
hari itu juga Syekh Ahmad bersama beberapa sahabatnya mendirikan Madrasah
Al-Irsyad Al-Islamiyyah, serta organisasi untuk menaunginya: Jam’iyat al-Islah
wal-Irsyad al-Arabiyah (kemudian berganti nama menjadi Jam’iyat al-Islah wal-
Irsyad al-Islamiyyah).13
Setelah tiga tahun berdiri, Perhimpunan Al-Irsyad mulai membuka sekolah
dan cabang-cabang organisasi di banyak kota di Pulau Jawa. Setiap cabang
ditandai dengan berdirinya sekolah (madrasah). Cabang pertama di Tegal (Jawa
Tengah) pada 1917, dimana madrasahnya dipimpin oleh murid Syekh Ahmad
Surkati angkatan pertama, yaitu Abdullah bin Salim al-Attas. Kemudian diikuti
13Tarikh Yayasan Pendidikan al-Irsyad al-Islamiyah Surabaya
Gerakan Politik Islam Indonesia | 8
dengan cabang-cabang Pekalongan, Cirebon, Bumiayu, Surabaya, dan kota-kota
lainnya.
Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok
pembaharu Islam di Nusantara, bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam
(Persis). Tiga tokoh utama organisasi ini: Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan
Ahmad Hassan (A. Hassan), sering disebut sebagai “Trio Pembaharu Islam
Indonesia.” Mereka bertiga juga berkawan akrab. Malah menurut A. Hassan,
sebetulnya dirinya dan Ahmad Dahlan adalah murid Syekh Ahmad Surkati, meski
tak terikat jadwal pelajaran resmi.Namun demikian, menurut sejarawan Belanda
G.F. Pijper, yang benar-benar merupakan gerakan pembaharuan dalam pemikiran
dan ada persamaannya dengan gerakan reformisme di Mesir adalah Gerakan
Pembaharuan Al-Irsyad. Sedang Muhammadiyah, kata Pijper, sebetulnya timbul
sebagai reaksi terhadap politik pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang
berusaha untuk menasranikan orang Indonesia.
Muhammadiyah lebih banyak peranannya pada pembangunan lembaga-
lembaga pendidikan. Sedang Al-Irsyad, begitu lahir seketika terlibat dengan
berbagai masalah diniyah. Ofensif Al-Irsyad kemudian telah menempatkannya
sebagai pendobrak, hingga pembinaan organisasi agak tersendat. Al-Irsyad juga
terlibat dalam permasalahan di kalangan keturunan Arab, hingga sampai dewasa
ini ada salah paham bahwa Al-Irsyad merupakan organisasi para keturunan Arab.
Al-Irsyad juga berperan penting sebagai pemrakarsa Muktamar Islam I di
Cirebon pada 1922, bersama Syarekat Islam dan Muhammadiyah. Sejak itu pula,
Syekh Ahmad Surkati bersahabat dekat dengan H. Agus Salim dan H.O.S.
Tjokroaminoto. Al-Irsyad juga aktif dalam pembentuan MIAI (Majlis Islam ‘A’laa
Indonesia) di zaman pendudukan Jepang, Badan Kongres Muslimin Indonesia
(BKMI) dan lain-lain, sampai juga pada Masyumi, Badan Kontak Organisasi Islam
(BKOI) dan Amal Muslimin.14Di tengah-tengah suasana Muktamar Islam di
Cirebon, diadakan perdebatan antara Al-Irsyad dan Syarekat Islam Merah, dengan
tema: “Dengan apa Indonesia ini bisa merdeka. Dengan Islamisme kah atau
Komunisme?” Al-Irsyad diwakili oleh Syekh Ahmad Surkati, Umar Sulaiman Naji
dan Abdullah Badjerei, sedang SI Merah diwakili Semaun, Hasan, dan Sanusi.
Selaku penganut paham Pan Islam, tentu Syekh Ahmad Surkati bertahan
dengan Islamisme. Semaun berpendirian, hanya dengan komunisme lah Indonesia
bisa merdeka. Dua jam perdebatan berlangsung, tidak ditemukan titik temu.
Namun Syekh Ahmad Surkati ternyata menghargai positif pendirian Semaun.
“Saya suka sekali orang ini, karena keyakinannya yang kokoh dan jujur bahwa
hanya dengan komunisme lah tanah airnya dapat dimerdekakan!”Peristiwa ini
sekaligus membuktikan bahwa para pemimpin Al-Irsyad pada tahun 1922 sudah
berbicara masalah kemerdekaan Indonesia!. Seperti yang diajarkan Muhammad
Abduh di Mesir, Al-Irsyad mementingkan pelajaran Bahasa Arab sebagai alat
utama untuk memahami Islam dri sumber-sumber pokoknya. Dalam sekolah-
sekolah Al-Irsyad dikembangkan jalan pikiran anak-anak didik dengan
menekankan pengertian dan daya kritik. Tekanan pendidikan diletakkan pada
tauhid, fikih, dan sejarah.
Sejak didirikannya, Al-Irsyad Al-Islamiyyah bertujuan memurnikan tauhid,
ibadah dan amaliyah Islam. Bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk
14Hussein, Al- Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa, 32.
Gerakan Politik Islam Indonesia | 9
merealisir tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan
lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Dan dalam
perkembangannya kemudian, kegiatan Al-Irsyad juga merambah bidang
kesehatan, dengan mendirikan beberapa rumah sakit. Yang terbesar saat ini
adalah RSU Al-Irsyad di Surabaya dan RS Siti Khadijah di Pekalongan.
Tercatat banyak lulusan Al-Irsyad, baik dari kalangan keturunan Arab
maupun non-Arab yang telah memainkan peran penting di berbagai bidang.
Lulusan pribumi yang turut berperan penting dalam modernisme Islam di
Indonesia antara lain:Yunus Anis: Alumnus Al-Irsyad yang dikenal sebagai seorang
pemimpin yang menonjol dari Gerakan Muhammadiyah. Ia mendapat kehormatan
dijuluki “tulang punggung Muhammadiyah” karena pengabdiannya sebagai
sekretaris jenderal di organisasi tersebut selama 25 tahun.Prof. Dr. T.M. Hasby As-
Shiddique: Putera asli Aceh, penulis terkenal dalam masalah hadist, tafsir, dan
fikih Islam moderen. Guru besar di IAIN Yogyakarta ini bahkan pernah menjabat
Rektor Universitas Al-Irsyad di Solo (sekarang sudah tutup). Prof. Kahar Muzakkir:
Berasal dari Yogyakarta. Lulus dari Madrasah Al-Irsyad, Kahar Muzakkir
melanjutkan studinya di Dar al-Ulum di Kairo. Ia sangat aktif berjuang untuk
kemerdekaan Indonesia dan termasuk penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni
1945. Kemudian ia menjadi Rektor Universitas Islam Indonesia di
Yogyakarta.Muhammad Rasjidi: Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama,
berasal dari Yogyakarta. Ia pernah menjadi professor di McGill University di
Montreal, Kanada, dan juga mengajar di Universitas Indonesia, Jakarta. Semasa
hidupnya menulis banyak buku.Prof. Farid Ma’ruf: Asli Yogyakarta, profesor di
IAIN, yang juga salah satu tokoh besar Muhammadiyah di awal-awal berdirinya.
Lulusan Madrasah Al-Irsyad ini sempat menjabat Direktur Jenderal Urusan Haji di
Departemen Agama.
Al-Ustadz Umar Hubeis: Jabatan pertamanya adalah sebagai Direktur
Madrasah Al-Irsyad Surabaya. Di waktu yang bersamaan ia aktif di Masyumi
(Majelis Syura Muslimin Indonesia). Umar Hubeis bahkan pernah menjadi anggota
DPR mewakili Masyumi. Ia juga menjadi professor di Universitas Airlangga,
Surabaya. Semasa ia hidupnya beliau juga menulis beberapa buku, terutama fikih.
Yang terkenal adalah Kitab FATAWA.Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani:
Lulusan Al-Irsyad Pekalongan ini sangat menguasai fikih dan menjadi professor di
Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta. Ia juga menulis buku-buku fikih. Di kalangan
cendekiawan dan intelektual Islam Indonesia, ia dijuluki Faqih Al-Irsyadiyin
(cendekiawan terkemuka di bidang hokum Islam dari Al-Irsyad). Sayang
kebanyakan bukunya yang umumnya ditulis dalam bahasa Arab, belum
diterjemahkan.Abdurrahman Baswedan: Pendiri Partai Arab Indonesia (PAI) dan
aktifis Masyumi ini pernah menjadi Wakil Menteri Penerangan RI.
Namun perkembangan Al-Irsyad yang awalnya naik pesat, kemudian
menurun drastic bersamaan dengan masuknya pasukan pendudukan Jepang ke
Indonesia. Apalagi setelah Syekh Ahmad Surkati wafat pada 1943, dan revolusi
fisik sejak 1945. Banyak sekolah Al-Irsyad hancur, diporak-porandakan Belanda
karena menjadi markas laskar pejuang kemerdekaan. Sementara beberapa gedung
milik Al-Irsyad yang dirampas Belanda, sekarang berpindah tangan, tanpa bisa
diambil lagi oleh Al-Irsyad.Sampai 1985, Al-Irsyad tinggal memiliki 14 cabang,
yang seluruhnya berada di Jawa. Namun berkat kegigihan para aktifisnya yang
sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, Al-Irsyad berkembang kembali,
sejak 1986. Puluhan cabang baru berdiri. Dan kini tercatat sekitar 130 cabang,
Gerakan Politik Islam Indonesia | 10
dari Sumatera ke Papua.Di awal berdirinya di tahun 1914, Perhimpunan Al-Irsyad
Al-Islamiyyah dipimpin oleh ketua umum Salim Awad Balweel.
Dalam Muktamar terakhir di Bandung (2000), yang dibuka Presiden
Abdurrahman Wahid di Istana Negara pada 3 Juli 2000, terpilih Ir. H. Hisyam
Thalib sebagai ketua umum baru, menggantikan H. Geys Amar SH yang telah
menjabat posisi itu selama empat periode (1982-2000).Perhimpunan Al-Irsyad Al-
Islamiyyah memiliki empat organ aktif yang menggarap segmen anggota masing-
masing. Yaitu Wanita Al-Irsyad, Pemuda Al-Irsyad, Puteri Al-Irsyad, dan Pelajar Al-
Irsyad. Peran masing-masing organisasi yang tengah menuju otonomisasi ini
(sesuai amanat Muktamar 2000), cukup besar bagi bangsa. Pemuda Al-Irsyad
misalnya, ikut aktif menumpas pemberontakan G-30-S PKI bersama komponen
bangsa lainnya. Sedang Pelajar Al-Irsyad termasuk salah satu eksponen 1966 yang
ikut aktif melahirkan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia).
Di luar empat badan otonom tersebut, Al-Irsyad Al-Islamiyyah memiliki
majelis-majelis, yaitu Majelis Pendidikan & Pengajaran, Majelis Dakwah, Majelis
Sosial dan Ekonomi, Majelis Awqaf dan Yayasan, dan Majelis Hubungan Luar
Negeri. Di luar itu ada pula Lembaga Istisyariyah, yang beranggotakan tokoh-tokoh
senior Al-Irsyad dan kalangan ahli).
Al-Irsyad adalah organisasi yang membawa pembaharuan Islam di
Indonesia. Meskipun awal berdirinya banyak menimbulkan kontroversi dan fitnah-
fitnah yang bermunculan dari pihak Jamiat Khair, tetapi dengan berjalannya
waktu al-Irsyad dapat membuktikan ke eksisannya di hadapan masyarakat
Indonesia. Al-Irsyad berkembang pesat jauh meninggalkan Jamiat Khair.
Keberhasilan al-Irsyad tersebut membawa beberapa penduduk pribumi untuk
belajar di al-Irsyad, seperti M. Rasyidi, Farid Ma’ruf, dan Yunus Anis. Mereka
belajar di al-Irsyad karena tertarik dengan keberhasilan al-Irsyad. Setelah
menempuh pendidikan di al-Irsyad, mereka berperan aktif dalam organisasi
Muhammadiyah.Dalam perkembangannya, al-Irsyad berhubungan baik dengan
organisasi lain meskipun tidak berjalan secara formal dan tidak secara tertulis.
Hubungan baik itu dimulai oleh pemimpin al-Irsyad yaitu Ahmad Soorkatty.
Ahmad Soorkatty adalah pemimpin yang alim dan berwawasan luas, disamping itu
ia juga mudah bermasyarakat dan dapat menempatkan diri dimanapun ia berada
demi menegakkan ajaran yang diyakininya. Misalnya pada kongres pertama yang
diadakan di Cirebon pada tahun 1922, pada sa’at pembacaan maulid berzanji ia
ikut berdiri. Padahal, Ahmad Soorkatty berkeyakinan bahwa Hal tersebut adalah
bid’ah.
Hal tersebut ia lakukan agar dapat berdialog secara terbuka dengan
Semaun(Pemimpin Syarikat Islam merah). Ahmad Soorkatty banyak menggunakan
waktunya untuk merdialog dengan para pemimpin Islam. Bagi Ahmad Soorkatty,
tanpa dialog pesan tidak akan tersampaikan.15
15Hussein, Al- Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa, 36.
Gerakan Politik Islam Indonesia | 11
Negara Islam Indonesia (NII)
Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul
Islam atau DI) yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah kelompok Islam di
Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini
dimulai pada 7 Agustus 1942 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh
seorang politisi Muslim radikal, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa
Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kelompok ini mengakui syariat islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan
ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jemaah
Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan.
Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru
saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara
Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar
negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam
Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya
dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah
Al Quran dan Sunnah". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas
menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang
berlandaskan syariat Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain
Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir".
Pergerakan
Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah,
terutama Jawa Barat (berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah),
Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan .[1][2] Untuk melindungi kereta api, Kavaleri
Kodam VI Siliwangi (sekarang Kodam III) mengawal kereta api dengan panzer tak
bermesin yang didorong oleh lokomotif uap D-52 buatan Krupp Jerman Barat.
Panzer tersebut berisi anggota TNI yang siap dengan senjata mereka. Bila ada
pertempuran antara TNI dan DI/TII di depan, maka kereta api harus berhenti di
halte terdekat. Pemberontakan bersenjata yang selama 13 tahun itu telah
menghalangi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda
dan ribuan anak-anak menjadi yatim-piatu. Diperkirakan 13.000 rakyat Sunda,
anggota organisasi keamanan desa (OKD) serta tentara gugur. Anggota DI/TII yang
tewas tak diketahui dengan tepat.[3]
Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini
menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dinyatakan
sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.[4][5]
Gerakan DI/TII Daud Beureueh
Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan "Proklamasi" Daud Beureueh
bahwa Aceh merupakan bagian "Negara Islam Indonesia" di bawah pimpinan Imam
Kartosuwirjo pada tanggal 20 September1953.
Daued Beureueh pernah memegang jabatan sebagai "Gubernur Militer
Daerah Istimewa Aceh" sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan
tahun 1947. Sebagai Gubernur Militer ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah
Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.
Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas Gubernur Militer, Daud Beureuh bisa
Gerakan Politik Islam Indonesia | 12
memperoleh pengikut. Daud Beureuh juga berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat
Pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Untuk beberapa waktu lamanya
Daud Beureuh dan anak-buahnya dapat mengusai sebagian daerah Aceh.
Sesudah bantuan datang dari Sumatera Utara dan Sumatera Tengah,
operasi pemulihan keamanan ABRI ( TNI-POLRI ) segera dimulai. Setelah didesak
dari kota-kota besar, Daud Beureuh meneruskan pemberontakannya di hutan-
hutan. Penyelesaian terakhir Pemberontakan Daud Beureuh ini dilakukan dengan
suatu " Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" pada bulan Desember 1962 atas
prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel Jendral Makarawong.[6].
Gerakan DI/TII Ibnu Hadjar
Pada bulan Oktober 1950 DI/ TII juga tercatat melakukan pemberontakan
di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Para pemberontak
melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI (TNI-POLRI).
Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut pemerintah pada mulanya
melakukan pendekatan damai kepada Ibnu Hadjar dengan diberi kesempatan
untuk menyerah, dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Ibnu Hadjar sempat
berpura-pura menyerah, akan tetapi setelah menyerah dia kembali melarikan diri
dan melakukan pemberontakan lagi sehingga pemerintah akhirnya terpaksa
menugaskan pasukan ABRI (TNI-POLRI) untuk menangkap Ibnu Hadjar. Pada
akhir tahun 1959 Ibnu Hadjar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap
dan dihukum mati.[7][8][9]
Gerakan DI/TII Amir Fatah
Amir Fatah merupakan tokoh yang membidani lahirnya DI/TII Jawa
Tengah. Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah
dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh
beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan
S.M. Kartosuwirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam radikal.
Kedua, Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur
Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh
oleh "orang-orang Kiri", dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya
pengaruh "orang-orang Kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI dianggap tidak
menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah
Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II,
harus diserahkan kepda TNI di bawah Wongsoatmojo. Keempat, adanya perintah
penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo. Hingga kini Amir Fatah dinilai
sebagai pembelot baik oleh negara RI maupun umat muslim Indonesia.[10]
Gerakan DI/TII Qahar Muzakkar
Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan
(KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Kahar Muzakkar
menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya
dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah
pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak
memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan
menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat
dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar
Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa
Gerakan Politik Islam Indonesia | 13
persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah
nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai
bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus1953. Tanggal 3
Februari1965, Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan ABRI (TNI-POLRI)
dalam sebuah baku tembak.[11]
Gerakan Politik Islam Indonesia | 14
KH. Hasyim Asy’ari dan Perkembangan Awal Nahdlatul Ulama’
KH. Hasyim Asy’ari dan NU
Dalam sejarah Indonesia, sejak masa pra-Kemerdekaan hingga saat ini,
posisi dan peranan ulama cukup penting terhadap proses perubahan sosial
kemasyarakatan, karena ulama merupakan tokoh panutan bagi umat Islam yang
merupakan agama terbesar di Indonesia.
KH. Hasyim Asy’ari merupakan seorang ulama yang terkemuka di
zamannya, karena dia adalah pendiri pondok pesantren Tebuireng dan ikut serta
mendorong untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan, di sisi lain dia
adalah tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama yang kelak dalam sejarah
Indonesia akan menjadi ormas Islam terbesar dan memainkan peranan yang
cukup signifikan dalam berbagai perubahan sosial dan politik di Indonesia.16
Kelahiran Nahdlatul Ulama merupakan respons terhadap munculnya
gagasan pembaharuan Islam di Indonesia yang banyak di pengaruhi pemikiran
atau faham Wahabi serta ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afgani dan
Muhammad Abduh.
Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa,
dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan yang kemudian pada 1912 membentuk
organisasi Muhammadiyah yang banyak melakukan kritik terhadap praktik-
praktik keagamaan yang dilakukan kelompok muslim tradisional, seperti menolak
tarikat atau praktik seperti talqin yang berkembang sebagai tradisi keagamaan
muslim tradisional.
Puncak dari pertentangan muslim “modern” dan muslim “tradisional” ini
terjadi ketika pemerintah Ibnu Saud dari kerajaan Saudi Arabia ingin mengadakan
kongres tentang kekhalifahan di Mekah dalam usahanya untuk mendirikan
kekhalifahan baru. Hal ini mendapatkan respons yang positif dari tokoh-tokoh
Islam di Indonesia, sehingga diadakanlah kongres di Bandung yang dihadiri
kelompok Islam modernis dan tradisional. Hasil dari kongres ini menunjuk
Tjokroaminoto dari SI dan KH. Mas Mansyur dari Muhammadiyah (keduanya
kelompok modernis) untuk mengikuti kongres tentang kekhalifahan di Mekah
tersebut. Hal ini menimbulkan kekecewaan kelompok Islam tradisional karena
tidak terwakili mengikuti kongres tersebut. Karena itu KH. Wahab Hasbullah
(kelompok tradisional) mengusulkan agar utusan Indonesia meminta kepada
pemerintah Wahabi Saudi Arabia agar tetap mempertahankan ajaran dan praktik
keagamaan empat mazhab, walaupun permintaan itu ditolak.17
Untuk memperjuangkan aspirasi ulama-ulama tradisional agar dapat bertemu
dengan Raja Ibnu Su’ud, pada 31 Januari 1926 KH. Wahab Hasbullah
mengundang ulama tradional terkemuka seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Asnawi,
dan beberapa tokoh lainnya untuk membicarakan langkah-langkah atas utusan
ulama tradisional untuk dapat mengirimkan utusan sendiri mengikuti kongres
kekhalifahan di Arab Saudi, dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa
keputusan penting sebagai berikut:
16 Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, (Yogyakarta: LKIS,
2002), hal. 15
17 Faisal Ismail, Pijar-pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur, (Jakarta: Departemen Agama Proyek
Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1992), hal. 76.
Gerakan Politik Islam Indonesia | 15
1. Mereka secara resmi membentuk komite Hijaz, yang akan mengirimkan
utusan sendiri untuk menghadapi Raja Ibnu Su’ud.
2. Membentuk organisasi yang berfungsi sebagai wahana para ulama dalam
membimbing ulama mencapai kejayaan, dan organisasi tersebut diberi
nama “Nahdlatul Ulama”.18
Adapun peranan KH. Hasyim Asy’ari dalam pembentukan NU ini sangat
penting, karena restu dan legitimasi yang dia berikan sangat berpengaruh
terhadap pembentukan organisasi NU. Oleh karena itu dia ditunjuk sebagai rais
akbar, sementara ketua tanfiziyahadalah H. Hasan Gipo. Dalam perkembangan
selanjutnya, warna dan corak NU sangat dipengaruhi oleh KH. Hasyim Asy’ari. Hal
ini terlihat dari pidato iftitahyang disampaikannya kepada warga NU tentang
faham Ahlussunnah Wal Jama’ah yang menganut satu dari empat mazhab yang
dijadikan sebagai azas NU. Bahkan muqaddimah NU Qonun Asasy karangan
beliau dijadikan sebagai satu kesatuan yang utuh dari Anggaran Dasar NU.
Lebih dari itu, kebesaran Kyai Hasyim bukan hanya karena ia seorang ulama
yang teguh, tetapi juga seorang patriot yang mencintai tanah airnya. Ia tanpa
kenal lelah mendidik santri-santrinya menjadi ahli agama sekaligus pejuang
bangsa untuk merebut kedaulatan dan kemerdekaan tumpah darahnya. Kyai
Hasyim bukan hanya melawan kolonialisme dalam arti militer, tetapi juga
kolonialisme kultural.
Karena itu, ia sempat mengharamkan santri dan masyarakat memakai pakaian
yang menjadi kebiasaan kaum penjajah seperti dasi dan celana. Seperti ditulis
Abdurrahman Wahid dalam Bunga Rampai Pesantren, pada masa perlawanan
terhadap pemerintah kolonial, kyai dan pesantren secara kultural berfungsi
sebagai benteng pertahanan menghadapi penetrasi kebudayaan luar.
Fungsi yang demikian menghendaki adanya proses “pemurnian”agama dalam
batas-batas tertentu, dimulai dari penonjolan aspek syara (formalisme hukum
agama) di pesantren. Patriotisme dan nasionalisme Kyai Hasyim juga ditunjukkan
ketika ia bersama sejumlah kyai memelopori Resolusi Jihad pada 22 Oktober
1945.
Resolusi itu berisi seruan kepada umat Islam untuk membangkitkan perang
suci (jihad) dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dengan mengusir
tentara Sekutu dan Belanda di belakangnya yang hendak kembali menjajah
Indonesia. Resolusi itu sendiri didasarkan atas fatwa Kyai Hasyim bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan Soekarno-Hatta adalah
sah secara fikih.
Dengan demikian, Kyai Hasyim telah memberi status kepada NKRI sebagai
negara yang sah di mata hukum agama (fikih). Di samping seorang nasionalis,
Kyai Hasyim juga bukan sosok yang haus jabatan. Ia tidak pernah tergoda untuk
berpolitik praktis. Ketika diberi jabatan oleh Jepang sebagai Kepala Shumubu
(Kantor Urusan Agama), misalnya, jabatan itu ia serahkan kepada putranya, KH.
A. Wahid Hasyim. Jadi Kyai Hasyim hanya menjadi kepala secara de jure.
Demikian juga jabatan sebagai Ketua Masyumi. Semua urusan politik praktis
didelegasikan kepada putranya, sementara Kyai Hasyim sendiri tetap istiqamah
berdakwah dan menjadi guru di pesantren. Ia tidak pernah meninggalkan-apalagi
melalaikan-tugas utamanya sebagai kyai pesantren.
18 Ismail, Pijar-pijar Islam, hal. 77.
Gerakan Politik Islam Indonesia | 16
Kyai Hasyim tidak pernah melarang kyai dan santri-santrinya berpolitik. Ia
sendiri memberi contoh bagaimana berpolitik. Namun politik Kyai Hasyim adalah
politik makrostrategis. Ia benar-benar melibatkan dirinya dalam urusan politik jika
ada situasi darurat yang mengancam kedaulatan bangsa dan kemerdekaan umat
untuk menjalankan ajaran agamanya.
Dengan demikian, Kyai Hasyim melibatkan diri dalam urusan politik untuk
jangka waktu tertentu, sementara urusan politik praktis diserahkan kepada orang
lain yang pas di bidang itu. Ibarat seorang resi yang hanya turun dari padepokan
di atas gunung ketika situasi masyarakat sedang kacau dan membutuhkannya.
Kalau situasi sudah normal, sang resi akan kembali berkhalwat di padepokannya.
Demikian juga Kyai Hasyim. Ia hanya terjun ke dunia politik dalam situasi dan
alasan khusus. Selebihnya ia kembali ke pesantren mengabdikan hidupnya untuk
pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.
NU pada Awal Perkembangan
Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 silam sebenarnya tak bisa
dilepaskan dengan perkembangan kelompok Islam yang secara relatif berhaluan
pembaruan ke arah “yang disebut” pemurnian (purifikasi) ajaran Islam.
Organisasi Muhammadiyah—didirikan di Yogyakarta pada 1912 oleh KH.
Ahmad Dahan—yang kemudian gerakannya dianggap cenderung berbeda dengan
kebiasaan praktik-praktik keagamaan (Islam) masyarakat lokal merupakan bagian
dari efek picu (trigger effect) yang mempercepat lahirnya NU.
Ditambah lagi pada saat itu gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah di
bawah pengaruh kuat ajaran Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi) dianggap
sudah kebablasan karena sudah sampai pada keinginan membongkar makam
Rasulullah SAW. Kalangan ulama Indonesia berhaluan Sunni akhirnya
membentuk komite (yang disebut Komite Hijaz) yang selanjutnya diutus khusus
untuk menemui Raja Fahd di Arab Saudi.
Dalam kerangka seperti itulah NU berdiri dan eksis sebagai pengayom
kepentingan semua kekuatan dengan gerakan yang berorientasi kerakyatan.
Infrastrukturnya sejak awal dibangun di atas tiga pilar utama, semangat
kebangsaan (nahdlatul wathan), semangat atau kebangkitan ekonomi ( nahdlatul
tujjar), dan gerakan pengembangan pemikiran (taswirul afkar)—Islam berbasis
kultural di Indonesia.
Dalam perjalanannya, karena watak reaktif itu pula NU kerap kali terjebak
pada situasi temporer, terutama terkait dengan agenda politik praktis. Para
tokohnya tampaknya tak ingin ketinggalan berpartisipasi dalam kancah
politik praktis, dengan alasan-alasan yang pada dasarnya bersifat pragmatis.
Apalagi, di kalangan tokoh NU itu muncul kesadaran tentang adanya basis massa
politik yang riil yang secara kuantitatif memiliki posisi tawar kuat.
Periode akhir abad 18 dan awal abad 19 merupakan masa transisi dalam
sejarah dunia. Revolusi Perancis yang diikuti dengan revolusi industri telah
mengubah mengubah dunia dalam pengertian yang mendasar. Sejak itu tatanan
lama di dunia Barat mulai ditinggalkan dan gagasan-gagasan yang lebih memberi
peluang kebebasan kepada masyarakat semakin mengemuka. Efek kejut dari
perubahan-perubahan tersebut segera melanda kekuatankekuatan kolonial lama.
salah satu diantaranya adalah Belanda. Selama abad 17 dan 18 Belanda
merupakan salah satu kekuatan perdagangan dunia. VOC adalah salah satu
Gerakan Politik Islam Indonesia | 17
perusahaan multinasional utama yang menempatkan bangsa Belanda dalam
periode itu sebagai salah satu bangsa yang terkemuka di Eropa. Tetapi memasuki
abad ke-19 status Belanda mengalami penurunan drastis. VOC harus ditutup
diakhir abad 18 karena bangkrut, sementara sejak tahun 1795 Belanda diduduki
oleh tentara Perancis.
Dalam konteks dunia yang sedang mengalami transisi besar tersebut,
muncul tokohtokoh di Indonesia yang mencoba untuk memberikan respon
tergadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sementara itu, perubahan-
perubahan besar yang melanda masyarkat Minangkabau telah memunculkan
gerakan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Cita-cita pemurnian
agama yang diusung oleh gerakan ini harus menghadapi realita. Pemerintah
kolonial tidak bisa mentoleransi adanya kekuatan kekuatan lokal yang ingin
menegakkan otoritas politik dan keagamaan.
Berbeda dengan Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro berusaha
memadukan cita-cita yang berladaskan pada nilai-nilai yang berakar pada budaya
Jawa dan agama Islam. Gagasan perjuangan diponegoro berhasil menarik simpati
rakyat Jawa secara luas. Dukungan masyarakat Jawa diberikan kepada
Diponegoro, karena ia tidak sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu. Lebih jauh lagi, Diponegoro ingin mengakhiri penderitaan dan
rasa terhina masyarakat Jawa yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan
pemerintah kolonial yang mengalami perubahan mendasar di awal abad 19. Pada
masanya, cita-cita perjuangan Diponegoro hanya dapat diterima dalam lingkup
budaya dan masyarakat Jawa. Agaknya momentum sejarah ketika itu belum
memihak kepada Diponegoro. Meski demikian, kisah perjuangan Diponegoro
merupakan sumber inspirasi yang kaya bagi dunia pergerakan nasional
Indonesia, revolusi kemerdekaan, dan bahkan hingga saat ini.
Begitu juga yang dilakukan KH. Hasyim Asy’ari sebagai pendiri NU dan
ulama terkemuka berpengaruh kuat pada sikap beragama umat Islam Indonesia.
Bahkan sampai saat ini pemikiran KH. Hasyim Asy’ari yang diformulasikan dalam
organisasi NU menjadi acuan dalam beragama. Berbagai lembaga pendidikan yang
didirikan seperti pesantren dan perguruan tinggi Islam merupakan tonggak
sejarah cikal-bakal lahirnya ulama-ulama NU, yang hingga kini masih tetap eksis
dan terus berkembang.
Gerakan Politik Islam Indonesia | 18
Referensi
1. ^ Robert Cribb. 2000. Historical Atlas of Indonesia. Halaman 162.
2. ^"Relevansi Darul Islam Untuk Masa Kini". crisisgroup.org. 16 Agustus
2010. Diakses tanggal 28 November 2014.
3. ^"History of Railways in Indonesia". keretapi.tripod.com. Diakses tanggal 28
November 2014.
4. ^"NII Has New Target, Pattern". kompas.com. 25 April 2011. Diakses tanggal
28 November 2014.
5. ^"Q&A: Indonesia’s Terrorism Expert on the Country’s Homegrown Jihadis".
world.time.com. 26 Agustus 2013. Diakses tanggal 28 November 2014.
6. ^"Keterangan Pemerintah tentang peristiwa Daud Beureuh : [diutjapkan
dalam rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia
tanggal 28 Oktober 1953] ; Djawaban Pemerintah [atas pemandangan
umum Dewan Perwakilan Rakjat mengenai keterangan Pemerintah] tentang
peristiwa Daud Beureuh : [diutjapkan oleh Perdana Menteri dalam rapat
pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 2 Nopember 1953] / [Ali
Sastroamidjojo]" (PDF). 1953.
7. ^"Mencari Ibnu Hajar dalam Sejarah". banjarmasin.tribunnews.com. 25
Juni 2013. Diakses tanggal 28 November 2014.
8. ^ Singh, Bilveer (2007). The Talibanization of Southeast Asia. Greenwood
Publishing Group, Inc. p. 31.
9. ^ Sjamsuddin, Nazaruddin (1985). The Republican Revolt: A Study of the
Acehnese Rebellion. Institute of Southeast Asian Studies. p. 247.
10. ^"Gerakan DI/TII Amir Fatah 1949-1950 : suatu pemberontakan kaum
Santri di Daerah Tegal-Brebes" (PDF). University of Indonesia Library.
Diakses tanggal 28 November 2014.
11. ^ Zurbuchen, Mary (2005). Beginning to remember : The past in the
indonesian present. Seattle: University of Washington Press.
12. Sumber: Website PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah: http://www.alirsyad.org
13. Barton, Greg, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman
Wahid, (Yogyakarta: LKIS, 2002).
14. Ismail, Faisal, Pijar-pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur, (Jakarta:
Departemen Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama,
1992)
15. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta,
Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, LP3ES
Gerakan Politik Islam Indonesia | 19
You might also like
- Sejarah Masuknya Islam Di MalukuDocument12 pagesSejarah Masuknya Islam Di MalukuMuhammad Qadri100% (1)
- Faktor Kbngkitan Islam (PNJJHN)Document29 pagesFaktor Kbngkitan Islam (PNJJHN)Areswat MachedaNo ratings yet
- Pemberotakan Masyarakat Islam Di MidanaoDocument24 pagesPemberotakan Masyarakat Islam Di MidanaoaqwalNo ratings yet
- Darah Keturunan Arab (Hafizul)Document5 pagesDarah Keturunan Arab (Hafizul)HafizulLurveDieylaNo ratings yet
- Skema Sejarah Trial Kelantan 2020Document20 pagesSkema Sejarah Trial Kelantan 2020aqwalNo ratings yet
- Masyarakat PluralDocument16 pagesMasyarakat PluralMohd Najib Zainal0% (1)
- Tajuk-Tajuk Pilihan Sem 2 2023Document29 pagesTajuk-Tajuk Pilihan Sem 2 2023Haziq FikriNo ratings yet
- NasionalismeDocument14 pagesNasionalismemuizzomarNo ratings yet
- Tahap NasionalismeDocument7 pagesTahap Nasionalismeabc7000100% (1)
- Pengaruh Tamadun Luar Dalam Kehidupan MaDocument13 pagesPengaruh Tamadun Luar Dalam Kehidupan MavityaaNo ratings yet
- Zaman GelapDocument17 pagesZaman GelapgreenoptimusNo ratings yet
- JIHADDocument2 pagesJIHADxhleeNo ratings yet
- Sejarah FreemasonDocument7 pagesSejarah Freemasondeanzbandung8941No ratings yet
- Tutorial Titas Minggu 3Document8 pagesTutorial Titas Minggu 3PI1-0620 Raihanah Binti AbasNo ratings yet
- Perkembangan Kesedaran Sosial Dan Politik Yang Berlaku Di Burma Dan Filipina Antara Tahun 1900-1940.Document15 pagesPerkembangan Kesedaran Sosial Dan Politik Yang Berlaku Di Burma Dan Filipina Antara Tahun 1900-1940.khilafahbundleNo ratings yet
- Sejarah Kemasyarakatan MASDocument27 pagesSejarah Kemasyarakatan MASsiew chang yeeNo ratings yet
- Masyarakat Majmuk Di MalaysiaDocument21 pagesMasyarakat Majmuk Di MalaysiaAreswat MachedaNo ratings yet
- 5 6215362828920948433Document155 pages5 6215362828920948433Keiron KastimNo ratings yet
- Sadn 1033 Bab 4Document31 pagesSadn 1033 Bab 4Anonymous wsqFdcNo ratings yet
- 04 Tajuk 4 Islam Dalam Tamadun MelayuDocument19 pages04 Tajuk 4 Islam Dalam Tamadun MelayunurulsyakillanabilaNo ratings yet
- FreemasonDocument10 pagesFreemasonNurraudhah AkmaliahNo ratings yet
- Tamadun Islam & Tamadun AsiaDocument30 pagesTamadun Islam & Tamadun AsiaLisa Wong0% (1)
- JMS214 - MohdKhairulnizamJoharDocument5 pagesJMS214 - MohdKhairulnizamJoharkhairulnizamNo ratings yet
- Sej Kolonialisme Kump NEW 1Document32 pagesSej Kolonialisme Kump NEW 1Mohd JefrieNo ratings yet
- Faktor Gerakan Nasionalisme Di Tanah MelayuDocument7 pagesFaktor Gerakan Nasionalisme Di Tanah Melayupembuyutan100% (18)
- Sumbangan Tamadun Islam Bab4Document83 pagesSumbangan Tamadun Islam Bab4Sandra MitNo ratings yet
- Forum 1Document4 pagesForum 1YATTNo ratings yet
- Pengaruh Kedatangan Islam Ke Atas Masyarakat Alam MelayuDocument3 pagesPengaruh Kedatangan Islam Ke Atas Masyarakat Alam Melayuatma afisahNo ratings yet
- Tajuk 4 Islam Dalam Tamadun MelayuDocument20 pagesTajuk 4 Islam Dalam Tamadun MelayuAZ ZakirahNo ratings yet
- Tajuk 4 - Islam Dalam Tamadun MelayuDocument20 pagesTajuk 4 - Islam Dalam Tamadun MelayuNoralifah ParminNo ratings yet
- Bacaan 2 - Sifat Ekonomi Tanah Melayu Pra Kolonial PDFDocument26 pagesBacaan 2 - Sifat Ekonomi Tanah Melayu Pra Kolonial PDFIrfan FazailNo ratings yet
- Fa HsiDocument10 pagesFa HsiShafinaz hamidiNo ratings yet
- Masyarakat Pluraliti Pada Zaman PenjajahanDocument35 pagesMasyarakat Pluraliti Pada Zaman Penjajahansyera_rashidNo ratings yet
- Ulasan Buku QadianiDocument3 pagesUlasan Buku QadianiAhmad Sahlan HatimNo ratings yet
- Handout Soalan No 7 Ail 1007Document9 pagesHandout Soalan No 7 Ail 1007Farah AffendyNo ratings yet
- Dakwah Dan Jihad Ahli TasawufDocument6 pagesDakwah Dan Jihad Ahli TasawufRohaitul AkmaNo ratings yet
- EseiDocument14 pagesEseiLee Chee ChungNo ratings yet
- EseiDocument14 pagesEseiLee Chee ChungNo ratings yet
- Ulasan Buku Liku-Liku Gerakan Islam Di MalaysiaDocument11 pagesUlasan Buku Liku-Liku Gerakan Islam Di MalaysiaMohd Fuad Mohd Salleh, UniselNo ratings yet
- Teori Kedatangan IslamDocument86 pagesTeori Kedatangan IslamSuzain SelemanNo ratings yet
- IDA102Document13 pagesIDA102safian pyanNo ratings yet
- Faktor Kebangkitan NasionalismeDocument6 pagesFaktor Kebangkitan Nasionalismemiszja290% (1)
- Pembentukan Masyarakat PluralistikDocument12 pagesPembentukan Masyarakat PluralistikNathanael MooreNo ratings yet
- Jelaskan PerubahanDocument3 pagesJelaskan PerubahanFirdaussii Ismail0% (2)
- Perkembangan Masyarakat Islam Pada Zaman Khulafa Al-RasyidinDocument3 pagesPerkembangan Masyarakat Islam Pada Zaman Khulafa Al-RasyidinNur Suzyliana Sarkawi100% (2)
- Presentation HST 224Document20 pagesPresentation HST 224Nik AtikahNo ratings yet
- Masyarakat Pluraliti Pada Zaman PenjajahanDocument36 pagesMasyarakat Pluraliti Pada Zaman PenjajahanmawarpinkNo ratings yet
- Free MasonDocument6 pagesFree MasonPencinta KebahagiaanNo ratings yet
- Nasionalisme Di Syria-NadyaDocument7 pagesNasionalisme Di Syria-NadyanadyaNo ratings yet
- Malaysia 2Document14 pagesMalaysia 2anounymousNo ratings yet
- Kesan PolitikDocument46 pagesKesan Politikeila chan67% (3)
- Pendahuluan - Kristian Di Asia Tenggara - HSA 3033Document13 pagesPendahuluan - Kristian Di Asia Tenggara - HSA 3033MUHAMAD FAHMI MUSTAFA KAMALNo ratings yet
- Hubungan Etnik EseiDocument11 pagesHubungan Etnik Eseiying1989No ratings yet
- Sejarah Pemikiran Pandang Ke Israel di Malaysia (1957-2003)From EverandSejarah Pemikiran Pandang Ke Israel di Malaysia (1957-2003)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (9)