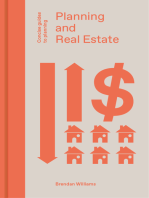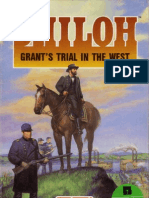Professional Documents
Culture Documents
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
66 viewsJurnal Bahasa Inggris Perkim
Jurnal Bahasa Inggris Perkim
Uploaded by
SusiyantiptrdhThis document discusses housing and settlement policy for urban communities in Indonesia. It notes the increasing problems of urbanization, including a large backlog and need for new housing units. Government policies often fail to meet resident needs due to competing interests. The research aims to identify, describe, interpret and analyze resettlement methods, involved actors, instruments used, and supporting/blocking factors. The results showed resettlement of slums and squatters occurs gradually through cooperation of various actors, not just government. Actors include communities, NGOs, professionals and consultants. Institutionalized groups like NGOs can effectively influence policy. Financial incentives are used but do not guarantee program continuity. Hybrid implementation models are used but never perfect, requiring new policies over
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You might also like
- Urban Planning TheoriesDocument6 pagesUrban Planning TheoriesVeeresh80% (5)
- Kebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban: DinamikaDocument17 pagesKebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban: DinamikaPutra RajaNo ratings yet
- Tugas Perkot Nuur Awaliyah 08161061Document8 pagesTugas Perkot Nuur Awaliyah 08161061liyaalfrzNo ratings yet
- Chapter 2. Literature Review: Urbanization - A Process of Transition of Urban AreasDocument42 pagesChapter 2. Literature Review: Urbanization - A Process of Transition of Urban AreasSARVESH NANDGIRIKARNo ratings yet
- The Role of The Architect in Slum Upgrading Practices - Karin Nord 4Document23 pagesThe Role of The Architect in Slum Upgrading Practices - Karin Nord 4Cami PetreNo ratings yet
- 1023 ArticleText 3563 1 10 20200629Document19 pages1023 ArticleText 3563 1 10 20200629Reza AlkautsaryNo ratings yet
- Unpacking Participation in Kathputli ColonyDocument9 pagesUnpacking Participation in Kathputli ColonydervishdancingNo ratings yet
- Sustainable Urban Futures: Urbanization in An Era of Globalization and Environmental ChangeDocument8 pagesSustainable Urban Futures: Urbanization in An Era of Globalization and Environmental ChangeAlma Rosa Mendoza CortésNo ratings yet
- Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 1 - Pebruari 2019Document17 pagesLocus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 1 - Pebruari 2019Gilang KrisnawanNo ratings yet
- Malvani Peoples Plan Summary PDFDocument3 pagesMalvani Peoples Plan Summary PDFAravind UnniNo ratings yet
- Sustainability 15 07248Document18 pagesSustainability 15 07248getawmekibebNo ratings yet
- Urbanismo ParticipativoDocument4 pagesUrbanismo ParticipativoEduardo HurtadoNo ratings yet
- Term Paper - Delos SantosDocument7 pagesTerm Paper - Delos SantosLigaya Delos SantosNo ratings yet
- Muhammad Anwar - BAB 1 John FriedmannDocument12 pagesMuhammad Anwar - BAB 1 John FriedmannMuhammad AnwarNo ratings yet
- The Concept of Spatial Planning and The Planning System (In The Book: Spatial Planning in Ghana, Chap 2)Document18 pagesThe Concept of Spatial Planning and The Planning System (In The Book: Spatial Planning in Ghana, Chap 2)gempita dwi utamiNo ratings yet
- RSW No. 6 - Javier, Danica T.Document33 pagesRSW No. 6 - Javier, Danica T.DaNica Tomboc JavierNo ratings yet
- Self Sustainable Township: Asst - Prof.Pad - Dr. D.Y.Patil College of Architecture, Akurdi - Pune, Maharashtra, IndiaDocument4 pagesSelf Sustainable Township: Asst - Prof.Pad - Dr. D.Y.Patil College of Architecture, Akurdi - Pune, Maharashtra, IndiaAbhijeetJangidNo ratings yet
- Metadata 11 03 02Document8 pagesMetadata 11 03 02SIOMARA MARIBEL JURADO GARCIANo ratings yet
- Summary of Urban Planning TheoryDocument13 pagesSummary of Urban Planning TheorymanishaNo ratings yet
- Prospek Peningkatan Kualitas Ruang Perumahan Dan Pemukiman Yang Berbasis Pada KomunitasDocument17 pagesProspek Peningkatan Kualitas Ruang Perumahan Dan Pemukiman Yang Berbasis Pada KomunitasMuhammad Arief Al HusainiNo ratings yet
- Improvement of Community Governance To Support Slum Upgrading Programs in IndonesiaDocument12 pagesImprovement of Community Governance To Support Slum Upgrading Programs in IndonesiaMade agungNo ratings yet
- Bowes ExploringInnovationinHousing 2018CFRDocument97 pagesBowes ExploringInnovationinHousing 2018CFRCecil SolomonNo ratings yet
- Cities For The Urban Poor in Zimbabwe Urban Space As A Resource For Sustainable Development OKDocument14 pagesCities For The Urban Poor in Zimbabwe Urban Space As A Resource For Sustainable Development OKNikos MarkoutsasNo ratings yet
- Smart and Sustainable Cities: The Main Guidelines of City Statute For Increasing The Intelligence of Brazilian CitiesDocument26 pagesSmart and Sustainable Cities: The Main Guidelines of City Statute For Increasing The Intelligence of Brazilian CitiesLovelyn Mae de LaraNo ratings yet
- Current Urban Planning ModelDocument3 pagesCurrent Urban Planning ModelSukhman ChawlaNo ratings yet
- Pengawasan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Ketersediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Kota Kudus (Studi Kasus Perumahan Bumi Rendeng Baru)Document10 pagesPengawasan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Ketersediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Kota Kudus (Studi Kasus Perumahan Bumi Rendeng Baru)indo sellerNo ratings yet
- Citizen Participation and Land Use Planning: (Focus in The City of San Juan)Document11 pagesCitizen Participation and Land Use Planning: (Focus in The City of San Juan)junNo ratings yet
- 4 Sustainable Planning Concepts at The Beginning of 21stDocument48 pages4 Sustainable Planning Concepts at The Beginning of 21stNeha SardaNo ratings yet
- Local Govt Administration: Current Issues in Local GovernmentDocument44 pagesLocal Govt Administration: Current Issues in Local GovernmentArimanthea LeeNo ratings yet
- Addresing The Challenges of UrbanizationDocument4 pagesAddresing The Challenges of UrbanizationRandalNo ratings yet
- Affordable Housingin DhakaDocument11 pagesAffordable Housingin DhakaAlNaeemNo ratings yet
- Konsep Perencanaan Permukiman Tepi Sungai Yang Berwawasan EkologiDocument6 pagesKonsep Perencanaan Permukiman Tepi Sungai Yang Berwawasan EkologiMyrabukitbatasNo ratings yet
- A-67-286 United Nations HabitatDocument52 pagesA-67-286 United Nations HabitatWellington MigliariNo ratings yet
- Tu and Zhang - 2023 - Land Use Change, Policy Dynamics and Urban GovernaDocument16 pagesTu and Zhang - 2023 - Land Use Change, Policy Dynamics and Urban Governachiyf0328No ratings yet
- Comprehensive PlanningDocument10 pagesComprehensive PlanningNaeem Akhtar SamoonNo ratings yet
- 5whose City Is It AnywayDocument27 pages5whose City Is It AnywayAbdullah ZubairNo ratings yet
- Course Title: Introduction To Urban: Institute of Land Administration Department of ArchitectureDocument120 pagesCourse Title: Introduction To Urban: Institute of Land Administration Department of ArchitectureMahiber KidussanNo ratings yet
- Lecture NotesDocument8 pagesLecture NotesPrinceNo ratings yet
- Sustainable ArchitectureDocument47 pagesSustainable ArchitecturePavithravasuNo ratings yet
- Housing Resilience and The Informal City: Paul JonesDocument11 pagesHousing Resilience and The Informal City: Paul JonesTSAMARANo ratings yet
- Urban DevelopmentDocument11 pagesUrban Developmentpaswanetakunda4ktNo ratings yet
- UNIT 1 Urban Housing PDFDocument68 pagesUNIT 1 Urban Housing PDFAnirudh VijayanNo ratings yet
- Access of Low Income People To Housing-KKB LahoreDocument12 pagesAccess of Low Income People To Housing-KKB LahoreObaidullah NadeemNo ratings yet
- Community Participation in Nature Conservation: The Chinese Experience and Its Implication To National Park ManagementDocument17 pagesCommunity Participation in Nature Conservation: The Chinese Experience and Its Implication To National Park ManagementIram AmmadNo ratings yet
- Marvin Critique 3Document4 pagesMarvin Critique 3edelyn joy reyesNo ratings yet
- Delhi Master PlanDocument40 pagesDelhi Master Plansubodh1984No ratings yet
- Atanu Chatterjee - PaperDocument25 pagesAtanu Chatterjee - PaperAtanuChatterjeeNo ratings yet
- Sahat Tulus Martua Silaban - 03061381722074Document63 pagesSahat Tulus Martua Silaban - 03061381722074Tulus Na JugulanNo ratings yet
- Rahel Worku FinalDocument74 pagesRahel Worku Finaltamerat bahtaNo ratings yet
- Literature Review On Urban Extension PlanningDocument17 pagesLiterature Review On Urban Extension PlanningAbicha Alemayehu100% (1)
- PDF of Culture X ArchitectureDocument7 pagesPDF of Culture X ArchitectureAnereeNo ratings yet
- Planning For Democracy in Protected Rural Areas: Application of A Voting Method in A Spanish - Portuguese ReserveDocument18 pagesPlanning For Democracy in Protected Rural Areas: Application of A Voting Method in A Spanish - Portuguese ReserveMónica De Castro PardoNo ratings yet
- Unit 5Document17 pagesUnit 5Honeylette MolinaNo ratings yet
- Reflection Report P4 Yiyi Lai 5327504Document5 pagesReflection Report P4 Yiyi Lai 5327504Sayali SaidNo ratings yet
- National Framework For Physical PlanningDocument15 pagesNational Framework For Physical PlanningDongzkie Vainkill100% (1)
- Urbanism As A Way o LifeDocument7 pagesUrbanism As A Way o LifedewarucciNo ratings yet
- Introduction To Urban PlanningDocument77 pagesIntroduction To Urban PlanningAMANUEL WORKUNo ratings yet
- Fundamentals of UrbanizationDocument98 pagesFundamentals of Urbanizationjudyachieng92No ratings yet
- Breaking the Development Log Jam: New Strategies for Building Community SupportFrom EverandBreaking the Development Log Jam: New Strategies for Building Community SupportNo ratings yet
- Peter GärdenforsDocument9 pagesPeter GärdenforsusamaknightNo ratings yet
- Social and Cultural Issues On GenderDocument25 pagesSocial and Cultural Issues On GenderKipi Waruku BinisutiNo ratings yet
- The Importance of Work-Life Balance On Employee Performance Millennial Generation in IndonesiaDocument6 pagesThe Importance of Work-Life Balance On Employee Performance Millennial Generation in IndonesiaChristianWiradendiNo ratings yet
- Resume Sample For TeenagerDocument6 pagesResume Sample For Teenagerafjwoovfsmmgff100% (2)
- TH 10 012Document10 pagesTH 10 012IAS CrackNo ratings yet
- Gas Flow in Pipeline NetworksDocument18 pagesGas Flow in Pipeline NetworksAbeer AbdullahNo ratings yet
- Principles of GeologyDocument10 pagesPrinciples of GeologyJoshuaB.SorianoNo ratings yet
- Understanding Feyerabend On GalileoDocument5 pagesUnderstanding Feyerabend On Galileorustycarmelina108No ratings yet
- BD F118S en WW - LDocument12 pagesBD F118S en WW - LyusufNo ratings yet
- Project 4Document6 pagesProject 4Trai TranNo ratings yet
- Pola Seismic Code CommentaryDocument15 pagesPola Seismic Code Commentary_ARCUL_100% (1)
- Problem Book in RelativityDocument25 pagesProblem Book in Relativitylinamohdzhor481520% (5)
- 1 (A) Derive The SI Base Unit of Force.: Test, Topic: MeasurementsDocument13 pages1 (A) Derive The SI Base Unit of Force.: Test, Topic: MeasurementsBilal RazaNo ratings yet
- FULL CycloCatalog Web 2 PDFDocument248 pagesFULL CycloCatalog Web 2 PDFprayogo1010No ratings yet
- Direção - Kia Picanto 2012Document16 pagesDireção - Kia Picanto 2012kiwel.01No ratings yet
- Covid 19 Notifiable PIDsr PDFDocument73 pagesCovid 19 Notifiable PIDsr PDFjheanniver nabloNo ratings yet
- Computer Assembly and DisassemblyDocument8 pagesComputer Assembly and DisassemblyPRECIOUS FAITH VILLANUEVANo ratings yet
- Best Rosin Press of 2020 PDFDocument4 pagesBest Rosin Press of 2020 PDFdannie gaoNo ratings yet
- General Physics Lesson 1 Methods of Electrostatic ChargingDocument46 pagesGeneral Physics Lesson 1 Methods of Electrostatic ChargingLeoj Levamor D. AgumbayNo ratings yet
- Roboti (E) 42Document8 pagesRoboti (E) 42pc100xohmNo ratings yet
- Shiloh Grant's Trail in The WestDocument37 pagesShiloh Grant's Trail in The Westremow50% (2)
- Achievement Report PDFDocument4 pagesAchievement Report PDFAnonymous IpBC61ZNo ratings yet
- WF Chapt1Document12 pagesWF Chapt1Shinmei KyoshiNo ratings yet
- Quality Control and Monitoring CONSTRUCTIONDocument38 pagesQuality Control and Monitoring CONSTRUCTIONcosmin_b100% (1)
- A Concept of Pilot Plant For Innovative Production of Ammonium FertilizersDocument6 pagesA Concept of Pilot Plant For Innovative Production of Ammonium FertilizersEndah SaraswatiNo ratings yet
- How To Calculate Paint QtyDocument2 pagesHow To Calculate Paint QtyVijay GaikwadNo ratings yet
- GK 2 Tieng Anh 9 (7N) 20 21Document6 pagesGK 2 Tieng Anh 9 (7N) 20 21SelenaNo ratings yet
- Chapter3 Electropneumatic UpdatedDocument60 pagesChapter3 Electropneumatic UpdatedViệt Đặng XuânNo ratings yet
- (Computer Science Project) To Generate Electricity Bill For Computer Science ProjectDocument33 pages(Computer Science Project) To Generate Electricity Bill For Computer Science ProjectHargur BediNo ratings yet
Jurnal Bahasa Inggris Perkim
Jurnal Bahasa Inggris Perkim
Uploaded by
Susiyantiptrdh0 ratings0% found this document useful (0 votes)
66 views4 pagesThis document discusses housing and settlement policy for urban communities in Indonesia. It notes the increasing problems of urbanization, including a large backlog and need for new housing units. Government policies often fail to meet resident needs due to competing interests. The research aims to identify, describe, interpret and analyze resettlement methods, involved actors, instruments used, and supporting/blocking factors. The results showed resettlement of slums and squatters occurs gradually through cooperation of various actors, not just government. Actors include communities, NGOs, professionals and consultants. Institutionalized groups like NGOs can effectively influence policy. Financial incentives are used but do not guarantee program continuity. Hybrid implementation models are used but never perfect, requiring new policies over
Original Description:
Original Title
jurnal bahasa inggris perkim
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentThis document discusses housing and settlement policy for urban communities in Indonesia. It notes the increasing problems of urbanization, including a large backlog and need for new housing units. Government policies often fail to meet resident needs due to competing interests. The research aims to identify, describe, interpret and analyze resettlement methods, involved actors, instruments used, and supporting/blocking factors. The results showed resettlement of slums and squatters occurs gradually through cooperation of various actors, not just government. Actors include communities, NGOs, professionals and consultants. Institutionalized groups like NGOs can effectively influence policy. Financial incentives are used but do not guarantee program continuity. Hybrid implementation models are used but never perfect, requiring new policies over
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Download as docx, pdf, or txt
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
66 views4 pagesJurnal Bahasa Inggris Perkim
Jurnal Bahasa Inggris Perkim
Uploaded by
SusiyantiptrdhThis document discusses housing and settlement policy for urban communities in Indonesia. It notes the increasing problems of urbanization, including a large backlog and need for new housing units. Government policies often fail to meet resident needs due to competing interests. The research aims to identify, describe, interpret and analyze resettlement methods, involved actors, instruments used, and supporting/blocking factors. The results showed resettlement of slums and squatters occurs gradually through cooperation of various actors, not just government. Actors include communities, NGOs, professionals and consultants. Institutionalized groups like NGOs can effectively influence policy. Financial incentives are used but do not guarantee program continuity. Hybrid implementation models are used but never perfect, requiring new policies over
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 4
KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
BAGI MASYARAKAT URBAN
Etty Soesilowati1
Abstract: The increasing of urbanization tends to generate various problems
everywhere, especially in term of basic need services to people such as
housing and other facilities. Housing and settlement policy done by
government oftentimes fail to accomplish requirement of the resident because
of so many interests. This research aimed to identify, descript, interpret and
analyze the method of people resettlement, what actors involved in it, what
kind of instrument used, and all factors, which supported and blocked. The
result of this research showed that mechanism of urban people resettlement
from slum and squatters done gradually through pluralism approach, where
every step generated policy and collective action among the actors which
involved. The actors are not merely the mayor and its connected institutions,
but also intellectuals, professionals, communities, entrepreneurs and
consultants. This research also showed that the existence of actors, which
institutionalized within a network and community such as NGO and group of
resident, would be more effective to influence the government policy.
Stimulating instrument such as money, used to relocate people, but in fact,
such instrument did not guarantee to continue the program. In term of some
research findings, the research has contributed to remedy the model of
implementation “hybrid” where the formula of resettlement policy always
realized in the form of action, but its action is never perfect, so it emerged new
policy, in the long time and influenced by outside conditions of organization. In
order to guarantee the continual of hybrid instrument program, regulation is
necessary to apply beside financial instrument. The practical contribution that
the researcher can provide is the use of group based approach.
Keywords: Resettlement, Slum and Squatter
PEDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Satu bidang dimana selalu ada kekurangan baik di negara maju
maupun berkembang yang diakibatkan tekanan penduduk ialah bidang
perumahan dan permukiman. Sebagian besar permintaan akan perumahan
berasal dari berjuta-juta migran luar kota yang datang berbondong-bondong.
Secara nasional kebutuhan perumahan relatif besar, meliputi : kebutuhan
rumah yang belum terpenuhi (backlog) sekitar 4,3 juta unit; pertumbuhan
kebutuhan rumah baru setiap tahunnya sekitar 800 ribu unit; serta kebutuhan
peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi persyaratan layak
huni sekitar 13 juta unit rumah (Menkimpraswil, 2002)
Kondisi di atas jelas menimbulkan permasalahan lingkungan,
khususnya pusat kota (inner-city) dimana akan tercipta kawasan dan
lingkungan kumuh (sick districts and neighborhoods) yang dapat diindikasikan
dengan munculnya permukiman kumuh dan liar (slum dan squatters),
kematian dan kerusakan kawasan bersejarah, kesemrawutan dan kemacetan
lalulintas (traffic congestion), kerusakan kawasan tepian air, bantaran sungai
dan tepian laut, kekacauan ruang-ruang publik (public domain,public space,
public easement), lingkungan pedestrian, isi dan arti komunitas, ketidak
sinambungan ekologi kota serta ketidak seragaman morfologi dan tipologi
kota.
Sementara berdasarkan UU No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman serta Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 327/KPTS/M/2002
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang
Kawasan Perkotaan, pemanfaatan ruang haruslah disusun untuk menjaga
keserasian pembangunan antar sektor dalam kerangka pengendalian
program-program pembangunan perkotaan jangka panjang. Dua hal pokok
yang menjadi azas pemanfaatan ruang di perkotaan Indonesia yakni yang
pertama, adanya tiga unsur penting manusia beserta aktivitasnya, lingkungan
alam sebagai tempat dan pemanfaatan ruang oleh manusia dilingkungan
alam tersebut. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling
berkaitan dan berada dalam keseimbangan sehingga aktivitas manusia dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya harus memperhatikan daya dukung
lingkungannya yang berorientasi pada kehidupan yang berkelanjutan. Kedua,
proses pemanfaatan ruang harus bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki
perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak secara
terpadu, berdayaguna dan serasi.
Paradigma baru perancangan kota tersebut harus mempertimbangkan
aspek globalisasi, desentralisasi, demokratisasi dan sistem pemerintahan.
Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut diharapkan di satu sisi,
pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat menjadi Good
Urban Governance yang berarti aparat dapat merespon berbagai
permasalahan pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan
akuntabel bersama-sama unsur masyarakat. Melalui mekanisme Good
Governance akan terjadi proses “co-guiding, co-steering dan co-managing”
dari ketiga stakeholder utama, yaitu Pemerintah Daerah, sektor swasta dan
masyarakat. Dengan demikian kondisi ini akan membentuk “sense of
belongingness” dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan publik dan
lingkungannya.
LANDASAN TEORI
Permukiman kumuh dan liar sebenarnya mudah dirasakan dan dilihat
daripada dikatakan. Menurut Huque, permukiman kumuh sebagai terjemahan
dari “marginal settlement” atau “shanty town” yang di berbagai negara
memperoleh nama tersendiri seperti barriada (Peru), gececondu (Turki),
buste (India), chika (Ethiopia), bidonville (Afrika) dan sebagainya (Huque,
Asraf, 1975 :32). Sedangkan Clerence Schubert dari United Nations Centre
for Human Settlement (UNCHS) memberikan batasan tentang “marginal
settlement” tersebut sebagai “primarily residential communities which are
KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI
MASYARAKAT URBAN
populated by low to middle income residents but which enerally lock municipal
infrastructure and social services and develop outside the formal urbanization
process” (Schubert, C, 1979 : 3)
Dengan batasan semacam itu yang mengartikan “marginal settlement”
sebagai lingkungan permukiman yang dihuni oleh sekelompok masyarakat
berpenghasilan rendah dan menengah akan tetapi kurang didukung
infrastruktur, fasilitas dan pelayanan social dan berkembang di luar proses
urbanisasi yang formal, maka tercakuplah kategori permukiman yang lazim
disebut kumuh (slums) dan liar (squatters). Slums adalah lingkungan
permukiman yang absah, legal dan permanen tetapi kondisi fisik
lingkungannya semakin memburuk karena kurang pemeliharaan, umur
bangunan yang menua, ketidak acuhan atau karena terbagi-bagi menjadi unit
pekarangan rumah dan kamar yang semakin kecil. Sedangkan squatters
adalah lingkungan permukiman liar yang menempati lahan illegal (bukan
daerah permukiman) seringkali tidak terkontrol dan tidak terorganisasi dengan
kondisi lingkungan dan bangunan yang sangat jelek tanpa dilayani oleh
sarana dan prasarana lingkungan (Drakakis Smith, David, 1979 : 24).
Permukiman kumuh tidak selalu liar, demikian juga permukiman liar tidak
selamanya kumuh. Hunian liar dikaitkan dengan status kepemilikan tanah,
yaitu hunian yang dibangun diatas tanah yang bukan haknya. Permukiman
liar di kota sebagian besar berada diatas tanah negara. Jadi apabila ada
permukiman kumuh yang menempati tanah negara atau bukan haknya
merupakan permukiman kumuh sekaligus liar.
Model penanggulangan permukiman kumuh dan liar dapat berwujud:
(1) program peremajaan kota (urban renewal), dimana merupakan proses
yang sangat mahal karena dihadapkan pada terbatasnya lahan dan tingginya
nilai lahan perkotaan;
(2) program perbaikan kampung (kampong
improvement programme), dimana berupaya meningkatan kualitas kawasan
perumahan dan permukiman diatas lahan yang memiliki status legal (sesuai
RTRW) yang secara fisik masih dimungkinkan untuk melakukan perbaikan
secara partial sehingga tidak harus melakukan perombakan yang mandasar
dan atau menggusur;
(3) rumah susun, dimana mempergunakan konsep
membangun tanpa menggusur dimana terdiri dari rumah susun sewa
sederhana dan rumah susun sederhana KPR;
(4) relokasi (Resettlement),
dimana merupakan proses pemindahan penduduk dari satu lokasi
permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang
disiapkan sesuai dengan rencana pembangunan kota;
(5) konsolidasi lahan
(land consolidation), dimana merupakan suatu model pembangunan yang
didasari oleh kebijakan pengaturan penguasaan lahan, penyesuaian
penggunaan lahan dengan Rencana Tata Guna Lahan atau Tata Ruang dan
pengadaan tanah;
(6) pembagian lahan (land sharing);
(7) pengembangan
lahan terarah (guide land development), dimana merupakan alternatif
penanganan pengendalian perkembangan daerah pinggiran yang
direncanakan untuk menampung kebutuhan perluasan daerah permukiman
atau kegiatan fungsional produktif lainnya.
Pembuatan suatu kebijakan publik hendaknya harus mampu
mengidentifikasikan tujuan kebijakan dan para aktor yang terlibat (siapa boleh
atau tidak boleh terlibat). Berbagai instrumen diperlukan untuk membuat
kebijakan-kebijakan tersebut dan membatasi aneka pilihan. Permasalahan
berbeda menggunakan instrumen yang berbeda pula (Howlett dan Ramesh :
1995 : 13). Pada prinsipnya aktor kebijakan yang berada pada organization
of state ataupun organization of society harus selalu terlibat dalam setiap
proses analisis kebijakan, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok
penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan
interrelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik.
Penyediaan pelayanan kesejahteraan seperti permukiman dilakukan
melalui seperangkat institusi dan instrumen yang kompleks dan beragam,
Ekonomi
Manajemen
You might also like
- Urban Planning TheoriesDocument6 pagesUrban Planning TheoriesVeeresh80% (5)
- Kebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban: DinamikaDocument17 pagesKebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban: DinamikaPutra RajaNo ratings yet
- Tugas Perkot Nuur Awaliyah 08161061Document8 pagesTugas Perkot Nuur Awaliyah 08161061liyaalfrzNo ratings yet
- Chapter 2. Literature Review: Urbanization - A Process of Transition of Urban AreasDocument42 pagesChapter 2. Literature Review: Urbanization - A Process of Transition of Urban AreasSARVESH NANDGIRIKARNo ratings yet
- The Role of The Architect in Slum Upgrading Practices - Karin Nord 4Document23 pagesThe Role of The Architect in Slum Upgrading Practices - Karin Nord 4Cami PetreNo ratings yet
- 1023 ArticleText 3563 1 10 20200629Document19 pages1023 ArticleText 3563 1 10 20200629Reza AlkautsaryNo ratings yet
- Unpacking Participation in Kathputli ColonyDocument9 pagesUnpacking Participation in Kathputli ColonydervishdancingNo ratings yet
- Sustainable Urban Futures: Urbanization in An Era of Globalization and Environmental ChangeDocument8 pagesSustainable Urban Futures: Urbanization in An Era of Globalization and Environmental ChangeAlma Rosa Mendoza CortésNo ratings yet
- Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 1 - Pebruari 2019Document17 pagesLocus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 1 - Pebruari 2019Gilang KrisnawanNo ratings yet
- Malvani Peoples Plan Summary PDFDocument3 pagesMalvani Peoples Plan Summary PDFAravind UnniNo ratings yet
- Sustainability 15 07248Document18 pagesSustainability 15 07248getawmekibebNo ratings yet
- Urbanismo ParticipativoDocument4 pagesUrbanismo ParticipativoEduardo HurtadoNo ratings yet
- Term Paper - Delos SantosDocument7 pagesTerm Paper - Delos SantosLigaya Delos SantosNo ratings yet
- Muhammad Anwar - BAB 1 John FriedmannDocument12 pagesMuhammad Anwar - BAB 1 John FriedmannMuhammad AnwarNo ratings yet
- The Concept of Spatial Planning and The Planning System (In The Book: Spatial Planning in Ghana, Chap 2)Document18 pagesThe Concept of Spatial Planning and The Planning System (In The Book: Spatial Planning in Ghana, Chap 2)gempita dwi utamiNo ratings yet
- RSW No. 6 - Javier, Danica T.Document33 pagesRSW No. 6 - Javier, Danica T.DaNica Tomboc JavierNo ratings yet
- Self Sustainable Township: Asst - Prof.Pad - Dr. D.Y.Patil College of Architecture, Akurdi - Pune, Maharashtra, IndiaDocument4 pagesSelf Sustainable Township: Asst - Prof.Pad - Dr. D.Y.Patil College of Architecture, Akurdi - Pune, Maharashtra, IndiaAbhijeetJangidNo ratings yet
- Metadata 11 03 02Document8 pagesMetadata 11 03 02SIOMARA MARIBEL JURADO GARCIANo ratings yet
- Summary of Urban Planning TheoryDocument13 pagesSummary of Urban Planning TheorymanishaNo ratings yet
- Prospek Peningkatan Kualitas Ruang Perumahan Dan Pemukiman Yang Berbasis Pada KomunitasDocument17 pagesProspek Peningkatan Kualitas Ruang Perumahan Dan Pemukiman Yang Berbasis Pada KomunitasMuhammad Arief Al HusainiNo ratings yet
- Improvement of Community Governance To Support Slum Upgrading Programs in IndonesiaDocument12 pagesImprovement of Community Governance To Support Slum Upgrading Programs in IndonesiaMade agungNo ratings yet
- Bowes ExploringInnovationinHousing 2018CFRDocument97 pagesBowes ExploringInnovationinHousing 2018CFRCecil SolomonNo ratings yet
- Cities For The Urban Poor in Zimbabwe Urban Space As A Resource For Sustainable Development OKDocument14 pagesCities For The Urban Poor in Zimbabwe Urban Space As A Resource For Sustainable Development OKNikos MarkoutsasNo ratings yet
- Smart and Sustainable Cities: The Main Guidelines of City Statute For Increasing The Intelligence of Brazilian CitiesDocument26 pagesSmart and Sustainable Cities: The Main Guidelines of City Statute For Increasing The Intelligence of Brazilian CitiesLovelyn Mae de LaraNo ratings yet
- Current Urban Planning ModelDocument3 pagesCurrent Urban Planning ModelSukhman ChawlaNo ratings yet
- Pengawasan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Ketersediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Kota Kudus (Studi Kasus Perumahan Bumi Rendeng Baru)Document10 pagesPengawasan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Ketersediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Kota Kudus (Studi Kasus Perumahan Bumi Rendeng Baru)indo sellerNo ratings yet
- Citizen Participation and Land Use Planning: (Focus in The City of San Juan)Document11 pagesCitizen Participation and Land Use Planning: (Focus in The City of San Juan)junNo ratings yet
- 4 Sustainable Planning Concepts at The Beginning of 21stDocument48 pages4 Sustainable Planning Concepts at The Beginning of 21stNeha SardaNo ratings yet
- Local Govt Administration: Current Issues in Local GovernmentDocument44 pagesLocal Govt Administration: Current Issues in Local GovernmentArimanthea LeeNo ratings yet
- Addresing The Challenges of UrbanizationDocument4 pagesAddresing The Challenges of UrbanizationRandalNo ratings yet
- Affordable Housingin DhakaDocument11 pagesAffordable Housingin DhakaAlNaeemNo ratings yet
- Konsep Perencanaan Permukiman Tepi Sungai Yang Berwawasan EkologiDocument6 pagesKonsep Perencanaan Permukiman Tepi Sungai Yang Berwawasan EkologiMyrabukitbatasNo ratings yet
- A-67-286 United Nations HabitatDocument52 pagesA-67-286 United Nations HabitatWellington MigliariNo ratings yet
- Tu and Zhang - 2023 - Land Use Change, Policy Dynamics and Urban GovernaDocument16 pagesTu and Zhang - 2023 - Land Use Change, Policy Dynamics and Urban Governachiyf0328No ratings yet
- Comprehensive PlanningDocument10 pagesComprehensive PlanningNaeem Akhtar SamoonNo ratings yet
- 5whose City Is It AnywayDocument27 pages5whose City Is It AnywayAbdullah ZubairNo ratings yet
- Course Title: Introduction To Urban: Institute of Land Administration Department of ArchitectureDocument120 pagesCourse Title: Introduction To Urban: Institute of Land Administration Department of ArchitectureMahiber KidussanNo ratings yet
- Lecture NotesDocument8 pagesLecture NotesPrinceNo ratings yet
- Sustainable ArchitectureDocument47 pagesSustainable ArchitecturePavithravasuNo ratings yet
- Housing Resilience and The Informal City: Paul JonesDocument11 pagesHousing Resilience and The Informal City: Paul JonesTSAMARANo ratings yet
- Urban DevelopmentDocument11 pagesUrban Developmentpaswanetakunda4ktNo ratings yet
- UNIT 1 Urban Housing PDFDocument68 pagesUNIT 1 Urban Housing PDFAnirudh VijayanNo ratings yet
- Access of Low Income People To Housing-KKB LahoreDocument12 pagesAccess of Low Income People To Housing-KKB LahoreObaidullah NadeemNo ratings yet
- Community Participation in Nature Conservation: The Chinese Experience and Its Implication To National Park ManagementDocument17 pagesCommunity Participation in Nature Conservation: The Chinese Experience and Its Implication To National Park ManagementIram AmmadNo ratings yet
- Marvin Critique 3Document4 pagesMarvin Critique 3edelyn joy reyesNo ratings yet
- Delhi Master PlanDocument40 pagesDelhi Master Plansubodh1984No ratings yet
- Atanu Chatterjee - PaperDocument25 pagesAtanu Chatterjee - PaperAtanuChatterjeeNo ratings yet
- Sahat Tulus Martua Silaban - 03061381722074Document63 pagesSahat Tulus Martua Silaban - 03061381722074Tulus Na JugulanNo ratings yet
- Rahel Worku FinalDocument74 pagesRahel Worku Finaltamerat bahtaNo ratings yet
- Literature Review On Urban Extension PlanningDocument17 pagesLiterature Review On Urban Extension PlanningAbicha Alemayehu100% (1)
- PDF of Culture X ArchitectureDocument7 pagesPDF of Culture X ArchitectureAnereeNo ratings yet
- Planning For Democracy in Protected Rural Areas: Application of A Voting Method in A Spanish - Portuguese ReserveDocument18 pagesPlanning For Democracy in Protected Rural Areas: Application of A Voting Method in A Spanish - Portuguese ReserveMónica De Castro PardoNo ratings yet
- Unit 5Document17 pagesUnit 5Honeylette MolinaNo ratings yet
- Reflection Report P4 Yiyi Lai 5327504Document5 pagesReflection Report P4 Yiyi Lai 5327504Sayali SaidNo ratings yet
- National Framework For Physical PlanningDocument15 pagesNational Framework For Physical PlanningDongzkie Vainkill100% (1)
- Urbanism As A Way o LifeDocument7 pagesUrbanism As A Way o LifedewarucciNo ratings yet
- Introduction To Urban PlanningDocument77 pagesIntroduction To Urban PlanningAMANUEL WORKUNo ratings yet
- Fundamentals of UrbanizationDocument98 pagesFundamentals of Urbanizationjudyachieng92No ratings yet
- Breaking the Development Log Jam: New Strategies for Building Community SupportFrom EverandBreaking the Development Log Jam: New Strategies for Building Community SupportNo ratings yet
- Peter GärdenforsDocument9 pagesPeter GärdenforsusamaknightNo ratings yet
- Social and Cultural Issues On GenderDocument25 pagesSocial and Cultural Issues On GenderKipi Waruku BinisutiNo ratings yet
- The Importance of Work-Life Balance On Employee Performance Millennial Generation in IndonesiaDocument6 pagesThe Importance of Work-Life Balance On Employee Performance Millennial Generation in IndonesiaChristianWiradendiNo ratings yet
- Resume Sample For TeenagerDocument6 pagesResume Sample For Teenagerafjwoovfsmmgff100% (2)
- TH 10 012Document10 pagesTH 10 012IAS CrackNo ratings yet
- Gas Flow in Pipeline NetworksDocument18 pagesGas Flow in Pipeline NetworksAbeer AbdullahNo ratings yet
- Principles of GeologyDocument10 pagesPrinciples of GeologyJoshuaB.SorianoNo ratings yet
- Understanding Feyerabend On GalileoDocument5 pagesUnderstanding Feyerabend On Galileorustycarmelina108No ratings yet
- BD F118S en WW - LDocument12 pagesBD F118S en WW - LyusufNo ratings yet
- Project 4Document6 pagesProject 4Trai TranNo ratings yet
- Pola Seismic Code CommentaryDocument15 pagesPola Seismic Code Commentary_ARCUL_100% (1)
- Problem Book in RelativityDocument25 pagesProblem Book in Relativitylinamohdzhor481520% (5)
- 1 (A) Derive The SI Base Unit of Force.: Test, Topic: MeasurementsDocument13 pages1 (A) Derive The SI Base Unit of Force.: Test, Topic: MeasurementsBilal RazaNo ratings yet
- FULL CycloCatalog Web 2 PDFDocument248 pagesFULL CycloCatalog Web 2 PDFprayogo1010No ratings yet
- Direção - Kia Picanto 2012Document16 pagesDireção - Kia Picanto 2012kiwel.01No ratings yet
- Covid 19 Notifiable PIDsr PDFDocument73 pagesCovid 19 Notifiable PIDsr PDFjheanniver nabloNo ratings yet
- Computer Assembly and DisassemblyDocument8 pagesComputer Assembly and DisassemblyPRECIOUS FAITH VILLANUEVANo ratings yet
- Best Rosin Press of 2020 PDFDocument4 pagesBest Rosin Press of 2020 PDFdannie gaoNo ratings yet
- General Physics Lesson 1 Methods of Electrostatic ChargingDocument46 pagesGeneral Physics Lesson 1 Methods of Electrostatic ChargingLeoj Levamor D. AgumbayNo ratings yet
- Roboti (E) 42Document8 pagesRoboti (E) 42pc100xohmNo ratings yet
- Shiloh Grant's Trail in The WestDocument37 pagesShiloh Grant's Trail in The Westremow50% (2)
- Achievement Report PDFDocument4 pagesAchievement Report PDFAnonymous IpBC61ZNo ratings yet
- WF Chapt1Document12 pagesWF Chapt1Shinmei KyoshiNo ratings yet
- Quality Control and Monitoring CONSTRUCTIONDocument38 pagesQuality Control and Monitoring CONSTRUCTIONcosmin_b100% (1)
- A Concept of Pilot Plant For Innovative Production of Ammonium FertilizersDocument6 pagesA Concept of Pilot Plant For Innovative Production of Ammonium FertilizersEndah SaraswatiNo ratings yet
- How To Calculate Paint QtyDocument2 pagesHow To Calculate Paint QtyVijay GaikwadNo ratings yet
- GK 2 Tieng Anh 9 (7N) 20 21Document6 pagesGK 2 Tieng Anh 9 (7N) 20 21SelenaNo ratings yet
- Chapter3 Electropneumatic UpdatedDocument60 pagesChapter3 Electropneumatic UpdatedViệt Đặng XuânNo ratings yet
- (Computer Science Project) To Generate Electricity Bill For Computer Science ProjectDocument33 pages(Computer Science Project) To Generate Electricity Bill For Computer Science ProjectHargur BediNo ratings yet