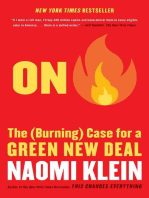Professional Documents
Culture Documents
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
31 viewsTeori Administrasi Dan Penerapannya Di Indonesia
Teori Administrasi Dan Penerapannya Di Indonesia
Uploaded by
sri wulanCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5822)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (852)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (823)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (403)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Etika Pembedahan ObstetriDocument17 pagesEtika Pembedahan Obstetrisri wulanNo ratings yet
- Upload JurnalDocument26 pagesUpload Jurnalsri wulanNo ratings yet
- Refarat Global Development Delay (GDD)Document17 pagesRefarat Global Development Delay (GDD)sri wulanNo ratings yet
- 1802 3939 1 PBDocument17 pages1802 3939 1 PBsri wulanNo ratings yet
- Guillain Barre Sindrom'Document37 pagesGuillain Barre Sindrom'sri wulanNo ratings yet
- Skripsi: Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Ilmu PemerintahanDocument159 pagesSkripsi: Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahansri wulanNo ratings yet
- 9 9 1 PB With Cover Page v2Document21 pages9 9 1 PB With Cover Page v2sri wulanNo ratings yet
- Isi Artikel 333261142398Document11 pagesIsi Artikel 333261142398sri wulanNo ratings yet
- 2015 Jurnal Tahun 2015Document192 pages2015 Jurnal Tahun 2015sri wulanNo ratings yet
- Makalah Semnas Fisip Ut 2012 Sub Tema: Birokrasi Dan Road Map Mdgs 2015 Di IndonesiaDocument16 pagesMakalah Semnas Fisip Ut 2012 Sub Tema: Birokrasi Dan Road Map Mdgs 2015 Di Indonesiasri wulanNo ratings yet
- Sri Wulan SNDocument9 pagesSri Wulan SNsri wulanNo ratings yet
- 6008-Full TextDocument100 pages6008-Full Textsri wulanNo ratings yet
- Hepatitis B NewDocument31 pagesHepatitis B Newsri wulanNo ratings yet
- Referat Tenia ImbrikataDocument18 pagesReferat Tenia Imbrikatasri wulanNo ratings yet
- Referat Demam TifoidDocument19 pagesReferat Demam Tifoidsri wulanNo ratings yet
- Lapsus DVT IsipDocument21 pagesLapsus DVT Isipsri wulanNo ratings yet
- TUTORIAL Anemia AplastikDocument21 pagesTUTORIAL Anemia Aplastiksri wulanNo ratings yet
- Kejang Demam KompleksDocument10 pagesKejang Demam Komplekssri wulanNo ratings yet
- PRINTTT REFARAT WULAN FixDocument54 pagesPRINTTT REFARAT WULAN Fixsri wulanNo ratings yet
- Formulir Penolakan Tindakan KedokteranDocument1 pageFormulir Penolakan Tindakan Kedokteransri wulanNo ratings yet
- SOP Identifikasi Nilai-NilaiDocument1 pageSOP Identifikasi Nilai-Nilaisri wulanNo ratings yet
- BasidiomycotaDocument9 pagesBasidiomycotasri wulanNo ratings yet
- Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)Document1 pageFormulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)sri wulanNo ratings yet
- 76040138-Referat-Fraktur-Pelvis EditDocument34 pages76040138-Referat-Fraktur-Pelvis Editsri wulanNo ratings yet
Teori Administrasi Dan Penerapannya Di Indonesia
Teori Administrasi Dan Penerapannya Di Indonesia
Uploaded by
sri wulan0 ratings0% found this document useful (0 votes)
31 views43 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
31 views43 pagesTeori Administrasi Dan Penerapannya Di Indonesia
Teori Administrasi Dan Penerapannya Di Indonesia
Uploaded by
sri wulanCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
You are on page 1of 43
AGUS DWIYANTO
TEORI
Os LSPA
PENERAPANNYA
DI INDONESIA
BAB 1
DIKOTOMI POLITIK DAN
ADMINISTRASI, IMPARSIALITAS,
DAN ETIKA NETRALITAS
PENDAHULUAN
Kontroversi tentang hubungan antara politik dengan administrasi tidak
pernah usai, walaupun isu tentang hal itu sudah sejak awal didiskusikan
oleh para pendiri Iimu Administrasi Publik. Wilson dan Godnow, generasi
pertama pemikir administrasi publik, mengingatkan perlunya pemisahan
politik dan administrasi, baik dalam tataran konsep maupun dalam praktik.
Kuatnya gagasan tentang pembagian kekuasaan negara ke dalam Trias
Politika amat berpengaruh terhadap pemikiran mereka tentang pemisahan
politik dan administrasi. Lebih dari itu, keinginan mereka untuk membangun
pemerintahan yang efisien, efektif, dan profesional dapat diwujudkan kalau
birokrasi dan aparatur sipil bebas dari intervensi para politisi. Walaupun
gagasan pemisahan politik dan administrasi dengan cepat memperoleh kritik
dari pemikir generasi kedua, seperti Waldo, Applebly, Simon, dan lainnya
sebagai hal yang mustahil dan tidak sesuai dengan realitas, tetapi dinamika
hubungan politik dan administrasi tidak pernah menurun. Para pemikir
administrasi publik mencoba memberi perspektif yang berbeda dalam
memahami dinamika hubungan antara politik dengan administrasi. Waldo,
misalnya, memahami hubungan politik dan administrasi dengan mencoba
menjelaskan hubungan antara birokrasi dengan demokrasi. Sementara itu,
Simon menggunakan metafora yang berbeda, dengan melihatnya sebagai
hubungan antara fakta dengan nilai, untuk menjelaskan hubungan antara
politik dengan administrasi.
Keterlibatan administrator dalam proses kebijakan, walaupun menjadi
realitas tak terbantahkan tetapi masih sering mengundang pertanyaan
tentang seberapa jauh administrator seharusnya terlibat dalam alokasi nilai
dan bagaimana pembagian kerjanya dengan para pejabat terpilih. Dalam
tataran praktik, perdebatan terjadi tentang bagaimana hubungan antara para
pejabat politik dengan para profesional, mereka yang menduduki jabatan
karena karier. Keinginan untuk memberi dukungan kepada para pejabat
politik terpilih untuk dapat mewujudkan visi dan janjinya ketika kampanye
menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh seorang pejabat terpilih dapat
melakukan intervensi pada birokrasinya untuk memastikan bahwa visi dan
janjinya selama kampanye benar-benar menjadi basis bagi birokrasi dalam
merumuskan program dan kegiatan pemerintah sehari-hari. Akan tetapi,
pada saat yang sama muncul juga pertanyaan tentang bagaimana mencegah
politisasi birokrasi dan pegawai aparatur sipil negara. Birokrasi dan aparatur
sipil negara dibentuk bukan untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan,
tetapi sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mereka harus
mengabdi pada nilai-nilai publik, bukan pada kepentingan politik sempit.
Walaupun tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut secara langsung, bab ini mencoba membahas berbagai aspek
dalam hubungan antara politik dengan administrasi, baik dalam tataran
konsepsual ataupun dalam praktik. Bab ini membahas pemikiran dikotomi
politik-administrasi, latar belakang, dan implikasi dari penerapan gagasan
untuk memisahkan politik dan administrasi. Bab ini juga membahas kritik
yang telah disampaikan oleh banyak pemikir administrasi publik terhadap
gagasan untuk memisahkan politik dengan administrasi. Generasi kedua
pemikir administrasi publik umumnya menganggap hubungan politik dan
administrasi tidak saling menegasikan, tetapi saling melengkapi. Oleh karena
itu, mereka mencoba mengembangkan pemikiran untuk mengintegrasikan
proses politik dan administrasi sebagai satu kegiatan dalam proses
kebijakan. Pejabat politik dan pejabat karier keduanya terlibat dalam proses
kebijakan. Yang membedakan keduanya dalam proses kebijakan adalah jenis
keterlibatan dan intensitasnya.
Sebagai konsekuensi dari pemikiran bahwa para pejabat politik
dan karier keduanya terlibat dalam proses kebijakan, penulis menentang
gagasan untuk mengembangkan etika netralitas. Administrator tidak
netral dan tidak boleh netral dalam proses kebijakan. Politik administrator
adalah politik kepublikan, bukan politik kekuasaan. Mereka terlibat
dalam proses alokasi nilai melalui proses kebijakan. Oleh karena itu,
mereka harus ikut bertanggung jawab terhadap tindakan dan dampak dari
tindakan yang dilakukannya dalam proses kebijakan. Posisi ini penting
untuk ditegaskan jika ingin membuat para pejabat karier dan administrator
menjadi sensitif terhadap kekuasaan yang dimilikinya dan berhati-hati dalam
menggunakan kekuasaannya untuk mengambil diskresi. Bab ini membahas
secara mendalam keterlibatan administrator dalam proses kebijakan dan
implikasinya terhadap gagasan untuk mengembangkan etika netralitas.
Bab ini juga membahas perlunya administrator bertindak imparsial
terhadap politik praktis dan politik kekuasaan. Walaupun administrator
terlibat dalam proses kebijakan, mereka harus imparsial ketika berhadapan
dengan kepentingan kekuasaan. Kepentingan administrator adalah
memperjuangkan nilai-nilai publik dan menjadikannya sebagai basis dalam
mengelola proses kebijakan. Kepentingan untuk memperjuangkan nilai-
nilai publik dengan kepentingan kekuasaan tidak selalu berjalan bersama-
sama. Konflik antarkeduanya sering tidak terhindarkan. Penulis dalam
bab ini menjelaskan bagaimana seharusnya administrator bertindak ketika
keyakinannya tentang nilai-nilai publik berbeda dengan pilihan politik
pimpinannya, yang notabene adalah pejabat terpilih yang memiliki mandat
untuk membuat kebijakan publik. Dengan membaca bab ini diharapkan
para pembaca dapat memahami kompleksitas hubungan antara politik
dengan administrasi dan dinamika yang terjadi dalam hubungan antara
para pejabat politik dengan para pejabat karier.
KONSEP DIKOTOMI POLITIK DAN ADMINISTRASI
Pemikiran tentang pemisahan politik dengan administrasi sudah lama
berkembang dalam kajian administrasi publik. Bahkan, gagasan tersebut
sudah disampaikan oleh generasi pertama pemikir administrasi publik,
seperti Wodrow Wilson, Goodnow, dan Weber. Kebanyakan pustaka yang
terbit sebelum era perang dunia kedua, umumnya sangat peduli dengan
keinginan untuk menjaga agar administrasi jauh dari hiruk-pikuk kegiatan
politik. Bahkan, sejak awal sejarah kelahiran ilmu administrasi publik,
Kotak 1.1.
Dinamika Pemikiran tentang
Hubungan antara Politik
dengan Administrasi
Generasi pertama pemikir
administrasi publik di era
sebelum perang dunia kedua,
seperti Wilson, Goodnow,
dan Weber mendorong
pemisahan kegiatan politik
dan administrasi. Di samping
sesuai dengan tradisi Trias,
Politika yang sangat kuat di
AS, pemisahan politik dan
administrasi juga merespons
kekhawatiran mereka terhadap
politisasi birokrasi di Eropa
dan AS pada waktu itu. Namun
; . Jabatan publik karena karier,
diinginkan? Apakah mungkin memisahkan_ | {2yiny?don rors kone
politik dengan administrasi, dan mencegah | Pandangannya tentang masalah
publik sering dipengaruhi oleh
pengalaman, tacit knowledge,
Jain. Undang Undang Aparatur sipil Negara _ | nilai, dan keyakinan profesinya.
A Orientasi politik administrator
No. 5 Tahun 2014 juga berusaha mencegah | [isin porte kepubiven,
politisasi birokrasi dengan membatasi ruang_ | yaitu memperjuangkan
. - a ; terwujudnya nilai dan
bagi para pejabat politik untuk terlalu jauh RevenincanttCneaaiary
masuk dalam arena birokrasi. Upaya itu | proses kebijakan. Perbedaan
. - . pandangan antarkeduanya
dilakukan dengan memindahkan jabatan_| Bayeengen crranees
pembina kepegawaian dari para pejabat | publik adalah wajar dan tak
politik. Akan tetapi, hal itu ternyata gagal | ‘thindarkan.
keduanya saling mengintervensi satu sama
13
dilakukan karena memperoleh resistansi yang kuat dari para politisi. Mereka
menganggap bahwa depolitisasi birokrasi dan aparaturnya akan membuat
para pejabat politik kehilangan pengaruh dan otoritas untuk menggerakkan
birokrasi dan aparaturnya untuk memenuhi mandat dan aspirasi politik dari
konstituennya. Apa yang diatur dalam UU ASN adalah mengharuskan
pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan
berdasarkan prinsip merit. Walaupun pelaksanaannya belum seperti yang
diharapkan tetapi sebagai salah satu cara mencegah politisasi birokrasi hal
itu penting dilakukan.
Amat sulit membayangkan para pejabat karier di Indonesia akan
mengundurkan diri dari jabatannya ketika mereka memiliki pandangan
yang berbeda tentang “what is good for the people”. Administrator tentu sah
memiliki pendapat mengenai yang seharusnya dilakukan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pengalaman, tacit knowledge yang
dimiliki, dan keyakinannya sebagai pemegang profesi dapat memberikan
petunjuk pada mereka tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk
memperjuangkan kepentingan publik. Apa yang diyakininya mungkin
berbeda dengan yang ingin dilakukan oleh para pejabat politik, seperti
gubernur, bupati, dan wali kota. Para pejabat politik mungkin terikat dengan
janjinya terhadap konstituennya. Mereka tentu ingin membalas dukungan
konstituen dengan proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur dan
sebagainya. Pertimbangan pejabat politik dalam alokasi dan distribusi proyek
pembangunan mungkin berbeda dengan yang dimiliki oleh administrator
sebagai pejabat karier. Pejabat politik lebih memperhatikan kepentingan
konstituen, sementara pejabat karier mungkin melihatnya dari perspektif
yang luas dari kepentingan warga secara keseluruhan. Mereka dapat berbeda
pendapat tentang sarana dan prasarana yang harus dibangun serta lokasinya.
Jika terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan, tentu
administrator harus patuh pada keputusan para pejabat politik, walaupun
dari kacamatanya mungkin pilihan tersebut tidak tepat. Namun demikian,
pertanyaannya apakah administrator tersebut dengan ikhlas dan sepenuh hati
melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan semangat yang dimiliki para
pejabat politik. Apakah mereka menyadari bahwa dalam politik kompensasi
pada konstituen adalah wajar adanya, bahkan ketika hal tersebut ditempatkan
di atas kepentingan publik secara keseluruhan? Jika tidak sepakat dan
14
tidak dapat menerima maka mereka akan berhenti dari jabatannya. Tentu
amat sulit membayangkan hal tersebut akan terjadi di Indonesia. Jabatan
struktural bagi seorang pejabat karier sangat penting dan mereka berjuang
dengan keras untuk dapat mendudukinya, tentu tidak mungkin mereka
akan meninggalkannya karena tidak sepakat dengan keputusan politik yang
diambil pimpinan.
Jika mereka tidak mundur, sebagaimana pengalaman yang terjadi di
negara-negara Barat pada masa lalu, tentu mereka juga memiliki banyak
cara dan kesempatan untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap
kebijakan yang diambil pejabat politik, apalagi jika peraturan dan UU
melindunginya dari intervensi politik. Jika mereka tahu bahwa apa pun
yang dilakukan untuk mengganggu pelaksanaan kebijakan yang dinilai
tidak adil dan tidak sesuai dengan keyakinan profesinya mereka tidak
dapat diberhentikan dari jabatannya maka peluang para administrator
untuk mengganggu pelaksanaan kebijakan sangat terbuka luas. Apakah
dalam situasi seperti ini pejabat politik tidak dapat mengintervensi proses
administrasi?
Mencegah intervensi politik dalam proses administrasi karena banyak
alasan sebenarnya tidak masuk akal, apalagi ketika dikotomi politik-
administrasi menempatkan proses politik sebagai superior daripada proses
administrasi, mencegah para politisi untuk tidak mengintervensi proses
administrasi adalah hal yang mustahil dilakukan. Para politisi yang tidak
sabar dan/atau melihat ada yang salah dalam implementasi akan selalu
gatal tangannya untuk tidak melakukan intervensi. Intervensi politik dalam
administrasi dalam beberapa hal wajar dan dapat dijustifikasi karena nasib
politisi juga ditentukan oleh kualitas dari proses administrasi.
Dari sisi administrator juga amat sulit mencegah mereka untuk tidak
terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai pelaksana kebijakan
tentu mereka yang paling tahu tentang kesulitan dalam memastikan bahwa
kebijakan yang diambil para pejabat politik dapat berjalan dengan baik.
Seandainya mereka sepakat dengan pilihan politik dari pimpinannya dan
peduli dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan mereka menyadari
bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki dari kebijakan, apakah mereka
akan membiarkannya? Jika mereka melaporkan kepada pimpinan dan
menyarankan akan perlunya perubahan-perubahan dalam kebijakan, apakah
15
hal itu bukan berarti intervensi terhadap keputusan politik? Jika pimpinannya
sepakat dengan pemikirannya, untuk melakukan perubahan terhadap
keputusan dan kebijakan yang telah diambilnya, apakah hal itu bukan berarti
para administrator tersebut juga terlibat dalam proses kebijakan publik?
Jika kita melihat realitas bahwa pejabat karier sering kali lebih
menguasai informasi daripada para pejabat politik karena pekerjaaan,
pengalaman, dan keahliannya. Pejabat karier memiliki informasi tentang
besaran anggaran, alokasi, dan distribusinya yang amat penting dalam
pengambilan keputusan politik. Mereka memonopoli informasi tentang
kapasitas supply of services dari pemerintahnya. Bahkan, tidak jarang karena
birokrasi juga memiliki mekanisme untuk menjaring informasi tentang
demand for services dari warganya, mereka juga memiliki informasi tentang
kebutuhan warga, jenisnya, dan lokasinya. Informasi yang dimiliki oleh
administrator mungkin tidak kalah lengkap dan canggih dari yang dimiliki
oleh para pejabat politik yang bersumber dari konstituennya. Bagaimana
mencegah mereka untuk tidak terlibat dalam proses kebijakan kalau mereka
menguasai dan/atau bahkan memonopoli informasi tentang “supply dan
demand for services”. Bukankah informasi adalah bahan baku utama dari
proses kebijakan publik?
Oleh karena itu, amat sulit membayangkan bahwa proses pembuatan
kebijakan dapat mencegah keterlibatan para pejabat karier dari setiap
tahap proses pembuatan kebijakan publik. Dari sejak perumusan agenda,
pengambilan pilihan tindakan, alokasi anggaran, hingga pelaksanaan dan
evaluasi kebijakan, peluang bagi adminisrator untuk terlibat dalam proses itu
sangat besar. Para pejabat politik tidak mungkin dapat mencegah keterlibatan
administrator, bahkan dalam tingkat tertentu mereka membutuhkan
keterlibatan administrator untuk membantunya dalam mengambil pilihan-
pilihan yang tepat dan sesuai dengan visi politiknya, Bahkan, dalam praktik
yang terjadi sering kali proses kebijakan didominasi oleh keterlibatan
administrator, Dapur dari keseluruhan proses kebijakan adalah urusan
administrator, peran utama para pejabat politik adalah pada pemberian
legitimasi dari keputusan yang diambil. Bahan baku dari keputusan disiapkan
oleh para administrator, tetapi keputusan diambil oleh para pejabat politik.
Jika realitas yang terjadi seperti digambarkan di atas, apa relevansinya
dikotomi politik-administrasi? Mengapa para akademisi dan praktisi pada
16
waktu itu sangat getol untuk memisahkan politik dengan administrasi? Apa
asumsi yang mereka miliki sehingga mereka menggagas pemikiran untuk
memisahkan politik dengan administrasi? Bahkan, pemisahan tersebut
dilakukan bukan hanya ada pada tingkat pemikiran, tetapi juga coba
diwujudkan dalam praktik.
KRITIKTERHADAP DIKOTOMI POLITIK-ADMINISTRASI
Tentu menarik untuk mengkaji asumsi-asumsi yang mendasari perlunya
melakukan dikotomi politik-administrasi. Walaupun dalam praktik terbukti
sulit memisahkan praktik politik dengan praktik administrasi tetapi sejarah
perjalanan ilmu administrasi publik mencatat bahwa gagasan pemisahan
tersebut sempat sangat berpengaruh dalam pengembangan teori dan praktik
adminstrasi publik. Bahkan, di negara-negara Barat dikotomi politik-
administrasi pernah diperlakukan sebagai salah satu paradigma dalam
ilmu adminstrasi publik. Diskusi penting untuk melihat apakah secara
pemikiran dikotomi politik-administrasi masuk akal dan perlu dielaborasi
kemungkinannya untuk diimplementasikan. Kegagalan implementasi tidak
selalu harus menggugurkan rasionalias dari gagasan tentang pemisahan
politik dan administrasi. Untuk mengkaji rasionalitas dari pemikiran
tersebut, berikut akan coba didiskusikan asumsi dan latar belakang dari
pemikiran dikotomi politik-administrasi.
Salah satu asumsi yang penting dari pemikiran dikotomi politik
administrasi adalah bahwa proses politik akan dapat menghasilkan kebijakan
pemerintah yang tegas, jelas, dan rinci sehingga tidak bisa dan tidak perlu
diterjemahkan kembali oleh para administrator sebagai agen pelaksana. Para
administrator tidak perlu dan tidak boleh memberi interpretasi terhadap isi
kebijakan karena tugas mereka hanya melaksanakan apa pun kebijakan
yang telah diambil oleh proses politik sesuai dengan semangat yang dimiliki
oleh para politisi itu. Administrator di sini ditempatkan sebagai robot atau
malaikat yang tidak memiliki kepentingan dan selalu patuh terhadap apa
pun yang diinginkan oleh para pengambil kebijakan.
Pertanyaannya, apakah asumsi tersebut masuk akal dan didukung
oleh realitas? Pertama, apakah mungkin proses kebijakan publik
menghasilkan kebijakan yang jelas, tegas, dan rinci sehingga tidak dapat
17
dan tidak perlu diinterpretasi kembali
1 2 A Kotak 1
oleh pelaksananya? Untuk menjawab | gag eeettn sikotom!
pertanyaan tersebut mungkin perlu dilihat Politik-Administrasi
pengalaman proses kebijakan publik yang. perran, sonatas trates
terjadi di Indonesia selama ini maupun | tidak memungkinkan proses
- gara-negara mai . kebijakan menghasilkan
yang terjadi di negara-negara maju di Barat. Pe seaiererclesrtion
Pengalaman selalu menunjukkan bahwa_ | Selalu ada kebutuhan bagi
F F birokrat untuk mengambil
proses kebijakan publik hampir selalu_ | vovtat wus oungen
menghasilkan kebijakan yang tidak jelas dan | dapat diimplementasikan.
Kedua, kapasitas mengambil
konsensus yang terbatas
yang berbeda sehingga menyisakan ruang | selalu menghasilkan kebijakan
Sadan A yang ambigu. Kebijakan
bagi administrator sebagai agen pelaksana ae tee el earey
untuk memberi interpretasi sesuai dengan | bagi pemangku kepentingan
. . ti dan agen pelaksana untuk
sistem nilai dan kognitifnya. memberi interpretasi berbeda-
Proses kebijakan adalah proses | beda terhadap nilai dan tujuan
oa . a ak. | Kebliakan. Ketiga, politik dan
politik dan selalu melibatkan tarik-menarik | i inictrasi adalah Feciseay
kepentingan antaraktor dan pemangku | yang saling melengkapi,
A bukan saling menegasikan.
kepentingan yang berbeda. Para aktor | yuansiy'g mencausk
dan pemangku kepentingan tentu akan | administrasi adalah hal yang
melakukan berbagai upaya untuk | ™#*hildilakukan.
memastikan bahwa kebijakan yang diambil
akan mengakomodasi kepentingannya.
akomodatif terhadap berbagai kepentingan
Mereka menyadari bahwa pilihan kebijakan yang diambil selalu
mendistribusikan manfaat dan kerugian kepada aktor dan pemangku
kepentingan yang berbeda. Apa yang menjadi manfaat bagi satu kelompok
dapat menjadi kerugian bagi kelompok lainnya. Proses kebijakan selalu
berusaha untuk mengambil jalan tengah dengan mencoba mengakomodasi
kepentingan yang berbeda-beda agar dukungan dan kepemilikan kebijakan
tersebut menjadi semakin luas.
Membayangkan proses kebijakan mampu menghasilkan pilihan yang
jelas, tegas, dan tidak dapat diinterpretasi secara berbeda oleh agen pelaksana
dalam realitas politik amat sulit diwujudkan, apalagi dalam masyarakat
yang pluralistis, seperti yang terjadi di Indonesia, bisa dikatakan proses
kebijakan tidak mungkin menghasilkan pilihan kebijakan yang jelas, tegas,
dan rinci karena untuk memperoleh kebijakan yang seperti ini diperlukan
18
konsensus politik yang sulit diwujudkan. Semakin jelas dan tegas pilihan
kebijakan semakin jelas pula distribusi manfaat dan kerugian dari pilihan
kebijakan tersebut. Semua aktor dan pemangku kepentingan dengan mudah
melihat posisinya dalam kebijakan tersebut, apakah mereka termasuk dalam
kelompok yang menerima manfaat atau sebaliknya, mereka termasuk dalam
kelompok yang dirugikan dan harus membayar ongkos dari kebijakan itu.
Dalam situasi tersebut maka proses kebijakan akan menjadi semakin
sulit untuk dikelola. Semakin jelas dan tegas distribusi manfaat dan kerugian,
semakin sulit konsensus dapat dicapai. Jika konsensus tidak dapat dicapai
maka resistansi akan semakin besar dan penolakan terhadap kebijakan yang
dirancang para pejabat politik akan menjadi semakin meluas. Jika hal ini
terjadi maka legitimasi dari pejabat politik juga akan tergerus dan mereka
juga dapat kehilangan kepercayaan dari konstituen dan warganya.
Kesulitan dalam mencapai konsensus ketika membuat kebijakan yang
jelas dan tegas menyebabkan para pejabat politik sering kali harus membuka
ruang untuk diskusi dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang
berbeda. Dalam realitas, proses kebijakan publik selalu mengakomodasi
pro dan kontra dari pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Mengelola
proses kebijakan adalah seni mengelola kompromi dari berbagai kepentingan
yang berbeda dalam rangka memperluas konsensus dan dukungan terhadap
kebijakan. Pilihan kebijakan yang diambil sering kali menggambarkan
optimalitas kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang
berbeda. Optimalitas sering dapat dicapai ketika kebijakan yang diambil
memberi peluang pada para pemangku kepentingan yang berbeda untuk
memberi penafsiran secara luas dan terbuka. Semakin terbuka dan luas
penafsiran yang dapat dibuat, semakin besar kemungkinan kebijakan itu
mengakomodasi kepentingannya.
Optimalitas kompromi dan dukungan pemangku kepentingan selalu
bergerak secara diametral dengan keinginan untuk menghasilkan kebijakan
yang rinci dan jelas. Proses politik sering membiarkan proses kebijakan
menghasilkan kebijakan yang ambigu dan memiliki makna ganda sehingga
bisa ditafsirkan secara berbeda-beda oleh pemangku kepentingannya.
Dengan cara ini, proses kebijakan publik dapat mengakomodasi kepentingan
para pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Akan tetapi, akibatnya
19
proses kebijakan selalu menyisakan ruang bagi agen pelaksana untuk
memberi interpretasi terhadap isi kebijakan.
Kesulitan merumuskan kebijakan publik yang tegas, rinci, dan jelas
juga muncul karena keterbatasan kemampuan memproduksi informasi yang
sempurna. Simon (1947) berpendapat bahwa manusia tidak akan pernah
mampu memprediksi masa depan secara sempurna karena mereka tidak
pernah mampu memproduksi informasi yang sempurna. Ia mengembangkan
konsep rasionalitas terbatas (bounded rationality). Aktor-aktor kebijakan
yang memiliki rasionalitas yang terbatas jelas tidak bisa diharapkan untuk
bisa menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab masa depan dengan
sempurna, Para pejabat politik tidak akan mampu memprediksi masa depan
dengan sempurna dan menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh
administrator untuk merespons setiap kontingensi yang mungkin terjadi.
Para pejabat politik tidak akan mampu merinci yang akan terjadi pada
masa mendatang, tindakan yang harus dilakukan oleh seorang administrator
untuk menjawab setiap kemungkinan yang terjadi pada masa mendatang.
Tidak mungkin proses kebijakan dapat merespons semua kemungkinan yang
terjadi. Oleh karena kebijakan publik tidak pernah mampu mengantisipasi
dan menjawab masa depan dengan sempurna, maka setiap kebijakan akan
selalu menyisakan ruang bagi para pelaksana untuk mengambil diskresi
ketika kebijakan tidak mengatur apa yang harus dilakukannya. Diskresi
dalam pengelolaan kebijakan adalah kenyataan yang tak terhindarkan.
Seorang pejabat karier harus mampu mengkompromikan kebijakan
publik dengan realitas sosial dan politik yang ada di lingkungannya ketika
harus mengambil diskresi mereka. Nilai dan semangat yang terkandung
dalam kebijakan publik tentu harus menjadi acuan dari diskresi yang akan
diambilnya. Akan tetapi, ketika kondisi yang berlaku tidak memungkinkan
untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana adanya maka diskresi harus
diambil untuk memastikan bahwa pemerintah dapat merespons problem
yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dengan cepat dan tepat. Ketika
seorang administrator mengambil diskresi tentu tidak dapat menghindari
bahwa sistem nilai, pengetahuan, dan pengalaman bahkan kepentingan
pribadi dan kelompoknya, yang secara langsung atau tidak langsung akan
memengaruhi tindakan yang diambilnya. Dalam konteks ini sebenarnya
20
mencegah keterlibatan administrator dalam proses kebijakan amat sulit
dilakukan.
Di samping melalui diskresi, keterlibatan administrator dalam proses
kebijakan juga mungkin terjadi melalui interpretasinya terhadap isi dan
substansi kebijakan. Dalam situasi ketika kebijakan publik bersifat ambigu
dan memberi kemungkinan terjadinya makna ganda, administrator sering
memiliki ruang yang memadai untuk melakukan interpretasi terhadap isi
kebijakan. Mereka memiliki peluang untuk menerjemahkan kebijakan publik
yang ambigu tersebut menurut sistem nilai, predisposisi, pengetahuan, dan
pengalamannya. Tidak jarang interpretasi yang diberikan oleh administrator
terhadap isi dari satu kebijakan publik berbeda dengan semangat yang
dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Akibatnya, sering kali muncul
gap antara kebijakan (policy in theory) yang dihasilkan oleh proses
politik dengan kebijakan atau diskresi (policy in use) yang diambil oleh
administrator. Dalam situasi seperti ini, sering terjadi pergeseran kebijakan,
bahkan penggusuran kebijakan karena kebijakan yang dihasilkan oleh
proses politik dan dibuat oleh para politisi dalam lembaga-lembaga politik
kemudian digeser dan digusur oleh diskresi yang dibuat oleh administrator
sebagai agen pelaksana.
Kalau pergeseran atau penggusuran kebijakan terjadi maka kebijakan
yang nantinya diimplementasikan adalah kebijakan yang dihasilkan oleh
proses administrasi, bukan yang dihasilkan oleh proses politik. Akibatnya,
kebijakan yang memengaruhi nasib rakyat adalah kebijakan birokrasi, bukan
kebijakan yang dirumuskan melalui proses politik oleh para pejabat politik.
Nasib rakyat tidak ditentukan oleh keputusan yang diambil oleh pihak yang
dipercaya dan memperoleh mandat dari rakyat, tetapi justru ditentukan oleh
para administrator, yang notabene tidak memiliki mandat untuk mewakili
kepentingannya. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menjadi pembuat
kebijakan, para pejabat politik atau para pejabat karier?
Asumsi kedua dari pemikiran dikotomi politik-administrasi adalah
tentang penguasaan informasi. Proses politik yang intens membuat para
pejabat terpilih memiliki informasi tentang demand for services. Mereka
memahami kemauan para pemilihnya serta proses politik dan birokrasi
akan dapat membantunya menerjemahkan kemauan pemilih dalam berbagai
tindakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Akan tetapi,
21
dalam praktik sering kali proses politik yang intens tidak terjadi. Pejabat
politik hanya mengunjungi warganya ketika membutuhkan suaranya.
Tidak ada hubungan emosional yang kuat antara pejabat politik dengan
konstituennya. Akibatnya, pemahaman mereka tentang aspirasi dan
kebutuhan warga sering kali amat terbatas.
Sementara itu, proses teknokrasi dan birokrasi dalam perencanaan
kegiatan dan pembuatan kebijakan sering tidak dapat dikontrol sepenuhnya
oleh para pejabat terpilih. Pork-barell budget atau dana aspirasi sebagai
salah satu instrumen untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan konstituen
dalam penerapannya sering menciptakan problem baru karena cenderung
menjadi arena korupsi di antara pejabat politik, pengusaha, dan birokrat.
Proses penganggaran yang berlaku juga sering memberi peluang kepada
administrator untuk memengaruhi keputusan tentang alokasi anggaran.
Administrator cenderung memiliki informasi tentang anggaran yang lebih
banyak dari yang dimiliki pejabat politik.
Ketika terjadi asimetri informasi, di mana para administrator menguasai
informasi, baik tentang kapasitas pemerintah maupun kebutuhan warga,
maka amat sulit bagi para pejabat politik untuk dapat mengendalikan proses
kebijakan agar sepenuhnya memperjuangkan aspirasi politiknya. Yang
sering terjadi justru sebaliknya, mereka harus mengkompromikan aspirasi
politik dan konstituen dengan proses teknokrasi dan birokrasi yang ada di
bawah kendali administrator. Dalam situasi ketidakseimbangan informasi
yang lebih menguntungkan birokrasi, maka menjadi sangat tidak mungkin
mencegah birokrasi untuk terlibat dalam proses kebijakan.
Dari diskusi ini tampak bahwa ketika asumsi tentang penguasaan
informasi yang dimiliki oleh para pejabat politik tidak terpenuhi amat sulit
mencegah keterlibatan administrator dalam proses kebijakan. Apalagi jika
realitas menunjukkan terjadi asimetri informasi, di mana birokrasi justru
lebih menguasai informasi daripada para pejabat politik maka dikotomi
politik-administrasi menjadi kehilangan basis rasionalitasnya.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemikiran dikotomi politik-
administrasi yang ingin memisahkan proses politik dan administrasi
sebenarnya tidak masuk akal. Mencegah keterlibatan administrator dalam
proses kebijakan sama sekali bukan hanya sulit, tetapi hampir tidak mungkin
dilakukan. Sebaliknya, mencegah para politisi tidak mengintervensi proses
22
pelaksanaan kebijakan publik juga tidak mungkin dilakukan. Para pejabat
politik yang harus mempertanggungjawabkan kebijakannya pada warga
dan konstituennya tidak akan rela membiarkan kebijakannya digusur
oleh diskresi yang diambil para agen pelaksananya. Para pejabat politik
sering kali harus melakukan intervensi dalam proses implementasi untuk
memastikan bahwa para pejabat birokrasi melaksanakan kebijakan sesuai
dengan semangat yang dimilikinya. Fenomena seperti ini menunjukkan
bahwa keinginan untuk memisahkan proses politik dan administrasi adalah
suatu kemustahilan.
Asumsi lainnya yang perlu dikritisi dari pemikiran dikotomi
politik- administrasi adalah persepsinya bahwa kedua kegiatan politik
dan administrasi berbeda secara jenis. Walaupun tampaknya masuk akal
memisahkan kegiatan perumusan tujuan negara dengan pelaksanaannya,
dalam realitas keduanya memiliki sisi yang saling tumpang-tindih, baik
dilihat dari sifat kegiatannya maupun dari pelakunya. Proses pembuatan
kebijakan melibatkan begitu banyak kegiatan, dari sejak menentukan tujuan
yang akan dicapai dan merumuskan masalah kebijakan sampai pengambil
keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan, Ada begitu banyak kegiatan
yang harus dilakukan, tidak semuanya ada di bawah kompetensi dari para
pejabat politik. Ada kalanya kompetensi justru lebih banyak dikuasai oleh
para administrator. Keseluruhan proses kebijakan tersebut tidak semuanya
melibatkan kegiatan yang sepenuhnya bersifat politik, tetapi juga melibatkan
kegiatan teknokratis dan birokratis. Oleh karena itu, walaupun pada dasarnya
proses pembuatan kebijakan adalah kegiatan politik, tetapi di dalamnya
terkandung banyak kegiatan teknokratis dan administratif.
Dengan demikian, sebenarnya klaim bahwa kegiatan politik dan
administrasi berbeda secara jenis adalah pemikiran yang keliru. Keduanya
berbeda lebih pada intensitas. Kegiatan pembuatan kebijakan memiliki
intensitas kegiatan politik yang tinggi, sementara kegiatan pelaksanaan
kebijakan memiliki intensitas politik yang rendah. Keduanya dapat
ditempatkan dalam satu kontinum dan sulit untuk diposisikan berbeda secara
kategorikal. Pelaksanaan kebijakan juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan
politik karena hal itu terkait dengan akuntabilitas dari para pejabat politik.
Implementasi kebijakan yang buruk dapat menurunkan kredibilitas dan
kepercayaan warga kepada pejabat politik. Kepercayaan dan akuntabilitas
23
publik dari para pejabat politik memengaruhi elektabilitasnya. Oleh karena
itu, wajar kalau mereka diberi ruang untuk memastikan bahwa implementasi
kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan yang diharapkannya.
DIKOTOMI POLITIK-ADMINISTRASI DAN NETRALITAS,
Konsep dikotomi politik-administrasi sering dikaitkan dengan konsep
netralitas birokrasi. Isu netralitas sudah lama menjadi perdebatan di kalangan
para praktisi dan akademisi administrasi publik. Bahkan, perdebatan
tersebut terjadi sejak awal sejarah perkembangan ilmu adminisrasi publik.
Akan tetapi, perdebatan di kalangan para akademisi dan awam tentang
netralitas administrator cenderung memiliki isu yang berbeda dan jika
tidak diklarifikasi hal tersebut dapat menyesatkan. Pertama, netralitas
administrator dan birokrasi sebagaimana diperdebatkan dalam dikotomi
politik administrasi itu terkait dengan pro dan kontra tentang keterlibatan
administrator dalam pengambilan keputusan politik. Pertanyaannya,
sebagaimana telah didiskusi di bagian sebelumnya, apakah administrator
terlibat dalam proses pembuatan kebijakan? Apakah administrator terlibat
dalam alokasi nilai? Bukankah alokasi nilai mestinya menjadi hak mereka
yang memperoleh mandat dari rakyat, yaitu para pejabat politik, yang dipilih
oleh rakyat? Pejabat karier karena tidak memperoleh mandat dari rakyat,
mereka tidak seharusnya terlibat dalam alokasi nilai.
Isu netralitas kedua dikaitkan dengan sikap dan perilaku administrator
dalam politik praktis. Meluasnya politisasi birokrasi di Barat pada
waktu itu membuat banyak pihak khawatir dengan dampak negatif dari
politisasi birokrasi terhadap kemampuan pemerintah melayani warganya
secara adil dan imparsial, terbebas dari afiliasi politik administrator dan
warganya. Politisasi birokrasi cenderung membuat keputusan dan tindakan
administrator tidak imparsial, tetapi dipengaruhi oleh kesamaan afiliasi
politik dari rezim pelayanan.
Walaupun isu imparsialitas dari tindakan administrator ini berkaitan
dengan isu netralitas dalam pengambilan keputusan, tetapi kesimpangsiuran
dalam memahami kedua isu netralitas tersebut dapat menyesatkan. Oleh
karena itu, dalam bagian ini saya merasa perlu membahas secara terpisah
agar para mahasiswa dan akademisi dapat menempatkan perdebatan tentang
24
kedua isu tersebut secara pas. Seorang administrator tidak boleh netral dan
sebaiknya terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada isu netralitas
yang pertama. Akan tetapi, pada isu netralitas kedua berpendapat bahwa
sebaiknya administrator netral dari kepentingan politik praktis. Kepentingan
politik administrator adalah kepentingan untuk mewujudkan keadilan sosial
dan kesejahteraan warganya. Administrator tidak boleh terlibat dalam
upaya seseorang dan bahkan dirinya sendiri dalam memperoleh dan/atau
mempertahankan kekuasaan.
Isu yang pertama adalah tentang proses kebijakan, yang dalam
pustaka sering disebut sebagai policy. Dalam konteks ini, administrator
seharusnya tidak boleh netral, tetapi terlibat dalam proses kebijakan untuk
ikut memengaruhi agar proses kebijakan berpihak pada kepentingan dan
nilai-nilai publik, bukan kepentingan partikularistik, sempit, kelompok,
dan partisan. Politik administrator adalah politik kepublikan, bukan politik
partisan. Oleh karena itu, dalam isu kedua, administrator seharusnya
imparsial. Mereka harus netral dan tidak berpihak kepada politik kekuasaan
dan partisan. Politik partisan menjadi arena para pejabat politik dan bukan
urusannya administrator.
ADMINISTRATOR DAN NETRALITAS
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Perdebatan tentang netralitas birokrasi pada level ini terkait pro
dan kontra terhadap keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan
politik. Dalam pemikiran dikotomi politik-administrasi, administrator dan
birokrasi harus netral karena mereka tidak seharusnya terlibat dalam proses
pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mereka
berpendapat ada pembagian kerja yang jelas dan tegas antara administrasi
dengan politik. Politik bertugas merumuskan tujuan negara, sedangkan
administrasi melaksanakan apa pun keputusan yang diambil dalam proses
politik. Administrator karenanya harus netral. Artinya, mereka tidak boleh
terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ada
di arena politik, dalam lembaga politik, dan dilakukan oleh mereka yang
dipilih oleh warga.
25
Yang dimaksud dengan netral adalah tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan, Netralitas tidak ada kaitannya dengan netralitas pada konteks
yang lain yang menjadi isu dalam pengembangan teori dan praktik
administrasi publik, yaitu netralitas terhadap kepentingan politik praktis.
Netralitas terhadap kepentingan politik praktis memiliki makna yang berbeda
dan akan dijelaskan dalam bagian kemudian.
Konsep netralitas dalam pengambilan keputusan memiliki implikasi
yang luas dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik.
Sebagian dari implikasinya sudah dijelaskan ketika menjelaskan konsep
dan kritik terhadap dikotomi politik administrasi. Salah satunya adalah
munculnya persepsi di kalangan ilmuwan dan praktisi bahwa “administration
begins when politics ends”. Dalam banyak pustaka bersumber dari Barat,
terutama dari administrasi publik di AS, persepsi dan pemahaman seperti
itu mendorong ilmu administrasi menjadi tidak sensitif terhadap nil. lai
penting, seperti keadilan sosial, responsivitas, akuntabilitas, kebebasan,
dan sebagainya. Proses administrasi terpisah dan tidak terlibat dalam
pengambilan keputusan sehingga relevansi dan akuntabiitas dari pilihan
kebijakan dianggap bukan isu dari administrasi publik. Para akademisi
menganggap hal tersebut menjadi urusan tetangga dan koleganya di ilmu
politik. Administrasi publik tidak perlu lagi ikut terlibat dalam diskursus
tentang hal tersebut.
Konsep netralitas memiliki implikasi ganda. Diskursus akademik
di komunitas administrasi publik menjadi semakin jauh dari isu-isu
yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi perhatian dari praktisi
administrasi publik. Para praktisi sering kali dihadapkan pada isu tentang
kemiskinan, keadilan sosial, kebebasan, dan semakin banyak masalah sosial
yang pada waktu itu terjadi negara Barat. Akan tetapi, mereka tidak dapat
berbuat banyak karena mereka tidak dibekali kapasitas untuk meresponsnya.
Ketika mereka menghadapi kenyataan bahwa program dan pilihan tindakan
yang diambil oleh para pejabat politik tidak sesuai dengan problem yang
dihadapi dan menuntut mereka untuk mengambil diskresi, mereka tidak
dapat berbuat banyak. Mereka tidak dididik untuk mengambil diskresi.
Mereka dididik dan disiapkan untuk melaksanakan apa pun keputusan
politik.
26
Terjadi perbedaan dan jarak yang semakin luas antara teori dengan
praktik administrasi publik. Teori mengajarkan para pejabat untuk bersifat
netral dan sekadar melaksakan keputusan politik, sementara praktik menuntut
untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warganya. Apalagi
administrator sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik adalah pihak
yang secara langsung berhadapan dengan warga pengguna. Mereka yang
sehari-hari bertemu dengan warga dan menerima keluhan dari mereka
Mereka juga yang paling tahu kesulitan pemerintah melayani warganya.
Oleh karena itu, wajar jika mereka diberi diskresi untuk merespons keluhan
dan aspirasi warganya. Diskresi yang diambil administrator berpengaruh
terhadap kehidupan warganya. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan
oleh Peter dan Pierce, melalui pelayanan publik administrator sebenarnya
melakukan tindakan politik karena mereka menentukan “who get what from
public sector”.
Teori administrasi publik tidak mengajarkan bagaimana administrator
terlibat dalam proses kebijakan sehingga teori tersebut gagal memberi
pedoman bagi praktisi untuk mengelola praktik. IImu administrasi publik
menjadi tidak responsif dan tidak relevan dengan praktik yang terjadi pada
waktu itu. [mu administrasi publik pada waktu itu cenderung memusatkan
perhatiannya pada efisiensi dan efektivitas, menjadikan kedua nilai tersebut
sebagai pedoman dalam mengelola praktik. Namun demikian, realitas
menghadapkan mereka pada kenyataan bahwa proses administrasi tidak
hanya harus memperhatikan kedua nilai tersebut. Administrasi efisien dan
efektif, tetapi tidak relevan dan akuntabel membuat kegiatan pelayanan
menjadi tidak banyak artinya.
Ketika warga pengguna mempersoalkan jenis pelayanan, masyarakat
mempersoalkan relevansi dari kegiatan pembangunan, dan akuntabilitas
dari tindakan yang diambil oleh pemerintah yang dianggapnya tidak sesuai
dengan aspirasi warganya, administrator dan birokrasi tidak dapat merespons
dinamika yang terjadi di lingkungannya. Warga tidak hanya butuh efisiensi
dan efektivitas, tetapi bagi warga juga membutuhkan kesesuaian antara
program dan tindakan pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasinya.
Kesesuaian antara tindakan dengan kebutuhan dan aspirasi justru menjadi
isu yang lebih penting. Meluasnya gap antara teori dan praktik administrasi
publik menimbulkan kegelisahan di kalangan akademisi dan praktisi
27
administrasi publik. Muncul kegelisahan yang meluas tentang keberadaan
dan arah pengembangan ilmu administrasi publik.
Kegelisahan yang menjadi penyebab utama munculnya gerakan di
kalangan akademisi muda pada waktu itu mengkritisi keberadaan ilmu dan
praktik administrasi publik. Mereka menggagas adanya “New Public
Administration” (Administrasi Publik Baru), yang menuntut ilmu
administrasi publik untuk peduli pada nilai-nilai keadilan sosial, kebebasan,
kemiskinan, dan sebagainya. Gerakan Administrasi Publik Baru mendorong
konsep dan teori administrasi publik untuk memperluas nilai-nilai yang
selama ini dijadikan dasar dalam pengembangannya dengan memasukkan
nilai keadilan, responsivitas, akuntabilitas, dan sebagainya. Konsep dan
teori administrasi publik tidak boleh hanya dikembangkan untuk
mewujudkan proses administrasi yang efisien dan efektif, tetapi juga menjadi
kegiatan administrasi relevan dan menjawab kebutuhan warganya. Teori
administrasi publik harus mampu memberi petunjuk dan pedoman agar
kehadiran pemerintah dan birokrasinya dirasakan manfaatnya oleh
warganya.
Mereka mengadakan seminar yang
sangat terkenal di University of Syracuse
untuk menjual gagasannya tentang
“New Public Administration”. Melalui
gagasannya itu, mereka menggugat
keberadaan konsep dan teori administrasi
publik yang dinilainya tidak relevan
arena terlalu memusatkan perhatiannya
pada efisiensi dan efektivitas. Mereka
juga menggugat arah pengembangan
ilmu administrasi publik yang cenderung
memperlebar jarak antara teori dengan
praktik. Pemikiran tentang netralitas
administrator yang berlaku pada waktu
itu dinilai telah membuat konsep, teori,
dan pendekatan administrasi publik
28
Kotak 1.6.
Administrator dan Etika Netralitas
Mengapa etika netralitas mesti
ditolak? Pertama, teori dan
praktik administrasi publik
sekarang ini gagal menjelaskan
perlunya pemisahan politik dan
administrasi. Yang terjadi keduanya
menjelaskan politik dan administrasi
saling melengkapi, bukan saling
megasikan. Kedug, sebagai manusia
biasa administrator memiliki akal
sehat, nurani, dan tacit knowledge
yang sering tidak dapat dicegah
keterlibatannya dalam proses
kebijakan. Keterlibatan subjektivitas
administrator tersebut harus
dipertanggungjawabkan pada
warganya. Ketiga, etika netralitas
menghalangi upaya untuk membuat
standar etika dan perilaku yang
tinggi bagi pegawai ASN. Standar
etika tersebut diperiukan dalam
melembagakan tata pemeritahan
yang berkualitas.
menjadi kurang relevan terhadap dinamika yang terjadi dalam praktik
administrasi publik.
Dikotomi politik-administrasi juga mendorong munculnya etika
netralitas. Etika netralitas mengajarkan bahwa administrator tidak
bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakannya. Etika ini
mengajarkan bahwa karena administrator tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan dan hanya melaksanakan apa pun yang telah diputuskan oleh
proses politik sehingga pertanggungjawaban keputusan dan kebijakan
pemerintah terletak pada pengambil keputusan. Jadi, jika keputusan dan
kebijakan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau jika gagal
mencapai apa yang diinginkan oleh warga maka pertanggungjawaban ada
pada para pejabat politik. Administrator tidak mengenal pertanggungjawaban
publik. Pertanggungjawaban publik adalah milik para pejabat politik.
Pertanyaannya adalah apakah benar administrator itu robot? Apakah
mereka malaikat dan tidak memiliki hawa nafsu? Apakah nilai, sikap,
dan kepentingan mereka tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan
setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat politik? Bagaimana kita dapat
menjamin bahwa ketika mereka melaksanakan kebijakan publik mereka
benar-benar mampu mengendalikan semua nilai dan kepentingannya
sehingga mereka melaksanakan kebijakan publik sebagaimana adanya?
Dalam diskusi sebelumnya sudah dibahas, bahwa hal tersebut sangat kecil
kemungkinan terjadinya. Ada banyak ruang yang membuat administrator
tidak bisa sepenuhnya tidak terlibat dalam alokasi nilai. Alokasi nilai tidak
hanya terjadi dalam pengambilan keputusan semata, tetapi juga dalam
proses implementasi.
Di dalam penjelasan sebelumnya, sudah didiskusikan panjang lebar
bahwa mencegah keterlibatan administrator dalam keseluruhan proses
kebijakan publik adalah hal yang mustahil. Jika demikian halnya, apakah
etika netralitas memiliki dukungan empiris? Bagaimana mereka membangun
argumentasi untuk membebaskan administrator dari pertanggungjawaban
publik atas tindakannya? Kalau mereka membangun basis pemikirannya
hanya atas dasar pemikiran dikotomi politik-adminstrasi, yang dalam
tulisannya terbukti tidak lebih dari utopia daripada realitas, maka gagasan
etika netralitas seharusnya ditolak. Administrator harus dapat dituntut
pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukannya.
29
Pertanyaannya kemudian, seberapa besar dan dalam hal apa
administrator harus bertanggung jawab dalam proses kebijakan. Jawabannya
tentu sangat tergantung pada apa yang dilakukan oleh administrator dalam
proses kebijakan. Seberapa besar keterlibatan administrator dalam proses
kebijakan. Seperti diketahui bahwa proses kebijakan melibatkan serangkaian
kegiatan dan tindakan, dari sejak muncul wacana publik tentang satu isu dan
masalah kebijakan sampai dengan terjadi perubahan sosial ekonomi sebagai
akibat dari tindakan pemerintah tertentu. Setiap tindakan yang dilakukan
oleh administrator dalam keseluruhan proses itu harus dapat dimintakan
pertanggungjawaban kepadanya.
Gagasan etika netralitas harus ditolak. Di samping tidak berbasis
pada realitas empiris juga sangat merugikan bagi pengembangan profesi
administrator. Bagaimana kita dapat membangun profesi administrator
kalau administator diperlakukan sebagai robot karena hanya melaksanakan
perintah dari pejabat politik? Tindakan robotik tidak dapat diperlakukan
sebagai profesi. Robot memang tidak perlu dan butuh profesi. Profesi hanya
dapat dikembangkan jika pemegang jabatan dan pekerja tersebut memiliki
otonomi untuk mengambil keputusan. Jika administrator tidak memiliki
ruang sama sekali untuk mengambil keputusan maka administrator tidak
dapat diperlakukan sebagai profesi. Justru karena administrator terlibat
dalam proses pengambilan keputusan dan dalam tingkat tertentu memiliki
otonomi untuk mengambil diskresi maka administrator perlu dan dapat
dikembangkan sebagai profesi.
Otonomi yang dimiliki administrator terbatas, tidak seperti otonomi
yang dimiliki profesi lainnya seperti dokter, adalah hal yang wajar. Besar-
kecil otonomi yang dimiliki oleh para pemegang profesi adalah isu yang
berbeda dan sangat tergantung pada jenis profesi. Otonomi yang dimiliki
oleh administrator terbatas karena tindakan administrator banyak diatur
oleh peraturan perundangan yang berlaku, mengingat besaran risiko yang
terjadi seandainya terjadi moral hazard dari pemegang profesi. Jika terjadi
malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter, mungkin risikonya tidak
sebesar ketika terjadi maladministration yang dilakukan oleh seorang
administrator. Malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter dapat membuat
kesehatan dan kehidupan seseorang terganggu. Jika seorang administrator
melakukan kesalahan dalam mengambil diskresi, maladministrasi dapat
30
menghasilkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar. Kesalahan diskresi
yang diambil oleh seorang administrator dapat menjadi pemicu konflik dan
kerusakan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
Mengenai besar kecilnya ruang yang tersedia bagi administrator
untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kewenangan
mengambil diskresi berbeda antarnegara tergantung pada sistem regulasi
yang dimilikinya. Di negara yang menganut sistem kontinental seperti
Indonesia, negara dan pemerintah cenderung membuat regulasi yang
membatasi dan mengatur secara rinci tindakan diskresi yang diambil oleh
administrator. Indonesia memiliki pemerintah yang sangat rule-driven.
Sebagian besar aspek penyelenggaraan pemerintah diatur secara formal
dan rinci dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
Di negara persemakmuran, ruang yang tersedia bagi para pejabat publik
dan administrator untuk mengambil diskresi relatif lebih terbuka. Mereka
menggunakan kode etik dan kode perilaku untuk melengkapi regulasi yang
tersedia untuk mengendalikan tindakan dari administrator.
Pengaturan tentang otonomi yang dimiliki oleh administrator penting
dan wajar adanya. Akan tetapi, sebaiknya pemerintah mulai memperkuat
pemanfaatan kode etika dan perilaku sebagai komplementer dari regulasi.
Rigiditas dan kompleksitas dari regulasi yang mengatur perilaku
administrator dalam pengambilan diskresi dan inovasi harus dikurangi dan
diimbangi dengan internalisasi kode etika dan perilaku. Apa pun bentuk
keseimbangan yang optimal yang dipilih antara regulasi dengan internalisasi
kode etika dan perilaku, sejauh administrator tetap memiliki kewenangan
untuk mengambil diskresi maka administrator dapat dikembangkan sebagai
satu profesi yang berdiri sendiri, sebagaimana profesi lainnya.
Di banyak negara yang memiliki administrasi publik yang berkelas
dunia, profesi administrator berkembang dengan baik. Di Indonesia,
melalui UU No. 5 Tahun 2014, negara mengakui Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebagai profesi. Pengakuan ASN sebagai satu profesi adalah langkah
maju karena selama ini administrator diperlakukan tidak lebih dari sebagai
satu jenis pekerjaan. Pengakuan kedudukan ASN sebagai profesi berarti
pengakuan terhadap otonomi yang dimiliki oleh ASN. Pegawai ASN
memiliki otonomi untuk menggunakan akal sehat, hati nurani, dan nilai-
nilai profesinya untuk membaca dan merumuskan masalah publik serta
31
merekomendasi pilihan kebijakan kepada pejabat politik atasannya. Mereka
juga dapat mengambil diskresi untuk memastikan kebijakan dan pelayanan
publik dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan warganya. Artinya,
administrator terlibat dalam proses alokasi nilai-nilai publik dalam proses
kebijakan. Dengan demikian, mereka juga harus mempertanggungjawabkan
tindakan dan dampak dari tindakan yang dilakukannya.
Penolakan terhadap etika netralitas di banyak negara juga dengan
mudah ditunjukkan dari berkembangnya profesi administator atau civil
services. Di banyak negara yang berkelas dunia, mereka umumnya
memiliki profesi civil service yang sangat maju dan tidak kalah dengan
profesi-profesi lainnya. Mereka juga mengembangkan kode etika dan
kode perilaku dan melembagakannya dalam kehidupan pegawai ASN
dan/atau administratomya. Bahkan, sebagian dari negara-negara berkelas
dunia mengatur kode etika dan kode perilaku administrator tersebut dalam
peraturan perundangan. Sebagian lainnya menjadikan sebagai bagian dari
budaya birokrasinya. Kedua pendekatan tersebut dalam konteksnya masing-
masing berhasil mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Sekali lagi, dengan melihat realitas yang ada, klaim pemikiran dikotomi
politik-administrasi bahwa administrator itu netral, yaitu karena tidak
terlibat dalam alokasi nilai dan/atau proses pengambilan keputusan, secara
empiris dan secara politik di banyak negara, termasuk di Indonesia, ditolak
keberadaannya. Administrator melalui berbagai kegiatan terlibat dalam
proses kebijakan. Mereka ikut mengalokasi nilai-nilai yang mereka yakini
sebagai nilai-nilai publik. Keyakinan dan persepsinya tentang nilai-nilai
publik tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada warganya. Dengan
demikian, gagasan tentang etika netralitas juga harus ditolak keberadaannya.
Penolakan terhadap etika netralitas juga penting untuk membangun:
standar etika yang tinggi bagi administrator. Bagaimana dapat membangun
standar etika yang tinggi jika etika netralitas mengajarkan bahwa
administrator tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakannya.
Tentu pemikiran etika netralitas tersebut sangat berisiko dan membuat
administrator tidak sensitif atas kewenangan yang dimiliki dan penggunaan
kewenangan itu dalam menjalankan profesinya. Yang terjadi seharusnya, kita
meyakinkan bahwa setiap administrator memiliki kewenangan yang melekat
pada jabatannya dan setiap penggunaan kewenangan dan dampak dari
32
penggunaan kewenangan itu memiliki efek terhadap kehidupan warganya.
Penggunaan kewenangan dan dampak dari penggunaan kewenangan
memiliki efek yang besar bagi kehidupan warganya sehingga administrator
harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan cara ini, administrator
menjadi berhati-hati dan sensitif terhadap penggunaan kewenangan yang
dimilikinya.
ADMINISTRATOR DAN IMPARSIALITAS
Penggunaan konsep netralitas yang kedua yang sering muncul
dalam praktik penyelenggaraan pemerintah sehari-hari adalah keinginan
menjadikan administrator dan birokrasi bersikap netral terhadap kepentingan
politik praktis. Politisasi birokrasi sudah berlangsung lama dan telah menjadi
perhatian para pemikir administrasi publik pada masa lalu. Munculnya
pemikiran dikotomi politik-administrasi terutama sebagian didorong oleh
terjadinya politisasi birokrasi pada masa itu. Mengapa ada upaya untuk
mengatur jabatan politik dan jabatan administrasi dan cara pengisiannya?
Banyak negara pada masa lalu juga peduli dengan risiko kegagalan
administrator dalam menjaga imparsialitasnya.
Imparsialitas administrator penting dan harus dijaga untuk
mewujudkan pemerintah yang berkelas dunia. Pemerintah berkelas dunia
hanya akan dapat diwujudkan sebagian jika administrator profesional
dan imparsial. Administrator yang seperti ini adalah mereka yang tidak
terlibat dalam politik praktis, yang dalam menjalankan tugas sehari-hari
didasarkan pada akal sehat, kode etika, dan kode perilakunya. Keputusan
yang diambil ketika dihadapkan pada keharusan mengambil diskresi harus
bersifat imparsial dalam keseluruhan dimensinya. Artinya, keputusan
tersebut harus imparsial dari kepentingan kekuasaan, afiliasi politiknya,
serta kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Ketika keputusan seorang pegawai ASN berbasis pada nilai-nilai,
kode etika, dan kode perilaku profesi maka ruang yang tersedia untuk
mengakomodasi subjektivitasnya sebagai perseorangan seharusnya dibatasi
pada tacit knoweledge dan pengalamannya ketika berhasil mengatasi
problem serupa pada masa lampau. Seorang pemegang profesi ASN
yang telah lama berkarier tentu memiliki banyak tacit knowledge. Tacit
33
knowledge yang diperolehnya ketika mengalami pembelajaran dalam
pelaksanaan beraneka tugas jabatan dipergunakan untuk mencari solusi
saat ketika mereka dihadapkan pada keharusan mengambil diskresi. Juga
ketika mereka berhasil menghadapi problem serupa pada masa lampau
dapat juga membantu mereka memiliki institusi untuk dipergunakan dalam
mengambil keputusan. Namun, ketika institusi dan tacit knowledge yang
bersifat sangat personal berbenturan dengan nilai-nilai profesi, kode etika,
dan kode perilaku maka administrator harus berpedoman pada kode etika
dan kode perilakunya.
Dalam perkembangan mutakhir, pemikiran dan praktik administrasi
publik di banyak negara berkelas dunia, administrator tidak netral dan
tidak boleh netral dalam alokasi nilai, tetapi administator harus imparsial
terhadap kepentingan politik praktis dan politik kekuasaan. Ketika mereka
terlibat dalam proses pengambilan keputusan maka sikap dan tindakannya
seharusnya didasarkan pada akal sehat, hati nurani, dan nilai-nilai profesinya.
Dengan mengembangkan teori yang mampu memberi petunjuk pada
administrator untuk terlibat dalam proses kebijakan, maka teori adminisrasi
akan menjadi semakin fungsional dan menarik banyak pihak mempelajari
dan mengembangkan ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi publik
menjadi semakin relevan terhadap dinamika yang terjadi di lingkungannya.
Para praktisi akan semakin terbantu dalam melaksanakan tugas
mereka sehari-hari, utamanya dalam mengelola proses kebijakan, Mereka
tidak lagi gagap ketika diminta oleh atasannya untuk membantu dalam
mengambil pilihan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah
dan/atau menjawab isu kebijakan yang harus direspons dengan tepat dan
cerdas. Administrator dapat memberi nasihat pada pimpinannya tentang isu
kebijakan yang berkembang dan membuat pimpinan menjadi knowledgable
sehingga ketika berhadapan dengan media massa mereka dapat dengan sigap
merespons setiap isu yang berkembang. Para pejabat politik akan selalu
dihadapkan pada berbagai macam isu kebijakan dan mereka tidak boleh
gagap dalam merespons semua isu kebijakan yang relevan dengan mandat
yang dimilikinya.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yang berlaku sekarang di
Indonesia, baik di pusat maupun daerah, politisasi birokrasi dan ASN terus
terjadi dan pada tingkat tertentu cenderung meluas. Di berbagai kementerian
34
dan pemerintah daerah, politisasi birokrasi dan ASN dapat dengan mudah
diamati. Banyak kementerian dipimpin oleh para politisi, jabatan pimpinan
tinggi (Pimti) di banyak kementerian diisi oleh mereka yang memiliki
afiliasi politik dan menunjukkan bahwa nepotisme dan klientalisme masih
mengakar dalam birokrasi. Walaupun UU ASN berusaha mencegahnya
dengan mengharuskan pengisian jabatan Pimti dilakukan melalui rekrutmen
terbuka, tetapi dalam praktik rekrutmen terbuka belum berjalan dengan baik
seperti yang diharapkan oleh pembentuk UU ASN.
Di daerah situasinya lebih buruk. Politisasi birokrasi dan ASN
berlangsung dengan cara masif dan pada tingkat tertentu agak brutal.
Pelaksanan pilkada secara langsung ternyata memiliki implikasi politik
yang luas dalam birokrasi di daerah. Landasan profesionalisme yang rapuh
dan praktik masa lalu di dalam Rezim Orde Baru! sehingga ketika pilkada
dilakukan di daerah banyak kepala daerah yang kemudian menjadikan
birokrasi dan ASN yang ada dalam kekuasaannya menjadi mesin pengumpul
suara. Pada sisi lain, banyak pegawai ASN yang memanfaatkan pilkada
sebagai peluang untuk membangun akses terhadap kekuasaan dan
mengambil jalan pintas dalam mengembangkan karier di birokrasinya.
Akibatnya, politisasi birokrasi menjadi keniscayaan.
Politisasi birokrasi dan ASN tentu merusak imparsialitas dari para
pejabat karier. Pada gilirannya, mereka bukan hanya terlibat dalam kegiatan
politik praktis, tetapi lambat laun tidak bisa dihindari akan memiliki afiliasi
politik yang sangat kuat dengan kekuatan politik tertentu. Bukan hanya
terlibat dalam pilpres dan pilkada, afiliasi politik sangat berisiko membuat
pengambilan keputusan dalam birokrasi menjadi terpengaruh oleh nilai dan
kepentingan politik, sesuatu yang dulunya memicu munculnya pemikiran
dikotomi politik-administrasi.
Kegagalan menjaga imparsialitas dari kekuatan politik pada
gilirannya dapat mengganggu netralitas dalam pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan dari administrator tidak lagi berbasis akal sehat,
nurani, dan pertimbangan profesi, tetapi dikhawatirkan akan didominasi
oleh kepentingan politik praktis dan jangka pendek. Administrator sebagai
T. Dalam zaman Orde Baru politisasi birokrasi adalah lumrah. PNS yang mestinya harus
imparsial justru mengalami golkarisasi. Tradisi politisasi ini yang mendorong ketika
Pilkada dilakukan para pejabat politik berusaha memanfaatkan birokrasi dan pegawainya
sebagai mesin pengumpul suara
35
sebuah profesi harus dijaga imparsialitas agar keputusan dan tindakannya
selalu dibimbing oleh akal sehat, hati nurani, dan nilai profesinya.
Kalau administrator terlibat dalam kegiatan politik maka keterlibatan
politik adminstrator adalah politik dalam arti policy, yaitu terlibat
dalam proses kebijakan. Politik administrator adalah politik kepublikan.
Kepentingan politik administrator adalah politik kebangsaan, yaitu politik
menjaga keutuhan dan kelangsungan bangsa dengan cara mewujudkan
nilai-nilai publik yang dulu menjadi inspirasi para pendiri bangsa untuk
mewujudkan Indonesia yang merdeka. ASN dan birokrasi harus menjadi
the guardian of the state, yaitu menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup
bangsa. Untuk kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa serta mewujudkan
cita-cita pendiri bangsa yang menjadi dasar menentukan nilai-nilai publik,
maka pegawai ASN harus bertindak dan tidak boleh netral. Bagaimana
menentukan apakah keberpihakan pada kepentingan bangsa diperlukan
sebagai bagian dari keterlibatan pada politik kepublikan maka akal sehat,
hati nurani, kode etik dan kode prilaku yang dimilikinya seharusnya menjadi
pedoman dalam menentukannya.
Pegawai ASN yang profesional dan ingin mempertahankan posisinya
yang imparsial sering dihadapkan pada pilihan yang sulit dan dilematis.
Jika mereka bersikap imparsial maka risiko akan kehilangan jabatan
sangat besar, siapa pun yang akan memenangkan pilkada. Sikap imparsial
dianggap tidak mendukung calon yang memenangkan pilkada. Akibatnya,
mereka dihadapkan pada risiko kehilangan jabatan strukturalnya. Akan
tetapi, jika mereka berpihak dan terlibat dalam politik praktik maka mereka
melanggar peraturan dan etika profesinya. Ilmu administrasi publik dan
profesi administrator dapat berperan untuk mengurangi tekanan politisasi,
nepotisme, dan klientalisme dalam birokrasi ketika mampu memberi
pedoman bertindak dan bersikap pada anggotanya ketika dihadapkan
pada problem tersebut. Untuk itu, profesi ASN harus segera membentuk
organisasi profesi yang dapat menyantuni pengembangan profesi dan
melindungi kepentingan anggotanya ketika dihadapkan pada tindakan
sewenang-wenang pejabat politik yang menjadi atasannya. Amat sulit
membayangkan Korps Pegawai Negeri (Korpri), yang sekarang menjadi
wadah tunggal para pegawai negeri, dikembangkan sebagai organisasi
36
profesi karena kendala struktural dan kultural yang selama ini melekat pada
organisasi tersebut.
Korpri yang menempatkan dirinya sebagai organisasi kedinasan
atau setengah kedinasan dan secara struktural pengurusnya diisi oleh para
pimpinan K/L dan pemerintah daerah tidak akan mampu mentransformasi
dirinya sebagai organisasi profesi yang sesungguhnya. Ketika dipimpin oleh
para pimpinan K/L yang nasibnya sebagai pejabat publik bergantung pada
Pembina Kepegawaian di K/L dan pemerintah daerah, mereka dipastikan
tidak akan dapat memperjuangkan nilai-nilai profesi ketika berhubungan
dengan kepentingan jangka pendek dari politik pemerintahan. Contoh
kasus benturan nilai-nilai profesi dengan kepentingan politik jangka pendek
pemerintah yang ingin menambah hukuman kebiri pada pelaku kejahatan
seksual pada anak dapat menjadi pembelajaran bagi profesi ASN. Kasus
ini seharusnya dapat menginspirasi pemegang profesi ASN untuk segera
membentuk organisasi profesi yang independen.
Pemerintah dapat berganti setiap lima tahun dan wajar ketika mereka
kemudian mengembangkan program-program jangka pendek dan menengah
agar selama lima tahun berkuasa ada banyak legasi yang dapat diklaim
sebagai modal kampanye untuk dapat dipilih kembali dan berkuasa pada
periode lima tahun berikutnya. Hampir semua pemerintahan melakukan hal
itu. Wajar kalau mereka tidak tertarik pada kepentingan jangka panjang.
Nilai-nilai publik, yang pada tingkat tertentu bersifat universal dan generik,
mewujudkannya perlu waktu relatif panjang. Misalnya, pemberdayaan
penduduk miskin, perempuan, kelompok marginal, keadilan sosial,
kesejahteraan, dan kebebasan berpendapat adalah bagian dari nilai dan
kepentingan publik yang seharusnya diperjuangkan oleh seorang pemegang
profesi ASN. Walaupun negara dibentuk untuk mewujudkan nilai-nilai
publik, tetapi adakalanya pemerintah, karena orientasinya jangka pendek
dan pada kepentingan konstituen politiknya, sangat mungkin terjadi benturan
antara program pemerintah yang berwawasan jangka pendek dengan nilai
dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, organisasi profesi ASN dapat
menyampaikan alternatif pandangannya tentang apa yang seharusnya
dilakukan oleh pemerintah agar programnya dapat memberi kontribusi
pada terwujudnya nilai-nilai publik. Oleh karena itu, penting menjaga
independensi dari organisasi profesi ASN.
37
Dari sisi kepentingan publik, mengembangkan ilmu administrasi
publik dan organisasi profesi ASN yang mampu memberi pedoman dan
petunjuk pada anggotanya ketika dihadapkan pada dilema seperti tersebut
di atas sangat menguntungkan. Dalam proses kebijakan, masyarakat luas
diuntungkan karena proses kebijakan menjadi semakin terbuka dan inklusif
karena nilai-nilai yang menjadi dasar dalam proses kebijakan bukan lagi
kepentingan politik jangka pendek dan kepentingan konstituen semata,
tetapi juga mencakup aspirasi pemangku kepentingan, termasuk nilai-nilai
dan kepentingan publik yang direpresentasikan oleh para pemegang profesi.
Apalagi ketika nantinya praktik pembuatan kebijakan menjadi semakin
evidence-based, proses pembuatan kebijakan akan melibatkan para birokrat
sebagai agen pelaksana. Sebagai agen pelaksana, birokrat adalah pihak yang
menguasai eviden karena mereka yang sehari-hari bergaul dengan kebijakan
dengan segala persoalan yang melekat padanya.
Umu adminisrasi publik yang mutakhir sekarang ini mengajarkan
proses kebijakan seharusnya berbasis evidence, siapa yang memiliki eviden
seharusnya menjadi aktor kebijakan yang penting. Pemegang profesi ASN
sebagai pelaksana kebijakan yang sehari-hari bergelut dengan dinamika
implementasi kebijakan tentu menjadi salah satu pihak yang menguasai
eviden. Masyarakat sipil dan dunia akademisi yang peduli dengan isu
kebijakan tertentu memiliki banyak eviden yang dapat dijadikan masukan
dalam pembuatan kebijakan sehingga mereka seharusnya juga terlibat dan
dilibatkan dalam proses kebijakan. Nilai-nilai dan gagasan yang disampaikan
oleh banyak aktor menjadi bagian dari perdebatan dalam proses kebijakan
sehingga konsensus yang diambil nantinya mencerminkan pandangan dari
sebagian besar pemangku kepentingan dan semakin mendekati nilai-nilai
dan kepentingan publik yang inklusif.
Kembali pada isu imparsialitas, bagi administrator sebagai pemegang
profesi ASN tidak ada pilihan lain, kecuali mereka harus imparsial dari
semua kekuatan politik. Haram hukumnya mereka terlibat dalam politik
pilkada dan politik kekuasan. Keterlibatan mereka dalam politik pilkada
dan politik kekuasaan bukan hanya merusak kualitas tata pemerintah yang
berlaku, tetapi juga merusak profesi ASN. Namun demikian, tidak berarti
pegawai ASN menjadi apolitik, tidak peduli dengan politik, dan acuh pada
dinamika lingkungan sosial politik sekitarnya. ASN yang profesional dan
38
imparsial harus peduli pada politik kepublikan, Ia harus terlibat dalam
proses kebijakan untuk memastikan bahwa proses kebijakan mengabdi pada
kepentingan publik yang luas, bukan pada kepentingan kekuasaan.
KESIMPULAN
Pemikiran terdahulu administrasi publik, terutama sebelum perang
dunia kedua yang dipelopori oleh Wilson, Weber, dan Goodnow, umumnya
mengajarkan perlunya pemisahan antara politik dengan administrasi.
Pemikiran tersebut di samping merespons dinamika yang terjadi pada masa
itu, terutama keinginan untuk mengembangkan aparatur sipil negara yang
imparsial, juga sesuai dengan tradisi konstitusi di Amerika Serikat yang
mengajarkan trias politika. Ajaran trias politika yang memisahkan fungsi
pengambilan keputusan (legislatif) dan fungsi eksekusi (eksekutif) dianggap
pas dengan gagasan dikotomi politik administrasi. Namun demikian, dalam
kenyataannya gagasan untuk memisahkan proses politik dan administrasi
sebagai sesuatu yang berbeda secara distinct bukan hal yang mudah karena
dalam praktik, politik dan administrasi adalah kegiatan yang komplementer.
Pascaperang dunia kedua, para pemikir generasi kedua yang dimulai
oleh Waldo dengan artikelnya yang sangat seminal, “Administrative
State”, Simon dengan konsepnya tentang rasionalitas terbatas (bounded
rationality), dan Applebly, semuanya menggugat gagasan pemisahan politik
dan administrasi. Pemisahan politik dan administrasi dinilai tidak masuk
akal dan tidak lebih dari mitos. Upaya untuk mengembangkan administrasi
publik yang imparsial tidak seharusnya dilakukan dengan memisahkan
proses politik dengan administrasi karena keduanya bersifat komplementer
dan hanya menggambarkan perbedaan intensitas. Administrator dalam
praktiknya terlibat dalam hampir semua proses kebijakan, yang membedakan
adalah derajat dari keterlibatannya, yang mungkin berbeda pada setiap sub
proses yang ada.
Diskusi dalam bab ini menunjukkan bahwa dilihat dari berbagai aspek
pemisahan politik dan administrasi, baik pada tingkat gagasan maupun
praktik, tidak mungkin dilakukan. Administrator, karena pekerjaan,
keahlian, dan profesinya, tidak mungkin untuk tidak terlibat dalam proses
kebijakan. Para pejabat politik, karena mandat yang diterima dari konstituen
39
dan pertanggungjawaban publik atas kebijakan yang diambilnya, juga
tidak mungkin untuk tidak terlibat dalam proses implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan tidak dapat diperlakukan sebagai taken for granted
karena nasib mereka juga ditentukan oleh kualitas dari implementasi. Nasib
konstituennya berubah bukan hanya karena kualitas dari keputusannya tetapi
juga bagaimana keputusan tersebut diwujudkan dalam program dan kegiatan
yang bermanfaat bagi konstituennya.
Namun demikian, walaupun secara gagasan pemisahan politik dan
administrasi dengan cepat ditinggalkan, isu tentang dinamika hubungan
antara politik dengan administrasi tidak pernah padam dan akan selalu
menarik untuk didiskusikan, baik dalam pengembangan diskursus akademik
ataupun dalam praktik administrasi publik. Keinginan untuk mewujudkan
administrasi publik yang imparisial dan nonpartisan tidak akan pernah
lekang dan selalu menjadi obsesi dari para akademisi dan praktisi.
Administrator memang tidak boleh terlibat dalam politik partisan dan
harus menjaga agar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
bersifat imparsial. Akan tetapi, hal itu tidak berarti administrator ignorance
dan tidak peduli dengan proses kebijakan. Harus dibedakan antara politik
partisan dengan policy, di mana untuk yang terakhir administrator harus
peduli dan memastikan bahwa proses kebijakan benar-benar mengabdi pada
terwujudnya nilai dan kepentingan publik. Politik dari administrator tidak
bersifat partisan, tetapi politik kepublikan.
Dalam menjalankan politik kepublikan, administrator dapat berperan
melalui pemberian opini dan/atau nasihat kepada para pejabat politik
tentang pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia untuk mewujudkan nilai dan
kepentingan publik dengan tanpa meninggalkan kepentingan konstituen.
Administrator juga dapat menjalankan politik kepublikan ketika mereka
mengambil diskresi dalam implementasi kebijakan. Dalam kegiatan
pemerintah sehari-hari, politik kepublikan ini tidak dapat dipisahkan dalam
hubungan antara pejabat politik dengan administrator. Keduanya seharusnya
bekerja bersama untuk menghindari politik partisan.
Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh administrator dalam
mewujudkan politik kepublikan. Pertama, administrator menghargai
posisi pejabat politik sebagai pemegang mandat dari pemilih. Mereka
yang dipercaya oleh warga dan diberi mandat untuk memperjuangkan
40
aspirasinya. Oleh karena itu, administrator harus menghargai gagasan
kebijakan dan tindakan yang ingin dilakukan oleh para pejabat politik
dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingan konstituen. Jika administrator
memiliki pandangan yang berbeda dengan yang dimiliki oleh para pejabat
politik karena pertimbangan profesi dan keahilan yang dimilikinya,
administrator dapat menyampaikannya secara tertutup. Administrator tidak
seharusnya mengkritisi secara terbuka gagasan kebijakan yang dimiliki oleh
para pejabat politik yang menjadi atasannya.
Kedua, sebagai pejabat karier yang menduduki jabatan karena merit
administrator harus menyadari bahwa di samping harus akuntabel pada
publik, mereka juga harus akuntabel pada pejabat politik yang menjadi
atasannya. Administrator harus menjaga agar kedua akuntabilitas ini sejalan
dengan nilai dan kepentingan publik. Jika karena satu dan lain hal keduanya
memberi tekanan yang diametral kepada administrator maka administrator
pertama-tama harus menempatkan kepentingan dan nilai publik di atas
yang lainnya. Tentu hal ini tidak sederhana dan mudah dilakukan karena
nasib administrator dalam banyak hal amat tergantung pada penilaian dari
para pejabat politiknya, Letak pentingnya profesi ASN memiliki organisasi
profesi yang independen, menyantuni pengembangan profesi, dan membela
kepentingan anggota dari tindakan sewenang-wenang pejabat politik
atasannya.
Ketiga, administrator tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik
partisan dan/atau politik elektoral. Administrator dalam segala tindakannya
harus dapat membebaskan dirinya dari tarik-menarik kepentingan politik
jangka pendek dan politik praktis. Mereka harus dapat membuktikan bahwa
mereka bertindak above all impartially. Hal ini dapat dilakukan dengan
selalu menjaga jarak dari semua kepentingan partai dan hanya lokus pada
politik kepublikan. Dalam sistem multi partai yang berlaku di Indonesia,
di mana partai politik yang berbeda dapat menguasai tingkat pemerintahan
yang berbeda-beda, maka administrator seharusnya dapat berperan untuk
menjaga keseimbangan antara kepentingan politik praktis dengan politik
kepublikan.
Keempat, administrator secara politik netral dan imparsial, tetapi secara
policy ikut terlibat dalam alokasi nilai. Apakah alokasi nilai dilakukan
melalui pemberian nasihat kepada pejabat politik atasannya atau melalui
41
diskresi yang diambilnya dalam proses implementasi, administrator harus
ikut bertanggung jawab tethadap diskresi dan dampak yang terjadi sebagai
akibat dari diskresi yang diambilnya. Profesi ASN harus mampu menetapkan
standar etika profesi yang tinggi sehingga setiap pegawai ASN memiliki
sensitivitas yang tinggi tethadap besamya kekuasaan yang dimilikinya dalam
mengambil diskresi dan dampak dari penggunaan kekuasaannya tersebut.
Besarnya warga dan dalam hal apa saja warga memperoleh manfaat dari
kehadiran negara melalui pelayanan publiknya ditentukan melalui diskresi.
42
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5822)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (852)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (823)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (403)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Etika Pembedahan ObstetriDocument17 pagesEtika Pembedahan Obstetrisri wulanNo ratings yet
- Upload JurnalDocument26 pagesUpload Jurnalsri wulanNo ratings yet
- Refarat Global Development Delay (GDD)Document17 pagesRefarat Global Development Delay (GDD)sri wulanNo ratings yet
- 1802 3939 1 PBDocument17 pages1802 3939 1 PBsri wulanNo ratings yet
- Guillain Barre Sindrom'Document37 pagesGuillain Barre Sindrom'sri wulanNo ratings yet
- Skripsi: Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Ilmu PemerintahanDocument159 pagesSkripsi: Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahansri wulanNo ratings yet
- 9 9 1 PB With Cover Page v2Document21 pages9 9 1 PB With Cover Page v2sri wulanNo ratings yet
- Isi Artikel 333261142398Document11 pagesIsi Artikel 333261142398sri wulanNo ratings yet
- 2015 Jurnal Tahun 2015Document192 pages2015 Jurnal Tahun 2015sri wulanNo ratings yet
- Makalah Semnas Fisip Ut 2012 Sub Tema: Birokrasi Dan Road Map Mdgs 2015 Di IndonesiaDocument16 pagesMakalah Semnas Fisip Ut 2012 Sub Tema: Birokrasi Dan Road Map Mdgs 2015 Di Indonesiasri wulanNo ratings yet
- Sri Wulan SNDocument9 pagesSri Wulan SNsri wulanNo ratings yet
- 6008-Full TextDocument100 pages6008-Full Textsri wulanNo ratings yet
- Hepatitis B NewDocument31 pagesHepatitis B Newsri wulanNo ratings yet
- Referat Tenia ImbrikataDocument18 pagesReferat Tenia Imbrikatasri wulanNo ratings yet
- Referat Demam TifoidDocument19 pagesReferat Demam Tifoidsri wulanNo ratings yet
- Lapsus DVT IsipDocument21 pagesLapsus DVT Isipsri wulanNo ratings yet
- TUTORIAL Anemia AplastikDocument21 pagesTUTORIAL Anemia Aplastiksri wulanNo ratings yet
- Kejang Demam KompleksDocument10 pagesKejang Demam Komplekssri wulanNo ratings yet
- PRINTTT REFARAT WULAN FixDocument54 pagesPRINTTT REFARAT WULAN Fixsri wulanNo ratings yet
- Formulir Penolakan Tindakan KedokteranDocument1 pageFormulir Penolakan Tindakan Kedokteransri wulanNo ratings yet
- SOP Identifikasi Nilai-NilaiDocument1 pageSOP Identifikasi Nilai-Nilaisri wulanNo ratings yet
- BasidiomycotaDocument9 pagesBasidiomycotasri wulanNo ratings yet
- Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)Document1 pageFormulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)sri wulanNo ratings yet
- 76040138-Referat-Fraktur-Pelvis EditDocument34 pages76040138-Referat-Fraktur-Pelvis Editsri wulanNo ratings yet