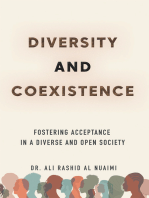Professional Documents
Culture Documents
102-Article Text-327-3-10-20190219
102-Article Text-327-3-10-20190219
Uploaded by
AzilCopyright:
Available Formats
You might also like
- MWB 2019 2020 en 1602190422Document77 pagesMWB 2019 2020 en 1602190422Vladan Colakovic55% (11)
- Basics of English Speaking For Workplace RevisedDocument170 pagesBasics of English Speaking For Workplace Revisedravi96100% (4)
- Potret Konflik Umat Beragama Di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi AgamaDocument15 pagesPotret Konflik Umat Beragama Di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi AgamaDzakiyyahNo ratings yet
- Etika Sosial Terhadap Paradoks Peran Agama Dan Kebebasan Beragama Dalam Kaitannya Dengan Konflik Di IndonesiaDocument19 pagesEtika Sosial Terhadap Paradoks Peran Agama Dan Kebebasan Beragama Dalam Kaitannya Dengan Konflik Di IndonesiaRian Armansyah ManggeNo ratings yet
- Pendidikan Agama Penopang Resolusi Konflik Umat BeragamaDocument9 pagesPendidikan Agama Penopang Resolusi Konflik Umat BeragamaNuma jerichoNo ratings yet
- Project - IRDocument18 pagesProject - IRSharad panwarNo ratings yet
- Social Integration and Communal Harmony in IndiaDocument12 pagesSocial Integration and Communal Harmony in IndiaSwethan AkkenapelliNo ratings yet
- Religions 9 Peace PDFDocument202 pagesReligions 9 Peace PDFShemusundeen MuhammadNo ratings yet
- 6.+PDF Barkah Toleransi 89-111 UIN+SGD+BDG+Document23 pages6.+PDF Barkah Toleransi 89-111 UIN+SGD+BDG+ALFARIZI B.a.ENo ratings yet
- 56-Article Text-575-2-10-20210618Document15 pages56-Article Text-575-2-10-20210618Free WriterNo ratings yet
- 266-Article Text-1472-1-10-20221025Document13 pages266-Article Text-1472-1-10-20221025DonyNo ratings yet
- Religion Con Icts in Indonesia Problems and Solutions: December 2015Document7 pagesReligion Con Icts in Indonesia Problems and Solutions: December 2015AnandaNo ratings yet
- Harmony of ReligionsDocument60 pagesHarmony of ReligionsVejella PrasadNo ratings yet
- .Document1 page.Divine Mendoza0% (2)
- Communal HarmonyDocument13 pagesCommunal HarmonyAlka RanjanaNo ratings yet
- Artikel KonseptualDocument13 pagesArtikel KonseptualElfen LiedNo ratings yet
- Peran Komisi DialogDocument23 pagesPeran Komisi DialogEroNo ratings yet
- Christian Islamic Resources For Peace5Document16 pagesChristian Islamic Resources For Peace5sir_vic2013No ratings yet
- Membangun Sikap Toleransi Beragama: Dalam Masyarakat PluralDocument12 pagesMembangun Sikap Toleransi Beragama: Dalam Masyarakat PluralrikkiNo ratings yet
- Communal HarmonyDocument8 pagesCommunal Harmonytajju_121No ratings yet
- 38 224 1 PBDocument14 pages38 224 1 PBFree WriterNo ratings yet
- Artikel Agama Dan Harmoni KehidupanDocument4 pagesArtikel Agama Dan Harmoni Kehidupancantikfida167No ratings yet
- Berdamai Dengan Pluralitas Paham Keberagamaan PDFDocument26 pagesBerdamai Dengan Pluralitas Paham Keberagamaan PDFIfa IffahNo ratings yet
- Ethn166 FinalDocument13 pagesEthn166 Finalapi-613875479No ratings yet
- Sumbangan Etika Global Hans Küng Demi Terwujudnya Perdamaian Dan Relevansinya Bagi IndonesiaDocument20 pagesSumbangan Etika Global Hans Küng Demi Terwujudnya Perdamaian Dan Relevansinya Bagi IndonesiaChristianNo ratings yet
- Kontestasi Umat Beragama Studi Tentang P 40cfa247Document13 pagesKontestasi Umat Beragama Studi Tentang P 40cfa247Deni Agustian WijayaNo ratings yet
- Religion and ConflictDocument9 pagesReligion and ConflictLorraine DomantayNo ratings yet
- Religion in The Global ConflictDocument3 pagesReligion in The Global ConflictCian TolosaNo ratings yet
- Enlightenment Twitter Meme ProjecDocument2 pagesEnlightenment Twitter Meme Projecapi-712100741No ratings yet
- Unit 30Document12 pagesUnit 30Likuna NaikNo ratings yet
- Hubungan Antarumat Beragama Berspirit Multikulturalisme: AbstrakDocument26 pagesHubungan Antarumat Beragama Berspirit Multikulturalisme: AbstrakAlex ZukisnoNo ratings yet
- 4812 10261 1 SM PDFDocument15 pages4812 10261 1 SM PDFNidaNo ratings yet
- Membangun Sikap Toleransi Beragama: Dalam Masyarakat PluralDocument12 pagesMembangun Sikap Toleransi Beragama: Dalam Masyarakat PluralBESSE HANUMNo ratings yet
- Jose Rizal University Senior High School DivisionDocument7 pagesJose Rizal University Senior High School DivisionVicky PungyanNo ratings yet
- Communal Violence, Its Causes and Solutions: Mohsin Iqbal NajarDocument3 pagesCommunal Violence, Its Causes and Solutions: Mohsin Iqbal NajarShahal MuhammedNo ratings yet
- Secularism and Communalism in IndiaDocument5 pagesSecularism and Communalism in IndiaSheela MoncyNo ratings yet
- EN Pluralism and Religious Tolerance in IndDocument10 pagesEN Pluralism and Religious Tolerance in IndAsmaa ZahroNo ratings yet
- Religions Cause ConflictDocument5 pagesReligions Cause Conflictapi-340635766No ratings yet
- Kecerdasan Komunikasi Spiritual Dalam Upaya Membangun Perdamaian Dan Toleransi BeragamaDocument18 pagesKecerdasan Komunikasi Spiritual Dalam Upaya Membangun Perdamaian Dan Toleransi BeragamaVikri RamadhanNo ratings yet
- The Dead End of Dialogue by St. SunardiDocument7 pagesThe Dead End of Dialogue by St. Sunardiavatarrista309No ratings yet
- Dinamika Konflik Dan Integrasi Antara Etnis Dayak Dan Etnis Madura (Studi Kasus Di Yogyakarta Malang Dan Sampit)Document20 pagesDinamika Konflik Dan Integrasi Antara Etnis Dayak Dan Etnis Madura (Studi Kasus Di Yogyakarta Malang Dan Sampit)muchammadnorsaniNo ratings yet
- Forum 6Document2 pagesForum 6Aubrey ArizoNo ratings yet
- Twenty First Century, Religion and PeaceDocument5 pagesTwenty First Century, Religion and PeaceMushtak MuftiNo ratings yet
- Dinamika Integrasi Nasional Bangsa Indonesia (Dalam Pendekatan Kerukunan Umat Beragama) Abdul Hamid (Dosen PAI FKIP Universitas Tadulako) E-MailDocument22 pagesDinamika Integrasi Nasional Bangsa Indonesia (Dalam Pendekatan Kerukunan Umat Beragama) Abdul Hamid (Dosen PAI FKIP Universitas Tadulako) E-MailManjutz AjirNo ratings yet
- Diversity and Coexistence: Fostering Acceptance in a Diverse and Open SocietyFrom EverandDiversity and Coexistence: Fostering Acceptance in a Diverse and Open SocietyNo ratings yet
- The Basis For A Hundu-Muslim Dialogue1Document17 pagesThe Basis For A Hundu-Muslim Dialogue1Sushant NauNo ratings yet
- 63-Article Text-622-1-10-20190208Document14 pages63-Article Text-622-1-10-20190208dandi irmansyahNo ratings yet
- Islam, Negara Dan Hak-Hak Minoritas Di Indonesia: Hasbi HasanDocument18 pagesIslam, Negara Dan Hak-Hak Minoritas Di Indonesia: Hasbi Hasanmelisa bayu prasetyaNo ratings yet
- SecularisationDocument5 pagesSecularisationDev Pratap singhNo ratings yet
- Secularism in IndiaDocument37 pagesSecularism in Indiaapi-3832446100% (1)
- Religious IntoleranceDocument3 pagesReligious IntoleranceInês Guedes MartinsNo ratings yet
- Religius and Harmony in Goverment IndonesiaDocument22 pagesReligius and Harmony in Goverment IndonesiaMTs Hidayatul Mubtadi'inNo ratings yet
- Module 4Document40 pagesModule 4WINORLOSENo ratings yet
- Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan KeagamaanDocument22 pagesKuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan KeagamaanichaNo ratings yet
- Unit 11 Communalism: 11.0 ObjectivesDocument11 pagesUnit 11 Communalism: 11.0 ObjectivesMansi SinghNo ratings yet
- Religion and Peace: Global Perspectives and PossibilitiesFrom EverandReligion and Peace: Global Perspectives and PossibilitiesNukhet A. SandalNo ratings yet
- Communal HarmonyDocument3 pagesCommunal HarmonygaridiyaNo ratings yet
- Challenges of Religious PluralismDocument9 pagesChallenges of Religious PluralismtughtughNo ratings yet
- Islam Dan Hubungan Antar Agama Oleh: Sulaiman Mohammad Nur: ISSN: 0000-0000Document27 pagesIslam Dan Hubungan Antar Agama Oleh: Sulaiman Mohammad Nur: ISSN: 0000-0000M KhoirudinNo ratings yet
- Agama Dan Politik - Hubungan Yang Ambivalen Dialog Versus "Benturan Peradaban"?Document30 pagesAgama Dan Politik - Hubungan Yang Ambivalen Dialog Versus "Benturan Peradaban"?Rocky Arfan BakkaraNo ratings yet
- SecularismDocument5 pagesSecularismkathy97No ratings yet
- A Dialogue with Truth: . . . the Wise Call It by Many NamesFrom EverandA Dialogue with Truth: . . . the Wise Call It by Many NamesNo ratings yet
- Inductive and Deductive ReasoningDocument16 pagesInductive and Deductive ReasoningCedrick Nicolas Valera0% (1)
- Mechanical PunchinelloDocument1 pageMechanical PunchinelloMarco FrascariNo ratings yet
- For 18 - 25: Deficiency of Liquid Assets. On July 1, 2020, The Following Information Was AvailableDocument3 pagesFor 18 - 25: Deficiency of Liquid Assets. On July 1, 2020, The Following Information Was AvailableExzyl Vixien Iexsha LoxinthNo ratings yet
- Exercise 2.6Document4 pagesExercise 2.6mohitgaba19No ratings yet
- 2015 Eccentric or Concentric Exercises For The Treatment of Tendinopathies...Document11 pages2015 Eccentric or Concentric Exercises For The Treatment of Tendinopathies...Castro WeithNo ratings yet
- The Enlightenment Salon. Activity Unit 1 - PDF - Age of Enlightenment - Early MoDocument2 pagesThe Enlightenment Salon. Activity Unit 1 - PDF - Age of Enlightenment - Early MoMarylee OrtizNo ratings yet
- The Renaissance ArchitectureDocument18 pagesThe Renaissance ArchitectureRazvan BataiosuNo ratings yet
- These Beautiful Butterflies Up in The Sky, Send Valentine Wishes As They Flutter byDocument6 pagesThese Beautiful Butterflies Up in The Sky, Send Valentine Wishes As They Flutter byRaquel SilvaNo ratings yet
- Gavieres V Pardo de Tavera - DepositDocument2 pagesGavieres V Pardo de Tavera - DepositAnonymous srweUXnClcNo ratings yet
- Lecture 2 Sociology 2018Document5 pagesLecture 2 Sociology 2018Yasir NawazNo ratings yet
- UntitledDocument1 pageUntitledErwinNo ratings yet
- Renewal of Notarial Commission 2022-2023 For UploadDocument3 pagesRenewal of Notarial Commission 2022-2023 For UploadmacrosalNo ratings yet
- Brent Kalar - The Demands of Taste in Kant's Aesthetics (Continuum Studies in Philosophy) (2006) PDFDocument189 pagesBrent Kalar - The Demands of Taste in Kant's Aesthetics (Continuum Studies in Philosophy) (2006) PDFPatricia Silveira PenhaNo ratings yet
- Imps, Flo, MonDocument22 pagesImps, Flo, MonMDaenery KlexxxNo ratings yet
- Lavendia Portfolio PR2 ABM12 4Document28 pagesLavendia Portfolio PR2 ABM12 4PresydenteNo ratings yet
- ID-IM-SQ-E ToolDocument9 pagesID-IM-SQ-E TooltriciacamilleNo ratings yet
- Contributors To Philippine Folk DanceDocument8 pagesContributors To Philippine Folk DanceChristle Joy ManaloNo ratings yet
- Group 5 Final - 064830Document8 pagesGroup 5 Final - 064830Stephen EwusiNo ratings yet
- Psci 6601w Jaeger w11Document23 pagesPsci 6601w Jaeger w11Ayah Aisa Dan SissyNo ratings yet
- Foreign Exchange Risk Management in Bank PDFDocument16 pagesForeign Exchange Risk Management in Bank PDFsumon100% (1)
- Chapter 1: The Study of Accounting Information SystemsDocument36 pagesChapter 1: The Study of Accounting Information SystemsAliah CyrilNo ratings yet
- Worksheet 1 - Fundamental of Research MethodologyDocument3 pagesWorksheet 1 - Fundamental of Research MethodologyRichard YapNo ratings yet
- Claims Arising Under A Construction ContractDocument5 pagesClaims Arising Under A Construction ContracthymerchmidtNo ratings yet
- Mathematics P2 Nov 2012 Memo EngDocument29 pagesMathematics P2 Nov 2012 Memo Engaleck mthethwaNo ratings yet
- RIOSA v. TabacoDocument3 pagesRIOSA v. Tabacochappy_leigh118No ratings yet
- Salaria v. Buenviaje G.R. No. L 45642 DIGESTDocument2 pagesSalaria v. Buenviaje G.R. No. L 45642 DIGESTMikee BornforThis MirasolNo ratings yet
- Fme Evaluating PerformanceDocument35 pagesFme Evaluating PerformanceDr.B.THAYUMANAVARNo ratings yet
- How One Ought To LiveDocument4 pagesHow One Ought To LiveVictor HoustonNo ratings yet
102-Article Text-327-3-10-20190219
102-Article Text-327-3-10-20190219
Uploaded by
AzilOriginal Description:
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
102-Article Text-327-3-10-20190219
102-Article Text-327-3-10-20190219
Uploaded by
AzilCopyright:
Available Formats
Resolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
Alim Roswantoro
UIN Sunan Kalijaga – Yogyakarta
alimroswa@yahoo.com
Abstract
Indonesia, as the plural nation in religion, has already
performed a positive and peaceful life of the religious
people who are different in faith and understanding. In
general, the life of religious people in Indonesia is lasting
well and peacefully. It does not mean that there never be
religious conflicts of the different religious people in
Indonesia. The conflicts had ever occurred and will
probably emerge in the future. The conflicts were often
seen as threat, or negativity, of religious life among
different-religious people in Indonesia. The writing does
not deny that indeed the conflicts are not wanted and have
to be overcome. But since the conflicts cannot be avoided
from the life of different-religious people of Indonesia, the
writing philosophically intend to see and understand the
conflicts in a different way. The religious conflicts can be
positively seen and understood, that is, as part of
communication among different-religious people
interacting in public sphere. Conflict-resolution that gives
the win-win solution for those who are involved in the
conflict has to be principle that should be made to be
tradition. Conflict resolution will be successful if the
transcendently moral principles, such as mutual respect,
Religió: Jurnal Studi Agama-agamaMutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Volume 78, Nomor 21, Desember20178| ISSN: (p) 2088-6330; (e) 2503-3778p-ISSN:
2088-7523; e-ISSN: 2502-6321| 2151-2341-24
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
mutually avoiding deformation of religion, and mutually
giving freedom, are provided for all.
[Indonesia sebagai negara yang majemuk dalam agama
telah menampilkan wajah hidup umat beragama dari
agama-agama yang berbeda yang damai. Secara umum,
kehidupan umat beragama di Indonesia berjalan dengan
penuh kedamaian. Ini bukan berarti tidak pernah ada
konflik keagamaan di Indonesia. Konflik-konflik
keagamaan telah pernah terjadi dan mungkin akan muncul
kembali di masa depan. Konflik-konflik ini sering dilihat
sebagai suatu ancaman atau sisi negatif dari kehidupan
religius di Indonesia. Tulisan ini tidak memungkiri bahwa
konflik-konflik ini memang tidak diinginkan dan harus
diatasi. Namun, karena konflik-konflik ini tidak bisa
dihindari dalam kehidupan antar umat beragama yang
berbeda, tulisan ini mencoba secara filosofis melihat dan
memaknai konflik-konflik ini secara berbeda. Konflik-
konflik keagamaan bisa dimaknai secara positif, sebagai
bagian dari komunikasi antara umat beragama yang
berbeda yang berinteraksi dalam ruang publik. Resolusi
konflik yang saling memenangkan masing-masing pihak
harus menjadi prinsip yang harus ditradisikan. Resolusi
konflik akan sukses, jika prinsip-prinsip moral transenden,
seperti saling menghargai, saling menghindari deformasi
agama, dan saling memberi ruang kebebasan, diberikan
untuk semuanya.]
Keywords: Religious conflict, conflict resolution,
masyarakat religius Indonesia
Pendahuluan
Perbedaan antar agama, kepercayaan keagamaan, dan
pemahaman keagamaan, berpotensi memunculkan konflik. Namun
dalam beberapa hal perbedaan keagamaan mampu menjadi medium
bagi orang-orang yang berbeda agama, kepercayaan keagamaan,
dan pemahaman keagamaan untuk mendewasakan keberagamaan
masing-masing.
Bagaimana mereka yang berbeda dalam religiusitas tidak
meninggikan martabat agama dan keberagamaannya dengan cara
pemaksaan kehendak dan kekerasan fisik. Hal ini merupakan
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
pemikiran yang mengupayakan kedewasaan beragama di tengah
pluralitas agama dan keagamaan. Sejalan dengan pemahaman
bahwa tidak ada martabat suatu agama atau suatu kepercayaan
keagamaan yang bisa ditinggikan dengan pemaksaan kehendak dan
kekerasan fisik. Sacks mengartikulasikan hal ini dengan
pernyataannya, “No religion won the admiration of the world by its
capacity to inflict suffering on its enemies.” 1 (Tidak ada agama
yang memenangkan kehormatan dunia dengan kemampuannya
menimpakan penderitaan pada musuh-musuhnya).
Munculnya konflik keagamaan di Indonesia beberapa dekade
terakhir menunjukkan bahwa potensi terjadinya konflik bisa dari
beberapa faktor seperti politik, ekonomi, kultur dan sebagainya.
Sehingga penting untuk memahami bagaimana kita melihat konflik
dengan cara berbeda. Konflik bukan sebagai ancaman, melainkan
sebagai komunikasi untuk membangun hubungan baik untuk saling
memberi ruang kebebasan dan saling menghargai.
Tulisan ini merefleksikan secara filosofis konflik-konflik
keagamaan yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi kembali
di masa yang akan datang. Dilihat dari fakta positifnya, perbedaan
keagamaan mampu mendewasakan keberagamaan insan religius.
Namun fakta negatifnya agama bisa menjadi kekuatan yang
mengancam dan meneror dunia. Menurut Mc Ternan, dalam
sejarah agama, setiap agama memiliki pengalaman melakukan
kekerasan atas nama agama, karena ajaran agamanya bisa dipahami
untuk membenarkannya.2 Namun seburuk-buruknya negativitas
kekerasan atas nama agama, Fuller menegaskan bahwa apa yang
dilakukan agama tidak lebih buruk daripada yang pernah dilakukan
oleh kekerasan ekstremis-ekstremis sekuler seperti fasisme,
nazisme, dan komunisme.3 Fakta positif kehidupan umat beragama
mengajak hidup untuk berbagi, hidup damai, dan saling mengasihi
1
Jonathan Sacks, Not in God’s Name: Confronting Religious Violence (Edinburg:
Hodder & Stoughton, An Hachette UK Company, 2015), 265.
2
Lihat Oliver McTernan, terutama pada bagian “Religion and the Legitimation
of Violence” dalam bukunya Violence in God’s Name (London: Darton,
Longman Todd Ltd., 2003), 45-76.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
kepada sesama manusia tanpa melihat latar belakangnya banyak
ditemukan dalam sejarah umat beragama hingga saat ini. Konflik-
konflik keagamaan bisa saja muncul kapan pun. Sehingga
bagaimana seharusnya sikap umat beragama memaknai konflik-
konflik ini dan bagaimana seharusnya melakukan resolusi untuk
meminimalisir kemunculannya menjadi fokus dari refleksi filosofis
tulisan ini.
Multikulturalisme Religius tanpa Konflik: Mungkinkah?
Konflik adalah bagian dari kehidupan manusia, namun ia
bukan merupakan tujuan dari kehidupan manusia. M. Amin
Abdullah menyebut bahwa konflik adalah min lawazim al-hayah
(konflik adalah bagian dari kewajaran hidup). “Dalam era apapun,
di mana pun dan kapan pun umat manusia tidak pernah terbebas
dari konflik, pertengkaran dan perselisihan.”4 Konflik selalu
mewarnai kehidupan manusia baik secara pribadi maupun kolektif.
Ia bisa terjadi dalam kehidupan diri pribadi manusia, dalam
kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, baik sosial,
budaya, politik maupun agama. Orang secara perorangan sering
terlibat konflik dengan dirinya sendiri, atau sering disebut orang
dengan konflik batin atau konflik kejiwaan.
Motivasi orang untuk tetap bisa bangkit dan bertahan hidup
adalah kebutuhan-kebutuhan hidupnya,5 mulai dari pemenuhan
kebutuhan pokok seperti makan, sandang, dan papan, sampai
kebutuhan non-pokok seperti pasangan hidup, hiburan, ekspresi
seni, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki cara yang berbeda
3
Graham E. Fuller, A World Without Islam (New York: Little, Brown and
Company, 2010), 348.
4
M. Amin Abdullah, “Peran Pemimpin Politik dan Agama dalam Mengurai dan
Resolusi Konflik dan Kekerasan” dalam Alim Roswantoro dan Abdul Mustaqim
(ed.), Antologi Isu-isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat (Yogyakarta:
Prodi Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan Penerbit Idea
Press, 2010), 1.
5
Henry Murray, Explorations in Personality (New York: Oxford University,
1938), 77-79.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga potensi konflik bisa
berawal dari sini. Hal ini menjadi masuk akal karena banyak
kebutuhan yang ingin diwujudkan, dalam proses pewujudan
kebutuhan-kebutuhan, tersembunyi di dalam diri mereka
kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi, sosial, budaya,
keagamaan, bahkan politik. Poitras dan Renaud menyebut
kenyataan ini sebagai wajar, dan bahkan keduanya memandang
mustahil ada kehidupan tanpa konflik. Kedua pemikir ini, dalam
pendahuluan bukunya menyatakan,
“It would be utopian to think that countries with millions of
inhabitants could go forever without any sort of conflict
arising. We all have different interests, and every public project
or policy, be it local or national in scope, impacts directly or
indirectly on those interests. Similarly, a dispute which initially
private may become public if it extends beyond the immediate
parties. “6
(Akan menjadi angan-angan kosong untuk berpikir bahwa
negara-negara dengan berjuta-juta penduduk dapat melangsungkan
hidupnya tanpa adanya konflik. Kita semua memiliki kepentingan-
kepentingan yang berbeda-beda, dan setiap proyek atau kebijakan
publik, apakah ia dalam lingkup lokal atau nasional, secara
langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kepentingan-
kepentingan tersebut. Sama halnya, suatu percekcokan yang
awalnya bersifat pribadi bisa menjadi publik jika ia meluas
melampaui kelompok-kelompok sosial yang ada).
Di masa lalu, berbagai konflik religius telah terjadi di
Indonesia, baik konflik antar perbedaan pemahaman atau konflik
keyakinan dalam suatu agama tertentu serta konflik antar agama,
hal ini menunjukkan bahwa pendapat Poitras dan Renaud benar
dengan fakta tidak mungkin menjalani kehidupan religius yang
berbeda-beda di Indonesia tanpa konflik-konflik religius. Masa
mendatang memang belum terjadi, namun tidak ada jaminan masa
yang akan datang hubungan hidup antar agama dan antar
kepercayaan di Indonesia akan steril dari konflik-konflik religius.
6
Jean Poitras and Pierre Renaud, “Introduction,” dalam Mediation and
Reconciliation of Interest in Public Disputes (Ontario: Carswell Thomson
Professional Publishing, 1997), 1.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Ada dua kemungkinan apakah multikulturalisme religius bisa
dijalankan tanpa konflik. Pertama, utopia karena dilihat dari
faktanya konflik religius tidak mungkin bisa dihindari di tengah
kehidupan masyarakat yang ragam agama dan budaya. Kedua, bisa
terjadi multikulturalisme tanpa konflik selama insan religius
mendorong dirinya sendiri dan orang-orang religius di sekitarnya
untuk selalu mempersiapkan diri mengantisipasi adanya konflik
dengan cara yang mampu menurunkan eskalasi (deescalation) dan
mengatasi konflik secara damai serta komunikatif. Ketika
kehidupan religius dalam keadaan damai dan harmoni, upaya
strategis untuk memperbanyak manusia-manusia religius dengan
karakter selalu respek, toleran, dan berlapang dada terhadap
komunitas agama lain, sering luput untuk dilakukan. Ada pendapat
tentang bom waktu tersembunyi yang siap mengubah keadaan
religiusitas, sehingga setiap umat beragama berperan untuk
mengantisipasi hal tersebut. Dengan cara demikian, konflik religius
seolah mengatakan pada kita bahwa harmoni dan kedamaian
religius antar umat beragama bukan merupakan sesuatu yang
didapat, melainkan sesuatu yang terus diperjuangkan.
Konflik dan Kebijaksanaan Pembelajaran Keberagamaan
Bagi Fiadjoe, secara potensial ada tiga hal yang menjadi asal-
usul munculnya konflik, yaitu nilai-nilai yang berbeda, kebutuhan-
kebutuhan dasar yang tak terpenuhi, sumber-sumber yang terbatas.
Pertama meliputi keyakinan-keyakinan, prioritas-prioritas, prinsip-
prinsip, dan kepercayaan-kepercayaan. Kedua mencakup
kepemilikan, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sementara
yang ketiga, atau sumber-sumber terbatas yang dimiliki manusia
meliputi waktu, uang, dan barang-barang yang dimiliki.7 Bagan di
bawah menjelaskan tentang The origins of conflict menurut
Fiadjoe:
Bagan Asal-usul Konflik8
AWAL-MULA KONFLIK
Nilai-Nilai Yang BBerbedaKebutuhan Dasar Tak Ditemui Sumber-Sumber Terbatas
Rasa memiliki Waktu
Kekuasaan Uang
7 Keyakinan
Albert Fiadjoe, Alternative Dispute
Prioritas
KebebasanResolution: A Developing World
Properti
Perspective (London. Sydney,Kesenangan
Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited,
Prinsip
2004), 9.
Kepercayaan
8
Ibid. 10
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Pandangan Watkins, seperti dikutip oleh Robbi I. Candra, 9 ada
dua hal penyebab terjadinya suatu konflik. Pertama, secara
potensial dan praktis/operasional, pihak-pihak yang terlibat
memiliki kemampuan untuk saling menghambat, sehingga dengan
jalan demikian konflik bisa terjadi. Kedua, konflik bisa terjadi
apabila ada suatu sasaran yang sama-sama dikejar, namun hanya
satu yang pada akhirnya harus mendapatkannya. Contoh untuk
yang pertama, ada dua institusi sekolah agama yang berbeda aliran,
dalam suatu wilayah yang sama, dan berebut untuk mendapatkan
murid. Untuk tujuan ini, kedua belah pihak sama-sama memiliki
potensi untuk melakukan aksi-aksi penghambatan publik untuk
tidak memilih sekolah yang menjadi pesaing, misanya dengan
membuat provokasi-provokasi tentang kelemahan sekolah melalui
sosialisasi publisitas sekolah. Sementara contoh untuk yang kedua,
tentang dua orang yang menjadi kandidat suatu jabatan penting
dalam suatu perusahaan. Perusahaan hanya membutuhkan salah
satu di antara keduanya. Persaingan ini bisa berkembang menjadi
konflik. Karena pihak manajemen perusahaan tidak mungkin
memenuhi keinginan keduanya sekaligus, maka keduanya secara
potensial dapat terlibat dalam suatu konflik.
Konflik-konflik yang terjadi, umumnya berawal dari konflik
tingkat antar individu, kemudian berkembang antar kelompok,
organisasi, partai-partai, etnis, agama, dan bahkan antar masyarakat
yang lebih besar cakupannya. Ragam individu, organisasi, partai,
etnis, agama dan kelompok-kelompok sosial lain yang terlibat
semakin meningkat dan lingkup yang dipertentangkan juga
berkembang kompleks mulai dari masalah ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Intensitas pertentangan yang semakin eskalatif dan
rumit menggambarkan suatu dinamika konflik. Dinamika konflik
9
Robby I. Chandra, Konflik dalam Hidup Sehari-hari (Yogyakarta: Penerbit
Kanisius, 1992), 20-21.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
dan situasinya ditentukan oleh isu-isu yang mendasari
pertentangan, seperti kepentingan-kepentingan yang berseberangan
atau cara-cara yang berlawanan dirasakan, dipahami, dan
diperdebatkan oleh banyak orang dengan latar sosial, budaya,
politik, ekonomi dan keagamaan yang berbeda-beda dalam rangka
memuaskan suatu kepentingan umum bersama. Dinamika konflik
yang berkembang sangat kompleks tentu membutuhkan
penanganan manajemen yang rumit pula dan memakan waktu lama
dalam menegosiasikan, memediasi, dan mengkomunikasikan
kemungkinan-kemungkinan terbaik dengan prinsip sebesar
mungkin keuntungan dan sekecil mungkin kerugian yang dirasa
semua pihak. Memahami dinamika konflik, dengan demikian, bisa
diperhatikan dari:
1. Aspek kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, dan nilai-nilai
apa yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak yang
berselisih.
2. Siapa-siapa saja yang berperan dan memainkan masalah-
masalah yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak yang
berselisih.
3. Bagaimana alat-alat dan sumber-sumber, desain, dan tabel
waktu yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak yang
berselisih.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Bagan Dinamika Konflik10
APA APA
Kepentingan-kepentingan CONFLICTING Kepentingan-kepentingan
Tujuan-tujuan GOALS Tujuan-tujuan
Nilai-nilai Nilai-nilai
PEMAIN Ekonomi PEMAIN
Sosial
Individu Politik Individu
Kelompok Etnik Kelompok
Organisasi Agama Organisasi
Negara Lingkungan Negara
dll.
BAGAIMANA BAGAIMANA
Alat & sumber CONFLICTING Alat & sumber
Desain MEANS Desain
Tabel waktu Tabel waktu
Konflik adalah sesuatu yang bergerak, bukan sesuatu yang
statis. Gerakan eskalatif atau deeskalasi nya bisa bervariasi, yang
jelas kadang-kadang dalam keadaan laten dan kadang-kadang
manifes. Semakin lama konflik tidak diantisipasi dan ditangani
dengan baik-efektif, semakin kompleks dan rumit konflik dan
semakin terbuka lebar pada terjadinya kekerasan dan perang.
Eskalasi konflik merupakan tanda adanya kegagalan suatu resolusi
konflik. Jadi konflik bukanlah hal yang harus dilihat secara statis,
melainkan dinamis. Lihat eskalasi konflik dalam bagan berikut:
Bagan Eskalasi Konflik
Perang Habis-habisan atau
Konflik Berakar Kuat dan Dalam
Polarisasi Kelompok Konflik
Konflik Manifes atau Konflik Terbuka
Konflik Laten atau Ketegangan
10
Bagan ini diambil dari Jean Poitras and Pierre Renaud, Mediation and
Reconciliation of Interest in Public Disputes (Ontario: Carswell Thomson
Professional Publishing, 1997), 9, dengan sedikit modifikasi.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Beragama merupakan kebutuhan hidup manusia. Meskipun
tidak semuanya, namun tidak salah mengatakan bahwa kebanyakan
manusia memerlukan agama. Beragama bukan merupakan
kebutuhan material manusia, namun merupakan kebutuhan spiritual
manusia. Mendasarnya kebutuhan ini bagi nilai dan makna
kehidupan orang, dan karena ragam agama dan kepercayaan yang
dipegangi, kehidupan beragama dari komunitas-komunitas umat
yang ragam agama dan kepercayaan rentan terhadap terjadinya
konflik. Konflik-konflik religius, boleh dibilang tidak jauh beda
dari konflik-konflik manusia pada umumnya, seperti dalam
penjelasan Fiadjoe di atas, muncul dari perbedaan nilai, dari tidak
terpenuhinya kebutuhan dasar, dan sumber-sumber yang terbatas.
Konflik-konflik religius muncul dari perbedaan nilai terutama
nilai kepercayaan. Bagi agama tertentu memandang patung yang
disembah dalam suatu agama sebagai berhala yang tidak suci,
sementara bagi agama yang meyakini memandangnya suci. Dalam
wilayah pribadi keyakinan yang memandangnya tidak suci tidaklah
menjadi soal, namun ketika dilontarkan dalam ranah publik bisa
menyinggung keyakinan yang memandangnya suci, dan bisa
menimbulkan konflik religius antara yang tidak meyakini dan yang
meyakini. Konflik-konflik religius muncul dari tidak terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti kebebasan menjalankan
keyakinan dan ritual agama dan kebebasan mendirikan tempat
ibadah. Problem ini sangat menonjol di negara-negara yang multi
agama. Problem kesulitan mendirikan tempat sembahyang di
Indonesia bagi warga kristiani banyak terjadi di tengah-tengah
komunitas yang mayoritas muslim. Di daerah lain, seperti di Bali,
bagi warga muslim juga tidak mudah dan serta merta bisa
mendirikan tempat ibadah di sembarang tempat; hal yang sama
juga bisa ditemukan di Papua, Manado dan daerah-daerah lain yang
mayoritasnya adalah kristiani.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Secara umum, warga kristiani barangkali mengalami kesulitan
mendirikan tempat sembahyang di Indonesia, tetapi harus diingat
juga tidak mudah bagi warga muslim di Eropa dan di Amerika bisa
mendirikan tempat ibadah atau islamic center. Pemenuhan
kebutuhan dasar religius sering terhalang dengan problem
mayoritas-minoritas. Konflik-konflik religius muncul dari sumber-
sumber yang terbatas. Sumber-sumber terbatas bisa berupa uang
atau dana yang melimpah mungkin bisa dimiliki baik yang
minoritas dan mayoritas, ketika penggunaannya yang tidak
menimbang perasaan yang lain tentu bisa memicu konflik, bisa
juga berupa sedikitnya penganut, sehingga kurang kuasa dalam
menghadapi hambatan dari pihak yang banyak penganut.
Konflik religius yang berasal dari tiga sumber tersebut muncul
hanya jika ada pihak-pihak religius yang satu memberikan
hambatan bagi pihak religius lainnya. Jika kedua pihak religius
saling menghambat dan terus mengembangkan hambatan-
hambatan, dari teori Watskin di atas, maka konflik religius menjadi
semakin eskalatif dan bisa terus memanas berkembang menjadi
konflik fisik. Mungkin awal konfliknya antar individu yang
berbeda agama. Jika mereka saling memprovokasi yang bernada
penistaan agama, maka konflik bisa berkembang menjadi konflik
religius yang bersifat antar kelompok. Ini karena provokasi dari
masing-masing individu di dalam komunitas religiusnya masing-
masing bekerja dan berhasil memancing emosi kelompoknya. Jika
pekerjaan saling menghambat dari kedua belah pihak terus
dibiarkan berkembang, maka konflik religius yang bersifat terbuka
dan meluas bisa terjadi. Pada tahap selanjutnya, konflik-konflik
religius dengan kepentingan, prinsip, dan nilai kepercayaan yang
berbeda bisa muncul dan menambah kompleks wajah konflik
religius.
Konflik bukanlah racun kehidupan, melainkan “bunga”
kehidupan. Pengalaman hidup manusia memberitahu kita bahwa
racun itu membahayakan dan bahkan mematikan, sementara bunga
yang kita lihat di taman, selain penuh warna, dalam proses
selanjutnya akhirnya ia menjadi buah yang memberi kesenangan
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
dan kebahagiaan bagi yang memanfaatkannya. Sama halnya
dengan berbagai kehidupan religius di Indonesia yang timbul-
tenggelam dalam penggal-penggal ruang-waktu historis berjalan
dari dulu hingga kini, bahkan selalu ada kemungkinan sampai di
masa-masa sesudah sekarang. Konflik kehidupan religius antar
umat beragama, baik yang intra maupun antar agama, adalah
bagian dari proses kehidupan religius manusia Indonesia, yang
tidak boleh dianggap oleh para pihak religius sebagai tujuan dari
kehidupan religius manusia Indonesia.
Konflik-konflik religius adalah “bunga” bagi kehidupan
religius manusia Indonesia. Kesadaran bahwa konflik-konflik
religius merupakan bagian dari komunikasi religius antara ragam
umat beragama selalu akan memberi “buah” atau hasil kehidupan
religius yang lebih matang. Oleh karena itu, lebih baik bagi setiap
insan religius di Indonesia merenungkan konflik-konflik religius
yang pernah terjadi di Indonesia sebagai tanda yang maknanya
secara semiotik harus diproduksi. Jika kehidupan religius tanpa
konflik religius tak terhindarkan, maka apa makna yang bisa
diungkapkan dari tanda seperti itu. Apakah ia menandakan bahwa
agama memang merupakan sumber konflik, atau apakah ia
menandakan sesuatu yang lain mengenai suatu makna hakiki dari
keberagamaan? Jika yang pertama dibenarkan, lalu bagaimana
dengan fakta kehidupan lain yang juga tidak berjalan tanpa konflik,
apakah lalu kita mengatakan semua bidang hidup manusia adalah
sumber konflik. Maka lebih arif mengambil kemungkinan yang
kedua, adanya konflik religius yang kita terlibat di dalamnya berarti
menandakan suatu makna mengenai apakah keberagamaan kita
sudah baik. Jika kita marah, memaki-maki atas konflik religius
yang terjadi, dan kemarahan dan makian ditujukan untuk
pembelaan keagamaan kita, maka berarti kita di dalam ruang
religius pribadi kita sedang terjadi konflik. Kita tidak bisa berdamai
dan harmoni dengan diri kita sendiri. Barangkali marah dan makian
akan memiliki makna yang lebih agung jika kita memaknai diri kita
yang belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri sebagai belum
matang secara religius.
Kemarahan dan makian ini biasanya datang dari komunitas
beragama yang kecil. Sebaliknya kita yang datang dari komunitas
religius besar, pantaskah kita merasa bangga, menang, dan kuat
setelah mampu menghalangi komunitas religius kecil yang ingin
menjalankan kebebasan beragamanya. Jika kita merasa pantas
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
dengan kebanggaan, kemenangan, dan kekuatan karena telah
mampu membuat komunitas religius kecil tak berdaya, maka
sungguh kita telah jatuh sedalam-dalamnya dari makna agung
keberagamaan sejati. Keberagamaan kita hancur karena
kecongkakan jiwa kita karena merasa paling benar tindakan
religiusnya. Keberagamaan yang benar tampaknya merupakan
keberagamaan yang selalu bisa harmoni dengan dirinya sendiri
meski harus memberi ruang kebebasan beragama dari orang
beragama yang berbeda. Demikian juga dari pihak yang telah diberi
ruang kebebasan beragamanya harus bisa berdamai dengan hatinya
sendiri dengan menghargai orang beragama yang telah memberi
ruang kebebasan beragama kepada dirinya. Diri religius sejati
adalah diri yang selalu meluap kebahagiaannya ketika diri-diri lain
yang berbeda agama dan kepercayaan bisa menjalankan kebebasan
beragama dan memeluk kepercayaan mereka. Jika setiap diri
religius bisa menangkap makna religiusitas sejati maka konflik-
konflik religius yang terjadi dilihatnya sebagai medan ujian bagi
kualitas keberagamaan untuk selalu menjadi lebih baik dan lebih
baik.
Konflik religius harus dilihat sebagai ruang komunikasi di
antara pihak-pihak yang terlibat konflik untuk saling mengasah
kedewasaan dalam beragama. Banyak kita temukan orang yang
menjadi hinduis, buddhis, kristiani, muslim dan lain sebagainya,
tetapi bisakah kita menemukan banyak hinduis, buddhis, kristiani,
muslim dan lain sebagainya yang matang keberagamaan mereka di
Indonesia. Memang banyak orang hindu, memang banyak orang
Buddha, memang banyak orang kristiani, dan memang banyak
orang muslim di Indonesia, namun sedikit orang hindu, sedikit
orang Buddha, sedikit orang kristiani, dan sedikit orang muslim
yang matang keberagamaan mereka di Indonesia. Banyak orang
beragama, tetapi sangat sedikit barangkali yang dewasa atau
matang keberagamaannya.
Resolusi Konflik Keagamaan di Indonesia
Resolusi konflik bagi Mc Cartney berarti suatu upaya manusia
untuk mengatasi konflik yang terjadi di antara manusia tidak lain
hanya untuk tujuan menganjurkan hubungan-hubungan komunitas
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
yang baik.11 Sementara yang dipandang penting dari resolusi
konflik bagi Samsu Rizal Panggabean, menyepakati pandangan
Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, adalah
menghindarkan konflik dari pecahnya kekerasan fisik dan apalagi
bersenjata. Tampak dalam pandangannya bahwa resolusi konflik
memiliki makna pengelolaan konflik untuk tidak berkembang
menjadi kekuatan destruktif, melainkan menjadi kekuatan
konstruktif. Dalam makna resolusi konflik seperti ini diasumsikan
bahwa kekerasan fisik dan bahkan bersenjata bukannya tidak bisa
dihindari. Kekerasan fisik dan bahkan bersenjata bisa dijauhkan
dari terjadi asalkan cara-cara dan usaha-usaha tertentu dibuat, dan
inilah yang dimaksudkannya dengan resolusi konflik.12
Batasan pengertian ini memunculkan persoalan apakah
penanganan konflik dengan menggunakan kekuatan fisik dan
bersenjata —karena alasan jalan komunikasi dan rekonsiliasi
dipandang buntu, dan bila dibiarkan berpotensi besar memunculkan
konflik yang lebih parah— tidak bisa dibenarkan dalam pengertian
resolusi konflik. Perdebatan mengenai apakah resolusi konflik
harus selalu diartikan tanpa penggunaan kekerasan atau tidak
merupakan persoalan yang menarik untuk didiskusikan. Lepas dari
pertanyaan ini, penulis sendiri mengakui bahwa resolusi konflik
yang ideal dan sejati memang penanganan konflik yang tanpa
menggunakan kekerasan.
Prinsip utama dalam resolusi konflik adalah prinsip
berkeadilan dan setara dalam memperlakukan para pihak yang
terlibat konflik. Cara terbaik untuk mengimplementasikan prinsip
ini adalah memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang
dipertentangkan dari dalam kesadaran dan kemauan para pihak
11
Clem McCartney, “Approaches To Ethnic And Religious Conflict Resolution:
Managing, Resolving Or Transforming” dalam Taryono (ed.), The Making of
Ethnic and Religious Conflicts in Southeast Asia: Cases and Resolutions
(Yogyakarta, Penang: Center for Security and Peace Studies (CSPS) Universitas
Gadjah Mada & Southeast Asian Conflict Studies Network (SEACSN) Universiti
Sains Malaysia, 2004), 69.
12
Samsu Rizal Panggabean, “Approaches to Ethnic and Religious Conflict
Resolution” dalam Taryono (ed.), The Making of Ethnic and Religious Conflicts
in Southeast Asia: Cases and Resolutions. (Yogyakarta, Penang: Center for
Security and Peace Studies (CSPS) Universitas Gadjah Mada & Southeast Asian
Conflict Studies Network (SEACSN) Universiti Sains Malaysia, 2004), 54-57;
lihat juga Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, and Tom Woodhouse, Contemporary
Conflict Resolution (Cambridge: Polity Press, 1999), 96.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
yang berkonflik, bukan dipaksakan dari luar mereka. pokok dari
resolusi konflik adalah proses mediasi atau menengahi pihak-pihak
yang berkonflik untuk memperoleh pemecahan yang saling
menguntungkan. Sebelum melakukan proses mediasi penanganan
konflik, siapa pun yang ingin menangani dan mengatasi suatu
konflik, hal pertama yang harus diperhatikan, harus mengerti
dengan baik apa itu konflik. Penjelasan di atas mengenai makna
konflik harus dijadikan pegangan.
Noel, Shoemake, dan Hale merangkum makna konflik yang
dimaksud untuk kepentingan resolusi konflik sebagai berikut: [1]
konflik merupakan suatu aspek alamiah dari kehidupan dan harus
dilihat secara konstruktif; [2] konflik memperkuat orang untuk
menegaskan diri mereka sendiri dan berkomunikasi secara efektif,
bukan hanya membangun karakter tetapi juga mengembangkan
otonomi personal, efikasi diri yang positif, dan kerangka referensi
yang lebih realistis; [3] konflik berhubungan dengan pembelajaran
untuk mengenal emosi-emosi sebagai bagian penting dari
komunikasi efektif antar perasaan-perasaan personal; dan [4]
konflik berkaitan dengan penunggangan perspektif-perspektif
orang lain, mengurangi kesenangan pada reaksi-reaksi keras atau
kurang pantas sambil membangun empati. 13
Dalam menangani konflik, orang tidak boleh condong pada
yang kuat, berkuasa, dan kaya, tetapi juga tidak boleh hanya
mementingkan yang lemah, yang dikuasai, dan yang miskin. Kedua
sisi ini pasti ada dalam setiap konflik, makanya perlakuan yang
berimbang dan berkeadilan terhadap semua pihak yang terlibat
konflik menentukan keberhasilan penanganan konflik dan
menggiring mereka ke dalam kesadaran konflik sebagai
pembelajaran berharga untuk menentukan kebersamaan mereka
yang lebih berkualitas di masa depan.
Ada beberapa pemikir yang mencoba memberikan prinsip-
prinsip mediasi dalam resolusi konflik di antaranya Andrea
Morrison, dan Jean Poitras and Pierre Renaud, dan Fiadjoe. Bagi
13
Brett R Noel, Ann Torfin Shoemake, and Claudia L. Hale, “Conflict
Resolution in a Non-Western Context: Conversations with Indonesian Scholars
and Practitioners” dalam Conflict Resolution Quarterly, vol. 23, no. 4, Summer
(2006): 430-431.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Morisson,14 ada lima prinsip mediasi yang harus ada, yaitu sebagai
berikut:
1. Mediasi adalah proses pemecahan masalah; parameter
ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (Problem
solving process: parameters defined by parties).
2. Pendekatan berbasis kepentingan dengan fokus pada masa
depan (Interest based approaches with ‘future’ focus).
3. Penciptaan sesering mungkin pihak-pihak yang berkonflik
saling berbicara secara langsung (Parties often speak directly
to each other).
4. Fakta-fakta dan penalaran adalah penting (Facts and reasoning
are important).
5. Kesepakatan yang didasarkan pada hasil saling memuaskan
(Agreement based on mutual satisfaction).
Sementara bagi Poitras dan Renaud,15 prinsip mediasi terdiri
dari empat hal, yaitu:
1. Pencegahan Konflik dari Eskalasinya (Prevent conflict from
escalating),
2. Rekonsiliasi kepentingan-kepentingan (Reconcile interests),
3. pencarian suatu solusi saling memberi atau menguntungkan
(Seek a mutual-gain solution),
4. pengoordinasian usaha kerja sama pihak-pihak yang berkonflik
(Coordinate party effort).
Fiadjoe16 menyebut lebih banyak prinsip mediasi, yaitu ada
sembilan prinsip atau ciri umum, sebagai berikut:
1. Netralitas mediator (Neutrality of mediator),
2. Hakikat otoritas mediator; mediator tidak memiliki otoritas
untuk memaksakan penyelesaian pada pihak-pihak yang
berselisih (Nature of the mediator’s authority; The mediator
has no authority to impose a settlement on the disputants),
14
Andrea Morisson, “Module Workshop The Trainers Training of Alternative
Dispute Resolution”58.
15
Jean Poitras and Pierre Renaud, Mediation and Reconciliation of Interest in
Public Disputes, (Ontario: Carswell Thomson Professional Publishing, 1997),
35.
16
Albert Fiadjoe, Alternative Dispute Resolution: A Developing World
Perspective,( London. Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited,
2004 ), 59-60.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
3. Resolusi konsensual (Consensual resolution),
4. Pemaksimalan kepentingan-kepentingan (Maximisation of
interests),
5. Penetapan lingkungan yang aman (Provision of secure
environment),
6. Penawaran kerahasiaan (Offer of confidentiality),
7. Ketidakmampuan menawarkan saran independent (Inabiity to
offer independent advise),
8. Pemberdayaan pihak-pihak yang berkonflik (Empowerment of
parties),
9. Pemeliharaan hubungan (Maintenance of relationships ).
Dari ketiga pendapat ini, prinsip-prinsipnya dapat
dikombinasikan menjadi sebagai berikut: Mediasi adalah proses
pemecahan masalah; parameter ditentukan oleh pihak-pihak yang
terlibat konflik, rekonsiliasi dan pemaksimalan kepentingan-
kepentingan, pengondisian sesering mungkin pihak-pihak yang
berkonflik saling berbicara secara langsung, pemeliharaan
hubungan, pemberdayaan pihak-pihak yang berkonflik, pentingnya
fakta-fakta dan penalaran, pengoordinasian usaha kerja sama pihak-
pihak yang berkonflik, dan kesepakatan yang didasarkan pada hasil
saling memuaskan dan menguntungkan yang berorientasi ke masa
depan.
Resolusi konflik untuk konflik-konflik keagamaan di Indonesia
sebenarnya telah sering dilakukan oleh orang-orang beragama
sendiri, di samping oleh pihak-pihak lain seperti pemerintah.
Konflik antara kelompok kristiani dan muslim tertentu, dan antara
kelompok hindu dan muslim tertentu, misalnya, selalu ada
kelompok kristiani, hindu, dan muslim lain yang merasa prihatin
dan mendorong untuk melakukan upaya-upaya pengharmonian
kembali. Yang ingin ditekankan di sini dari ungkapan ini adalah
bahwa setiap orang beragama bisa menjadi mediator yang baik
untuk menangani konflik-konflik religius yang terjadi demi
pembangunan kedamaian dan keharmonian hidup religius. Tentu
saja membangun hidup beragama yang damai dan komunikatif
tidak hanya dilakukan oleh orang-orang beragama saja, apalagi
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
oleh tokoh-tokoh agama saja tetapi banyak pihak yang bisa
berperan. David Litte dan Scott Appleby
Pembangunan perdamaian religius memiliki arti yang tidak
jauh beda dengan pembangunan perdamaian secara umum. Ia
menggambarkan lingkup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh
pelaku-pelaku dan institusi-institusi religius yang bermaksud untuk
memecahkan dan menransformasikan konflik yang
membahayakan. Maksud tersebut memiliki tujuan untuk
membangun hubungan-hubungan sosial dan institusi-institusi
politik yang dicirikan dengan suatu semangat toleransi dan tanpa
kekerasan. Pembangunan perdamaian religius tidak hanya berarti
melakukan usaha-usaha manajemen dan resolusi konflik di tempat-
tempat konflik. Ia juga dipengaruhi kuat oleh usaha-usaha orang
yang bekerja jauh di luar tempat-tempat terjadinya konflik, seperti
advokat-advokat hukum tentang hak-hak asasi religius manusia,
sarjana-sarjana yang melakukan riset yang berkaitan dengan dialog
lintas budaya dan lintas agama, dan teolog serta para ahli etika
dalam komunitas-komunitas agama yang menanggulangi dan
memperkuat tradisi-tradisi anti kekerasan mereka.17
Siapa pun yang ingin terlibat melakukan pembangunan
perdamaian religius di Indonesia dan melakukan upaya-upaya
resolusi konflik, maka prinsip-prinsip dasar mediasi dalam resolusi
konflik di atas harus diindahkan. Upaya mediasi atau rekonsiliasi,
atau dalam konsep Islam dikenal dengan istilah shulh, bertujuan
untuk mempromosikan, memperjuangkan dan mewujudkan
perdamaian. Sebelum mengurai langkah-langkah resolusi konflik
yang seperti apakah untuk meminimalkan konflik religius di
Indonesia, oleh karena itu, perlu dimengerti dulu apa yang
dimaksudkan dengan perdamaian.
Menurut Dower, Perdamaian bisa dipahami dalam pengertian
negatif dan positif. Pertama pengertian negatif, peace is a minimal
17
David Litte and Scott Appleby, “A Moment of Oppurtunity? The Promise of
Religious Peacebuilding in an Era of Religious and Ethnic Conflict”, dalam
Harold Coward and Gordon S. Smith (eds.), Religion and Peacebuilding
(Albany, New York: State University of New York Press, 2004), 5.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
relation between different human beings or groups of human
beings. “…It exists when there is no war or active violence between
the parties in volved.”18 (perdamaian adalah suatu hubungan
minimal antara orang atau kelompok-kelompok orang yang
berbeda-beda ... Ia ada ketika tidak ada perang atau kekerasan aktif
antara kelompok-kelompok yang terlibat); Kedua pengertian
positif, terinspirasi dari pemikir Macquarrie dan Curle, “Peace …
is regarded as a state of harmony or wholeness, ‘shalom’ or a set of
peaceful relationships between people and groups characterized by
love, mutual respect, sence of justice, or lack of fracture.” 19
(Perdamaian … dianggap sebagai suatu keadaan harmoni atau
keutuhan, “shalom” atau sederet hubungan-hubungan damai antar
orang dan kelompok-kelompok orang yang dicirikan dengan cinta,
salang menghargai, rasa keadilan, atau kurangnya perpecahan).
Pandangan Islam tentang perdamaian diperkuat dengan salah
satu pemikir muslim Amerika, J.E. Rash yang menegaskan bahwa
Islam lebih mengapresiasi perdamaian dalam pengertian positif,
karena perdamaian, keamanan, kasih sayang yang sesungguhnya
sebenarnya merupakan dimensi spiritualitas manusia. J.E. Rash
memandang perdamaian sebenarnya ada di dalam diri manusia itu
sendiri, dan itulah mengapa definisi perdamaiannya seperti berikut
ini:
“Peace is composed of attributes that enter and exit our
hearths and minds throughout our lives. Peace comes in
moments of compassion, of patience, of error and repentance,
of forgiveness. It comes in bursts of creativity, in the awareness
of limitations, in a sense of destiny. …peace depends on more
than structures, on more than laws, and more than social
principles. It depends on establishing peace within human
beings.”20
18
Nigel Dower, An Introduction to Global Citizenship (Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2003), 69.
19
Ibid. Lihat J. Macquarrie, The Concept of Peace (New York: Harper and Row,
1973) dan A. Curle, True Justice (London: Quaker Home Service, 1981).
20
J.E. Rash, Islam and Democracy: A Foundation for ending extrimsm and
preventing conflict (Wingspan, 2006),31.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
(Perdamaian terdiri dari sifat-sifat yang memasuki dan keluar
dari hati-hati dan pikiran-pikiran kita sepanjang hidup kita.
Perdamaian masuk dalam momen-momen belas kasih, kesabaran,
kesalahan dan pertobatan, dan pengampunan. Ia masuk dalam
ledakan-ledakan kreativitas, dalam kesadaran atas keterbatasan-
keterbatasan, dalam suatu perasaan takdir. … perdamaian
bergantung pada lebih dari sekedar struktur-struktur, pada lebih dari
sekedar hukum-hukum, dan lebih dari sekedar prinsip-prinsip
sosial. Ia bergantung pada penegakan perdamaian di dalam diri
manusia).
Pengalaman-pengalaman konflik manusia telah memberinya
pengalaman-pengalaman berbuat salah atau bahkan kejam,
memandang rendah orang lain, mau menang sendiri, dan
seterusnya; dan juga telah memberinya pengalaman-pengalaman
direndahkan, dicibirkan, dihina, ditipu, dipinggirkan, dianiaya, dan
seterusnya. Menyikapi secara positif pengalaman-pengalaman
tersebut, orang menjadi sadar dari kesalahannya, memohon ampun
dan maaf, dan mulai mencoba menghargai eksistensi orang atau
masyarakat lain; orang menerima kenyataan dengan kesabaran,
tidak membalas, dan mudah memberi maaf. Orang, masyarakat,
dan negara dari waktu ke waktu mengaca pada pengalaman-
pengalaman yang mungkin tidak diinginkan manusia seperti
konflik dan peperangan. Mereka belajar mengerti keinginan,
kebutuhan, dan kepentingan pihak lain, belajar menghubungkan
keinginan, kebutuhan, dan kepentingan pihak lain itu dengan
keinginan, kebutuhan, dan kepentingan mereka sendiri dengan
cara-cara yang baik di bawah spirit cinta-kasih kemanusiaan dan
saling menghargai satu sama lain. Dalam proses inilah perdamaian
yang sesungguhnya bisa diharapkan.21
Konflik-konflik keagamaan di Indonesia harus ditangani
terutama oleh orang-orang religius Indonesia itu sendiri, karena
tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Setiap agama pasti
menganjurkan kebaikan dan kedamaian. Jika konflik-konflik antar
orang beragama terjadi, berarti masih ada masalah dalam beragama
kita. Kesalahan ini bukan dari ajaran agamanya, melainkan dari
ajaran orang beragamanya. Orang-orang beragama yang sadar akan
21
Alim Roswantoro, “Islam dan Pembangunan Perdamaian: Mengenal
Pemikiran J.E. Rash” dalam Teologia Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, Fakultas
Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, vol 20, Nomor 1( Januari 2009) : 189.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
hal ini sebagai ketidakmatangan dalam beragama harus mengambil
inisiatif untuk memperbaiki cara beragama yang baik dan
manusiawi. Salah satu, yang paling mudah dipahami, dari ciri
beragama yang baik adalah sikap membenci egoisme, kekerasan
dan ketidakadilan, dan menganjurkan kerja sama, toleransi, dan
keadilan yang muncul dari kesadaran dari dalam diri manusia
beragama itu sendiri, bukan dari luar atau dipaksakan melalui
kekuasaan.
Pemuka-pemuka agama dan para intelektual dan peneliti
agama di Indonesia harus diberdayakan menjadi motor mediasi dan
rekonsiliasi atas konflik-konflik religius yang ada. Sebagai motor
berarti mereka mengondisikan sebanyak mungkin manusia
beragama sebagai mediator dan pemersatu hidup dalam
masyarakat. Para mediator ini pada gilirannya akan menggerakkan
institusi-institusi keagamaan dan masyarakat mereka menjadi agen-
agen peacebuilder of religious life, dan mendorong negara untuk
menjadi penguat membangun kedamaian religius secara netral dan
lepas dari sikap-sikap yang menunjukkan favoritisme keagamaan.
Dengan prinsip-prinsip mediasi yang telah diurai di atas, manusia-
manusia religius sebagai mediator konflik-konflik keagamaan
mendorong komunitas-komunitas religius yang berbeda-beda di
Indonesia menemukan common ground yang bisa saling merasa
saling puas dan saling diuntungkan sehingga kepentingan-
kepentingan masing-masing bisa saling didapatkan tanpa cara-cara
kekerasan. Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai ijtihad
merubah wajah kehidupan religius Indonesia ke depan yang lebih
baik, dan ini sebagai upaya resolusi konflik sepanjang hayat di
antaranya adalah sebagai berikut:
1. Mengajak orang-orang beragama, baik yang belum pernah
terlibat konflik maupun yang pernah terlibat konflik, berpikir
dari realitas keragaman fakta agama dan keragaman fakta
keberagamaan, dengan mendiskusikan bagaimana agama-agama
yang berbeda itu ada, bagaimana pengaruh-pengaruh budaya
dalam proses pemahaman keagamaan, dan bagaimana
pentingnya membangun saling belajar dari perbedaan,
merupakan hal yang harus diberikan di komunitas-komunitas
agama masing-masing melalui forum-forum keagamaan maupun
pendidikan-pendidikan keagamaan di sekolah.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
2. Menjadikan komunitas-komunitas religius dan budaya yang
beragam agama/keyakinan dan beragam etnis sebagai
laboratorium pembelajaran agama pluralistik-multikultural.
Pendekatan yang dipakai jangan sekedar idea to idea approach,
melainkan person to person or people to people approach.
Jangan sekedar memberikan sederet teori-teori mengenai
perbedaan, tetapi kondisikan mereka untuk bercerita mengenai
dunia budaya dan agama masing-masing dengan menunjukkan
suka-duka, harapan yang diinginkan dan tidak diinginkan, dan
kemudian berbagai bersama secara komunikatif dan menemukan
harapan bersama apa yang diinginkan dan tidak diinginkan, dan
sikap-perilaku apa yang mereka bersama kehendaki dan tidak
kehendaki untuk bisa saling memberi ruang eksistensi masing-
masing.
3. Memberi pengalaman langsung mengenai kegiatan bersama
yang bersifat lintas agama dan lintas budaya. Kegiatan semacam
ini memerlukan suatu desain pembelajaran yang bersifat
kolaboratif antar komunitas-komunitas religius yang beragama
tersebut. Muatan kegiatan sebaiknya lebih bersifat sosial
daripada religius, yakni bukan bicara masalah doktrin religius,
tetapi bekerja bareng dalam urusan-urusan sosial-kemanusiaan.
Tujuan dasarnya adalah menanamkan perasaan tanggung jawab
bersama atas berbagai persoalan publik di ruang publik. Di
ruang privat, masing-masing memiliki aturan kepercayaan dan
moral sendiri-sendiri, namun di ruang publik, ada aturan main
bersama yang sama-sama harus dijunjung tinggi untuk
memperkuat kemanusiaan “tanpa baju” perbedaan.
4. Pengetahuan dan ketrampilan mengenai conflict resolution dan
peacebuilding sangat penting diberikan kepada orang-orang
beragama yang hidup dalam masyarakat yang multireligius dan
multikultural. Dalam kehidupan yang pluralistik-multikultural,
perbedaan-perbedaan berpotensi kuat memunculkan gesekan-
gesekan, ketegangan-ketegangan, dan konflik-konflik. Tanpa
pengetahuan dan ketrampilan melakukan penanganan konflik
dan pembangunan perdamaian tidak akan terjadi penguatan
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
masyarakat pluralistik-multikultural. Yang terpenting dari hal ini
adalah bahwa pembiasaan sikap hidup yang tidak merendahkan,
menghina, melecehkan, dan melukai orang karena ia berbeda
merupakan pencegahan yang efektif untuk memunculkan
ketegangan dan konflik. Prinsip-prinsip resolusi konflik yang
telah diurai di atas harus dikenal dengan baik oleh sebanyak
mungkin manusia beragama di Indonesia. Tempat-tempat
ibadah, forum-forum agama, sekolah, dan lain sebagainya
merupakan sarana strategis untuk memberikan pengetahuan dan
ketrampilan ini.
5. Membuat forum-forum lintas agama/iman untuk menjalankan
kegiatan pemberdayaan sosial dan kegiatan berekonomi.
Membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari
komunitas lintas agama untuk pemberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat pedesaan dan pinggiran kota berbasis
keagamaan sangat strategis untuk saling mendekatkan kesadaran
bersama sebagai manusia meskipun berbeda tetapi saling
memberdayakan untuk kepentingan sosial bersama dan
pemenuhan kecukupan hidup secara ekonomi.
Penutup
Resolusi konflik-konflik religius yang terbaik adalah resolusi
yang dibangun dari dalam umat beragama itu sendiri. Apa yang kita
ketahui dari Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya adalah orang
harus bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri dan melalui
pengalaman-pengalaman hidup mempertahankan kehidupan yang
damai, aman, dan nyaman. Perasaan damai, saling menghargai,
saling memberdayakan dari suatu masyarakat religius yang
beragam akan lebih bertahan lama dan fundamental sifatnya jika
datang dari dalam masyarakat religius yang beragam itu sendiri,
daripada dari luar mereka. Tentu saja mengondisikan perdamaian
religius dari luar bukan hal yang buruk malah memang tidak bisa
dihindari untuk dilakukan. Namun hanya berhenti di sini tidaklah
cukup dan harus diikuti dengan proses penanaman nilai-nilai moral
kemanusiaan secara terus-menerus yang dipandang sebagai inti sari
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
dari pembangunan perdamaian religius, sehingga akan tumbuh
kesadaran dari dalam betapa pentingnya perdamaian religius.
Perdamaian religius tak mungkin terwujud tanpa kesadaran
nilai-nilai etis yang tumbuh dalam diri manusia beragama untuk
menopang perwujudannya. Tetapi harus diingat pula tentang
perdamaian religius dari luar bahwa untuk mengondisikan
perdamaian dari luar tentu tidak boleh dengan paksaan yang
mengorbankan kebebasan manusia baik secara individu maupun
kolektif, karena cara ini kontra produktif dengan hakikat
perdamaian itu sendiri dan dekat dengan kekerasan. Kekuatan-
kekuatan dari luar seperti dari institusi-institusi politik memang
penting, tetapi ini akan rapuh kalau tidak ada kesadaran dari dalam
masyarakat religius itu sendiri. Tugas resolusi konflik religius
bukan tugas-tugas musiman melainkan tugas sepanjang masa.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Daftar Pustaka
Abdullah, M. Amin. “Peran Pemimpin Politik dan Agama dalam
Mengurai dan Resolusi Konflik dan Kekerasan.” Dalam Alim
Roswantoro dan Abdul Mustaqim (ed.). Antologi Isu-isu
Global dalam Kajian Agama dan Filsafat. Yogyakarta: Prodi
Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan
Penerbit Idea Press, 2010.
Chandra, Robby I. Konflik dalam Hidup Sehari-hari. Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 1992.
Coward, Harold and Smith, Gordon S.. (eds.). Religion and
Peacebuilding. Albany, New York: State University of New
York Press, 2004.
Curle, A. True Justice.London: Quaker Home Service, 1981.
Dower, Nigel. An Introduction to Global Citizenship. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2003.
Fiadjoe, Albert. Alternative Dispute Resolution: A Developing
World Perspective. London. Sydney, Portland, Oregon:
Cavendish Publishing Limited, 2004.
Fuller, Graham E.. A World Without Islam. New York: Little,
Brown and Company, 2010.
Litte, David and Appleby, Scott. “A Moment of Oppurtunity? The
Promise of Religious Peacebuilding in an Era of Religious and
Ethnic Conflict.” Dalam Harold Coward and Gordon S. Smith
(eds.). Religion and Peacebuilding. Albany, New York: State
University of New York Press, 2004.
Macquarrie, J. The Concept of Peace. New York: Harper and Row,
1973.
McCartney, Clem. “Approaches To Ethnic And Religious Conflict
Resolution: Managing, Resolving Or Transforming.” Dalam
Taryono (ed.). The Making of Ethnic and Religious Conflicts in
Southeast Asia: Cases and Resolutions. Yogyakarta, Penang:
Center for Security and Peace Studies (CSPS) Universitas
Gadjah Mada & Southeast Asian Conflict Studies Network
(SEACSN) Universiti Sains Malaysia, 2004.
McTernan, Oliver. Violence in God’s Name. London: Darton,
Longman Todd Ltd., 2003.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Miall, Hugh; Ramsbotham, Oliver; and Woodhouse, Tom.
Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press,
1999.
Murray, Henry. Explorations in Personality. New York: Oxford
University, 1938.
Noel, Brett R.; Shoemake, Ann Torfin; and Hale, Claudia L.
“Conflict Resolution in a Non-Western Context: Conversations
with Indonesian Scholars and Practitioners.” Conflict
Resolution Quarterly, vol. 23, no. 4, Summer 2006.
Panggabean, Samsu Rizal. “Approaches to Ethnic and Religious
Conflict Resolution.” Dalam Taryono (ed.), The Making of
Ethnic and Religious Conflicts in Southeast Asia: Cases and
Resolutions. Yogyakarta, Penang: Center for Security and
Peace Studies (CSPS) Universitas Gadjah Mada & Southeast
Asian Conflict Studies Network (SEACSN) Universiti Sains
Malaysia, 2004.
Poitras, Jean and Renaud, Pierre. Mediation and Reconciliation of
Interest in Public Disputes. Ontario: Carswell Thomson
Professional Publishing, 1997.
Roswantoro, Alim dan Mustaqim, Abdul (ed.). Antologi Isu-isu
Global dalam Kajian Agama dan Filsafat. Yogyakarta: Prodi
Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan
Penerbit Idea Press, 2010.
Roswantoro, Alim. “Islam dan Pembangunan Perdamaian:
Mengenal Pemikiran J.E. Rash” dalam Teologia Jurnal Ilmu-
ilmu Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo
Semarang, vol 20, Nomor 1, Januari 2009.
Sacks, Jonathan. Not in God’s Name: Confronting Religious
Violence. Edinburg: Hodder & Stoughton, An Hachette UK
Company, 2015.
Taryono (ed.). The Making of Ethnic and Religious Conflicts in
Southeast Asia: Cases and Resolutions. Yogyakarta, Penang:
Center for Security and Peace Studies (CSPS) Universitas
Gadjah Mada & Southeast Asian Conflict Studies Network
(SEACSN) Universiti Sains Malaysia, 2004.
ER CONTESTING RELIGION AND ETHNICITY IN
MADURESE SOCIETY
Akhmad Siddiq
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Yogyakarta
shidiq987@yahoo.com
Fatimah Husein
State Islamic University of Sunan Kalijaga, Yogyakarta
fatimahhusein@yahoo.com
Leonard C. Epafras
Christian University of Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta
leonard.epafras@mail.ugm.ac.id
Abstract
Abstract: This article describes historical phases of Madurese identity
construction, the origins of Madurese ethnicity, inter-ethnic and inter-
cultural relation, Madurese Pendalungan culture, and how Islam involves
into cultural identities of the Madurese. In this paper, I will argue that
Islam has become part of cultural values of the Madurese, that is,
embedded within traditional activities and local wisdom. However, the
involvement does not mean to exclude other “non-Islamic” and “non-
Madurese” tradition in the process of construing Madurese identity. By
exploring how Madurese identity was culturally constructed, someone
could draw more visible connection between religion, tradition, and
social identity. This paper illustrates how Madurese identity culturally
produced, nurtured and matured. Since identity is a way of perceiving,
interpreting, and representing the existence of people, I persist that
Madurese identity has also been produced and reproduced depending on
the political, social, and cultural situation. In this regard, inter-religious or
inter-ethnic relation remains essential.
Keywords: ethnicity, identity, Islam, Madurese.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Abstrak: [Artikel ini menjelaskan fase terbentuknya identitas orang-
orang Madura, asal-usul etnis, hubungan lintas-budaya dan antaretnis,
budaya Pendalungan, dan bagaimana Islam berinteraksi dengan identitas
budaya orang Madura. Dalam artikel ini saya meneguhkan bahwa Islam
telah menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai budaya Madura, yang
bisa dilihat dari dalam aktivitas sosial dan kearifan lokal orang Madura.
Meski demikian, hal ini tidak menafikan bahwa tradisi “non-Islam” atau
“non-Madura” juga memiliki peran dalam proses pembentukan identitas
Madura. Dengan mengurai proses konstruksi identitas sosial Madura,
seseorang bisa melihat dengan lebih jelas hubungan erat antara agama,
tradisi, dan identitas sosial. Artikel ini juga menggambarkan bagaimana
identitas Madura diproduksi, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebab
identitas adalah sebuah persepsi, interpretasi, dan representasi, artikel ini
menyimpulkan bahwa identitas Madura pun tidak lepas dari tahapan itu:
bergantung pada kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam
konteks ini, relasi antaragama dan antaretnis menjadi sangat penting.]
Keywords: ethnicity, identity, Islam, Madurese.
“Madura is not an island, but an ocean of knowledge.”
(Zawawi Imron, 2017)22
Introduction
When I visited Jakarta for the first time in 1998, a friend of mine
from the city asked me curiously, “Are you Madurese? I didn’t hear
22
He is a Madurese poet who wrote many issues relating to Madura and
Madurese culture. Among his writing are Semerbak Mayang (1977), Celurit
Emas (1980), Bulan Tertusuk Ilalang (1982), Raden Sagoro (1984), Madura
Akulah Darahmu (1999), and Mata Badik Mata Puisi (2012). He achieved many
awards, e.g. The S.E.A Write Award.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
your Madurese dialect when you are speaking in Bahasa. It is
unexpected.” I just smiled at him. At the time, even I did not
honestly realize that people would identify my social identity
through my accent. To some extent, it was logical because
Madurese dialect at the time has become one of the great parodied
enunciations among comedians of television-series. We might
mention here at least two persons: Buk23 Bariah24 and Kadir.25
Through their Madurese-like dialect, people could quickly identify
the figure of Buk Bariah and Kadir as Madurese, even not every
Madurese obtained that kind of lingo. Until today that personal
experience has occasionally returned to me.
Since many people have their commonsense of Madurese identity,
such experience also happened to many other Madurese people
living within the non-Madurese community. Commonly,
stereotypes of Madurese involved in dialect, character, attitude, and
vocation.26 Muthmainnah, in his book Jembatan Suramadu: Respon
Ulama terhadap Industrialisasi, A Suramadu Bridge: An ʿUlamāʾ’s
Response to Industrialization, shared the same story: her friends
hardly believed that she was from Madura and her parent were not
sate or soto vender, nor a barber. She wrote about her Madurese
friend’s story where the Javanese student at his university insisted
that he was not Madurese because his skin was lightly white and
his body was not firm.27 In today’s Indonesia, we may highlight a
23
Buk is Madurese language used to call matured woman, similar to Ibu in
Indonesian language.
24
She is one of the prominent characters in the movie of Film Si Unyil
(broadcasted in TVRI between 1981 and 1993).
25
He is a comedian known as Madurese person (although he is actually not) who
inherited Madurese dialect in his performance. Among his movies are Kanan
Kiri Oke (1989), Ikkut-ikutan (1990), “Salah Pencet” (1992), “Kapan di Luar
Kapan di Dalam” (1995), and “Ngebut Kawin” (2010).
26
Read Huub De Jonge, “Stereotypes of Madurese” in Kees van Dijk, Huub De
Jonge, and Elly Touwen-Bouwsma, Across Madura Strait (Leiden: KITLV Press,
1995).
27
Muthmainnah, Jembatan Suramadu, Respon Ulama terhadap Industrialisasi
(Yogyakarta: LKPSM, 1998), xiv-xv.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
political and judicial figure easily identified as a Madurese
representative from his dialect: Muhammad Mahfud MD for
instance.28 This phenomenon reveals that some non-Madurese
people tend to identify Madurese through visible and discernable
entities.
Stereotypes of Madurese people, culturally acknowledged as their
identity marker, had been traditionally embodied and embedded
until today. Stereotypes contain knowledge, belief, and expectation
about a social group, and they have been rooted in standard and
ubiquitous cognitive process. In this regard, stereotypes could be
perceived as categories of a social group. They work automatically
and cognitively. “Stereotypes—like social categories more
generally—are not individual attitudinal predilections, but deeply
embedded, shared mental representations of the social object.”29
However, it is essential to explain that there is an in-depth
relationship between individual and social concerning how to
produce and operate stereotyped patterns of a social object.
Aronson and McGlone place stereotypes as social identity threat
which may create a disruptive effect and impairment of social
intelligence. It may create defensive adaptations that can affect
individuals to engage or disengage from social activities where
stereotypes are relevant for decreasing intellectual improvement.30
From this idea, it is plausible when some Madurese working and
living in migrated-city prefer to hide their Madurese identity to
evade stereotyping categorization and social identity threat from
28
He is a prominent figure, politician, lecture and lawyer. He was the chief
justice of the Constitutional Court of Indonesia, the Minister of Defense (2000)
and the Minister of Justice and Human Rights (2001).
29
Roger Brubaker, Ethnicity Without Groups (Harvard: Harvard University
Press, 2004), 72.
30
Joshua Aronson and Matthew S. McGlone, “Stereotypes and Social Identity
Threat” in Nelson, Todd D, Handbook of Prejudice, Stereotypes, and
Discrimination (New York: Psychology Press, 2009), 154.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
others.31 Eriksen assumes that there may be a correlation between
ethnicity and class: individuals belonging to specific ethnicity also
belong to the particularcategory.32 The violent conflict between
Madurese migrant and local Dayaks in West Kalimantan in 1996
could be portrayed as a glaring example of how ethnicity and social
class were misused for having communal violence. In this conflict,
both Dayaks and Madurese had been playing ethnic boundaries to
stimulate racial awareness among people. The ethnic strife
strengthens the sensibility of people to persist ethnic identity
marker during their interaction with outsiders. Here, ethnic identity,
according to Klinken, grows through competition, not through
isolation.33
As a mirror, social categories sometimes appear in an individual
character which is varied from one individual to another. Some
people tend to identify individual from stereotypes entrenched
within his fictitious social style. Such identification often happens
when people guess individual as Madurese only from its physical
appearances, such as black-hard body and loud voice.34 The
phenomenon reminds us to reflect on “imagined” and
“experienced” Madurese identity carefully. Holy and Stuchlik
describe that one of the goals of anthropological research is to
untangle discrepancies between notions and actions, between
people perception and their experience.35 Eko, for instance, a
31
Isnani, “Kehidupan Orang-Orang Madura di Kota-kota Perantauan,”
Lokakarya Laporan Penelitian Sementara, 4-6 Juli, published in proceeding
book, Madura II, published by Department of Education and Culture, Republic
of Indonesia, (1978), 154-176.
32
Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological
Perspectives (New York: Pluto Press, 2010), 11.
33
Gerry van Klinken, Communal Violence and Democratization in Indonesia:
Small Town Wars (New York: Routledge, 2007), 65.
34
This is compared with Javanese or Sundanese people who are stereotyped as
relatively white, calm and quiet.
35
Read Ladislav Holy and Milan Stuchlik, Actions, Norms and Representations:
Foundation of Anthropological Inquiry (Cambridge: Cambridge University
Press, 1983).
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Javanese person living in Madura more than 30 years, insisted that
the real life of the Madurese society could be different from
whatever non-Madurese has perceived it.36 Here, lived experiences
and encounters are needed. In line with Pak Eko, Hermawan, a
Moluccan living in Madura for more than ten years, stated that
stereotypes attached to Madurese do not utterly exist in their daily
life. In fact, he found some fine social characteristics among
Madurese which reasonably must be culturally enclosed as
“stereotypes” of Madurese, such as loyalty and honesty.37 Huub de
Jonge wrote that in the first step he planned to go to Madura his
colleagues gave him an early warning and advice to be careful with
Madurese people.38
According to Eriksen stereotypes may help the individual to divide
the multifaceted social world into kinds of people and provide
simple criteria.39 The kinds and criteria will give personal
impression whereby he or she can understand society. In this
regard, it is also important to note that people commonly (and
stereotypically) recognized all Madurese as Muslims: to be a
Madurese is to be a Muslim. Many individuals perceive Madura as
Serambi Madinah (the veranda of Medina) linked with Aceh
Darussalam as Serambi Mekah (the veranda of Mecca). This social
embodiment sustained during vividly cultural changes occurred
within Madurese society. The statistical report affirms that non-
Muslim citizen in Madura represented less than one percent of the
Madurese population in Madura.40 However, it does not mean to
exclude non-Muslim existence from Madurese society. In fact, the
36
Interview with Eko (4/11/2017).
37
Interview with Hermawan (4/12/2017).
38
Huub de Jonge, Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan
Ekonomi dan Islam (Jakarta: Gramedia, 1989).
39
Eriksen, Thomas Hylland. Ethnicity and Nationalism: Anthropological
Perspectives (New York: Pluto Press. 2010), 30.
40
Read annual report of Statistics in Bangkalan dalam Angka, Sampang dalam
Angka, Pamekasan dalam Angka, and Sumenep dalam Angka, 2016, from
Central Bureau of Statistic (BPS).
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
non-Muslim population in Madura played their roles in coloring
and elevating Madurese culture.
Perceiving Madurese people as Muslim society is an aptly religious
category that coincides with the social fact of historical Madura. By
scrutinizing history of Madura, we will find a peak-point of social
classes where Islam has been put as an ethnic and identity marker
of the Madurese. Even though the history of Madura does not begin
with Islamic narratives, it is easy to link Madurese knowledge and
believe with Islam and Islamic outgrowth.
Madurese Ethnicity and Inter-Ethnic Relation
Craig Prentiss assumes that religion has a subtle but significant role
in making and preserving the social construction of race and
ethnicity. In the fundamental argument, he insists that race and
ethnicity are the product of human imagination: they did not exist
from the beginning of time, but a result of complex interplay of
human construction. Within this connection, religion originates
from playing its role.41 This idea follows what Berger elucidates in
his Social Construction of Reality that reality was socially
constructed through the sociological transformation of human life.42
Madurese mythology of Raden Segoro is meaningful to excavate
sociological knowledge of Madurese ethnicity. In spite of
questioning whether the story of Raden Segoro is myth or historical
fact, it is principal to see that this story influenced culturally-
constructed memory of Madurese knowledge concerning to their
ancestry and ethnicity. Various versions emerge relating to the
mythology of naming. Some assume that Madura is an abbreviation
of madue ra ara (honey in the land), referring to the story of honey
41
Craig R Prentiss, Religion and the Creation of Race and Ethnicity (New York:
New York University Press, 2003), 1-4.
42
Peter L. Berger and Thomas Luckman, The Social Construction of Reality
(New York: Penguin Book, 1991).
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
and bee-nests found by the Princess Tunjungsekar in the island,
some suppose that it refers to maddhunadara (honey blood), and
others believe that it was originated in the term of paddhu ara
(corner pot).43 Otherwise, Rifa’i wrote that it might be adopted
from the city in eastern India called Madura, that is, surrounded by
arid and waterless lands.
Madurese mythology does not give a definitive explanation on how
Madurese ethnicity was constructed and how religion (especially
Islam) influenced that construction. If we approve Brubaker’s idea
that ethnicity is a social consensus constructed by unity of blood
while the solidarity of citizenship constructs nationalism, we might
assume that ethnicity of the Madurese was inherited within the
story of Raden Segoro as “the founder” of the island. Zawawi
Imron, a well-known Madurese poet, outlines Madurese identity
through a Madurese maxim, lahir e madhureh,
nginumaengmadhureh, teteporengmadhureh (someone who was
born in Madura and drinks its water is a Madurese).44
However, Madurese ethnicity also belongs to inter-ethnic relation.
Ethnicity, according to Eriksen, refers to “aspects of relationships
between groups which consider themselves, and are regarded by
others, as being culturally distinctive.”45The discourse of ethnicity
involves majority and minority, dominating and discriminated
group, in-group and out-group, and another subtheme of intergroup
relation issues. Intergroup relation may conserve and influence the
internal-external identification process within social actors, through
categorical ethnic exclusion or inclusion. In this context,
boundaries are culturally imagined to construct in-group and out-
group perspective by the actors on seeing themselves and others.
Barth presumes that ethnic group stem from biologically self-
43
Mien A Rifa’i, Manusia Madura, (Yogyakarta: Pilar Media. 2007), 30.
44
Interview with D. Zawawi Imron, 26/10/2017.
45
Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological
Perspectives (New York: Pluto Press, 2010), 4-5.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
perpetuating, fundamental cultural values, the field of
communication and interaction, and a membership which identifies
itself and is identified by others.46 In what follows, these defining
elements of an ethnic group will be explored.
46
Fredrick Barth, Ethnic Group and Boundaries (Boston: Little Brown and
Company, 1969), 10-11.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Self-Perpetuating
In his book, Manusia Madura, Rifa’i described some cultural
aspects that perpetuate Madurese identities, such as religion,
language, art, and the system of knowledge.47 He wrote that the
ancestor of Madurese people believed in animism, that is, approved
by the relic of Bato Kennong or Bato Egghung (sacred stone)
which could be found in many places in Madura. Hindu and
Buddhism have also colored the past of Madurese religiosity and
inherited several names in social-anthropology of Madura, such as
Candi (holy place) and Mandala (ascetic legacy). Hindus and
Buddhist traces have also ingrained within Madurese tradition such
as rokat tase’ (religious ritual of the sea), and nyalase(flowering the
grave).
In the 15thcentury, Madurese people acknowledged Islam, and it
quickly increased and nurtured as a religion of the majority that
inspired everyday life and culture. Islam did not only encourage
Madurese in the way of being Muslim, but also in the way of being
Madurese: many Arabic words influenced their language, Arabic
names inspired their naming, Arabic clothing motivated their
clothing, and Arabic religiosity revived their religious vision.
Islamic perpetuation within Madurese tradition has retained in any
aspect of people life, including language and literacy. Some Arabic-
absorptive words that could be found in the Madureselanguage
areaseyam (fasting, from Arabic al-ṣiyām), mosakkat (difficult,
from Arabic al-mashaqqah), and mosiba (disaster, from Arabic al-
muṣībah). Living in the santri culture,48 Madurese people have
47
Mien A Rifa’i, Manusia Madura, (Yogyakarta: Pilar Media. 2007), 42-78.
48
Yanwar Pribadi persists that Madurese constructed their santri culture from
three elements: the pesantren (Islamic traditional education system), the
Nahdlatul Ulama (Muslim organization), and the kiai (tradisional Islamic
authority. Read Yanwar Pribadi, “Religious Networks in Madura: Pesantren,
Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture”, Al-Jami‘ah, Vol. 51,
No. 1, (2013 M/1434 H), 1-31.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
been familiar with Arabic-Islamic expressions, both in formal and
informal manners.
The art performance of Saman signifies cultural expression of the
Madurese rooted in Islamic-Arabic tradition. In Saman, Muslim
performers chanted beautiful songs and praises in the Madurese
language for the Prophet Muhammad, through mixed-elements of
traditional Madurese art and Islamic commendations to the Prophet
and God.49 Madurese also introduced what they called mamaca (the
art of chanting recited Madurese poetry concerning with history of
the Prophet). However, Bouvier asserted that element of pre-
Hinduism and pre-Islam hadbeen deeply embedded in the theatrical
art of mamacan.50
In addition, Madurese people have good knowledge on how to
interact with the nature and environment around them. For a long
time, Madurese are renowned as a seafarer and fisherman who
perceive the ocean as their “world.” The Madurese mastered sailing
and fishing in the sea. In one of the famous traditional songs,
Madurese people symbolize their life as abentalombe’ asapo’
anginsalanjengah (always pillowed by the wave and covered by
the wind). Kurt Stenross describes that the Madurese are among the
great maritime and trading people of the Indonesian archipelago.
He argues that the ecology and demography of Madura contributed
to the success of the Madurese as maritime entrepreneurs.51
Human-nature interaction of the Madurese could also be revealed
within Madurese aphorism. To mention a few of them: balibisabali
ka rabbana (like a grouse coming back to its nest), malekko’ mara
tangghiling (coiled like an ant-bear), and pegha’ juko’najhe’
palekkoaenggha (catch the fish, do not mess the water). These
49
Helena Bouvier, Lebur: Semi Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat
Madura (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 218-220.
50
Ibid., 158-160.
51
Read Kurt Stenross, Madurese Seafarers: Prahus, Timber and Illegality on the
Margins of the Indonesian State (Singapore: NUS Press, 2011).
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
aphorisms exemplified that Madurese people have construed their
social knowledge based on their interaction with nature. In naming
natural phenomenon, for instance, the Madurese expressed their
close understanding of nature, such as calling rainy season as
nembhara (because of the wind of the west [bhara’]) and dry
season as nemor (because of the wind of the east [temor]). The
direction was an important aspect of Madurese ecology: they have
regarded and upheld Madurese local wisdom on making a path in
building houses. Traditionally, the Madurese will always build their
home facing to the south52, with the langgar built in the western
part of the yard, while the kitchen has its position in the southern
part of the yard. This traditional and cultural architecture was called
taneyanlanjeng.53
52
Based on Madurese mythology, traditional Madurese perceived the north as a
threat of the past from which their ascendant came and avoided to remember that
memory.
53
Pudji Pratitis Wismantara, “Struktur Pemukiman Taneyan Lanjheng Berbasis
Budaya Santri dan Non-Santri di Madura” in Argo Twikromo et.al, Pencitraan
Adat Menyikapi Globalisasi (Yogyakarta: PSAP UGM, 2010), 174-211.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Fundamental Cultural Values
Mieder asserts that proverb fulfills people need to summarize their
experiences into pieces of wisdom or poetical words that inherit
cultural—individually or socially—affairs.54 It signifies the
contextual condition of the people and involves imagined situation
of them. In some cases, it becomes practical and strategic
communication that might describe and influence the social identity
of the particular community. There are types of the proverb, and the
Madurese have at least three kinds. The first is called parebhasan,
analogical term to express specific condition of individual or
community in animal/nature/object illustration. For instance, to
convey that there is always an exceptional person in a family,
Madurese proverb says tellorsapatarangan ta’ kerahbecce’ kabbhi
(there is always a rotten egg among eggs). The second is paparegan
which can be identified as a simple poem such as tamba jato
tambakelang; tambalakotambapakan (additional job requires other
wage). The third is called saloka that contains wisdom and
beautiful words, e.g.,pae’ jhe’ dulihpalowa, manisjhe’
dulihkalodhu’ (do not directly vomit the bitter thing, do not
immediately swallow the sweet one).55
Besides attempts to describe Madurese identity through proverbs,
Iqbal Nurul Azhar tried to elucidate Madurese characters through
Madurese songs and lyrics. In his article “Karakter Masyarakat
Madura dalam Syair-syairlagu Daerah Madura” (Characters of
Madurese Society within the Local Songs of Madura), Azhar stated
that several characters of the Madurese could be discovered within
lyrics of the Madurese local songs, such as being patriotic,
54
Wolfgang Mieder, Proverbs: A Handbook (London: Greenwood Press, 2004),
1.
55
Misnadin, “Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pepatah-pepatah Madura (Positive
Cultural Values of Madurese Proverbs)” Atavisme Jurnal Ilmiah Kajian Sastra,
Vol. 15, No. 1. (2012), pp. 75-84.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
religious, hard worker, responsible, polite, and faithful to the
family.56 He refined these characters from selected songs written by
Madurese artists and musicians. The songs were compiled in the
book of Kumpulan Lagu Daerah Madura (The Compilation of
Madurese Songs).
Madurese proverbs and songs had, in fact, influenced the life of
Madurese society. Benjamin Lee Whorf assumes that speakers of
different kinds of language were cognitively different from one
another, because of those language differences. Language, in some
degrees, influences people thought and mind.57 In this regard,
proverb and song produced and reproduced based on lived
experiences of specific society might construct different
perspective among different people.
Within these characters, Madurese identity as religious people
becomes convincingly confirmed. They represented themselves as
Muslim who believe in and practice Islam as the way of life.
Adapted from nuggets of the famous song of Tanduk Majhang,
Madurese recognized themselves as abhentalsyahadat, asapo’
iman, apajhung Allah,asandhing Nabi (pillowed by confession,
covered by faith, pawned by God, and accompanied by the
Prophet). The Islamic representation within the local culture could
also be identified in Minangkabau people who acknowledge Islam
as their basic principle on building culture: adat basandisyara’,
syara’ basandikitabulah (tradition is based on Islamic law, Ian
slamic law is based on the holy book [the Qur’an]). Islam and
Madurese tradition have culturally intertwined and entangled each
other. Strengthening this reality, Rifa’i wrote, “…if there was a
Madurese believed in Catholicism or Christianity, that was a very
56
Iqbal Nurul Azhar, “Karakter Masyarakat Madura dalam Syair-syair Lagu
Daerah Madura” Jurnal Atavisme, Vol 12, No 2, Desember (2009): 217-227.
57
Read Benjamin Lee Whorf, Language, Thought and Reality: Selected Writings
of Benjamin Lee Whorf (Massachusetts: The MIT press, 1962), 207-219; Julia M
Penn, Linguistic Relativity versus Innate Ideas (Paris, Mouton, 1972), 53-56.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
extraordinary exceptional.”58 However, it is worth noting that few
of Madurese living in Madura Island converted to Christianity and
Catholicism.59Also, there is Madurese community in Sumberpakem
Jember who believed and practiced Christianity for centuries.60
Islamic values infiltrated within the cultural activities of the
Madurese and staged as an ethnic identity marker.61Islamic rituals
and festivals have inherently become social fiestas, such as tellasan
(the holy day of Ied), molod (the birth day of the Prophet),
tajhinsorah (the celebration of Islamic new year), and tajhin sappar
(another food celebration in Safar). Madurese people are highly
obsessed to implement Islamic order, including to visit Mecca and
Medina for performing ḥājj (pilgrimage). For Madurese, Islam
does create not only religiousactivism but also shape social and
ethnic prestige. Mansurnoor emphasizes that ulama (Islamic leader)
in Madura are an inseparable part of the local social structure. They
have a strategic position that allows exercising a leadership role in
the local context. The social leadership of Madurese people to
some extents depends on religious leadership. He acknowledges
Madurese recognition to the ulama through Madurese term of
Keyaeh (the ulama of pesantren who has extensive relation with
broader society) and Mak Kaeh (the ulama with closeconnection).
In his term, he called the second as local kyai and the first as supra-
local kyai.62
58
Mien A Rifa’i, Lintasan Sejarah Madura. (Surabaya: Yayasan Lebbar Legga,
1993), 49.
59
Based on my interview with several priests in four municipalities (Bangkalan,
Sampang, Pamekasan, and Sumenep) in Madura, it is proven that more than 30
Madurese individuals embraced Christianity and Catholicism in our times.
60
Read Asy’ari, Melintasi Batas-Batas Beragama: Studi Atas Konstruksi Sosial
Keagamaan dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Islam dan Kristen di
Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Jawa Timur
(Thesis--State Islamic University of Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016); Edy
Sumartono, Kidung di Kaki Gunung Raung (Bandung: Bina Media Informasi,
2009).
61
Interview with Latief Wiyata, 17/11/2017.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Besides the authority of the ulama as Muslim leader among
Madurese people, other social bodies influence cultural entities in
Madura. In his thesis, Islam and Politics in Madura, Yanwar
Pribadi mentioned other social authorities outside the ulama in
Madura, namely blater63 (local strongmen) and klebun64 (village
heads). Pribadi argues that these authorities (kiai, blater,
andklebun) have overriding access to use religious power, physical
force, and formal leadership within their controlled territory.65 The
boundaries of power-relation between these authorities somehow
melted in distorted arena and territories. Kiai as religious leader
currently tends to plunge into practical politics that has ethically
been avoided in the past by kiai within pesantren tradition.
However, this phenomenon shows that religious or Islamic traces
are strongly attached within Madurese activities, including practical
politics. Madurese interpretation of Islamic values into proverb
could be identified in bango’ jhuba’a e ada’ etembang jhubha’ e
budih (motivating people to have good ending [ḥusn al-khātimah]
in their life), lakonah lakonih,kennengngah kennenngih (ordering
people to do the right job related to their capacity and capability),
manossa coma dharmah(reminding people that human duty is only
to serve), and kembhang malate kembhang bhabur, mandhar
bhadha’a paste, terro daddhia haji mabrur (hoping to make a
pilgrimage and have a blessed journey).
62
Iik Arifin Mansurnoor, Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura
(Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1990), 335.
63
To understand the relationship between kiai and blater on competing social
power in Madura, read Abdul Rozaki, Menabur Kharisma Menuai
Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura (Yogyakarta:
Pustaka Marwa, 2004).
64
For further reading of klebun and its relation with the kiai, read Endy Saputra,
Kiai Langgar and Kalebun: A Contestation between Cultural Broker in a Non-
Pesantren Village in Madura, Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2009).
65
Yanwar Pribadi, Islam and Politics in Madura: Ulama and Other Local
Leaders in Search of Influence (1990-2010) (Doctoral thesis--Leiden University,
Leiden, 2013), 9.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Another proverb that signifies an innate character of the Madurese
is etembhang pote mata, bhango’ pote tolang (it is better to die than
to get shy). This proverb is commonly understood as the instinctive
desire of the Madurese to fight and make violence. Carok, as an art
of traditional martial fight between two (or more) individuals
involved in a conflict, was generally labeled to Madurese people as
a peaceful way to solve a conflict. In some cases, when Madurese
person decided to do carok, he will come to kiai for asking a
blessed permit and amulet. Madurese people said, mon
kerraspa’akerres (if you want to become a strongman you must
have a power). They tend to keep silent on responding or resolving
their problem, including to fight or attack their opponent. They
said, mon raja ghaludhugga ta’ kera raja ojhenna (the louder you
speak, the weaker you are). Latief Wiyata explored some reasons
that encourage Madurese to conduct carok which might be simply
classified into (1) family problem and (2) social prestige.66
For the Madurese, family and kinship are principal elements to
build society. When ethnicity was identified as solidarity based on
united blood, a kinship, Madurese people traditionally attempted to
keep their kinship through the marital approach and devoted
friendship. They preserve the term of settongdhere (one blood) and
taretandhibhi’ (our family) to express their ancestral network with
other. On the one hand, this principle creates a strong attachment
from in-group people, on the other hand, it produces imaginable
detachment of out-group people. However, Madurese people have
also acknowledged as individualistic: ngala’ karebbhadhibhi’
(individualistic). Many of them ignored the kinship and family
network, and prefer to separate themselves from family ties. In this
context, there is a Madurese proverb said orengdeddihtaretan,
taretandeddihoreng (other becomes family, the family becomes
other).
66
Latief Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura
(Yogyakarta: LKiS, 2002).
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Field of Communication and Interaction
Cultural differences mark ethnic groups and measure social identity
by a manner of in and out of groupness. Communication and social
interaction between two or more collective parties become one of
the crucial keywords within cultural studies of social identity and
ethnicity. It is plausible to say that ethnic groups are what people
believe or imagine to be, where the process of identification arises
out of and within interactions. Referring to Barth, ethnicity focuses
more on relationships of cultural differentiation, and specifically
upon contact between collectivities, between them and us.67
Madurese people identified cultural and ethnic groupness by using
the term of taretandibhi’ (our family) and settong dere (one blood)
to include Madurese people into in-group and others into out-group
classification. The sense of ethnic partiality of the Madurese could
be noticed when they meet each other, especially wherever outside
the mainland of Madura. Ethno-social conflict in Kalimantan
between Madurese and Dayak in 1996s, for instance, was exploded
because of ethnic preference of the Madurese and the Dayaks.68 On
doing racial classification, Madurese people to some extent use the
word orenglaen (another person) or orengjeu (people far away) to
call individuals or groups detached from their community. Such
identification eventually creates a different approach to inter-ethnic
communication and interaction.
As a neighboring ethnic group of the Madurese, Javanese people
was somewhat represented as a mirror and an ideal for the
Madurese as well as a threat. In anthropological studies, Madura
has remained ignorant of being research concern: seemingly before
67
Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations (Los
Angeles: Sage Publication, 2008), 11-12.
68
Read Huub de Jonge, “Why the Madurese? Ethnic Conflicts in West and East
Kalimantan Compared,” Asian Journal of Social Science,Volume 34, Issue 3,
(2006),456 – 474.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
1977, Madura had no proper geographical and cultural identity for
most authors.69 In the past, traditional Madurese acknowledged
only two worlds: Jabah (Java) and Madureh (Madura). Many
people in Madura perceived Kalimantan—as another destination
island for working—as Jabah Dajah (the Northern Java) rather
than Borneo or Kalimantan. Madurese people regarded Java and
Javanese culture as culturally “superior” and call Madurese
migration to Java as onggha (going up) and return to Madura as
toron (going down).70 Madurese people also utilized this kind of
communicative approach in interaction with other different ethnic
groups and highlighted Madurese saying kor jhe’ la nyala (as long
as they do not make problems) as a basis. Madurese people, in fact,
lived in close interaction with other groups. They had no exclusive
livelihood, although in some degree they seem to be self-protective
of their identity and ethnicity.71
Some of the non-Madurese individuals are afraid to start
communication with Madurese persons because of stereotypes
marked to them as unpredictable and temperamental. “It is not true
that Madurese people are temperamental and rude. I have been here
in Madura for more than ten years, and I have known that they are
respectable and loyal people. What I like from Madurese is that
they are very frankly. They say what they want and what they do
not, without keeping any feelings,” said Hermawan.72The same
69
Lawrence Husson, “Eigth Centuries of Madurese Migration to East Java,”
Asian and Pacific Migration Journal, Vol 6, No 1, (1997), 77-102.
70
Muhammad Djakfar, “Tradisi Toron Etnis Madura: Memahami Pertautan
Agama, Budaya, dan Etos Bisnis,” Jurnal el Harakah, Vol 14, No 1, (2012), 34-
50.
71
Take an example of the case of Suramadu Bridge plan where Madurese ulama
—representing Madurese society—rejected the plan in the name of religious
idealism, cultural values of the Madurese, and social sustainability. The
resistance brings the issue of out-group expansion into Madura as a threat toward
in-group existence of the Madurese. Read Yanwar Pribadi, “The Suramadu
Bridge Affairs: Un-Bridging the State and the Kyai in New Order Madura,”
Studia Islamika, Vol 22, No 2, (2015), 233-268.
72
Interview with Hermawan (4/12/2017).
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
impression was expressed by other non-Madurese persons who
lived in Madura for a long time. Madurese people build inter-ethnic
and social communication based on mutual respect.73 Social
tensions that sometimes appear, according to them, are political-
based problems triggered through religious and ethnic identity
issues.
Ethnic Group Membership
In his paper “Kehidupan Orang-orang Madura di Kota-Kota
Perantauan” Isnani persisted that some of the Madurese migrants
living in the big city felt ashamed to declare their ethnic identity of
being Madurese.74 Being identified as a member of specific ethnic
groups somewhat sharpen a cultural barrier or boundary to another
ethnic group which may influence how people interact with each
other. To obscure such cultural limit, many Madurese avoid to
uncover their ethnic identity publicly. In this regard, they recognize
to politically and sociologically govern ethnic-group membership.
In Madura, ethnic membership is ascribed by patrilineal descent:
the father’s position has significant influence to determine social
association within the ethnic group of the Madurese. However,
ethnic group membership of the Madurese is fluid that to some
extent creates indefinite identification. Ethnic group membership
attachment or detachment depends on many aspects, including
political and economic interest. Jenkins supposes that collective
interest does not reflect perceived similarities and differences
between ethnic groups, but it does encourage ethnic identification.75
In his writing, Weber wrote that “ethnic membership does not
73
Interview with Bing, Eko, Erni, Frans, Ana, and Sumardi.
74
Isnani, “Kehidupan Orang-orang Madura di Kota-Kota Perantauan,” Research
paper presented in in Lokakarya, Batu, 4-6 July, (1978).
75
Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations (Los
Angeles: Sage Publication, 2008), 10.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
constitute a group; it only facilitates group formation of any kind,
particularly in the political sphere.”76 To explore ethnic-group
membership we may examine through “cultural stuff,” that is,
experienced within ethnic and inter-ethnic relations such as the way
people perceive their group, the prominent characteristics of them
and other groups, and particular worldviews maintained, contested
and transformed among them. Referring to Weber’s theory of
“ethnic community action,” Eriksen emphasizes that ethnic
differences have become so visible in many societies that it has
become impossible to ignore them.77 Mead affirms that group
membership is a symbolic, not a physical matter.78The members
internalize symbols of group membership and affect their acts. If
we cite Randall Collins’ idea, we may say that particularacts are
always micro, but the structure (group membership) that generates
it into a macro.79
76
Max Weber, Economy and Society (Berkeley: University of California Press,
1978), 389.
77
Eriksen, Thomas Hylland. Ethnicity and Nationalism: Anthropological
Perspectives (New York: Pluto Press. 2010), 2.
78
Anselm Strauss, The Social Psychology of George Herbert Mead (Chicago:
The University of Chicago Press, 1956), xiii.
79
Randal Collins, Interaction Ritual Chains (Princeton: Princeton University
Press, 2004), 5-6.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Pendalungan: A Cultural Encounter
Pendalungan could be identified as periukbesar (great melting pot)
where various traditions meet, integrate, and decisively produce a
new alteration of culture. It may also defined as the descendant of
inter-ethnic marriage between Madurese and Javanese people or
cultural encounter between Javanese and Madurese tradition.80
Konstantinos Retsikas elucidates that pendalungan stem from
Javanese words, medal,andlunga, which mean “going out to stay in
a certain place.”81 The word pandalunganto some extent means
speaking or talking by using vague and discourteous language,82
because every migrant community reserves their language on the
one hand and recognize another language on the other.
As a multicultural society, Madurese pendalungan tend to be
inclusive. Sutarto classified seven characters of pendalungan
culture: (1) they are in-between society living in transition between
traditional and industrial era; (2) the majority are primary-orality
people who prefer to talk and chat, not to think out of the box; (3)
adaptive and open to social change; (4) expressive and transparent;
(5) paternalistic; (6) regarding kinship relation; and (7) somehow
temperamental and unpredictable.83 These characters stem from
inter-cultural interaction and inter-ethnic communication.
Term of Pendalungan covers certain culture assimilated with
another culture, such as Chinese Pendalungan or Arab
80
Ikwan Setiawan, “Mengapa (Harus) Pendalungan? Konstruksi dan
Kepentingan dalam Penetapan Identitas Jember,” conference paper presented in
Seminar Budaya Membincang Kembali Terminologi Pandalungan, Jember: 10
December, (2016).
81
Yongky Gigih Prasisko, Blandongan: Perebutan Kuasa Budaya Masyarakat
Jawa dan Madura (Yogyakarta: LPRIS, 2015), 42.
82
Prawiroatmodjo, Bausastra Jawa-Indonesia II (Jakarta: Gunung Agung,
1981), 53-81.
83
Ayu Sutarto, “Sekilas tentang Masyarakat Pandalungan,” Conference paper
presented in seminar Jelajah Budaya, 7-10 August, (2006).
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Pendalungan. Indeed, it could be classified as an independent
assimilation-based culture84 as well as becomes a distinctive
cultural identity stemmed from inter-ethnic acculturation. It is
supposed that more than two times of Madurese people live within
pendalungan culture and experience Madurese tradition outside
Madura because of migration.85 From this reality, anecdotal
classification of Madura Swasta (unofficial Madurese) and Madura
Negeri (official Madurese) emerges. The first is to identify
Madurese people who were born in the area of Tapal Kuda in East
Java and wherever outside Madura, while the second implies all
Madurese born and live in the mainland and its surroundings. That
sketchy classification remains historical experiences of inter-ethnic
relation among the Madurese which constructed “cultural borders”
not only between them and another ethnic group but also among
the Madurese themselves.
Having that that the human world may be constructed in three
different layers of order: individual order, interaction order, and
institutional order,86 it is worth noting that internal-external
identification represents a keyword to look at selfhood as an
embodied individual. Interaction order, furthermore, enrich what
Erving Goffman calls as “the art of impression management”:
orchestrating a cultural spot where self-image and public-image
encounter. Here, in some respects, Goffman asserts that
identification is a part of daily human activities.87 In line with this,
Randall Collins persists that individual is not only a body: it
represents dynamics of situations. He argues that individual is
84
Christanto P Raharjo, “Pendhalungan: Sebuah Periuk Besar Masyarakat
Multikultural,” paper presented in the conference of Jelajah Budaya, 13 August,
(2006).
85
Read Lawrence Husson, “Eigth Centuries of Madurese Migration to East
Java,” Asian and Pacific Migration Journal, Vol 6, No 1, (1997), 77-102.
86
Richard Jenkins, Social Identity (London: Routledge, 2004), 5.
87
Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (Edinburgh:
University of Edinburgh, 1956), 132-151.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
“moving precipitate across situations.”88 Individuals are
interactional. They need social space to express their ideas and
practices.
Pendalungan culture represents inclusiveness and multicultural
mind of the Madurese on building and keeping their social identity.
In the Madurese Christian community in Sumberpakem, for
instance, there are many couples born and lived within the
pendalungan tradition in term of ethnicity (Madurese and Javanese)
or religion (Islam and Christianity). Madurese Christian in the
district could interact with Muslim neighbor through shared
cultural activities in everyday life. They do not need to cover their
identity as Christians to get recognition as a part of Madurese
society. It happens because of historical time that gradually
eliminates cultural detachment between Christianity and Madurese
identity. This phenomenon differs from the experience of some
Madurese Christians living in the mainland who prefer to obscure
their Christianity unless to whom they are familiar with. Emma, a
Madurese woman, born in the Muslim family, told that her story of
being Christian was a story of rejection and resistance. Her family
and neighbor refused her to live in the district and forced her to
leave. Her family and neighbor exclude her from a Madurese
group-ness because if her conversion to Christianity.89 Guttmann
assumes that partition and cultural-border making which is more
stable is structured in the mind of people.90 Perspective about the
other strongly influences the way someone constructs inter-
subjective and inter-ethnic group relation. In line with this,
Apostolov suggests considering the civilizational frontier as a zone
88
Randal Collins, Interaction Ritual Chains (Princeton: Princeton University
Press, 2004),4.
89
Interview with Emma, 9/11/2017.
90
Mario Apostolov, The Christian–Muslim Frontier: A Zone of Contact, Conflict
or Cooperation (London: Routledge-Curzon, 2004), 105.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
of contact, in which the alternative between accommodation and
confrontation is open, rather than a fault-line of encounter.91
Conclusion
For the Madurese, Islam remains meaningful to deal with ethnic
identification. Madurese person who believes and practices
Christianity will be perceived as less Madurese and recognized out
of ethnic-groupness. Some of Madurese Christian tend to live
outside Madura (and Madurese society) to experience contented
public space of Christianity.92 Islam has become part of ethnic
markers that finds its justification through cultural assimilation
with the local tradition. Madurese proverb abhentalsyahadat,
asapo’ iman, apajhung Allah,asandhing Nabi describes the
culturally rooted connection between Islam and Madurese ethnicity,
that is, practiced by the people.
Islamic values have for centuries influenced everyday life of the
Madurese not only in term of constructing internal identification of
Muslim community but also of creating external categorization of
others, including Madurese Christian. To some degree, Madurese
people tend to restrain ethnic traces just for specific religious
values (Islam) although there has been Madurese community
existing and practicing Christianity outside the mainland. In many
cases of Madurese Muslim conversion, the Madurese maxim
orengdeddihtaretan, taretandeddihoreng (other becomes family, the
family becomes other) preserves to create a cultural and ethnic
partition. The domain of religious differentiation raises more
strongly than the spirit of racial resemblance. Jenkins asserts that
ethnicity is centrally a matter of shared meaning.93 Similarly, Islam
91
Ibid., 1.
92
Interview with Sumardi, 25/1/2017.
93
Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations (Los
Angeles: Sage Publication, 2008), 14.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
—as an important factor within Madurese tradition—becomes a
social necessity to construe ethnicity and Madurese locality.
However, Madurese ethnicity could be socially intertwined with
Christianity, that is, witnessed within Madurese Christian life in
Sumberpakem, Jember. Compared with the homogenous condition
in the mainland that separate Christianity from cultural ingredients
of Madurese ethnicity, Madurese Christians in the district uphold
Christianity as a religion on the one hand and preserve Madura as
an ethnic identity on the other. One of the reasons is that the
Madurese community in Sumberpakem had been living near to
pendalungan culture which improves inclusive and multicultural
society. Cultural and inter-ethnic encounters may construe different
ways of perceiving the (religious or ethnic) others.
Ethnicity is a way of perceiving, interpreting, and representing the
social world. It is not a thing in the world, but perspectives on the
world.94 In line with this, Madurese ethnicity is a matter of
produced and reproduced meaning based on social interaction and
categorization of others, which is different (and always changing)
between one and another cultural situation and time. Budi, a
Madurese Christian living in Bondowoso, East Java, expressed his
past-Islamic experience of being Madurese descendant of inter-
religious (Islam-Christianity) and inter-ethnic (Madurese-Chinese)
marriage in Madura. There was no rejection from his family and
neighbor at first time for that marriage, but eventually, his father
preferred to live outside the Madura when the situationwas
changed.95
Madurese inclusiveness, religiously and culturally, creates social
possibilities for assimilation and acculturation. It was witnessed by
the presence of non-Madurese ethnics, e.g., Chinese, Arab,
Javanese, Ambonese, and Moluccan in Madura or non-Islam
94
Roger Brubaker, Ethnicity Without Groups (Harvard: Harvard University
Press, 2004), 17.
95
Interview with Budi, 13/8/2017.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
religions such as Christianity and Buddhism. The thing that must
be prevented as a treat for this pluralism and multiculturalism is a
spirit of Islamism which has currently elevated in various religious
movement. This kind of excessive religiosity drives to put several
Muslim movements as “the main vehicle of religious and moral
excellence within a generally wayward, unenlightened, or heedless
community.”96 It happens, for some reasons, because perceptions
and understanding of Christianity vary among Muslim Madurese,
that is, depending on background knowledge and institutionalized
(Islamized or ethnicized) practice. Excessive religiosity and
ethnicity tend to reduce Madura as an accessible public sphere for
“Muslim” and “Madurese.” This perception aims to restrain
geographical boundary with ideological or theological barriers. To
exemplify fluidity of Madura and the Madurese identity, Zawawi
Imron insists that “Madura is not only an island but ocean of
knowledge.”
References
Abdurachman. Sejarah Madura: Selayang Pandang. Sumenep. No
year.
Apostolov, Mario. The Christian–Muslim Frontier: A Zone of
Contact, Conflict or Cooperation. London: Routledge-Curzon.
2004.
Aronson, Joshua and McGlone, Matthew S. “Stereotypes and
Social Identity Threat” in Nelson, Todd D, Handbook of Prejudice,
Stereotypes, and Discrimination. New York: Psychology Press.
2009.
96
Clifford Geertz, Peddlers ad Princes: Social Development and Economic
Change in Two Indonesia Towns (Chicago: University of Chicago Press, 1963),
150.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Asy’ari. Melintasi Batas-Batas Beragama: Studi Atas Konstruksi
Sosial Keagamaan dalam Membangun Kerukunan Antar Umat
Islam dan Kristen di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe
Kabupaten Jember Jawa Timur. Thesis--State Islamic University of
Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016.
Azhar, Iqbal Nurul. “Karakter Masyarakat Madura dalam Syair-
syair Lagu Daerah Madura,” in Atavisme: Jurnal Ilmiah Kajian
Sastra, Vol 12, No 2, Desember. 2009.
Barth, Fredrick. Ethnic Group and Boundaries. Boston: Little
Brown and Company. 1969.
Berger, Peter L. and Luckman, Thomas. The Social Construction of
Reality. New York: Penguin Book. 1991.
Bouvier, Helena. Lebur: Semi Musik dan Pertunjukan dalam
Masyarakat Madura. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002.
Brubaker, Roger. Ethnicity Without Groups. Harvard: Harvard
University Press. 2004.
Collins, Randal. Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton
University Press. 2004.
Djakfar, Muhammad. “Tradisi Toron Etnis Madura: Memahami
Pertautan Agama, Budaya, dan Etos Bisnis,” Jurnal el Harakah,
Vol 14, No 1. 2012.
Eriksen, Thomas Hylland. Ethnicity and Nationalism:
Anthropological Perspectives. New York: Pluto Press. 2010.
Geertz, Clifford. Peddlers ad Princes: Social Development and
EconomicChange in Two Indonesia Towns. Chicago: University of
Chicago Press. 1963.
Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life.
Edinburgh: University of Edinburgh. 1956.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Holy, Ladislav and Stuchlik, Milan. Actions, Norms and
Representations: Foundation of Anthropological Inquiry.
Cambridge: Cambridge University Press. 1983.
Husson, Lawrence. “Eight Centuries of Madurese Migration to East
Java,” Asian and Pacific Migration Journal, Vol 6, No 1. 1997.
Isnani. “Kehidupan Orang-Orang Madura di Kota-kota
Perantauan,” in proceeding book published by Department of
Education and Culture, Republic of Indonesia, Madura II:
Lokakarya Laporan Penelitian Sementara, 4-6 July. 1978.
Jenkins, Richard. Rethinking Ethnicity: Arguments and
Explorations. Los Angeles: Sage Publication. 2008.
Jenkins, Richard. Social Identity. London: Routledge. 2004.
Jonge, Huub de, et. al. (ed.). Across Madura Strait. Leiden: KITLV
Press. 1995.
Jonge, Huub de. “Why the Madurese? Ethnic Conflicts in West and
East Kalimantan Compared,” Asian Journal of Social
Science,Volume 34, Issue 3. 2006.
Jonge, Huub de. Madura dalam Empat Zaman: Pedagang,
Perkembangan Ekonomi dan Islam. Jakarta: Gramedia. 1989.
Klinken, Gerry van. Communal Violence and Democratization in
Indonesia: Small Town Wars. New York: Routledge. 2007.
Mansurnoor, Iik Arifin. Islam in an Indonesian World: Ulama of
Madura. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 1990.
Mieder, Wolfgang. Proverbs: A Handbook. London: Greenwood
Press. 2004.
Misnadin. “Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pepatah-pepatah
Madura,” in Atavisme: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra, Vol. 15, No. 1.
2012.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Muthmainnah. Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap
Industrialisasi. Yogyakarta: LKPSM. 1998.
Penn, Julia M. Linguistic Relativity versus Innate Ideas. Paris:
Mouton. 1972.
Prasisko, Yongky Gigih. Blandongan: Perebutan Kuasa Budaya
Masyarakat Jawa dan Madura. Yogyakarta: LPRIS. 2015.
Prawiroatmodjo. Bausastra Jawa-Indonesia II. Jakarta: Gunung
Agung. 1981.
Prentiss, Craig R. Religion and the Creation of Race and Ethnicity.
New York: New York University Press. 2003.
Pribadi, Yanwar. “Religious Networks in Madura: Pesantren,
Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture.” Al-
Jami‘ah, Vol. 51, No. 1. 2013.
Pribadi, Yanwar. “The Suramadu Bridge Affairs: Un-Bridging the
State and the Kyai in New Order Madura,” Studia Islamika, Vol 22,
No 2. 2015.
Pribadi, Yanwar. Islam and Politics in Madura: Ulama and Other
Local Leaders in Search of Influence (1990-2010). Doctoral
thesis--Leiden University, Leiden. 2013.
Raharjo, Christanto P. “Pendhalungan: Sebuah Periuk Besar
Masyarakat Multikultural,” paper presented in Seminar Jelajah
Budaya. 2006.
Rifa’i, Mien A. Lintasan Sejarah Madura. Surabaya: Yayasan
Lebbar Legga. 1993.
Rifai, Mien A. Manusia Madura. Yogyakarta: Pilar Media. 2007.
Rozaki, Abdul. Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai
dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura. Yogyakarta: Pustaka
Marwa. 2004.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Akhmad Siddiq DkkLuthfi Rahman
Saputra, Endy. Kiai Langgar and Kalebun: A Contestation between
Cultural Broker in a Non-Pesantren Village in Madura, Indonesia.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
Setiawan, Ikwan. “Mengapa (Harus) Pendalungan? Konstruksi dan
Kepentingan dalam Penetapan Identitas Jember,” paper presented
in Seminar Budaya Membincang Kembali Terminologi
Pandalungan, Jember. 2016.
Siddiq, Akhmad. “Religious Obesity: Sidestepping Radicalism
through Ulama Network,” paper presented in the 2nd International
Conference on South East Asian Studies, Yogyakarta. 2017.
Stenross, Kurt. Madurese Seafarers: Prahus, Timber and Illegality
on the Margins of the Indonesian State. Singapore: NUS Press.
2011.
Strauss, Anselm. The Social Psychology of George Herbert Mead.
Chicago: The University of Chicago Press. 1956.
Sumartono, Edy. Kidung di Kaki Gunung Raung. Bandung: Bina
Media Informasi. 2009.
Sutarto, Ayu. “Sekilas tentang Masyarakat Pandalungan,” paper
presented in Seminar Jelajah Budaya, 7-10 August. 2006.
Weber, Max. Economy and Society. Berkeley: University of
California Press. 1978.
Whorf, Benjamin Lee. Language, Thought and Reality: Selected
Writings of Benjamin Lee Whorf. Massachusetts: The MIT press.
1962.
Wismantara, Pudji Pratitis. “Struktur Pemukiman Taneyan
Lanjheng Berbasis Budaya Santri dan Non-Santri di Madura” in
Argo Twikromo et.al, Pencitraan Adat Menyikapi Globalisasi.
Yogyakarta: PSAP UGM. 2010.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Er Contesting Religion and Ethnicity in Madurese SocietyA Comparative Study on
Shi‘îte
Wiyata, Latief. Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang
Madura. Yogyakarta: LKiS. 2002.
Zamzami, Mukhammad, et. al. “Islamism and the Development of
Religious Movement in Madura: From Strengthening of Religious
Symbols to Authoritarianism.” Paper presented in the 3rd
International Conference on Social and Political Sciences, Jakarta.
2017.SHI‘ÎÎ
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
PEMIMPIN ORMAS KEAGAMAAN SEBAGAI MAN OF
COMMUNION DALAM SITUASI KONFLIK MENURUT
PAUS BENEDIKTUS XV DAN YOHANES XXIII
Alphonsus Tjatur Raharso
Dosen Hukum Gereja di STFT Widya Sasana – Malang
atjaturr@gmail.com
Abstract:
This article is written out of concern about religious leadership trend
performed by some Islamic mass organization leaders during the first
three month of 2017 in Jakarta, which ended in horizontal conflicts and
frictions based on religious and racial issues. Through the comparative
method, this article shows the leadership role model of Catholic religious
leaders, especially two Catholic popes during the World War I and II era,
Pope Benedict XV and Pope John XXIII. While the world leaders were
confronting to each other and created blocks to provoke wars, the both
popes were present as fathers who loved and embraced all humankind
across the nations. They placed themselves as the peace makers and
invited the world to build peaceful co-habitation, which respected human
right, as well as imposed justice for all humankind. The both popes were
man of communion and sign of peace in amid of world conflicts. To be
man of communion and sign of peace, the religious leaders need to
restrain themselves to not be affected by the conflict issues that make
them be sectarian, extremist, partisan, or partial. When there is a conflict
because of any factors, the religious mass organization leaders might only
observe whether there is a violation of human right, justice or bonum
commune. If there is any, regardless from which race, religion, and class
the victims are, they should fight for the justice, invoke human right, and
generate bonum commune based on the legal law, by encouraging peace
and harmony in the society.
[Artikel ini lahir dari sebuah keprihatinan mengenai model
kepemimpinan religius yang ditampilkan oleh beberapa pemimpin ormas
keagamaan Islam pada trimester pertama tahun 2017 di ibukota Jakarta
Religió: Jurnal Studi Agama-agamaMutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Volume 78, Nomor 21, Desember20178| ISSN: (p) 2088-6330; (e) 2503-3778p-ISSN:
2088-7523; e-ISSN: 2502-6321| 2151-23425-49
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
dan berakhir pada gesekan dan konflik horisontal berdasarkan suku dan
agama. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode komparatif, yakni
dilakukan dengan menggali gaya kepemimpinan religius pemuka agama
Katolik, khususnya dua orang Paus Gereja Katolik di masa Perang Dunia
pertama dan kedua, yakni Benediktus XV dan Yohanes XXIII. Kedua
Paus itu tampil sebagai bapa yang mencintai dan merangkul semua orang
dan bangsa, menjadi juru-damai, serta mengajak para pemimpin bangsa
untuk membangun cohabitation yang damai, yang menghormati hak dan
martabat pribadi manusia, serta menegakkan keadilan bagi semua orang.
Kedua Paus itu telah menjadi man of communion dan sign of peace yang
efektif dalam situasi konflik mondial. Dari studi komparatif dapat
ditemukan bahwa untuk bisa menjadi man of communion dan sign of
peace dalam situasi konflik para pemimpin ormas keagamaan di
Indonesia perlu menahan diri agar tidak terkooptasi dan menjadi
sektarian, partisan atau parsialistik di hadapan dan di dalam kelompok
yang dipimpinnya sendiri. Dalam konflik karena faktor apapun, para
pemimpin ormas keagamaan sejatinya hanya mengawasi apakah terjadi
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, keadilan, atau bonum
commune.]
Keyword: religious leadership, plural society, man of universal
unity.This article is written out of a concern about the religious leadership
trend performed by some Islamic mass organization leaders during the first
three month of 2017 in Jakarta which ended in horizontal conflicts and
frictions based on religious and racial issues. Through the comparative
method, this article would show the leadership role model of Catholic
religious leaders, especially two Catholic popes during the World War I and
II era, Pope Benedict XV and Pope John XXIII. While the world leaders
were confronting to each other and created blocks to provoke wars, the both
popes were present as fathers who loved and embraced all humankind across
the nations. They placed themselves as the peace makers and invited the
world to build peaceful co-habitation, which respected human right, as well
as imposed justice for all humankind. The both popes were man of
communion and sign of peace in amid of world conflicts. To be man of
communion and sign of peace,the religious leaders need to restrain
themselves to not be affected by the conflict issues that make them be
sectarian, extremist, partisan, or partial. When there is a conflict because of
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
any factors, the religious mass organization leaders might only observe
whether there is a violation of human right, justice or bonum commune. If
there is any, regardless from which race, religion, and class the victims are,
they should fight for the justice, invoke human right, and generate bonum
commune based on the legal law, by encouraging peace and harmony in the
society.
Keyword: religious leadership, plural society, man of universal unity
Abstrak:Artikel ini lahir dari sebuah keprihatinan mengenai model
kepemimpinan religius yang ditampilkan oleh beberapa pemimpin ormas
keagamaan Islam pada trimester pertama tahun 2017 di ibukota Jakarta dan
berakhir pada gesekan dan konflik horisontal berdasarkan suku dan agama.
Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode komparatif, yakni dilakukan
dengan menggali gaya kepemimpinan religius pemuka agama Katolik,
khususnya dua orang Paus Gereja Katolik di masa Perang Dunia pertama dan
kedua, yakni Benediktus XV dan Yohanes XXIII. Kedua Paus itu tampil
sebagai bapa yang mencintai dan merangkul semua orang dan bangsa,
menjadi juru-damai, serta mengajak para pemimpin bangsa untuk
membangun cohabitation yang damai, yang menghormati hak dan martabat
pribadi manusia, serta menegakkan keadilan bagi semua orang. Kedua Paus
itu telah menjadi man of communion dan sign of peace yang efektif dalam
situasi konflik mondial. Dari studi komparatif dapat ditemukan bahwa untuk
bisa menjadi man of communion dan sign of peace dalam situasi konflik para
pemimpin ormas keagamaan di Indonesia perlu menahan diri agar tidak
terkooptasi dan menjadi sektarian, partisan atau parsialistik di hadapan dan di
dalam kelompok yang dipimpinnya sendiri.Dalam konflik karena faktor
apapun, para pemimpin ormas keagamaan hanya boleh mengawasi apakah
terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, keadilan, atau bonum
commune.
Pendahuluan
Pada trimester pertama tahun 2017 Negara Kesatuan Republik
Indonesia mengalami ujian berat mengenai kebhinekaannya. Kasus
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
penistaan agama Islam oleh Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur
DKI Jakarta, telah memicu sentimen keagamaan yang selanjutnya
menimbulkan gelombang demonstrasi di ibukota. Isu SARA
dimunculkan sedemikian mencolok, sehingga menggantikan isu
politik seputar pilkada DKI saat itu. Tampak juga gelombang
demonstrasi itu di-backing-i, digelorakan, dan bahkan dipimpin
langsung oleh beberapa pemimpin ormas keagamaan. Akibatnya,
sikap dan tindakan yang tidak proporsional terhadap kasus
penistaan agama beresiko menimbulkan keterpecahan bangsa atas
dasar perbedaan agama dan ras. Sedangkan, politisasi sentimen
keagamaan dan SARA mengandung resiko disintegrasi bangsa dan
hancurnya sendi-sendi demokrasi negara, yang sudah lama
dibangun atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Toleransi antar umat
beragama di Indonesia, yang sudah terkenal dan dipuji di seluruh
dunia, dan bahkan dijadikan model toleransi bagi negara-negara
lain, kini sungguh-sungguh mengalami ujian berat dan mulai
dipersoalkan verifikasinya.
Situasi sosial-politik di ibukota NKRI saat itu sedemikian
panasnya, sehingga pemerintah melalui Kementerian Agama
memunculkan gagasan untuk melakukan standarisasi melalui
sertifikasi bagi para pengajar dan pengkotbah agama Islam, agar
dakwah mereka di masjid-masjid dan dalam pertemuan jemaah
secara massal tidak hanya menyampaikan ajaran Islam dalam
keutuhan dan kemurniannya, melainkan juga berisi pesan damai
dan persaudaraan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia
yang bhinneka. Asumsi pemerintah ialah bahwa pemuka dan
pendakwah agama memiliki posisi dan peran yang utama dan
sentral dalam masyarakat agamis Indonesia. Kata-kata dan ajaran
mereka didengarkan dengan penuh minat, dianggap dogma, dan
dipatuhi oleh umatnya. Karena itu, mereka diharapkan memberikan
dakwah agama yang menyuarakan kesejukan, serta perdamaian dan
persaudaraan sejati. Meskipun wacana itu menimbulkan pro-kontra,
Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakormubin) mendukung
upaya Kemenag, bahkan dengan membuat program kerja untuk
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
mendidik sejuta mubalig penebar Islam damai. Program itu
melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, dan
budayawan. Gagasan dibalik program itu ialah bahwa mubalig
tidak boleh sekedar mendalami ilmu ke-Islaman, melainkan dalam
konteks Indonesia mereka juga harus dibekali dengan pemahaman
Pancasila serta UUD 1945. Melalui upaya itu diharapkan bahwa
para mubalig akan menjadi penebar Islam yang damai, ikut aktif
memecahkan masalah keagamaan di Indonesia, khususnya masalah
pendangkalan sikap religius dan gejala islamofobia.97
Dengan latar belakang tersebut artikel ini mengkaji model
kepemimpinan religius para pemimpin ormas keagamaan di NKRI
yang plural. Dalam artikel ini dikupas bagaimana idealnya para
pemimpin religius di Indonesia pada umumnya, dan khususnya dari
agama Islam yang memiliki mayoritas penganut di bumi nusantara
ini, menjalankan kepemimpinannya, sehingga dalam situasi yang
rentan terhadap gesekan atau konflik sosial mereka mampu
menjalankan kepemimpinan religius yang menyumbang secara
efektif kondisi bangsa yang rukun, bersatu dan damai, demi
pembangunan integral yang berkelanjutan.
Tulisan ini berangkat dari sebuah persoalan sederhana namun vital,
yakni apa yang kurang dalam kepemimpinan religius beberapa
pemimpin ormas keagamaan dalam gelombang demo tersebut,
sehingga membuat mereka begitu emosional dan jatuh dalam
ekstremisme, eksklusivisme, dan sektarianisme, yang semakin
memanaskan gesekan sosial dan mengancam kohesi sosial yang
sudah dibangun dengan susah-payah sejak lama? Dengan kata lain,
apa yang perlu dilengkapi dalam kepemimpinan religius mereka,
agar mampu menjadi figur rohaniawan yang sejuk dalam ajaran,
santun dalam ujaran, merangkul dan mendamaikan semua
golongan? Selain itu, apakah religius leadership itu merupakan
prinsip-prinsip kepemimpinan umum yang diterapkan di bidang
religius, ataukah ada unsur-unsur lain yang harus ditambahkan?
97
Jawa Pos, 26 Februari 2017, 3.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
Pertanyaan itu dijawab dengan metode komparatif, yakni dengan
menampilkan beberapa figur pembanding yang berasal dari
lingkungan Gereja Katolik. Figur pembanding itu ialah para
pemuka umat Katolik, khususnya Paus Benediktus XV dan Paus
Yohanes XXIII. Metode komparatif dipakai, karena ada kemiripan
situasi, yakni konflik politik dan sosial, meski skalanya berbeda.
Gereja Katolik sendiri pernah memiliki pengalaman buruk dan
pahit, di mana dari tahun 1096 hingga 1487 para pemimpinnya di
Eropa (Paus, para Uskup dan imam) menebarkan pesan-pesan
kebencian, dan bahkan menyerukan di seluruh Gereja peperangan
melawan ekspansi Islam, yang mencoba menguasai tanah suci dan
sekaligus memasuki benua Eropa. Gereja Katolik ingin
membangun kepemimpinan religius yang baru, melalui pembaruan
mentalitas dan peraturan yang mengatur sikap dan tindakan
kepemimpinan para imamnya. Metode komparatif ini sama sekali
tidak bermaksud menunjukkan siapa dan mana yang lebih baik,
melainkan apa yang dapat dipelajari dan diteladani dari kedua figur
tersebut. Melalui metode komparatif tulisan ini menunjukkan
keutamaan, kecerdasan, dan gaya kepemimpinan religius yang
mestinya dianut oleh para pemimpin ormas keagamaan di tengah-
tengah masyarakat Indonesia yang plural namun masih rentan
terhadap gesekan sosial antar kelompok agama.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
Profil Singkat Paus Benediktus XV
Paus Benediktus XV lahir di Genova (Italia Utara) pada tanggal 21
November 1854 dengan nama Giacomo Della Chiesa. Ia bergelar
doktor dalam yurisprudensi sipil, dan kemudian menempuh studi di
Kolese Capranica dan Universitas Gregoriana di Roma. Ia
ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 21 Desember 1878, dan
langsung disekolahkan untuk menjadi diplomat Gereja Katolik.
Dari 1883 hingga 1887 ia menjadi sekretaris Nuntius di Spanyol
dan membantu Nuntius untuk menjadi penengah antara Jerman dan
Spanyol dalam persoalan kepulauan Caroline. Keinginannya untuk
menjadi Nuntius tidak tercapai, karena Paus Pius X mengangkatnya
menjadi Uskup di Bologna pada tahun 1907. Pada Mei 1914 ia
diangkat menjadi Kardinal. Melalui konklaf 3 September 1914
beliau terpilih menjadi pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia
dengan nama Benediktus XV, menggantikan Paus Pius X yang
wafat pada 20 Agustus 1914. Keterpilihannya sangat mengejutkan,
karena beliau sama sekali tidak dijagokan sebagai kandidat kuat
(papabilis), mengingat baru tiga bulan diangkat menjadi Kardinal.
Para peserta konklaf agaknya sungguh-sungguh sadar akan situasi
kritis yang melanda Eropa, sehingga mereka sengaja memilih figur
yang telah terbukti piawai di bidang diplomasi.98 Agar
pelantikannya tidak kontras dengan situasi prihatin yang
diakibatkan oleh perang yang baru saja pecah, Benediktus XV
memilih Kapel Sistina sebagai tempat inkoronasinya, bukan
Basilika Santo Petrus seperti biasanya.99 Setelah lebih dari tujuh
tahun melayani sebagai Paus yang ke-258, ia wafat pada tanggal 22
Januari 1922.
98
John N.D. Kelly, Grande Dizionario Illustrato dei Papi, terj. A. Riccio (Casale
Monferrato: Piemme,1995), 744.
99
Erminio Lora dan Rita Simionati, eds., Enchiridion delle Encicliche, vol. 4,
Pio X e Benedetto XV (1903-1922) (Bologna: Dehoniano, 1998), 455.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
Sikap dan Tindakan Paus Benediktus XV selamapada Perang
Dunia I
Pelayanan Benediktus XV sangat diwarnai dengan keprihatinan
mendalam dan konsisten atas perang dunia I. Beliau mengeluarkan
serentetan kecaman dan kutukan atas peperangan, dengan
menyebutnya sebagai “pemandangan yang mengerikan”, “kutukan
kemarahan Allah”, “ladang pembantaian yang menghinakan
Eropa”, “dunia menjadi rumah sakit dan tumpukan tulang-belulang
akibat perang”, “tindakan bunuh diri Eropa”.100Mudahnya
menggunakan senjata dalam menyelesaikan masalah dianggap oleh
Paus sebagai “tragedi paling kelam dari kebencian dan kebodohan
manusia”.101
Benediktus XV tidak hanya melancarkan kutukan atau kecaman
verbal, melainkan secara aktif mengupayakan perdamaian. Beliau
bersikap imparsial terhadap semua pihak yang berperang. Beliau
sangat menghukum peperangan, namun tidak mau menjadi hakim
yang menjatuhkan penilaian atau putusan mengenai motif-motif
khusus yang dimiliki setiap negara ketika memulai peperangan.
Paus ingin merangkul semua negara dan menjadi bapa rohani bagi
semua pihak yang berperang. Sambil menyerukan agar perang
segera diakhiri, beliau menginginkan perdamaian yang adil bagi
semua, tanpa ada yang menang atau yang kalah, tanpa ada yang
mendominasi atau yang ditundukkan, sehingga semua kekuatan
bisa berdialog bersama. Karena itu, pada 1 Agustus 1917 Paus
mengusulkan poin-poin perdamaian kepada semua negara yang
terlibat perang, yakni (i) pengurangan senjata secara serempak dan
pembentukan lembaga arbitrase yang mengikat semua pihak, (ii)
kebebasan berlayar di laut dan pemilikan bersama wilayah perairan
Eropa, (iii) tanggung-renteng pengeluaran akibat perang dan biaya
pemulihan, (iv) saling mengembalikan teritori yang diduduki, dan
pemberian jaminan bagi Belgia untuk mendapatkan
100
Lora dan Simionati, Enchiridion delle Encicliche, 456.
101
Ibid. 456.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
kemerdekaannya secara penuh, (v) melakukan pengaturan bersama,
berdasarkan inspirasi umum masyarakat Eropamengenai masalah
territorial yang harus didiskusikan antara Jerman, Perancis, Italia,
dan Austria, (vi) pengamatan dan perlakuan yang adil bagi
Armenia, negara-negara Balkan, dan teritori bekas Kerajaan
Polandia. Usulan Paus tersebut memunculkan perdebatan di antara
semua negara yang berperang, namun sama sekali tidak membawa
dampak. Itu karena sebelumnya telah terjadi perjanjian rahasia di
London pada 26 April 1915, malah atas usulan Italia, bahwa
perwakilan Tahta Suci tidak akan dilibatkan dalam perjanjian
perdamaian. Selain itu, beberapa pihak untuk sementara tidak ingin
mengakhiri peperangan karena yakin akan memenangi peperangan.
Meski demikian, Paus tetap kukuh dalam aksinya sebagai juru
damai. Pada 24 Oktober 1917 beliau mengirim surat kepada Raja
Austria, mengusulkan upaya “perdamaian melalui kompensasi
tanpa humiliasi”, untuk menghindarkan agitasi politik yang sulit
diprediksi.102
Di samping upaya diplomatik yang gagal karena tak digubris itu,
Vatikan melakukan karya karitatif dan aktivitas mitigasi dampak
peperangan, melalui pertukaran korban luka, pengiriman bahan
makanan dan bantuan bagi tawanan perang. Ribuan tawanan
perang yang mengalami cacat dikembalikan ke tanah air mereka,
demikian pula para tawanan yang merupakan ayah dari banyak
anak, atau yang telah melewati 18 bulan di penjara. Karya karitatif
kepausan membebaskan warga sipil yang ditawan, mengembalikan
para pengungsi ke rumah tinggal mereka, menyediakan tempat
penampungan di Swiss bagi lebih dari 30 ribu orang Perancis,
Inggris, Belgia, dan Austria, memberikan hari libur pada hari
Minggu bagi mereka yang dipenjara, dan sebagainya. Istana
Kepausan sendiri telah melayani 700 ribu permohonan informasi,
memulangkan 40 ribu orang pengungsi, melakukan 500 ribu
bantuan komunikasi dengan keluarga dari para pengungsi atau
tawanan. Semua negara Eropa merasa berhutang budi kepada Paus,
102
Lora dan Simionati, Enchiridion delle Encicliche, 457-458.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
dan mengakui beliau sebagai guru peradaban dan persaudaraan
insani. Dalam banyak kesempatan Paus menyampaikan
keyakinannya bahwa perjanjian Versailles masih jauh dari
sempurna untuk menjamin perdamaian yang pasti, dan menegaskan
perlunya perdamaian yang langgeng, yang hanya bisa dijamin
melalui pembaruan hidup religius.103
Dalam ensikliknya berjudul Pacem Dei Munus (1920), Paus
mengingatkan kepada semua warga dunia dan negara-negara bahwa
meskipun perang sudah berakhir hampir di semua tempat dan telah
ditandatangani perjanjian-perjanjian perdamaian, namun benih-
benih pertengkaran lama masih tetap bercokol dalam hati. Karena
itu, beliau menyerukan agar diupayakan sekuat tenaga untuk
membuang semuapenyebab pertikaian, menegakkan keadilan bagi
semua, dan bangsa-bangsa membangun kembali persatuan dan
persaudaraan.104
Profil Singkat Paus Yohanes XXIII
Paus Yohanes XXIII lahir pada tanggal 25 November 1881 sebagai
anak ketiga dari 13 bersaudara, dalam sebuah keluarga petani
sederhana di desa Sotto il Monte (Bergamo). Ia diberi nama Angelo
Giuseppe Roncalli. Ia ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10
Agustus 1904, dan kemudian sebagai Uskup pada tanggal 19 Maret
1925. Ia juga aktif dalam pelayanan diplomatik bagi Tahta Suci,
yakni sebagai delegatus apostolik di Bulgaria (1931), di Turki dan
Yunani (1934), sebagai Nuntius di Perancis (1945). Ia kemudian
diangkat menjadi Kardinal pada tanggal 12 Januari 1953, dan tiga
hari kemudian sebagai Batrik Venezia. Setelah dilakukan 12 kali
pemungutan suara dalam tiga hari konklaf, pada tanggal 28
Oktober 1958 ia dipilih menjadi Paus Gereja Katolik yang ke-261
dengan gelar Yohanes XXIII.
103
Ibid. 458-459.
104
Ibid. 459.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
Banyak kalangan dalam Gereja Katolik mengira bahwa karena
usianya yang sudah 77 tahun, Yohanes XXIII hanya akan
melakukan aktivitas rutin dan administratif belaka. Ternyata ia
mencetuskan dan melaksanakan gagasan-gagasan yang kemudian
menjadi tonggak sejarah Gereja Katolik abad ke-20 dan seterusnya.
Sekurang-kurangnya ada tiga proyek besar yang saling berkaitan,
yakni Sinode Keuskupan Roma, Konsili Vatikan II, dan pembaruan
UU universal Gereja.105
Paus Yohanes XXIII sebenarnya tidak memiliki kaitan apa-apa
dengan Perang Dunia I. Namun, beliau mengalami situasi perang
itu, ketika masih sebagai imam muda berusia sekitar 30-an tahun.
Beliau juga mengalami Perang Dunia II ketika usianya menjelang
60 tahun, dan aktif dalam pelayanan sebagai Uskup dan diplomat
Vatikan. Kedua perang tersebut memberi dampak fisik, psikologis,
dan spiritual bagi Angelo Roncalli (nama sebelum menjadi Paus).
Kedua perang dunia itu telah menempa kepribadiannya,
membangun refleksinya sebagai pemimpin umat, dan ikut
menentukan visi-misinya sebagai pastor, terutama ketika bertugas
sebagai delegatus apostolik, baik sebelum maupun selama perang
dunia II, dan kemudian ketika menjadi Paus.
Kepemimpinan Religius Paus Yohanes XXIII Selama Konflik
Mondial Perang Dunia II
Ketika pecah Perang Dunia I, Angelo Roncalli baru sepuluh tahun
menjadi imam. Setelah Italia memutuskan untuk melibatkan diri
dalam Perang Dunia I dan menyatakan secara resmi berperang
melawan Austria, pada 24 Mei 1915 Romo Angelo dipanggil
kembali untuk menjalankan dinas militer di Korps Medis di semua
Rumah Sakit di Bergamo, dan kemudian sebagai kapelan militer.
Tugas itu ia laksanakan sampai 10 Desember 1918. Wajib militer
pernah beliau jalani sebelumnya, yakni ketika masih sebagai
105
Kelly, Grande Dizionario, 755.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
seorang seminaris teologan (November 1901-November 1902),
yang diakhirinya dengan pangkat sersan.
Kebiasaan menulis refleksi harian sejak di Seminari Menengah
praktis terhenti selama Perang Dunia I. Kompilator catatan
hariannya tidak menemukan catatan pribadi apa pun dari Romo
Angelo selama kurun waktu 1915-1918, dengan alasan “perang”.
Hanya ada satu catatan singkat tertanggal 23 Mei 1915, sehari
menjelang keberangkatannya menuju dinas militer. Dalam catatan
itu Romo Angelo bertanya dalam diri sendiri, apakah ia akan
kembali lagi ke Bergamo ataukah Tuhan menetapkan hari
terakhirnya di medan peperangan. Ia tidak tahu, namun yang ia cari
hanyalah kehendak Allah dalam segala hal dan di setiap saat, serta
bekerja untuk kemuliaan-Nya dengan pengorbanan diri yang
total.106
Setelah Perang Dunia I berakhir dan selesai juga dinas militernya,
sebelum memulai tugas baru sebagai pembimbing rohani bagi para
frater di Seminari Tinggi Bergamo, dalam kesempatan retret pada
akhir April 1919 Romo Angelo mengucap syukur kepada Tuhan
bahwa selama empat tahun terjun di dunia yang sarat dengan
penderitaan akibat perang ia diberi banyak kesempatan untuk
melakukan kebaikan bagi sesama. Ia mengenang semua prajurit
muda yang ia antarkan jiwanya memasuki alam baka. Kenangan
akan jiwa-jiwa itu sungguh hidup dalam batinnya, dan bayangan
bahwa mereka akan berdoa baginya sangat menghibur dan
menyemangatinya. Selanjutnya, Romo Roncalli ingin
menghidupkan kembali prinsip-prinsip hidup beriman dan hidup
imamat yang sudah dianutnya sejak masa muda, yakni kemuliaan
Allah, pengudusan diri, surga, Gereja, keselamatan jiwa manusia.
Menurutnya, kontak dengan medan pertempuran telah
106
John XXIII, Journal of a Soul, terj. Dorothy White (London: Geoffrey
Chapman, 2000), 190.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
mentransformasi prinsip-prinsip itu ke dalam aksi nyata, dan ia
menghidupi prinsip-prinsip itu dalam kepemimpinan religiusnya.107
Pada tanggal 10 Juni 1940 Italia kembali mengumumkan secara
resmi keterlibatannya dalam Perang Dunia II, berkoalisi dengan
Jerman untuk berperang melawan Inggris dan Perancis. Pada
malam harinya Mgr. Roncalli, yang sedang menjabat sebagai
delegatus apostolik di Istambul, langsung menulis di buku
hariannya: “Hari ini sangat menyedihkan buatku. Italia telah
memaklumkan diri berperang melawan Inggris dan Perancis.
Perang selalu mengakibatkan kehancuran yang luar biasa. Bagi
seorang kristiani yang mengimani Kristus dan Injil-Nya, perang
sama dengan permusuhan dan kontradiksi. Mulai hari ini tanggung
jawab dan kewajibanku menjadi lebih serius dan berat, untuk
bertindak bijaksana, penuh pertimbangan dan kasih. Saya harus
menjadi Uskup bagi semua orang, consul Dei, bapa, terang, dan
pengharapan bagi semua. Sebagai manusia biasa saya berharap
negara asalku Italia berhasil dan menang dalam Perang Dunia ini.
Namun, sebagai seorang kristiani rahmat Allah mendorongku untuk
membawa damai dan mengupayakan perdamaian bangsa-bangsa.
Kodrat mendorongku untuk menginginkan kemenangan bagi
negaraku. Namun, rahmat menginspirasiku untuk mengupayakan
perdamaian”.108 Roncalli sungguh-sungguh menghadapi situasi
yang amat pelik saat itu, terutama dari aspek psikologis dan
kemanusiaan. Lingkungan kerjanya di Kantor Delegasi Apostolik
bercorak internasional, dan rekan-rekan kerjanya berasal dari
berbagai kebangsaan: Perancis, Inggris, Italia, dan Jerman. Tanpa
adanya perang saja beliau sudah merasa kesulitan untuk menjaga
situasi plurinasional dan plurietnis yang seimbang dan penuh
kekeluargaan di kantornya. Kini dengan adanya perang antar
negara dan antar bangsa, komunitasnya menjadi terpecah.
107
John XXIII, Journal of a Soul, 192.
108
. Allegri, Il Papa Buono: La Storia di Giovanni XXIII (Milano: Oscar
Mondadori, 2000), 182; A. Tjatur Raharso, Pernak-Pernik Ajaran dan
Keutamaan San Giovanni XXIII (Malang: Widya Sasana Publication, 2014), 154.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
Nasionalisme yang tidak sehat telah menciptakan perpecahan,
kebencian, dan dendam.109
Di kantor delegasi apostolik itu Roncalli memiliki seorang rekan
kerja, biarawan berkebangsaan Perancis, mantan serdadu Perancis
dalam Perang Dunia I. Ketika Italia menyatakan perang melawan
Perancis, Roncalli langsung membayangkan bahwa rekan kerjanya
itu akan merasa tidak nyaman dan tidak enak bekerja di kantornya.
Perasaan itu muncul karena Italia dan Perancis sedang bermusuhan
dan berperang. Karena itu, keesokan hari setelah Italia
memaklumkan perang, pada pukul 8 pagi Roncalli berdiri di pintu
masuk kantornya untuk menunggu kedatangan rekan kerjanya
berkebangsaan Perancis itu. Ketika datang, Roncalli membukakan
pintu baginya, mempersilakan masuk, dan merangkulnya erat-erat,
sambil membisikkan kata-kata: “Apa yang sedang terjadi di antara
kedua negara kita, semoga tidak mengganggu kebersamaan kita.
Kita adalah saudara di dalam Kristus, dan kita tetap saling
mengasihi seperti biasanya”.110
Pada suatu hari di Istambul ada seorang pejabat resmi
berkebangsaan Inggris meninggal dunia. Ia seorang Katolik.
Namun, tak seorang pun memberitahu Mgr. Roncalli, dengan
alasan karena Inggris sedang bermusuhan dan berperang melawan
Italia. Ketika Roncalli kemudian mengetahui hal itu, dia sangat
kecewa dan marah terhadap para pegawainya, karena tidak
mendapat kesempatan mendoakan dan memberkati jenazah pejabat
itu. Beberapa minggu kemudian seorang pejabat berkebangsaan
Italia meninggal dunia. Kali ini Roncalli langsung diberitahu.
Namun, beliau berkata: “Saya akan berdoa bagi kesejahteraan
arwah pejabat yang telah meninggal dunia itu. Namun, saya tidak
akan datang dalam misa requiem, karena saya sebelumnya tidak
datang dalam misa requiem bagi pejabat Inggris itu. Orang-orang
mengira bahwa saya seorang nasionalis seperti kebanyakan orang
109
Allegri, Papa Buono, 182-83.
110
Allegri, Papa Buono, 183.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
pada saat ini. Itu keliru besar. Bagi seorang imam, semua orang
adalah saudara dan saudari”.111
Analisis Gaya Kepemimpinan Religius Kedua Paus dalam
Situasi Konflik
Bilamana Paus Benediktus XV dan Yohanes XXIII melakukan
diplomasi aktif untuk menghentikan peperangan, serta menegakkan
dan memelihara perdamaian dunia, hal itu mereka lakukan karena
merasa diutus tidak hanya untuk memperhatikan umatnya sendiri,
melainkan juga menggembalakan “domba-domba lain yang bukan
dari kandang ini” (Yoh 10:16). Mereka juga bertindak sebagai
“guru dan pelindung kebenaran” di hadapan setiap hati nurani, dan
utamanya di hadapan para penguasa atau petinggi negara-negara.
Paus Benediktus XV mengatakan: “Ketika dari ketinggian martabat
apostolik ini sekilas kami memandang kejadian-kejadian di dunia,
di hadapan kami langsung tersodor kondisi memprihatinkan
masyarakat sipil. Kami sungguh-sungguh merasa sakit dan sedih.
Bagaimana mungkin sebagai bapa semua orang, hati kami tidak
merasa tercabik-cabik oleh pemandangan yang tergelar di Eropa,
dan bersama Eropa seluruh dunia; sebuah pemandangan paling
gelap dan paling menyedihkan sepanjang sejarah?”112 Patut kita
garis bawahi ungkapan “bapa semua orang” (pater omnium
communis) yang digunakan oleh Paus Benediktus XV.
Demikian juga, Yohanes XXIII menyebut dirinya sebagai Uskup
bagi semua orang, consul Dei (penasihat dari Allah), bapa, terang,
111
Allegri, Papa Buono, 183.
112
Benediktus XV, Ensiklik Ad Beatissimi Apostolorum Principis, 1 November
1914, dalam Enchiridion delle Encicliche, vol. 4, Pio X e Benedetto XV (1903-
1922), ed. Erminio Lora dan Rita Simionati (Bologna: Dehoniano, 1998), 467.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
dan pengharapan bagi semua. Mengenai para pelarian politik,
Yohanes XXIII merasakan kepahitan mendalam, karena terdorong
oleh “perasaan sebagai bapa seluruh bangsa manusia” (paterna
caritas) yang dinyalakan oleh Allah dalam hatinya.113 Dari kisah
yang sudah dipaparkan di atas “menjadi Uskup bagi semua orang”
berarti menjadikan semua orang saudara dan saudari, merangkul
semua orang tanpa membedakan suku, bangsa, asal-usul negara,
ras, dan golongan. Itu juga berarti melawan dan menolak
nasionalisme yang sempit, radikal, dan tidak sehat. Dalam
ensikliknya yang terkenal, Pacem in terris (11 April 1963), dalam
rangka meredam perang dingin antara AS dan Uni Sovyet,
“menjadi Uskup bagi semua orang” diungkapkan oleh Yohanes
XXIII dengan mengajak dan mendesak semua pemimpin negara
serta semua orang yang berkehendak baik untuk berpikir
melampaui sekat-sekat, untuk melihat, mengakui, dan
mengupayakan bersama nilai-nilai universal serta bonum commune
universal.
Ada banyak butir pemikiran Yohanes XXIII mengenai prinsip-
prinsip dan nilai-nilai universal itu. Pokok-pokok pikirannya tidak
hanya berkaitan dengan kedua perang dunia yang sudah lewat,
melainkan tetap relevan untuk mengantisipasi setiap potensi
konflik atau peperangan di kemudian hari, entah berskala kecil
ataupun besar, baik konflik internal dalam sebuah negara maupun
konflik internasional antar negara. Dalam tulisan ini kita angkat
secara ringkas beberapa pokok pikiran terpenting.
Pertama, dunia jelas sangat membutuhkan tatanan. Namun tatanan
itu tidak bersumber dari adu kekuatan manusia, apalagi dengan
menggunakan senjata, melainkan berdasarkan tatanan yang
ditetapkan Allah dan sudah tertanam dalam harkat dan martabat
pribadi manusia. Konflik dan peperangan merupakan buah deviasi
113
Yohanes XXIII, Litt. Enc. Pacem in Terris, 11 April 1963, dalam Enchiridion
delle Encicliche, Vol. 7, Giovanni XXIII e Paolo VI, ed. Erminio Lora dan Rita
Simionati (Bologna: Dehoniano, 1994), 433.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
ketika kehidupan bersama bangsa manusia ditentukan oleh
kekuatan yang dibangun oleh masing-masing negara dan
terkontaminasi oleh unsur-unsur irasional. Tidaklah cukup bagi
negara-negara untuk sekadar menciptakan co-exsistence (ada
berdampingan), melainkan hidup bersama-sama dan bekerjasama
saling membangun (convictus, co-habitation). Co-habitation yang
tertata dan membangun harus didasarkan pada prinsip bahwa setiap
individu adalah persona yang rasional dan berkehendak bebas,
subjek hak dan kewajiban yang universal, yang tidak bisa dilanggar
atau dipisahkan dari pribadinya. Selanjutnya, Yohanes XXIII
menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban itu, antara lain hak
untuk hidup dan membangun kehidupan yang bermartabat, hak atas
pendidikan, hak untuk beribadah kepada Allah berdasarkan
keyakinan hati nurani, baik secara privat maupun di ruang publik,
hak atas kebebasan memilih status kehidupan, hak atas kebebasan
berinisiatif di bidang ekonomi dan pekerjaan, hak untuk berkumpul
dan membentuk asosiasi, hak untuk bermigrasi, dan hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan publik demi mewujudkan bonum
commune (kebaikan umum).114
Kedua, co-habitation antara bangsa-bangsa yang tertatamenuntut
adanya otoritas public, yang menjamin keberlangsungan tatanan itu
hingga semua elemen masyarakat dapat bersama-sama
mewujudkan bonum commune. Namun, Yohanes XXIII
menegaskan bahwa otoritas publik bukanlah organ yang bebas dari
kontrol dan pengawasan. Otoritas publik harus menjalankan tugas
dan kewenangannya berdasarkan rasionalitas dan moralitas.
Otoritas duniawi hanya dapat memerintahkan sesuatu secara moral
kepada bawahan hanya jika mencerminkan dan berpartisipasi pada
otoritas Allah. Dengan demikian, ketaatan warga kepada otoritas
publik bukan lagi merupakan ketaatan bawahan terhadap atasan,
ketaatan man-to-man belaka, melainkan ungkapan ketaatan kepada
Allah Pencipta. Karena itu pula, jika perintah atau hukum yang
diciptakan oleh otoritas publik bertentangan dengan kehendak
114
Yohanes XXIII, Pacem in Terris, 384-393.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
Tuhan dan tatanan-Nya, maka perintah atau hukum itu kehilangan
dayawajibnya di dalam hati nurani para warganya.115
Ketiga, dalam mempromosikan dan mewujudkan bonum commune
hendaknya diperhitungkan keragaman etnis dalam setiap negara.
Dalam konteks keragaman itu, setiap warga memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam mewujudkan bonum commune masing-masing
dalam tingkat yang berbeda berdasarkan kondisi, tugas, dan jasanya
dalam komunitas itu. Selanjutnya, otoritas publik menjamin dan
mempromosikan hak setiap orang demi kebaikan semua orang,
tanpa preferensi atau privilege apa pun terhadap warga atau
kelompok tertentu. Demi keadilan dan cinta-kasih yang lebih
tinggi, otoritas publik memberikan perhatian khusus kepada
anggota masyarakat yang paling lemah, yang berada dalam kondisi
inferior dalam mewujudkan hak-haknya dan dalam mengupayakan
kebutuhan-kebutuhannya yang legitim.116
Keempat, sudah menjadi kenyataan bahwa ada perbedaan atau
kesenjangan resources antara negara yang satu dengan yang lain.
Ada negara yang memiliki segala-galanya, baik kekayaan alam
maupun modal untuk mengolahnya. Namun, ada juga negara yang
hanya memiliki kekayaan alam, namun minim modal. Kenyataan
itu seharusnya tidak membuat masing-masing negara menutup diri
dan merasa cukup dengan diri sendiri, melainkan membangun
kerjasama yang memudahkan sirkulasi modal, kekayaan, dan
tenaga manusia. Modal atau kapital seharusnya disirkulasi ke
tempat-tempat dimana berkumpul tenaga kerja, bukan sebaliknya
tenaga kerja berlari-lari menuju tempat menumpuknya kapital,
sehingga tenaga kerja menjadi tercerabut dari tanah airnya dan dari
komunitasnya menuju tempat yang asing baginya.117
115
Ibid. 403-407.
116
Yohanes XXIII, Pacem in Terris, 407-409.
117
Ibid. 431-433.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
Kelima, perdamaian dunia sebenarnya tidak bisa dan tidak boleh
didasarkan pada keseimbangan dalam kepemilikan senjata di antara
negara-negara. Ketika negara yang satu mulai memiliki senjata,
maka negara-negara yang lain merasa berhak juga untuk
mempersenjatai diri demi keadilan dan keseimbangan. Yang
kemudian terjadi ialah persaingan dalam pemilikan persenjataan,
dan sekaligus perlombaan untuk mempercanggih persenjataan dan
sistem keamanan masing-masing negara. Sekalipun seandainya
negara-negara itu menyatakan akan bertanggung-jawab
memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh persenjataannya,
dan seandainya berjanji tidak akan mengumumkan perang, umat
manusia tetaplah hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran
mendalam bahwa konflik terpanas akhirnya mengantar negara-
negara untuk saling berperang dengan menggunakan senjata
tercanggihnya. Jadi, Paus menegaskan bahwa perdamaian yang
sejati tidak mungkin lahir dari keseimbangan sistem persenjataan
antar negara. Dengan kata lain, demi keadilan, kebijaksanaan dan
demi kemanusiaan Paus Yohanes XXIII menyerukan agar semua
pemerintah negara tidak mudah lari kepada penggunaan senjata
untuk menyelesaikan konflik internasional secara bertahap
bersama-sama mengurangi persenjataan, dan menghentikan sama
sekali percobaan atau pemilikan senjata nuklir.118
Kedua Paus tersebut, seperti banyak Paus lainnya, menunjukkan
sikap kebapaan yang merangkul semua orang dari berbagai
golongan, suku, agama, kebangsaan, dan aliran politik. Dalam
konflik dan peperangan para Paus tidak hanya memikirkan dan
membela hak-hak umat Katolik atau Gereja Katolik saja,
melainkan memikirkan kebaikan umum semua orang dan
perdamaian dunia. Mereka tidak ikut menjadi sektarian atau
partisan, tidak memihak atau menggabungkan diri pada satu
kelompok atau aliran untuk memerangi aliran atau kelompok lain.
Para Paus tidak mau terkooptasi atau memihak pada satu kelompok
atau aliran tertentu dari pihak-pihak yang bertikai, melainkan ingin
118
Yohanes XXIII, Pacem in Terris, 435-437.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
berdiri di tengah-tengah untuk merangkul semua pihak dan
mengajak semua mengupayakan bersama-sama perdamaian dan
persaudaraan universal. Seruan dan himbauan moral mereka
didasarkan pada nilai-nilai universal, yang bisa diterima oleh akal
sehat dan oleh semua orang yang berkehendak baik. Dalam
kesemuanya itu, kedua Paus telah menjadi man of communion
(insan persekutuan) dan sekaligus sign of peace bagi seluruh warga
dunia.
Man of Communion: Makna dan Implikasi Etis bagi
Kempemimpinan Religius
Gaya kepemimpinan religius yang ditampilkan kedua Paus itu
sebenarnya bukanlah kekhasan pribadi mereka berdua saja. Sebagai
pemimpin tertinggi mereka telah menjadi contoh yang terbaik dan
paling menonjol. Namun, kepemimpinan religius seperti itu juga
dijalankan oleh para pemuka umat Katolik yang tersebar di seluruh
dunia, yakni Uskup, imam, dan diakon di tempat masing-masing.
Mereka telah dibentuk oleh sekumpulan kode etik yang ditetapkan
dalam UU Gereja Katolik, yang terkenal dengan nama Kitab
Hukum Kanonik (disingkat KHK). Norma pertama menetapkan
cara hidup para imam Katolik di tengah-tengah masyarakat
majemuk: “Para klerikus hendaknya selalu memupuk damai dan
kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus
dipelihara di antara sesama manusia” (KHK 1983, kan. 287, §1).119
Kata “sesama manusia” menunjukkan bahwa upaya membangun
relasi yang damai dan rukun tidak hanya dibatasi secara internal
119
Yang dimaksud dengan klerikus (clerics) ialah pemimpin umat Katolik yang
telah ditahbiskan menjadi diakon, imam, atau Uskup. KHK adalah singkatan dari
Kitab Hukum Kanonik (Latin: Codex Iuris Canonici), sebuah kitab UU yang
dikeluarkan oleh kuasa legislatif tertinggi Gereja Katolik dan diberlakukan di
seluruh Gereja Katolik di dunia. Yang berlaku sekarang ialah yang diundangkan
pada tanggal 25 Januari 1983 (KHK 1983), untuk menggantikan yang
dikeluarkan pada tahun 1917 (KHK 1917). Pasal-pasal dalam UU ini disebut
dengan istilah “kanon” (disingkat kan.).
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
pada umat Katolik saja, melainkan dengan semua orang dari semua
golongan SARA. Norma tersebut merumuskan secara positif apa
yang ditetapkan secara negatif oleh UU lama: “Para klerikus juga
dilarang berpartisipasi dengan cara apapun dalam perang saudara
atau huru-hara publik” (KHK 1917, kan. 141).120
Norma kan. 287, §1 di atas menggandengkan damai dan kerukunan
dengan keadilan. Hal ini selaras dengan ajaran konstan Gereja
Katolik bahwa tidak ada kedamaian dan kerukunan bila prinsip-
prinsip keadilan dilupakan atau dilanggar. Kedamaian dan
kerukunan ada dan langgeng jika didasarkan pada keadilan. Tanpa
keadilan, kedamaian dan kerukunan hanyalah semu atau palsu.
Karena itu, keadilan selalu bisa dituntut dan diperjuangkan oleh
setiap orang, termasuk para pemuka agama atau pemimpin ormas
keagamaan, demi mewujudkan kedamaian dan kerukunan yang
autentik. Namun, perjuangan menuntut keadilan harus tetap
menjunjung tinggi dan memelihara kedamaian dan kerukunan di
antara semua warga masyarakat. Karena itu pula, dengan tetap
menjaga perdamaian dan kerukunan di antara semua orang, melalui
aktivitas para imam dan seluruh umat Gereja berwenang untuk
selalu dan di mana saja memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga
yang menyangkut tata kemasyarakatan, dan memberi penilaian
tentang segala halikhwal manusiawi, sejauh hak-hak asasi manusia
atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya (kan. 747, §2).
Norma kan. 287, §1 berinspirasi pada ajaran para Uskup peserta
Konsili Vatikan II (1963-1965), yang menegaskan bahwa tugas
imam Katolik tidak hanya dibatasi pada pelayanan individual umat
di lingkungan Gereja katolik saja, melainkan mencakup semua
orang.121 Peran dan tugas imam ialah menjadi figur publik yang
120
John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green, eds., New Commentary
on the Code of Canon Law (New York: Paulist Press, 2000), 379. Dalam bahasa
Latin norma lama itu berbunyi: “Neve intestinis bellis et ordinis publici
perturbationibus opem quoquo modo ferant (clerici)”.
121
Konsili Vatikan II, Dekret Presbyterorum Ordinis, 7 Desember 1965, dalam
Dokumen Konsili Vatikan II, terj. Robertus Hardawiryana (Jakarta: Dokpen KWI
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
merepresentasi Gereja. Jadi, sebagai pemimpin Gereja setiap imam
mengemban visi dan misi Gereja: “Sebagaimana Allah Bapa itu
adalah sumber segala sesuatu, kita semua dipanggil untuk menjadi
saudara. Karena bersama-sama mengemban panggilan manusiawi
dan ilahi yang sama, kita dapat dan memang wajib juga bekerja
sama tanpa kekerasan, tanpa tipu muslihat, untuk membangun
dunia dalam damai yang sejati.122 Sinode Para Uskup pada tahun
1971 tentang keadilan di dunia juga menegaskan bahwa Gereja
menerima dari Yesus Kristus misi untuk mewartakan pesan Injil,
persaudaraan universal, dan tuntutan keadilan di dunia. Karena itu,
Gereja memiliki hak dan kewajiban untuk mewartakan keadilan
sosial, baik di level nasional maupun internasional, dan untuk
menggugat situasi yang tidak adil, sejauh dituntut oleh hak-hak
fundamental manusia dan keselamatannya.123
Selanjutnya, kan. 287, §2 menetapkan bahwa para klerikus dilarang
mengambil bagian aktif dalam partai-partai politik, kecuali jika
menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu
untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kebaikan
umum. Norma ini tidak ada dalam UU yang lama. Meski demikian,
sesudah PD I sebenarnya ada banyak dekret telah dikeluarkan oleh
Vatikan untuk melarang para klerikus melakukan aktivitas
politik.124 Karena norma tersebut berisi larangan, maka penafsiran
atas norma itu tidak boleh longgar atau luas, melainkan harus
dilakukan secara sempit dan ketat (bdk. kan. 18). Dengan
demikian, sekadar menjadi penasihat atau anggota dewan
pertimbangan partai atau pemerintah tidak dilarang.125
/ Obor, 1998), 472.
122
Konsili Vatikan II, Konstitusi PastoralGaudium et spes, 7 Desember 1965,
dalam Dokumen Konsili Vatikan II, terj. Robertus Hardawiryana (Jakarta:
Dokpen KWI / Obor, 1998), 636.
123
Sinode Para Uskup, Convenientes ex Universo, 30 November 1971, dalam
Enchiridion Vaticanum, vol. 4, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1971-1973,
ed. Erminio Lora (Bologna: Dehoniano, 1978), 819.
124
Beal, Coriden, dan Green, New Commentary, 380.
125
Ibid. 376.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
Memang bisa dibayangkan betapa umat akan kehilangan orientasi
dan terpecahbelah, bilamana imam-imamnya terlibat aktif dalam
partai-partai politik. Ini mengingat adanya banyak partai dan faksi-
faksi politik berdasarkan ideologi yang berbeda-beda, yang saling
bersaing merebut kekuasaan dan menjalankan pengaruh di antara
warga masyarakat agar mereka menyambut ideologinya serta
membangun negara berdasarkan ideologi itu. Kalaupun para imam
Katolik terjun hanya di satu partai politik, itupun sudah
menciptakan kesan bahwa partai itulah yang didukung oleh Gereja
Katolik, sehingga menempatkan Gereja Katolik beroposisi terhadap
partai-partai lain. Akhirnya, Gereja malah terkooptasi dan
terkungkung dalam ideologi politis atau sistem politik tertentu, lalu
kehilangan kebebasannya untuk bergerak dan bekerja sama dengan
semua orang dari berbagai ideologi demi kebaikan semua warga.
Jangan sampai terjadi bahwa seorang imam Katolik, barangkali
karena terdorong oleh panggilan hati nuraninya, terjun ke dunia
politik dengan maksud untuk menyehatkan kehidupan politik
nasional, dengan cara memerangi ketidakadilan, eksploitasi dan
berbagai bentuk penjajahan, malah terjerumus bersama partai itu ke
dalam bentuk eksploitasi yang baru dan lebih buruk terhadap kaum
miskin, atau terlibat dalam praktik korupsi partai itu.126
Ketentuan tersebut di atas juga berinspirasi secara langsung pada
ajaran Konsili Vatikan II, bahwa dalam membangun kehidupan
iman jemaat para imam tidak pernah bekerja demi suatu ideologi
atau bagi suatu partai.127 Sinode Para Uskup di Roma pada tahun
1971 menegaskan kembali ajaran Konsili tersebut dengan nada
sedikit lain: “Bilamana ada bermacam-macam pilihan politik,
sosial, atau ekonomi yang legitim, para imam Katolik memiliki hak
untuk menentukan posisi dan pilihannya, seperti setiap warga
negara yang lain. Namun, mengingat pilihan-pilihan politik pada
126
Jorge De Otaduy, Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, Vol.
II/1, ed. Angel Marzoa, Jorge Miras, dan Rafael Rodríguez-Ocaña (Canada /
Chicago: Wilson&Lafleur / Midwest Theological Forum, 2004), 385-87.
127
Konsili Vatikan II, Presbyterorum Ordinis, 473.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
dasarnya bersifat sementara (contingent) dan tidak pernah
menafsirkan atau mencerminkan Injil secara tetap dan utuh, maka
setiap imam Katolik harus menjadi saksi mengenai “dunia yang
akan datang”, dan karenanya harus menjaga jarak dari jabatan atau
keterlibatan politik. Agar tetap bisa menjadi tanda dan alat
pembangun kesatuan yang efektif, serta dapat mewartakan Injil
dalam kepenuhannya, para imam dapat diwajibkan untuk
berpantang dan menjauhkan diri dari bidang politik”.128 Meski
demikian, norma kan. 287, §2 sama sekali tidak bermaksud
menghapus hak-hak politik para imam. Mereka tetap memiliki
secara utuh dan penuh hak atas pendapat politik pribadi dan
mewujudkan hak itu dalam pemberian suara (coblosan) menurut
hati nuraninya sendiri.
Sebelumnya, dalam norma kan. 285, §3 para klerikus dilarang
menerima jabatan-jabatan publik yang mengandung pelaksanaan
otoritas sipil. Otoritas sipil itu mencakup kuasa legislatif,
administratif, dan yudikatif, misalnya anggota DPR, presiden,
menteri, gubernur, walikota, camat, hakim negara, dan sebagainya.
Yang dilarang tidak hanya “menerima jabatan publik”, melainkan
juga “mencalonkan diri untuk suatu jabatan publik”.129 Berkaitan
dengan hal ini, secara lebih jelas dan konkret Sinode Para Uskup
1971 mengajarkan bahwa mengemban fungsi pemimpin atau secara
aktif menjadi sayap militer bagi kepentingan sebuah partai politik
harus dijauhkan dari kehidupan imam Katolik, kecuali dalam
kasus-kasus kekecualian hal itu sungguh-sungguh dituntut demi
kebaikan umum, namun selalu dengan persetujuan Uskup, setelah
Uskup itu berkonsultasi dengan Dewan Imam, dan jika perlu
dengan Konferensi Para Uskup.130
128
Sinode Para Uskup, Ultimis Temporibus, 30 November 1971, dalam
Enchiridion Vaticanum, Vol. 4, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1971-1973,
ed. Erminio Lora (Bologna: Dehoniano, 1978), 781.
129
Beal, Coriden, dan Green, New Commentary, 376; Tomas Rincón Peréz, Code
of Canon Law Annotated, ed. Ernest Caparros, Michel Thériault, dan Jean Thorn
(Montréal: Wilson&Lafleur, 1993), 236-370.
130
Sinode Para Uskup, Ultimis Temporibus, 781.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
Kembali ditekankan dalam norma-norma itu bahwa selaku figur
publik dan pemimpin jemaat para imam Katolik harus menjadi
representasi Gereja, yang mengemban visi dan misi Gereja secara
utuh. Apakah visi dan misi Gereja Katolik itu? Para Bapa Konsili
Vatikan II mengajarkan bahwa misi khusus yang dipercayakan oleh
Yesus Kristus kepada Gereja tidak terletak di bidang politik,
ekonomi atau sosial, melainkan di bidang religi. Selanjutnya,
berdasarkan misi dan hakikatnya Gereja tidak terikat pada bentuk
khas kebudayaan manusiawi atau sistem politik, sistem ekonomi
atau sosial manapun juga. Dengan kata lain, Gereja tidak
mengidentikkan diri dan tidak diidentikkan dengan partai politik
mana pun, melainkan bekerja sama dengan sistem politik dan
sistem pemerintahan mana pun yang sah, demi kebaikan umum,
persaudaraan dan persatuan bangsa manusia. Karena itu,
berdasarkan sifat universalnya Gereja dapat menjadi tali pengikat
yang sangat erat antar berbagai masyarakat dan bangsa manusia,
asal mereka mempercayai Gereja, dan sungguh-sungguh mengakui
kebebasannya yang sejati untuk menunaikan misinya itu.131
Selain itu, larangan untuk mengambil bagian secara aktif dalam
partai politik dimaksudkan agar para imam tidak mengambilalih
apa yang menjadi peran dan tugas khas kaum awam di dalam
Gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai anggota penuh
Gereja dan masyarakat sipil, kaum awam memiliki tugas khas
mengelola bidang-bidang duniawi (ilmu pengetahuan dan
teknologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan, dan
keamanan) dalam terang ajaran Injil dan ajaran Gereja, serta
digerakkan oleh cinta-kasih kristiani. Di bidang-bidang itulah kaum
awam Katolik hadir dan berkiprah secara langsung dan konkret.132
Ketentuan itu juga didukung oleh norma kanonik lain, bahwa para
klerikus hendaknya mengakui dan memajukan misi yang
dilaksanakan awam dalam Gereja dan dunia menurut peranannya
masing-masing (kan. 275, §2). Paus Benediktus XVI, ketika masih
131
Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, 559.
132
Konsili Vatikan II, Apostolicam Actuositatem, 349.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
memimpin Kongregasi Ajaran Iman, menegaskan bahwa
keterlibatan di bidang politik adalah tugas khas kaum awam. Kaum
awam tidak pernah boleh dihalangi atau diasingkan dari partisipasi
aktif dan langsung dalam kehidupan politik suatu bangsa, dalam
kerja sama dengan semua warga negara yang lain, sebagaimana
juga tidak bisa diasingkan dari berbagai aktivitas di bidang
ekonomi, sosial, legislatif, administratif, dan kultural, demi
menumbuhkembangkan bonum commune secara organik dan
institusional. Bonum commune itu mencakup promosi dan
pemeliharaan tatanan publik dan perdamaian, kebebasan dan
kesamaan atau kesetaraan, hormat terhadap hidup manusia dan
lingkungan hidup, keadilan, dan solidaritas, dan sebagainya.133
Selanjutnya, menjadi tugas hierarki Gereja untuk mendorong
kegiatan kaum awam yang khas itu dengan menunjukkan prinsip-
prinsip berpolitik yang benar dan memberikan bantuan rohani.
Untuk itu, para Uskup hendaknya memberikan imam pendamping
bagi kaum awam yang terlibat aktif dalam perpolitikan, agar dalam
berpolitik kaum awam sungguh-sungguh dibimbing oleh hati-
nurani kristiani, mengambil pilihan-pilihan politis yang tidak
mengkhianati tuntutan-tuntutan etis fundamental demi kebaikan
umum masyarakat luas. Ini karena tuntutan etis fundamental
berakar dalam martabat pribadi manusia dan merupakan bagian
dari hukum moral kodrati.134
Kontribusi bagi Kepemimpinan Religius Para Pemimpin
Ormas Keagamaan di Indonesia
Beberapa pemimpin ormas keagamaan Islam di DKI Jakarta dan
sekitarnya, pada trimester pertama 2017 sebenarnya telah
133
Kongregasi Ajaran Iman, Nota Doktrinal L’impegno del cristiano, 24
November 2002, dalam Enchiridion Vaticanum, Vol. 21, Documenti Ufficiali
della Santa Sede 2002, ed. Erminio Lora (Bologna: Dehoniano, 2005), 1023-24.
134
Konsili Vatikan II, Apostolicam Actuositatem, 370; Kongregasi Ajaran Iman,
L’impegno del Cristiano, 1030.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
menerapkan leadership yang efektif dan mengagumkan dalam
mengompakkan secara internal dan eksternal segenap anggota
kelompoknya, untuk menghadapi isu penodaan agama Islam oleh
seorang calon pilgub DKI Jakarta. Mereka tidak ingin si penoda
agama itu kembali memimpin ibukota Jakarta untuk lima tahun
lagi. Karena itu, mereka ingin agar ia diadili dan dihukum, dan
sekaligus gagal dalam pilkada gubernur Jakarta. Fakta
menunjukkan bahwa para pemimpin ormas keagamaan itu berhasil
mengkonsolidasi tidak hanya kelompoknya saja, melainkan juga
ormas-ormas lain yang menganut nilai-nilai keagamaan yang sama.
Menurut teori-teori leadership, mereka berhasil menerapkan
leadership as the exercise of influence. Artinya, para pemimpin
ormas keagamaan itu menggunakan kepemimpinannya untuk
melancarkan sebuah pengaruh, lewat pidato, sikap dan perilaku
yang jelas, agar segenap anggota organisasi memiliki sikap dan
perilaku yang sama, serta bersama-sama menjalankan aksi tertentu
untuk mencapai satu target yang sama.135 Selain itu, mereka
berhasil menjalankan leadership as a form of persuasion. Artinya,
mereka menggerakkan seluruh anggota kelompoknya untuk suatu
aksi bersama, dengan menggunakan persuasi dan inspirasi, yang
diungkapkan dalam bentuk ajakan-ajakan yang sangat emosional.
Model kepemimpinan seperti itu biasanya memang digunakan
dalam dunia politik, dan dalam menghadapi perkara-perkara sosial-
keagamaan.136
Sebenarnya tidak ada yang salah dalam cara memimpin kelompok
seperti di atas. Namun, jika kepemimpinan itu ternyata
menimbulkan dampak negatif berkepanjangan terhadap kehidupan
bersama yang damai antar warga masyarakat majemuk hingga
mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, maka ada kekurangan
yang berat dan serius di sana. Persoalannya tentu tidak terletak
pada organisasi internal kelompok, melainkan pada bagaimana
135
Bernard M. Bass, ed., Stogdill’s Handbook of Leadership: A Survey of Theory
and Research (New York: Free Press; London: Collier Macmillan, 1981), 9-10.
136
Bass, Stogdill’s Handbook of Leadership, 10-11.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
pemimpin religius mampu melihat dan memperkenalkan perspektif
dan paradigma baru kepada segenap anggota kelompok atau
bawahannya, yang tadinya terkungkung pada cara pandang yang
sempit, sektarian, ekstrim, dan intoleran. Studi komparatif dengan
melihat gaya kepemimpinan para pemuka agama Katolik,
khususnya Paus Benediktus XV dan Yohanes XXIII, menunjukkan
unsur-unsur yang perlu ditambahkan pada model kepemimpinan
para pimpinan ormas keagamaan tersebut.
Unsur baru itu bisa dirumuskan secara negatif sebagai berikut.
Dalam situasi konflik atau potensi konflik horisontal di antara
kelompok-kelompok masyarakat, para pemimpin ormas keagamaan
tidak boleh ikut terkooptasi dan menjadi sektarian, partisan atau
parsialistik dengan membela kepentingan kelompoknya sendiri atau
kelompok-kelompok lain yang memiliki identitas dan sentimen
keagamaan yang sama, untuk menghadapi dan memusuhi
kelompok agama yang lain. Kalau tidak, pemuka agama bukannya
mendamaikan dan mempersatukan warga masyarakat, melainkan
justru memecah-belah berdasarkan sentimen keagamaan, alias
mengalihkan dan mengkanalisasi konflik dan perpecahan, yang
sebelumnya barangkali disebabkan oleh faktor-faktor non-agama,
menjadi konflik atas dasar perbedaan agama atau keyakinan
religius. Sejarah membuktikan bahwa konflik atas dasar sentimen
keagamaan adalah yang paling panas, paling mengerikan, dan
sangat irasional. Konflik itu tidak hanya menimbulkan banyak
korban jiwa, melainkan juga peradaban dan persaudaraan insani,
serta pendangkalan paham dan praktik keimanan yang autentik dari
warga masyarakat.
Bila dirumuskan secara positif, dalam situasi konflik berdasarkan
primodialisme SARA pemimpin ormas keagamaan harus memiliki
dan menunjukkan kepada para anggota atau bawahannya sebuah
kecerdasan spiritual, yakni dengan mengajak keluar dari dirinya
sendiri, mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang
mampu mendekatkan dan bahkan menyatukan kelompoknya
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda agama atau
keyakinan religius, demi kebaikan umum, keadilan, persaudaraan
universal, penegakan hak asasi manusia, khususnya kebebasan
agama dan beragama, yang merupakan cita-cita bersama
masyarakat plural. Tidaklah sulit menemukan prinsip-prinsip dan
nilai-nilai universal itu dalam ajaran agama masing-masing. Agama
Islam sendiri sebenarnya merupakan agama rahmatan lil’alamin,
rahmat bagi seluruh alam semesta. Prinsip dan nilai tersebut
mestinya mendorong para pemimpin ormas keagamaan Islam untuk
mengambil posisi berdialog dengan semua unsur alam, khususnya
sesama manusia dari berbagai suku, agama dan keyakinan religius.
Keragaman merupakan rahmat dan anugerah Allah yang Mahaesa,
dan sejauh berasal dari keesaan Allah keragaman akan mengantar
kepada kesatuan dan persatuan. Dengan demikian, kebhinnekaan
bukanlah musuh yang harus diperangi, melainkan menjadi alasan
untuk bersyukur dan memuji Tuhan Allah yang Maha Esa
(celebration of diversity).
Penutup
Sebagai negara kesatuan yang terdiri dari aneka ragam suku,
agama, ras, dan golongan, Indonesia selalu berada dalam resiko
keterpecahan, jika kesatuan dalam keragaman ini tidak dirawat
dengan baik dan dihidupi dengan penuh syukur. Posisi dan peran
pemuka agama dan pemimpin ormas keagamaan sangat penting
dan strategis dalam persoalan ini. Ketika muncul konflik atau
potensi konflik sosial yang mengandung unsur primordial SARA,
pemuka agama dan pemimpin ormas keagamaan tidak boleh jatuh
kepada sektarianisme, ekstremisme, dan sikap partisan, yang
semakin mempertajam atau memperparah konflik horisontal antar
warga. Sebaliknya, para pemuka agama dan pemimpin ormas
keagamaan harus segera awas dan mawas diri terhadap bahaya
yang mengancam kehidupan bersama. Mereka harus menunjukkan
kecerdasan spiritual dalam melaksanakan kepemimpinan mereka
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
terhadap para anggota atau bawahannya. Kecerdasan spiritual itu
berupa kemampuan dan kerelaan untuk keluar dari diri sendiri,
mengatasi kesempitan wawasan diri, mengadopsi kepentingan yang
lebih luas daripada kepentingan organisasi atau kelompok
agamanya. Dengan meninggalkan dan menanggalkan kepentingan
sempit dan sepihak golongannya, mereka hendaknya menerapkan
rasionalitas dan moralitas yang diterima umum, memperjuangkan
prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang di-share oleh semua orang dari
semua golongan, yakni bonum commune, keadilan, hak asasi
manusia, peaceful co-habitation masyarakat majemuk. Jika terjadi
pelanggaran terhadap nilai universal itu, bolehlah mereka
memperjuangkan penegakan hukum, tidak hanya jika pelanggaran
itu merugikan kelompoknya sendiri, melainkan juga ketika
merugikan orang dari luar kelompoknya. Meski demikian, dalam
menuntut penegakan hukum mereka tetap harus menjunjung
setinggi-tingginya damai dan kerukunan di antara warga
masyarakat.
Daftar Pustaka
Allegri, Renzo. Il Papa Buono: La Storia di Giovanni XXIII.
Milano: Oscar Mondadori, 2000.
Bass, Bernard M, ed. Stogdill’s Handbook of Leadership: A Survey
of Theory and Research. New York: Free Press; London: Collier
Macmillan, 1981.
Beal, John P., James A. Coriden, dan Thomas J. Green, eds. New
Commentary on the Code of Canon Law. New York: Paulist Press,
2000.
Benediktus XV. Ensiklik Ad beatissimi Apostolorum Principis, 1
November 1914. Dalam Enchiridion delle Encicliche, Vol. 4, Pio X
e Benedetto XV (1903-1922), diedit oleh Erminio Lora dan Rita
Simionati, 464-95. Bologna: Dehoniano, 1998.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Pemimpin Ormas Keagamaan A Comparative Study on Shi‘îte
Caparros, Ernest, Michel Thériault, dan Jean Thorn, eds. Code of
Canon Law Annotated. Montréal: Wilson&Lafleur, 1993.
Kelly, John N.D. Grande Dizionario Illustrato dei Papi,
diterjemahkan oleh Antonella Riccio. Casale Monferrato: Piemme,
1995.
Kongregasi Ajaran Iman, Nota DoktrinalL’impegno del Cristiano.
24 November 2002. Dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 21,
Documenti Ufficiali della Santa Sede 2002, diedit oleh Erminio
Lora, 1022-37. Bologna: Dehoniano, 2005.
Konsili Vatikan II. Dekret Apostolicam Actuositatem. Dalam
Dokumen Konsili Vatikan II, diterjemahkan oleh Robertus
Hardawiryana, 339-80. Jakarta: Dokpen KWI / Obor, 1993.
______-----. Dekret Presbyterorum Ordinis. Dalam Dokumen
Konsili Vatikan II, diterjemahkan oleh Robertus Hardawiryana,
459-508. Jakarta: Dokpen KWI / Obor, 1993.
______-----. Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes. Dalam
Dokumen Konsili Vatikan II, diterjemahkan oleh Ro-bertus
Hardawiryana, 509-637. Jakarta: Dokpen KWI / Obor, 1993.
Lora, Erminio, dan Rita Simionati, eds. Enchiridion delle
Encicliche, vol. 4, Pio X e Benedetto XV (1903-1922). Bologna:
Dehoniano, 1998.
Marzoa, Angel, Jorge Miras, dan Rafael Rodríguez-Ocaña, eds.
Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, vol. II/1.
Canada / Chicago: Wilson&Lafleur / Midwest Theological Forum,
2004.
Sinode Para Uskup. Convenientes ex Universo. 30 November 1971.
Dalam Enchiridion Vaticanum, vol. 4, Documenti Ufficiali della
Santa Sede 1971-1973, diedit oleh Erminio Lora, 800-39. Bologna:
Dehoniano, 1978.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Alphonsus Tjatur Raharso Luthfi Rahman
______-----. Ultimis Temporibus. 30 November 1971. Dalam
Enchiridion Vaticanum, vol. 4, Documenti Ufficiali della Santa
Sede 1971-1973, diedit oleh Erminio Lora, 750-99. Bologna:
Dehoniano, 1978.
Tjatur Raharso, Alphonsus. Pernak-Pernik Ajaran dan Keutamaan
San Giovanni XXIII. Malang: Widya Sasana Publication, 2014.
Yohanes XXIII. Journal of a Soul, diterjemahkan oleh Dorothy
White. London: Geoffrey Chapman, 2000.
______-----. Ensiklik Pacem in Terris. 11 April 1963. Dalam
Enchiridion delle Encicliche, Vol. 7, Giovanni XXIII e Paolo VI
(1958-1978), diedit oleh Erminio Lora dan Rita Simionati, 380-
469. Bologna: Dehoniano, 1994.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
REVITALISASI IDENTITAS DIRI KOMUNITAS MASJID
DALAM PERUBAHAN BUDAYA GLOBAL:STUDI PADA
KOMUNITAS MASJID SAKA TUNGGAL BANYUMAS,
MASJID RAYA AL FATAH
AMBON, DAN MASJID AGUNG JAMI’ SINGARAJA BALI
DALAM PERUBAHAN BUDAYA GLOBAL
Ahmad Salehudin, MA.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ahmad_salehudin@yahoo.co.id
Dr. Moch Nur Ichwan
Dicky Sofjan, Ph.D
Abstract
This study examines how three communal mosques: Masjid Saka
Tunggal Cikakak Banyumas, Masjid Raya Al Fatah Ambon, and Masjid
Agung Jami’ Singaraja respond toward globalization. Globalization that
is characterized with the territorial demarcations of states’ administration
jurisdiction, political currents, economic strata, and religions has shaped
global villages with cultural homogeneity as its estuary. Strong cultures
tend to crush the vulnerable cultures. These conditions tend to
generate a dilemma for the existence of an identity, including the identity
of communal mosques. However, communal mosques are not merely a
set of inanimate objects which can only passively accept external
influences. They are a collection of beings who “tactically”
respond to the “strategy” of the global cultural cooptation. The result
of this study reveals that communal mosques become a collective
awareness of each its individual to respond to and live the life amidst the
increasingly uncontrollable wave of global cultures. Global cultures, as
long it benefits, are adapted and adopted to strengthen their communal
identity and, otherwise, left when they bring disadvantages. In order to
protect communal identities, the result of this study offers three
Religió: Jurnal Studi Agama-agamaMutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Volume 78, Nomor 21, Desember20178| ISSN: (p) 2088-6330; (e) 2503-3778p-ISSN:
2088-7523; e-ISSN: 2502-6321| 2151-23450-77
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
ways: habituation and institutionalization of the communal identity,
reinforcing the ancestral authority, and affirming the institutional vision
and mission.
[Abstrak: Penelitian ini mengkaji respon tiga komunitas masjid, yaitu
Masjid Saka Tunggal Cikakak Banyumas, Masjid Raya Al Fatah Ambon,
dan Masjid Agung Jami’ Singaraja terhadap globalisasi. Globalisasi yang
ditandai oleh menghilangnya batas-batas administrasi negara, aliraan
politik, strata ekonomi, dan agama telah membentuk kampung global
dengan homogenisasi budaya sebagai muaranya. Budaya yang kuat
cenderung menggilas budaya yang lemah. Kondisi ini cenderung
melahirkan dilemma bagi eksistensi identitas, termasuk identitas
komunitas masjid. Namun demikian, komunitas masjid bukanlah
sekumpulan benda mati yang hanya bisa pasrah menerima pengaruh luar,
tetapi sekumpulan mahluk hidup yang “taktik” untuk merespon “strategi”
kooptasi budaya global. Hasil penelitian menunjukkan masjid-masjid
komunitas menjadi collective awareness para individu untuk merespon
dan menjalani kehidupan di tengah samudra budaya global yang semakin
tak terkendali. Budaya global diadaptasi dan diadopsi selama bermanfaat
untuk menguatkan identitas komunitasnya, dan bersikap acuh jika tidak
sesuai atau membahayakan. Untuk melindungi identitas komunitasnya,
ada tiga hal yang dilakukan, yaitu melalui pembiasaan dan pelembagaan
identitas komunitas, meneguhkan otoritas leluhur, dan peneguhan visi
misi lembaga.]
Key word: globalization, identity, community, tactic, strategy.
globalisasi, identitas, komunitas, taktik, strategi.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Pendahuluan
Masyarakat di seluruh dunia saat ini sedang ditransformasikan
secara dramatis oleh globalisasi.137 Globalisasi telah
menginteraksikan masyarakat yang bertebaran dengan segenap
perbedaan ras, agama, dan geo-kultur yang dimilikinya berada
dalam satu perkampungan besar yang disebut global village.138
Dengan jaringan teknologi informasi yang berkembang secara
revolusioner, seperti jaringan telekomunikasi dan situs internet,
masyarakat di suatu negara dengan di negara lain dapat berinteraksi
tanpa hambatan waktu dan batas-batas kewilayahan. Proses sosial
ini menghasilkan perubahan besar-besaran dan cepat dalam semua
dimensi kehidupan umat manusia. Kondisi ini kemudian disebut
juga sebagai era globalisasi.139
Globalisasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan, interaksi sosial,
dinamika politik, cara beragama hingga cara makan, berpakaian
dan menikmati kehidupan. Semua bidang kehidupan masyarakat
dipengaruhi oleh globalisasi.140Tidak ada satu pun masyarakat di
dunia ini yang tidak terkena efek globaliasasi, termasuk pada
komunitas keagamaan.141 Globalisasi tidak saja menjanjikan
137
George Ritzer & Dougles J. Goodman, Teori Sosiologi Modern,
Diterjemahkan oleh Alimandan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm.
587.
138
M. Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina,
1995), hlm. 110.
139
A. Qodri Azizy, Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 19-20, AsiaDHRRA Secretariat, The Impact
Globalization on the Social-Cultural Live of Grassroots People in Asia, (Jakarta:
Grasindo, 1998), hlm. 7.
140
Martin Wolf, Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan, Diterjemahkan oleh
Samsudin Berlian, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), xi., Bdk.
Firmansyah, Globalisasi: Sebuah Proses Dialektika Sistemik, (Jakarta: Yayasan
Sad Satria Bhakti, 2007), hlm. 10.
141
Menurut Down Browning seperti dikutip oleh Pdt. E. Gerrit Singgih,
menjelaskan bahwa globalisasi memberikan arti sebagai; 1) misi universal dari
gereja, 2) kerjasama ekumenis, 3) dialog diantara agama Kristen dengan agama-
agama lain, dan 4) masalah ketidakadilan sosial, Lihat, E. Gerrit Singgih,
“Globalisasi dan Kontekstualisasi: Menuju Sebuah Kesadaran Baru Mengenai
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
harapan-harapan yang indah bagi masyarakat, melainkan juga
menimbulkan kegelisahan-kegelisahannya tersendiri.142 Globalisasi
menghadirkan hantu ketakutan dan kegelisahan, salah satunya
adalah adanya anggapan bahwa kebudayaan-kebudayaan di luar
Barat harus menyesuaikan diri dengan gagasan-gagasan kultural
Barat,143sehingga globalisasi juga ditandai dengan terciptanya
sistem dunia yang tunggal.
Kondisi ini memicu munculnya krisis identitas. Persoalan identitas
masyarakat menduduki tempat yang unik di era globalisasi yang
tengah berlangsung. Ia kembali menemukan vitalitasnya untuk
eksis dalam langgam yang berbeda.144Ini artinya, identitas dapat
lahir dalam langgam menolak pemangkiran yang sewenang-
wenang terhadap jatidiri. Oleh karena itu, dalam proses
pencariannya tidak mungkin lagi suatu masyarakat mampu
merumuskan esensi tanpa suatu identitas, sebab persoalan identitas
pada dasarnya lebih sebagai hasil proses kontestasi, bukan sekedar
fiksasi. Persoalan identitas merupakan representasi diri berhadapan
dengan pihak yang kuat.145
Dalam konteks globalisasi, persoalan identitas menjadi semakin
menguat dalam dinamika masyarakat Islam. Ada adagium kuat
Realitas di Sekitar Kita”, dalam Transformasi Praktek-Praktek Keagamaan
Lokal, Renai: Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora, Tahun II, No. 34, Edisi
Juli-Oktober 2002, hlm. 44.
142
Globalisasi dengan demikian menjadi paradok, di satu sisi ia membuat dunia
menuju ke arah yang lebih demokratis, semakin banyak negara yang
menghormati hak asasi manusia, kesetaraan, dan keterbukaan. Namun di sisi
lain, ia juga menghasilkan penindasan dan dominasi baru yang membahayakan
kemanusiaan, seperti maraknya perang, terorisme, dan kesenjangan distribusi
kekayaan, baik di negara maju maupun negara berkembang, Lihat, Firmansyah.
Globalisasi: Sebuah Proses. Hlm. 8-9.
143
George Ritzer & Dougles J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, 588, M.
Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, 110, Fredric Jameson & Masao
Miyoshi, eds., The Culture of Globalization, (USA: Duke University Press,
2004), hlm. 32.
144
Martin Lukito Sinaga, Identitas Poskolonial Gereja Suku dalam Masyarakat
Sipil, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 5.
145
Martin Lukito Sinaga, Identitas Poskolonial Gereja. Hlm. 5.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
dalam komunitas Muslim di Indonesia, globalisasi yang dianggap
bias kebudayaan Barat merupakan aktor hegemonik yang telah
mengakibatkan perubahan dalam sendi-sendi kehidupan sosial
Islam, terutama timbulnya krisis identitas. Krisis identitas seperti
pedang bermata dua, ke dalam dapat meneguhkan identitas
sosialnya, namun keluar menjadi kontraproduktif bagi eksistensi
komunitas Islam itu sendiri, seperti munculnya stigmatisasi global
atas Islam dengan aksi terorisme dan kekerasan yang dilakukan
oleh kelompok-kelompok radikal pada satu sisi,146dan kegagalan
Islam dalam memberikan kontribusi positif bagi globalisasi yang
dipandang bias tersebut.147
Di era globalisasi, identitas menemukan vitalitasnya karena
kebutuhan terhadap penemuan dan pencarian jatidiri dalam
merumuskan esensi atau makna. Namun demikian, selain
meneguhkan, globalisasi juga menghasilkan persoalan atas diri
identitas itu sendiri.148Letak persoalannya ada pada ketika
peneguhan identitas keagamaan, misalnya diekspresikan melalui
gerakan resistensi yang menimbulkan stigmatisasi, sebagaimana
yang pernah dilakukan oleh kelompok Laskar Jihad dalam konflik
Muslim dan Kristen di Maluku sepanjang tahun 1999-2003.
Kekristenan yang dianggap mewakili Dunia Barat menimbulkan
146
Bdk., Muhammad Wildan, Mapping Radical Islamism in Solo: A Study of the
Poliferation of Radicalism in Central Java, dalam al-Jamiah Journal of Islamic
Studies UIN Sunan Kalijaga, Volume 46, No. 1/ 2008, hlm. 61.
147
Perdebatan-perdebatan penting yang mengairahkan dalam mencari bentuk
masyarakat ideal dan sistem kemasyarakatan yang sanggup mengangkat hajat
hidup orang banyak terus berlangsung dalam era globalisasi ini. Demikian pula
perdebatan mengenai gagasan-gagasan besar di bidang sosial, politik, agama dan
kebudayaan terus terjadi dalam berbagai bentuknya, terutama tema-tema besar di
seputar hubungan Islam dan Barat di awal abad ke-21 ini, Lihat, Martin Wolf,
Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan, hlm. xi.
148
Globalisasi telah membuat banyak orang kehilangan orientasi dan definisi
atas dirinya, sehingga mereka ingin kembali ke identitas dasarnya yang dibangun
di atas dasar “materi tradisional bentukan dunia komunal”. Identitas kemudian
membantu mengatasi krisis individu maupun kelompok dengan membangun
kembali makna yang hilang, Lihat, Radjasa Mu’tasin, ed., Model-Model
Penelitian dalam Studi Keislaman, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan
Kalijaga, 2006), hlm. 83-84.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
ancaman dan krisis identitas bagi sekelompok Muslim di Maluku,
sehingga melahirkan konflik dan kekerasan berlarut-larut yang
membahayakan kesatuan nasional.149 Belum lagi munculnya
gerakan terorisme dan aksi bom bunuh diri sebagai bentuk
“perlawanan” atas globalisasi yang dianggap membahayakan
identitas komunitas, seperti yang pernah terjadi di Jimbaran dan
Pantai Kuta Bali, Hotel Ritz Cartlon Jakarta, dan rangkaian aksi
bom bunuh diri lainnya di Indonesia.150
Dalam konteks lokal, globalisasi juga melahirkan ruang-ruang
responsi identitas kelompok dalam bentuk pengikatan diri pada
kesadaran etnik dan budaya. Ketika kesadaran etnik dan budaya,
bahkan agama bertemu, maka pembentukan identitas sosial kian
menemukan vitalitasnya.151Salah satunya adalah komunitas masjid.
Masjid merupakan identitas bagi komunitasnya, sehingga menjadi
bagian penting yang “terancam” oleh globalisasi. Namun demikian,
hampir tidak ada peneliti yang mencoba melihat bagaimana upaya
komunitas masjid dalam merespon globalisasi. Misalnya tulisan
tentang masjid yang lebih menitik beratkan pada aspek sejarahnya
dapat dilihat pada hasil penelitian yang diterbitkan Departemen
Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro tahun 1999/2000.
Penelitian tersebut dilakukan untuk pijakan pengambilan kebijakan
149
Lihat Badrus Saleh, Conflict, Jihad, and Religious Identity in Maluku,
Eastern Indonesia, dalam al-Jamiah Journal of Islamic Studies UIN Sunan
Kalijaga,Volume 46, No. 1/2008, hlm. 72.
150
Muhammad Harfin Zuhdi, “Radicalism and Effort De-Radicalization of
Religious Understanding”, dalam The Strategic Role of Religious Education in
the Development of Culture of Peace, (Jakarta: Center for Research and
Development of Religious Education and Religion Ministry of Religious Affairs
of the Republic of Indonesia, 2012), hlm. 252.
151
Menurut Mead sebagaimana dikutip oleh Deddy Mulyana, identitas sosial
yang dikaitkan dengan etnisitas bertolak dari konsep diri individu dalam
berkelompok itu bersumber dari partisipasinya dalam budaya dimana ia
dilahirkan dan diterima. Budaya diperoleh individu melalui simbol-simbol yang
memberikan makna dengan cara eksprimentasi terus menerus sehingga
membentuk ikatan kekeluargaan (familiarity), Lihat, Deddy Mulyana,
Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.
231
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
dengan judul Konservasi dan Pengembangan Masjid Agung
Kauman Semarang untuk Identitas Budaya dan Pariwisata. Dari
hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa dari segi arkeologis
masjid Kauman Semarang masih mempunyai arsitektur bangunan
yang mengacu pada tradisi Hindu. Hal ini mendorong kebijakan
untuk dilestarikan sebagai bagian dari asset wisata.
Tulisan lain yang terfokus pada sejarah juga dapat dilihat dari
Masmedia Pinem dengan judul Masjid Pulo Kameng Akulturasi
dan toleransi Masyarakat Aceh. Hasil penelitian Masmedia
mengatakan bahwa sejarah berdirinya masjid Pulo Kameng
merupakan hasil dari akulturasi budaya Cina, Hindu-Budha dan
kebudayaan setempat. Pendirian masjid Pulo Kameng dilaksanakan
pada masa kerajaan Teuku Kejruen Amansyah, pada tanggal 28
Ramadan 1285 H/12 Januari 1869 M dengan melibatkan
masyarakat sekitar dari berbagai wilayah dari Kampung Paya,
Kampung Purut, Kampung Kluet, Kampung Krueng Batu,
Kampung Ruwak, dan Kampung Tinggi.
Tulisan Sulkhan Chakim yang berjudul Estetika, Masjid dan
Dakwah. Dalam tulisan tersebut lebih menekankan pada dimensi
fungsi masjid. Masjid sebagai ruang spiritual menduduki posisi
sebagai tempat ibadah shalat dan bingkai kemanusiaan. Sedangkan
masjid sebagai kontrol dari akhlak masyarakat tertuju pada dua hal
yaitu peningkatan harkat dan martabat manusia dan kedaulatan
masyarakat. Terakhir, masjid sebagai media dakwah untuk
menyebarkan ajaran Islam dimaknai sebuah tempat untuk
memberikan petunjuk pada orang lain dan sebagai upaya
pembebasan dari berbagai belenggu kehidupan yang bersifat
duniawi.
Tulisan lain yang mengkaji tentang masjid adalah tulisan Yulia Eka
Putri yang berjudul Kontradiksi Simbol dan Substansi Nilai Islam
dalam Arsitek Masjid. Penelitian ini melibatkan beberapa masjid
yaitu Masjid Agung Semarang, Masjid An-Nur Pare, Kediri, Masjid
At-Tin TMII dan Masjid Dian al-Mahri, Depok. Penelitian tersebut
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
menggunakan teori normative criticism dengan hasil bahwa saat ini
masjid yang dibangun di beberapa daerah cenderung
mengedepankan arsitektur yang bersifat monumental. Artinya,
lebih mengedepankan simbol kemewahan atau kejayaan pada
masa-masa tertentu, sehingga tujuan masjid sebagai tempat ibadah
yang seharusnya mengajarkan tentang kesederhanaan berubah
menjadi kemewahan. Dampaknya fungsi masjid berubah menjadi
tempat wisata atau ziarah masjid yang berbau komersil. Hasil akhir
dari penelitian tersebut mengatakan bahwa beberapa masjid yang
diteliti memiliki unsur kontradikstif dengan nilai-nilai
kesederhanaan, kemanfaatan, keterbukaan, kesetaraan,
kesetempatan dan penghindaran kemudharatan. Sedangkan hasil
penelitian yang terfokus pada tema peran masjid dapat dilihat dari
tulisan Purwanto yang berjudul Peranan Keberadaan Masjid Agung
Demak dalam Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi dan
Budaya Masyarakat Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak. Menurutnya, Masjid Agung Demak mempunyai
pengaruh dalam usaha untuk memakmurkan kehidupan masyarakat
setempat.
Tulisan Ahmad Salehudin (2007) dengan judul satu dusun tiga
masjid: Anomali Ideologisasi Agama dalam Agama menyajikan
fakta menarik bahwa masjid tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga
identitas kelompok-kelompok keagamaan. Sebagai identitas,
masjid menjadi ruang yang sangat terbatas, yaitu menjadi pemilah
antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Namun
demikian tulisan Salehudin tersebut belum membahas tentang
bagaimana masjid sebagai identitas tetap eksis dalam budaya
global.
Dari beberapa penelitian tersebut, ada tiga fokus yang menjadi ciri
khusus dari penelitian tentang masjid yaitu: sejarah berdirinya
masjid, peran dan manfaat masjid dalam menegakkan ajaran dan
syari’at Islam serta kajian arsitektur, dan simbol dari bangunan
masjid. Pada kasus komunitas tiga masjid, yaitu Masji Saka
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Tunggal Banyumas, Masjid Al Fattah Ambon, dan Masjid Agung
Singaraja Bali, identitas sosial tidak hanya mengalami revitalisasi
melainkan juga dipakai untuk meresponsi perubahan budaya
global. Ketiga masjid tersebut terbentuk dalam sejarahnya yang
panjang, yaitu merupakan hasil dari pergumulan dengan budaya
lokalnya, sekaligus di tengah kemajemukan agama masyarakatnya.
Namun perubahan budaya global kekinian tentunya menimbulkan
persoalan sendiri bagi identitas ketiga masjid tersebut. Ada tiga hal
yang dibahas dalam artikel ini, yaitu mengapa hal itu dapat terjadi?
bagaimana gambaran sosiologis-antropologisnya ketika identitas
sosial terbentuk sekaligus menciptakan responsi atas perubahan
budaya global? Dan adakah pengaruh perubahan budaya global
tersebut terhadap eksistensi identitas komunitas ketiga masjid
tersebut?
Globalisasi dan Dinamika Identitas Komunitas: Tinjauan
Teoritik
Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, berakar dari
bahasa Latin, “idem” yang berarti sama dan “identidem” yang
berarti “berulang-ulang atau berkali-kali”. Kedua istilah ini
membentuk kata baru identitas yang berarti, sebelah menyebelah
dengan mereka yang serupa (likeness) dan satu (oneness).152
Dengan demikian, secara harfiah kata identitas bermakna sama,
baik sama dalam bentuk maupun isi. Identitas mencerminkan suatu
kelompok yang mempunyai kesamaan dalam rupa yang
diwujudkan ke dalam simbol dan atribut sosial di masyarakat.
Simbol dan atribut kemudian mengikat isi, yakni karakteristik nilai
dan cita-cita sosial yang sama yang menjadi identitas sosialnya.
Henri Tajfel adalah tokoh awal yang menggagas teori identitas
sosial yang berkaitan dengan penjelasan mengenai prasangka,
152
Markus Dominggus Lere Dawa, Teori-teori Sosial Tentang Identitas, Tugas
Makalah Program Doktor Sosiologi Agama UKSW Salatiga, 2011, hlm. 5.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
diskriminasi, konflik antarkelompok dan perubahan sosial.153 Tajfel
membedakan antara proses kelompok dari proses yang di alami
oleh individu. Jadi harus membedakan antara proses seseorang dari
orang lain dan proses identitas sosial yang menentukan apakah
seseorang dengan ciri-ciri tertentu termasuk atau tidak dalam
kelompok sosial.154 Identitas merupakan proses dari keindviduan
menuju pada proses berkelompok karena kesamaan ciri-ciri khusus
dari masing-masing individu dalam berperilaku. Perilaku kelompok
dapat berbeda dengan perilaku individu, sehingga setiap individu
akan menciptakan identitas sosial di tengah identitas diri yang
berproses, yang membantunya untuk mengonseptualisasi dan
mengevaluasi diri sendiri. Identitas sosial juga mencakup banyak
karakteristik unik, seperti nama seseorang, konsep diri, agama,
gender, dan lain sebagainya.
Seorang komunitas Islam aboge (alif rabo wage) yang hidup dan
berkembang dengan berpusat di Masjid Saka Tunggal Cikakak
Banyumas misalnya, dapat menjadi contoh baik bagaimana
individu (penganut Islam Aboge) dan komunitasnya (kelompok
Islam Aboge) berkembang dan berproses dengan cara yang
berbeda. Identitas sebagai penganut Islam Aboge hanyalah satu dari
sekian identitas yang melekat dirinya. Identitas sebagai penganut
Islam aboge melekat pada individu sebagaimana identitas-identitas
lainnya melekat, misalnya sebagai ayah, menantu, petani, dan lain
sebaginya. Identitas-identitas tersebut menjadi sumber referensi
bagaimana individu melakukan konseptualisasi dan sekaligus
memaknai hidup dan kehidupannya. Dalam konteks ini keberadaan
komunitas Islam Aboge menjadi sangat penting bagi penganut
Islam Aboge, yakni sebagai collective awareness untuk merespon
dan menjalani kehidupannya.
153
Idham Putra, “Teori Identitas Sosial”, dalam
http://idhamputra.wordpress.com. Diunduh 4 April 2015.
154
Idham Putra, “Teori Identitas Sosial”, Diunduh 4 April 2015
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Dalam kontek agama dan identitas, Hans Mol memberikan
gambaran yang jelas tentang korelasi antara identitas dengan
agama. Mol mengemukakan empat ciri peranan agama pada
masyarakat atau juga disebut komunitas masjid yang menentukan
pembentukan identitasnya. Pertama, agama berperan dalam
dramatisasi dialektika dalam masyarakat, yang lazim disebut mitos
dalam bentuk keyakinan primitif dan kebijaksanaan moral, teologi
dalam agama-agama dunia, dan ideologi dalam bentuk sekuler.
Mitos, teologi, dan ideologi menyediakan suatu “pedoman” bagi
individu dan masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih
baik.155Kedua, agama membuat keteraturan transedental
masyarakat. Semakin komplek masyarakat, diperlukan suatu “nilai
suci tertinggi” agar keteraturan sosial terjaga.156Ketiga, agama
dapat mengembangkan keterikatan emosional atau komitmen
sosial. Komitmen berkaitan erat dengan agama, akan membawa
kepada kehendak bersama, seperti yang dilakukan oleh sebuah
suku bangsa tertentu dalam memperkuat solidaritas sosialnya. Ia
menjadi pegangan emosional dalam pemusatan-pemusatan identitas
yang serba banyak. Keempat, agama, terutama dalam bentuk ritual,
dapat menegakkan nilai kebersamaan. Ritual akan memberikan rasa
memiliki dan identitas bagi manusia dalam berkelompok.
Identitas keagamaan menjadi menarik untuk dibincangkan dalam
konteks globalisasi. Kata globalisasi berasal dari istilah dalam
bahasa Inggris, yaitu globe dan globalization yang berarti dunia
atau proses masuknya ke ruang lingkup dunia.157 Dalam konteks
sosial, globalisasi adalah suatu istilah yang berhubungan dengan
era peningkatan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di
seluruh dunia melalui jalan perdagangan, politik, perjalanan,
budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi sosial lain, sehingga
155
Hans Mol, “Religion and Identity: A Dialectic Interpretation of Religious
Phenomena”, dalam Hayes, V.C. ed., Identity Issues and World Religions
(Bedford Park, Australia: Australian Association for the Study of Religion,
1986), hlm. 66.
156
Hans Mol, “Religion and Identity: Hlm. 68.
157
http://www.kbbi.web.id/globalisasi, Diunduh 2 Januari 2015.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
mengakibatkan batas-batas suatu negara dan bangsa menjadi kabur.
Globalisasi juga merupakan proses interaksi sosial tanpa adanya
batasan jarak yang menjadikan ruang lingkup kehidupan umat
manusia semakin bertambah luas, terutama dalam memainkan
peranan sosialnya ketika melihat dunia sebagai kesatuan tunggal.158
Menurut Roland Robertson fenomena globalisasi berfokus pada ide
tentang glokalisasi, lawan dari globalisasi sebagai sistem dunia.
Glokalisasi adalah proses integrasi antara “yang global” dan “yang
lokal”. Dalam cultural studies, glokalisasi termasuk paradigma
hibridisasi budaya yang menekankan keberagaman yang semakin
meningkat terkait dengan percampuran unik antara yang global
dengan yang lokal. Robertson menjelaskan empat unsur penting
dalam globalisasi yang dianut oleh orang-orang yang menekankan
glokalisasi. 1) Dunia sedang bertumbuh semakin pluralistik. 2)
Individu-individu dan kelompok-kelompok lokal mempunyai
kekuasaan besar untuk menyesuaikan diri, memperbaharui, dan
melakukan manuver dalam sebuah dunia yang glokal. Teori
glokalisasi melihat individu-individu dan kelompok-kelompok
sebagai agen yang penting dan kreatif. 3) Proses-proses sosial
adalah berhubungan dan saling tergantung. Globalisasi
membangkitkan berbagai aksi umpan balik dari kubu
nasionalis/etnis sehingga menghasilkan glokalisasi. 4) Komoditas-
komoditas dan media, arena dan kekuatan kunci dalam perubahan
budaya pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 M, tidak dilihat
sebagai kekuatan yang memaksa namun lebih sebagai penyedia
materi untuk dimanfaatkan dalam kreasi individual dan kolektif di
seluruh wilayah dunia yang terglokalisasi.159
Robertson menfokuskan analisisnya mengenai globalisasi sebagai
fenomena masyarakat dunia yang patut menjadi obyek kajian
dalam skala global. Ruang lingkup kajian global itu dapat meliputi
158
May T. Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah Masalah
Global (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 5.
159
Ashad Kusuma Djaya, Teori-Teori Modernitas dan Globalisasi (Yogyakarta:
Kreasi Wacana, 2012), hlm. 122.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
ilmu sosial, politik, hubungan internasional, ekonomi maupun
budaya yang mempunyai ruang lingkup luas menyangkut proses
interaksi sosial dan berbagai koneksi.160 Ini artinya dalam konteks
glokalisasi, globalisasi juga merupakan pemicu dari menguatnya
identitas lokal di ruang-ruang publik yang disebut glocalization.161
Komunitas Masjid di Tengah Globalisasi
Masjid tidak semata-mata tentang sebuah bangunan yang kemudian
digunakan oleh orang Islam untuk melaksanakan ibadah, tetapi
juga merupakan pengejawantahan simbolisme dari nilai-nilai yang
dianut, diyakini, dan dilaksanakan oleh komunitasnya. Untuk
memahami simbolisme masjid tersebut, tidak cukup hanya dengan
melihat tampilan fisik masjid, tetapi juga perlu meneroka sejarah
dan semua aktivitas yang ada di dalamnya. Aspek fisik dan non
fisik dari sebuah masjid akan menjadi sumber informasi yang
sangat kaya tentang pola keberagamaan dan keyakinannya, struktur
sosial, serta corak dan watak masyarakat pendudukungnya.
Masjid Agung Jami’ Singaraja Bali: Identitas Islam Bali yang
Toleran
Masjid Agung Jami’ Singaraja adalah salah satu masjid tertua di
Kabupaten Buleleng, tepatnya di Jalan Imam Bonjol 65 kota
singaraja. Secara administratif, masjid yang dibangun di atas lahan
seluas 1980 m2 dan dikelilingi pagar besi ini berada di Kelurahan
Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
160
Roland Robertson, “Mapping the Global Condition: Globalization as the
Global Concept” Theory, Culture and Society. Vol. 7(London: SAGE
Publications, 1990), hlm. 20.
161
Richard Giulianotti and Roland Robertson, “Glocalization, Globalization and
Migration: The Case of Scottish Football Supporters in North America”,
International Sociology, March 2006, Vol. 21 (London: Sage Publications,
2006), hlm. 171-198.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
Buleleng, Provinsi Bali. Berada di area masjid Agung Jami’
Singaraja akan membuat kita lupa bahwa masjid tersebut berada di
Bali, yang seringkali diasosiasikan sebagai kawasan Hindu.
Suasana di kawasan Masjid Agung Jami’ Singaraja, mirip dengan
suasana di Jawa, khususnya Jawa Timur. Laki-laki memaakai
sarung dengan berpeci, perempuan berjilbab, dan saat menjelang
waktu salat dari pengeras suara masjid terdengar orang ngaji.
Masjid Agung Jami’ Singaraja merupakan potret relasi harmonis
antara Hindu dan Islam di Kerajaan Buleleng. Masjid ini didirikan
pada tahun 1846M pada masa pemerintahan Raja Buleleng A.A.
Ngurah Ketut Jelantik Polong (putra A.A. Panji Sakti, raja Buleleng
I). Keberadaan masjid ini merupakan bentuk perhatian dan dan
kepedulian Raja Buleleng yang beragama Hindu kepada Umat
Islam di daerah tersebut. Raja Buleleng memberikan tanah sebagai
tempat pembangunan masjid, mengawal proses pembangunan
masjid dengan menugaskan saudaranya bernama A.A. Ngurah
Ketut Jelantik Tjelagie162 dan Abdullah Maskati yang beragama
Islam untuk memimpin pembangunan, memerintahkan juru ukir
puri untuk membuat ukiran masjid, dan memberikan kori (gerbang
Puri) untuk dijadikan gerbang masjid.
Secara keseluruhan, arsitektur Masjid Agung Jami’ Singaraja
merupakan perpaduan antara spirit Islam dengan arsitektur Bali.
Atap Masjid berbentuk limasan dan pada setiap sudut terdapat
ukiran cungkup (seperti sulur) enam buah. Pada daun pintu dan
jendela terdapat ukiran stilisasi bunga-bunga dengan warna-warna
yang cerah, sangat khas Bali.
162
A.A. Ngurah Ketut Jelantik Tjelagie memiliki peran besar dalam
menyebarkan Islam dan membangun kehidupan yang harmoni antara Islam dan
tradisi Bali, salah satunya adalah menulis ulang al-Quran dengan hiasan motif
khas Bali di bagian pinggirnya. Al-Quran tulisan tangan A.A. Ngurah Ketut
Jelantik Tjelagie saat ini tersimpan di masjid Agung Jami’ Singaraja dalam
kondisi tidak terawat. Al-Quran bersejarah tersebut diletakkan dalam kotak kaca
terkunci dibagian belakang mimbar tanpa mendapat perawatan yang layak,
kelihatan kumal dan lusuh. Hanya diletakkan dalam kotak kaca yang dikunci
dengan kunci gembok.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Secara formal, alasan pembangunan masjid Agung Jami’ Singaraja
karena masjid Keramat atau masjid tua163 --masjid pertama di
daerah Buleleng-- yang berada di jalan Hasanuddin dan berada
dipinggir Sungai Tukad Mungga tidak lagi mampu menampung
jumlah jamaah yang setiap tahun semakin bertambah. Upaya
perluasan masjid keramat juga tidak memungkinkan karena di
samping kanan, kiri serta sebelah barat masjid telah dipenuhi
rumah-rumah penduduk. Namun, mungkin saja ide pembangunan
masjid baru bukan karena alasan formal tersebut, tetapi untuk
menghindari pembongkaran masjid bersejarah nan sakral
tersebut.164
Ritual keagamaan yang dijalankan di Masjid Agung Jami’
Singaraja cukup menarik. Sebelum adazan masuk waktu salat, dari
speaker masjid di putar qiraah selama kurang lebih lima menit.
Imam memimpin salat dengan mengeraskan bacaan basmalah dan
setelah salam berdizikir bersama dengan suara keras, dengan
membaca subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahuakbar. Selama
melakukan penelitian, terdapat fenomena cukup menarik, yaitu
ketika Imam salat selalu membaca qunut nazilah165dalam setiap
163
Masjid tua atau masjid keramat ditemukan oleh masyarakat Muslim yang
pindah dari pelabuhan Buleleng ke pinggiran Sungai Tukad Mungga pada tahun
1654. Jarak pelabuhan Buleleng ke Sungai Tukad Mungga sekitar 500 meter.
Pada saat ditemukan, bangunan segi empat berukuran 15 kali 15 meter persegi
tersebut dipenuhi semak belukar dan di dalamnya terdapat sebuah mimbar
masjid yang diukir dari ornamen khas Bali. Warga berkesimpulan bangunan ini
adalah masjid. Sayangnya, tidak diketahui siapa yang telah membangunnya.
Namun demikian, warga terus berupaya menjaga keaslian bangunan tersebut.
Tiga pintu masjid masih terlihat ukiran ormanem khas Bali. Dindingnya berasal
dari kapur yang dicampur bebatuan. Terlepas dari siapa saja yang telah
membangunnya, keberadaan masjid kuno atau masjid keramat tersebut
menunjukkan bahwa kawasan pelabuhan Buleleng merupakan daerah
persinggahan para saudagar Muslim. Selain itu, keberadaan masjid tersebut
menjadi bukti bahwa di daerah Buleleng pada tahun 1654 telah disinggahi
(ditinggali) oleh orang-orang Islam.
164
Alasan serupa terjadi pada pembangunan Masjid Raya Al Fatah Ambon. Lebih
lanjut pembahasan tentang Masjid Raya Al Fatah akan dibahas tersendiri.
165
Penulis sempat terkejut dengan pembacaan qunut tersebut, namun ternyata
pembacaannya bukan sebuah kebetulan, tetapi memang dilakukan dengan
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
salat fardhu. Sebagian besar jamaah mengamini, namun ada juga
beberapa jamaah yang diam saja. Menurut salah satu informan,
pembacaan qunut tersebut atas instruksi Ketua Takmir, yaitu untuk
memohon pertolongan Allah.
Hari Jumat menjadi salah satu hari yang menarik. Suara speaker
yang memperdengarkan pembacaan ayat-ayat suci al-Quran
terdengar beberapa saat sebelumnya pelaksananaan salat Jumat.
Takmir menyalakan perangkat elektronik untuk menunjang
kelancaran salat, seperti microphone dan video shooting. Video
digunakan untuk menshooting khotib yang sedang membaca
khutbah Jumat dan Imam yang sedang memimpin salat. Salat Jumat
dilakukan dengan adzan dua kali, khutbah dengan bahasa
Indonesia, dan setelah selesai diawali dengan dua kali. Menurut
penuturan salah seorang responden, salat tarawih dan witir 23
rakaat, walau ada juga yang hanya sebelas.
Majid Raya al-Fattah Ambon: Merawat Islam Ambon dari Banjir
Bandang Budaya Global
Masjid raya Al Fattah Ambon terletak di tengah kota Ambon,
berdekatan dengan pasar dan pelabuhan, tepatnya berada di jalan
Sultan Babullah, Ambon, Maluku. Masjid ini berada persis di
samping Masjid Jami’ An-Nur, salah satu masjid tertua di Ambon
dan masjid yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Pada
dasarnya pembangunan Masjid al-Fatah merupakan perluasan
bangunan dari masjid Jami’ yang sudah tidak lagi menampung
jumlah umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah.
sengaja. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama melakukan penelitian,
pembacaan qunut tersebut dilakukan setiap salat, seperti Dhuhur, Ashar, Maghrib
dan Isya’ selalu membaca Qunut Nazilah. Menurut Koordinator keagamaan
Masjid Agung Jami’ Singaraja, Hariyanto, pembacaan Qunut tersebut atas
perintah dari Bapak Ta’mir, yaitu untuk mendoakan agar bangsa Indonesia, dan
khususnya umat Islam senantiasa mendapat pertolongan dari Allah SWT dan
dijauhkan dari segala bencana.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Posisinya yang berada di tengah kota, masjid ini menjadi tempat
strategis dan mudah dijangkau oleh siapa saja yang ingin beribadah
atau sekedar melepas lelah. Selepas salat Dzuhur misalnya, kita
dapat melihat para jamaah yang duduk-duduk di dalam atau
emperen masjid, baik sedang ngobrol, atau hanya sekedar
memainkan gadgetnya. Halaman masjid yang luas juga cukup
memberikan kenyaman kepada siapa saja yang membawa
kendaraan, walaupun pada saat pelaksanaan salat Jumat tetap saja
tidak muat. Namun demikian, posisinya yang berada di tengah kota
dengan akses yang sangat mudah sering kali menjadi persoalan
tersendiri, khusunya terkait dengan keamanan. Menyadari keadaan
tersebut, pihak pengelola masjid memasang beberapa CCTV di
sudut-sudut masjid. Selain itu, ketika jam kerja, khsusnya pagi
sampai siang hari, semua pintu gerbang ditutup dan dikunci. Jika
tetap ingin masuk harus ijin terlebih dahulu kepada satpam.
Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilakukan oleh
Presiden pertama Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno pada tanggal
1 Mei 1963, dan diberi nama Masjid Raya “Al Fatah”. Masjid Raya
Kemenangan, ditamsilkan dari peristiwa kembalinya Irian Barat
dalam pangkuan Ibu Pertiwi, buah usaha final Trikora, Pimpinan
Jenderal Soeharto. Pada tahun 1984, Masjid Raya Al Fatah
diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Agama Republik
Indonesia. Dan dalam rangka menyambut dan mensukseskan MTQ
Nasional ke 24 di Kota Ambon, pada tahun 2010 masjid Raya Al –
Fatah direnovasi.
Keberadaan Masjid al-Fattah Ambon sangat penting tidak saja
karena sebagai pusat penyiaran Agama Islam, tetapi juga peran
positifnya terutama ketika meledak konflik Ambon pada tahun
1999 silam. Masjid ini menjadi tempat pengungsian masyarakat
Muslim yang bertempat tinggal di Ambon. Selain itu, masjid ini
juga menjadi rumah dan benteng bagi Islam Ambon yang toleran
dan akomodatif terhadap budaya lokal dari pengaruh faham
keislaman yang cenderung keras dan intoleran.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
Masjid Raya Al Fattah merupakan pengejawantahan dari Islam
Ambon yang ramah dan toleran terhadap budaya lokal dan
penganut agama lain. Masjid al-Fattah adalah identitas komunitas
Islam Ambon. Secara organisasi, Islam yang dijalankan di masjid al
Fattah Ambon tidak berafiliasi dengan organisasi apapun, seperti
NU dan Muhammadiyah. Secara ritual keagamaan menjalankan
Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Setelah salat lima waktu kami
melakukan dzikir bersama, membaca qunut setiap salat subuh,
adzan dua kali saat salat Jumaat, dan ada pembacaan tarhim
sebagai penanda waktu salat sebelum dikumandangkannya adzan.
Demikian disampaikan oleh salah satu penghulu masjid, ustadz
Nashir Rahawarin, ketika ditanyakan Islam apakah yang dijalankan
di Masjid Al Fattah Ambon.
Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan selama berada di
Ambon, yang disampaikan oleh ustadz Nashir Rahawarin adalah
benar adanya. Dalam setiap salat jamaah yang dilakukan, selalu
diakhiri dengan dzikir bersama membaca Istighfar, Subhanallah,
Alhamdulillah, dan Allahu Akbar secara nyaring dan berulang-
ulang, serta diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh
Imam. Untuk salat-salat berjamaah yang memungkinkan
pembacaan al-fatihah dan surat-surat pendek secara nyaring, imam
selalu membaca basmalaah diawal bacaan surat.
Masjid Saka Tunggal Banyumas: Identitas Komunitas Islam Jawa
Masjid Masjid Saka Tunggal Baitussalam atau lebih dikenal dengan
Masjid Saka Tunggal, terletak di Desa Cikakak, Kecamatan
Wangon, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
Masjid ini dianggap sebagai masjid tertua di Indonesia, karena
menurut tahun yang tertera pada saka tunggalnya, masjid ini
dibangun pada tahun 1288 Masehi oleh mbah Mustholeh yang
dimakamkan di atas bukit disebelah barat masjid Saka Tunggal.
Jika dilihat dari angka tahun pendiriannya, maka masjid ini
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
merupakan satu-satunya masjid tertua di pulai Jawa yang dibangun
sebelum masa dakwah Wali Sembilan (Wali Songo). Jika benar
bahwa masjid saka tunggal didirikan pada tahun 1288 M (abad ke-
12), maka masjid ini telah ada 2 abad sebelum era Wali Songo
hidup pada masa abad 15-16 Masehi, dan bahkan lebih dulu ada
dari kerajaan Majapahit.
Masyarakat Banyumas secara konvensional menyebutnya sebagai
masjid Saka Tunggal. Penyebutan ini berhubungan dengan
konstruksi masjid yang dibangun dengan satu pilar utama (tiang
penyangga tunggal) yang berada di tengah masjid. Pilar utama ini
memiliki empat sayap sebagai penopang bangunan atap masjid.
Tiang dengan empat sayap penopang yang berada di tengah masjid
ini terlihat seperti sebuah totem. Pada bagian bawah tiang terdapat
kaca pelapis yang berfungsi untuk melindungi bagian yang terdapat
tulisan tahun pendirian masjid tersebut. Saka masjid ini berdiri
menjulang hingga bagian wuwungan yang berbentuk limas. Bentuk
limas ini sama dengan bentuk wuwungan Masjid Agung Demak.
Letak masjid berada tepat di kaki bukit (gunung) Cikakak, dan
relatif jauh dari jalan raya. Untuk sampai ke lokasi kita harus
melewati jalan kampung beraspal yang tidak terlalu bagus, namun
diujung jalan sudah tersedia lapangan parkir untuk kendaraan
berziarah dan/atau berwisata ke Masjid Saka Tunggal. Untuk
sampai dilokasi masjid, kita harus melwati pintu gerbang dengan
membayar karcis. Lokasi masjid berada tepat diujung jalan di
bawah gunung Cikakak. Di sekitar masjid hanya ada tiga rumah
yang ditempati oleh keturunan pendiri masjid Cikakak Mbah
Mustholeh yang sekaligus berperan sebagai juru kunci masjid.
Jika malam menjelang, suasana di sekitar masjid Cikakak sangat
lengang. Hanya beberapa lampu kecil yang menerangi. Hampir
tidak ada kehidupan sama sekali, terutama selepas salat Isya’.
Suasana nampak sangat berbeda pada pagi dan siang hari. Kawanan
kera yang yang jumlah sangat banyak akan memenuhi sekitar
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
wilayah masjid. Kera-kera tersebut turun dari bukit yang berada di
sebelah barat masjid Saka Tunggal.
Ada empat sayap yang menopang di bagian saka masjid saka
tunggal tersebut. Dari model arsitektur seperti itu tidak terlepas dari
filosofi yang dikandung di dalamnya yaitu papat kiblat lima pancer
atau empat mata angin dan satu pusat. Empat kiblat berarti manusia
sebagai pusat pusaran dikelilingi oleh empat mata angin yaitu api,
angin, air dan bumi. Dari empat penjuru mata angin ini maka
manusia sebagai makhluk hidup harus mampu menciptakan
keseimbangan. Adapun saka tunggal itu berarti bagi manusia
seyogyanya seperti huruf alif, yaitu tidak bengkok, manusia yang
tidak bengkok artinya tidak boleh bengkok, tidak nakal dan tidak
berbohong. Ada sebuah kontrol serta pernyataan yang bersifat
sanksi dari ajaran ini, yaitu apabila manusia bengkok maka tidak
layak disebut manusia.
Adapun filosofi keseimbangan dari empat penjuru mata angin yaitu
ajaran untuk tidak berlebihan dalam penggunaan air agar tidak
tenggelam, jangan banyak bermain angin bila tak ingin masuk
angin, jangan berlebihan bermain api agar tidak terbakar dan
jangan berlebihan memuja bumi agar tidak terjatuh. Empat mata
angin dan satu penjuru tersebut juga mempunyai merujuk makna
pada terminlogi Islam –Jawa yang disebut dengan allawwamah,
muthmainnah, shufiyyah dan amarrah.166
Komunitas Masjid Saka Tunggal berada di bawah gunung Cikakak
Cikakak dan menganut tradisi budaya Islam Aboge. Aboge
merupakan singkatan dari Alif Rebo Wage, yaitu sebuah sistem
perhitungan kalender yang menggabungkan kalender winduan
dengan beberapa jumlah perhitungan hari pasaran dalam tradisi
Jawa yakni Pon, Wage, Kliwon, Legi dan Pahing. Jika dirunut dari
sisi historis, perhitungan sistem Aboge ini dimulai dari perintah
Sutan Agung Hanyakrakusuma sebagai pemegang kekuasaan
166
Fungsi Antropologi Masjid Saka Tunggal,. Hlm . 5.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
tertinggi di Kerajaan Mataram pada saat itu. Sistem penaggalan ala
Aboge mengisyaratkan kepastian waktu jatuhnya hari Idul Adha,
Idul Fitri dan permulaan Ramadhan.167 Dalam keperayaan Aboge,
shalat Idul Fitri disebut dengan Shalat Ngiqti (Iqti) dilaksanakan
setelah puasa syawal pada tanggal 8 bulan Syawal pada pagi hari
dan ada pula shalat Rebo wekasan yang dilaksanakan pada hari
rabu terakhir pada bulan Safar.168
Ritual keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Saka Tunggal
cukup unik. Mereka memulai kegiatan ibadah dengan menabuh
bedug dan kentongan yang dilakukan oleh juru kunci dialanjutkan
dengan adzan langgam Jawa. Setiap orang yang datang
melaksanakan salat sunnah yang jumlahnya sekitar empat salam
masing-masing dua rakaat. Setelah melaksanakan salat sunnah,
sambil menunggu pak Imam, jamaah salat Maghrib membaca
syiiran yang lafadznya campuran antara bahasa Arab dan Bahasa
Jawa yang dilagukan seperti orang berguman. Bagi mereka yang
tidak terbiasa dengan bahasa Jawa ngapak, sangat sulit untuk
memahami rangkaian syiiran yang dibaca.
Bedug kembali ditabuh sebagai tanda akan segera dilaksanakannya
salat magrib. Imam berdiri dan salah satu jamaah membaca
iqamah. Ketika membaca surat fatihah dan suta pendek, Imam
membacanya dengan cepat dan cenderung seperti orang bergumam.
Bagi mereka yang terbiasa membaca al Quran dengan tartil akan
merasa janggal dengan cara membacanya. Gerakan-gerakan salat
juga cenderung cepat, namun para jamaah yang sebagian besar
sudah berusia lanjut dapat mengikutinya. Setelah salam,
dilanjutkan dengan pembacaan dzikir. Lagi-lagi dengan pelafadzan
yang cenderung bergumam. Bacaan yang cukup menarik dan
mudah diterka adalah pembacaan kalimat lailahaiillallah yang
dalam jumlah hitungan tertentu berubah menjadi illallah, hu Allah,
167
Sulaiman. “Islam Aboge: Pelestarian Nilai-nilai Lama di Tengah Perubahan
Sosial”. Jurnal “Analisa” Volume. 20 No.01 Juni 2013,. Hlm . 9.
168
Joko Tri Haryanto. “Relasi Agama dan Budaya dalam Hubungan Intern Umat
Islam”. Jurnal SMaRT Volume 01 No. 01 Juni 2015. Hlm. 44.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
dan hu’. Setelah selesai wiridan, pak imam memimpin para jamaah
untuk melaksanakan salat sunnah yang jumlahnya sekitar 10 salam,
dimana masing-masing salam berjumlah dua rakaat. Setelah selesai
melaksanakan salat sunnah tersebut, dilanjutkan dengan
pelaksanaan salat Isya’ secara berjamaah. Rangkaiannyapun dan
ritual yang dilakukan sama dengan pelaksanaan salat maghrib. Ada
kejadian unik dan mendebarkan pada saat dzikiir setelah salat Isya’,
tiba-tiba salah satu jamaah mematikan semua lampu dan pintu
masjid juga ditutup. Setelah selesai dzikir baru dihidupkan dan
dibuka lagi.
Pelaksanaan salat Jumat juga cukup unik. Tidak ada pengeras
suara, hanya beduk yang ditabuh oleh juru kunci: tidak terus-
terusan, tetapi ada jedanya. Sambil menunggu waktu salat Jumat,
jamaah melaksanakan salat sunnah dan melantukan syiiran
berbahasa Arab yang bercampur dengan bahasa Jawa Banyumasan.
Adzan pertama dilakukan oleh empat orang memakai jubah
berwarna putih dan menutup kepalanya dengan udeng batik warna
biru, dengan menggunakan langgam Jawa. Unik dan sangat indah.
Hal unik lainnya adalah ketika khotib naik ke atas mimbar. Sang
khotib ketika membacakan khutbahnya yang berbahasa Arab walau
hanya terdengar sekilas berada dibalik tirai. Dengan berada dibalik
tirai tersebut, para jamaah tidak dapat melihatnya.
Keunikan lainnya dapat dilihat saat melaksanakan salat Jumat,
dzikir setelah salat, dan pelaksanaan solat sunnah yang jumlah
sekitar sepuluh salam dimana setiap salah terdiri dari dua rakat.
Setelah selesai melaksanakan rangkaian ritual salat tersebut, para
jamaah tidak langsung pulang, tetapi ada yang bergeser ke
belakang lalu ndeprokdalam posisi sujud, seperti menyembah
sesuatu. Setelah itu baru para jamaah meninggalkan masjid.
Komunitas Masjid Merespon Globalisasi: Merawat Identitas
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Dunia global tidak semata-mata proses homogenisasi budaya, tetapi
juga memberi peluang bagi terjadinya kehidupan dunia yang
semakin heteregon, pluralistik. Individu-individu dan komunitas-
komunitas –bahkan yang marginal sekalipun—memliki ruang dan
kesempatan yang sama dengan kelompok dominan untuk
melakukan adaptasi, explorasi nilai-nilai diri, dan manuver dalam
arena globalisasi. Individu dan komunitas-komunitas lokal bukan
benda mati yang hanya bisa menerima dan mengikuti stimus yang
datng dari luar, tetapi adalah agen penting dan kreatif, yang mampu
untuk memilah dan memilih apa unsur-unsur luar yang dapat
diterima, diadaptasi dan apa yang harus ditolak sesuai dengan
kebutuhan dan kerentanan identitasnya (Salehudin, 2015).
Komunitas-komunitas masjid tersebut tentu ---meminjam teori
Michel de Certeaudalam bukunya the practice of every day life
(1984)—memiliki taktik untuk merespon strategi kooptasi budaya
global.
Komunitas Masjid ditengah Budaya Global
Masjid merupakan simbol identitas bagi komunitasnya. Dengan
kata lain, masjid merupakan pengejawantahan dari identitas
komunitasnya. Masjid Saka Tunggal yang menjadi identitas
komunitas Islam Jawa yang dikenal orang sebagai Islam Aboge
atau alif rabo wage. Masyarakat umum hanya mengenal Islam
Aboge sebagai Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan,
salat Idul fitri, dan salat idul adha cenderung berbeda dari
kebanyakan Islam di Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia
melalui kementerian Agama dan kelompok-kelompok Islam di
Indonesia sibuk mengadakan sidang itsbat, mereka tidak peduli.
Jika menurut mereka sudah waktu puasa, salat idul fitri, dan salat
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
idul adha berdasarkan hitungan yang diwariskan oleh leluhur
mereka ---disebut aboge atau alif sabtu wage---, mereka akan
melaksakan puasa, Salat Idul Fitri dan/atau Salat Idul Adha, tidak
peduli apakah sesuai dengan keputusan pemerintah atau tidak.
Masjid Saka Tunggal Cikakak berada cukup terpencil, persis dikaki
sebuah gunung dengan jalan akses yang relatif sulit, namun cukup
dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya menjelang
pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada dua momentum
tersebut, beberapa media baik televisi maupun media cetak dan
online berdatangan untuk melihat, meliput dan mengabarkan
kepada dunia bahwa di sebuah tempat terpencil ada penganut Islam
yang melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha pada waktu yang
berbeda dari waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan,
mereka melaksanakannya ketika pemerintah masih berdebat hangat
untuk menentukan kapan waktunya. Namun walaupun menjadi
buah mata mass media, mereka seolah-olah tidak ambil pusing.
Melongok ke dalam masjid Saka Tunggal, kita akan mengetahui
identitas komunitas masjid Saka Tunggal Cikakak yang khas dan
unik. Mereka menjalankan ritual keagamaan sebagai orang-orang
Islam Jawa, yaitu Islam yang sangat menghargai dan menghormati
leluhur, dengan teguh dan tawadhu’. Di tengah hiruk pikuk
Arabisasi dan purifikasi ke-Islaman yang gelorakan oleh mass
media, khususnya televisi dan media cetak, mereka tetap secara
teguh menjalankan Islam sebagaimana diajarkan oleh leluhur
mereka. Membaca surat-surat al-Quran dalam salat dengan
langgam Jawa dan dialek Ngapak sehingga terdengar samar-samar
dan terasa tidak sesuai dengan kaidah-kaidah membaca al-Quran
sering kali akan mengundang orang non komunitas Saka Tunggal
(baca: non Islam Aboge) untuk menyalahkan mereka. Namun
kekhusuan mereka untuk berdzikir setelah salat fardhu (wajib),
melaksanakan ragam salat sunnah setelah salat wajib hingga
puluhan salam dengan dua rakaat, tradisi salaman setelah salat
atarjamaah, dan diakhir dengan sujud syukur menunjukkan betapa
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
agamisnya mereka. Nampaknya tidak salah jika kita berkesimpulan
bahwa hidup mereka hanya untuk beribadah kepada sang Maha
Pencipta. Globalisasi dengan segala pernak-pernik nilai yang
dibawanya seolah-olah berhenti di pintu masuk masjid Saka
Tunggal.
Masjid sebagai simbol identitas dari komunitas pendukungnya juga
dapat dilihat dari keberadaan Masjid Agung Jami’ Singaraja
sebagai representasi Identitas Islam Bali dan Masjid al Fatah
Ambon yang merupakan representasi dari identitas komunitas
Islam Ambon. Namun berbeda dengan Masjid Saka Tunggal
Cikakak Banyumas, Masjid Agung Jami’ Singaraja cenderung
akomodatif dengan globalisasi dan nilai-nilai yang dibawanya.
Kedua masjid ini memanfaatkan secara kreatif dan selektif
teknologi modern sesuai dengan kebutuhannya. CCTV yang
dipasang hampir di setiap pojok masjid. Masjid yang luas dan
posisinya yang terletak di tengah kota dan/atau pinggir jalan raya,
maka penggunaan CCTV merupakan kebutuhan untuk menjamin
kemananan fasilitas masjid dan kenyaman para jamaah. “Dengan
CCTV ini, kami dapat mengawasi semua bagian masjid dari
ruangan ini. Salah satu persitiwa yang mendasari dipasangnya
CCTV ini adalah seringnya kehilangan sandal para jamaah,
khusunya saat salat Jumat,” ungakp Hariyanto, salah satu Takmir
Masjid Agung Jami’ Singaraja.
Selain CCTV, di Masjid Al Fatah Ambon dan Masjid Agung Jami’
Singaraja juga terdapat vidio shoting yang digunakan setiap salat
Jum’at, yaitu untuk menshote khotib yang sedang menyampikan
khutbah dan Imam yang sedang mengimami, dan relay melalui
televisi yang berada di beberapa temppat dalam masjid. Dengan
cara ini, para jamaah salat Jum’at dan melihat khotib dan imamnya.
Khusus untuk Masjid Al Fatah Ambon, penyebaran materi khutbah
juga dilakukan dengan siaran langsung RRI Ambon. Teknologi
dimanfaatkan oleh komunitas Masjid Al Fatah Ambon dan Masjid
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
Agung Jami’ Singaraja untuk “mengkomunikasikan” identitas
komunitasnya.
Nilai-nilai modern juga digunakan oleh komunitas Masjid Al Fatah
Ambon dan Masjid Agung Jami’ Singaraja untuk melakukan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan masjid. Setiap minggu
(Jum’at), selalu dilaporkan sirkulasi keuangan yang didapat dari
infaq jamaah dan/atau donasi lainnya, termasuk juga
penggunaannya. Jamaah juga mendapatkan informasi siapa yang
akan menjadi imam dan khotib Salat Jumat, imam salat fardhu,
pengisi pengajian rutin, dan kegiatan-kegiatan lain yang akan
dilaksanakan. Namun demikian, bukan berarti modernitas dapat
masuk ke masjid secara leluasa, tetapi ada pembatasan sedemikian
rupa, misalnya ketika waktu salat atau masuk masjid HP harus
dimatikan atau disilent. Seolah-olah ada ruang yang jelas antara
ruang agama dan ruang dari modernitas. Namun demikian, tidak
sedikit yang masih memainkan HPnya saat khotib sedang
menyampaikan khutbahnya.
Jika melihat latar depan –tampilan arsitektur dan kelengkapan
masjid-- kita menemukan akomodasi selektif terhadap modernitas,
maka pada latarbelakangnya –nilai interiksinya-- kita akan
menemukan kecenderungan untuk secara tegas menjaga
identitasnya, yaitu sebagai represantasi dari identitas komunitas
Islam yang ramah terhadap budaya lokal, dan toleransi positif
keberadaan agama lain. Masjid Al Fatah Ambon merupakan
representasi dari identitas komunitas Islam Ambon yang ramah dan
toleran terhadap budaya lokal, demikian pula dengan Masjid Agung
Jami’ Singaraja yang merupakan identitas dari komunitas Islam
Bali yang ramah dan toleran terhadap budaya lokal.
Agen dalamPertahanan Identitas
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Globalisasi memberikan peluang yang besar bagi komunitas lokal
untuk melakukan aktualisasi diri secara kreatif sesuai dengan
kemampuan, kebutuhan dan tujuannya. Sebagaimana telah dibahas
sebelumnya, komunitas tiga masjid, yaitu Masjid Sakatunggal
Cikakak, Masjid al-Fatah Ambon, dan Masjid Agung Jami’
Singaraja Bali secara kreatif mampu mempertahankan identitasnya
di tengah banjir bandang budaya global. Salah satu faktornya
adalah keberadaan pemimpin ketiga komunitas masjid tersebut.
Pemimpin Masjid Sakatunggal Cikakak lebih dikenal dengan
sebutan juru kunci. Posisi juru kunci sangat penting penting dalam
semua segmen kehidupan masyarakat komunitas Islam Masjid
Saka Tunggal (Islam Aboge). Semua ritual keagamaan yang
dilaksanakan di masjid Saka Tunggal semuanya di pimpin oleh
para juru kunci. Sebagai keturunan Kiai Mustholih, juru kunci juga
menjadi mediator masyarakat untuk ngalap berkah dari Mbah
Mustoleh. Siapapun yang hendak berziarah dan/atau ngalapberkah
harus didampingi oleh juru kunci. Selain itu, sebagai representasi
Mbah Mustoleh, mereka memiliki legitismasi untuk “mengatur”
masyarakat. Apapun yang dikatakan oleh juru kunci, masyarakat
akan mengikutinya, bahkan tanpa bertanya sama sekali. Dalam
konteks globalisasi, keberadaan juru kunci menjadi sangat penting.
Dia memiliki “wewenang” sangat besar untuk menggerakkan
komunitasnya, menerima atau menolak globalisasi. Penerimaan
dan/atau penolakan atas globalisasi yang dilakukan oleh juru kunci
akan akan diikuti oleh komunitasnya tanpa bertanya. Menolak atau
melawan juru kunci sama halnya menolak dan melawan Mbah
Mustoleh.
Aktor di Masjid Raya al-Fatah Ambonadalah Bapak Imam. Bapak
Imam memiliki peran sangat penting dalam menentukan warna dan
corak keberagamaan komunitas masjid Al Fatah. Semua keputusan
terkait dengan keberagamaan masjid sepenuhnya ditentukan Bapak
Imam, mualai dari menentukan Khotib Jumat, Pengisi Pengajian
rutin Ba’da Maghrib, dan pengajian anak-anak. Tanpa persetujuan
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
Bapak Imam, siapapun tidak mungkin dapat memimpin kegiata
ibadah di Masjid Raya al-Fatah Ambon. Dalam konteks globalisasi,
peran Bapak Imam sangat penting untuk menjaga identitas
komunitas.
Aktor di Masjid Agung Jami’ Singaraja adalah Ketua Takmir. Peran
Ketua Takmir di Masjid Agung Jami’ Singaraja relatif sama dengan
penghulu di Masjid Raya Al Fatah Ambon. Ketua takmir memiliki
otoritas mutlak untuk mengelola masjid, seperti menentukan siapa-
siapa yang boleh menjadi imam salat, khotib Jum’at dan
penceramah pengajian. Dalam konteks globalisasi, peran Bapak
Imam sangat penting untuk menjaga identitas komunitas.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Proses Meneguhkan Identitas Komunitas di tengah Globalisasi
Agama seringkali berada pada posisi berhadapan dengan
globalisasi, namun celakanya globalisasi sendiri merupakan
keniscayaan sejarah yang tidak mungkin dibendung oleh agama
sekalipun. Oleh karenanya, yang dapat dilakukan oleh komunitas
masjid bukan melawannya, tetapi menyikapinya dan memanfaatkan
globalisasi untuk memperkuat identitasnya. Ketiga komunitas
masjid tersebut secara cerdas melakukan respon terhadap
globalisasi: membiarkannya sebagaimana dilakukan komunitas
Masjid Saka Tunggal, dan memanfaatkannya sebagaimana
dilakukan oleh komunitas Masjid Raya Al Fattah Ambon dan
Masjid Agung Jami’ Singaraja. Secara garis besar, ada tiga proses
yang dilakukan untuk menjaga identitasnya. Pertama, pembiasaan
dan pelembagaan. Identitas disosialisasikan dan diinternalisasikan
melalui pembiasaan dan pelembagaan, misalnya setelah salat
melakukan dzikir bersama, adzan dua rakaat pada salat Jumat, dan
lain sebagainya. Dengan cara ini, akan terjadi proses internalisasi
nilai-nilai yang pada akhirnya akan memperkuat identitas
komunitas. Kedua, peneguhan otoritas leluhur. Salah satu cara
efektif untuk “melawan” strategi kooptasi globalisasi adalah
dengan taktik meneguhkan otoritas leluhur. Hal ini sebagimana
dilakukan oleh Komunitas Islam Aboge Masjid Saka Tunggal
Cikakak Banyumas. Mereka membentengi dirinya dengan
menyandarkan diri kepada leluhur, yaitu dengan mematuhi dan
menjalankan ajarannya. “Anane awake dewe iku kerono anane
leluhur, lah kalo ora taat marang leluhur terus awak dewe iki
disebut opo?” ungkap salah satu narasumber. Mereka harus
menjalankan semua yang telah dijalankan dan diajarkan oleh
leluhur dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak maka akan kuwalat.
Konsep kuwalat menjadi taktik jitu untuk menyikapi globalisasi.
Dengan alasan takut kuwalat, komunitas Masjid Saka Tunggal terus
mempertahankan ajaran leluhurnya. Ketiga, penguatan visi misi
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
kelembagaan. Keberadaan visi misi lembaga relative efekti untuk
membendung banjir bandang globalisasi, sebagaimana dapat dilihat
pada apa yang dilakukan oleh komunitas Masjid Raya Al Fattah
Ambon dan Masjid Agung Jami’ Singaraja untuk menjaga identitas
komunitasnya. Visi misi lembaga menjadi dasar untuk menentukan
siapa dan seperti apa khotib dan penceramah yang boleh tampil di
Masjid Raya Al Fattah Ambon dan Masjid Agung Jami’ Singaraja.
Kemampuan ketiga komunitas tersebut mempertahankan diri
menunjukkan bahwa globalisasi tidak semata-mata menciptakan
homogenisasi budaya, tetapi memfasilitasi terciptanya pluralitas
budaya. Globalisasi merupakan ruang besar yang disediakan untuk
semua kebudayaan –termasuk komunitas agama—untuk bertemu,
tampil, bernegosiasi, dan berkontestasi untuk menujukkan
eksistensinya. Komunitas masjid bukan benda mati yang tidak
berdaya menyikapi apapun yang terjadi pada dirinya, tetapi mahluk
kreatif yang dapat memilah dan memilih bagian-bagian dari
globalisasi yang dapat digunakan untuk memperkuat dirinya atau
harus ditolak karena bertentangan dengan identitas komunitasnya.
Globalisasi adalah ancaman pada satu pihak dan peluang pada
pihak yang lain. Komunitas Masjid Raya Al Fattah Ambon, Masjid
Agung Jami’ Singaraja, dan Masjid Saka Tunggal Cikakak
Banyumas mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan
globalisasi untuk memperkuat identitas komunitasnya. Komunitas
masjid tersebut ibarat ikan yang berenang di lautan. Walaupun
memanfaatkan lautan untuk tempat hidup dan meneruskan
transmisi kehidupannya, ikan itu sendiri tidak menjadi asin.
Penutup
Globalisasi adalah kenyataan yang harus diterima, dihadapi, dan
disikapi oleh siapa saja, termasuk komunitas masjid. Globalisasi
meniscayakan tatanan dunia baru yang disebut kampung global,
yaitu dunia yang tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat agama, suku
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
bangsa, administrasi negara, dan aliran politik. Situasi ini seringkali
diangap sebagai ancaman bagi identitas karena mendorong
terjadinya terjadinya homogenisasi budaya. Padahal, jika melihat
fenomena Masjid Saka Tunggal Cikakak, Masjid al-Fatah Ambon,
dan Masjid Agung Jami’ Singaraja kita akan menemukan betapa
globalisasi malah memperkuat identitas komunitas. Malahan,
identitas komunitas masjid menjadi jangkar bagi identitas individu.
Globalisasi memberi ruang kepada setiap individu untuk
membangun identitasnya secara bebas sesuai dengan keinginannya.
Namun dalam kondisi demikian, individu dapat terjeba dalam
situasi tanpa identitas sehingga akan kesulitan dalam
mengidentifikasi diri dan memaknai hidupnya.
Masjid Agung Jami’ Singaraja merupakan identitas dari komunitas
Islam Bali, Masjid Raya Al Fatah Ambon merupakan identitas dari
komunitas Islam Ambon, dan Masjid Saka Tunggal Cikakak
merupakan identitas dari komunitas Islam Jawa atau yang dikenal
dengan Islam Aboge (Alif Rabo Wage). Dalam konteks globalisasi,
Individu-individu anggota komunitas masjid tersebut dapat
menyerap nilai-nilai dari mana saja, namun ketika masuk ke dalam
masjid individu-individu tersebut harus menyesuaikan diri dengan
identitas komunitasnya. Identitas komunitas merupakan collective
awareness untuk merespon dan menjalani kehidupan ditengah
samudra budaya global yang semakin tak terkendali.
Fenomena yang terjadi di Masjid Saka Tunggal Cikakak, Masjid al-
Fatah Ambon, dan Masjid Agung Jami’ Singaraja menunjukkan
bahwa komunitas-komunitas tersebut tidak hanyut oleh banjir
bandang globalisasi. Komunitas masjid bukanlah sekumpulan
benda mati yang hanya bisa pasrah menerima pengaruh luar, tetapi
sekumpulan mahluk hidup yang memiliki otoritas untuk bersikap,
yaitu untuk memilah, mimilih dan sekaligus menyikapi setiap nilai-
nilai yang datang dari luar diri dan komunitasnya. Mereka memiliki
―---meminjam bahasa De Certeau (1984)―--- taktik untuk
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
merespon startegi budaya global. Seperti ikan di lautan, hidup dan
berenang di dalamnya namun tidak menjadi asin.
Daftar Pustaka
AsiaDHRRA Secretariat, The Impact Globalization on the Social-
Cultural Live of Grassroots People in Asia, Jakarta: Grasindo,
1998.
Abdullah, Irwan, dkk. (ed.), Agama dan Kearifan Lokal dalam
Tantangan Global, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2007.
Appadurai, Arjun, “Disjuncture and Difference in the Global
Cultural Economy” dalam The Globalization Reader, Second
Edition, Frank J. Lechner and Jhon Bali (ed), 2006.
Abdul Fattah, Munawir, Tradisi Orang-Orang NU, Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, 2006.
Anand, Chaiwat Satha, Agama dan Budaya Perdamaian,
Diterjemahkan oleh Taufik Adnan Amal, Yogyakarta: Forum Kajian
Agama dan Budaya, 2002.
Aulia, Rizky, Makna Simbolik Arsitektur Masjid Pathok Negoro
Sulthoni Ploso Kuning Yogyakarta, Yogyakarta: Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2013.
Beyer, Peter, Religion and Global Society, New York: Routledge,
2006.
Berger, Peter, and Semuel P. Huntington (ed), Many Globalization
Cultural Diversity in the Contemporery World, Oxford: Oxford
University Press, 2000.
Balya, M. Danial, Tinjauan Kritis Terhadap Hubungan Antara
Identitas dan Agama dalam Identity and Religion, Hans Mol (ed),
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
dalam http://posapohlenteh.blogspot.com, diakses tanggal 11 April
2014
Cahyono, Eko, Kraton Sebagai Simbol Pesantren Besar, http.//
www.gp-ansor.org,
Castells, Manuel, The Power of Identity, UK: Blackwell Publishing,
2003.
Connolly, Peter, ed. Aneka Pendekatan Studi Agama,
Diterjemahkan oleh Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 1999.
De Graff, H.J. dan TH. Pigead, Kerajaan Islam Pertama di Jawa:
Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVl, Jakarta: Graffiti Press,
2003.
Djaya, Ashad Kusuma, Teori-Teori Modernitas dan Globalisasi,
Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
Eliade, Mircea, Mitos Gerak Kembali Yang Abadi Kosmos dan
Sejarah, Diterjemahkan oleh Cuk Ananta, Yogyakarta: Iron
Teralitera, 2002.
Ekopriyono, Adi, Jawa Menyiasati Globalisasi: Studi Paguyuban
Arso Tunggal Semarang, Salatiga: Program Pascasarjana Studi
Pembangunan UKSW Salatiga, 2011.
Farell, Clare O’, Michael Foucault (London: Sage Publications,
2005).
Firmansyah, Globalisasi Sebuah Proses Dialektika Sistemik,
Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2007.
Giddens, Anthony, Runway World, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2001.
Giddens, Anthony, The Constitution of Society: Outline of the
Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984).
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
-----.______________. New Roles of Sociological Methode
(California: Stanford University Press, 1993).
Geertz, Clifford, Kebudayaan dan Agama, terjemahan, Yogyakarta:
Kanisius, 1992.
-------------------,. Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat
Jawa, Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya,
1983.
-----.--------------------, The Interpretation of Cultures, New York:
Basic Book, Inc, Publishers, 1973.
G. Glaser, Barney dan L. Strauss, Anselm, Penemuan Teori
Grounded: Beberapa Strategi Penelitian Kualitatif,Surabaya:Usaha
Nasional, 1985.
Goss, Jon. “Understanding the “Maluku Wars”: overview of
Sources Communal Conflict and Prospect for Peace”. Journal
Cakalele, Vol. 11 (2000).
Haryanto, Joko Tri. “Relasi Agama dan Budaya dalam Hubungan
Intern Umat Islam”. Jurnal SMaRT Volume 01 No. 01 Juni 2015.
Huntington, Samuel P., Benturan AntarPeradaban dan Masa
Depan Politik Dunia, Diterjemahkan oleh M. Sadat Ismail,
Yogyakarta: Qalam Media, 2001.
Ife, Jim, and Frank Tesoriero, Community Development; Alternatif
Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Diterjemahkan
oleh Sastrawan Manullang, dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008.
Jameson, Fredric, and Masao Miyoshi, TheCulture of
Globalization, USA: Duke University Press, 1998.
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1973.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Kusumaningtyas, Safitri, Globalisasi, http:/safitrikusumaningtyas.
web.unair.ac.id., Diunduh pada 1 Juni 2014.
Kristiawan, Agus, “Globalisasi Pernahkah Kalian Merasakan?”,
http://kristiawan8893.blogspot.com, 2012, Diunduh pada 1 Juni
2014.
Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 1998.
Masroer Ch. Jb., History of Java Sejarah Perjumpaan Agama-
Agama di Jawa, Yogyakarta: Arruzz Media, 2004.
Pamuji, Nanag.,dkk. “LaporanPenelitian: Succes Story Mekanisme
Komunitas dalam Penanganan dan Pencegahan Konflik: Studi
Kasus di Desa Wayame (Ambon) dan Desa Tangkura (Poso)”
(Institute titian Perdamaian dan Friedrich Ebert Stiftung, 2008),
Piliang, Yasraf Amir, Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas
Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya
Postmodernisme, Bandung: Mizan, 1998.
Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang . “Islam Aboge: Islam and
Cultural Java Dialogue: a Study of Islam Abooge Communities in
Ujungmanik, Cilacap, Central java Indonesia. ” International
Journal of Nusantara Islam.
Qodri, A Azizy, Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran
Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Raharawin, Yunus. “Kerjasama antar Umat Beragama: Studi
Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual”. Kalam: Jurnal
Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol. 7 No. 1 Juni 2013.
Rijal, Faried, Masjid Sebagai Identitas Keislaman,
http.//www.lazuardibirru.org.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ahmad Salehudin, MA. DkkLuthfi Rahman
Ritzer, George, The Globalization of Nothing, Thousand Oaks: Pine
Forge Press, 2004.
Romas, Chumaidi Syarief, Kekerasan di Kerajaan Surgawi,
Gagasan Kekuasaan Kyai Dari Mitos Wali Hingga Broker Budaya,
Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
Safril Mubah, A, Perkembangan Proses Globalisasi, Surabaya:
Hubungan Internasional Universitas Airlangga, tt.
Salehudin, Ahmad, Satu Dusun Tiga Masjid: Ideologisasi Agama
atas Agama, Yogyakarta, Pilar Media, 2007
Saptono. “Kebudayaan sebagai Identitas Masyarakat Banyumas”.
Diakses melalui http://repo.isi-dps.ac.id
Shaleh, Badrus, Conflict, Jihad, and Religious Identity in Maluku,
Eastern Indonesia, dalam al-Jamiah Journal of Islamic Studies UIN
Sunan Kalijaga,Volume 46, No. 1, 2008.
Sulaiman. “Islam Aboge: Pelestarian Nilai-nilai Lama di Tengah
Perubahan Sosial”. Jurnal “Analisa” Volume. 20 No.01 Juni 2013.
Suparlan, Parsudi. “Keyakinan Keagamaan dalam Konflik antar
Suku Bangsa”. Jurnal Antropologi Indnesia 66, 2001.
Sugihardjanto, Ali, dkk., Globalisasi Perspektif Sosialis,
Yogyakarta: C-Books, 2003.
Tanzeh, Ahmad, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Teras,
2009.
Trianton, Teguh, “Fungsi antropologi masjid Saka Tunggal Fungsi
Antropologis Masjid Saka Tunggal: Studi Etnografi Pada Umat
Islam Aboge Banyumas”, dalam di Jurnal Ibda, Vol. 12, Nomor 1,
JanuariJuni 2014. ISSN: 1693-6736.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid dalam Perubahan Budaya GlobalA
Comparative Study on Shi‘îte
Widyastuti, Fungsi, Latar Belakang, Pendiri dan Peranan Masjid-
Masjid Pathok Negara di Kasultanan Yogyakarta, Yogyakarta:
Skripsi Fakultas Sastra UGM Yogyakarta, 1995.
Wolf, Martin, Globalisasi Jalan Munuju Kesejahteraan,
Diterjemahkan oleh Syamsudin Berlian, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2007.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
HUMANISME DALAM SERAT JANGKA JAYABAYA
PERSPEKTIF JAVANESE WORDVIEW
Gusti Garnis Sasmita
Universitas Sebelas Maret
gustigarnis@gmail.com
Hermanu Joebagio
Universitas Sebelas Maret
hermanu.joebagio@gmail.com
Sariyatun
Universitas Sebelas Maret
sari_fkip_uns@yahoo.co.id
Abstract
Serat Jangka Jayabaya, as part of Javanese local knowledge, remains
relevant to Indonesian history of the 18th century which could be
strategically elaborated as value-based process of historical learning. The
elaboration of humanism in Serat Jangka Jayabaya becomes fascinating
because it shows that Javanese society at the time have maintained ideal
foundations on responding social changes. Using descriptive-analytical
method, semiotic approach (denotative and connotative) for interpreting
Javanese literrature, and historical connection between text and the
context, this research attempts to elucidate Javanese social mentality. In
this paper, I describe humanism values through the content of Jangka
Jayabaya, authorship, and its influences. This research found that the
Religió: Jurnal Studi Agama-agamaMutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Volume 78, Nomor 21, Desember20178| ISSN: (p) 2088-6330; (e) 2503-3778p-ISSN:
2088-7523; e-ISSN: 2502-6321| 2151-23478-96
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
concept of “jangka” as Javanese worldview embodied social guideline as
well as social control for understanding social phenomenon, which are
represented within humanism values, such as local knowledge, equity,
equality, dignity, and moral ethics.
[Serat Jangka Jayabaya, sebagai salah satu local knowledge masyarakat
Jawa, memiliki relevansi terhadap sejarah Indonesia pada abad ke-18
yang secara strategis bisa digunakan untuk pembelajaran sejarah berbasis
nilai. Eksplorasi nilai humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya menarik
untuk dikaji karena menunjukkan bahwa masyarakat pada abad ke-18
memiliki pijakan ideal dalam merespon perubahan sosial. Menggunakan
metode penelitian analisis-deskriptif, dengan pendekatan semiotik
denotasi dan konotasi dalam menginterpretasi sastra Jawa, juga
pendekatan historis dalam mengaitkan teks dengan sejarah
kepengarangan, makalah ini bertujuan menelaah sejauh mana mentalitas
masyarakat Jawa pada masa itu. Nilai humanisme Jangka Jayabaya
dijelaskan berdasarkan konten, kepengarangan, serta kegunaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa konsep “jangka” sebagai Javanese
worldview merupakan petunjuk sekaligus kontrol masyarakat Jawa dalam
memahami fenomena sosial. Hal tersebut terangkum dalam konsep
humanitarianisme, yakni pengetahuan lokal, keadilan, kesederajatan,
martabat, serta etika moral.]
Keywords: Serat Jangka Jayabaya, humanism, Javanese
worldview.Abstrak: Serat Jangka Jayabaya sebagai salah satu local
knowledge masyarakat Jawa memiliki relevansi terhadap sejarah
Indonesia pada abad ke- 18 yang strategis untuk digunakan dalam
pembelajaran sejarah berbasis nilai. Eksplorasi nilai humanisme
dalam Serat Jangka Jayabaya sangat menarik untuk dikaji. Hal
tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada abad 18 memiliki
pijakan ideal dalam merespon berbagai perubahan sosial.
Menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan
pendekatan semiotik denotasi dan konotasi dalam menginterpretasi
sastra Jawa, juga pendekatan historis dalam mengaitkan teks
terhadap sejarah kepengarangan digunakan untuk mengetahui
sejauh mana mentalitas masyarakat Jawa pada masa itu. Nilai
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
humanisme Jangka Jayabaya dieksplanasikan berdasarkan konten,
kepengarangan serta kegunaan. Hasilnya menunjukkan bahwa
konsep “jangka” sebagai Javanese worldview merupakan petunjuk
sekaligus kontrol masyarakat jawa dalam memahami berbagai
fenomena sosial. hal tersebut terangkum dalam konsep
humanitarian yakni pengetahuan lokal, keadilan, kesederajatan,
martabat, serta etika moral. Selain itu, penokohan ahumanis tokoh
Jayabaya dalam serat ini di lain sisi justru sengaja ditampilkan
pengarang sebagai bentuk kritik humanisme yang mengindikasikan
lahirnya humanisme Jawa pada masa itu.
Kata kunci: Jangka Jayabaya, Humanisme, Javanese worldview.
Pendahuluan
Pentingnya penggunaan local knowledge dalam pembelajaran
sejarah sebagai transfer of value merupakan upaya dalam
pembentukan karakter humanitarian. Isu belakangan ini ramai
diberitakan di media sosial telah banyak menampilkan bentuk -
bentuk diskriminasi, intoleransi, serta fanatisme yang berbalut
politik identitas. Di sinilah paham kebhinekaan masyarakat
Indonesia mulai dipertanyakan kembali. Salah satu tindakan yang
dapat menanggulangi dampak-dampak isu sosial khususnya
terhadap generasi muda adalah dengan pembelajaran sejarah
sebagai character building. Dalam hal ini diperlukan sebuah
sumber sejarah yang memiliki nilai-nilai humanis dan dapat
direfleksikan dalam permasalahan kekinian. Salah satu di
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
antaranya adalah dengan menggunakan manuskrip Jawa yang kaya
akan kearifan lokal. Dipilihnya Serat Jangka Jayabaya sebagai
manuskrip jawa dalam model pembelajaran bukan tanpa sebab,
terlebih jika menguak konten menarik yang terkandung di
dalamnya. Dalam mengupas intisari dari Serat Jangka Jayabaya,
peneliti akan menggunakan dua sudut pandang, yakni analisis
berdasarkan konten penokohan dan isi narasi
Penggunaan teori semiotik denotasi dan konotasi dalam analisis
teks sastra akan mengungkap makna di balik simbol atau pertanda.
Denotasi sebagai tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan
penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit,
langsung, dan pasti. Sedangkan konotasi sebagai tingkat pertandaan
yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di
dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung,
dan tidak pasti. Konotasi sudah menguasai masyarakat akan
menjadi mitos.169Makna konotasi meliputi aspek makna yang
berkaitan erat dengan perasaan dan emosi serta nilai-nilai
kebudayaan dan ideologi.170Sebagai contoh, makna jangka secara
bahasa diartikan sebagai ramalan, ramalan merupakan hal yang
syirik dan tidak dapat dipercaya. maka, jangka dikenal sebagai
mitos bagi sebagian masyarakat Terkait denganlocal
knowledgemasyarakat terhadap konsep “jangka” atau ramalan yang
merujuk pada pemahaman ngelmu titen, yang secara lanjut
dilakukan guna ketercapaian bawana tentrem dalam ihwal space
culture sekaligus spiritual culture falsafah memayu hayuning
bawana.171Memayu hayuning bawanasebagai Javanese
worldviewWorldviewdiartikan sebagai cara pandang masyarakat
jawa dalam melihat dan mengerti segala sesuatu di alam dan
kehidupanya.
169
Yusita Kusumarini, Teori Semiotik (Surabaya: Universitas Kristen Petra,
2006), 31.
170
Yasraf Amir Piliang, Hipersemiotika Tafsir Cultural Studie Atas Matinya
Makna (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), 54.
171
Endraswara,Memayu Hayuning Bawana (Jakarta: Narasi, 2013), 16-17.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
Pemikiran tersebut muncul karena setiap manusia mengetahui
bahwa realitas dapat dipahami dan diartikan secara berbeda oleh
setiap masyarakat berdasarkan cara pandangnya. Maka guna
memperindah alamnya “hayuning–bawana” masyarakat jawa
harus mampu menempatkan diri sesuai dengan nilai etika dan
moral dalam setiap tindakannya, sehingga keseimbangan bawana
terwujud melalui kecerdasan, baik intelektual, emosional maupun
spiritual. Nilai humanis dalam Serat Jangka Jayabaya merupakan
petunjuk yang dapat digunakan sebagaik refleksi historis guna
melihat berbagai permasalahan sosial yang marak terjadi dalam
masyarakat Indonesia dewasa ini. Hal tersebut dapat digunakan
dalam pembelajaran sejarah, sebagaimana pada masa kesultanan
Mataram, Serat Jangka Jayabaya digunakan sebagai pedoman
kehidupan bermasayarakat sekaligus kontrol sosial.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut
paradigma postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen
kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
pada generalisasi172. Pengumpulan data menggunakan metode
wawancara dengan beberapa ahli tafsir sastra Jawa beserta analisis
dokumen. Data primer dalam penelitian ini adalah Serat Jangka
Jayabaya koleksi museum Radyapustaka, dan data sekunder berupa
salinan Serat Jangka Jayabaya dalam aksara Jawa koleksi
perpustakaan Universitas Sebelas Maret dan buku terjemahan Serat
Jangka Jayabaya karya Suyami dengan judul Kajian Budi Pekerti
dalam Serat Jangka Jayabaya maupun sumber penunjang lainnya.
Adapun wawancara dilakukan kepada berbagai ahli seperti tafsir
sastra jawa R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum selaku salah satu
tenaga pendidik sastra jawa UNIVET, Totok Yasmiran selaku
petugas alih naskah sekaligus penerjemah manuskrip Jawa
Museum Radya Pustaka, dr . R. Wisnu Kusumawardana selaku
ahli tafsir filsafat serta berbagai pihak dalam kegiatan diskusi
172
Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2011), 27.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
bersama. Wujud data kualitatif kemudian dianalisis dengan
pendekatan CDA (Critical Discourse Analysis) dimana analisis
wacana kritis dilakukan terhadap wacana yang berkembang dan
dikembangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, memiliki
kekuasaan, dengan memproduksi wacana dominan untuk
menguasai ruang publik agar pihak-pihak lain juga ikut terdominasi
dan terkuasai. Sebagaimana sastra Jawa yang memiliki relasi
dialektikal antar wacana dan elemen dalam kehidupan sosial
pengarang/penyadur yang penuh dengan aneka karakter dengan
proses-proses perjuangan politik
Adapun upaya penarikan nilai-nilai humanis dalam Serat Jangka
Jayabaya menggunakan teori semiotik teks tentang simbolisme atau
pertanda dalam suatu teks. Analisis teks merupakan analisis sebuah
kelompok atau kombinasi berupa kumpulan tanda yang membentuk
teks. Pada dasarnya teks mengandung representasi sikap, ideologi,
atau mitos tertentu. Dalam hal ini teks dalam Serat Jangka
Jayabaya tampaknya tidak hanya mengandung konotasi tetapi juga
denotasi. Konotasi tanda berkaitan dengan kode nilai, makna sosial,
dan berbagai perasaan, sikap, atau emosi. Tiap teks adalah
kombinasi sintagmatik tanda-tanda yang melalui kode sosial
tertentu menghasilkan konotasi tertentu. Konotasi yang berbeda
bergantung pada posisi sosial pembaca dan faktor lain yang
mempengaruhi cara berpikir dan menafsirkan teks. Konotasi yang
diterima luas secara sosial akan menjadi denotasi atau makna teks
yang dianggap benar. Denotasi merepresentasikan mitos budaya,
kepercayaan, dan sikap yang dianggap benar.
Javanese Worldview: Konsep Humanisme Dalam Serat Jangka
Jayabaya
Dalam memahami Javanese worldview yang tercermin dalam serat
ini, pelurusan makna jangka yang lebih luas bukan hanya perihal
ramalan yang dipercayai dalam mitologi jawa. Jangka sebagai
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat dicerminkan dari
berbagai nilai humanisme dalam manuskrip tersebut. Hal ini
dikarenakan sebuah petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat
hendaklah senantiasa berpegang tegung pada konsep kemanusiaan.
Walaupun jika kita lihat bersama persoalan kemanusiaan abad 18
dengan masa kini memang dua hal yang berbeda. Akan tetapi hal
ini dapat digunakan sebagai refleksi historis masyarakat di mana
nilai humanisme Serat Jangka Jayabaya masih sangat ideal
diterapkan dimasa kini.
Penelitian lain berjudul “Serat Jangka Jayabaya: Relasi Sastra,
Sejarah dan Nasionalisme” menunjukkan bahwa terdapat konten
menarik dalam manuskrip tersebut sehingga memiliki pengaruh
besar terutama pada awal mula lahirnya benih nasionalisme. Hal itu
dilandasi kepercayaan setempat atau kejawen yang merujuk pada
ideologi pengabsahan pergerakan resistensi melawan penjajahan
pada masa kolonialisme abad ke-19173. Jika dalam penelitian
tersebut memfokuskan diri terhadap konsep Ratu Adil sebagai
mesias atau pembebas terhadap berbagai kekacauan zaman yang
merujuk pada diskursus resistensi terhadap kolonialisme, dalam
penelitian ini membahas local knowledge yang terdapat dalam
Serat Jangka Jayabaya sehingga mampu mempengaruhi (sekaligus
berakar dalam) mentalitas masyarakat Jawa. Apa sebenarnya
gagasan humanisme yang telah tumbuh pada masa tersebut dan
bagaimana refleksi yang dapat dilakukan pada masa kini.
Sebelum dilakukan analisis terkait nilai-nilai humanisme yang
terdapat dalam Serat Jangka Jayabaya, terlebih dahulu dijabarkan
pengertian dari humanisme itu sendiri. Humanisme
merupakansuatu pandangan atau paham yang menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia yang mana setiap manusia memiliki
kedudukan, keistimewaan serta keunikan masing-masing. Sehingga
manusia sebagai pusat dari alam semesta bisa menjaga setiap
173
Sasmita, G, “Serat Jangka Jayabaya: Relasi Sastra, Sejarah dan
Nasionalisme”, Historica Volume 6 Nomor 2 (2018), 391-402.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
perbuatan guna tercapainya keselarasan hidup.Seseorang yang telah
mampu berpedoman pada nilai-nilai humanis dalam setiap
pemikiran dan perbuatannya disebut sebagai humanitarian. Maka,
seseorang yang telah atau sedang mempelajari sejarah adalah dalam
upaya mewujudkan pribadi humanitarian. Hal ini didasarkan pada
sumsi bahwa dalam setiap penjelasan sejarah atau eksplanasi
sejarah diharapkan memberikan nilai-nilai positif dan
kebermanfaatan berdasarkan esensi peristiwa masalalu dalam
refleksi kekinian. Eksplanasi Serat Jangka Jayabayamerupakan
upaya merevitalisasi nilai-nilai local genius masyarakat Jawa.
Sebagai acuan nilai humanitarian dalam membedah Serat Jangka
Jayabaya, Figur Abdurrahman Wahid dipilih sebagai humanitarian
ideal. Hal ini mengacu pada pendapat Greg Barton setelah
menelusuri pemikiran dan tulisan Abdurrahman Wahid menemukan
sebuah tema palingdominan dalam pemikiran Gus Dur, yaitu
humanitarianisme.174 Adapun prinsip humanitarian tersebut adalah
local knowledge (pengetahuan lokal), equity (keadilan) dan equality
(kesederajatan atau persamaan). Seseorang yang humanis pada
dasarnya memiliki kemampuan intelektual serta menjunjung tinggi
nilai keadilan dan persamaan/kesederajatan. Prinsip tersebut
digunakan sebagai refleksi serat Jangka Jayabaya karena dianggap
memiliki karakteristik humanitarian yang ideal yakni tercermin dari
berbagai pemikiran dan gagasan Abdurrahman Wahid tentang
humanisme ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Deskribsinilai humanis dalamSerat Jangka Jayabayabisa
dipaparkan sebagai berikut;
Pengetahuan lokal (Local knowledge)
“Punika cariyosipun Prabu Jayabaya kala katamuan pandhita
saking Rum anama Molana Ngali Samsujen. Prabu Jayabaya
langkung kurmat dening katamuan pandhita linuwih, misuwur,
174
reg Barton, Liberalisme Dasar-Dasar Pemikiran Abdurrahman
Wahid(Yogyakarta: LkiS, 1997),166-167.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
saget amemaca, uninga saderenging winarah. Prabu Jayabaya
lajeng puruhita ing sasuraosing jangka ingkang gaib-gaib,
wadosing cipta sasmita...”
Diceritakan suatu ketika Raja Jayabaya bertemu dengan pendeta
(ahli agama) dari negeri Rum yang bernama Maulana Ali
Samsuzen. Prabu Jayabaya menghormati beliau sebagai pendeta
yang memiliki pengetahuan (kemampuan) lebih, terkenal, serta
dapat membaca, mengerti sebelum terjadi. Raja Jayabaya kemudian
diberi pengetahuan terkait jangka yang gaib-gaib dan tanda yang
bersifat rahasia175. Dalam penggalan ini ditampilkan bagaimana
jangka merupakan suatu pengetahuan empirik yang dilestarikan
secara turun temurun guna memahami atau membaca berbagai
peristiwa untuk dapat memproyeksikan masa depan agar lebih baik
daripada masa kini. Pengetahuan yang semacam ini, pada konteks
kontemporer sangat berkaitan dengan pembelajaran sejarah. Karena
memlalui sejarah seseorang akan mampu mempelajari berbagai
peristiwa masa lalu agar tidak kembali terjadi kejadian dengan pola
yang sama pada masa kini dan masa depan.
“Sasampunipun rampung panganggiting jangka Prabu Jayabaya
ingkang kababaraken dados lalampahaning jaman satunggal-
satunggal, kestokaken dening Molana Ngali Samsujen...”
Sesudah selesai menggubah jangka yang dijelaskan menjadi
pembabakan zaman satu per satu, Raja Jayabaya lalu
mepertunjukkan hasilnya kepada pendeta Maulana Ali Samsuzen.
Dalam bait tersebut tampak adanya akulturasi terhadap
pengetahuan awal dengan keyakinan Jayabaya dalam memahami
berbagai fenomena sosial yang ada. Hal tersebut merupakan salah
satu bentuk enkulturasi yakni proses internalisasi nilai norma
kebudayaan yang dialami seorang individu dimana pola
kebudayaan yang diterima berdasarkan pembawa kebudayaan
sebelumnya dianggap ideal dan diakulturasi terhadap konsep diri.
175
Suyami, Kajian Budi Pekerti dalam SeratJayabaya (Yogyakarta: Balai
Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 2015), 125.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
“Prabu anom adhiku, lajeng matur menggah tegesipun sesegah
wau, dumungpun ing kraton satunggal-satunggal...” Raja Anom
adikku, adapun arti sesungguhnya dari sesuguhan tadi ada
kaitannya dengan kerajaan satu persatu. Bahkan seorang rajapun
memiliki penjelasan di balik segala tindakan yang telah
diperbuatnya. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa transparasi
memang diperlukan dalam setiap tindakan yang ditujukan kepada
khalayak umum atau kebaikan bersama.
Seseorang dikatakan sebagai humanitarian ketika ia memiliki
kompetensi intelektual sesuai dengan bidang yang ia kuasai.
Sebagai contoh, seorang raja harus memiliki kecerdasan
intelektual, emosional dan spiritual, seorang mahasiswa pendidikan
sejarah memiliki kemampuan dalam melakukan eksplanasi sejarah
dengan ketrampilan dalam berbagai tahapan metodologi sejarah,
baik dalam heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.
Pengetahuan lokal atau local knowledge sebagaimana dijelaskan
oleh Nygren, merupakan sebuah istilah yang problematik yang
justru dianggap tidak ilmiah jika dibandingkan dengan pengetahuan
Barat. Titik temu antara pengetahuan lokal yang tidak ilmiah dan
yang ilmiah tersebut berdasar pada rasionalitas Barat dimana
keduanya berada pada bagaimana cara memahami dunia mereka
sendiri. Pengetahuan lokal dapat ditelusuri dalam berbagai bentuk
baik pragmatis maupun supranatural. Akan tetapi, justru pola
demikian merupakan hal yang rasional bagi masyarakat Jawa
dalam memahami setiap kejadian. Pertanda sebagaimana
diakumulasikan secara empirik kemudian di-sebarluaskan secara
turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.
Penokohan Jayabaya dalam Serat Jangka Jayabaya yang
merupakan symbol dari local knowledge dapat dilihat bagaimana ia
menggunakan kompetensi yang dimiliki guna memecahkan
permasalahan yang akan dihadapi rakyatnya di kemudian hari yang
disimbolkan dengan penghayatan tapa semedi. Hal ini jika
direfleksikan pada masa kini dapat diartikan sebagai pembelajaran
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
dalam konteks lifelong learning, dimana setiap orang mampu
mengkonstruksi pengetahuan yang ia dapat dan mengkombinasikan
dengan konstruksi pengetahuan di dalam dirinya sendiri.
Raja yang dianggap sebagai sosok pemimpin yang senantiasa
diagungkan oleh rakyatnya pastilah seseorang yang memiliki
kompetensi dalam berbagai hal baik secara intelektual maupun
spiritual seperti halnya Raja Jayabaya yang dianggap sebagai
pengejawantahan Dewa Wisnu di muka bumi. Jayabaya memiliki
tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya menggunakan
pengetahuan lokal yang ia dapat dari gurunya, dikembangkan dan
disebarluaskan untuk kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut
tercermin dalam Serat Jangka Jayabaya yang menceritakannya
tokoh Jayabaya yang datang menemui pendeta dari Rum, Maulana
Ali Samsuzen untuk ngangsu kaweruh atau mencari ilmu dan
diperlihatkanlah jangka atau ramalan tentang zaman-zaman sesuai
dengan Kitab Musarar.
Jayabaya sebagai seorang raja tidak lantas congkak dan merasa
puas terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Seseorang yang
belajar, sesuai teori konstruktivisme, mampu mengkonstruksi
pengetahuannya secara mandiri. Disini Jayabaya melakukan tapa
semedi setelah mendapatkan kaweruh dari Maulana Ali Samsuzen.
Kemudian Ia mampu mengartikan arti dari simbolisme 7 suguhan
yang pernah diberikan oleh Ajar Subrata sebagaimana ia
menggubah jangka yang dijelaskan menjadi pembabakan zaman
satu persatu dan mempertunjukkan hasilnya kepada pendeta
Maulana Ali Samsuzen. Kemudian dijabarkanlah arti dari sesuguh
tersebut kepada adiknya Raja Anom.
Ramalan atau jangka ialah pengejawantahan pengalaman empirik
masalaluatau dalam istilah jawa dikenal sebagaingelmu
titen.Sehingga, disini Jayabaya secara empirik memaknai dalam
setiap kejadian, baik yang telah atau sedang terjadi, agar bermakna
untuk sesama sebagaimana ungkapan “history make man wise” dan
Historie vitae magistra:yakni pembelajaran sejarah sebagai guru
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
terbaik dalam mengantarkan umat manusia menjadi bijaksana dan
bermartabat.
Keadilan (Equity)
Keadilan merupakan sebuah simbol dari terlaksananya
kesejahteraan. Maka seorang yang humanis adalah seseorang
menjunjung tinggi nilai keadilan. Didalam Serat Jangka Jayabaya
khususnya pada pembabakan zaman kalabendu ditampilkan
berbagai kekacauan yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Kekacauan tersebut menggambarkan bahwa rakyat semakin
sengsara akibat raja yang hanya memikirkan harta sehingga pajak
rakyat semakin naik, bahkan rakyat yang tak mampu membayar
dengan barang yang ditentukan memberikan pajak dengan berbagai
wujud. Jika dilihat dari latar belakang kepengarangan nampaknya
terkait keadilan dalam pajak merujuk pada pengenalan sistem pajak
oleh pemerintah kolonial Belanda terutama terkait pajak tanah.
Dalam hal ini unsur dari materialisme dan egosentrisme penguasa
ditampilkan dengan sangat jelas oleh pengarang.
“Ing sajroning jaman kalabendu ana jamaning ratu hartati, tegese
sarupaning manungsa kang kaesthi mung harta...wadale wong cilik
warna-warna, ana metu mas salaka, beras pari sapanunggalane,....
ing ngantara mangsa sangsaya mundhak mundhak pajeging wong
cilik...”
Didalam zaman kalabendhu ada zamannya Ratu Hartati, (berasal
dari kata harta + ti yang berarti kekayaan atau ekonomi) sejenis
manusia yang hanya memikirkan harta pajak rakyat kecil yang
bermacam-macam, berupa mas salaka, beras, padi dan lain
sebagainya. Disuatu masa semakin naiklah pajak rakyat kecil.176
Berdasarkan penggalan tersebut, terlihat bagaimana ratu yang
hanya memikirkan kekayaan pribadi sehingga kesejahteraan rakyat
tidak diperhatikan, berbagai macam pajak mengindikasikan bahwa
176
Suyami, Kajian Budi Pekerti, 133.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
rakyat sudah tidak mampu membayar pajak berupa emas atau uang,
sehingga apapun yang dimilikinya digunakan untuk membayar
pajak.
“Karana sangsaya mundak-mundak muksibating nagara, kongsi
retu adiling ratu, amarga wong agunge pada jahil, wong cilik podo
jawal...”
Karena semakin banyaknya musibah yang menimpa negara, tidak
ada ratu yang adil karena pembesarnya berhati jahat dan orang
kecilpun nakal. Kekacauan yang terjadi dalam penggambaran
zaman kalabendhu secara jelas ditegaskan oleh pengarang dalam
gambaran ketiadaan ratu yang adil. Pemimpin sebagai panutan
yang mengemban tanggung jawab dalam setiap kehuidupan
rakyatnya tidak lagi memikirkan kesejahteraan rakyat kecil, tetapi
justru sibuk dalam memperkaya diri.
“Apngaling wong asalin-salin... kerep ana prang, sujana-sarjana
kontit, durjana dursila saya andadra,... ing wektu iku wus parek
wekasaning jaman kalabendu, ing kana harjaning tanah jawa wus
ilang mamalaning bumi, amarga sinapih tekaning ratu ginaib,
wijiling utama...... jumeneng ratu pinandhita adil paramarta,
lumuh maring arta, kasebut nama sultan Herucakra...”
Sifat manusia berubah-ubah, sering terjadi perang, orang-orang
berpengetahuan dan berpendidikan semakin tersingkir itu tanda
sudah dekat akhir zaman kalabendhu digantikan zaman kejayaan
tanah jawa, sudah hilang musibahnya bumi karena dihentikan oleh
raja gaib, lahir dari kebaikan, beliau menjadi raja yang adil dan
sabar, tidak suka pada harta, dikenal dengan nama sultan
Herucakra.177
Kutipan serat tersebut menggambarkan bagaimana seseorang akan
kehilangan jatidirinya hingga menampilkan berbagai perilaku
ahumanis karena kondisi sosial yang tidak lagi benar, Sementara
177
Suyami, Kajian Budi Pekerti, 134.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
pembesar yang dianggap sebagai panutan justru bertindak tidak
benar. Hal ini ditunjukkan berdasarkan ungkapan apngaling wong
asalin-salin, perilaku orang berubah-ubah atau plin-plan yang
berarti tidak memiliki pendirian tetap, kongsi retu adiling ratu,
adanya keadaan yang buruk/kekacauan tanpa hadirnya ratu adil,
dan berbagai ungkapan lainnya yang mengindikasikan bahwa tanpa
keadilan berbagai kekacauan akan terjadi dalam suatu masyarakat.
Konsep ratu adil ditampilkan sebagai harapan terhadap
pembebasan berbagai kekacauan,sebagai sosok ratu gaib yang
membebaskan musibah bumi. Secara harfiah hal itu merujuk pada
pemaknaan bahasa Jawa terhadap penokohan Herucakra terdiri dari
dua kata yakni heru yang berarti hera-heru atau huru hara atau
perlambang terhadap permasalahan atau kekacauan. Sedangkan
cakra berarti roda. Jika dikaitkan dengan senjata, cakra merupakan
senjata milik Dewa Krisna yang mampu menghentikan jagad raya
termasuk matahari (dalam kisah Bharatayuda).Maka, Herucakra
merupakan perlambang seseorang yang mampu menumpas
berbagai kekacauan yang dihadapi pada zaman kalabendhu. Lalu
sesungguhnya yang menarik disini adalah siapakan sultan
Herucakra.Secara filosofis, setiap manusia memiliki sosok
Herucakra (juru selamat) didalam dirinya masing-masing, karena
keadilan diciptakan dan bukan ditemukan. Manusia diberi akal budi
pekerti oleh Tuhan untuk dapat menentukan nasibnya. Setiap
pijakan dalam tindakan manusia senantiasa bertitik tumpu pada
nilai keadilan, adil terhadap diri sendiri dan orang lain.
Kesederajatan (equality)
Persamaan dan kesederajatan dalam nilai humanis Barat diartikan
dengan penyamarataan atas hak dan kewajiban setiap orang.
Namun, kesederajatan dalam konteks budaya Timur bukan sekedar
pengakuan akan kesamaan derajat melainkan bagaimana
seseorang mampu bertindak sesuai dengan derajat diri dan
posisinya (mampu menempatkan diri dalam setiap situasi dan
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
kondisi). Ia mampu mengenali siapa dirinya dan mampu bertindak
sesuai dengan peran yang ia miliki secara bertanggung jawab.
Sebagai contoh, jika hal ini direfleksikan pada masa kini,
bagaimana seorang mahasiswa harus mampu bertindak sesuai
dengan etika yang ia miliki sebagai bagian dari proses belajar.
Seorang penguasa harus mampu menempatkan diri layaknya
Herucakra.Konsep ini juga berkaitan dengan kemampuan
intelektual.
“Punika cariyosipun Prabu Jayabaya kala katamuan pandhita
saking Rum anama Molana Ngali Samsujen. Prabu Jayabaya
langkung kurmat dening katamuan pandhita linuwih, misuwur,
saget amemaca, uninga saderenging winarah.”
Diceritakan suatu ketika Raja Jayabaya bertemu dengan pendeta
(ahli agama) dari negeri Rum yang bernama Maulana Ali
Samsuzen. Prabu Jayabaya menghormati beliau sebagai pendeta
yang memiliki pengetahuan (kemampuan) lebih, terkenal, serta
dapat membaca, mengerti sebelum terjadi.178
“duh wruhanira kulup kulup ingsun, iki panjanmaning wisnu murti,
kabubuhan agawe harjaning bumi-bumi....” Ketahuilah bahwa
sesungguhnya aku adalah pengejawantahan Dewa Wisnu untuk
menjaga kedamaian (kesejahteraan) bumi.
Seorang Jayabaya di dalam Serat Jangka Jayabaya menyatakan diri
sebagai pengejawantahan atau titisan Dewa Wisnu mengisyaratkan
bahwa ia adalah seorang yang beragama Hindu tetapi tetap
menjunjung tinggi nilai kesederajatan tatkala ia menerima
pengetahuan dengan seorang pendeta dari Rum, yang beragama
Islam Maulana Ali Samsuzen. Di sini jayabaya mengakui adanya
kesederajatan walaupun dalam bingkai perbedaan.
Untuk memahami manuskrip Jawa, tidak dapat diilepaskan dari
konsep martabat (dignity) dan nilai (value). Nilai humanisme akan
178
Suyami, Kajian Budi Pekerti, 135.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
menjadikan seseorang bermartabat. Nilai moral dan etika adalah
dasar terbentuknya martabat tersebut. Setiap serat memiliki
tuntunan atau wejangan kepada generasi muda, sembari
mengingatkan nilai budaya luhur yang perlu dilaksanakan dan
dilestarikan.
Martabat akan menciptakan sebuah keadaan yang harmonis dalam
kehidupan. Sebaliknya, hilangnya martabat pada diri sseorang akan
menyebabkan kekacauan. Dalam hal ini, martabat akan tercapai
ketika seseorang mampu menempatkan diri di dalam perannya di
masyarakat. Proses pemartabatan diri bisa dicapai melalui
pendidikan yang mengarah pada transfer of knowledge and value.
Nilai dan moralitas merupakan pedoman kehidupan bermasyarakat.
Nilai-nilai ini senantiasa mengalami pergeseran sepanjang zaman.
Revitalisasi nilai-nilai local genius diperlukan dalam pembelajaran.
Serat Jangka Jayabaya sebagai salah satu sumber sejarah
menggambarkan bagaimana kekacauan dalam setiap zaman
memiliki penyelesaian, yang bukan hadir dari orang asing
melainkan dari jati diri yang dihayati bersama sesuai dengan nilai
budaya Jawa.
Gambaran di atas merupakan kajian penokohan Jayabaya sebagai figur
humanitarian dengan jangka yang ia sampaikan. Pengarang juga
memberikan hal menarik yang justru bertentangan dengan kaidah
humanitarian: dapat dilihat pada bait dimana Jayabaya menumpas Ajar
Subrata yang merupakan murid Maulana Ali Samsuzen. Menumpas
dalam sastra memang tidak dapat diartikan sebagai membunuh, akan
tetapi secara luas adalah mematikan pengaruh terhadap suatu kondisi.
Dalam hal ini, Ajar Subrata dapat dikatakan sebagai lawan politik
Jayabaya, yang dapat mengancam jangka yang telah ia buat.
Tindakan tersebut merupakan perilaku ahumanis, dimana seharusnya
seorang pemimpin tidak menggunakan dalih kesejahteraan dalam
pembenaran perilaku politik yang ia lakukan. Jika hal ini, ditarik pada
zaman Ranggawarsita sang penyadur naskah, latar belakang sosio
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
kultural merupakan alasan kuat mengapa naskah tersebut ditedhak
kembali. Bahkan pada masa tersebut popularitas Jangka Jayabaya
semakin meningkat tatkala konsep Ratu Adil yang di-adaptasi dalam
Serat Jangka Jayabaya, dikembangkan menjadi kritik sosial dalam serat
Kalathida yang sangat terkenal dengan istilah zaman edan. Adaptasi
tersebut merupakan suatu bentuk enkulturasi dimana ia menganggap
harus ada keberanian dalam kritik sosial daripada pendahulunya yang
banyak menyadur naskah tersebut.
Kepedulian terhadap ketertindasan masyrarakat pribumi baik rakyat
jelata, bangsawan maupun kaum terpelajar merupakan dasar bagaimana
paham himanisme mulai lahir pada masa itu. Kolonialisme sebagai
gambaran kekacauan dimana seseorang diperlakukan secara tidak
manusiawi justru menumbuhkan kesadaran pentingnya menghargai
harkat dan martabat manusia, terlepas dari kelas sosial yang ia sandang.
Terkucilkannya Ranggawarsita dari lingkungan keraton, sehingga ia
menjalin relasi akademis Mangkunegaran IV terutama dalam berbagai
penulisan sastra Jawa, secara tidak langsung merupakan bentuk
ketidakharmonisan dengan kasunanan. Melalui gubahan Serat Jangka
Jayabaya, ia menampilkan kembali sebuah kritik kepada penguasa atas
tindakan yang kurang pantas. Ia memberi gambaran bahwa dalam
melegitimasi kekuasaan seorang pemimpin, dengan dalih kesejahteraan
rakyat, bisa menghalalkan segala cara dengan menyingkirkan pihak-
pihak yang dianggap mengganggu.
Local Genius Masyarakat dalam Konsep Jangka
Pembelajaran sejarah secara kontekstual tidak terlepas dari nilai.
Didalam setiap sumber sejarah, baik tersirat maupun tersurat, selalu
terdapat nilai yang ingin disampaikan. Serat Jangka Jayabaya
merupakan sember sejarah berupa dokumen-manuskrip-serat
peninggalan kerajaan Mataram Islam sekitar abad ke-18 yang
sumber kitab musarar. Hal ini merujuk pada kitab Asrar karangan
Sunan Giri ke 3 yang ditulis pada tahun 1618 M. Kitab Jangka
Jayabaya pertama dan yang dianggap asli adalah karya Pangeran
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
Wijil I dari Kadilangu yang mendapat sebutan Pangeran Kadilangu
II, yang dikarang pada tahun 1741-1743 M179.
Dari sisi konten, Serat Jangka Jayabaya merupakan sebuah
sinkretisme Islam-kejawen. Hal ini tampak pada akulturasi budaya
dalam bagian pembuka, ketika diceritakan Sang Prabu Jayabaya
bertemu dengan gurunya Maulana Ali Samsudin. Dari hal
tersebut,diketahui bahwa agama Islam memiliki nilai toleransi yang
besar antar sesama, Yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan
kemanusiaan. Disisi lain, agama Islam juga dapat dimaknai
memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada Hindu, terlihat dari
bagaimana seorang Raja Jayabaya, sebagai pengejawantahan Dewa
Wisnu, justru berguru kepada seorang Muslim. Selain itu,
bagaimana pembabakan zaman yang menampilkan tujuh zaman
juga mengindikasikan adanya pencampuran unsur Islam dengan
kejawen yang mana dalam agama islam sangat sering
menggunakan angka tujuh seperti dalam ungkapan langit sap 7.
Serat Jangka Jayabaya berakar pada mentalitas orang Jawa secara
luas. Hal tersebut dipahami sebagaimana local genius masyarakat
terhadap konsep jangka atau ramalan yang merujuk pada
pemahaman ngelmu titen, yang secara lanjut dilakukan guna
ketercapaian bawana tentrem dalam ihwal space culture sekaligus
spiritual culture falsafah memayu hayuning bawana180.
Kepercayaan masyarakat Jawa atau yang sering disebut dengan
kejawen memiliki ketertarikan yang besar terhadap berbagai hal-hal
seperti jangka, ramalan dan klenik. Hal ini berhubungan dengan
local knowledge masyarakat yang senantiasa memahami berbagai
peristiwa secara kosmologis. Beberapa jangka dalam karya sastra
lama sangat menarik untuk dikaji, ditinjau dari popularitasnya yang
tak pernah surut dari perbincangan.
179
Soewarno, Ramalan Joyoboyo versi Sabdopalon (Kediri: Cagar Budaya,
2004), 65.
180
Endraswara,Memayu, 16-17.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
Seiring dengan arus modernisasi, masyarakat mulai kritis terhadap
kesahihan sebuah jangka. Jangka secara konotasi seringkali
diartikan sebagai ramalan, sementara ramalan secara denotasi
dimaknai sebagai hal berbau syirik atau musyrik karena
mempercayai kehendak lain selain Tuhan. Akan tetapi, secara
interpretasi teks, Jangka dalam Serat Jangka Jayabaya merujuk
pada pengertian petunjuk atau pertandasebagaimana jangka
menunjukkan gambaran zaman-zaman seperti halnya kitab suci
Alquran.
Petunjuk yang demikian seyogyanya merupakan pengetahuan
terhadap akumulasi pengalaman empiris yang terangkum menjadi
satu. Sedangkan pertanda dapat diartikan sebagai keterangan dari
petunjuk tersebut. Maka, Serat Jangka Jayabaya lebih tepat jika
diartikan sebagai petunjuk yang diperoleh melalui metode
keilmuan dan spiritual kapujanggan. Namun, persepsi yang justru
berkembang dalam masyarakat menganggap Jangka Jayabaya
sebagai mitos atau takhayul terkait pemaknaan “ramalan” yang
cenderung mengarah pada makna denotasi kesesatan. Untuk
memahami lebih lanjut isi dari petunjuk yang sengaja
direpresentasikan oleh pengarang dalam karya ini bisa dengan cara
mendalami berbagai simbolisme dalam manuskrip tersebut.
Dalam karya sastra jawa, simbolisme memegang peranan atas
terhadap ketercapaian penyampaian nilai kepada khalayak umum.
Simbolang digunakan sebagai perantara pemahaman terhadap
obyek yang merupakan perlambang, berupa suatu benda, keadaan,
atau hal lain yang memiliki arti. Manusia adalah mahluk budaya,
dan budaya manusia penuh dengan simbol-simbol. Dapat dikatakan
bahwa budaya manusia penuh diwarnai oleh simbolisme, tata
pemikiran yang mengikuti pola-pola mendasarkan diri pada
simbol-simbol.181
181
Herusatoto, Simbolisme Jawa (Yogyakarta: Ombak, 2008), 46.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
Simbol yang digunakan oleh satu masyarakat dengan masyarakat
lainnya berbeda satu sama lain. Kata pujangga berasal dari bahasa
sanskerta bhujangga yang artinya ular, dianggap sebagai lambang
kebijaksanaan yang istimewa, Sebaliknya, simbol ular bagi
kebudayaan Barat dianggap sebagai simbol setan atau keburukan182.
Maka untuk memahami sebuah simbol, kita perlu menempatkan
diri pada sudut pandang tempat dan waktu dimana simbol tersebut
digunakan. Secara harfiah Jayabaya menurut Adi Kusumawardhani
dan Totok Yasmiran, merujuk pada kata jaya yang berarti berjaya
atau menang. Sedangkan baya berarti bebayan atau bahaya atau
sebuah simbol masalah. Jadi, Serat Jangka Jayabaya merupakan
sebuah gambaran bagaimana tokoh utama menang dalam
mengatasi permasalahan melalui berbagai petunjuk-petunjuk
zaman. Alasan terkait pemilihan Jayabaya sebagai tokoh utama
oleh pengarang dalam manuskrip ini merujuk pada keterhubungan
nilai-nilai dengan tokoh tersebut. Perspektif pengarang
mengisyaratkan bahwa masa pemerintahan Jayabaya merupakan
hal ideal bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini
senada dengan kondisi yang diharapkan oleh pengarang pada masa
lalu, renaisans Jawa. Oleh karena itu, salah satu nilai sentral yang
dapat dicuplik dari serat ini adalah nilai kedamaian atau peace
building.
Nilai merupakan sesuatu yang penting dari kebudayaan. Pergeseran
nilai dalam masyarakat berkembang senantiasa mempengaruhi
perubahan folkways dan mores. Hal ini dipengaruhi oleh faktor
intern maupun ekstern dalam suatu masyarakat. Secara eksternal,
nilai dalam masyarakat Jawa mengalami pergeseran antara sebelum
dan sesudah penjajahan Belanda. Filsafat Jawa yang senada dengan
eksistensialime humanis mengalami pergeseran ke arah
materialisme. Pergeseran nilai yang dipegang oleh sekelompok
orang tertentu dalam masyarakat merupakan sebuah anomali
tatkala terjadi ketidaksesuaian dengan nilai yang dianut
sebelumnya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan
182
Ibid., 98-99.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
sosial. Secara sederhana kita dapat menyatakan bahwa seseorang
menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat
perilaku atau tindakan tersebut diluar kebiasaan, adat-istiadat,
aturan, nilai atau norma sosial yang berlaku).183
Untuk menjelaskan isi zaman kalabendu pada Serat Jayabaya, kita
perlu meminjam teori penyimpangan sosial, yakni bagaimana
kekacauan terjadi pada zaman tersebut, apa penyebabnya dan
bagaimana penyelesaiannya. Terjadinya pergeseran perilaku
masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh Serat Jangka Jayabaya
pada zaman kalabendu, yang mana salah satunya ditunjukkan oleh
uangkapan apngaling wong asalin-salin, merupakan ungkapan atas
kondisi seseorang yang berubah-ubah, plin-plan dan kehilangan jati
dirinya. Keterkaitan penyimpangan harus dihubungkan dengan
konteks waktu dan tempat terjadinya penyimpangan. Artinya nilai
dan norma yang berlaku didalam satu kelompok sosial bisa saja
tidak berlaku pada kelompok sosial lainnya.184
Nilai moral dan budi pekerti yang ditampilkan dalam Serat Jangka
Jayabaya merupakan pencerminan nilai humanis yang diungkapkan
pengarang melalui pencitraan tokoh Jayabaya dalam jangka tujuh
zaman. Menurut yasmiran serat jayabaya merupakan gubahan
Raden Ngabei Ranggawarsita.185 Dalam kepenulisan, seorang
pujangga memiliki konsepsi yang sama dengan budaya literasi
masa kini. Hal ini tampak dalam kajian intertekstualitas serat yang
memiliki hubungan dengan serat lainnya. Seorang pujangga dalam
karyanya seringkali memuat kutipan karya lain yang berkenaan
dengan konsep pedoman yang di pegang teguh. Sarat Jangka
Jayabaya merupakan karya gubahan atau tedhakan yang senantiasa
dilestarikan karena dianggap memiliki nilai luhur dan relevan pada
zaman Ranggawarsita.
183
E. M. Setiadi, Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala
Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Group,
2018), 187.
184
Ibid., 188.
185
Wawancara dengan Yasmiran, 17/02/2018
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
Konsep ratu adil atau heru cakramenjadi esensial ketika simbol
kesejahteraan diharapkan menjadi resolusi bagi ketimpangan sosial
yang terjadi di masyarakat. Pola pikir berdasarkan ramalan
merupakan perwujudan dari mentalitas masyarakat Jawa
tradisional. Namun, kesalahan persepsi yang berkembang dalam
masyarakatmenganggap Sang Maharaja Sri Aji Jayabaya sebagai
seorang pencipta dari jangka tersebut. Mungkin itu terjadi karena
secara tidak langsung Serat Jangka Jayabaya menyebutkan bahwa
ia mengkonstruksi pengetahuan yang bersifat mengembangkan
ramalan jaman sesuai Kitab Musarar yang ditunjukkan oleh
pendeta Maulana Ali Samsuzen.
Pada dasarnya muatan dalam serat Jayabaya memiliki titik temu,
yakni konten yang sama mengenai harapan terhadap kondisi yang
seharusnya. Hal ini merupakan prinsip hidup masyarakat Jawa
yang sangat memperhatikan tatanan norma masyarakatdan budi
pekerti luhur. Gubahan Serat Jayabaya karya Ranggawarsita
memiliki daya tarik tersendiri jika dihubungkan dengan sosio
kultural kepengarangan. Bagaimana sosok Ranggawarsita
kemudian mampu menghidupkan kembali serat Jayabaya yang
diadopsinya sehingga menghasilkan serat Kalatidha, yang dalam
serat Jayabaya berarti zaman kalabendu. Dari sinilah kemudian
konsep ratu adil hingga sampai saat ini melekat pada pandangan
masyarakat Jawa.
Konsep kesejahteraan akan dapat terwujud tatkala ada sosok juru
selamat. Jika ditarik dalam konteks pembelajaran sejarah, juru
selamat merupakan pengetahuan itu sendiri atau siswa yang mampu
memahami dan mengkonstruksi pengetahuannya agar mampu
mencari dan mengusahakan kesejahteraan dan keselamatan atas
dirinya sendiri serta lingkungan disekitarnya. Disinilah mengapa
perlu dilakukan kajian intertekstual terhadapserat Jayabaya dalam
narasi sejarah. Teori intertekstualitas dalam sastra didefinisikan
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
oleh Kristeva sebagai bagunan teks melalui mozaik kutipan-kutipan
atau sebagai penyerapan dan transformasi dari teks lain.186
Kesimpulan
Konsep Jangka dalam Serat Jangka Jayabaya merujuk pada
pengertian petunjuk atau pertanda sebagaimana jangka
menunjukkan gambaran zaman-zaman, Misalnya dalam kitab suci
Alquran. Petunjuk seyogyanya merupakan pengetahuan akumulatif
dari pengalaman empiris yang terangkum menjadi satu. Sedangkan
pertanda dapat diartikan sebagai keterangan dari petunjuk tersebut.
Maka, Serat Jangka Jayabaya lebih tepat jika diartikan sebagai
petunjuk yang diperoleh melalui metode keilmuan dan spiritual
kapujanggan memiliki relevansi jika diterapkan pada masa kini.
Nilai humanisme sebagai esensi manuskrip tersebut tercermin
dalam prinsip humanitarian penokohan Jayabaya dengan: (1) local
knowledge sebagaimana simbol raja yang memiliki kemampuan
tinggi tetapi tetap berguru kepada orang lain yang memiliki
pengetahuan lebih, (2) equity ditunjukkan oleh berbagai kekacauan
dalam pembabakan zaman kalabendu akibat tidak adanya ratu adil
diselesaikan melalui datangnya seorang misianis sebagai Raja yang
adil hingga rakyatnya kembali makmur, dan (3) equality yang
ditunjukkan oleh penerimaan Raja Jayabaya Hindu berguru kepada
orang Muslim, Maulana Ali Samsuzen. Seseorang dikatakan
bermartabat jika ia mampu menempatkan diri dalam segala situasi
dan kondisi dan senantiasa berpegang teguh kepada etika dan moral
agar senantiasa menjadi juru selamat untuk dirinya sendiri dan
orang sekitar.
Seorang humanitarian, harus menyelaraskan pikiran, perkataan dan
perbuatan. Seorang pemimpin sebagai panutan rakyatnya tidak
dibenarkan melakukan perilaku ahumanis guna kepentingan
186
M. B. Leckrone, Teori Sastra dan Julia Kristeva(Denpasar: Bali Media
Adikharsa, 2005), 76.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
humanis karena hal tersebut tidak mencerminkan martabat
kemanusiaan. Iaharus mampu bertindak sesuai dengan tempatnya.
Adapun sisi ahumanis yang ditampilkan pengarang dalam
manuskrip ini menunjukkan bagaimana protes humanisme
ditujukan kepada pemimpin masyarakat. Hal ini mengindikasikan
bahwa pada abad ke 18 dan19 Masehi telah lahir paham
humanisme Jawa sebagai dampak dari kolonialisme bangsa Barat.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview A
Comparative Study on Shi‘îte
Referensi
Barton, Greg. Liberalisme Dasar-Dasar Pemikiran Abdurrahman
Wahid. Yogyakarta: LkiS, 1997.
Endraswara, S. Memayu Hayuning Bawana. Jakarta: Narasi, 2013.
Herusatoto, B. Simbolisme Jawa. Yogyakarta: Ombak, 2008.
Kusumarini,Yusita. Teori Semiotik. Surabaya: Universitas Kristen
Petra, 2006.
Leckrone, M. B. Teori Sastra dan Julia Kristeva. Denpasar: Bali
Media Adikharsa, 2005.
Narwoko, D., & Suyanto, B. Sosiologi Teks Pengantar Terapan.
Jakarta: Prenada, 2014.
Nasution. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi
Aksara, 2003.
Piliang, Yasraf Amir.Hipersemiotika Tafsir Cultural Studie Atas
Matinya Makna.Yogyakarta: Jalasutra, 2003.
Purwanto, B. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris. Yogyakarta:
Ombak, 2006.
Purwasito, A. Imageri India. Surakarta: UNS Press, 2017.
Ratna, N. K. Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Ratna, N. K. Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Gusti Garnis Sasmita DkkLuthfi Rahman
Ray, S. Gayatri Cakravorty Spivak-Sang Liyan. Denpasar: Bali
Media Adikharsa, 2009.
Sasmita, G. G. Serat Jangka Jaybaya: Relasi Sastra, Sejarah dan
Nasionalisme. Historia,Vol. 6,No. 2, 2018.
Schulte, H. Persepektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
Setiadi, E. M., & Kolip, U. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta
dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta:
Kencana Prenada Group, 2010.
Soewarno, H. Ramalan Joyoboyo versi Sabdopalon. Kediri, 2004.
Spivak, G. C. Acritique of Postkolonial Reason Toward a History
of the Vanishing Present. London: Harvard University Press, 1999.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta, 2011.
Suyami. Kajian Budi Pekerti dalam Serat Jayabaya. Yogyakarta:
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2015.
Yasmiran, T. (2018, Februari 17). Kepengarangan Serat Jangka
Jayabaya. (G. G. Sasmita, Interviewer)
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
EKSISTENSI WAROK DAN GEMBLAK DI TENGAH
MASYARAKAT MUSLIM PONOROGO TAHUN 1960-1980
Nia Ulfia Krismawati
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Niaulfia5544@gmail.com
Warto
Universitas Sebelas Maret Surakarta
warto_file@yahoo.com
Nunuk Suryani
Universitas Sebelas Maret Surakarta
nunuksuryani@staff.uns.ac.id
Abstract
Warok is a central figure within the life of Ponorogo Society. Their
existence, authority, and highly social status create and represent social
capital on perpetuating ideology of kanuragan. Waroks believe that
woman is source of weakness in term of mysticism that may impose them
to resist and avoid lust of woman. Some of waroks selected figures of
gemblak as diversion of lust as well as an assistant in various activities.
The menggemblak tradition has not been considered in accordance with
religious value because it leads to deviant practices. This research is
aimed at analyzing the existence of warok and gemblak in social structure
Religió: Jurnal Studi Agama-agamaMutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Volume 78, Nomor 21, Desember20178| ISSN: (p) 2088-6330; (e) 2503-3778p-ISSN:
2088-7523; e-ISSN: 2502-6321| 2151-23497-11920
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
of Ponorogo society and how the former attempts to perpetuate gemblak
tradition among Muslim society. This research found that strategic
position, social status, and cultural power are politically represented to be
social capital for influencing social structure and socializing practices of
ablution as kanuragan ideology. Meanwhile, Muslim society have
attempted to transform gemblak tradition through cultural modification
into appropriate ritual based on religious values.
[Warok merupakan figur sentral dalam kehidupan masyarakat Ponorogo.
Eksistensi, otoritas, dan status sosial mereka yang tinggi mampu
mewujudkan kapital sosial dalam upaya melestarikan ideologi duni
kanuragan. Terkait dengan mistisisme dalam dunia kanuragan, para
warok memiliki kepercayaan bahwa perempuan adalah sumber
kelemahan: hal yang membuat mereka menghindari perempuan sebagai
bagian dari kesenangan. Sebagian dari mereka memilih figur gemblak
sebagai sumber kesenangan sekaligus sebagai asisten dalam pelaksanaan
ritual. Tradisi menggemblak semacam ini dianggap menyimpang dari
kacamata agama (Islam), karena dapat melahirkan praktik-praktik yang
tidak normal. Penelitian ini bermaksud menganalisis keberadaan warok
dan gemblak dalam struktur masyarakat Ponorogo dan bagaimana warok
berupaya melestarikan tradisi gemblak di tengah masyarakat Muslim.
Penelitian ini menemukan bahwa posisi strategis, status sosial, dan
kekuasaan kultural secara politis direpresentasikan sebagai modal sosial
untuk mempengaruhi struktur sosial dan merawat praktik-praktik
menyimpang sebagai bagian ideologi ilmu kanuragan. Di samping itu,
masyarakat Muslim Ponorogo senantiasa berupaya untuk mengubah
tradisi gemblak melalui cara-cara kultural agar bertransformasi menjadi
ritual masyarakat yang berbasis nilai-nilai agama.]
Keywords: warok, gemblak, social structure, religious acculturation,
Islam.
Abstract: Warok is a central figure in the life of Ponorogo Society. The
existence, authority, and high social status became a social capital in the
perpetuating of an ideology of kanuragan. The groups of Warok has believed
that a woman is a source of weakness for mysticists that forces them to resist
the lust and avoid a woman. Some of Warok presented a figure of gemblak as
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
diversion of lust as well as an assistant in the various activities. The
“menggemblak” behavior was considered not in accordance with religious
values and norms because it leads to deviant practices. This study is aimed to
analyze the existence of warok and gemblak in the social structure of
Ponorogo society and how warok attempted to perpetuate gemblak tradition
among the Muslim society as majority. The result showed that the strategic
position, social status, and power to influence in the social structure became
the social capital to socialize the practice of ablution as kanuragan ideology
and it is normal. Meanwhile, the Islamic efforts in shifting the gemblak
tradition were carried out through modification of Reog which is considered
as an appropriate means of conveying religious values.
Keyword:the existence of warok, gemblak, the social structure, religious
acculturation, Islam
Pendahuluan
Ponorogo merupakan daerah dengan dominasi budaya yang kuat.
Terbentuknya sebuah budaya tidak terlepas dari proses atau
interaksi sosial yang merupakan syarat umum terjadinya aktivitas
kemasyarakatan. Interaksi sosial atau hubungan yang dinamis antar
individu maupun kelompok dapat terjalin jika masyarakat bersifat
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
terbuka terhadap sesuatu yang baru.187Melalui interaksi antar
individu tersebut terciptalah sebuah identitas dan budaya khas pada
suatu daerah. Sejak awal terbentuknya Ponorogo, masyarakat telah
menetapkan warok sebagai sebuah simbol identitas. Sifat yang
dimiliki seperti kaya ilmu dan sakti, berjiwa penolong, mengayomi
keluarga dan masyarakat, bersikap adil dan jujur, menjadikan
warok sebagai sosok ideal yang diinginkan. Warok merupakan
seorang tokoh yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu kanuragan
(kekebalan tubuh) dan mempunyai jiwa spiritual sehingga
menempatkannya pada posisi tinggi dalam tatanan masyarakat
Ponorogo. Dalam kesenian reog sosok ini digambarkan sebagai
pasukan yang bersandar pada kebenaran dalam pertarungan antara
yang baik dan buruk.188
Warok merupakan sosok sentral yang berpengaruh besar baik dalam
masyarakat kalangan bawah maupun elit politik. Pada masa
Bathara Katong, warok berperan sebagai seorang demang atau
pemimpin desa yang memiliki pengaruh dalam segi politik. Posisi
sebagai pemimpin dan penanggung jawab dalam kesenian reog,
serta adanya keputusan terkait penambahan komponen tari warok
dalam kesenian tersebut, menempatkannya menjadi seorang tokoh
budaya yang semakin memperkuat posisinya dalam masyarakat.
Pada perkembangannya, warok menjadi seorang elit strategis yang
mempunyai pengaruh kuat sehingga diperhitungkan oleh
elitpenguasa.189Hal tersebut didukung dengan realitas bahwa warok
merupakan elit lokal yang sebagian besar menjadi anggota
eksekutif dan legislatif daerah. Jika dilihat dari segi status atau
kehormatan, maka warok berada pada kelas atas dalam lapisan
sosial masyarakat Ponorogo.
187
Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grasindo,
2002). 78.
188
L.S. Kencanasari, “Warokdalam Sejarah Kesenian Reog Ponorogo Perspesktif
Eksistensialisme.”Jurnal Filsafat, Vol. 19, No. 2, Agustus 2009, 182.
189
Khorurrosyidin,“Dinamika Peran Warok dalam Politik di Ponorogo”,Jurnal
Humanity, Vol. 9, No. 2, Maret 2014,26.
[http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2389].
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
Sejarah kemunculan warok diperkirakan berawal pada masa
kejayaan Kerajaan Wengker. Kata warok, pada awalnya merupakan
gelar yang hanya dimiliki oleh Prabu Jaka Bagus (Sri Gasakan)
yakni raja muda dari Kerajaan Wengker sekitar tahun 941M.
Keinginan warga kerajaan untuk menjadi sakti layaknya raja,
menjadikan gelar warok sebagai gelar kehormatan bagi seorang
yang mampu menguasai ilmu kanuragan dan berhati suci.
Kelompok warok sangat erat kaitannya dengan hal yang berbau
mistik dan memiliki linuwih dalam bidang supranatural. Menurut
cerita rakyat, kelompok ini merupakan pahlawan lokal dalam
membela bangsa dan negara pada masa pra Islam hingga masa
penjajahan.190Istilah warok pada awalnya juga ditujukan kepada
seorang wiratama pemeluk setia agama Budha Tantrayana yang
tangguh dalam peperangan, dan selalu berbuat kebaikan.191Hal ini
menunjukkan bahwa eksistensi warok sudah ada sejak masa Hindu
Budha, Islam dan sampai sekarang.
Pada abad ke-15, Bathoro Katong berhasil mengambil alih daerah
bekas Kerajaan Wengker untuk dijadikan kota baru yang dikenal
sebagai Ponorogo atas perintah Raden Patah, Raja Demak.192
Perhitungan tahun berdirinya Ponorogo didasarkan pada prasasti
candrasengkala berangka tahun 1418 Saka.193 Penamaan Ponorogo
agaknya ditujukan untuk menggambarkan sosok ideal masyarakat
yang diinginkan oleh penguasa. Ponorogo berasal dari kata
pramana raga yang kemudian dikenal sebagai panaraga yakni
“Pana” yang berarti sadar atau mengerti dan “Raga” yang berarti
badan. Maka dapat disimpulkan bahwa panaraga mengandung
maksud seseorang yang diharuskan mampu menempatkan dirinya
190
AlipSugianto, Bahasa dan Budaya Etnik Jawa Panaragan (Surakarta: CV
Kekata Grup, 2017), 43.
191
Moelyadi, Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reyog Ponorogo
(Ponorogo: Liguin Veteran RI Daerah Kabupaten Tingat II, 1986), 79-80.
192
Soemarto,Melihat Ponorogo Lebih Dekat (Ponorogo: Apix Offset, 2011), 15.
193
A.C. Rofiq, “Dakwah Kultural Bathoro Katong di Ponorogo”Jurnal Islamuna,
Vol.4 No.2, (Desember 2017), 308.
[http://dx.doi.org/10.19105/islamuna.v4i2.1593].
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
dihadapan orang lain.194 Pada masa mendatang diharapkan
masyarakat mempunyai jiwa yang bersifat bersih, suci, dan mampu
membaca keadaan serta memposisikan dirinya pada berbagai
kondisi.
Keberhasilan Bathoro Katong dalam mendirikan kota baru dengan
warna keislaman kemudian memberikan pengaruh pada budaya
masyarakat di masa selanjutnya.195 Agama Islam kemudian menjadi
agama mayoritas dan tanpa terkecuali warok dan pendampingnya.
Hal ini juga berdampak pada pemaknaan kata warok yang
mengalami perubahan dari masa Hindu pada masa Islam. Secara
terminologi, warok pada masa pra-Islam berasal dari kata “wara”
yang berarti pria agung. Dalam literatur sufi (mistik islam) dikenal
istilah wara’ yang berarti menjauhkan diri dari segala sesuatu yang
mengandung subhat dan menjerumuskan masyarakat pada
keharaman. Penamaan warok ditujukan kepada seorang yang
berjiwa bersih dan mampu menjadi panutan dalam menjalani
kehidupan. Pemaknaan warok, kemudian disesuaikan dengan
ajaran Islam yakni taubah, wara, zuhud, tawakal, sabar, dan
mempunyai sifat yang rela atau suka menolong.196 Pemaknaan
kembali agaknya sengaja dilakukan untuk membangun kembali
citra warok menjadi tokoh Islam yang berperang di jalan Allah.
Terdapat tiga keutamaan yang harus dimiliki oleh warok yakni,
sucining swara (kesucian suara), sucining roso (kesucian rasa), dan
sucining tenogo (kesucian tenaga). Keutamaan dapat dimiliki
dengan jalan mempercayai dan memuji dzat yang bersuara dengan
mantra dan doa, menyembah kepada yang menciptakan gerak dan
melakukan salat serta semedi.197 Agama yang dianut dan budaya
Jawa yang masih dipegang teguh pada akhirnya berdampak pada
194
Soemarto,Melihat Ponorogo Lebih Dekat (Ponorogo: Apix Offset, 2011), 15.
195
Ibid., 15.
196
AmalTaufiq, “Perilaku Ritual Warok Ponorogo dalam Prespektif Teori
Tindakan Max Weber”,Jurnal Sosiologi Islam, Vol.3, No.2,Oktober 2013,112-
122.
197
Taufiq, “Perilaku Ritual Warok”, 118.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
perilaku ritual yang dilakukan oleh kelompok warok. Terlihat
bahwa warok telah percaya kepada Allah dan melakukan
perintahnya dengan melaksanakan salat serta melakukan semedi
sebagai bentuk lelakon spiritual Jawa. Berdasarkan penjelasan
tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah runtuhnya Kerajaan
Wengker, mayoritas warok beragama Islam namun masih
memegang lelakon dari ajaran Hindu seperti bertapa atau disebut
sebagai kelompok abangan. Selain itu, serangkaian puasa yang
juga diutamakan dalam Islam turut dilakukan sebagai bentuk upaya
dalam menahan nafsu. Namun puasa yang dilakukan oleh kalangan
warok lebih mengarah pada lelakon ritual kejawen yakni, pertama,
puasa ngrowot yakni berpantangan dengan nasi: kedua, puasa
ngidang yakni makan sayuran dengan langsung menggunakan
mulut: ketiga, puasa mendem yakni bertapa didalam tanah sehingga
tidak terkena sinar matahari: dan keempat, puasa mutih yang hanya
memakan nasi putih.198
Dalam menjalani kehidupannya, seorang warok diharuskan
menjaga sahwat atau nafsu kepada wanita. Dalam kepercayaan
warok terdapat anggapan bahwa wanita adalah sirikan yang harus
dijauhi karena dipercaya dapat melemahkan kekuatan batin dan
daya mistik yang telah dimiliki. Didukung pernyataan dari
Poerwowijoyo yang menjelaskan bahwa berhubungan dengan
wanita mengakibatkan hilangya kekuatan yang dimiliki sehingga
membuat para warok memutuskan untuk menunda pernikahan atau
bahkan tidak menikah. Dalam perkembangannya, beberapa dari
mereka menghadirkan sosok laki-laki muda tampan yang dikenal
sebagai gemblak. Menurut Moelyadi kebiasaan menggemblak
sudah ada sejak masa Kerajaan Wengker dan dilakukan oleh Raja
muda Wengker sebagai pengarih-arih.199Praktek menggemblak
yang dianggap sebagai ajaran ideologi kanuragan dalam kalangan
warok hampir dijalani oleh semua kelompok warok. Meskipun
pada akhir tahun 1980an ideologi ini dianggap tidak sesuai dengan
198
Ibid.,119.
199
Poerwowijoyo,Reog Ponorogo(Ponorogo: Depdikbud Kanwil, 1985), 35.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
nilai dan norma agama sehingga dihilangkan dari kehidupan
masyarakat.
Pada perkembangannya, Warok dan gemblak dikenal sebagai satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa
mayoritas dari kelompok ini mempunyai gemblak sebagai
klangenan yang telah dikenal sebagai ideologi priyayi atau kaum
elit lainnya. Klangenan, dari kata langen (senang), yang merujuk
seks sebagai obyek kesenangan birahi.200 Kepemilikan atas gemblak
agaknya hanya menjadi citra birahi yang menyenangkan dan
menjadi sasaran utama. Hal inilah sebabnya dominasi kekuasaan
sering menyelimuti dunia kesenangan yang salah satunya adalah
pemenuhan birahi. Dalam praktek menggemblak, seorang anak
laki-laki muda, bertubuh bagus, dan berkulit bersih telah
mengalahkan pesona wanita dan menggantikannya sebagai sumber
birahi bagi para pelakunya. Agaknya kondisi ini bisa jadi memang
dikarenakan kuatnya kebiasaan yang umum dilakukan oleh
kelompok warok.
Meskipun dunia warok tidak dipisahkan dengan hadirnya sosok
gemblak, namun tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa dari
mereka memilih menjaga kesucian dengan hidup tanpa
pendamping maupun gemblak. Kelompok ini menganggap bahwa
beribadah dan menjaga kesucian diri adalah bentuk upaya dalam
mencapai kesempurnaan hidup. Beberapa penelitian terdahulu
menyebutkan bahwa hubungan yang terjadi antara warok dan
gemblak merupakan praktek homoseksual yakni penyuka sesama
jenis. Agaknya pernyataan ini harus ditegaskan kembali karena
mayoritas warok pada abad ke-20 mempunyai istri dan anak. Hal
ini menunjukkan bahwa hubungan antara warok dan gemblak
mengarah pada praktek homoseksual tingkat 1.201 Artinya label
homoseksual aktif agaknya kurang tepat jika digunakan dalam
200
Suwardi Endraswara, Rasa Sejati, Misteri Seks Dunia Kejawen. (Yogyakarta:
Narasi, 2006), 22.
201
Heteroseksual predominan (lebih menonjol) homoseksual hanya kadang-
kadang muncul hanya pada suatu waktu).
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
melihat hubungan yang terjadi diantara keduanya. Menurut Weber,
perilaku dalam menggemblak tergolong pada tindakan tradisional
yang hanya didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat tanpa mempunyai dasar yang kuat.202 Berdasarkan
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat secara luas, prakek
menggemblak menjadi hal yang lumrah dan dapat diterima.
Kehormatan, wibawa, dan posisi yang tinggi dalam mayarakat
berhasil menjadi modal sosial dalam melanggengkan kebiasaan
tersebut.
Pada abad ke-20 mayoritas masyarakat Ponorogo telah beragama
Islam dan tidak terkecuali dengan para waroknya. Kebiasaan dalam
menggemblak yang mengarah pada aspek seksualitasdalam
realitanya mendapatkan tentangan dari pemuka agama dikarenakan
tidak sesuai dengan norma, nilai, dan ajaran Islam. Eksistensi
warok yang telah berhasil melanggengkan kebiasaan menggemblak
sebagai salah satu bentuk ideologi kanuragan menjadi suatu hal
yang sulit untuk dihilangkan. Namun berbagai faktor seperti
kesejahteraan ekonomi, meningkatnya kualitas pendidikan, dan
pemahaman nilai-nilai agama pada akhirnya berhasil menghapus
kebiasaan menggemblak dalam kehidupan masyarakat Ponorogo
pada akhir tahun 1980an. Hal ini juga didukung dengan antusias
pemerintah dan masyarakat dengan menghadirkan penari jatil
perempuan dalam kesenian reog yang semakin menggeser ruang
gemblak untuk muncul dalam ranah publik. Pada akhirnya, banyak
dari kalangan warok memutuskan untuk menjalani kehidupan
layaknya orang biasa dan kembali pada keluarganya.
Penelitian ini menggunakan metode historis dengan mengumpulkan
data sejarah yang bersifat primer dan sekunder. Data primer
didapatkan melalui wawancara pada pelaku dan saksi sejarah yakni
warok, mantan gemblak, keluarga warok dan gemblak. Sementara
itu, sumber sekunder didapatkan melalui wawancara pada informan
202
Bradbury,Pengantar Teori-Teori Sosial (Edisi Revisi) (Jakarta: Obor, 2016),
118.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
yang hidup pada saat peristiwa terjadi dan studi pustaka terhadap
penelitian terdahulu mengenai budaya ponorogo, eksistensi warok
dan gemblak, dan agama mayoritas masyarakat. Kritik sumber
dilakukan untuk menguji kebenaran informasi melalui penyelidikan
latar belakang informan dan melakukan perbandingan serta
pencocokan antara sumber satu dengan lainnya. Penelitian ini
berusaha menganalisis eksistensi warok dan gemblak dalam
struktur sosial masyarakat Ponorogo, modal sosial yang berhasil
digunakan dalam melanggengkan ideologi kanuragan di tengah
masyarakat muslim, dan pengaruhnya bagi masyarakat luas yang
membuktikan tingginya eksistensi warok sebagai elit strategis di
abad ke-20.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
Perilaku Warok Dalam Prespektif Teori Tindakan Max Weber
Terdapat empat pola tindakan sosial menurut Weber dalam Tom,
antara lain: pertama, rasional instrumen, merupakan tindakan yang
terarah pada tujuan yang akan dicapai. Perilaku ini dilakukan
dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang ditempuh
dengan tujuan yang akan dicapai. Kedua, tindakan rasional
berorientasi nilai, merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan
nilai dan manfaat yang akan diperoleh, namun tujuan yang hendak
dicapai tidak terlalu diperhitungkan oleh pelaku. Anggapan yang
ada yaitu kesesuaian tindakan pada kriteria yang baik dan benar
menurut ukuran dan penilaian masyarakat. Ketiga, tindakan
tradisional, merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan ini dilakukan
tanpa memperhitungkan alasan dan membuat perencanaan terlebih
dahulu terkait cara dan tujuan yang akan dicapai. Keempat,
tindakan afektif, merupakan tindakan yang sebagian besar dikuasai
oleh perasaan tanpa mempertimbangkan akal budi atau spontanitas
manusia.
Jika melihat perilaku warok berdasarkan teori tindakan menurut
Max Weber, terdapat beberapa jenis yang dapat dijelaskan.
Pertama, perilaku ritual warok dalam mendapatkan kesaktian dan
kesempurnaan hidup tergolong pada pola tindakan rasional
berorientasi nilai. Hal ini dikarenakan semua ritual dan lelakon,
dilakukan atas dasar perhitungan tujuan dan manfaatnya. Sebagai
contoh, warok melakukan ritual puasa ngebleng dengan tujuan
menghindarkan diri dari peliknya dunia dan selalu melakukan
intropeksi diri. Selain itu, warok juga melakukan ritual dengan
bertapa yakni tapa ngeli dengan cara menghanyutkan diri di sungai
sampai hitungan beberapa malam dan tapa kungkum dengan cara
menenggelamkan diri atau beredam di dalam air selama sehari
semalam. Dalam rangka mensucikan diri, kelompok warok sepakat
untuk melakukan tiga patrap yakni pertama, patrap lungguh, yang
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
merupakan aktivitas duduk, disebut shalat daim, bertujuan untuk
mensucikan wujud; kedua, patrap sujud (semedi) yang dilakukan
dengan tujuan mensucikan rasa dan perasaan; ketiga, patrap
ngadeg atau disebut sebagai shalat hajat yang bertujuan untuk
mensucikan daya kekuatan.203 Dalam konteks ini perilaku ritual
warok yang dengan sadar dilakukan tanpa adanya niatan untuk
menyakiti orang lain dan tidak bertentangan dengan norma
masyarakat, disepakati sebagai lelakon yang disarankan.
Perilaku ritual warok, didasarkan pada segi lahiriah yang dilihat
sebagai cerminan dari realitas esensial yang halus dan batiniah.
Hubungan keduanya baik secara hirarkis maupun terkoordinasi
harus beriringan dan menjaga keharmonisan. Sebuah harmoni dapat
dicapai bila manusia mampu membersihkan batin, menjaga diri
dari dunia yang bersifat kasar, menjalani kehidupan moral yang
sesuai dengan tatanan masyarakat, dan melatih rasa sehingga
bermanfaat bagi diri sendiri dan tidak merugikan orang lain.
Sementara itu, upaya warok dalam mencapai ketentraman batin dan
pengetahuan sejati dilakukan dengan cara menjauhi sesuatu yang
bersifat materiil dan kasar serta memperbesar kemampuan-
kemampuan halusnya sehingga dapat mencapai sebuah penerangan
maupun eksistensi moral. Hal ini membutkikan bahwa pemikiran
warok masih sejalan dengan gaya pemikiran dan kebudayaan Jawa
pada umumnya.204
Selain melakukan ritual dan tirakat, kelompok warok diharuskan
memiliki sembilan keutamaan yang terdiri dari, berhati bersih dan
suci, tidak melakukan kejahatan, jujur, tulus, dan berhati-hati dalam
melakukan segala aktifitas, mengurangi keinginan nafsu, selalu
mengingat hakikat dari sebuah kehidupan dengan mencari
kesempurnaan batin, dan pandai beradaptasi, tidak membeda-
bedakan, berbelas kasih kepada sesama, jujur lahir batin, dan hidup
203
Taufiq, “Perilaku Ritual Warok Ponorogo”, 118.
204
NeilMulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa, Kelangsungan
dan Perubahan Kulturil (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 19.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
patuh terhadap Tuhan. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan
dalam menobatkan seseorang menjadi warok sejati. Namun dalam
perkembangannya, banyak kalangan masyarakat yang menyebut
dirinya sebagai warok atas dasar kekayaan, kekuatan, dan ilmu
kesaktian yang dimiliki. Maka dari itu, tidak jarang dari kelompok
ini melakukan molimo yang bahkan sangat dilarang dalam prinsip
menjalani kehidupan sebagai warok. Sementara itu, perilaku
menggemblak yang dikatakan sebagai bentuk ideologi kanuragan,
tergolong pada tindakan tradisional yang dilakukan atas dasar
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Teori Akulturasi Budaya
Akulturasi budaya akan terjadi bila terdapat dua budaya yang
berbeda kemudian berpadu sehingga tercipta budaya baru tanpa
menghilangkan kedua unsur budaya yang ada.205Menurut Robert
Redfield, Ralph Linton, dan Melville, akulturasi merupakan sebuah
fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang
berbeda budaya saling berhubungan dan berkesinambungan
sehingga berdampak pada perubahan budaya asli yang telah lama
dianut oleh suatu kelompok masyarakat.206 Sementara itu menurut
Kim, akulturasi biasanya dilakukan oleh imigran atau pendatang
yang membawa budaya, kepercayaan dan agama, untuk
menyesuaikan diri atau bahkan mendominasi budaya lama dengan
budaya baru dan berhasil dikomunikasikan kepada masyarakat
sehingga menjadi perpaduan yang saling melengkapi.
Kepercayaan dan agama adalah salah satu contoh hasil
pengintegrasian dan pengabsorsian dari bentuk-bentuk sistem yang
telah lama berkembang. Akulturasi dapat terjadi jika terdapat
205
Kodiran,“Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan”,Jurnal
Humaniora, No.8, Agustus 1998, 87.
206
H.K.Romli, “Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar
Etnik”,Jurnal Ijtimaiyya, Vol. 8, No. 1, Februari 2015, 1.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
interaksi atau komunikasi intensif yang dilakukan masyarakat
sehingga memunculkan budaya baru yang disetujui secara
kolektif.207 Proses interaksi tidak berjalan dalam waktu singkat
melainkan membutuhkan beberapa proses panjang sampai pada
akhirnya dapat diterima dan dijadikan pedoman dalam menjalani
hidup. Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Ponorogo
sejak awal abad ke-15 bersifat transenden, sepanjang sejarahnya,
telah membantu para penganutnya dalam memahami realitas yang
pada gilirannya mewujudkan pola pandangan hidup baru.208 Ketika
masyarakat merasa nyaman dan sejalan dengan ajaran yang
diberikan dan dapat diterima secara rasional terutama dalam
pranata-pranata sosial, maka agama ini dikatakan berhasil dalam
melakukan interaksi pada masyarakat. Maka terjadilah interaksi
antara budaya lama dengan budaya yang dibawa Islam yang
tergambar dalam perilaku masyarakat Ponorogo.
Budaya dan Agama Masyarakat Ponorogo
Budaya pada prinsipnya mencakup dua dimensi yakni fisik dan non
fisik seperti agama, kesenian, kepercayaan dan lain sebagainya.
Adanya dimensi budaya tersebut turut mempengaruhi pola hidup
suatu kelompok masyarakat. Budaya digambarkan sebagai sebuah
tatanan yang sengaja disosialisasikan secara turun temurun yang
mengandung norma dan nilai yang telah disepakati oleh
masyarakat. Budaya sebagai bentuk perilaku suatu kelompok
masyarakat yang terlokalisasi atau disebut sebagai budaya lokal
memang tidak dapat dibatasi oleh dimensi budaya saja melainkan
terbatas pada garis wilayah yang didiami oleh suatu kelompok.209
Sebagai contoh budaya yang berlaku dalam masyarakat Ponorogo
hanya dianut dan hanya ada di wilayah tersebut, meskipun tidak
207
Ibid.
208
HamzahJunaid, “Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal”Jurnal
Sulasena, Vol. 8, No. 1, 2013, 1. [DOI: https://doi.org?10.24252?.v8i1.1271].
209
Kodiran,“Akulturasi”, 2.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
menutup kemungkinan terdapat kesamaan dengan daerah yang
berdekatan letaknya. Kesamaan budaya pastinya dilatarbelakangi
oleh kesamaan historis maupun adanya interaksi yang dilakukan di
masa lampau. Budaya dalam masyarakat Ponorogo merupakan
hasil akulturasi antara budaya yang dipengaruhi oleh kepercayaan
animisme dan dinamis, agama Hindu, dan Islam.
Menurut sejarah, agama yang dianut oleh Kerajaan Wengker adalah
agama Hindu sehingga mayoritas masyarakat meyakininya sebagai
pegangan hidup. Bukti kentalnya pengaruh Agama Hindu dalam
kehidupan masyarakat terlihat pada bentuk budaya yang
didominasi oleh pelaksanaan ritual dan kegiatan yang berbau
mistik. Hindu mengajarkan tentang pemberian sesaji kepada
danyang atau penguasa yang dianggap mempunyai kekuatan dari
sebuah tempat yang dikeramatkan.210 Pemberian sesaji dipercaya
dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan mahluk ghaib
yang mendiami suatu tempat. Gagasan mistik memang
mendapatkan sambutan hangat di daerah Jawa yang salah satunya
adalah wilayah Ponorogo yang merupakan bekas Kerajaan
Wengker. Besarnya pengaruh Hindu masih terlihat dalam bentuk
kegiatan masyarakat seperti ritual, slametan, acara pernikahan, dan
lain sebagainya. Hal ini dikarenakan sejak sebelum Agama Islam
datang, budaya Hindu sudah mendarah daging dalam diri
masyarakat.211
Pada masa Bathoro Katong, wilayah Kerajaan Wengker kemudian
diambil alih dan diganti dengan kota baru yakni Ponorogo. Adapun
misi utamanya adalah menyebarkan agama Islam sebagai agama
baru. Keberhasilan Bathoro Katong dalam menyebarkan agama
Islam terlihat pada mayoritas agama dari masyarakat Ponorogo.
Agama baru turut memberikan pengaruh pada kebudayaan
210
N.U.Krismawati, “Larung Risalah Do’a; Upacara Ritual Syukur sebagai
Warisan Budaya Hindu Jawa Prespektif Sejarah local”, (prosiding seminar
nasional “Sejarah Lokal: Tantangan dan Masa Depan, 26 April 2017, Universitas
Negeri Malang), 336.
211
Koentjaraningrat,Kebudayaan Jawa (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 53.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
masyarakat dan tidak jarang dari mereka melakukan akulturasi
budaya dengan mengkombinasikan antara budaya nenek moyang,
Hindu, dan Islam yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini
kemungkinan memberikan pengaruh pada lelakonwarok pada masa
Hindu dan Islam. Terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan
warok dalam mendapatkan kesaktian dan kesucian diri. Hal ini
terlihat pada perilaku religiusitas warok yakni ritual semedi atau
bertapa yang merupakan ajaran Hindu dan berpuasa serta membaca
wirid yang merupakan ajaran Islam. Beberapa hal yang tidak sesuai
kemudian ditinggalkan dan diselaraskan dengan ajaran dari agama
baru yang diyakini. Namun hal ini tidak mempengaruhi idelogi
warok dalam menjadikan gemblak sebagai klangenan atau pengalih
hawa nafsu kepada wanita. Meskipun pada akhir tahun 1980,
pemahaman masyarakat tentang Agama Islam berhasil menggeser
dan menghilangkan kebiasaan tersebut.
Warna ekspresi keberagamaan yang terjadi dalam masyarakat
Ponorogo mengindikasikan bahwa kuatnya tradisi dan budaya lokal
dalam mempengaruhi karakter asli agama formalnya dan begitu
juga sebaliknya.212 Proses dialektika antara agama dan budaya yang
dianggap sebagai proses eksternalisasi, objektivasi, maupun
internalisasi memberikan pengaruh pada pemahaman agama dan
perilaku sosial masyarakat. Hadirnya agama baru yang
menggantikan agama lama memunculkan sebuah perpaduan
budaya yang terwujud dalam perilaku mistik Islam Kejawen.
Adapun bentuk perpaduan antar budaya yang saat ini dilakukan
oleh masyarakat Ponorogo, yakni; mempercayai hal gaib yang ada
disekitar dan benda-benda yang dianggap keramat sebagai bentuk
budaya Animisme dan Dinamisme yang tergambar pada
pelaksanaan upacara larung sesaji; penggunaan sesajen pada setiap
ibadah atau ritual upacara doa yang dilakukan sebagai sarana
komunikasi pada roh gaib yang merupakan ajaran Hindu-Budha;
beribadah dalam bentuk salat, membaca doa dan wirid, serta puasa
212
Roibin,“Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik?”,Jurnal
Hukum dan Syariah, Vol. 1, No. 1, 2010, 2.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
dengan tujuan menahan hawa nafsu pada suatu hal yang bersifat
buruk merupakan ajaran Islam. Sementara itu, perilaku atau lelakon
warok dalam mendapatkan kesaktian dan kesempurnaan ilmu turut
menggambarkan adanya proses dialektika antara agama dan budaya
yang eksis dalam masyarakat.
Eksistensi Warok dan Gemblak dalam Struktur Sosial
Masyarakat Ponorogo
Warok merupakan tokoh sentral yang mempunyai posisi strategis
dalam kehidupan masyarakat Ponorogo. Posisi sebagai elit strategis
dan tokoh budaya memberikan kedudukan bagi warok sehingga
berpengaruh besar yakni menjadi penggerak sosial dan jembatan
penghubung antara masyarakat dengan elit politik dan penguasa.
Menurut Harsono kedudukan sosial warok dalam pandangan
masyarakat setingkat dengan para kiai dan pejabat pemerintahan.213
Kelompok ini mendapatkan posisi dalam masyarakat dikarenakan
kemampuan supranatural dan olah kanuragan yang dimiliki. Posisi
warok sebagai pemimpin paguyuban kesenian reog yang dielu-
elukan pada jamannya turut menjadi pertimbangan. Bahkan sampai
sekarang kesenian reog masih menjadi kesenian kebanggaan yang
selalu dipergunakan dalam acara-acara besar yakni ulang tahun
Ponorogo dan perayaan 1 Suro yang dianggap sebagai bulan sakral
oleh masyarakat Ponorogo.
Kesenian reog adalah salah satu sarana yang dimanfaatkan oleh
kelompok warok dalam melanggengkan praktek hegemoni dalam
bentuk memelihara gemblak. Kesenian ini merupakan kesenian
tradisional yang berfungsi sebagai kesenian rakyat dan alat
penggerak masa.214 Kesenian memang menjadi bagian dari
kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai alat pemersatu dan
213
J Harsono dan SSlamet, Sosiologi Masyarakat Ponorogo (Ponorogo: UMPO
press, 2016), 111.
214
HerryLisbijanto, Reog Ponorogo (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
penghibur. Kedudukan warok sebagai tokoh budaya dan pemimpin
paguyuban menempatkannya pada posisi yang strategis dalam
mensosialisasikan praktek menggemblak sebagai bentuk penentuan
status sosial. Semakin banyak gemblak yang dimiliki maka akan
semakin tinggi status sosial dan kedudukan yang akan disandang.
Hal ini kemudian menjadi simbol kekuatan, kewibawaan yang
menjadi modal sosial bagi kelompok warok dalam melanggengkan
kebiasaan yang disebut sebagai tradisi gemblak oleh para
penganutnya. Tradisi ini tidak bertahan secara otomatis, melainkan
melalui proses panjang yakni transmisi dan hasil mufakat dan kerja
keras dari agen-agen sosial dalam hal ini adalah warok.215
Terdapat pergerseran fungsi kesenian reog dalam kehidupan
masyarakat Ponorogo. Pada jaman dulu, fungsi kesenian reog
adalah sebagai sarana persyaratan perkawinan dalam bahasa jawa
disebut sebagai bebana dan seserahan serta berfungsisebagai
pertunjukan yang tidak mempunyai unsur komersiil dan hanya
berdasarkan nilai seni semata. Pada masa kemerdekaan, fungsi
kesenian reog antara lain, sebagai alat penggerak masa yakni
penciptaan gerak tari yang bersifat dinamis dan atraktif sengaja
disesuaikan dengan tujuannya yakni penggerak masa. Ketertarikan
akan kesenian reog membuat masyarakat bergerak untuk menonton
dan bahkan menari bersama. Fungsi yang kedua adalahsebagai
pertunjukan rakyat. Kesenian ini sengaja digelar sebagai alat
penghibur yang biasanya diselengarakan pada acara hajadan yakni
acara pernikahan, khitanan, sepasaran bayi, dan peringatan ulang
tahun. Fungsi yang terakhir adalah fungsi perjuangan. Iringan
kesenian reog yang berbentuk barisan terselipkan sesuatu
didalamnya kesiap-kesiagaan dari barisan dalam menghadapi
bahaya.216 Perubahan fungsi reog menggambarkan bahwa kesenian
ini mampu menjaga eksistensinya dan terus menyesuaikan dengan
perkembangan zaman sehingga menjadi wadah yang tepat bagi
215
PeterBurke, Sejarah dan Teori Sosial, (Jakarta: Obor, 2015), 102.
216
Moelyadi,Ungkapan Sejarah,106-107.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
kalangan warok dalam melanggengkan ideologi kanuragan yang
dianut.
Kelompok warok menjalankan peran dan fungsi yang
penting yakni posisi tawar menawar dengan penguasa.217
Kemampuan warok yang merupakan elit lokal dalam
mempengaruhi masyarakat dikarenakan diakuinya kekuasaan
informal dan tingginya pengetahuan serta wawasan yang
dimiliki.218 Hal ini semakin mempertegas besarnya pengaruh dan
tingginya kedudukan warok dalam struktur sosial masyarakat
Ponorogo. Kehormatan, wibawa, dan kekuatan yang dimiliki
menjadi suatu hal yang diinginkan oleh beberapa kalangan
masyarakat khususnya kaum laki-laki. Bahkan sebagian
masyarakat percaya bahwa dengan melakukan ritual dan kebiasaan
warok maka mereka dapat menjadi seorang warok. Ideologi
kanuragan yang dipercaya dapat meningkatkan kesaktian dan
kewibawaan yakni dengan menghadirkan sosok gemblak. Tindakan
tersebutdijalani sebagai tradisi masyarakat pada kultur Ponorogo
yang tidak memandang status sosial dan sosial-religius.219
Menurut teori Marxis dan Post-Marxis pertanyaan terkait
ideologi menititikberatkan pada pertanyaan fundamental yaitu
mengapa orang menerima dan menginternalisasikan kondisi yang
disadari telah merugikan salah satu pihak. Penanaman ideologi
yang merupakan seperangkat kebiasaan atau ritual dan ide-ide yang
diunggulkan oleh kelas sosial tertentu dapat dikatakan berhasil
dalam kasus tradisi menggemblak.220 Citra warok yang dianggap
sebagai sesepuh terhormat, membuat masyarakat perlahan
217
Khoirurrosyidin,“Dinamika Peran Warok”, 26.
[http://ejournal.umm.ac.id.index.php/humanity/article/view/2389].
218
Ibid., 41.
219
S Yuwana, Homoseksual Di Kalangan Warok, Warokan, Sinoman, Gemblak Di
Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo (Jakarta: Universitas
Indonesia, 1994). 121.
220
DaniCavallaro, Teori Kritis dan Teori Budaya (Yogyakarta: Futuh Printika,
2004). 36.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
menerima gemblak sebagai bagian dari tatanan alamiah. Praktek
gemblak yang dikelompokkan ke dalam tipe normal, menjadi salah
satu alasan berkembang dan bertahannya kelompok tersebut. Tidak
adanya bentuk resistensi yang signifikan dari masyarakat telah
menjadikannya sebagai sebuah tradisi yang dilakukan secara turun
temurun. Terlebih lagi keberhasilan dari pembentukan mentalitas
sosial masyarakat, telah membawa sosok gemblak pada posisi
sentral yaitu sebagai simbol status sosial wong Ponorogo. Gemblak
dianggap sebagai bukti dari kemampuan dan kekayaan seseorang
sehingga menempatkannya pada kelas atas. Besarnya biaya yang
harus dikeluarkan untuk mengontrak gemblak, hanya dapat
dilakukan oleh kelompok elit masyarakat dijadikan patokan dalam
penentuan status sosial. Mengingat pada masa itu harga dari anak
sapi dan tanah (sewa kontrak) sangat tinggi.
Hubungan yang terjadi antara warok dengan anak laki-laki
yang telah dikontrak untuk dijadikan pendamping, dipandang
sebagai gejala yang bersifat normal oleh para pelakunya. Hal
tersebut berdasarkan pandangan Ruth Benedict atas konfigurasi
budaya yang mengacu pada tipe kepribadian normal. Masyarakat
Ponorogo yang berbuat sesuai dengan tipe dominan (praktek
menggemblak)disebut sebagai kepribadian yang lazim. Jika dilihat
dari segi pandangan emik, maka perilaku menyimpang warok
tergolong pada gejala umum. Hal tersebut dikarenakan perilaku
menggemblak dilakukan dengan sadar dan diterima oleh
masyarakat Ponorogo. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku
menggemblak merupakan gejala umum dikarenakan diterima dan
bahkan menjadi kebiasaan mayoritas. Terlebih lagi, menjadikan
gemblak sebagai simbol status sosial menandakan bahwa adanya
penerimaan masyarakat yang bersifat dominan.
Tradisi menggemblak merupakan bentuk kebiasaan yang
tergolong pada praktek hegemoni dari kelas atas. Dalam
kenyataannya, hegemoni berkembang pesat dengan meyakinkan
kelompok-kelompok sosial subordinat sehingga mau menerima
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
sistem kultural yang dihargai oleh kelompok atas. Citra warok yang
dianggap sebagai sesepuh terhormat, membuat masyarakat
perlahan menerima gemblak sebagai bagian dari tatanan alamiah.
Praktek menggemblak yang dianggap sebagai tipe normal ini
menjadi salah satu alasan berkembang dan bertahannya tradisi
tersebut. Menurut Durkheim, fakta sosial memiliki tiga sifat yaitu
(1) ekternal, fakta berada diluar pertimbangan manusia, (2) koersif
(memaksa), fakta yang memiliki kekuatan menekan dan memaksa
individu dalam menerima dan melaksanakannya, dan (3) menyebar
(general), fakta sosial merupakan milik bersama, bukan sifat
individu perseorang. Fakta sosial terkait praktek menggemblak
mendorong terciptanya mentalitas kolektif sehingga menjadi
collective memory masyarakat. Memori kolektif akan adanya
gemblak, dijadikan sebagai modal sosial dalam melanggengkan
praktek hegemoni kelompok tertentu. Dalam hal ini, kelompok
yang dimaksud adalah kelompok warok, warokan, dan masyarakat
yang menjadikan gemblak sebagai simbol status sosial.
Besarnya pengaruh warok dalam masyarakat berhasil
menjadi modal sosial yang mampu meyakinkan masyarakat luas.
Menurut Putnam, modal sosial merupakan perekat bagi individu
dalam bentuk norma dan kepercayaan sehingga menjadi
pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama yang saling
menguntungkan. Sebetulnya modal sosial seharusnya menekankan
pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan dalam
memperbaiki kualitas kehidupan yang dimiliki. Namun dalam
perilaku menggemblak, modal sosial justru dijadikan jembatan
untuk memperoleh tujuan yang menguntungkan kelompok tertentu
yaitu kelompok warok, warokan, dan penggemblak. Keberhasilan
dalam pelestarian tradisi menggemblak tidak dapat terlepas dari
eksistensi warok yang terbentuk dalam sebuah jaringan sosial.
Kehadiran Warok yang diterima oleh semua kalangan, telah
membawanya pada posisi strategis dan sentral dalam struktur sosial
masyarakat Ponorogo. Posisi sentral yang dimaksud adalah terkait
dengan kedudukan warok sebagai seorang terhormat dan kaya di
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
tengah masyarakat. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi tradisi
menggemblak tumbuh subur dan terjaga eksistensinya hingga
menjelang akhir tahun 1980an.
Eksistensi Tradisi Menggemblak di tengah Masyarakat Muslim
Ponorogo Tahun 1960-1980
Pada akhir abad ke-20, Islam berhasil menjadi agama mayoritas
masyarakat Ponorogo. Wilayah Ponorogo terbagi menjadi lima
bagian yakni Ponorogo Utara (berbatasan dengan Madiun),
Ponorogo Timur (berbatasan dengan Trenggalek), Ponorogo
Selatan (berbatasan dengan Pacitan), Ponorogo barat berbatasan
dengan Wonogiri yang merupakan bekas wilayah Kerajaan
Wengker, dan Ponorogo tengah yang merupakan pusat
pemerintahan sekaligus pusat penyebaran agama Islam yang
dipimpin oleh Bathoro Katong. Pemahaman Islam dari berbagai
wilayah mengalami perbedaan yang dipengaruhi oleh budaya yang
dianut masyarakat terdahulu. Pada hakikatnya, masyarakat
Ponorogo masih mengindahkan Islam Kejawen yakni dengan
memadukan ajaran Islam dengan budaya nenek moyang yang
terlihat pada pelaksanaan ritual upacara bersih desa, larung sesaji,
dan lain sebagainya yang dipadukan dengan bacaan doa yang
diajarkan oleh Islam. Hal ini dikarenakan proses masuknya Islam di
Ponorogo dilakukan melalui saluran budaya yang dianut oleh
masyarakat sehingga menelurkan perpaduan budaya. Kelompok
masyarakat tipe ini dapat dikatakan sebagai Islam abangan yang
masih mengindahkan budaya dalam berpikir dan berperilaku. Mbah
Tobroni menyatakan bahwa mayoritas kelompok warok adalah
seorang muslim namun masih mengindahkan tradisi Jawa dan
ideologi kanuragan dengan cara menghadirkan gemblak sebagai
pengalih nafsu sekaligus dijadikan sebagai daya tarik dalam
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
kesenian reog.221Dalam hal ini tradisi dan ideologi masih
mendominasi perilaku warok dalam keseharian.
Terjadinya persoalan interaksi antara Islam dan budaya lokal selalu
melibatkan pertarungan antara agama sebagai doktrin yang bersifat
absolut dengan nilai-nilai budaya yang bersifat empiris dan
disetujui oleh masyarakat luas.222 Dalam kasus praktek
menggemblak, beberapa daerah di Ponorogo mampu menjaga
eksistensinya ditengah masyarakat muslim dikarenakan besarnya
dominasi budaya dan tradisi dalam diri masyarakat dan minimnya
penerimaan dan pemahaman agama Islam. Dapat terlihat sebelum
tahun 1980, terjadi ketegangan antara tradisi dan agama yang
keduanya bersikukuh mempertahankan eksistensinya masing-
masing. Pelaku tradisi dengan besarnya pengaruh yang dimiliki
melakukan interaksi kepada masyarakat dengan tujuan untuk
melanggengkanpraktek menggemblak sebagai kebiasaan umum
yang bersifat normal. Sementara itu, masyarakat juga menghindari
adanya komodifikasi komponen kesenian reog sebagai upaya
dalam menjaga kemurnian warisan leluhur yang semakin
memberikan ruang bagi gemblak untuk terus eksis dalam
masyarakat. Dalam kasus ini terlihat bahwa budaya dominan
mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku
masyarakat. Kebiasaan menggemblak yang disebut sebagai tradisi
oleh para penganutnya, dalam beberapa kasus dijelaskan sebagai
bentuk seksualitas yang menyimpang dan berpengaruh pada
kegalauan gender. Hal ini terlihat pada hasil wawancara dengan
mantan gemblak dan warok yang membenarkan adanya sentuhan
fisik seperti mencium dan memeluk gemblak yang merupakan
wujud perilaku seksual. Bahkan terdapat penelitian yang
menyatakan bahwa praktek menggemblak tergolong pada
221
Mbah Tobroni (Warok), wawancara (2 Februari 2016).
222
S.M. Harahap, “Islam dan Budaya Lokal, Studi terhadap Pemahaman,
Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di
Padangsidimpuan Perspektif Antropologi”, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi
Umat Beragama, Vol.7, No.2, Juli-Desember 2015, 155.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
homoseksual atau pencinta sesama jenis. Namun doktrin tersebut
tidak dapat diberlakukan untuk semua penggemblak dikarenakan
hanya beberapa dari mereka yang melakukan praktek seksual.
Sementara itu, adanya kegalauan gender terlihat pada
seorang anak yang berperan sebagai gemblak yang diharuskan
memiliki sifat kemayu dan pintar berdandan layaknya wanita.
Umumnya mereka diharuskan memakai celana pendek yang ketat,
baju dengan warna mencolok seperti merah, hijau, dan kuning,
menggunakan kacamata, dan riasan yang menambah
kecantikannya. Hal ini mengindikasikan terjadinya kebingungan
seorang anak dalam menentukan perilaku yang sesuai dengan jenis
kelamin yang dimiliki. Dalam kesenian reog, seorang gemblak
yang berperan sebagai penari jathil diharuskan pintar menari dan
berlenggak-lenggok layaknya wanita. Terlebih lagi, penggunaan
make up yang menor juga menambah nuansa feminim yang
melekat dalam diri gemblak. Warna lipstik bibir yang merah
mencolok dan pemakaian asesoris berupa gelang dan kalung yang
umumnya digunakan oleh wanita, menjelaskan bahwa adanya
penggambaran sosok wanita dalam tubuh seorang anak laki-laki
muda. Berperan sebagai gemblak lambat laun berpengaruh pada
kepribadian seorang anak laki-laki yang seharusnya identik dengan
sifat maskulin, kuat, dan tegas menjadi menjadi sosok yang lemah
lembut, murah senyum, dan bertingkah kemayu layaknya wanita
yang sedang mencari perhatian. Hal ini patut menjadi perhatian
bahwa tradisi menggemblak turut berpengaruh pada kepribadian
seorang anak. Hal ini tentunya bertentangan dengan nilai dan
norma agama Islam dikarenakan seorang laki-laki dilarang
menyerupai sosok wanita dan begitu juga sebaliknya. Namun
agaknya rendahnya pemahaman tentang agama menyebabkan
kebiasaan ini terus dilakukan tanpa melihat akibat yang
ditimbulkan.
Pada nyatanya, keberadaan gemblak sulit dihilangkan dari
kehidupan masyarakat Ponorogo. Hal ini disebabkan oleh beberapa
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
faktor meliputi, faktor budaya, dominasi kaum elit, dan ekonomi.
Pada faktor budaya, keberadaan gemblak sebagai pelaku seni dalam
kesenian reog menjadi ruang bagi kelompok ini untuk menjada
eksistensinya. Kecintaan masyarakat pada kesenian dan
penerimaan pada sosok gemblak sebagai bagian dari masyarakat
menjadikan tradisi menggemblak sulit untuk dihilangkan. Pada
faktor adanya dominasi kaum elit yakni kelompok warok dan
masyarakat kelas atas, menjadikan praktek menggemblak sebagai
bentuk gaya hidup kaum menengah ke atas. Besarnya pengaruh dan
tingginya posisi justru menjadikan gaya hidup tersebut sebagai
trend yang dianggap normal bahkan menjadi patokan. Hal ini
terlihat pada munculnya istilah penggemblak yakni kelompok non
warok yang mempunyai gemblak atas dasar ingin mendapatkan
status sosial yang tinggi yang semakin mendorong tumbuh
suburnya tradisi menggemblak. Faktor yang ketiga adalah ekonomi
yang menjadi alasan dibalik kerelaan orang tua dalam menyerahkan
anaknya untuk dijadikan seorang gemblak. Mayoritas gemblak
biasanya berasal dari keluarga miskin dan kekurangan. Hal ini
justru menjadi harapan bagi keluarga gemblak untuk mendapatkan
kehidupan ekonomi yang lebih baik.
Disisi lain, agama memberikan sejumlah konsepsi kepada
masyarakat mengenai konstruk realitas yang didasarkan bukan
pada pengetahuan dan pengalaman melainkan sebagai bentuk
otoritas Ketuhanan.223 Pada awalnya tradisi masih menjadi
pegangan hidup, namun pada akhir tahun 1980an ketegangan yang
terjadi antara tradisi dan agama mulai mereda. Islam terus
melakukan upaya dan gerakan intensifikasi, Islamisasi, dan
pembaharuan dalam banyak segi seperti menghilangkan unsur
mistik dalam kehidupan masyarakat dan menggantinya dengan
ibadah yang bersifat rasional, menggeser perilaku tradisional yang
hanya memberikan manfaat pada kelompok tertentu, dan
mengembalikan peran masyarakat berdasarkan gendernya. Adanya
perubahan pola pikir dan pemahaman masyarakat pada ajaran Islam
223
Ibid.,156.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
berdampak pada perubahan budaya. Perilaku mistik yang mengarah
pada tindakan tradisional dan irrasional mulai ditinggalkan karena
tidak sesuai dengan nilai agama dan perkembangan zaman.
Tingginya tingkat pendidikan masyarakat turut mempengaruhi pola
pikir bahwa praktek hegemoni dan ideologi yang merugikan salah
satu pihak mengarah pada penindasan hak asasi manusia. Selain
itu, pemberian ruang bagi kelompok elit justru semakin mendorong
berkembangnya praktek hegemoni yang hanya menguntungkan
kelompok tertentu. Adanya campur tangan pemerintah dalam
perkembangan kesenian reog membawa dampak bagi perubahan
komponen dan nilai utama dari kesenian tersebut. Pada tahun 1988,
pemerintah pusat menghendaki pertunjukan kesenian reog dengan
menampilkan sosok wanita sebagai penari jatil. Permintaan ini
sepertinya sengaja dilakukan untuk mengembalikan masyarakat
pada konteks keluarga ideal yakni laki-laki dengan sosok maskulin
dan wanita dengan sosok feminim. Pada akhirnya, peristiwa ini
turut menjadi salah satu faktor dalam pergeseran kelompok
gemblak dalam kesenian reog.
Pada akhir tahun 1980, gemblak mulai jarang ditemui dalam
kehidupan masyarakat Ponorogo. Pada hakikatnya, upaya
penggeseran tradisi menggemblak dalam struktur masyarakat
Ponorogo yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma telah
lama dilakukan. Pada masa Bathoro Katong, beberapa upaya
dilakukan yakni dengan mengganti komponen kesenian reog yang
sangat digemari oleh masyarakat. Kesenian ini pada awalnya juga
menjadi wadah bagi para penggemblak dalam melanggengkan
kebiasaan memiliki gemblak sebagai simbol status sosial.
Modifikasi pada kesenian reog dengan memasukkan nilai-nilai
islami di dalamnya turut berdampak pada eksistensi gemblak dalam
dunia per warok an. Adapun dominasi unsur Islam ditonjolkan pada
perubahan penari jatil yang awalnya dimainkan oleh gemblak yang
kemudian digantikan oleh wanita, menggunakan tasbih yang
merupakan sumber dzikir sebagai salah satu asessoris pada dadhak
merak, penggambaran angka tujuh belas sebagai lambang jumlah
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
roka’at salat pada musik gamelan yang dinamakan laras slendro,
penggantian asal makna dari asal kata reog yakni riyoqun yang
berarti khusnul khatimah dan kebaikan yang akan didapatkan jika
manusia mau bertobat, penyampaian konsep nafsu yang harus
dikendalikan yakni amma>rah, lawwa>mah, dan mut}mainnah ke
dalam pemaknaan alat musik kendang dan penggantian makna
warok yang diadopsi dari bahasa arab yang berarti wira’i yakni
jiwa yang berhati-hati.224 Paparan tersebut menggambarkan adanya
upaya Islam dalam menghilangkan unsur-unsur negatif dan
meminimalisir ruang warok dalam melanggengkan praktek
menggemblak yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai-
nilai dari agama Islam.
Pemahaman keislaman masyarakat Ponorogo pada akhir tahun
1980 turut menggeser dan bahkan menghilangkan gemblak dalam
tatanan kehidupan. Agaknya hal ini dikarenakan tingginya
pemahaman nilai-nilai Islam sehingga berpangaruh pada pola pikir
dan perilaku masyarakat. Gemblak dianggap tidak sesuai dengan
nilai Islam dikarenakan pengaruhnya pada kegalauan gender dan
perilaku yang mengarah pada seksualitas. Islam menegaskan bahwa
hanya terdapat dua jenis kelamin yang diciptakan yakni laki-laki
yang harus berperan dan bersikap maskulin dan wanita yang
bersifat feminim. Selain itu, agaman ini turut melarang penggunaan
barang atau suatu hal yang dapat menyebabkan kebingungan
gender seperti penggunaan asesoris wanita pada laki-laki sehingga
menciptakan kesan cantik dan feminim pada diri laki-laki. Terlebih
lagi, Islam tidak membenarkan adanya cinta sesama jenis atau
perilaku yang mengarah pada perbuatan tersebut. Hal ini
mempengaruhi pola pikir masyarakat bahwa memelihara gemblak
dengan tujuan sebagai klangenan dan pengalih nafsumerupakan
bentuk perbuatan yang mengarah pada praktek homoseksual
sehingga perlu ditinggalkan karena tidak sesuai dengan ajaran
agama.
224
Rofiq, “Dakwah Kultural”, 309.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
Kesimpulan
Proses terbentuknya budaya dan tradisi tidak dapat terlepas dari
adanya interaksi intensif yang dilakukan oleh suatu kelompok
masyarakat. Kepercayaan dan agama yang merupakan salah satu
bentuk hasil interaksi yang dilakukan. Kebudayaan yang dimiliki
oleh masyarakat Ponorogo, merupakan bentuk akulturasi budaya
antara agama nenek moyang, Hindu, dan Islam yang memunculkan
perpaduan budaya yang indah. Bentuk akulturasi terlihat pada
lelakon warok dalam mendapatkan kesaktian dan kehidupan yang
sempurna. Warok merupakan tokoh sentral dalam mayarakat
Ponorogo dan berpengaruh dalam semua kalangan. Eksistensi
kelompok ini berhasil menciptakan sebuah sistem stratifikasi sosial
baik dalam kalangan warok maupun masyarakat secara umum.
Sebagai contoh keberhasilan warok memberikan pengaruhnya pada
masyarakat luas adalah diterimanya ideologi kanuragan yang
bahkan menjadi trand dan penentu status sosial. Gemblak adalah
wujud praktek hegemoni yang berhasil disembunyikan dalam kata
ideologi.
Pada kenyataannya banyak kelompok baik warok maupun
masyarakat yang memilih gemblak sebagai alat untuk mendapatkan
kedudukan yang tinggidalam strukturmasyarakat yang ada. Namun
dalam perkembangannya, praktek ini mengarah pada perilaku
seksual yang tidak sesuai dengan norma dan nilai agama Islam
yang dianut oleh masyarakat. Sementara itu, dampak menjadi
gemblak juga dirasakan oleh seorang anak laki-laki yakni menjadi
seorang yang feminim dan lemah lembut lanyaknya wanita. Hal ini
sekali lagi bertentang dengan norma agama yang melarang seorang
laki-laki berperilaku layaknya wanita dan begitupun sebaliknya.
Pada akhir tahun 1980, adanya dominasi agama Islam,
meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat telah
berhasil menggeser bahkan menghilangkan tradisi menggemblak
dari kalangan masyarakat. Banyak dari pelakunya memutuskan
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
untuk menjalai kehidupan secara normal dan kembali pada
keluarganya.
Daftar Pustaka
Burke, Peter. Sejarah dan Teori Sosia, Edisi Kedua. Jakarta: Obor,
2015.
Bradbury. Pengantar Teori-Teori Sosial. Jakarta: Obor, 2016.
Cavallaro, Dani. Teori Kritis dan Teori Budaya. Yogyakarta: Futuh
Printika, 2004.
Endraswara, Suwardi. Rasa Sejati, Misteri Seks Dunia Kejawen.
Yogyakarta: Narasi, 2006.
Harahap, S.M. “Islam dan Budaya Lokal, Studi terhadap
Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat
Batak Angkola di Padangsidimpuan Prespektif Antropologi”.
Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol.7, (2),
2015.
Harsono, J. & Slamet, S. Sosiologi Masyarakat Ponorogo.
Ponorogo: UMPO Press, 2016.
Hartono. Reog Ponorogo, untuk Perguruan Tinggi. Ponorogo:
DepDikBud, 1980.
Junaid, Hamzah. “Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya
Lokal”. Jurnal Sulesana Vol. 8 (1), 2013.
Kencanasari, L.S. “Warok Dalam Sejarah Kesenian Reog Ponorogo
Perspektif Eksistensialisme”. Jurnal Filsafat, Vol. 19,No. 2, 2009.
Kodiran. “Akulturasi sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan”.
Jurnal Humaniora, No. 8, 1998.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
Ulfia Krismawati DkkLuthfi Rahman
Khoirurrosyidin. “Pergeseran Peran Warok dalam Politik Lokal Di
Kabupaten Ponorogo”. Jurnal Aristo, Vol. 1 No. 2, 2013.
-------. “Dinamika Peran Warok Dalam Politik di Ponorogo”.
Jurnal Humanity, Vol.9 No. 2,2014.
Krismawati, N.U. “Larung Risalah Do’a; Upacara Ritual Syukur
sebagai Warisan Budaya Hindu Jawa Prespektif: Sejarah local”.
Prosiding seminar nasional “Sejarah Lokal: Tantangan dan Masa
Depan, 26 April 2017, Universitas Negeri Malang.
Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Jakarta: PT Balai Pustaka,
1984.
Lisbijanto, Herry. Reog Ponorogo. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Maunah, Binti. “Strattifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam
Perspektif Sosiologi Pendidikan”. Jurnal Ta’allum, Vol. 03, No.
1,2015.
Moelyadi. Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reog
Ponorogo. Ponorogo: Leguin Veteran RI Daerah Kabupaten
Tingkat II, 1986.
Mulder, Neils. Kebatinan dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa,
Kelangsungan dan Perubahan Kulturil. Jakarta: PT Gramedia,
1984.
Poerwowijoyo. Reog Ponorogo. Ponorogo: Depdikbud Kanwil,
1985.
Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Pedoman Dasar Kesenian
Reog Ponorogo dalam Pentas Budaya Bangsa. Ponorogo:
Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, 1993.
Roibin. “Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif Atau
Kompromistik?”. Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 1,No. 1,2010.
XReligió: Jurnal Studi Agama-agamaMutâwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Eksistensi Warok Dan Gemblak di tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980A
Comparative Study on Shi‘îte
Rofiq, A.C. “Dakwah Kultural Bathoro Katong di Ponorogo”.
Jurnal Islamuna, Vol.4 No. 2,2017.
Romli, H.K. “Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi
Antar Etnik”. Jurnal Ijtimaiyya,Vol. 8 No. 1,2015.
Taufiq, Amal. “Perilaku Ritual Warok Ponorogo dalam Prespektif
Teori Tindakan Max Weber”. Jurnal Sosiologi, Vol.3,No. 2,2013.
Sugiyanto, Alip. Bahasa dan Budaya Etnik Jawa Panaragan.
Surakarta: CV Kekata Group, 2017.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja
Grasindo, 2002.
Soemarto. Melihat Ponorogo Lebih Dekat. Ponorogo: Apix Offset,
2011.
-------.Menelusuri Perjalanan Reog Ponorogo. Ponorogo: Kota
Reog Media, 2014.
Yuwana, S. Homoseksual di Kalangan Warok, Warokan, Sinoman,
Gemblak di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten
Ponorogo. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
Volume 8, Nomor 1 2018Volume 7, Nomor 2, Desember 2017 X
IMPLIKASI DISKURSUS KRISTIANITAS
DALAM SERAT DHARMOGANDHUL DAN PEMIKIRAN
KIAI IBRAHIM TUNGGUL WULUNG TERHADAP
KOMUNITAS KRISTEN TEGALOMBO PATI
Reni Dikawati
Sebelas Maret University Surakarta
renydika77@gmail.com
Sariyatun
Sebelas Maret University Surakarta
sari_fkip_uns@yahoo.co.id
Warto
Sebelas Maret University Surakarta
warto_file@yahoo.com
Abstract:
The construction of Javanese Christianity is not only built on the basis of
biblical interpretation but also on acceptance capacity, communication
pattern, adjustments of cultural context, and the role of agency. The
manuscript of Dharmogandul remains significant part of the construction
of Christian ideas and values embraced by Javanese people. This research
examines texts and discourses of Serat Dharmogandul through
genealogical approaches and links it with religious thoughts of Kiai
Ibrahim Tunggul Wulung as a real-life context who provided Christian
worldview within Tegalombo Christian community in Pati. Genealogical
Religió: Jurnal Studi Agama-agamaMutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis
Volume 788, Nomor 212 , Desember201788| ISSN: (p) 2088-6330; (e) 2503-3778p-ISSN:
2088-7523; e-ISSN: 2502-6321| 2151-234120186-1456208
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
exploration of Serat Dharmogandul shows that the text starts with
religious concept to reach syncretism, which eventually becomes devoted
part of comparative study of religion. The research found that
comparative study of religion has accommodated religious encounters
within the text of Serat Dharmogandul and the real context of Tegalombo
Christian community.
[Kontruksi Kristen Kejawen tidak hanya dibangun atas dasar penafsiran
kitabiah. Wacana dan pengetahuan yang termuat dalam teks sastra
menunjukkan adanya kapasitas penerimaan, pola komunikasi, dan
penyesuaian konteks kultur, serta peran penting agency. Serat
Dharmogandul merupakan salah satu teks yang menjadi bagian dari
kontruksi ide, nilai dan gagasan mengenai kekristenan yang dipahami
masyarakat Jawa. Penelitian ini bertujuan menelaah dinamika teks dan
wacana serat Dharmogandul dengan pendekatan geneologi serta
menghubungkan dan membandingkannya dengan pemikiran Kiai Ibrahim
Tunggul Wulung sebagai real life context, sekaligus figur psikologis yang
memberikan worldview terhadap komunitas Kristen di Tegalombo, Pati.
Jelajah geneologi serat Dharmogandul menunjukkan bahwa teks berawal
dari konsep religiusitas kemudian bergeser ke arah sinkretis lalu menjadi
bagian dari perbandingan agama formal. Hasil penelitian menujukkan
pertentangan dan perbandingan dalam mengakomodasi wacana
perjumpaan beberapa agama dalam serat Dharmogandul dengan kondisi
riil komunitas Kristen Tegalombo.]
Keywords: Christianity, Dharmogandul, Ibrahim Tunggul Wulung.
Javanese Christianity construction is not only built on the basis of biblical
interpretation. Discourse and knowledge contained in literary texts show the
existence of acceptance capacity, communication patterns and adjustments to
the cultural context, as well as the important role of the agency.
Dharmogandul manuscript is a text that is part of the construction of ideas,
values, ideas, about Christianity that is understood by Javanese people. This
study aims to examine the dynamics of the Dharmogandul fiber texts and
discourses with genealogy approaches, connect and compare with the
thoughts of Kiai Ibrahim Tunggul Wulung as a real life context, as well as
2| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
psychological figures that provide worldview to the Christian community in
Tegalombo, Pati. Exploring Dharmogandul fiber genealogy shows that the
text originated from the concept of religiosity, in the historical development
there was a shift in the meaning of Dharmogandul fiber in syncretic
direction, until it became attached and became part of the comparison of
formalistic religion. The results of the study showed some contradictions and
comparisons in accommodating the discourse of meeting several religions in
the Dharmogandul fiber with the real conditions of the Tegalombo Christian
community.
Abstrak: Kontruksi Kristen Kejawen tidak hanya dibangun atas dasar
penafsiran kitabiah. Wacana dan pengetahuan yang termuat dalam teks sastra
menunjukkan adanya kapasitas penerimaan, pola komunikasi, dan
penyesuaian konteks kultur, serta peran penting agency. Serat Dharmogandul
merupakan salah satu teks yang menjadi bagian dari kontruksi ide, nilai dan
gagasan mengenai kekristenan yang dipahami masyarakat Jawa. Penelitian
ini bertujuan menelaah dinamika teks dan wacana serat Dharmogandul
dengan pendekatan geneologi serta menghubungkan dan membandingkannya
dengan pemikiran Kiai Ibrahim Tunggul Wulung sebagai real life context,
sekaligus figur psikologis yang memberikan worldview terhadap komunitas
Kristen di Tegalombo, Pati. Jelajah geneologi serat Dharmogandul
menunjukkan bahwa teks berawal dari konsep religiusitas kemudian bergesr
ke arah sinkretis lalu menjadi bagian dari perbandingan agama formal. Hasil
penelitian menujukkan pertentangan dan perbandingan dalam
mengakomodasi wacana perjumpaan beberapa agama dalam serat
Dharmogandul dengan kondisi riil komunitas Kristen Tegalombo.
Kata Kunci: Christianity, dharmogandul, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung.
Pendahuluan
Perlawanan budaya terhadap dominasi konservatisme Kristen di
bawah penjajahan Belanda terjadi dalam konteks kehidupansosial
di Nusantara.225 Hal ini karena pertentangan yang terjadi antara
225
Konservatisme berasal dari bahasa latin conservare, yang berarti melestarikan,
menjaga, memelihara dan mengamalkan. Konservatisme dalam konteks ini
Volume 8, Nomor 2 2018 |3
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Kristen Kejawen di bawah misionaris lokal dan zending pemerintah
kolonial. Kristen Kejawen dibawah misionaris lokal dinilai
mengalami perjumpaan dengan kepercayaan yang telah lebih
dahulu dihayati dan diterima melalui dialog antar agency
keagamaan, sehingga melahirkan bentuk sinkretisme sebagai tradisi
maupun media menyebarkan agama.226 Lebih diskursif pemerintah
Kolonial juga memanfaatkan dominasinya untuk mereduksi
pengajaran misionaris Nusantara.227 Oleh karena itulah secara
struktur sosial dalam kondisi yang tidak equity, menjadi katalisator
terbentuknya perlawanan dari misionaris lokal sebagai wujud
persinggungan dengan pemerintah Kolonial.
Hal yang kemudian menjadi menarik dikembalikan pada konteks
masanya, yaitu fakta bahwa perlawanan budaya di dukung oleh
politik identitas yang lebih dahulu diterapkan pemerintah. Politik
identitas ini hanya menguntungkan pihak pendominasi, sehingga
berimplikasi melahirkan sensitifitas dalam bentuk budaya tanding.
Sebagai reflektif dapat dianalisis dari penggambaran yang
dihidupkan dalam serat Dharmogandul. Dalam sejarah produksinya
serat Dharmogandul memuat kontruksi ide, nilai dan gagasan
sebagai perlawanan budaya terhadap konservatisme Islam, bahkan
mewacanakan diskursus kristianitas sebagai bentuk perbandingan
merujuk pada pola penyampaian Kristen di Nusantara yang dilakukan oleh
zending kolonialdengan tujuan penguatan dan mempertahankan ajaran yang
dilembagakan. Neil, S. Colonialism and Christian Mission. (London:
Lutterworth Press, 1996), 33.
226
J.S Aritonang. Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. (Jakarta:
BPK Gunung Mulia, 2006),13.
227
Tahun 1870 kedudukan gereja Hervormed yang beraliran calvinis semakin
merosot, sehingga gereja baru banyak bermunculan menggunakan nama baru
“gereformeerd” yang disertai dengan pembentukan lembaga zending. Tahun
1983 terdapat zending terbesar di Nusantara Zending der Gereformeede Kerken
(ZGK) dan Christian and Missionary Alliance (CMA). Dengan adanya factor
tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan dibentuk organisai tersebut untuk
mendirikan gereja dan menyebarkan Kristen di Hindia Belanda sesuai dengan
ajaran yang telah mapan. Muller Kruger. Sejarah Gereja di Indonesia. (Jakarta:
Badan Penerbit Kristen, 1959), 103.
4| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
agama formal.228 Dinamika serat Dharmogandul yang ditelaah
secara geneologis dari segi produksi dan reproduksinya
memberikan ruang diskusi agar tidak menjadi perbandingan
formalistik keagamaan yang bersifat rasial, paradoksal, hingga
menghancurkan humanisme religioustolerant, rukun, dan kesatuan
dalam keberagaman di era demokrasi kontemporer saat ini.
Secara implisit telaah genealogis Serat Dharmogandul melahirkan
ruang dalam memahami idealitas yang diharapkan individu
(indigeneous) dan kritik pinggiran yang disuarakan sebagai bentuk
perlawanan terhadap konservatisme saat itu. Wacana dalam serat
menggambarkan budaya perlawanan dalam bentuk protes terhadap
konservatisme Islam dan pengharapan terhadap Kristen. Hal ini
sekaligus dapat menggambarkan pola nalar (indigeneous
pshychology), hingga kuasa, penguasa yang eksis mendominasi.229
Secara geneologis transformasi wacana dalam serat dapat
diidentifikasi dari adanya limit individu yang mengadopsi dan
mereproduksi gagasan yang telah ada untuk tujuan mempribumikan
wacana. Kesimpulan, dalam struktur sosial gagasan yang termuat
dalam serat dapat mengidentifikasikan sistem kebudayaan yang
mempengaruhi mentalitas sosial dalam memandang pro dan kontra
dengan tipe ideal religiusitas, spiritualitas yang dihidupkan
didalamnya.
Perbandingan konteks serat dengan kondisi real life context perlu
dibangun sebagai telah kritis. Komparasi dengan pemikiran
sezaman dan memiliki kedekatan, keterkaitan menjadi bentuk
pertimbangan kembali pemahaman situasi kondisi saat menganalisa
perang wacana dalam bingkai perbedaan kepentingan, motif, dan
228
Damar Sasangka. Dharmogandhul: Kisah Kehancuran Jawa dan Ajaran-
Ajaran Rahasia. (Jakarta: Dolphin, 2011), 311.
229
Dinamikadari proses transformasi wacana di lingkungan sosial mengalami
penyesuaian konteks, kepentingan, dan tujuan. Diskursus ini memiliki power
untuk menguatkan, mengukuhkan, atau menggoyahkan tatanan yang telah ada.
Kebenaran dalam wacana bersifat dinamis. MichaelFoucaulth. Archeology of
Knowledge. (London: Routhledge, 2004), 44.
Volume 8, Nomor 2 2018 |5
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
tujuan. Oleh karena itu, peneliti memerlukan kerangka analisis
wacana serat Dharmogandul yang disandingkan dengan konteks
real life sebagai kerangka worldview yang dimiliki oleh komunitas
Kristen Tegalombo, Pati. Worldview yang dimiliki komunitas
Tegalombo dalam menghayati kristianitas relevan dengan validasi
kritis terhadap ambiguitas yang ada dalam serat Dharmogandul.
Korelasi telaah kritis wacana dan pengetahuan yang termuat dalam
teks sastra maupun pemikiran agency mampu menunjukkan
kapasitas penerimaan, pola komunikasi dan penyesuaian konteks
kultur serta peran penting agency itu sendiri dalam membentuk
sistem mentalitas komunitasnya.230
Penelitian mengenai geneologi serat Dharmogandul dan pemikiran
Kiai Ibrahim Tunggul Wulung diperlukan untuk merevitalisasi
kontruksi gagasan berbasis nilai, agar dapat diselaraskan dengan
sistem mentalitas modern. Dengan demikian usaha ini dapat
menghubungkan dan membandingkan diskursus kristianitas yang
diwacanakan dalam serat Dharmogandul dengan kehidupan sosial
masyarakat Tegalombo Pati sebagai penerima transfer pengetahuan
dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Usaha ini menjadi alternatif
solusi membangun dialog agar tidak serta merta kontruksi ide,
gagasan, maupun wacana dalam serat Dharmogandul digunakan
sebagai dasar rujukan perbandingan agama formalistik, maupun
penilaian dydadic dan monadic dalam studi perbandingan agama.
230
Ricci. New Direction in The Study of Javanesse Literature: Reasoning, Ideas,
Method, and Theories in The Study of The Literature of Java Indonesia.
(Jerusalem: Literacy Studies Hebrew University of Jerussalem, 2018), 3.
6| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
Dinamika Serat Dharmogandhul
Tradisi menulis masyarakat Jawa tradisional telah berlangsung di
sekitar lingkup keraton yang dilakukan oleh para elite intelektual
yang disebut sebagai pujangga.231 Secara umum tugas pujangga
terkait dengan produksi dan reproduksi naskah, yang terdiri dari
beberapa hal, yaitu anyerat atau menulis, angganggit (mengarang),
angiket (mengumpulkan), akarya sastra (mengerjakan teks), dan
anedhak(menyalin).232 Proses transformasi pengetahuan yang telah
dikembangkan oleh Pujangga tidak hanya melingkupi keraton
untuk kepentingan raja, melainkan dengan transmisi lisan-tulisan-
lisan melalui beberapa praktik budaya seperti nembang, pitutur,
dan pewayangan.233 Perkembangannya tradisi menulis ini pada
akhirnya juga dihadapkan dengan tradisi Tulis Barat bersamaan
dengan proses kolonialisme.234 Salah satunya yang menjadi fokus
penelitian terkait dengan serat Dharmogandhul.
Serat Dharmogandul telah banyak menjadi pembahasan oleh
peneliti terdahulu seperti yang dilakukan oleh Redaksi Almanak H
Bunning, Yogykarta (1920) dalam versi puisi (tembang).
Sedangkan dalam versi prosa (gancaran) diterbitkan oleh T.B Sadu
Budi, Solo (1959). Secara geneologis sejalan dengan budaya tulis
sastra yang menggunakan nama samaran, atau bahkan anonim
231
Pujangga berasal dari bahasa Jawa kuno “bhujangga” yang secraa harfiah
bermakna ular. Pujangga merupakan analogi yang menggambarkan symbol
untuk agen-agen intelektual yang memiliki pemikiran tajam. Istilah ini dalam
tradisi penulisan kontemporer sering disebut dengan istilah Courtpoet atau
sastarawan istana. Sri Margana. Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 125-127.
232
Ibid,.
233
Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tulisan dan lisan dalam transformasi
pengetahuan dan domestifikasi sistem mentalitas masyarakat Jawa tidak dapat
dipisahkan dalam perkembangannya. Walter J Ong. Kelisanan dan Keaksaraan.
(Yogyakarta: Gading Pustaka, 2013), 17. Lihat juga J. J Ras. Masyarakat dan
Kesusteraan Jawa. (Jakarta: YOI, 2014), 69.
234
Sri Margana. Pujangga Jawa,126.
Volume 8, Nomor 2 2018 |7
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
menjadikan serat Dharmogandul bersifat kontroversial dari segi
pengarang dan muatan isinya.235 Apabila dilihat dari dasar rujukan
yang digunakan oleh peneliti terdahulu seperti yang dilakukan oleh
Damar Shasangka maupun beberapa peneliti lain diketahui berasal
dari induk serat Dharmogandul yang disimpan oleh K.R.T
Tandhanagara, yang diperkirakan hasil cipta karya Ranggawarsita
(1802-1873). Sebagai hasil cipta karya serat Dharmogandul
merupakan bentuk produksi pengetahuan yang dikonsepsikan oleh
agen intelektual yang dapat mempengaruhi atau menjadi sistem
mentalitas yang mendukung penguasa (kuasa), dan disisi lain juga
dapat menjadi bentuk narasi pinggiran yang mengkritik situasi,
kondisi, dominasi, dan kuasa penguasa.
Abad 19 diperkirakan menjadi kurun waktu diproduksinya serat
Dharmogandul yang diwarnai dengan adanya perlawanan budaya
dari Jawa, Islam dan penetrasi Kristen. Konteks saat itu juga
melahirkan adanya proses pribumisasi Kristen dibawah misionaris
lokal seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung.236 Serat Dharmogandul
mengandung diskursus kristianitas dengan simbolisasi wit kawruh.
Secara umum muatan gagasan dalam serat memposisikan agama
Budi sebagai agama Nusantara, sedangkan Islam sebagai agama
Arab dan Kristen sebagai agama pemerintah Kolonial.
Konservatisme Islam yang digambarkan dalam serat dianggap
berbahaya bagi agama Budi maupun pemerintah Kolonial. Bahkan
dalam konteks sosial idealisme pemerintah Kolonial yang bersifat
politik dan agama turut memberikan kontribusi reproduksi serat
235
Salah satu ciri sastra di Nusantara bersifat anonim, pengarangnya biasa
menggunakan nama samara atau bahkan tidak menuliskan sama sekali
identifikasi dirinya. Biasanya isi dari serat mengacu pada sifat-sifat historis,
didaktis, dan religious. Damar Sasangka, Dharmogandhul, 421.
236
Peminggiran Islam secara berulang dalam teks menunjukkan adanya
keinginan melawan tatanan mapan Islam,mempertanyakan ulang, dan
menghidupkan harapan baru dengan menyebut Kristen. Hal yang harus dipahami
kecenderungan ini menunjukkan bahwa daya tarik agama dalam kehidupan
sosial menunjukkan realitas sosial yang terbangun saat itu, maka hal ini
menunjukkan bagaimana individu yang kalah, patah, dan tertindas menyuarakan
narasi pinggirannya sebagai perlawana.ibid,.
8| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
Dharmogandul sebagai perbandingan agama formalistik. Melihat
keterkaitan ini, memungkinkan telaah geneologis dikembangkan
untuk menganalisa muatan wacana dalam serat dan perbandingan
dengan pemikiran Tunggul Wulung.
Tradisi produksi dan reproduksi wacana dari serat Dharmogandul
dapat dirunut asal usulnya dalam konsepsi budi hawa yang
berkembang di Nusantara khususnya Jawa.237Budi hawa dalam
konsepsi tersebut dipersepsikan sebagai dzathyang widhi, dan hawa
sebagai kehendak hati. Penggambaran individu yang tidak memiliki
kekuatan apapun, hanya sekedar menjalani, dan budilah yang
menggerakkannya (tata lampah ing urip). Konteks isinya berawal
dari konsep religiusitas, yang dihayati dalam kapasitas penerimaan
personal individu dan sensitifitasnya terhadap unsur-unsur
keagamaan. Sensitifitas ini digambarkan dengan adanya idealitas
yang dibangun pengarang terhadap unsur keagamaan disertai
dengan memperbandingkan satu dengan yang lain. Kontruksi
gagasan ini menunjukkan wacana sebagai instrumen kekuasaan,
hambatan, resistensi dan sebagai strategi perlawanan.238 Sebagai
karya cipta budaya. agen intelektual (pujangga) memiliki kapasitas
membentuk mentalitas, mendukung suatu dominasi, menyerang
dominasi yang secara struktur sosio-politik berada di bawah
penguasa, atau kedekatan dengan penguasa. Efek wacana yang
dihasilkan ditujukan pada struktur sosial politik secara luas.
Realitas sosial menunjukkan dalam perkembangan historisnya serat
Dharmogandul tidak hanya bermuatan tentang perbandingan agama
Budi, Islam, Kristen melainkan juga menunjukkan pergeseran
pemaknaan ke arah sinkretis, hingga melekat dan menjadi bagian
dari perbandingan agama formalistik.239 Berikut merupakan kutipan
237
Huda. Tokoh Antogonis. (Yogyakarta; Pura Pusaka, 2005), 114.
238
Michael Foucoult. The History of Sexsuality: in Introduction. (London:
Penguin, 1990), 101.
239
Perbedaan cara pandang dalam memahami konteks wacana dalam serat
Dharmogandhul disebabkan oleh adanya simbol sebagai produk budaya, yang
mengandung kompleksitas dan multi intepretasi, sejak produksi dan
Volume 8, Nomor 2 2018 |9
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
yang mengidentifikasikan sensitifitas membangun wacana
perbandingan agama:
“Pitane Lata wal Ngujya/ bab agami binage tri pakawis/wit Budi
kang rumuhun/ woh kawruh kalihira/wit kuldi punika ping
tiganipun/ woh budi nama kelingan/ woh kawruh wigya mangerti.
Woh wit kuldi iku pangan/ yen wong Jawa tedhane woh wit Budi/
wong Indi nedha woh kawruh/ woh kuldi tiyang Ngarab/ trima
sugih dagangan daging alemu/ sadhiyan pakaning rayap/ kawruhe
tan dados wiji.... yang nedha woh kawruh wreksa/ anyungkemi
agama srana-srani/ nebut ngisa rohollahu/ tangia rahsaning tyas/
amangeran kawigyan lan kawruhipun/ mung ngauwr bacik lan ala/
kang bener lawan kang sisip.”240
Konteks tersebut menunjukkan adanya sensitifitas terhadap Islam,
dan lebih pengidealan terhadap agama budi dan Kristen. Meskipun
demikian narasi yang menyudutkan Islam untuk mengidealkan
Kristen tidak memiliki pijakan yang kuat dan perlu untuk
dipertanyakan ulang validitasnya.
Temuan tersebut didukung dengan kurangnya pemahaman akan
doktrin kekristena, dan pengetahuan kitabiah. Kesalahan ini
nampak dalam mengutip salah satu cerita yang dipetik dari
perjanjian lama dalam 2 Samuel pasal 15-18 mengenai perebutan
kekuasaan antara Daud dan Absalom. Hal ini juga dapat ditarik dari
pengamatan motif yang melatar belakangi kemunculan serat yang
dinilai mengandung unsur kedekatan dengan pemerintah Kolonial
(politik budaya) dalam menyerang konservatisme Islam. Diskursus
kristianitas yang diwacanakan hanyalah ungkapan apresiasif yang
reproduksinya dibuat oleh beragamam kepentingan, aspirasi, dan tujuan. Naskah
ini berada dalam masa peralihan sehingga ingin menunjukka situasi yang ada
saat itu dimana agama budi hawa (Hindhu-Budha) mulai terpinggirkan oleh
Islam, dan Islam akan tergantikan oleh kristen. Suatu perspektif pemproduksi
wacana dalam serat yang menunjukkan ‘pilihan yang disengaja”. Nancy Florida.
Javanesse Literature In Surakarta Manuscripts, Vol. 1. (New York: Cornell
Modern Indonesia Project, 1995), 32.
240
Damar Sasangka, Dharmogandhul,324.
10| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
melihat begitu berbedanya penghayatan keagamaan dari pemeluk
Kristen dan Islam.241 Selain itu dibawah dominasi pemerintah
Kolonial kemunculan teks Dharmogandul juga diwarnai oleh
kondisi ketidakstabilan kuasa yang ditandai akomodasi Ratu Adil
dalam berbagai konteks kehidupan.
Kecenderungan memproduksi serat Dharmogandhul menunjukkan
diskursus kristianitas dibangun lebih ideal dibandingkan narasi
Islam. Hal ini sebenarnya menunjukkan gejolak umat yang
berusaha direpresentasikan melalui penyeretan nilai religius dalam
pertarungan kepentingan politik. Kondisi ini bila direfleksikan
dalam konteks saat itu justru memanifestasikan tujuan pencarian
dukungan dari suara mayoritas. Perasaan ini menjadi imaginer,
menginginkan keseimbangan, kesetaraan antara kepercayaan budi
hawa dengan kepercayaan Kristen yang saat itu dinilai paling
tinggi oleh pemerintah Kolonial. Suatu ekspresi keputusasaan atas
represi, dan perubahan peradaban. Suatu dilema personal yang
digambarkan oleh pemproduksi untuk menginginkan kejayaan budi
hawa, ataupun pengharapan baruakan Kristus sebagai lawan
konservatisme Islam.
Sejalan dengan pendapat Foucoult setiap kebenaran selalu
memiliki bingkai subjek, wacana, kekuasaan, relasi pengetahuan,
pemegang kebenaran, govermentality dan technologies of the self
(penunjuk identitas) yang semuanya mengarah pada hasrat
kekuasaan pemerintah dengan penguasaan pengetahuan. Realitas
dari proses panjang penjajahan telah berhasil membentuk berbagai
wacana, cara pandang, mentalitas untuk mendukung kelanggengan
hegemoninya. Cara-cara yang digunakan tidak hanya
mengandalkan fisik, melainkan juga intelektual dengan merepresi
budaya, dan membentuk mentalitas baru dengan standardisasi
Barat. Serat Dharmogandul menunjukkan pembenaran dari kajian
241
R M Freener. “Religious Competition and Conflict the longue duree:
Christianity and Islam In The Indonesia Archipelago”. Asian Journal of Religion
and Society , Vol. 5, No.1. 1-22.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 11
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Edward Said (1978) dalam orientalisme yang menggambarkan
bagaimana praktik diskursif digunakan untuk melegitimasi
kekuasaan secara berkesinambungan melalui cara pandang Barat
terhadap Timur.242 Sejalan juga dengan konteks hegemoni Antonio
Gramci (1987) yang menggambarkan pentingnya proses hegemoni
dengan konsensus (consenso) dari pada melalui penindasan
terhadap kelas sosial lain.243
Hegemoni yang disuarakan dalam serat Dharmogandul dengan
meminggirkan Islam memiliki kontradiksi dengan konsep
pengajaran Kristen di Tegalombo. Diskursus kristianitas dalam
serat digambarkan sebagai budaya tanding terhadap Islam, dalam
bentuk narasi patah dari individu yang merasa terancam dalam
lingkup struktur sosial. Sedangkan dalam konteks real life
menunjukkan spirit indigenous mencapai kebebasan dengan
keterbukaan cara pandang. Diskursus kristianitas dalam kontek
sosial dihayati sebagai pengharapan baru akan keselamatan. Hasil
penelitian menunjukkan pengaruh Tunggul Wulung
justrumembentuk mentalitas berdaya dan bebas yang dihayati
melalui kasih Kristus. Kebebasan tersebut juga tampak dalam
konsistensi Tungul Wulung membentuk worldview komunitas
Kristen Kejawen di Tegalombo. Secara sosial perbenturan tidak
pernah terjadi dalam perjumpaan Kristen dengan kepercayaan lain.
Dialog antar agama (jadal) dan konsep guru ngelmu mampu
242
Said menegaskan bahwa orientalisme adalah suatu gaya berpikir yang dibuat
antara Timur sebagai (The Orient), dan Barat (the accident). Pola berpikir inilah
yang saat itu melingkupo kondisi saat itu, dimana yang ideal adalah Barat,
sehingga untuk menjadi sama atau modern individu harus mengikuti gaya Barat.
Lebih jauh lihat Edward Said. Orietalisme. (Bandung: Penerbit Pustaka, 2001),
12.
243
Konsep hegemonik yang dipaparkan oleh Gramci merujuk ada intelektual dan
moral. Hal ini akan mendukung sutu persetujuan dari kelas bawah atas dominasi
kelas atas, karena keberhasilan emnanamkan ideology kelompoknya.
Internalisasi ideology ini dilakukan dengan membangun sostem dan lembaga
seerti Negara, common sense, kebudyaan, pendidikan, domestifikjasi gagasan,
yang dapat emperkuat hegemoni tersebut. Andi Ariez & Nezar Patria. Antonio
Gramchi: Negara dan Hegemoni. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 171.
12| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
mengakomodasi wacana perjumpaan beberapa agama tanpa
peminggiran dan pertikaian.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 13
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Pemikiran Kiai Ibrahim Tunggul Wulung
Perbincangan mengenai telaah kritis pemikiran tokoh, tidak dapat
dipisahkan dari semangat zaman disertai dengan konsistensinya
dalam struktur sosial. Pemikiran merupakan kontruksi ide sebagai
usaha intelektual membangun suatu kondisi yang melingkupinya.
Pemikiran akan menjadi suatu realitas bila disampaikan dan
membawa dampak perubahan situasi. Kiai Ibrahim Tunggul
Wulung memenuhi kriteria sebagai tokoh dan ditokohkan karena
pemikirannya dalam struktur sosial. Kriteria sebagai tokoh dapat
diukur melalui terpenuhinya tiga persyaratan. Pertama, berhasil
dibidangnya, kedua, memiliki karya monumental, dan ketiga
mempunyai pengaruh di masyarakat. Tunggul Wulung ditokohkan
karena peranannya mengembangkan Kristen. Selain itu
ketokohannya juga diakui oleh masyarakat luas melalui ritus
makamnya. Sebagai tolak ukur keberhasilan Tunggul Wulung yang
mampu menerapkan spiritualitas kristus dalam sistem mentalitas
masyarakat.
Pemikiran agen-agen sosial pada masa kolonial diwarnai dengan
perbincangan retorika sejarah dan budaya mengkritik kondisi sosial
Hindia-Belanda yang dikaitkan dengan unsur kultural
historis.Tokoh intelektual ini lebih akrab dikenal sebagai agency.
Sejalan dengan teori Pier Bordieu, agensi mengarah pada
kompetensi yang dimiliki individu sebagai modal mengubah
lingkungan.244 Berdasar hal tersebut tujuan reposisi pemikiran
Tunggul Wulung dalam penelitian sebagai upaya
mengkontekstualisasikan imaginer dalam wacanakan kristianitas
pada serat Dharmogandul. Mengingat sebagai agency, Tunggul
Wulung juga merupakan agen intelektual yang mampu membangun
sistem mentalitas dan memiliki kapasitas menerapkan gagasan
244
David Swartz. Cultural and Power: The Sociology of Piere Bordieu.
(Chicago: The University Of Chichago Press, 1997), 4.
14| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
dalam struktur sosial masyarakat.245 Berdasar perspektif peneliti,
pemikiran Tunggul Wulung berkolerasi dan setara dengan latar
belakang produksi serat Dharmogandul kaitannya dengan semangat
zaman.
Tunggul Wulung membangun kritik akan kondisi sosial Hindia
Belanda yang dikaitkan dengan unsur kultural historis dibidang
sosial keagamaan.246 Kritik tersebut digambarkan dalam pilihan
cara yang diambil Tunggul Wulung dengan melakukan tapa brata
dan lelana untuk mengembangkan pengetahuan kristianitas, bukan
dengan mengikuti sekolah zending. Tunggul Wulung lahir di Jepara
dengan nama asli Ngabdullah. Tunggul Wulung memanfaatkan
modal sosial dan personal yang dimiliki dan sengaja dibentuk
sebagai pendukung nilai kharismatik dan penerimaan dari
komunitasnya.247 Tunggul Wulung dalam hal ini memanfaatkan
konsep Ratu Adil sebagai penghimpun kekuasaan dan
menggunakan daya usaha ritual tapa brata untuk mengkultuskan
dirinya sebagai titisan Tuhan. Konsep ini menunjukkan mentalitas
245
Ketokohan Tunggul Wulung sebagaifigur psikologis yang membangun
mentalitas komunitas Kristen di Tegalombo dengan transmisi pengetahuan
kekristenan yang dipahaminya dalam hal ini diakui oleh masyarakat setempat.
Agama dalam konteks hubungan dialektis antara masyarakat dan manusia
melalui tiga tahap, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Hal inilah
yang melahirkan kenyataan, yang baru dirasakan sebagai sesuatu yang rill
apabila telah mengalami litimasi kognitif. Pada proses legitimasi ini agama
menempati kedudukan sentral. Agama praktis dapat dikatakan sebagai
pembentuk “komunitas kognitif” (cognitive community). Lihat juga P Kartiko.
Pokok-Pokok Ajaran Gereja Injil di Tanah Jawa.(Pati: Tim Penyusun Pokok-
Pokok Ajaran GITJ, 2007), 35.
246
Agama mampu menjadi salah satu daya tarik bagi suatu perkumpulan dengan
semangat (faith, truth), membicarakan agama, kohesi dan integrasi telah
menjadikan agama sebagai realitas sosial, sebagai sebuah fakta historis dan
sosiologis. Konsekuensinya agama dalam hal ini tidak hanya dilihat sebagai
serangkaian ajaran dan landasan nilai yang kompleks tentang hubungan manusia
dengan konsep ketuhanan yang bertransenden, tetapi juga sesuatau yang
membentuk corak dan bentuk dari realitas sosial dan proses perubahan sosial.
Bryan S Turner. Religion and Social Theory. (London: Heinemann Education
Books Ltd, 1983), 55.
247
Johannes Verkuyl. Contemporery Missiology: An Introduction. (Grand Rapid:
Ermand Publishing Compeny, 1978), 44.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 15
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
masyarakat Jawamenggunakan kesakten untuk mencapai tujuan
dengan menyandarkan kekuatan diluar daya manusia.248
Pengakomodasian simbol Ratu adil maupun Tunggul Wulung yang
digunakan Ngabdullah membangun kesakten menunjukkan
legitimasi geneologis. Legitimasi geneologis terbukti membuatnya
memiliki kapasitas kedigdayaan.249 Simbol ratu adil dalam konteks
kehidupan sosial di Nusantara, khususnya Jawa memberikan janji
imaginer terhadap komunitasnya atas kesejahteraan, keadilan,
kebebasan, dan penghubung antara dunia makrokosmos dan
mikrokosmos.250 Sedangkan seminasi makna Tunggul Wulung
dalam kehidupan sosial di Nusantara merupakan simbol yang telah
lama digunakan sebagai penyebutan benda, individu, maupun
segala sesuatu yang memiliki kesakten, sakral dan nilai
kebermanfaatan. Seminasi Tunggul Wulung yang dimanfaatkan
Ngabdullah dalam konteks ini merupakan sebutan masyarakat
Kediri yang secara geneologis merupakan sebutan untuk pengikut
Raden Brawijaya V yang moksa dan menjaga Gunung Kelud.
Keahlian Tunggul Wulung dalam menyebarkan ajaran Kristen
dengan cara jadal (debat) melahirkan simbolisasi Kiai sebagai
apresiasi dari pengikutnya. Konteks Kiai dalam Kristen Kejawen
merupakan bagian dari konsep guru ngelmu yang menjadi sarana
transfer pengetahuan. Guru ngelmu dalam konsepsi tersebut
dipersepsikan sebagai perwujudan individu yang mampu
membangun, mengorganisir dan menyebarkan pengetahuan
248
Koentjaraningrat. Sejarah Teori Antropologi I. (Jakarta: UI Press, 2004), 51.
249
Kedigdayaan akan diperoleh individu ketika masyarakat melihat dalam
dirinya terdapat virtues. Virtues dinilai sebagai keutamaan/kebajikan utama “etis
filosofis” kebaikan (merit) penampakan ilahi (self declaration on the part of the
Gods), keberanian, kepahlawanan, dan kekestarian (martial variour). Tunggul
Wulung dalam komunitas Tegalombo menjadi virtues yang dinilai memiliki
kekuatan ilahi, sebagai ratu adil, dan pengukuhan diri dengan kekuatan-kekuatan
adikodrati (pulung) menjadi bentuk kharisma keunggulan pribadi. E Ferquson.
Background of early Chriatianity. (Grand Rapid, W.B Eerdmans, 1987), 135.
250
Patmono. “Gerakan Ratu Adil di Jawa”. Majalah Peninjau, Vol. 1, No. VI,
1979,. P. 59.
16| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
keagamaan.251 Dalam konsep guru ngelmu pihak yang kalah debat
akan mengikuti yang menang sebagai gurunya. Realitas ini juga
ditunjukkkan dalam komunitas Tegalombo. Pengajaran spiritual
Kristen diberikan oleh tunggal wulung setelah pembukaan lahan
kepada pengikut-pengikutnya yang awalnya memeluk agama lain.
Sejalan dengan wacana yang digambarkan dalam konteks serat
Dharmogandul, sebagai berikut:
“Wong Jawa ganti agama/padha tinggal agama Islam
benjing/asalin agama kawruh/ Sunan Kaliturira/Yen mekaten
utaminipun pukulan/kawula prayogi bekta/kang tirta arum
puniki ....Denya ajar dadi wong Jawa/Jawa Jawi mengerti mata
siji/yen wis siji matanipun/padha eling agama/Buda budi amangan
uwohing kawruh/tegese ran purbalingga/prabawanira wong
Jawi.”252
Oleh karena itu, baik dalam serat Dharmogandul maupun
kehidupan rill di masyarakat, hal tersebut menunjukkan fenomena
perpindahan kepercayaan.
Pendekatan praktikal dalam menganalisis pemikiran Kiai Ibrahim
Tunggul Wulung perlu digunakan sebagai telaah. Transfer
pengetahuan yang dilakukan Tunggul Wulung melahirkan sistem
mentalitas berupa humanisme religious yang terus dipertahankan
sebagai dasar sikap.253 Masyarakat Tegalombo hingga kini hidup
dalam rukun, toleran, menjunjung ajaran hidup yang dibawa oleh
Tunggul Wulung. Mengakarnya sistem pengajaran Tunggul
Wulung juga melahirkan budaya yang diabadikan di area situs
makam. Membuktikan dalam dinamika naik turunnya pengajaran
dan pandangan terhadap Kristen Kejawen semasa pemerintah
251
Bambang Noorsena. Menyongsong Sang Ratu Adil: Perjumpaan Iman
Kristen dan Kejawen. (Yogyakarta: Yayasan Andi, 2003), 21.
252
Damar Sasangka, Dharmogandhul, 327.
253
Hoekema. Kristus dan Kebudayaan: Suatu Panduan Teologi Mennonite
dalam Pangabean. Penabur Benih Mahzab Teologi: Menuju Manusia Baru.
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 177.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 17
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Kolonial, tidak melunturkan penghayatan akan konsep
humanismereligious yang ditransfer Tunggul Wulung.254 Ritus
makam Tunggul Wulung yang masih dilestarikan menunjukkan
ketokohan dan perannya sebagai agency tertanam sebagai identitas
sosial masyarakatnya.
Penafsiran kitabiah dan iman Kristen Tunggul Wulung menjadi
pedoman komunitasnya menerima keyakinan baru. Tunggul
Wulung menghendaki Kristen Kejawen, bukan Kristen Kolonial
(penetrasi Kristen).255 Sehingga proses penyebarannya Kristen yang
dilakukan oleh Tunggul Wulung menggunakan wacana-wacana
lebih bebas. Kapasitas penerimaan diskursus kristianitas yang
dihayatinya menunjukkan kemerdekan pola pikir. Meskipun secara
struktur sosial, pemikiran Tunggul Wulung berimplikasi pada
upaya purifikasi oleh pemerintah Kolonial. Pengajaran Kristen
Kejawen ini dinilai bertentangan dengan pemerintah dan perlu
untuk dimurnikan sesuai kitabiah. Proliferasi ini menunjukkan
upaya teologi lokal yang dilakukan Tunggul Wulung sebagai
penganut kristus sekaligus masyarakat Jawa dengan sistem
mentalitas Kejawen.256
Menilai konsistensi pemikiran Tunggul Wulung dapat dilihat dari
dinamika ajaran Kristen Kejawen yang ditransfernya di Tegalombo,
dan life cycle (putaran kehidupan) masyarakatnya. Secara umum
Kristen Kejawen tidak menjadikan masyarakat pribumi menjadi
Barat saat mengimaninya. Identitas kultural masyarakat Jawa terus
254
Ariarajah. Alkitab dan Orang-Orang yang Berkepercayaan Lain. (Jakarta:
BPK Gunung Mulia, 2000),183.
255
Tunggul Wulung menilai dominasi kolonial merugikan pribumi dalam
berbagai kehidupan, bahkan untuk akses perbaikan nasib. Sistem hegemonik dan
dominasi kekuasaa mudah memancing pola perilaku hegemonik, otoriter, dan
tak-toleran. Oleh karena Tunggul Wulung menghendaki adanya kebebasan dari
ikatan kolonial, dan melahirkan counter culture terhadap hegemonik kolonial.
Taufik Abdullah. “Disekitar Masalah Agama dan Kohesi Sosial: Pengalaman dan
Tantangan”. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 1, No. 1, 2009, 21.
256
M.C Ricklef. Religious Reform and Polarization in Java. (Singapore: ISIM
REVIES 21 SPRING, 2008), 4-5.
18| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
diusung sebagai bagian dari etika keagamaan yang menjadi pola
laku masyarakat. Bahkan dalam hal ini Kristen Kejawen
melahirkan relasi struktural dan fungsional. Pembentukan
komunitas tidak hanya menyentuh segi personal, melainkan juga
komunal sebagai identitas bersama. Identitas bersama ini terus
dikukuhkan dengan pembangunan perekonomian. Konsepnya,
semakin masyarakat memperoleh kesejahteraan secara ekonomi,
semakin mudah pembelajaran agama diakomodasi untuk melawan
dominasi kolonial.257. Mengidentifikaiskan diskursus kristianitas
yang dihayati oleh masyrakat Tegalombo-Pati melahirkan
spiritualitas yang tidak hanya berhubungan dengan iman Kristen,
melainkan juga etika Kristen dalam hidup bersama.
Metode debat dinilai memperkuat penafsiran keagamaan yang telah
dihayati Tunggul Wulung sekaligus sebagai upaya pengakuan dari
agama lain.258 Suasana dialog sedikit banyak melahirkan
sinkretisme dan penyesuaian dengan konteks budaya. Oleh karena
itu, resepsi penerimaan ajaran Kristen perlu dilihat dari dua konteks
utama, pertama bagaimana penafsiran dan pemaknaan yang
dihayati komunitas. Kedua,bagaimana komunitas Kristen Kejawen
di Tegalombo Pati menghubungkan konteks dirinya dikehidupan
sosial dengan konteks injil sebagai pedoman.259 Hanya saja
limitasinya terdapat dalam konsensus bahwa teologi yang dibangun
masyarakat Tegalombo tidak tersusun secara sistematis, tenggelam
dalam teologi resmi. Teologi komunitas Kristen Tegalombo
cenderung dicurigai sebagai tidak murni Kristen, terampur dengan
keyakinan (agama) Jawa, dianggap klenik yang tercampur dengan
257
Scherer Savitri Prastiti. “Harmony and Dissonance: Early Nationalist Thought
in Java”. Penerjemah. Jiman S Rimbo. Keselarasan dan Kejanggalan:
Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Abad XX. (Jakarta: PT Sinar
Agape Press, 1985), 22.
258
Anthony Reid. Religious Pluralism as an Asian Tradition dalam Risakotta.
Dealing with Diversity: Religion, Globalization, Gender, and Disaster in
Indonesia. (Yogyakarta: Indonesia consorioum for Religious Studies, 2014), 46.
259
Imam Suprayogo. Metodologi Penelitian Sosial Agama. (Bandung:
Rosdakarya, 2013), 122.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 19
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
gugoh tuhon dan takhayul.260 Implikasinya dianggap bentuk
okultisme yang harus dimusuhi, sehingga pergumulan teologis
komunitas Kristen Tegalombo berlangsung di lingkungan yang
tertutup dan terasing.
Philip Van Akkeren menggambarkan bagaimana kontradiksi sengit
antara kekristenan yang tumbuh diseputar tradisi budaya
masyarakat Jawa (Kejawen) dengan kekristenan “murni” di bawah
misionaris resmi dari pusat-pusat pekabaran Belanda.261 Maka
secara spesifik hal ini menunjukkan rasionalisasi dari pola awal
transfer pengetahuan yang dilakukan oleh Tunggul Wulung dengan
penyesuaian perilaku masyarakat. Penyesuaian ini terjadi karena
adanya kepentingan kuasa dan menjaga kepercayaan yang identik
dengan daya kekuatan alam, yang mengharuskan adanya
keseimbangan manusia, alam dan dunia transenden. Maka dalam
sistem masyarakat Jawa penyesuaian kultural historis berada dalam
posisi terpinggirkan. Berbenturan dengan agama-agama yang
telahlebih dulu mapan dan memiliki jaringan luas. Bagian yang
kemudian menunjukkan konsistensi keberhasilan Tunggul Wulung
dapat dilihat dari teologi pinggiran yang dikembangkan Tunggul
Wulung dan komunitasnya agar tetap hidup meskipun berada
dalam dinamika pasang surut perjalanan sejarah gereja lokal.262
Tunggul Wulung memanifestasikan pengajaran Kristen melalui
pengobatan, pendidikan, literatur dan pelayanan-pelayanan sosial,
iman, dan nalar.263 Gagasan Tunggul Wulung dalam menghayati
260
Pradjarta Dirjosanjoto, Pudjaprijatma, Josien Folbert. Menyimak Tuturan
Umat: Upaya Berteologi Lokal. (Salatiga: Percik, 2010), 40.
261
Akkeren P W. Dewi Sri dan Kristus: Sebuah Kajian tentang Gereja Pribumi
di Jawa Timur. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 23.
262
Agama mendukuing sub sistem lain dalam struktur sosial. Sebaliknya sosial,
politik, ekonomi memungkinkan agama mengembangkan ajarannya. Taufik
Abdulah. Agama, etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi. (Jakarta: LP3ES,
1978). p. 23.
263
Tobing D I. Kristologi Non Apologetis: Kristologis Hermeneutis di dalam
Konteks Postmodern dalam Y. A.A. Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di
Indonesia Buku Penghormatan Prof. Dr. Sularso Sopater. (Jakarta: BPK Gunung
20| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
kristianitas harus dilakukan secara pribadi. Dengan mempelajari
dan mengenal kebenaran-kebenaran dan janji-janji Allah melalui
Firman Tuhan (Alkitab) secara pribadi, maka keseimbangan
spiritual, emosional akan terbangun. Sebagai pendukung, tujuan
Tunggul Wulung mengharuskan masyarakat bisa membaca dan
menulis sebagai jalan menyampaikan kebenaran Injil. Tunggul
Wulung menerjemahkan Alkitab, buku-buku Kristen ke dalam
bahasa lokal, bahasa kawi. Transfer pengetahuan ini dinilai selain
mengajarkan keagamaan, juga agar masyarakat sadar pentingnya
membaca agar memahami kebijakan pemerintah yang tidak
menguntungkan untuk pribumi. Dalam pemikiran Tunggul Wulung
literasi menjadi pondasi utama mengangkat derajat dari
kemiskinan, sarana membangun akumulasi karakter yang diakui
bersama sebagai sebuah identitas, sehingga apa yang harusnya
dibangun dalam keagamaan adalah kerukunan dan perlawanan
terhadap segala bentuk hegemoni.264
Pemikiran Tunggul Wulung mengenai pengajaran Kristen di
Tegalombo menampilkan adanya spiritualitas, diimbangi asketisme
serta kesadaran politik untuk menentukan hak nasib sendiri,
resistensi atas represi kolonial yang secara implisit menampilkan
keinginan hidup bersama dalam suasana demokrasi. Ajaran yang
dibawa Tunggul Wulung, tidak saja peduli pada aspek keselamatan,
tetapi juga menyentuh dimensi-dimensi kemanusiaan yang lebih
luas. Tunggul Wulung berani menantang ketidakadilan, memimpin
pemberdayaan penduduk, dan menstimulasi unsur-unsur utama
demokrasi. Kristianitas dipahami sebagai agama pembebasan, yang
akan memberikan sokongan dan wujud saling ketergantungan
dalam membangun kesejahteraan bersama sebagai bentuk kasih.
Misi diterjemahkan sebagai transformasi dan partisipasi. Sehingga
dalam hal ini pengetahuan dianggap menjadi pembentuk utama
Mulia, 2004), 45.
264
Rakhmat. Bangunan Agama dan Toleransi dalam Hardianto. Agama dalam
Dialog: Pencerahan, pendalaman, dan Masa Depan. (Jakarta: BPK Gunung
Mulia, 2001), 92.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 21
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
kesadaran setiap individu untuk mengembangkan segala potensi,
menghapus ketidakberdayaan, dan mengukuhkan jati diri sebagai
individu bebas dan merdeka.
Kontradiksi wacana Kristianitas dalam serat Dharmogandul
dan real life contextKomunitas Kristen Tegalombo Pati.
Agama tidak pernah terdefinisikan secara formal dalam sistem
pemerintahan, hanya saja indikator agama yang diakui
dikembangkan oleh lembaga keagamaan. Beberapa indikator
agama di Nusantara antara lain ditunjukkan dengan adanya afiliasi
internasional, memiliki pengikut, memiliki konsep kenabian, kitab
suci dan memiliki wilayah asal. Implikasinya, status agama lokal
yang tidak memiliki afiliasi internasional dianggap sebagai bentuk
bid’ah.265 Secara historis,geneologydari konteks ini telah
berkembang di Nusantara dan tergambarkan dalam serat
Dharmogandul dalam bentuk pertentangan antar agama.
Penggambaran ini dinarasikan dalam bentuk wacana saling tuduh
sebagai “Kafir”. Berikut sensitifitas yang digambarkan dalam serat
Dharmogandul:“Angandika Sri Narendra/ yen mangkono sira
pinasthi kapir/ Ki Sabda palon umatur/ kulo kapir punapa/ wong
netepi agama betuwah luhur/ kang tetap kapir punika/ purun tilar
gumi luri”.266
Pertentangan ini menunjukkan adanya ketidakterimaan akan
eksistensi yang lain, yang dinilai mereduksi kemasyuran yang
sudah mantap sebelumnya.Sensitifitas tersebut juga
menggambarkan adanya ketidakberdayaan akan kuasa pendominasi
dalam menyebarkan kepercayaan sebagai yang ideal. Sifat nativism
yang menginginkan adanya “Njawa” terhadap agama Budi
265
Rafiq. Eksistensi Agama Lokal di Indonesia: Agama Kaharingan di
Masyarakat Adat Dayak Maratus; Diskusi Publik Agama dan Budaya
LokalLABEL UIN Sunan Kalijaga dan AIFIS. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2014), 39.
266
Damar Sasangka, Dharmogandhul,314.
22| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
(kesadaran) menunjukkan bentuk perlawanan untuk mengkritik
konservatisme Islam, dan juga pencarian dukungan dengan
mendukung agama Kaweruh dari pemerintah Kolonial. Pola
gagasan yang digambarkan dalam mewacanakan diskursus
kristianitas dalam serat Dharmogandul menunjukkan pengaruh
kuasa dominasi terhadap keagamaan yang berkembang bahkan juga
dijadikan sebagai media dalam menyerang lawan dan tatanan yang
telah mapan.Ketimpangan terbangun ketika diskusus kristianitas
dalam serat dibangun dengan kesadaran ketidakseimbangan antar
agama. Melihat sensitifitas dan ketidakterimaan akan pergeseran
peradaban ini mengarahkan pada pengidealan satu agama dengan
menilai yang lain lebih rendah.
Agama dan kuasa selain terlihat dalam serat Dharmogandul juga
tampak dari respon pemerintah terhadap Kristen Kejawen yang
ditransfer Tunggul Wulung. Agama sebagai bagian politik
kekuasaan pemerintah menjadi politik identitas keagamaan yang
memposisikan agama Kristen sebagai agama ideal. Hal ini juga
telah ditunjukkan dari awal kedatangannya ke Nusantara dengan
semboyan gold, glory, dan gospel. Dalam konteks sosial misionaris
Kejawen seperti Tunggul Wulung mengalami persinggungan baik
dari pemerintah Kolonial, maupun indigeneous people yang
berbeda kepercayaan.267 Konteks ini menunjukkan bagaimana
kewibawaan agama juga menjadi bagian penting dalam sebuah
komunitas sebagai identitas.268 Percampuran disatu sisi dinilai
sebagai media memperoleh simpati, disisi lain menjadi bentuk
sinkretis yang dinilai bid’ah dan tidak berdasar. Sama halnya
267
Headley. Jesus in Java: an Orthodox experiences. Revue Francaise de
I’orthodoxie No 193, 3rd, trimester, 2000, 1-14.
268
Pemerintah dalam hal ini hanya mengakui pengkabaran injil yang dilakukan
oleh zending yang menyelesaikan penidikan. Pada tahun 1888 berdasarkan usul
pdt.Wilhelm sudah didirikan sekolah Keuchenius untuk mendiidk anak-anak
Kristen yan akan menjadi guru sekolah dan guru ngaji. Sedangkan dalam
konteks ini Tunggul Wulung menggunakan cara/pola tradisional dengan
menggunakan piling, dan pencarian kesakten untuk menunjukkan dirinya sebagai
agency atau ditokohkan. Lihat J D Wolteerbeek. Babad Zending di Pulau Jawa.
(Yoyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1995), 190.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 23
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
dengan muatan gagasan yang terdapat dalam serat Dharmogandul
bahwa sensitifitas atas konservatisme dan fanatisme melahirkan
penyerangan-penyerangan akibat daya tarik, energi, dan sumber
daya keagamaan yang mulai luntur.
Serat Dharmogandul melahirkan diskursus kristianitas yang
dihadirkan sebagai tandingan dari konservatisme Islam.269
Sensitifitas ini menunjukkan ketidakmampuan individu
menyatukan religiusitas, keimanan dan kebebasan. Spiritualitas
belum mengarah pada penghayatan akan keagamaan dan kehidupan
sosial yang seimbang. Sehingga dalam hal ini masih terdapat
perbedaan pendapat. Bahkan dalam konteks pencarian kebenaran
dilakukan dengan mengintimidasi kepercayaan lain, bukan
penghayatan akan keimanan untuk perdamaian. Sensitifitas yang
digambarkan dalam serat Dharmogandul tidak memiliki dasar
pijakan yang kuat dalam mewacanakan keagamaan. Dalam kondisi
ketidakterimaan, diskursus kristianitas dihadirkan dalam serat
Dharmogandul sebagai narasi dari yang patah, sehingga perlu
dikontekstualisasikan kembali dengan kondisi real life context.
Perjumpaan kepercayaan lokal, Hindhu, Budha, Islam dan Kristen
baik yang termuat dalam pemikiran Kiai Ibrahim Tunggul Wulung
maupun dalam serat Dharmogandul menujukkan kontradiksi dan
perbandingan dalam mengakomodasi wacana perjumpaan beberapa
agama.270 Serat Dharmogandul mengakomodasi sensitifitas dan
kebimbangan pijakan dalam mewartakan ajaran Kristen, sedangkan
dalam tataran pengajaran Kristen di komunitas Tegalombo
menampilkan adanya spiritualitas, diimbangi dengan asketisme
serta kesadaran politik untuk menentukan hak nasib sendiri,
resistensi atas represi kolonialisme yang secara implisit
menampilkan keinginan hidup bersama dalam suasana demokrasi.
Serat Dharmogandul menunjukkan daya tarik energi dan sumber
269
Boogert. Rethinking javanesse Islam: Towards Javanesse Islam: Towards new
Description of Javanesse Tradition. (Leiden: University Leiden, 2015), 217-237.
270
Beatty. Varieties of Javanese Religion: An Antropological Account.
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999),18.
24| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
daya keagamaan yang mulai luntur. Sedangkan dalam pemikiran
Tunggul Wulung menunjukkan adanya humanisme religious yang
merupakan tataran lebih tinggi dari religiusitas, suatu penghayatan
akan keagamaan dan keseimbangan dengan kehidupan sosial.
Diskursus kristianitas dalam serat Dharmogandul menunjukkan
mekanisme peminggiran terhadap konservatisme Islam dan
glorifikasi agama Kristen sebagai era harapan baru. Mekanisme
peminggiran yang beriringan ini menunjukkan fungsionalistik
progresif bahwa apa yang terbangun sebelumnya dari agama Budi
merupakan suatu kesadaran yang mulai dilunturkan oleh Islam dan
Kristen memberikan harapan baru terhadap pembaharuan
modernitas.271Progesifitas itu bila ditelaah merupakan bentuk
dorongan yang sejalan dengan harapan pemerintah kolonial untuk
melakukan pembaharuan, dan pembawaan Kristen sebagai
pedoman kehidupan modern.272 Hal tersebut menunjukkan bahwa
sensitifitas serat Dharmogandul tidak hanya sebuah usaha
berteologi dari seorang Jawa melainkan merupakan bentuk
penggambaran akan kondisi yang berkembang saat itu.
Menunjukkan pula bagimana kemudian pemerintah kolonial
dengan cara intelektual menanamkan idealitasnya pada pribumi.
Sehingga pribumi dalam hal ini tidak hanya mengikuti karena
kuasa dominasi juga dengan keputusasaan dari yang terjajah karena
merasa memiliki.
271
R. W Hefner. Of Faith and Commitmen: Christian Conversation in Muslim
Java. (London; University Of California Press, 1993),111.
272
Modernitas dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai pengunaan teknologi,
maupun embukaan pasar bebas. Karena sejatinya modernitas merupakan pola
pikir, sehingga dalam hal ini system mentalitas modern menjadi sanat penting.
Pemerintah sejalan dengan semboyannya gold glory dan gospel menhendaki
agama Kristen yang akan menjadi bagian dari system mentalitas modern, bukan
agama lainnya. Bahkan dalam struktur social terjadi perbenturan antara
pemerintah kolonial dengan entitas komunitas muslim yang disebabkan karena
sensitifitas sebagai ancaman terhadap keberadaannya. Semakin mudah untuk
dipahami mengingat dalam sejarahnya di Barat perbenturan antara islam dan
kekuatan Eropa termasuk di dalamnya Kristen. Wilfred Canwell Smith. Islam In
Modern History. (Canada: The New American Library, 1959),100.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 25
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Mekanisme polarisasi dan kategorisasi secara berkesinambungan
digunakan untuk mewacanakan agama Budi, Islam dan Kristen
dalam serat Dharmogandul. Penggunaan istilah prediktatif negatif
terhadap Islam secara berulang digunakan untuk mempertanyakan
kebenaran Islam dan merusak tatanan konservatisme sehingga
melahirkan ideal agama Budi maupun Kristen, misalnya;
“Tugu iyasaning nabi/ nabi niku gih manusa/ kawulanira Hyang
manon/ yang sekadar diberi wahyu/ yang cerdas dan tajam
ingatannya/ diberi anugerah terang kesadarannya/ tahu hal yang
belum terjadi. ... dene kawula udani/ wujude nagari mekkah/
manusane arang cewok/ tanah padhas awis toya/ tanem tuwah tan
medal/ panas banter awis jawuh/ kong wang budi ahli nalar. ...
nagri tanah jawi ngriki/ nagari kang suci mulya/ madya asrep lan
panase/ tanah pasir mirah toya/ barang tinanem medal/ jaler
bagus esti ayu/ madya luwes kang wicara.”273
Pola polarisasi dan katergorisasi dengan penyebutan positif dan
negatif untuk menggambarkan citra suatu penganut kepercayaan
menunjukkan ketidakpahaman spiritualitas yang tinggi.
Pada konteks pemikiran Kiai Ibrahim Tunggul Wulung
menunjukkan adanya kontradiksi dengan apa yang diwacanakan
dalam serat.274 Tunggul Wulung menggambarkan ungkapan iman
yang dapat direfleksikan melalui iman dan nalar. Dalam konteks
kehidupan sosial, komunitas Tegalombo-Pati dibawah pemikiran
Kiai Ibrahim Tunggul Wulung yang diterima sebagai mentalitas
menunjukkan cara pandang hunamis. Perbedaan dalam
kepercayaan dipandang sebagai suatu harmoni, suatu kekuatan
bersama untuk mewujudkan kebersamaan dalam keberagaman.
Kristen dalam pemikiran Tunggul Wulung memberikan dasar
terbangunnya keseimbangan, kesetaraan dan pengakuan akan
martabat yang lain. Humanisme religious Tunggul Wulung untuk
273
Damar Sasangka, Dharmogandhul, 179.
274
C Groenen. Sejarah Dogma Kristologi: Perkembangan Pemikiran tentang
Yesus Kristus pada Umat Kristen. (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 13.
26| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
menciptakan peradaban humanitarian dilakukan dalam
menstransfer ajaran Kristen dengan tanpa paksaan.
Peran Kiai Ibrahim Tunggul wulung pada masa penjajahan diakui
sebagai seorang Kiai oleh masyarakat yang notabenenya tidak
semua menganut Kristen. Hal ini menunjukkan luhurnya budi
pengatahuan dan proses pembawaan ke arah peradaban. Cara-cara
yang dipilihnya menggambarkan bagaimana kapasitas Tunggul
Wulung sebagai agency membentuk peradaban kehidupan ke arah
kesejahteraan, kemandirian dan jati diri.275 Pilihan atas cara-cara
yang tersedia dan digunakan untuk mewujudkan konsep
pemikirannya merupakan alasan yang menjelaskan tindakan. Hal
inilah yang kemudian dapat dikatakan sebagai proses pembentukan
mentalitas sosial, sehingga membentuk pola pikir, laku dan dasar
membangun jati diri bangsa. Tindakan Tunggul Wulung dalam
konteks saat itu, menunjukkan kelapangan pikiran yang
memandang kesejajaran, pembebasan dan kepemilikian jati diri
harus di bangun dengan mengupayakan kemandirian sebagai
bentuk harga diri dan eksistensi.
Tunggul Wulung melarang adanya separatisme keagamaan dan
perbedaan pandangan terhadap pemeluk agama lain276. Perbedaan
cara pandang harus dilselesaikan dengan cara dialog. Sesuai
dengan prinsip guru ngelmu yang selama ini digunakan sebagai
pendekatan dalam menyampaikan diskursus kristianitas yang
dipahaminya. Sebagian besar konteks pengajaran agama yang
didialogkan dalam bentuk jidâl di bangun dalam bentuk teologi
rukun dan toleran. Tunggul Wulung menginginkan adanya
kesetaraan dan kesatuan dalam melawan dominasi kolonial dengan
mengembangkan Kristen Kejawen. Maka, dalam konsepsi Tunggul
275
Borrong, R. P. Teologi dan Ekologi Buku Pegangan.(Jakarta: Gunung Mulia,
2001),44.
276
Pendekatan sosial kultural menyebabkan transfer pengetahuan yang
dilakukan Tunggul Wulung pada komunitasnya mampu bertahan karena
menampilkan suara nyaman bahkan saat keabsahan etikanya dipertanyakan.
Relogious mindness akan berganti menjadi religiousness.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 27
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Wulung, kesetaraan diarahkan sebagai perjuangan tanpa kelas.
Inilah yang hendak dicapai dari humanisme religious yang
ditransfernya pada masyarakat. Tunggul Wulung menghendaki
adanya networking collective memories dalam budaya rukun.
Penghayatan akan kristianitas dipahami Tunggul Wulung sebagai
bentuk pengetahuan dan pemberdayaan diarahkan untuk
membebaskan pribumi dari kesengsaraan.277 Tunggul Wulung
menyatakan pentingnya pengetahuan sebagai dasar memiliki jati
diri.278. Pengetahuan menyeimbangkan emosional, spiritual dan
rasional. Pengetahuan dalam pandangan Tunggul Wulung dinilai
menjadi akar tumbuhnya kesadaran. Tidak sekedar bentuk intuitif,
posisi pengetahuan menguatkan kapasitas potensi individu menjadi
kompetensi yang dapat digunakannya untuk survive di tengah
represi kolonial.279 Tunggul Wulung tidak menggunakan cara-cara
kekerasan dalam mengajarkan pengetahuannya dandialog menjadi
bagian penting dalam konsep pemikiran Tunggul Wulung. Hal
inilah yang semakin membuatnya memberikan penekanan akan
pentingnya pengetahuan dalam diri individu. Ajaran Kristen yang
diterima Tunggul Wulung menjadi penuntun yang memberikan
277
A Jonathan. “19th Century Christianity in Java; Kristen Jowo as a New
Dimension for Javanese Identity”. En Arche: Indonesian Journal of Inter-
Religious Studies, Vol. 1, No.1, 2011,35.
278
Seperti pilihan cara yang digunakan oleh zending kolonial dalam mewartakan
Kristen dalam konsepsi Tunggul Wulung pendidikan juga menjadi entry point
utama. Hal ini mebuktikan bahwa keterbukaan diri Tungul Wulung dalam
mengkontruksi Kristen dalam mentalitas masyarakat tegalombo tidak sekedar
menunjukkan keterputusasaan terhadap situasi dan kondisi, melainkan sebagai
jalan baru mengukuhkan eksistensi setiap individu di bawah represi kolonial.
Borrong, R. P. Teologi dan Ekologi, 45.
279
Kebebsan pada konteks ini tidak hanya mengarah pada politik. Kebebasan
juga diartikan dalam menyuarakan pendapat mempertahankan eksistensi,
memenuhi kebutuhan perekonomian. Benih kesatuan tidak akan terbentuk tanpa
upaya memenuhi kebutuhan lahiriah individu, karena dalam kondisi kekurangan,
individu akan disibukkan dengan pribadinya, tidak bergabung, berkumpul
membicarakkan kepentingan bersama. Kartiko,Pokok-Pokok,40.
28| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
pengharapan akan kebebasan, mendatangkan kesejahteraan,
kemuliaan, keberdayaan dan keberagaman.280
Tunggul Wulung membangun sistem organisasi sosial yang
dibentuk oleh agama sebagai dasar identitas bersama.281 Pilihan
cara yang menunjukkan kapasitas penerimaan masyarakat saat itu
sangat identik dengan bahasa agama. Agama melebur dalam tata
hubungan sosial dan dalam perilaku manusia secara individu atau
kelompok. Agama menjadi suatu kekuatan besar yang melahirkan
motivasi dan menciptakan integrasi. Sedangkan dalam serat
Dharmogandul, diskursus kristianitas dipandang sebagai agama
asing, berbeda dengan pemikiran Tunggul Wulung bahwa agama
Kristen Nusantara merupakan penghayatan akan spiritualitas,
pengharapan baru. Konteks sosial yang berbeda dengan
penggambaran dalam serat Dharmogandul, tidak menunjukkan
adanya penyerangan wacana, meskipun dalam konteks struktur
sosial pemikiran Tunggul Wulung berbenturan dengan pemerintah
kolonial, maupun agama agama yang telah terlebih dahulu mantap
di Nusantara.282 Menunjukkan bahwa sensitifitas dalam agama itu
dinarasikan, diimajinasikan, dibentuk untuk menyerang mentalitas
rukun.
Kesimpulan
Serat Dharmogandul menunjukkan sensitifitas dan kebimbangan
pijakan dalam mewartakan ajaran Kristen. Pola polarisasi dan
katergorisasi dengan penyebutan positif untuk Budi Hawa dan
Kristen dan negatif untuk menggambarkan Islam menunjukkan
citra suatu penganut kepercayaan dengan ketidakpahaman
280
M Kruithof. Shouting in a Dessert: Dutch Misionary Encounters With
Javanesse Islam 1850-1910. (Netherlands: Erasmus University Rotterdam,
2014), 206.
281
Ibid.,108
282
C Gulliot. Sadrach: Riwayat kristenisasi di Jawa. (Jakarta, Grafiti, 1960), 20.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 29
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
spiritualitas yang tinggi. Konteks ini menunjukkan semakin
lunturnya daya tarik agama yang disebabkan oleh konservatisme.
Sedangkan dalam tataran pengajaran Kristen di komunitas
Tegalombo menampilkan adanya spiritualitas, diimbangi dengan
asketisme serta kesadaran politik untuk menentukan hak nasib
sendiri yaitu resistensi atas represi kolonialisme yang secara
implisit menampilkan keinginan hidup bersama dalam suasana
demokrasi.
Narasi peminggiran Islam dalam serat Dharmogandhul dilakukan
secara berulang untuk menunjukkan bentuk protes terhadap ajaran
yang telah mapan. Penggunaan istilah prediktatif negatif terhadap
Islam menunjukkan kecenderungan sebagai narasi dari individu
yang patah dan merasa kalah atas kejayaan masa lalu, sehingga
menginginkan tatanan lama kembali sebagai bentuk protes atas
konservatisme Islam saaat itu. Secara umum penghidupan
diskursus kristianitas dalam serat mengambarkan keinginan
imaginer untuk mensejajarkan agama Budi Hawa dan ajaran
kristianitas yang dipahami oleh agensi menunjukkan imaginer
untuk pengharapan baru akan tatanan sosial. Konteks ini menjadi
mudah dipahami kembali ketika di hadapkan dengan konteks social
saat itu, dimana mencari pijakan dapat dilaukan dengan dua hal,
menjadi sama dengan pemerintah kolonial dan bersifat pro dengan
kolonial.
Secara fungsionalistik progresif, wacana peminggiran terhadap
Islam dalam serat Dharmogandul menggambarkan progesifitas
wacana yang dihidupkan sebagai bentuk dorongan yang sejalan
dengan harapan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial yang
menyadari arti penting sebuah teks ikut campur tangan dalam
reproduksi suatu wacana. Sehingga penerapan diskursus kristianitas
dapat berjalan seiring dengan melakukan pembaharuan dengan
tujuan utama pembawaan Kristen sebagai pedoman kehidupan
modern. Mengingat awal mula karakteristik filologi Belanda,
cenderung melihat Islam sebagai sesuatu yang tidak lebih dari
30| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
lapisan tipis dalam kesadaran kultural masyrakat Jawa. Hal ini juga
menunjukkan bahwa situasi saat itu tampak dalam peralihan dari
Hindhu-Budha yang mulai bergeser dengan corak pembaharuan
dengan keyakinan Islam dan Kristen.
Diskursus kristianitas dalam serat menunjukkan kontradiksi
dengan real life context komunitas Kristen Kejawen di Tegalombo
dibawah kepemimpinan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Pemikiran
Kiai Ibrahim Tunggul Wulung tidak terikat dengan pemerintah
Kolonial, posisinya sebagai agency yang mandiri, sehinga dalam
hal ini memiliki kebebasandalam mentransfer gagasannya. Konsep
kebebsan dalam sudut pandang Tunggul Wulung diartikan sebagai
bentuk kebebsan dari dominasi, kemampuan memenuhi kebutuhan,
kesejahteraan dan keseimbangan dalam menjunjung martabat.
Suatu bentuk spiritualitas, diimbangi dengan asketisme serta
kesadaran politik untuk menentukan hak nasib sendiri. Ajaran kasih
dalam pengajaran Tungul Wulun menjelma dalam teologi rukun,
yan saling membangun kesejahteraan bersama, dan sebagai upaya
utama membangun identitas social yang akan menguatkan
keberadaannya sebagai individu yan merdeka.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kontruksi
Kristen yang dipahami oleh masyarakat Jawa tidak hanya dibangun
berdasarkan atas penafsiran kitâbiah. Wacana dan pengetahuan
yang termuat dalam teks sastra menunjukkan adanya kapasitas
penerimaan, pola komunikasi, dan penyesuaian konteks kultur,
serta peran penting agency. Upaya-upaya pemahaman context, dan
real life context menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam
memahami narasi-narasi yang didomestifikasikans sebagai sistem
mentalitas. Tidak hanya untuk melihat orisinilitas, melainkan juga
sejauh apa dalam proses produksi dan reproduksinya memiliki
relasi kuasa dan penguasa. Menyadarkan bahwa dalam memahami
substansi isi sutau pengajaran, terlebih studi perbandingan agama,
tidak serta merta sebagai perbandingan agama formalistik. Karena
Volume 8, Nomor 2 2018 | 31
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
ketika agama dihubungkan dengan struktur social, maka menjadi
bagian dari realitas sosial.
Daftar Pustaka
Akkeren, P. V. (1995). Dewi Sri dan Kristus: Sebuah Kajian
Tentang gereja Pribumi di Jawa Timur. Jakarta: Gunung Mulia.
Ariarajah, W. (2000). Alkitab dan Orang-orang yang
berkepercayaan Lain.Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Andi Ariez & Nezar Patria. (1999), Antonio Gramchi: Negara dan
Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Anthony Reid. (2014). Religious Pluralism as an Asian Tradition
dalam Risakotta. Dealing with Diversity: Religion, Globalization,
Gender, and Disaster in Indonesia. Yogyakarta: Indonesia
consorioum for Religious Studies.
Aritonang, J. S. (2006). Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di
Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Beatty, A. (1999). Varieties of Javanesse Religion: An
Antropological Account. Cambridge: Cambridge University Press.
Boogert, J. v. (2015). Rethinking Javanesse Islam: Towards new
description of Javanesse Tradition. Leiden: University Of Leiden.
Borrong, R. P. (2001). Teologi dan Ekologi Buku Pegangan.
Jakarta: Gunung Mulia.
Bryan S Turner. (1983). Religion and Social Theory. London:
Heinemann Education Books Ltd.
David Swartz. (1997). Cultural and Power: The Sociology of Piere
Bordieu. Chicago: The University Of Chichago Press.
32| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
Dhamarsasangka. (2011). Darmagandhul: Kisah Kehancuran Jawa
dan Ajaran-Ajaran Rahasia. Jakarta: Dolphin.
Edward Said. (2001). Orietalisme. .Bandung: Penerbit Pustaka,
2001.
E Ferquson. (1987). Background of early Chriatianity. Grand
Rapid, W.B Eerdmans.
Feener, R. M. (2017). Religious Competition and Conflict over the
longue duree: Christianity and Islam in The Indonesian
Archipelago. Asian Journal of Religion and Society Vol.5, No. 1, 1-
22.
Foucault, M. (2004). Archeology of Knowledge. London:
Routhledge.
-------. (1990). The History of Sexuality: An Introduction. London:
Penguin.
Groenen, C. (1988). Sejarah Dogma Kristologi: Perkembangan
Pemikiran Tentang Yesus Kristus Pada Umat Kristen. Yogyakarta:
Kanisius.
Gulliot, C. (1960). Sadrach: Riwayat Kristenisasi di Jawa. Jakarta:
Grafiti.
Headley, F. S. (2000). Jesus in Java: an Orthodox experiences.
Revue Francaise de I'orthodoxie No.191, 3rd, trimestre, 1-14.
Hefner, R. W. (1993). Of Faith and Commitment: christian
Conversion in Muslim Java. London: University Of California
Press.
Hoekema, A. (2000). Kristus dan Kebudayaan: Suatu Pandangan
Teologi Mennonite. In Y. Pangabean, Penabur Benih Mahzab
Teologi: Menuju Manusia Baru (p. 177). Jakarta: BPK Gunung
Mulia.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 33
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Huda, N. (2005). Tokoh Antagonis. Yogyakarta: Pura Pustaka.
Imam Suprayoga, d. (2013). Metodologi Penelitian Sosial Agama.
Bandung: RosdaKarya.
J D Wolteerbeek. (1995). Babad Zending di Pulau Jawa.
Yoyakarta: Taman Pustaka Kristen.
Jonathan, A. (2011). 19th century Christianity in Java: Kristen
Jowo as a New Dimenssion for Javanese Identity. EN ARCHE:
Indonesian Journal of Inter-Religious Studies, Vol. 1, No. 1., 31-51.
Kartiko, P. (2007). Pokok-Pokok Ajaran Gereja Injili di Tanah
Jawa. Pati: Tim Penyusun Pokok-Pokok Ajaran GITJ.
Koentjaraningrat. (2014). Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: UI
Press.
Kruithof, M. (2014). Shouting in a Dessert: Dutch Missionary
encounters with Javanesse Islam 1850-1910. Netherlands: Erasmus
University Rotterdam.
Muller Kruger. (1959). Sejarah Gereja di Indonesia. Jakarta: Badan
Penerbit Kristen.
Nancy Florida. (1995). Javanesse Literature In Surakarta
Manuscripts, Vol. 1. (New York: Cornell Modern Indonesia Project.
Neil, S. (1966). Colonialism and Christian Mission. London:
Lutterworth Press.
Noorsena, B. (2003). Menyongsong Sang Ratu Adil: Perjumpaan
Iman Kristen dan Kejawen.
Patmono. (1979). Gerakan Ratu Adil di Jawa. Majalah Peninjau
No. I Vol. VI, 59.
34| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
Pradjarta Dirjosanjoto, Pudjaprijatma, Josien Folbert. (2010).
Menyimak Tuturan Umat: Upaya berteologi Lokal. Salatiga:
Percik.
Rafiq, A. (2014). Eksistensi agama lokal di Indonesia: Agama
Kaharingan di Masyarakat adat Dayak Maratus. Diskusi Publik
Agama dan Budaya Lokal LABEL UIN Sunan Kalijaga dan AIFIS
(pp. 35-39). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Rakhmat, I. (2001). Bangunan Agama dan Toleransi. In d.
Hardianto, Agama dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian dan
Masa Depan (p. 92). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Reid, A. (2014). Religious Pluralism as an Asian Tradition. In B. A.
Risakotta, Dealing with diversity: Religion, Globalization,
Violence, Gender, and Disaster in Indonesia (pp. 47-62).
Yogyakarta: Indonesia Consorium For Religious Studies.
Ricci, R. (2018). New Direction in The Study of Javanese
Literature: Reassesing ideas, methods, and theories in the study of
the literature of Java Indonesia. Jerussalem: Literacy Studies
Hebrew University of Jerusalem.
Ricklef, M. C. (2008). Religious Reform & Polarization in Java.
Singapore: ISIM REVIES 21/ SPRING.
Sasangka, D. (2011). Dharmagandhul: Kisah Kehancuran Jawa
dan Ajaran-Ajaran Rahasia. Jakarta: Dolphin.
Scherer Savitri Prastiti. (1985). “Harmony and Dissonance: Early
Nationalist Thought in Java”. Penerjemah. Jiman S Rimbo.
Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi
Nasionalis Jawa Abad XX. Jakarta: PT Sinar Agape Press.
Taufik Abdulah. (1878). Agama, etos Kerja, dan Perkembangan
Ekonomi. Jakarta: LP3ES.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 35
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Tobing, D. L. (2004). Kristologi Non-Apologetis: Kristologi
Hermeneutis di dalam Konteks Postmodern. In Y. A. A,
Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia Buku
Penghormatan 70 Tahun Prof. Dr. Sularso Sopater (p. 45). Jakarta:
BPK Gunung Mulia.
Wilfred Canwell Smith. (1959). Islam In Modern History. Canada:
The New American Library.
luthfirahman@walisongo.ac.id
Abstract: This paper engages with the theological discourse on the state of
al-Mahdi in Shi‘Shi‘iî’
Abstrak: Artikel ini mengulas tentang perbandingan diskursus teologis
tentang keadaan posisiShî‘ahteologihî‘Alquran dan
AlkitabShî‘ahkemunculanîdoktrin gereja,sama-sama menyatakan
Introduction
The notion of al-MahdîShi‘îêî“”îShi‘îêShi‘îê
îî{îShi‘îâî}{îhîl{îîâ}îShi‘îêShi‘î}îî
îShi‘î
“
”“”
Shi‘îîîShi‘îShi‘î
36| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
The State of aî
îîîwîî
î{âîîîh
îShi‘îî‘Mas‘ûd“î””
î{{îShi‘î{
îShi‘îShi‘îal{îal{â}âîalû
“Allah has promised, to those among you who believe and work
righteous deeds, that He will, of a surety, grant them in the land,
inheritance (of power), as He granted it to those before them; that He will
establish in authority their religion-the one which He has chosen for
them; and that He will change (their state), after the fear in which they
(lived), to one of security and peace: ‘‘”
Shaykh T{{î“’îâ’”
{â}â’îmujtama‘}â}
{â}âî“”
{î“Shi‘îî”””âââ{â{â}âîîîîShi‘î
{â}â’î——î
{î”îâûû}â┓”î“â”âh“”a{â“”aâ“”{â}â’î{î
îî
{â}â{î“
“””
Volume 8, Nomor 2 2018 | 37
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
}}âî
{â}â’î
’îââhMahdîMahdî”{â}â’i——î
-ââî-{îââîîîîShi‘îîîâhîâîîdîââî{î
Isaiah 11:1-9 – The Peaceful Kingdom: Jewish Messianism
This section is a space for defining Messianic concept within
Judaism and exposing Isaiah283 11:1-9 interpretation through two
commentators of Old Testament such as Joseph Blenkinshopp and
Brevard S. Childs to help give the obvious depiction of
Messianism.284The word ““”’
283
He prophesied in Jerusalem from the death of Uzziah until the middle of
Hezekiah's reign (741-701 BCE). Of noble family, he was closely connected with
the royal court and, especially under Hezekiah, was prominent in public affairs.
According to legend, he was put to death by Manasseh. The prophet protests
strongly against moral laxity; kindness, pity, and justice to the poor and
underprivileged are more significant to God than offering sacrifice. The hand of
God is predominant in all historical events, even Assyria serving only as an
instrument of Divine anger. He opposes all treaties with neighboring states;
Israel as the people of God must trust solely in Him. The people of Israel will be
punished for its sins but not exterminated; a remnant will return and renew the
link between God and the Land of Israel. Isaiah is the seer of eternal peace at the
end of days when the Lord’'s Anointed shall judge the nations. See Cecil
Roth, The Standard Jewish Encyclopedia (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1962),
971.
284
There are three types of Messianism in Israel. First, centering around the king
and the nation, expressed hope for a glorious national future under the house of
David. The second type has been apocalyptic and frequently catastrophic,
implying a divine warrior who should overthrow the heathen and establish the
kingdom of Israel. The third type of Messianism has been ethical, spiritual and
universal, almost the antithesis of the first. It has portrayed an ideal state in
which love and service actuate ruler and ruled, and the will of Jahweh is realized.
See Wilson D. Wallis, Messiahs: Their Role in Civilization (Washington:
American Council on Publ. Affairs, 1943), 5.
38| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
“1 A shoot will come up from the stump of Jesse;
A shoot will come up from the stump of Jesse;
from his roots, a Branch will bear fruit.
The Spirit of the LORD will rest on him
Volume 8, Nomor 2 2018 | 39
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
the Spirit of wisdom and of understanding,
the Spirit of counsel and of might,
the Spirit of the knowledge and fear of the Lord
And he will delight in the fear of the Lord
He will not judge by what he sees with his eyes,
or decide by what he hears with his ears;
but with righteousness, he will judge the needy,
with justice, he will give decisions for the poor of the earth.
He will strike the earth with the rod of his mouth;
with the breath of his lips, he will slay the wicked.
Righteousness will be his belt
and faithfulness the sash around his waist.
The wolf will live with the lamb,
the leopard will lie down with the goat,
the calf and the lion and the yearling[a] together;
and a little child will lead them.
The cow will feed with the bear,
their young will lie down together,
and the lion will eat straw like the ox.
The infant will play near the cobra’s den,
and the young child will put its hand into the viper’s nest.
40| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
They will neither harm nor destroy
on all my holy mountain,
for the earth will be filled with the knowledge of the LORD
as the waters cover the sea.”
“”-
——}
“”
—i’
Theology of Hope within the State of aî
îShi‘î——îîî“”“”
îShi‘î“”
î“”
î-Shi‘î
Shi‘îîîShi‘i“”
Framing Hope in The Jewish and Muslim Scriptures
Volume 8, Nomor 2 2018 | 41
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
As the Bible narrates, the children of Israel, travelled from Canaan
to Egypt to look for foods during a food crisis time. In time, they
were caged in slavery since then, they became ““”
“”“”
“”
Shi‘i’’
h-
Closing Remarks
State of Al-Mahdi and Peaceful Kingdom represent theology of
hope within the belief system of Shi'i and Jewish tradition. These
two conceptions draw upon optimism of both religious traditions in
dealing with the future. However, it does not merely draw that
optimism but also, to some extent, teaches people to make the state
and the kingdom happen from now on until the coming of the
Mahdi and Messiah through performing positive peace, which
entails true obedience, faithfulness, and worship of God. Besides,
there should be society concerning with the poor, the oppressed and
the marginalized and accordingly act with justice, righteousness
and peace both at home and toward other neighboring societies.
Bibliography
42| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
Ali, Abdullah Yusuf.The Holy Qur-an: Text, Translation, and
Commentary. Lahore: the Ripon, 1938.
Arenal, Mercedes.Messianism and Puritanical Reform: Mahdîs of
the Muslim West. Leiden: Brill, 2006.
Ayoub, Mahmoud. “The Speaking Qur’an and the Silent Qur’an: A
Study of the Principles and Development of Imami Shi‘îte Tafsîr “,
in Rippin A., Approaches to the History of the Interpretation of the
Qur’an. Oxford: Rippin, 1988.
-----. Redemptive Suffering in Islâm: a Study of the Devotional
Aspects of ʻÂshûrâʼ in Twelver Shîʻism. The Hague: Mouton, 1978.
Blenkinsopp,Joseph. The Anchor Bible a New Translation with
Introduction and Commentary. New York: Doubleday, 2000.
Childs,Brevard S. Isaiah. London: Westminster John Knox, 2001.
H{asan, Sa‘d Muh}ammad.al-Mahdîyah fî al-Islâm. Egypt: Dâr al-
Kitâb, 1953.
Kelly, Anthony.Eschatology and Hope. Maryknoll, N.Y.: Orbis
Books, 2006.
Madelung, W. “al-Mahdî“ in C. E. Bosworth et.al., The
Encyclopaedia of Islam: New EditionVolume V. Leiden: E. J. Brill,
1954.
Moltmann,Jürgen.Theology of Hope; on the Ground and the
Implications of a Christian Eschatology, 1st U.S. ed.New York:
Harper & Row, 1967.
Mughnîyah, Muh}ammad Jawâd.al-Shî‘ah fî al-Mîzân. Beirut: Dâr
al-Shurûq, 1970.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 43
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Renard,John. Islam and Christianity: Theological Themes in
Comparative Perspective. Berkeley: University of California Press,
2011.
Roth,Cecil. The Standard Jewish Encyclopedia. Garden City, N.Y.:
Doubleday, 1962.
Sachedina,Abdulaziz A. “Messianism and The Mahdi,”
in Expectation of the Millenium: Shi‘îtesm in History, Seyyed
Hossein Nasr, ed.New York: State University of New York Press,
1988.
Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein.Islamic Messianism: the idea
of Mahdî in the twelver Shîʻism. Albany: State University of New
York Press, 1981.
T{abarsî (al), Ibn al-H{asan. Majma‘ al‐Bayân, Vol.IXX-XX.
Beirut: Dâr al-Fikr, 1955.
T{abât{abâ’î (al),Muh}ammad H}usayn. al-Mîzân fî Tafsîr al-
Qur’ân,Vol. 17. Beirut: Mu’assasat al-A‘lamî, 1973.
Ṭabâṭabâʼî, Muḥammad Ḥusayn.Shiʻite Islam, 1st ed. Albany: State
University of New York Press, 1975.
Thomas, Scott M. “Isaiah’s Vision of Human Security” Isaiah’s
Vision of Peace in Biblical and Modern International Relations:
Swords into Plowshares, Raymond Cohen and Raymond
Westbrook, ed.New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Vaziri, Mostafa.The Emergence of Islam: Prophecy, Imamate, and
Messianism in Perspective. New York: Paragon House, 1992.
Wallis, Wilson D. Messiahs: Their Role in Civilization.
Washington: American Council on Publ. Affairs, 1943.
44| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
Al-T{abarsi, Ibn al-Hasan. Majma' al‐Baya>nVolume IXX-XX.
Beirut: Dar al-Fikr, 1955.
Al-T{aba>t{aba>’i>, Muh}ammad H}usayn. Al-Mi>za>n Fi>
Tafsi>r al-Qur’a>n Volume XV. Beirut: Mu’assasah al-A’la>mi,
1973.
_______. Shi’i>te>te Islam. Translated and Edited by Seyyed
Hossein Nasr. Albany: SUNY, 1977.
Arenal, Mercedes. Messianism and Puritanical Reform: Mahdīs of
the Muslim West. Leiden: Brill, 2006.
Ayoub, Mahmoud. Redemptive Suffering in Islam: A Study of the
Devotional Aspects of
‘Ashura’ in Twelver Shi’i>tesm. The Hague: Mouton, 1978.
________. “The Speaking Qur’an and the Silent Qur’an: A Study
of the Principles and Development of Imami Shi’i>te Tafsi>r ” in
Rippin A., Approaches to the History of the Interpretation of the
Qur’an. Oxford: Rippin, 1988. 178-198.
Blenkinsopp, Joseph. The Anchor Bible a New Translation with
Introduction and Commentary. New York: Doubleday, 2000.
________. Opening the Sealed Book: Interpretations of the Book of
Isaiah in Late Antiquity. Grand Rapids, Mich.: William B.
Eerdmans Pub. Co., 2006.
Childs, Brevard S. Isaiah. London: Westminster John Knox, 2001.
Fredericks, James L. Buddhist, and Christians: Through
Comparative Theology to
Volume 8, Nomor 2 2018 | 45
Reni Dikawati DkkLuthfi RahmanAlim Ruswantoro
Solidarity. Maryknoll, New York: Orbis Books, 2004.
Hasan, Sa’d Muhammad. Al-Mahdi>yya Fi> al-Isla>m. Egypt:
Da>r al-Kita>b, 1953.
Herbert, A.S. The Book of The Prophet Isaiah. London:
Cambridge University, 1973.
Madelung, W.. “Al-Mahdi>” in The Encyclopaedia of Islam: New
EditionVolume V. Edited by C. E. Bosworth, et.all. Leiden: E. J.
Brill, 1954. 1231-1239.
Meeks, Wayne A.. and Jouette M. Bassler.The HarperCollins Study
Bible: New Revised Standard Version, with the
Apocryphal/Deuterocanonical Books. New York, NY:
HarperCollins, 1993.
Moltmann, Jürgen. Theology of Hope; on the Ground and the
Implications of a Christian Eschatology.. [1st U.S. ed. New York:
Harper & Row, 1967.
Mughniyya, Muhammad Jawa>d. Al-Syi>’a Fi> al-Mi>za>>n.
Beirut: Da>r al-Shuru>q, 1970.
Nasr, Seyyed Hossein. The expectation of the Millenium:
Shi’i>tesm in History. New York: State University of New York
Press, 1988.
Renard, John. Islam and Christianity: Theological Themes in
Comparative Perspective. Berkeley: University of California Press,
2011.
Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein. Islamic Messianism: the Idea
of Mahdī in Twelver Shīʻism. Albany: State University of New
York Press, 1981.
46| Religió: Jurnal Studi Agama-agama
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat DharmogandhulA Comparative Study on
Shi‘îteResolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia
_______. “Messianism and The Mahdi,” in Expectation of the
Millenium: Shi’i>tesm in History, Seyyed Hossein Nasr, ed. (New
York: State University of New York Press, 1988), 24-34.
Smith, Wilfred Cantwell. Towards a World Theology: Faith and the
Comparative History of Religion. Philadelphia, Pa.: Westminster
Press, 1981.
Thomas, Scott M.. “Isaiah’s Vision of Human Security” in Isaiah's
Vision of Peace in Biblical and Modern International Relations:
Swords into Plowshares. Raymond Cohen and Raymond
Westbrook, ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 169-179.
Vaziri, Mostafa. The Emergence of Islam: Prophecy, Imamate, and
Messianism in perspective. New York: Paragon House, 1992.
Wallis, Wilson D.. Messiahs: Their Role in Civilization.
Washington: American Council on Publ. Affairs, 1943.
Roth, Cecil. The Standard Jewish Encyclopedia. Garden City, N.Y.:
Doubleday, 1962.
Volume 8, Nomor 2 2018 | 47
You might also like
- MWB 2019 2020 en 1602190422Document77 pagesMWB 2019 2020 en 1602190422Vladan Colakovic55% (11)
- Basics of English Speaking For Workplace RevisedDocument170 pagesBasics of English Speaking For Workplace Revisedravi96100% (4)
- Potret Konflik Umat Beragama Di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi AgamaDocument15 pagesPotret Konflik Umat Beragama Di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi AgamaDzakiyyahNo ratings yet
- Etika Sosial Terhadap Paradoks Peran Agama Dan Kebebasan Beragama Dalam Kaitannya Dengan Konflik Di IndonesiaDocument19 pagesEtika Sosial Terhadap Paradoks Peran Agama Dan Kebebasan Beragama Dalam Kaitannya Dengan Konflik Di IndonesiaRian Armansyah ManggeNo ratings yet
- Pendidikan Agama Penopang Resolusi Konflik Umat BeragamaDocument9 pagesPendidikan Agama Penopang Resolusi Konflik Umat BeragamaNuma jerichoNo ratings yet
- Project - IRDocument18 pagesProject - IRSharad panwarNo ratings yet
- Social Integration and Communal Harmony in IndiaDocument12 pagesSocial Integration and Communal Harmony in IndiaSwethan AkkenapelliNo ratings yet
- Religions 9 Peace PDFDocument202 pagesReligions 9 Peace PDFShemusundeen MuhammadNo ratings yet
- 6.+PDF Barkah Toleransi 89-111 UIN+SGD+BDG+Document23 pages6.+PDF Barkah Toleransi 89-111 UIN+SGD+BDG+ALFARIZI B.a.ENo ratings yet
- 56-Article Text-575-2-10-20210618Document15 pages56-Article Text-575-2-10-20210618Free WriterNo ratings yet
- 266-Article Text-1472-1-10-20221025Document13 pages266-Article Text-1472-1-10-20221025DonyNo ratings yet
- Religion Con Icts in Indonesia Problems and Solutions: December 2015Document7 pagesReligion Con Icts in Indonesia Problems and Solutions: December 2015AnandaNo ratings yet
- Harmony of ReligionsDocument60 pagesHarmony of ReligionsVejella PrasadNo ratings yet
- .Document1 page.Divine Mendoza0% (2)
- Communal HarmonyDocument13 pagesCommunal HarmonyAlka RanjanaNo ratings yet
- Artikel KonseptualDocument13 pagesArtikel KonseptualElfen LiedNo ratings yet
- Peran Komisi DialogDocument23 pagesPeran Komisi DialogEroNo ratings yet
- Christian Islamic Resources For Peace5Document16 pagesChristian Islamic Resources For Peace5sir_vic2013No ratings yet
- Membangun Sikap Toleransi Beragama: Dalam Masyarakat PluralDocument12 pagesMembangun Sikap Toleransi Beragama: Dalam Masyarakat PluralrikkiNo ratings yet
- Communal HarmonyDocument8 pagesCommunal Harmonytajju_121No ratings yet
- 38 224 1 PBDocument14 pages38 224 1 PBFree WriterNo ratings yet
- Artikel Agama Dan Harmoni KehidupanDocument4 pagesArtikel Agama Dan Harmoni Kehidupancantikfida167No ratings yet
- Berdamai Dengan Pluralitas Paham Keberagamaan PDFDocument26 pagesBerdamai Dengan Pluralitas Paham Keberagamaan PDFIfa IffahNo ratings yet
- Ethn166 FinalDocument13 pagesEthn166 Finalapi-613875479No ratings yet
- Sumbangan Etika Global Hans Küng Demi Terwujudnya Perdamaian Dan Relevansinya Bagi IndonesiaDocument20 pagesSumbangan Etika Global Hans Küng Demi Terwujudnya Perdamaian Dan Relevansinya Bagi IndonesiaChristianNo ratings yet
- Kontestasi Umat Beragama Studi Tentang P 40cfa247Document13 pagesKontestasi Umat Beragama Studi Tentang P 40cfa247Deni Agustian WijayaNo ratings yet
- Religion and ConflictDocument9 pagesReligion and ConflictLorraine DomantayNo ratings yet
- Religion in The Global ConflictDocument3 pagesReligion in The Global ConflictCian TolosaNo ratings yet
- Enlightenment Twitter Meme ProjecDocument2 pagesEnlightenment Twitter Meme Projecapi-712100741No ratings yet
- Unit 30Document12 pagesUnit 30Likuna NaikNo ratings yet
- Hubungan Antarumat Beragama Berspirit Multikulturalisme: AbstrakDocument26 pagesHubungan Antarumat Beragama Berspirit Multikulturalisme: AbstrakAlex ZukisnoNo ratings yet
- 4812 10261 1 SM PDFDocument15 pages4812 10261 1 SM PDFNidaNo ratings yet
- Membangun Sikap Toleransi Beragama: Dalam Masyarakat PluralDocument12 pagesMembangun Sikap Toleransi Beragama: Dalam Masyarakat PluralBESSE HANUMNo ratings yet
- Jose Rizal University Senior High School DivisionDocument7 pagesJose Rizal University Senior High School DivisionVicky PungyanNo ratings yet
- Communal Violence, Its Causes and Solutions: Mohsin Iqbal NajarDocument3 pagesCommunal Violence, Its Causes and Solutions: Mohsin Iqbal NajarShahal MuhammedNo ratings yet
- Secularism and Communalism in IndiaDocument5 pagesSecularism and Communalism in IndiaSheela MoncyNo ratings yet
- EN Pluralism and Religious Tolerance in IndDocument10 pagesEN Pluralism and Religious Tolerance in IndAsmaa ZahroNo ratings yet
- Religions Cause ConflictDocument5 pagesReligions Cause Conflictapi-340635766No ratings yet
- Kecerdasan Komunikasi Spiritual Dalam Upaya Membangun Perdamaian Dan Toleransi BeragamaDocument18 pagesKecerdasan Komunikasi Spiritual Dalam Upaya Membangun Perdamaian Dan Toleransi BeragamaVikri RamadhanNo ratings yet
- The Dead End of Dialogue by St. SunardiDocument7 pagesThe Dead End of Dialogue by St. Sunardiavatarrista309No ratings yet
- Dinamika Konflik Dan Integrasi Antara Etnis Dayak Dan Etnis Madura (Studi Kasus Di Yogyakarta Malang Dan Sampit)Document20 pagesDinamika Konflik Dan Integrasi Antara Etnis Dayak Dan Etnis Madura (Studi Kasus Di Yogyakarta Malang Dan Sampit)muchammadnorsaniNo ratings yet
- Forum 6Document2 pagesForum 6Aubrey ArizoNo ratings yet
- Twenty First Century, Religion and PeaceDocument5 pagesTwenty First Century, Religion and PeaceMushtak MuftiNo ratings yet
- Dinamika Integrasi Nasional Bangsa Indonesia (Dalam Pendekatan Kerukunan Umat Beragama) Abdul Hamid (Dosen PAI FKIP Universitas Tadulako) E-MailDocument22 pagesDinamika Integrasi Nasional Bangsa Indonesia (Dalam Pendekatan Kerukunan Umat Beragama) Abdul Hamid (Dosen PAI FKIP Universitas Tadulako) E-MailManjutz AjirNo ratings yet
- Diversity and Coexistence: Fostering Acceptance in a Diverse and Open SocietyFrom EverandDiversity and Coexistence: Fostering Acceptance in a Diverse and Open SocietyNo ratings yet
- The Basis For A Hundu-Muslim Dialogue1Document17 pagesThe Basis For A Hundu-Muslim Dialogue1Sushant NauNo ratings yet
- 63-Article Text-622-1-10-20190208Document14 pages63-Article Text-622-1-10-20190208dandi irmansyahNo ratings yet
- Islam, Negara Dan Hak-Hak Minoritas Di Indonesia: Hasbi HasanDocument18 pagesIslam, Negara Dan Hak-Hak Minoritas Di Indonesia: Hasbi Hasanmelisa bayu prasetyaNo ratings yet
- SecularisationDocument5 pagesSecularisationDev Pratap singhNo ratings yet
- Secularism in IndiaDocument37 pagesSecularism in Indiaapi-3832446100% (1)
- Religious IntoleranceDocument3 pagesReligious IntoleranceInês Guedes MartinsNo ratings yet
- Religius and Harmony in Goverment IndonesiaDocument22 pagesReligius and Harmony in Goverment IndonesiaMTs Hidayatul Mubtadi'inNo ratings yet
- Module 4Document40 pagesModule 4WINORLOSENo ratings yet
- Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan KeagamaanDocument22 pagesKuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan KeagamaanichaNo ratings yet
- Unit 11 Communalism: 11.0 ObjectivesDocument11 pagesUnit 11 Communalism: 11.0 ObjectivesMansi SinghNo ratings yet
- Religion and Peace: Global Perspectives and PossibilitiesFrom EverandReligion and Peace: Global Perspectives and PossibilitiesNukhet A. SandalNo ratings yet
- Communal HarmonyDocument3 pagesCommunal HarmonygaridiyaNo ratings yet
- Challenges of Religious PluralismDocument9 pagesChallenges of Religious PluralismtughtughNo ratings yet
- Islam Dan Hubungan Antar Agama Oleh: Sulaiman Mohammad Nur: ISSN: 0000-0000Document27 pagesIslam Dan Hubungan Antar Agama Oleh: Sulaiman Mohammad Nur: ISSN: 0000-0000M KhoirudinNo ratings yet
- Agama Dan Politik - Hubungan Yang Ambivalen Dialog Versus "Benturan Peradaban"?Document30 pagesAgama Dan Politik - Hubungan Yang Ambivalen Dialog Versus "Benturan Peradaban"?Rocky Arfan BakkaraNo ratings yet
- SecularismDocument5 pagesSecularismkathy97No ratings yet
- A Dialogue with Truth: . . . the Wise Call It by Many NamesFrom EverandA Dialogue with Truth: . . . the Wise Call It by Many NamesNo ratings yet
- Inductive and Deductive ReasoningDocument16 pagesInductive and Deductive ReasoningCedrick Nicolas Valera0% (1)
- Mechanical PunchinelloDocument1 pageMechanical PunchinelloMarco FrascariNo ratings yet
- For 18 - 25: Deficiency of Liquid Assets. On July 1, 2020, The Following Information Was AvailableDocument3 pagesFor 18 - 25: Deficiency of Liquid Assets. On July 1, 2020, The Following Information Was AvailableExzyl Vixien Iexsha LoxinthNo ratings yet
- Exercise 2.6Document4 pagesExercise 2.6mohitgaba19No ratings yet
- 2015 Eccentric or Concentric Exercises For The Treatment of Tendinopathies...Document11 pages2015 Eccentric or Concentric Exercises For The Treatment of Tendinopathies...Castro WeithNo ratings yet
- The Enlightenment Salon. Activity Unit 1 - PDF - Age of Enlightenment - Early MoDocument2 pagesThe Enlightenment Salon. Activity Unit 1 - PDF - Age of Enlightenment - Early MoMarylee OrtizNo ratings yet
- The Renaissance ArchitectureDocument18 pagesThe Renaissance ArchitectureRazvan BataiosuNo ratings yet
- These Beautiful Butterflies Up in The Sky, Send Valentine Wishes As They Flutter byDocument6 pagesThese Beautiful Butterflies Up in The Sky, Send Valentine Wishes As They Flutter byRaquel SilvaNo ratings yet
- Gavieres V Pardo de Tavera - DepositDocument2 pagesGavieres V Pardo de Tavera - DepositAnonymous srweUXnClcNo ratings yet
- Lecture 2 Sociology 2018Document5 pagesLecture 2 Sociology 2018Yasir NawazNo ratings yet
- UntitledDocument1 pageUntitledErwinNo ratings yet
- Renewal of Notarial Commission 2022-2023 For UploadDocument3 pagesRenewal of Notarial Commission 2022-2023 For UploadmacrosalNo ratings yet
- Brent Kalar - The Demands of Taste in Kant's Aesthetics (Continuum Studies in Philosophy) (2006) PDFDocument189 pagesBrent Kalar - The Demands of Taste in Kant's Aesthetics (Continuum Studies in Philosophy) (2006) PDFPatricia Silveira PenhaNo ratings yet
- Imps, Flo, MonDocument22 pagesImps, Flo, MonMDaenery KlexxxNo ratings yet
- Lavendia Portfolio PR2 ABM12 4Document28 pagesLavendia Portfolio PR2 ABM12 4PresydenteNo ratings yet
- ID-IM-SQ-E ToolDocument9 pagesID-IM-SQ-E TooltriciacamilleNo ratings yet
- Contributors To Philippine Folk DanceDocument8 pagesContributors To Philippine Folk DanceChristle Joy ManaloNo ratings yet
- Group 5 Final - 064830Document8 pagesGroup 5 Final - 064830Stephen EwusiNo ratings yet
- Psci 6601w Jaeger w11Document23 pagesPsci 6601w Jaeger w11Ayah Aisa Dan SissyNo ratings yet
- Foreign Exchange Risk Management in Bank PDFDocument16 pagesForeign Exchange Risk Management in Bank PDFsumon100% (1)
- Chapter 1: The Study of Accounting Information SystemsDocument36 pagesChapter 1: The Study of Accounting Information SystemsAliah CyrilNo ratings yet
- Worksheet 1 - Fundamental of Research MethodologyDocument3 pagesWorksheet 1 - Fundamental of Research MethodologyRichard YapNo ratings yet
- Claims Arising Under A Construction ContractDocument5 pagesClaims Arising Under A Construction ContracthymerchmidtNo ratings yet
- Mathematics P2 Nov 2012 Memo EngDocument29 pagesMathematics P2 Nov 2012 Memo Engaleck mthethwaNo ratings yet
- RIOSA v. TabacoDocument3 pagesRIOSA v. Tabacochappy_leigh118No ratings yet
- Salaria v. Buenviaje G.R. No. L 45642 DIGESTDocument2 pagesSalaria v. Buenviaje G.R. No. L 45642 DIGESTMikee BornforThis MirasolNo ratings yet
- Fme Evaluating PerformanceDocument35 pagesFme Evaluating PerformanceDr.B.THAYUMANAVARNo ratings yet
- How One Ought To LiveDocument4 pagesHow One Ought To LiveVictor HoustonNo ratings yet