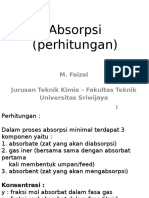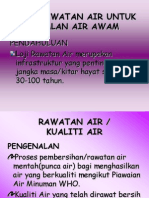Professional Documents
Culture Documents
Teknologi Air Buangan & Industri
Teknologi Air Buangan & Industri
Uploaded by
Elisabet Aprilyanti TampubolonCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Teknologi Air Buangan & Industri
Teknologi Air Buangan & Industri
Uploaded by
Elisabet Aprilyanti TampubolonCopyright:
Available Formats
TEKNOLOGI AIR DAN
BUANGAN INDUSTRI
(TKK 405)
Departemen Teknik Kimia
Fakultas Teknik
Universitas Sumatera Utara Medan
PENDAHULUAN
Air merupakan sarana utama untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.
Melalui penyediaan air yang baik, baik dari segi kualitas
maupun kuantitasnya, diharapkan penyebaran penyakit
yang diakibatkan oleh penggunaan air yang tidak bersih
dapat diminimalkan.
Peningkatan kualitas air sebagai bahan baku air minum
melalui pengelolaan yang baik mutlak diperlukan.
Sistem pengolahan air menjadi pertimbangan penting
dalam menentukan apakah sumber air tersebut layak
atau tidak untuk digunakan sebagai sumber air untuk
bahan baku air minum.
Secara garis besar, mata kuliah ini meliputi :
Air sebagai sumber daya
Pengelolaan air sebagai bahan baku air minum
Pengolahan air untuk umpan ketel dan proses
Pencemaran air dan limbah industri
Pengelolaan limbah cair dan dasar-dasar
pengolahannya
Pengelolaan limbah padat
Pengelolaan limbah gas
Industri merupakan salah satu sarana untuk
mencapai peningkatan pendapatan negara.
Kegiatan industri akan memanfaatkan segala
sumber daya, baik materi, enersi dan
manusia.
Untuk pelaksanaan proses produksinya,
industri selalu membutuhkan air.
Masalah yang ditimbulkan industri, selain
penggunaan air (baik air tanah ataupun air
permukaan), juga masalah limbah yang
dihasilkan oleh industri tersebut.
SUMBER DAYA AIR
Beberapa ketetapan Pemerintah yang
berkaitan dengan Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah PP no. 82 thn 2001:
Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di
bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas
dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam
pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau,
situ, waduk dan muara.
Permasalahan umum sumber daya air
meliputi:
Kuantitas cenderung menurun karena kebutuhan
meningkat
Kualitas air cenderung menurun akibat
perkembangan industri, pertanian, pertambangan,
penduduk dan pemukiman.
Berdasarkan PP no. 82 thn 2001:
Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan
atau diuji berdasarkan parameter-parameter
tertentu dan metoda tertentu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4
(empat) kelas :
Kelas satu untuk air baku air minum, dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan.
Kelas dua untuk prasarana/sarana rekreasi air,
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk
mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan
kegunaan tersebut.
Kelas tiga untuk pembudidayaan ikan air tawar,
peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut.
Kelas empat untuk mengairi pertamanan dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
Sumber Air Minum
siklus hidrologi:
Sumber-Sumber Air :
Air laut Mempunyai sifat asin, karana
mengandung garam NaCl. Kadar garam NaCl
dalam air laut 3%. Dengan keadaan ini; maka air
laut tak memenuhi syarat untuk air minum.
Air Atmosfir, air meteriologik, air hujan
mempunyai sifat agresif terutama terhadap pipa-
pipa penyalur maupun bak-bak reservoir,
sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya
korosi (karatan). Juga air hujan ini mempunyai
sifat lunak, sehingga akan boros terhadap
pemakaian sabun
Air permukaan
Air sungai Dalam penggunaannya sebagai air
minum, haruslah mengalami suatu pengolahan yang
sempurna, mengingat bahwa air sungai ini pada
umumnya mempunyai derajat pengotoran yang
tinggi sekali. Debit yang tersedia untuk memenuhi
kebutuhan akan air minum pada umumnya dapat
mencukupi.
Air rawa/danau Kebanyakan air rawa ini
berwarna yang disebabkan oleh adanya zat-zat
organis yang telah membusuk, misalnya asam
humus yang larut dalam air yang menyebabkan
warna kuning coklat. Dengan adanya pembusukan
kadar zat organis tinggi, maka umumnya kadar Fe
dan Mn akan tinggi pula. Apabila kandungan O
2
kurang sekali (anaerob), maka unsur-unsur Fe dan
Mn ini akan larut. Pada permukaan air kan tumbuh
algae (lumut) karena adanya sinar matahari dan O
2
.
Air Tanah
air tanah dangkal
air tanah dalam
mata air
Mata Air
Mata air biasanya mempunyai kualitas yang baik
jika air itu berasal dari suatu akuifer dan bukannya
rembesan air sungai yang baru menempuh jarak
pendek. Karena itu penting sekali untuk memelihara
atau mempertahankan kualitas air yang baik ini
dengan cara melindungi mata air dan sekelilingnya
dari kontaminasi kotoran manusia dan binatang.
Bak pengumpul air harus dibangun untuk
menangkap mata air dan mencegah reruntuhan.
Sumur Pantek
Sumur Gali Tangan (Hand-Dug Wells)
Pipa-pipa Rembesan ((infiltration Galleries)
PENGOLAHAN AIR
Sarana Pengolahan Air sebagai Bahan Baku Air
Minum
Pengolahan air sebagai bahan baku air minimum meliputi
tiga tahap:
- Tahap 1 adalah pengolahan secara fisik
mengurangi/menghilangkan kotoran-kotoran, lumpur,
dan pasir, serta mengurangi kandungan senyawa organik
dalam air yang diolah.
- Tahap 2 adalah Pengolahan secara kimia Dengan
penambahan senyawa kimia tertentu untuk
membantu/menyempurnakan proses pengolahan
selanjutnya. Misalnya penambahan alum untuk
meningkatkan penghilangan padatan terlarut/tersuspensi.
- Tahap 3 adalah Pengolahan bakteriologis
memunaskan bakteri-bakteri yang terkandung dalam air
melalui penambahan desinfektan.
Sarana pengolahan air sebagai bahan baku air
minum terdiri dari:
1. Bangunan pengumpul/penampung air
2. Bangunan pengendap pertama
3. Pembuluhan koagulan
4. Bangunan pengaduk cepat
5. Bangunan pembentuk flok
6. Bangunan pengendap kedua
7. Bangunan penyaring
8. Bangunan sterilisasi (desinfektasi)
9. Reservoir (Bangunan enyimpanan)
10. Pompa
1. Bangunan Pengumpulan /
Penampungan
Suatu bangunan untuk mengumpulkan air
dari suatu sumber asal air, untuk dapat
dimanfaatkan.
Fungsi menjaga kontinuitas pengaliran.
Pengelolaan bangunan pengumpulan air
secara umum meliputi:
1. Kuantitas
2. Kualitas
2. Bangunan Pengendap Pertama
Fungsi mengendapkan partikel-partikel padat
dari air sungai dengan gaya gravitasi.
Tidak ada pembunuhan zat/bahan kimia.
Penanganan pada sarana ini ditujukan terhadap:
Aliran sungai dijaga supaya aliran air pada sarana
ini laminar (tenang)
Sarana instalasi Untuk menjaga efektivitas ruang
pengendapan dan pencegahan pembusukan lumpur
endapan, maka secara periodik lumpur endapan
harus dikeluarkan.
3. Pembubuhan Koagulan
Koagulan bahan kimia yang dibutuhkan
pada air untuk membantu proses
pengendapan partikel-partikel kolloidal yang
tak dapat mengendap dengan sendirinya
(secara gravitasi).
Fungsi membubuhkan koagulan secara
teratur sesuai dengan kebutuhan (dengan
dosis yang tepat).
Alat pembubuh koagulan:
Secara gravitasi, dimana bahan/zat kimia
(dalam bentuk larutan) mengalir dengan
sendirinya karena gravitasi.
Memakai pompa (dosering pump);
pembubuhan bahan/zat kimia dengan
bantuan pemompaan.
Bahan/zat kimia yang dipergunakan
sebagai koagulan biasanya aluminium
sulfat
4. Bangunan Pengaduk Cepat
Fungsi meratakan bahan/zat kimia
(koagulan) yang ditambahkan agar dapat
bercampur dengan air secara baik,
sempurna dan cepat.
Cara pengadukan:
Alat mekanis: motor dengan alat
pengaduknya
Penerjun air: dengan bantuan udara
bertekanan
Fungsi membentuk padatan yang lebih
besar agar dapat diendapkan dari hasil
reaksi partikel (kolloidal) dengan bahan/zat
koagulan yang dibubuhkan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk-
bentuk flok :
Kekeruhan
Jenis padatan tersuspensi
pH
Alkalinitas
Koagulan yang dipakai
Lamanya pengadukan
5. Bangunan Pembentuk Flok
6. Bangunan Pengendap Kedua
Fungsi mengendapkan flok yang terbentuk
pada sarana bak pembentuk flok.
Pengendapan terjadi dengan gaya berat flok
sendiri (gravitasi).
Pengadukan dilakukan secara cepat ataupun
lambat yang dikenal dengan nama:.
Accelator Clarifier
Pulsator Clarifier
7. Filtrasi (Bangunan Penyaring)
Proses penjernihan air minum dikenal dua
macam filter:
Saringan pasir lambat (slow sand filter)
Saringan pasir cepat (rapid sand filter)
Berdasarkan bentuk bangunannya saringan
dikenal dua macam:
Saringan yang bangunannya terbuka (gravity filter)
Saringan yang bangunannya tertutup (pressure filter)
8. Bangunan Sterilisasi (Desinfektasi)
Proses desinfektasi proses pemusnahan
bakteri patogen (yang dapat menimbulkan
penyakit) dalam air yang diolah.
Proses desinfektasi dapat dilakukan dengan
beberapa cara pemanasan, penyinaran
ultraviolet, menggunakan senyawa kimia (asam
atau basa, Cu dan perak) ataupun dengan
klorinasi.
Senyawa-senyawa klor yang biasa digunakan:
Gas klor
Senyawa hipoklorit (kalsium hipoklorit atau kaporit)
[Ca(OCl2)]
Sodium klorit [NaClO2]
9. Reservoir (bangunan Penyimpanan)
Air yang telah melewati filter (saringan)
sudah dapat dipakai sebagai bahan baku
air minum. Air tersebut telah bersih dan
bebas dari bakteriologis dan ditampung
pada bak reservoir (tandom) untuk
diteruskan pada konsumen.
10. Pengolahan Air Umpan Ketel (Boiler)
Jika air dikonversi menjadi uap dalam ketel (boiler),
maka padatan tersuspensi dan padatan terlarut
dalam air akan terdeposisi dalam ketel.
Jika senyawa-senyawa ini membentuk endapan
yang melekat pada dinding disebut scales,
sementara yang tidak melekat disebut sludge atau
mud.
Senyawa pembentuk scales atau mud yang
terutama adalah CaCO
3
, CaSO
4
, Mg(OH)
2
dan
SiO
2
. Scales mempunyai konduktivitas termal
rendah yang mengakibatkan transfer panas dalam
ketel menjadi tidak effisien. Akibatnya terjadi
pemborosan dalam penggunaan bahan bakar.
Senyawa lain yang tidak diinginkan ada dalam air
umpan ketel adalah silika, minyak dan gas terlarut.
Dalam hal ini silika akan membentuk endapan
kalsium silika, sodium aluminium silikat atau
endapan silika. Minyak akan terhidrolisa
membentuk asam lemak yang mengakibatkan
terjadinya korosi pada material ketel. Gas terlarut
misalnya O2 akan mengakibatkan korosi pada
dinding permukaan ketel, sementara itu
H2S, SO2 akan merusak material ketel.
Pengolahan air umpan ketel (boiler)
meliputi tahapan-tahapan berikut:
Tahap 1 (pengolahan eksternal) untuk
menghilangkan senyawa-senyawa penyebab
terbentuknya scales (endapan), sludge,
ataupun korosi pada boiler.
Tahap 2 (pengolahan internal)
penambahan senyawa kimia tertentu untuk
menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak
hilang pada tahap 1 atau untuk mengolah air
tambahan akibat penguapan (make up water).
Pengolahan eksternal terdiri dari satu atau
dua proses berikut ini :
1. Proses pelunakan air, meliputi:
- pelunakan dengan zeolit
- proses pertukaran ion
- pelunakan dengan soda atau kapur
atau gabungan soda-kapur
2. Proses penghilangan silika dengan
menambahkan mula-mula MgO atau
Fe
2
(SO
4
)
3
dan NaOH.
3. Proses penghilangan gas-gas terlarut (deaerasi) seperti
O
2
dengan cara:
Menggabungkan efek panas dan tekanan untuk mengurangi
kelarutan O
2
dan
CO2
dalam air.
Penambahan senyawa pereduksi seperti Na
2
SO
3
, N
2
H
4
, dan
lain-lain.
4. Proses pengolahan karbonat
Proses ini dilakukan dengan menggunakan Na
2
CO
3
Reaksi: CO
3
2-
+ H
+
HCO
3
-
HCO
3
-
+ H
+
H
2
O + CO
2
pH air sebaiknya 10 - 11
5. Proses pengolahan pospat
Proses ini dilakukan dengan menggunakan senyawa
Ca
3
(PO
4
)
2
dengan pH air 10 11
Reaksi 3CaSO
4
(s) + 2 PO
4
3-
Ca
3
(PO
4
)
2
(s) + 3 SO
4
2-
Proses Pelunakan Air
Proses pelunakan air proses untuk
menghilangkan garam-garam Ca dan Mg yang
menyebabkan kesadahan air. Air sadah adalah air
yang mengandung ion-ion Ca
2+
dan Mg
2+
Ada dua jenis kesadahan, yaitu:
Kesadahan sementara (temporer) yang disebabkan oleh
ion HCO
3
-
Ca(HCO
3
)
2
CaCO
3
+ H
2
CO
3
H
2
CO
3
H
2
O + CO
2
Kesadahan tetap yang disebabkan oleh ion SO
4
2-
Jenis-jenis proses pelunakan air :
Pelunakan dengan kapur (lime softening)
Reaksi: Ca(HCO
3
)
2
+ Ca(OH)
2
2CaCO
3
+
2H
2
O
Kelemahan proses ini karena waktu kontak
biasanya singkat maka sering masih
ditemukan CaCO
3
dalam air hasil proses
timbul pengendapan (kerak) dalam jaringan
distribusi.
Pencegahan terbentuknya kerak :
Proses Karbonasi
Reaksi: CaCO
3
+ H
2
O + CO
2
Ca(HCO
3
)
2
Penambahan pospat untuk mencegah
pengerakan.
Pelunakan dengan soda (soda softening)
Jumlah soda abu sebanding dengan
kesadahan non-karbonat.
Reaksi: CaSO
4
+ Na
2
CO
3
CaCO
3
+ Na
2
SO
4
- Pelunakan dengan kapur berlebih
kesadahan magnesium karbonat
Reaksi: Mg(HCO
3
)
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
+
MgCO
3
+ 2H
2
O
pada pH > 11
Reaksi: MgCO
3
+ Ca(OH)
2
Mg(OH)
2
+ CaCO
3
Pelunakan dengan soda kapur berlebih
dihasilkan lumpur dalam jumlah relatif besar
Recovery kapur pembakaran dan
pencelupan kembali dalam air
CaCO
3
CaO + CO
2
CaO + CO
2
Ca(OH)
2
Dasar presipitasi Ca
2+
sebagai CaCO
3
dengan penambahan CO
3
2-
dan OH
-
berlebih
Ca(HCO
3
)
2
+ Ca(OH)
2
2 CaCO
3
+ 2 H
2
O
~ disebut TCH
Mg(HCO
3
)
2
+ 2Ca(OH)
2
2 CaCO
3
+2 H
2
O
+ Mg(OH)
2
~ disebut TMH
TCH : Temporary Calcium Hardness
TMH : Temporary Magnesium Hardness
MgCl
2
+ Ca(OH)
2
Mg(OH)
2
+ CaCl
2
MgSO
4
+ Ca(OH)
2
Mg(OH)
2
+ CaSO
4
~ disebut PMH
PMH : Permanent Magnesium Hardness
CO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
+ H
2
O
M SO
4
+ Na
2
CO
3
M CO
3
+ Na
2
SO
4
M Cl
2
+ Na
2
CO
3
M CO
3
+ 2 NaCl
M : Ca atau Mg
Jumlah kapur Ca(OH)
2
dibutuhkan :
= (TCH + 2TMH + PMH)(74/100 + ppmCO
2
)
(74/44) mg/liter
74 : BM Ca(OH)
2
44 : BM CO
2
Kesadahan dinyatakan dalam ppm CaCO
3
Jumlah soda abu Na
2
CO
3
dibutuhkan :
= (PCH + PMH) ( 106/100 ) mg/liter
106 : BM Na
2
CO
3
Contoh soal
1. Hitunglah jumlah alum yang digunakan
(BM = 342) dalam kg/10
6
liter air dengan
dosis 7 mg/liter. Jika air mengandung 2,5
mg/liter alkalinitas bikarbonat, berapa
Ca(OH)
2
dibutuhkan agar terjadi reaksi
sempurna dengan alum ?
Penyelesaian
Untuk 1 liter air dibutuhkan 7x10
-6
kg alum.
Jadi alum perlu = 7 x 10
-6
x 10
6
kg
= 7 kg per 10
6
liter air
a. Al
2
(SO
4
)
3
+ 3 Ca(HCO
3
)
2
2 Al(OH)
3
+ 3 CaSO
4
+ 6 CO
2
1 mol Al
2
(SO
4
)
3
= 6 ekv. HCO
3
-
Jumlah Al
2
(SO
4
)
3
dibutuhkan :
= (2,5 x 342) / (6 x 61) = 2.33 mg/liter
b. Jumlah Al
2
(SO
4
)
3
tersisa setelah bereaksi
dengan alkalinitas bikarbonat = 7 2,33
= 4,67 mg/l
Al
2
(SO
4
)
3
+3Ca(OH)
2
2Al(OH)
3
+ 3CaSO
4
1 mol Al
2
(SO
4
)
3
= 3 mol Ca (OH)
2
Jumlah Ca(OH)
2
perlu untuk bereaksi
dengan 4,67 mg/l Al
2
(SO
4
)
3
:
= (4,67 x 3 x 74) / 342
= 3,05 mg/liter
= 3,05 kg / 10
6
liter
2. Hitunglah jumlah kapur Ca(OH)
2
dan soda
Na
2
CO
3
dibutuhkan untuk melunakkan 1
juta liter air yang mengandung senyawa-
senyawa berikut per liter :
senyawa konsent., mg/l
Ca(HCO
3
)
2
243
Mg(HCO
3
)
2
73
CaSO
4
102
MgCl
2
95
NaCl 500
Penyelesaian :
NaCl tidak menentukan kesadahan air. Mis.
Semua kesadahan dinyatakan dalam mg/l
CaCO
3
. Maka
Kapur perlu = (TCH + 2 TMH + PMH) 0,74
Soda perlu = (PCH + PMH) 1,06
TCH = 243 x 100/162 = 150 mg/l
TMH = 73 x 100/146 = 50 mg/l
PMH = 95 x 100/95 = 100 mg/l
PCH = 102 x 100/136 = 75 mg/l
Terlihat CH = 200 mg/l dan NCH = 175 mg/l
Kapur perlu/liter = (150 + 100 + 100) 0,74
= 259 mg
Untuk 10
6
liter, kapur perlu = 259x10
-3
x10
6
= 259 kg
Soda perlu /liter = (100 + 75) 1,06
= 185,5 mg/l
Untuk 10
6
liter, soda perlu = 185,5x10
-3
x10
6
= 185,5 kg
5. Pelunakan dengan pertukaran ion
(Ion Exchange process)
Tidak menghasilkan lumpur seperti proses
pelunakan
Jika kapasitas penukar ion telah
terlampaui, penukar ion harus
diregenerasi
Penggunaan umum : pelunakan air atau
demineralisasi air untuk ketel uap.
Contoh : zeolit (senyawa kompleks
sodium-alumino-silikat)
Zeolit ~ Na
2
x
Ca
2+
Ca
2+
+ Na
2
X X + 2 Na
+
Mg
2+
Mg
2
+
Air Air olahan
Regenerasi:
Ca
2+
Ca
2+
X + 2NaCl Na
2
X + Cl
2
Mg
2+
Mg
2+
Air Limbah cair
Zeolit alami : siklus natrium mempunyai
kapasitas penukar ion 200 grek / m
3
dengan kebutuhan bahan regenerasi 5
grek / grek yang ditukar.
Resin sintetis :
- siklus natrium kapasitas penukar ion
2x lebih besar, tetapi regeneran 1/2x le
bih sedikit. Harga jauh lebih mahal.
Ca
2+
Ca
Mg
2+
+ H
2
Z Mg Z + 2 H
+
2Na
2+
2Na
Regenerasi:
Ca
2+
Ca
2+
Mg Z + 2H
+
H
2
Z + Mg
2+
2Na 2 Na
Air
Penukar kation siklus hidrogen untuk proses
demineralisasi air
Penukar anion ROH R = radikal senyawa organik
HNO
3
NO
3
H
2
SO
4
SO
4
HCl + ROH Cl + H
2
O
H
2
SiO
3
SiO
3
H
2
CO
3
CO
3
Regenerasi basa kuat
NO
3
NO
3
SO
4
SO
4
Cl + NaOH ROH + Na Cl
SiO
3
SiO
3
CO
3
CO
3
R
Kinerja penukar anion : kapasitas
pertukaran 800 grek / m
3
, kebutuhan
regeneran 6 grek / grek yang ditukar.
Senyawa-senyawa pengganggu proses :
1. Materi tersuspensi menutupi
permukaan media penukar ion
2. Material organik mengakibatkan
pengotoran penukar ion
Derajat kesadahan air berdasarkan kandungan
kalsium karbonat
Derajat
kesadahan
CaCO
3
(ppm) Ion Ca
2-
(ppm)
Lunak
Agak sadah
Sadah
Sangat sadah
< 50
50 100
100 -200
> 200
< 2.9
2.9 5.9
5.9 11.9
> 11.9
< PP no. 82 thn 2001 >
Pencemaran air masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, enersi
dan atau komponen lain ke dalam air oleh
kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun
sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan air tidak dapat berfungsi
sesuai dengan peruntukkannya.
PENCEMARAN AIR DAN
LIMBAH INDUSTRI
Unsur-unsur pencemar :
unsur non-konservatif yaitu unsur yang
dapat diuraikan oleh mikroorganisme,
misalnya senyawa organik.
unsur konservatif yaitu unsur yang tidak
dapat diuraikan oleh mikroorganisme,
misalnya senyawa anorganik.
buangan termal (panas), radioaktif
ataupun mikroorganisme.
Proses biodegradasi yaitu proses penguraian
senyawa kimia di dalam suatu badan air oleh
mikroorganisme menjadi senyawa lain yang lebih
sederhana.
Biodegradasi tingkat awal penguraian suatu
senyawa kimia menjadi senyawa yang berbeda
dengan senyawa mula-mula.
Biodegradasi yang dapat diterima lingkungan
penguraian suatu senyawa kimia menjadi senyawa
yang tidak berbahaya bagi lingkungan.
Biodegradasi ultimasi penguraian suatu senyawa
kimia menjadi senyawa yang sederhana, misalnya
H
2
O, CO
2
, NH
3
, dan lain-lain.
Beberapa istilah dalam penguraian
senyawa pencemar
BOD (Biochemical Oxygen Demand)
angka yang menyatakan jumlah oksigen
terlarut yang dibutuhkan untuk menguraikan
senyawa kimia organik oleh mikroorganisme.
Dilakukan dengan menginkubasi sampel
pada 20
o
C
Dikenal BOD
5
dan BOD
ultimasi
COD (Chemical Oxygen Demand)
angka yang menyatakan jumlah oksigen
terlarut yang dibutuhkan untuk
menguraikan senyawa kimia organik
dengan menggunakan bahan kimia seperti
KMnO
4
.
Nilai COD > nilai BOD
Proses eutrofikasi yaitu proses
pertumbuhan besar-besaran dari tanaman
air (eceng gondok, plankton) karena
adanya nutrisi tanaman dalam jumlah
berlebihan seperti ion fosfat dan ion nitrat.
Keseimbangan Oksigen terlarut (O2) badan air
keseimbangan proses deoksigenasi dengan
proses reoksigenasi di badan air.
Proses deoksigenasi proses penggunaan
oksigen, misalnya untuk pernafasan, dan
penguraian senyawa kimia.
Proses reoksigenasi proses penambahan
oksigen dari atmosfir atau secara buatan
melalui permukaan badan air.
Kurva O2-sag (lendutan O2)
Persamaan Streeter-Phelps
Proses deoksigenasi : - dL = K
1
L
dt
Proses reoksigenasi : - dD = K
2
D
dt
Dimana:
L = nilai BOD badan air
D = Cs C
Cs = konsentrasi O2 terlarut jenuh
C = konsentrasi O2 terlarut pada waktu tertentu
Integrasi : L = Lo e
K1t
D = Do
e-K2t
Kombinasi kedua proses :
t K
o
t K t K
o
e D e e
K K
L K
D
2 2 1
) (
1 2
1
+
=
limbah cair
Q
2
, C
2
, T
2
__________________________________
Q
1
, C
1
, T
1
Q
3
, C
3
, T
3
sungai
__________________________________
Dimana Q = debit
C = konsentrasi
T = temperatur
Dari neraca massa : Q
3
= Q
1
+ Q
2
Q
3
. C
3
= Q
1
. C
1
+ Q
2
. C
2
Apabila digabung C
3
= Q
1
C
1
+ Q
2
C
2
Q
1
+ Q
2
=================
Analog : T3 = Q
1
T
1
+ Q
2
T
2
Q
1
+ Q
2
================
Apabila digabung C
3
= Q
1
C
1
+ Q
2
C
2
Q
1
+ Q
2
=================
Analog : T
3
= Q
1
T
1
+ Q
2
T
2
Q
1
+ Q
2
================
Contoh Soal
Suatu sungai dengan debit = 2,8 m
3
/dtk, BOD
5
= 4mg/lt,
O
2
terlarut = 8,2 mg/lt dan temperatur = 17
o
C. Pada
tempat tertentu dibuang limbah cair ke sungai tersebut
dengan debit sebesar = 560 lt/dtk, BOD
5
= 50 mg/lt,
O
2
terlarut = 3 mg/lt dan temperatur 23
o
C. Apabila
kecepatan linear air sungai sesudah terjadi
pencampuran sebesar = 0,18 m/dtk, tentukanlah:
a. Debit, BOD
5
, O
2
terlarut dan temperatur air sungai
sesudah pencampuran.
b. Apabila waktu yang perlu agar O
2
terlarut mencapai
minimum selama 1,8 hari, tentukanlah jarak yang
ditempuh.
c. Tentukanlah nilai O
2
terlarut minimum
Diketahui:
Konst.pr.deoksigenasi K
1
= 0,1 x 1,047
(t-20)
hari
-1
= 0,10 (1,047
)(t-20)
Konst.pr.reoksigenasi K
2
= 0,31 x 1,022
(t-20)
hari
-1
= 0,31 (1,022
)(t-20)
Konst.pr.penghilangan BOD k = 0,1 x 1,047
(t-20)
hari
-1
= 0,10 (1,047)
(t-20)
Kand.O
2
terlarut jenuh pada 18
o
C =9 ,5 mg/lt
Penyelesaian:
Sesudah pencampuran:
BOD
5
= 2,8x4+0,56x50 = 11,7 mg/lt
2,8+0,56
DO = 2,8x8,2+0,56x3 = 7,3 mg/lt
2,8+0,56
T = 2,8x17+0,56x23 = 18
o
C
2,8+0,56
b. Waktu yang perlu agar DO min = 1,8 hari
Jadi jarak yang ditempuh:
18 hari x 0,18 m/detik x 86400 detik/hari = 28 km
c. Defisit DO pada saat DOmin Gunakan persamaan
Streeter & Phelps:
atau
t K
o
t K t K o
e D e e
K K
L K
D
2 2 1
) (
1 2
1
+
=
t K
o
t K t K o
D
K K
L K
D
2 2 1
10 ) 10 10 (
1 2
1
+
=
K
1
= 0,10x1,047
(t-20)
= 0,10x1,047
(18-20)
= 0,09 hari
-1
K
2
= 0,31x1,022
(t-20)
= 0,31x1,022
(18-20)
= 0,30 hari
-1
) 10 1 (
5
Kt
BOD
ltr mg L
x
o
/ 1 , 17
) 10 1 (
7 , 11
5 10 , 0
=
=
Lo = BODultimasi =
K = 0,01x1,047
(t-20)
= 0,10 x 1,047
(20-20)
= 0,10
Jadi:
DO jenuh pada 18
o
C = 9,5 mg/lt (dari tabel)
Jadi Defisit DO mula-mula : DO = (9,5-7,3) mg/lt
= 2,2 mg/lt
Defisit DO pada saat minimum:
= 0,09x17,1 (10
(-0,09x1,8)
-10
(-0,30x1,8)
)+2,2x10
-0,3x1,8
0,30-0,09
= 3,6 mg/lt
Jadi DO
minimum
= (9,5-3,6) mg/lt = 5,9 mg/lt
t K
o
t K t K o
D
K K
L K
D DO
2 2 1
10 ) 10 10 (
1 2
1
min
+
= =
Kecepatan reaksi penghilangan BOD
(Biochemical Oxygen Demand)
Reaksi penghilangan BOD reaksi orde satu
yang secara matematis dapat dinyatakan
sebagai berikut:
dL / dt = k L
dimana L = jumlah BOD tersisa
k = konstanta
Jika diintegralkan diperoleh :
L = Lo e
-kt
dimana Lo = BOD ultimasi
Jika y = Lo L,
maka y = Lo (1 e
-kt
)
Berdasarkan sumbernya:
Limbah domestik
Limbah industri
Berdasarkan fasanya :
Limbah cair
Limbah padat
Limbah gas
Klasifikasi Limbah
Kontaminan penting dalam limbah cair
Kontaminan Sumber Akibat
Padatan tersuspensi - Penggunaan domestik
- Limbah industri
- Erosi
- Deposit
- Kondisi anaerobik
Senyawa kimia
terbiodegradasi
- Limbah domestik dan
industri
- Defisit O
2
terlarut
Mikroorganisme patogen - Limbah domestik - Penyebaran penyakit
Senyawa nutrisi - Limbah domestik dan
industri
- Eutrofikasi
Senyawa organik refraktori - Limbah industri - Rasa, bau, karsiogenik
Logam berat - Limbah industri,
pertambangan, dll
- Toksik
Padatan anorganik terlarut - Limbah domestik dan
industri
- Berpengaruh pada
penggunaan kembali
Limbah Industri
Limbah industri hasil samping dari kegiatan suatu
industri, yang dibuang ke lingkungan karena sulit
diproses, ataupun jika diproses kembali maka biaya
operasionalnya menjadi tidak ekonomis.
Proses Pembentukan Limbah adalah sebagai berikut;
Bahan baku primer
Bahan baku sekunder
Proses
Produksi
Produk
Limbah Pengguna
Upaya pengelolaan limbah
Reduksi pada
sumbernya
Pemanfaatan limbah:
- Penggunaan kembali (Re-use)
- Daur ulang (Recycle)
- Perolehan kembali (Recovery)
Pengolahan
Limbah
Pembuangan limbah sisa
pengolahan limbah
Minimasi
limbah
Reduksi limbah pada sumbernya
meliputi:
House Keeping yang baik
Segregasi aliran limbah
Preventive Maintenance yang terjadwal
Pengolahan bahan
Pengaturan kondisi proses dan operasi
Modifikasi proses dan alat
Modifikasi/substansi penggunaan bahan
Penggunaan teknologi bersih
Pemanfaatan Limbah meliputi:
Penggunaan kembali untuk keperluan yang
sama tanpa mengalami proses pengolahan
Daur ulang menghasilkan suatu produk
setelah melalui proses pengolahan fisik.
Perolehan kembali mengambil kembali
komponen yang terkandung dalam limbah
melalui proses tertentu.
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN
DASAR-DASAR PENGOLAHANNYA
Limbah cair limbah berfasa cair, yang
umumnya berasal dari rumah tangga (domestik),
industri dan dari rembesan.
Jumlah rata-rata aliran limbah cair yang berasal
dari industri tergantung dari:
Jenisnya
besar kecilnya
pengawasan prosesnya
tingkat penggunaan air
dan tingkat pengolahan limbah cair yang ada.
Gambaran susunan bahan yang terkandung
dalam limbah cair
Padatan
(0,1%)
Senyawa
Organik
Kerikil,
pasir, dll
Limbah
Cair
Cairan
99,9%
Satuan Operasi, Satuan Proses, dan
Sistem untuk Pengolahan Limbah Cair
No Pencemar Unit Operasi, unit proses, atau sistem pengolahan
1 Padatan tersuspensi Sedimentasi
Screening dan Comminution
Penyaringan
Penambahan bahan kimia polimer
Koagulasi
Sistem pengolahan tanah
2 Bahan organik teruraikan Variasi lumpur aktif
Fixed film: trickling filter
Fixed film: rotating biological cantactora
Variasi kolam oksidasi
Saringan pasir berselang-selang
Sistem pengolahan tanah
Sistem fisika-kimia
3 Organisme penyakit Klorinasi
Hipoklorinasi
Ozonisasi
Sistem pengolahan tanah
4 Nutrisi Variasi pertumbuhan tersuspensi bakteri nitrifikasi
dan denitrifikasi
Variasi fixed film nitrifikasi dan denitrifikasi
Ammonia stripping
Penukar ion
Klorinasi pada titik pecah (break point chlorination)
Sistem pengolahan tanah
5 Pospor Penambahan garam logam
Pengendapan/koagulasi dengan C
n
O
Penghilangan secara kimia-biologi
Sistem pengolahan tanah
6 Padatan organik
teruraikan
Adsorpsi karbon
Ozonisasi tertier
Sistem pengolahan tanah
7 Logam berat Pengendapan secara kimia
Penukar ion
Sistem pengolahan tanah
8 Padatan anorganik
terlarut
Penukar ion
Osmosis balik
Elektrodialisa
Penyebaran senyawa organik dalam limbah
cair
Limbah cair
Padatan
tersuspensi
volatile
Kolloidal
Seny. Organik
terlarut
terdegradasi tidak
terdegradasi
Dapat diserap Tidak dapat
diserap
terdegradasi
Tidak
terdegradasi
Contoh Perhitungan
Suatu limbah cair mengandung 150 mg/l etilen glikol
C
2
H
6
O
2
dan 100 mg/l phenol C
6
H
6
O
Tentukan COD dan TOC
Tentukan COD pada BOD
5
Penyelesaian:
a. Etilen glikol
Reaksi: C
2
H
6
O
2
+ 2,5 O
2
2 CO
2
+ 3 H
2
O
l mg l mg x TOC
l mg l mg x COD
/ 58 / 150
62
24
/ 194 / 150
62
) 32 ( 5 , 2
= =
= =
Phenol
Reaksi: C
6
H
6
O + 7 O
2
6CO
2
+ 3 H
2
O
l mg l mg total TOC
l ml l mg total COD
maka
l mg l mg x TOC
l mg l mg x COD
/ 135 / ) 77 58 (
/ 432 / ) 238 194 (
/ 77 / 100
94
72
/ 238 / 100
94
) 32 ( 7
= + =
= + =
= =
= =
b. Jika sesudah pengolahan, nilai BOD
5
= 25
mg/l, tentukanlah besarnya COD.
Diketahui: k
10
= 0,1 / hari
COD = BOD
ultimasi
/ 0,92
Maka:
l mg
l mg
COD
maka
l mg BOD
BOD
l mg
BOD
BOD
ult
x
ult ult
/ 39
92 , 0
/ 36
:
/ 36
) 10 1 (
/ 25
) 1 , 0 5 (
5
= =
=
= =
Evaluasi Limbah Cair
No Parameter Penyimpanan atau Pengawetan Lama
Penyimpanan
1 Keasaman-kebasaan Pendingin pada 4
o
C 24 jam
2 BOD Pendingin pada 4
o
C 6 jam
3 Kalsium Tidak perlu -
4 COD 2 ml H
2
SO
4
/l sampel 7 hari
5 Klorida Tidak ada -
6 Warna Pendingin pada 4
o
C 24 jam
7 Oksigen terlarut Diukur ditempat -
8 Flourida Tidak ada -
9 Kesadahan Tidak ada -
10 Total logam 5 ml HNO
3
/l sampel 6 bulan
11 Nitrogen, amonia 40 mg HgCl
2
/l sampel pada 4
o
C 7 hari
12 Nitrogen,kyeldahl 40 mg HgCl
2
/l sampel pada 4
o
C Tidak stabil
13 Lemak dan minyak 2 ml H
2
SO
4
/l sampel pada 4
o
C 24 jam
14 Karbon organik 2 ml H
2
SO
4
/l sampel (pH=2) 7 hari
15 pH Diukur ditempat -
16 Fenol 1 gr CuSO
4
+ H
3
PO
4
hingga pH 4 24 jam
17 Pospor 40 mg HgCl
2
/l sampel pada 4
o
C 7 hari
18 Padatan Tidak ada -
19 Daya hantar listrik Tidak ada -
20 Sulfat Pendingin pada 4
o
C 7 hari
21 Sulfida 2 ml Zn-asetat/lsampel 7 hari
22 Bau Pendinginan pada 4
o
C 24 jam
23 Kekeruhan Tidak ada -
Metoda Pengolahan Limbah Cair
Tujuan pengolahan limbah cair:
Menghilangkan bahan tersuspensi dan terapung.
Menguraikan senyawa organik yang dapat terurai.
Meningkatkan tentang arti dampak buangan limbah yang
tidak diolah atau sebagian diolah terhadap lingkungan air.
Meningkatkan pengetahuan dan pemikiran terhadap efek
jangka panjang yang mungkin ditimbulkan oleh komponen
ntu dalam limbah yang dibuang ke badan air.
Meningkatkan kepedulian nasional untuk perlindungan
lingkungan
Meningkatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan
terutama ilmu kimia, biokimia, dan mikrobiologi.
Melestarikan sumber daya alam.
Mengembangkan berbagai metoda yang sesuai untuk
pengolahan limbah.
Dalam merancang suatu unit pengolah limbah,
langkah penting yang harus dilakukan:
Menentukan sifat limbah dan fluktuasinya.
Memilih periode rancangan proses.
Menetapkan kualitas hasil yang diinginkan.
Menentukan konstanta kinetik dan daya olah.
Memilih reaktor yang sesuai.
Memilih lokasi yang sesuai.
Memastikan tersedianya peralatan yang
diinginkan dan tenaga kerja.
Proses pengolahan limbah cair dapat pula
digolongkan dalam beberapa tahap
perlakuan, yaitu:
Pra-perlakuan (pre-treatment)
Perlakuan pertama (primary treatment)
Perlakuan kedua (secondary treatment)
Perlakuan ketiga (tertiary treatment)
Bahan pencemar dalam limbah cair dapat
dikurangi atau dihilangkan melalui tiga
perlakuan, yaitu:
Perlakuan/pengolahan secara fisika (satuan
operasi secara fisik)
Perlakuan/pengolahan secara kimia (satuan
proses secara kimia)
Perlakuan/pengolahan secara biologi (satuan
proses secara biologi)
Pengolahan secara Fisika (Satuan
Operasi secara Fisik)
Dua prinsip utama yang dapat dipakai
untuk pemisahan partikel-partikel padat
dari air, yaitu:
Screening (penapisan), penyaringan
pemanfaatan gravitasi misalnya
pengendapan, pengapungan (floatasi), dan
sentrifuge.
Penapisan
Fungsi memisahkan potongan-potongan kayu,
plastik, dan bahan yang berukuran besar lainnya.
Alat penapis berupa kisi-kisi yang lurus atau bengkok
dan dipasang dengan sudut kemiringan antara 75-90
derajat. Keefektifannya tergantung pada jarak diantara
kisi-kisi.
Beberapa contoh penapis, yaitu:
Hand-Cleaned Bar Screen (Kisi penapis yang dapat
dibersihkan dengan tangan)
Penapis bengkok
Penapis lurus, berfungsi otomatik
Basket screen (penapis keranjang)
Grit Chambers
Tujuan:
Menghilangkan bau kerikil, pasir, dan
partikel-partikel lain yang mungkin
mengakibatkan penyumbatan dalam pipa.
Mencegah pompa dan alat-alat istilah yang
dipakai untuk menghilangkan atau membuang
bahan padat dengan ukuran partikel lebih
kecil hingga 0,2 atau 0,1 mm.
Saringan (Strainers)
Kecepatan pengendapan partikel dinyatakan berdasarkan
hukum Stokes sebagai berikut:
Dimana, Vs : kecepatan pengendapan
g : percepatan gravitasi
: densitas partikel
s : densitas fluida tersuspensi
D : diameter
: viskositas molekuler fluida tersuspensi
Persamaan di atas berlaku apabila bilangan Reynold partikel
(Re) lebih kecil dari 2. Bilangan Reynold didefinisikan
sebagai:
18
) (
2
d g
V
s
s
=
d V
R
s
s
=
batas kecepatan pengendapan minimum adalah:
dimana, D : kedalaman tangki
t : waktu tinggal hidraulis rata-rata
Dalam aliran kontinyu, waktu tinggal ini dirumuskan sebagai berikut:
dimana, AD : volume tangki = V
A : luas permukaan tangki
Q ; denit aliran
Dari kedua persamaan tersebut diatas dapat dirumuskan:
Bentuk Q/A ini disebut sebagai laju aliran atas (over flow rate)
t
D
V
s
=
Q
AD
V
s
=
A
Q
V
s
=
Contoh Soal
Tangki pengendapan sirkuler dengan waktu
tinggal 4 jam dan kecepatan overflow
maksimum sebesar 20 m
3
/m
2
.hari. tentukan
diameter tangki dan kedalaman air dalam tangki
jika kecepatan alir rata-rata air ke dalam tangki
sebesar 6 Ml/hari.
Penyelesaian
V = Q x TD
= 6 Ml/hari x 1/24 x 4
(1 Ml = 10
6
l = 10
3
m
3
)
Q = 6 ml/hari
= 6 x 10
3
/hari
A
Q
V
o
=
2
2 3
3 3
300
/ 20
/ 10 6
m
hari m m
hari m x
A
Q
A
o
= = =
2
4
D A
H
=
m
x A
D 60
14 , 3
300 4 4
~ =
H
=
Kedalaman air dalam tangki =
m
m
m
A
V
33 , 3
300
10
3
3 3
= =
Pengolahan Tahap Pertama (Pengolahan
secara Kimia)
Keuntungan pengolahan secara kimia adalah:
Pembersihan bahan pencemar hampir sempurna
dan bahan pencemar anorganik dapat diperoleh
kembali.
Bahan pencemar beracun yang dapat menghalangi
atau menghentikan proses pengolahan secara
biologi berikutnya tidak ada.
Pengolahan secara biologi sangat peka terhadap
perubahan konsentrasi. Oleh karena itu
memerlukan waktu penyesuaian yang lama,
sedangkan proses kimia tidak.
Kelemahannya:
Meningkatkan kandungan garam logam menambah
jumlah lumpur.
Metoda-metoda pada proses pengolahan limbah
cair secara kimia:
Penetralan bahan buangan yang bersifat asam atau
alkali.
Pemisahan bahan organik terlarut sebagai koloidal
Pembersihan bahan organik terlarut sebagai koloidal
Pembersihan sisa-sisa minyak dan lemak
Pengapungan dan penyaringan
Pengoksidasian bahan-bahan beracun atau bahan
tak teruraikan
Netralisasi
Proses netralisasi yang umum dipakai
adalah:
Netralisasi asam dengan alkali atau
sebaliknya
Penambahan bahan kimia
Penyaringan melalui bahan netral misalnya
kalsium karbonat (CaCO
3
)
Kemungkinan netralisasi dari aliran
tergantung pada proses produksi yang
dipakai. Jenis netralisasi ini sangat umum
dalam pengolahan yang diikuti penukar
ion.
Netralisasi buangan limbah cair dapat dilakukan
dengan:
penambahan Ca(OH)2 (kalsium hidroksida),
NaOH (natrium hidroksida),
CaCO
3
(kalsium karbonat), atau
Na
2
CO
3
(natrium karbonat),
Proses netralisasi dipengaruhi oleh
bahan bahan kimia yang akan dinetralkan,
jumlah limbah cair, dan
keadaan setempat
Pengendapan dengan penambahan bahan
kimia
Dalam pengolahan limbah cair industri
proses pengendapan dilakukan untuk:
menghilangkan logam berat beracun
menghilangkan sulfat
menghilangkan fluorida
menghilangkan pospat
Proses pengendapan ini dapat dijelaskan dengan
persamaan kimia sebagai berikut:
CuCl2 + NaOH Cu(OH)2 + 2 NaCl
Cd(NO3)2 + Ca(OH)2 Cd(OH)2 + Ca(NO3)2
NiCl2 + NaOH Ni(OH)2 + s NaCl
Fe2(SO4)2 + 3Ca(OH)2 2Fe(OH)3 + 3CaSO4
coklat putih
2NaF + Ca(OH)2 CaF2 + 2 NaOH
Bahan-bahan pembentuk kompleks seperti NTA
(nitrilo triacetic acid) atau EDTA (ethylene
diamine tetra acetic acid)
Tidak membentuk endapan dengan logam-logam
berat, tetapi membentuk senyawa kompleks.
Untuk proses penguraian dapat ditambahkan
garam-garam besi dan polimer tertentu, ataupun
senyawa yang mengandung gugus sulfida
(dengan berat molekul 60.000-100.000) yang
menghasilkan endapan dengan sifat-sifat
flokulasi yang baik bila bereaksi dengan logam
berat.
Endapan sulfat dalam limbah cair
Dengan konsentrasi sulfat yang tinggi
mengakibatkan pengkaratan pada bahan pipa
dan tangki.
Konsentrasi sulfat sebesar lebih kurang 2.500
mg/l diperoleh dengan penambahan kalsium
hidroksida. Selanjutnya, ditambahkan pula
kalsium aluminat agar konsentrasi sulfat turun
menjadi 50 mg/l.
Pengendapan fluorida
Pengendapan fluorida dengan menggunakan kalsium
hidroksida menghasilkan konsentrasi fluorida dalam
limbah cair hingga 30-40 mg/l. Penambahan kalsium
aluminat dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi
fluorida yang tersisa sebesar di bawah 3 mg/l.
Pengendapan posfat
Pengendapan pospat terutama dalam pengolahan
limbah cair bertujuan untuk mengurangi eutrofikasi air
permukaan. Pengurangan atau penghilangan pospat
dari limbah cair penduduk dapat dilakukan dengan
metoda yang berbeda-beda misalnya penambahan
kalsium hidroksida, garam besi, dan aluminium.
Koagulasi dan Flokulasi
Tujuan untuk mengubah bahan
pencemar dalam bentuk tersuspensi dan
koloid yang relatif halus menjadi bentuk
yang lebih besar dengan cara
penggabungan. Dengan demikian akan
mudah mengendap yang selanjutnya
dipisahkan dari limbah mudah cair.
Tahapan proses:
1. Penambahan koagulan atau flokulan
yang cepat bercampur ke dalam limbah
cair
2. Penghilangan sistem kestabilan koloid
3. Penggabungan partikel-partikel yang
tidak stabil, membentuk mikroflok
4. Penggabungan mikroflok yang kemudian
mengendap, lalu di saring atau
diapungkan.
Untuk menghasilkan kestabilan koloid
dilakukan dengan penambahan bahan kimia
yang bekerja dengan mekanisme pengikatan
atau penyerapan (adsorpsi) untuk mengurangi
gaya tolak menolak antar partikel, misalnya
muatan listrik atau sifat hidrofilik partikel koloid
(partikel koloid dalam limbah cair umumnya
bermuatan negatif).
Selanjutnya, penggabungan partikel koloid
bermuatan netral sebagai hasil dari bermacam-
macam gaya tarik menarik yang bekerja di luar
partikel.
Pengolahan tahap Kedua (Pengolahan
biologis)
Substrat
dalam
limbah
cair
O
2
mikroorganisme
Limbah
cair
olahan
Mikroorganisme
baru
+ +
Kec. pertumbuhan mikroorganisme :
dx / dt = y (dSr / dt)
Dimana X : massa padatan mikroorganisme
(MLVSS)
Sr: massa substrat terlarut BOD
t : waktu
y : koeffisien hasil
Untuk waktu tinggal relatif lama :
(dx / dt)
net
= y (dSr / dt) Kd.x
Dimana
Kd : konst. kec. penguraian senyawa
organik dalam sel
Waktu tinggal hidraulis :
t = V / Q
Dimana t : waktu tinggal hidraulis
V: volume
Q: debit alir
Umur sludge :
t
c =
massa pdtan dlm sistem per massa
pdtan keluar sistem / hari
t
c
= (x.V) / (x
.Q)
Contoh soal :
Pada suatu sistem pengolahan limbah cair
secara biologis, konsentrasi BOD
diturunkan dari 250 mg/l menjadi 30 mg/l.
Debit alir limbah = 4000 m
3
/hari, volume
reaktor = 700 m
3
dan MLVSS = 3000 mg/l.
Asumsi : y = 0,5
Kd= 0,09 hari
-1
Rasio F / M yaitu menyatakan kecepatan
penghilangan substrat per satuan padatan
dalam sistem :
F / M = (S
0
S) / x.t
Dimana S
0
: jumlah substrat awal
Penyelesaian :
Substrat hilang
= (250 30)mg/l . 4000 m
3
/hari. 10
3
/10
6
= 880 kg / hari
MLVSS = 3000 mg/l. 700 m
3
. 10
3
/10
6
= 2100 kg
Padatan dihasilkan per hari net
= y (substrat hilang) Kd.x
= 0,5. 880 kg/hari 0,09 hari
-1
. 2100 kg
= 251 kg
Umur sludge = 2100 kg / (251 kg/hari)
= 8,36 hari
Waktu tinggal hidraulis
= (700 m
3
.24 jam/hari) / (4000 m
3
/hari)
= 4,2 jam
F / M = (880 kg/hari) / 2100 kg
= 0,42 kg/hari per kg padatan
Estimasi BOD effluent :
BOD effluent total =
BOD terlarut + BOD yg keluar dlm effluent
BOD terlarut : diestimasikan dari persamaan
penghilangan substrat
Metoda pengolahan biologis :
1. sistem pertumbuhan tersuspensi :
- lumpur aktif dan modifikasinya
- aerated lagoon
- waste stabilization ponds
2. sistem pertumbuhan melekat
- trickling filter
- rotating disc
- submerged media beds
Limbah mentah
Q
(Q + Q
r
) Limbah olahan
Sludge yang diresirkulasi dibuang
Q
r
Proses Pengolahan dengan Lumpur Aktif
(Activated Sludge Process)
Aerator
Sludge
T.S = Tangki sedimentasi
T.S I
T.S II
Ciri ciri :
- alat utama : aerator
- lahan yang diperlukan relatif tidak besar
- waktu reaksi relatif singkat
- biaya operasional cukup mahal
Rasio F / M = (Q.BOD) / (V.MLSS)
Dimana Q : debit, m
3
/hari
BOD : mg/l
V : volume tangki, m
3
MLSS : mg/l
Umur sludge (waktu tinggal sel) :
t
c
= (MLSS.V) / (SS
e
.Q
e
+ SS
w
.Q
w
)
Dimana SS
e
: padatan tersuspensi dlm effluent
SS
w
: padatan tersuspensi dalam sludge
Q
e
: debit effluent
Q
w
: debit sludge
Sludge Volume Index (SVI) :
SVI = (V. 1000) / MLSS
Dimana V : volume padatan mengendap
dalam kolom 1 liter setelah 30
menit
SVI : baik, jika bernilai 50 150 mg/l
Debit sludge yang diresirkulasi :
Q
r
/ (Q + Q
r
) = V / 1000
Q
r
= (V.Q
) / (1000 V)
Dimana V : volume padatan yang meng -
endap
Padatan tersuspensi dalam sludge
yang diresirkulasi :
SS
r
= (10
6
) / SVI
SS
r
= {MLSS(Q + Q
r
)} / Q
r
Asumsi :
tidak ada kehilangan padatan tersuspensi
dalam effluent
Contoh soal:
1.Konsentrasi MLSS dalam tangki aerasi =
2400 mg/l. Volume sludge setelah 30
menit dalam kolom silinder 1 liter = 220 ml.
a. SVI = (220 ml/l. 1000) / 2400 mg/l
= 92 ml/gr baik
b. Q
r
/Q = 220 Q / {Q(1000 220)}
= 0,28
c. SS
r
= 10
6
/92
= 11000 mg/l
2. Laju alir limbah cair = 29000 m
3
/hari
Volume aerator = 8500 m
3
Influent : - padatan total = 599 mg/l
- pdtan tersuspensi= 120mg/l
- BOD = 173 mg/l
Effluent : - padatan total = 499 mg/l
- pdtan tersuspensi= 22 mg/l
- BOD = 20 mg/l
MLSS = 2500 mg/l
Laju alir resirkulasi sludge = 10000 m
3
/hari
Jumlah sludge = 200 m
3
/hari
Pdtan tersuspensi dlm sludge= 9800 mg/l
A. Waktu tinggal dalam tangki aerasi
= 8500 m
3
/(2900 m
3
/hari) x 24 jam/hari
= 7 jam
B. Beban BOD
= (173 mg/l x 29000 m
3
/hari) / 8500 m
3
= 590,24 gr/(m
3
.hari)
C. F/M = (29000 m
3
/hr.173 mg/l)/(8500 m
3
.
2500 mg/l)
= 0,24 (gr BOD / hari) / gr MLSS
D. Effisiensi penghilangan padatan total
= {(599 497) / 599 } x 100 %
= 17,03 %
E. Eff. penghilangan pdtan tersuspensi
= {(120 22) / 120} x 100 %
= 81,07 %
F. Effisiensi penghilangan BOD
= {(173 20) / 173 } x 100 %
= 88,44 %
G. Padatan tersuspensi dalam sludge
= (9800 mg/l x 200 m
3
/hari) / 1000
= 1960 kg / hari
H. Padatan tersuspensi dalam effluent
= (22 mg/l x 29000 m
3
/hari) / 1000
= 638 kg / hari
I. Umur sludge
= {(2500 mg/l x 8500 m
3
)/(638 kg/hari +
1960 kg/hari)} x 10
-3
= 8,2 hari
J. Laju resirkulasi sludge (%)
={(10.000m
3
/hari)/(29.000m
3
/hari)}100%
= 34,48 %
Proses Aerasi
Aerasi Proses perpindahan massa gas
cairan dimana gaya gerak pada
fasa gas adalah tekanan parsial
gas (P
g
) dan pada fasa cair
adalah gradien konsentrasi (C
s
C)
Perpindahan massa per satuan waktu
= k
L
. a (C
s
C)
Dimana k
L
: koeffisien film cairan
a : luas antar muka perpindahan
per satuan volume
= (luas permk. A) / (volume V)
Faktor - faktor yang mempengaruhi perpindahan O
2
:
- temperatur
- konsentrasi O
2
terlarut
- karakteristik aerator
Fungsi aerator : - input O
2
- pencampuran
Jumlah O
2
yang ditransfer di lapangan dipengaruhi
oleh :
- rasio konsentrasi O
2
jenuh dalam limbah cair
dengan
konsentrasi O
2
jenuh air distilasi
- rasio laju perpindahan O
2
dalam limbah cair
dengan laju perpindahan O
2
dalam air leiding
- ketinggian lokasi
- temperatur
Konsentrasi O
2
jenuh rata-rata :
C
s,m
= C
s
x 0,5 {(P
b
/ P
a
) + (O
t
/ BM O
2
)}
Dimana
P
a
: tekanan atmosfir
P
b
: tekanan absolut pada kedalaman tertentu
O
t
: % konsent . O
2
dlm udara keluar
Didefenisikan :
o = (C
s
limbah cair) / (C
s
air leiding)
| = (k
La
limbah cair) / (k
La
air)
Contoh soal :
Pada proses transfer O
2
(aerasi) diperoleh data
unit diffusi sbb:
Laju alir udara = 25 ft
3
/ menit
Volume = 1000 ft
3
Temperatur = 54
o
F
Kedalaman cairan dalam tangki = 15 ft
D
gelembung
rata-rata = 0,3 cm
Kec. gelembung rata-rata = 32 cm / detik
waktu, menit C
L
, mg/l
3 0,6
6 1,6
9 3,1
12 4,3
15 5,4
18 6,0
21 7,0
Dik. : Konst. O
2
jenuh (54
o
F) =10,8 mg/l
Konst. O
2
jenuh (20
o
F) = 9,1 mg/l
Konst. O
2
jenuh (32
o
F) = 7,4 mg/l
o = 0,82
| = 0,99
O
2
= 0,232 lb / lb udara
udara
= 0,0746 lb / ft
3
Penyelesaian :
Udara diasumsikan mengandung 21 % O
2
,
C
s,m
= C
s
x 0,5 (P
b
/P
a
+ O
t
/21)
P
a
= 14,7 psi = 1 atm
P
b
= {(15 ft / 2,3 ) + 14,7} = 21,2 lb/in
2
O
t
= {21(10,1)}/ {21(1-0,1)+79} = 19,3%
C
s,m
= 10,8 x 0,5{(21,2/14,7)+(19,3/21)}
= 12,7 mg/l
waktu, menit C
s,m
C
L
3 12,1
6 11,1
9 9,6
12 8,4
15 7,3
18 6,7
21 5,7
Dari pers. (1/V) N = dC/dt
= k
L
A/V . (C
s
C
L
)
Integrasi :
C
s
C
L
= (C
s
C
0
) e
-kla.t
k
L
.A/V = k
L
a
Atau log (C
sm
C
L
) = log (C
sm
C
0
) k
L
at/2,3
20
10
Cs
m
-C
L
0 20 6 10 14 18 22
K
La
= 2,6 jam
-1
Waktu, menit
Proses Kolam Stabilisasi Limbah
(Waste Stabilization Ponds Process)
Ciri-ciri metoda ini:
mengandalkan sinar matahari
memerlukan lahan yang luas
waktu reaksi cukup lama
Oksidasi aerobik
Tahap 1 :
seny. organik (dengan mikroorganisme)
sel baru + camp. Asam - asam organik
Tahap 2 :
camp. asam organik sel baru + CH
4
+ CO
2
+ H
2
O + . . .
Oksidasi aerobik
seny. organik + O
2
(dengan bantuan mikroorganisme)
sel + H
2
O + CO
2
+ NH
3
+ .. .
Sumber O
2
: pr. fotosintesa algae
CO
2
+ H
2
O (dengan sinar matahari dan algae)
sel algae baru + H
2
O +O
2
+
Simbiosis algae dan bakteri pada kolam
stabilisasi limbah
Jenis jenis kolam :
1. Kolam anaerobik
- Kedalaman optimal 4 meter
- Effektif untuk beban BOD tinggi
- Hasil proses oksidasi menghasilkan gas-gas
seperti CH
4
, H
2
S, dll.
- Masalah : bau, terutama jika konsentrasi sulfur
sebagai sulfat > 100 ppm
2. Kolam fakultatif
- sebagian aerobik, sebagian anaerobik
- kedalaman lebih kurang 0,3 meter
agar penetrasian sinar matahari baik
- beban organik permukaan :
= (10 Q L
i
) / A
dimana Q : debit alir limbah cair
L
i
: konsent. BOD dalam influent
A : luas permukaan
- Beban organik diizinkan ;
= 20 T 120
Dimana T : temperatur dalam
o
C
- Luas permukaan kolam :
A = {Q(L
i
L
e
)} / {18 D (1,05)
T 20
}
Dimana L
e
: konsentrasi BOD dalam effluent
D : kedalaman kolam
4. Kolam maturasi
- beroperasi secara aerobik
- terutama untuk menghilangkan bakteri
faecal
- penghilangan FC :
Dimana Ne = jumlah FC/100 ml effluent
Ni = jumlah FC / 100 ml influent
| || || |
n
mat
t b
fak
t b
an
t b
t K t K t K
Ni
Ne
*
) (
*
) (
*
) (
. 1 . 1 . 1 + + +
=
t
*
= waktu tinggal an : anaerobik
fak : fakultatif
mat : maturasi
n = jumlah kolam maturasi yang disusun seri
K
b(t)
= konstanta penghilangan FC pada
t
0
C, hari
-1
K
b(t) = 2,6 (1,19)
t-20
Faktor-faktor yang mempengaruhi
ekosistem kolam :
1. karakteristik limbah cair & fluktuasinya
2. temperatur dan radiasi sinar matahari
3. pola pertumbuhan algae
4. pola pertumbuhan mikroorganisme
Pertumbuhan algae & produksi O
2
:
Enersi rata-rata yang diterima
= enersi min. + { (enersi maks. enersi
min.) x faktor kecerahan langit }
Enersi maks. dan enersi min. : dlm tabel
Hasil penelitian :
Produksi O
2
= 1,3 produksi algae
Contoh soal :
Kolam stabilisasi limbah mengolah limbah cair
domestik dengan debit 10.000 m
3
/hari dan
kandungan BOD
5
sebesar 630 mg/l. Temperatur
operasi 20
o
C dan diinginkan BOD
5
effluent < 25
mg/l dan FC < 5000 per 100 ml sampel.
Diinginkan penggunaan kolam fakultatif dan
kolam maturasi !
Penyelesaian
Kolam fakultatif :
Mis. L
e
= 60 mg/l dan kedalaman = 1,2 m.
Luas permukaan :
A = {Q (L
i
L
e
)} / {18 D (1,05)
T 20
}
= {10.000 (630 60)} / (18.1,2.1)
= 264.000 m
2
Beban organik permukaan
= (10 Q L
i
) / A
= (10 . 10000. 630) / 264000
= 240 kg / Ha.hari
Beban organik diizinkan
= 20 T 120
= 20. 20 120 = 280 kg / hari
Rancangan memenuhi
Kolam maturasi :
Mis. Digunakan 2 kolam maturasi yang disusun
seri dengan waktu tinggal masing-masing 7 hari.
Diketahui : K
b
= 2,6
Jumlah FC/100 ml influent = 4x10
7
Waktu tinggal dalam kolam fakultatif :
= V / Q
= (264.000 x 1,2) / 10.000
= 32 hari
Jumlah FC / 100 ml effluent
= 4x10
7
/ {(1 + 2.6 x 32)(1 + 2,6 x 7)
2
}
= 1300 FC / 100 ml
Rancangan memenuhi
Mis. Kedalaman kolam = 1,2 m.
Luas permukaan kolam
= (10.000 m
3
/hari x 7 hari) / 1,2 m
= 58.000 m
2
Pengolahan tahap ketiga (lanjut)
(Tertiary treatment)
Proses ini dilakukan apabila dengan
pengolahan tahap-tahap sebelumnya
(tahap pertama dan kedua) kualitas limbah
cair olahan belum memenuhi persyaratan
yang diinginkan
Proses pada tahap ini dapat berupa proses
fisika, biologis, kimia, ataupun gabungan dari
proses-proses tersebut.
Contoh :
1. Absorbsi untuk menghilangkan senyawa
organik yang sulit dibiodegradasi
2. Stripping dengan udara untuk menghilangkan
gas tertentu yang larut dalam limbah cair
3. Filtrasi untuk menghilangkan partikel-partikel
berukuran tertentu
Penerapan operasi fisis pada pengolahan
limbah cair
Metoda Penerapan
1. Screening Menghilangkan pasir dan padatan
terendapkan
2. Comminution Menggiling padatan menjadi lebih kecil
3. Flokulasi Membentuk flok
4. Sedimentasi Mengendapkan padatan
5. Flotasi Menghilangkan padatan tersuspensi/halus
6. Filtrasi Proses penyaringan
Penerapan operasi kimia pada pengolahan
limbah cair
Metoda Penerapan
1. Pengendapan
kimia
Menghilangkan senyawa pospor dan
padatan tersuspensi
2. Adsorpsi Menghilangkan senyawa organik
3. Disinfektasi Menghilangkan organisme berbahaya
Sumber-sumber limbah padat secara
umum
Limbah padat kota: rumah tangga,
perdagangan, rumah sakit, tempat umum,
dan lain-lain.
Limbah padat industri
Limbah padat pertanian/peternakan, dan lain-
lain.
PENGELOLAAN LIMBAH
PADAT
Karakteristik komponen limbah padat:
Mudah membusuk
Mudah terbakar
Wadah bekas: drum, botol, dan lain-lain
Patogenik, toksid
Serbuk/abu
Lumpur hasil pengolahan limbah
Puing bangunan
Radioaktif, dan lain-lain
Limbah Padat kota
Timbulan dipengaruhi oleh:
Tingkat hidup masyarakat
Musim
Pola hidup dan mobilitas
Iklim dan geografi
Evolusi Timbulan
Limbah padat kota
Pengumpulan
- Dijual ibu rumah tangga
- Dijualpembantu rumah tangga
- Pemulung
- Tercecer
Daur ulang
-Dipulung pengangkut
-Dipulung petugas TPA
-Dipulung pemulung
TPA
Sifat Fisik
1. timbulan
2. komposisi
3. densitas kg/m
3
Dimana: BJ = berat jenis
W
1
= berat sampah + kontainer
W
2
= berat kontainer
V = volume kontainer
V
W W
BJ
2 1
=
4. Kadar air pada 105
o
C
Kadar air (% berat basah) =
5. Kadar abu dan materi volatil 550 600
o
C
% 100 x
awal berat
hilang akhir berat awal berat
% 100
ker
x
asal ing berat
hilang yang berat
Padatan volatil (% berat kering) =
6. Nilai kalor penting untuk insenerasi
Komposisi Kadar Air
(%)
Kadar Abu
(%)
Kalor
(kkal/kg)
- Limbah
organik
- Kertas
- Kayu
- Kain/tekstil
- Karet/kulit
- plastik
71,67
54,61
40,50
59,75
35,60
44,72
6,92
4,42
0,98
1,86
2,63
3,47
894,33
1409,07
2003,28
1480,18
2930,11
3779,23
Sifat Kimia
Kandungan karbon kandungan materi
organik 2/3 bagian dari karbon sumber
enersi
Kandungan nitrogen proses pengomposan
Penting; C/N dalam limbah padat 30/1
Kandungan fosfat proses pengomposan
Penting; C/P dalam limbah padat 90-150
pH
Pengolahan Limbah Padat
Aspek pengumpulan/penyimpanan
karakteristik limbah
Aspek pengangkutan
Aspek pengolahan, pendaurulangan dan
pemusnahan
Penanganan pendahuluan
pengelompokan limbah
Pendaurulangan limbah perlu kajian
ekonomis
Pemusnahan secara fisik, kimia, biologis
Penyingkiran ditimbun
Sampah kota di Indonesia
Tujuan pengelolaan kota yang bersih,
sehat dan teratur
Komponen pengelolaan secara umum:
a. Operasi dan manajemen
Peraturan pemerintah
Pola sistem operasional
Kapasitas kerja sistem
Lingkup kerja dan tugas
b. Institusi pengelola Dinas kebersihan kota
Otda
Keterbatasan tenaga yang sesuai
Sarana pengembangan terbatas
Sulit koordinasi
c. Aspek Teknik Operasional
Kapasitas pengelolaan yang terbatas
Program pemeliharaan alat minimum
Tenaga lepas sulit pembinaan
Sulit koordinasi siklus operasi putus
Program perencanaan dan pengendalian
minim perencanaan operasinal jangka
pendek
d. Pembiayaan
Retribusi yang terkumpul terbatas
Prioritas pengelolaan dalam dana
pembangunan rendah/kecil
e. Peran serta Masyarakat
Tingkat pendidikan tidak merata
Belum ada pola baku pembinaan
masyarakat
f. Pengaturan
Aspek ini didasarkan bahwa negara kita
adalah Negara Hukum. Masalah umum
yang sering dijumpai antara lain:
Beberapa peraturan tidak memperhatikan
kemampuan daerah setempat.
Beberapa peraturan tidak dilengkapi
petunjuk pelaksanaan.
Teknik Operasional Pengelolaan Sampah
Kota
Sistem pengumpulan sampah dikenal dengan
beberapa pola seperti:
Pola individual pengumpulan sampah dari rumah
ke rumah dengan alat angkut jarak pendek (gerobak
dan sebagainya) untuk diangkut ke penampungan
sementara; dapat pula pola ini dilakukan door-to-door
dengan truk sampah untuk langsung diangkut ke
pembuangan sampah.
Pola komunal pengumpulan smapah dari
beberapa rumah dilakukan pada satu titik pengumpul
langsung oleh penghasil sampah, untuk kemudian
diangkut ke tempat pembuangan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
sistem pengumpulan ini adalah:
Peta timbulan smapah, daerah kepadatan sampah
serta jenis sampahnya.
Kapasitas kerja komponen pengumpul smapah
Ritasi alat angkut
Frekwensi pengumpulan
Pola pengumpulan
Peta penyapuan jalan dan pembersihan selokan
Peta blok operasi
Subsistem pemindahan menerima sampah yang
berasal dari sumber, untuk kemudian diangkut
ke tempat pembuangan akhir. Dikenal dua pola,
yaitu:
Sistem ysng permanen
Sistem ysng dapat diangkat dan dipindahkan
Subsistem pemindahan mempunyai sasaran:
Sebagai peredam tingkat ketergantungan fase
pengumpulan dengan fase pengangkutan
Pos pengnedalian tingkat kebersihan wilayah yang
bersangkutan
Subsistem pengangkutan terdiri dari tiga
jenis, yaitu:
Pengangkutan dari suatu lokasi pemindahan
ke tempat pembuangan akhir
Pengangkutan dari kelompok pemindahan
menuju ke tempat pembuangan akhir
Pengangkutan dengan pola door to door.
Pemusnahan / Pengolahan Sampah /
Limbah Padat
Ada tiga metoda umum;
1. Pengolahan agar lebih mudah dalam pengelolaannya:
Penghalusan
Pemadatan
Solidifikasi/pengaplusan
proses yang biasa digunakan: teknik
termoplasti, proses dengan penyemenan
uji kualitas produk: gaya tekan, permeabilitas,
stabilitas, materi toksik
2. Pengolahan agar dihasilkan produk
bermanfaat
Pengomposan dihasilkan humus
Insenerasi dihasilkan enersi panas
Metanisasi dihasilkan gas bio
3. Pembuangan ke suatu tempat agar tidak
kontak dengan manusia
lahan urug (landfill)
laha pengolahan (land treatment)
Proses pengomposan (composting) dekomposisi
biologis dari materi organik limbah di bawah kontrol
terhadap kondisi proses yang berlangsung
Operasi pengomposan dapat berupa:
Operasi pemilahan secara fisik sehingga dapat
dipisahkan bagian samapah yang biodegradabele dan
yang non biodegradabel atau sangat sulit terurai
secara biologis
Berbagai teknik yang berbeda yang memungkinkan
berlangsungnya fermentasi aerob dari materi organik
biodegradabel.
Operasi penghalusan kompos sesuai kebutuhan yang
diperlukan oleh pemakai kompos
Penyimpanan dan pematangan (maturasi) kompos
Pengomposan
Fungsi :
sebagai pupuk organik
memperbaiki struktur tanah
meningkatkan kemampuan tanah menyerap air dan
zat hara lain.
Metoda
1. Secara anaerobik
2. Secara aerobik :
tidak menimbulkan bau
lebih cepat
temperatur tinggi bakteri patoge mati
lebih hieginis
Prinsip pengomposan
sampah disortir dari bahan non-organik
Dibuat tumpukan, dipadatkan sehingga stabil
dan porous, disiram
Tumpukan dibalik pada hari ke 11 dan
seterusnya dengan kelipatan 5 sampai ke 41
Hari ke 46 kompos matang
Land Disposal
Dikenal pengolahan dengan cara:
Land treatment (lahan sanitasi) aplikasi
limbah dipermukaan tanah
Land fill (lahan urug) pengurugan limbah di
dalam tanah
Land disposal Pemusnahan/penyingkiran
limbah ke dalam tanah
yang banyak diterapkan
untuk limbah padat.
Land treatment (Lahan sanitasi)
Metoda ini memperhitungkan kemampuan asimilasi
tanah untuk:
Mengurangi daya toksik
Mendegradasi (kimia, biologis)
Menahan (immobilize) pencemar yang terdapat
dalam limbah
Untuk mengoptimumkan proses biologis dan kimiawi
serta memanfaatkan kapasitas assimilasi tanah,
maka limbah dimasukkan secara berkala sesuai
kemampuan tanah tersebut.
Dikenal konsep land limiting constituent (LLC)
akan berkaitan erat dengan beberapa hal
seperti:
Batas kemampuan mikrobiologis tanah untuk
menguraikan limbah tersebut (untuk komponen
limbah biodegradable),
Batas akumulasi limbah yang mungkin sehingga tidak
menimbulkan efek phytotoxic/racun terhadap
tanaman (untuk komponen limbah yang immobile dan
nondegradable)
Batas standard kualitas air tanah (bagi komponen
limbah yang mobile)
Limbah padat mempunyai ciri-ciri umum:
Mudah terurai
Mudah ternetralkan (assam/basa)
Mudah dibuat menjadi kurang mobile
Mudah dibuat menjadi kurang toksik
Maka akan dapat disingkirkan dengan
metode land treatment
Beberapa operasi umum yang perlu mendapat
perhatian:
Limpasan hujan dicegah masuk dalam bagian yang
aktif.
Limpasan dari bagian aktif harus dikumpulkan dan
ditangani secara khusus.
Memerlukan analisis periodik dari limbah yang akan
dibuang
Tidak berada dalam zona pengembangan sumber
makanan.
Perlu program pasca operasi.
Lahan Urug (Land Disposal)
Landfill metoda pengurugan limbah ke dalam
tanah, kemudian dilakukan pemadatan sebelum
limbah tersebut ditutup setiap hari dengan tanah
penutup.
Penyingkiran dan pemusnahan limbah ke
dalam tanah (land disposal) merupakan cara
yang selalu disertakan dalam pengelolaan
limbah, karena pengolahan limbah tidak dapat
menuntaskan permasalahan yang ada.
Lahan urug tetap merupakan bagian yang sampai saat
ini sulit untuk dihilangkan dalam pengelolaan limbah,
antara lain karena alasan-alasan:
Teknologi pengelolaan limbah seperti reduksi di
sumber, daur ulang, daur pakai atau minimasi limbah,
tidak dapat menyingkirkan limbah secara menyeluruh.
Tidak semua limbah mempunyai nilai ekonomis untuk
di daur ulang
Teknologi pengolahan limbah seperti insinerator atau
pengolahan secara biologi atau kimia tetap
menghasilkan residu yang harus ditangani lebih lanjut.
Kadangkala sebuah limbah sulit untuk diuraikan
secara biologis, atau sulit untuk dibakar, atau sulit
untuk diolah secara kimia.
Timbulan limbah tidak dapat direduksi sampai tidak
ada sama sekali.
Jenis lahan urug:
Metode Area
Dapat diterapkan pada site yang relatif datar
Sampah membentuk sel-sel sampah yang
saling dibatasi oleh tanah penutup
Setelah pengurugan akan membentuk slope
Penyebaran dan pemadatan sampah
berlawanan dengan kemiringan
Metode Slope (ramp)
Sebagian tanah digali
Sampah kemudian diurug pada tanah
Tanah penutup diambil dari tanah galian
Setelah lapisan pertama selesai, operasi
berikutnya seperti metode area
Metode Parit (trench)
Site yang ada digali, sampah ditebarkan
dalam galian, dipadatkan dan ditutup harian.
Digunakan bila air tanah cukup rnedah
sehingga zone non aerasi di bawah landfill
cukup tinggi (> 1,5 m)
Operasi selanjutnya seperti metode area.
Metode pit/canyon/quarry
Pemanfaatkan cekungan tanah yang ada
(misalnya bekas tambang)
Pengurugan sampah dimulai dari dasar
Penyebaran dan pemadatan sampah seperti
metode area
Dilihat dari sudut penanganan sampah baik sebelum
diurug maupun setelah diurug, maka di Perancis
dikenal beberapa jenis aplikasi lahan urug, yaitu:
Dilihat dari sudut prapengolahan sampah sebelum
diurug.
Sampah tanpa pemotongan
Sampah dengan pemotongan (shredding)
Sampah dibuat dalam balok-balok sampah
(baling)
Dilihat dari sudut penanganan sampah di area
pegunungan
Secara tradisional
Dengan alat berat pemadat (compactor)kaki
kambing
Pengoperasian Lahan Urug
Fungsi lahan urug seperti:
Pengurangan masuknya air eksternal pada area penimbunan,
misalnya dengan pengaturan limpasan melalui drainase.
Pengintegrasian antara tanah penutup dan penutup final.
Pengendalian erosi permukaan.
Pencegahan pengaliran air tanah dan sekitarnya menuju
timbunan
Pengurangan/pencegahan pencemaran pada air tanah
misalnya dengan pemasangan lapisan dasar yang
terintegrasi
Pengumpulan dan pengolahan lindi
Pengontrolan emisi gas dengan perlengkapan penangkap
gas.
Pencegahan bau, kebakaran dan ledakan dengan pengadaan
ventilasi dan aplikasi tanah penutup.
Skema sel dalam lahan urug
Biodegradasi Materi Organik pada Sebuah
lahan urug dan Potensi Gas Bio
Tolak ukur yang biasa digunakan untuk memantau
kestabilan sebuah lahan urug
Kandungan lindi yang telah sesuai dengan baku
mutu yang berlaku
Potensi gas bio yang telah dapat diabaikan
Penurunan (settlement) timbunan yang dapat
diabaikan
Pada awalnya sampah yang ditimbun akan mengalami
proses degradasi secara aerob
Kondisi aerob sebetulnya diinginkan, mengingat
membawa keuntungan antara lain:
Relatif tidak menimbulkan bau
Proses degradasi lebih cepat
Lindi yang dihasilkan akan lebih ringan
Memungkinkan kondisi eksotermis
Tetapi sejalan dengan teknik operasional yang sampai
saai ini dianut, yaitu sampah ditimbun lapis berlapis dan
setiap periode tertentu ditutup dengan tanah penutup,
maka kondisi aerob tidak dapat lama bertahan dalam
sebuah lahan urug. Kondisi yang paling dominan
kemudian adalah kondisi anaerob.
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap
proses dekomposisi adalah:
a. Temperatur
Produksi gas bio mengenal 2 zone temperatur
optimum sesuai aktivitas 2 mikroflora yang berbeda,
yaitu:
Antara 36o 40oC dikenal sebagai zone mesofilik
Antara 55o 60oC dikenal sebagai zone termofilik
b. Kelembaban
Laju produksi gas bio akan bertambah dengan
bertambahnya kelembaban
c. Faktor pH dan potensi redoks
Produksi metan akan baik pada kondisi netral.
Turunnya pH, misalnya akibat akumulasi asam-asam
volatil akan merupakan penghalang bagi aktivitas
metanogenes.
d. Nutrisi
Untuk hidup dan pertumbuhannya, bakteri
menggunakan kira-kira 30 bagian karbon untuk 1
bagian nitrogen. Nilai C/N biasanya terletak antara
20-35, sedang nilai C/P yang ideal terletak sekitar
150.
e. Pemotongan
Dalam reaktor anaerob biasa, pengurangan ukuran
materi biasanya akan mendorong lebih banyak
produksi metan karena adanya peningkatan luas
permukaan substrat yang dapat kontak dengan
mikroorganisme, misalnya akibat pemotongan bahan
tersebut.
f. Densitas
De Walle (1978) menyatakan bahwa kenaikan
densitas timbunan sampah akan menurunkan luas
permukaan efektif yang dapat kontak dengan
mikroorganisme, sehingga akan mengurangi produksi
gas bio. Sebaliknya Buivid et al (1981) berpendapat
bahwa pemadatan timbunan sampah justru akan
lebih mempercepat produksi metan karena
mengurangi masuknya oksigen ke dalam sistem.
Kedua pendapat tersebut belum pernah dikonfirmasi
dalam lahan urug yang dioperasikan pada kondisi
berbeda secara nyata di lapangan.
Pengolahan limbah dengan Insinerator
Insenerasi proses konversi limbah organik
menjadi limbah anorganik dengan
menggunakan oksidasi termal pengurangan
massa, bakteri, virus serta materi toksik yang
terkandung sebelumnya.
Insinerator merupakan teknologi proses termal
yang paling sering digunakan untuk mengolah
limbah organik berbahaya, karena teknologi ini
memungkinkan destruksi yang tinggi dalam
banyak jenis limbah organik, walaupun pada
saat yang sama dikeluarkan pencemar udara.
Secara umum tahapan proses dari sebuah
insinerator dapat dipisahkan menjadi
beberapa langkah, yaitu:
Penyiapan limbah
Pemasokan limbah
Pembakaran limbah
Pengolahan gas dan partikulat hasil
pembakaran
Penanganan residu abu
Suatu insinerator yang baik akan
mengurangi volume limbah sampai 8 -
95%, sedang pengurangan berat dapat
mencapai 70 80%.
Sebuah insinerator biasanya terdiri dari
elemen-elemen dasar, termasuk sistem
penyuplaiannya, yaitu:
Satu atau lebih ruang pembakaran (tunggu)
Sistem cerobong gas
Sistem pembuangan akhir abu
Perlengkapan tambahan dapat berupa:
Pemotongan limbah
Pemilah limbah ( dihulu atau di hilir sistem)
Pengontrol pencemaran udara
Sistem penangkap panas yang dihasilkan (recovery)
Guna menjamin pembakaran sempurna perlu
diperhatikan tiga hal sebagai berikut:
Waktu operasi, dipengaruhi oleh kadar air dan ukuran
sampah.
Turbulensi (olakan), hal ini berkaitan dengan
pencampuran dalam ruang pembakaran.
Temperatur
Udara/c.w
Gas cerobong asap
Tungku
Residu
IPAL
Debu
Abu, dsb
Air
Limbah
cair
Residu
padat
Lahan
urug
Udara
Hasil
bakar
Insinerator teknologi proses termal
Limbah
olahan
Sludge (Lumpur, endapan)
Sludge
Pengolahan awal
(grinding,
blending)
Thickening
(sentrifugasi)
Stabilisasi
(digestion)
Conditioning
(heat treatment) Disinfektasi
Dewatering
(drying bed)
Composting
Thermal
reduction
(inceneration)
Disposal
(landfill, reuse)
Komposisi sludge
Komponen Ses. Pengolahan
awal
Ses. Digestion
Padatan total (PT), %
Padatan menguap, % PT
Lemak, % PT
Protein, % PT
pH
Asam organik
(sbg mg/l as. Asetat)
2,0 8,0
60 80
6,0 30
20 30
5 - 8
200 - 2000
6,0 12,0
30 60
5,0 20,0
15 20
6,5 7,5
100 - 600
Hubungan massa dan volume
Dimana; M
s
= massa padatan
M
f
= massa padatan mineral
S
s
= spesifik graviti padatan
S
f
= spesifik graviti mineral
w
= densitas air
M
v
= massa padatan teruapkan
S
v
= spesifik graviti padatan teruapkan
Volume sludge:
Dimana: S
Sl
= spesifik graviti sludge
P
s
= % padatan
w v
v
w f
f
w s
s
S
M
S
M
S
M
+ =
s Sl w
s
P S
M
V
=
Contoh soal:
Tentukan volume cairan sebelum dan sesudah
proses digestion dan % pengurangannya pada
sludge sebanyak 500 kg (basis kering) dengan
data sebagai berikut;
Komponen Awal Ses.digesti
on
% padatan
Senyawa menguap, %
Sg mineral
Sg padatan menguap
5
60
2,5
1,0
10
60 (hilang)
2,5
1,0
w v
v
w f
f
w s
s
S
M
S
M
S
M
+ =
76 , 0
0 , 1
6 , 0
5 , 2
4 , 0 1
= + =
s
S
32 , 1
95 , 0
32 , 1
05 , 0 1
+ =
sl
S
05 , 0 01 , 1 . / 1000
500
3
x m kg
Penyelesaian;
Jika
w
= 1100 kg/m
3
Awal
Sehingga S
s
= 1,32
S
Sl
awal =
S
sl
= 1,01
Volume sludge awal =
= 9,9 m
3
% 100
300 ) 4 , 0 ( 500 ) 4 , 0 (
) 500 6 , 0 ( 4 , 0
x
x
+
625 , 0
0 , 1
375 , 0
5 , 2
625 , 0 1
= + =
s
S
Ses. Digestion:
% senyawa menguap =
= 37,5%
S
l
= 1,6
0 , 1
9 , 0
6 , 1
1 , 0 1
+ =
sl
S
10 , 0 04 , 1 . / 1000
00 ) 300 ( 4 , 0 ) 500 ( 4 , 0
3
x m kg
+
% 7 , 68 % 100
9 , 9
1 , 3 9 , 9
=
x
S
Sl
ses. digestion
S
Sl
= 1,04
Volume sludge ses. digestion =
= 3,1 m
3
Persentase pengurangan;
PENCEMARAN UDARA
Troposfir: temp turun ( 6,5
o
C) setiap naik 1 km
dari permukaan bumi
Stratosfir:
temperatur naik dengan ketinggian permukaan
ditemukan gas ozon
Mesosfir: temperatur turun dengan naiknya
ketinggian
Mesosfir
Stratopause
Stratosfir
Tropopause
Troposfir
50
15
Tinggi (km)
Komposisi udara
Campuran gas (N
2
, O
2
, Ar, CO
2
, O
3
, uap air)
Komposisi tidak tetap cuaca, temperatur, lokasi
Fungsi udara atau atmosfir :
Sebagai kondenser dalam siklus hidrologi
Sebagai penyerap emisi sinar kosmis, hanya radiasi
dengan = 300 2500 nm
dan = 0,01 40 m yang ditransmisikan
Sebagai sumber oksigen (O
2
) dan karbon dioksida
(CO
2
)
Sebagai penyeimbang panas bumi
Komposisi atmosfir :
N
2
: 78,08 %
O
2
: 20,95 %
Ar : 0,934 %
CO
2
: 0,034 %
H
2
O : 1 5 %
Gas-gas mulia : Ne, He, Kr, Xe
Fungsi udara atau atmosfir :
Sebagai kondensor dalam siklus hidrologi
Sebagai penyerap emisi sinar kosmis, hanya
radiasi dengan = 300 2500 nm dan =
0,01 40 m yang ditransmisikan
Sebagai sumber oksigen (O2) dan karbon
dioksida (CO2)
Sebagai penyeimbang panas bumi
Klasifikasi senyawa pencemar udara :
A. Berdasarkan sumbernya
a. pencemar primer SO
2
, HC
b. pencemar sekunder ozon (O
3
), per-
oksi asetil nitrat (PAN)
B. Berdasarkan komposisi kimianya
a. pencemar organik alkohol,ester,eter
b. pencemar anorganik CO, H
2
S, dll
C. Berdasarkan bentuknya :
a. bentuk partikulat debu, asap, abu
b. bentuk gas HC, nitrogen oksida NO
Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas udara :
1. Temperatur
2. Ketinggian
3. Stabilitas atmosfir
4. Kelembaban udara
5. Arah dan kecepatan angin
Kualitas udara akan stabil jika sejumlah massa udara
yang naik pada suatu ketinggian lebih berat dan
suhunya lebih rendah dari udara sekitarnya.
Kualitas udara menjadi tidak stabil jika sejumlah
massa udara yang naik lebih ringan dan suhunya lebih
tinggi dari udara sekitar sehingga akan terus bergerak
atau berpindah
Tekanan atmosfir :
P
h
= P
0
e
- Mgh / RT
P
h
: tekana pada ketinggian h
P
0
: tekanan pada ketinggian nol
M : berat molekul udara rata-rata
g : percepatan gravitasi
R : konstanta gas
T : temperatur absolut (
0
K)
Reaksi-reaksi di atmosfir
1. Reaksi fotokimia
- melalui pembentukan molekul terek -
sitasi yang reaktif dan tidak stabil
- contoh :
NO
2
+ h NO
2
*
h : tetapan Planck = 6,62 x 10
-27
erg.dtk
: frekwensi cahaya terserap
2. Reaksi fotoionisasi menghasilkan
elektron dan ion positip
a. Reaksi oksigen atmosferik
- atom oksigen O
O
2
+ h O + O
- atom oksigen tereksitasi
O
3
+ h O
*
+ O
2
O
3
O
2
+ O
*
- Ozon ( O
3
)
> terutama di daerah stratosfir
> berfungsi menyerap radiasi ultraviolet
yang berbahaya
> dihasilkan melalui reaksi fotokimia sbb.
O
2
+ h O + O
O + O
2
+ M M + O
3
dimana M adalah O
2
atau N
2
> secara termodinamika tidak stabil
> pada dosis tinggi bersifat toksik, merusak
mata, mengganggu pernafasan
- Ion Oksigen
> dihasilkan oleh radiasi sinar ultraviolet
atau oleh absorbsi sinar ultraviolet
b. Reaksi nitrogen atmosferik
> pada ketinggian > 100 km dihasilkan
ion N
2
+
> pada ketinggian 50 85 km : NO
+
c. Reaksi karbon dioksida atmosferik
> konsentrasi di atmosferik relatif kecil
> pada bagian atas atmosfer, terjadi foto
dissosiasi CO
2
menjadi CO
d. Partikel dalam atmosfir
> terutama pada daerah troposfir
> fungsi : sebagai nuklei (inti) pembentuk-
an kristal es dan titik-titik air
> partikel Aitken : aerosol dari bahan ala
miah (asap, abu, dll) dengan d < 0,2 m
Karbon monoksida (CO)
> di atmosfir : 1 ppm
> sumber : - reaksi oksidasi metana oleh ra-
dikal hidroksil
- degradasi klorofil tumbuhan
- proses pembakaran pada me
sin bakar
- reaksi fotodissosiasi CO
2
Penghilangan CO di atmosfir :
> dengan reaksi radikal hidroksil (HO*) dan
hidroperoksil (HO
2
*
) sbb.
HO
*
+ CO CO
2
+ H
H + O
2
+ M HO
2
*
+ M
HO
2
*
+CO HO
*
+ CO
2
HO
2
*
+ NO HO
*
+ NO
2
HO
2
*
+ HO
2
*
H
2
O
2
+ O
2
H
2
O
2
+ h 2 HO
*
> dengan mikroorganisme tanah
> dengan menggunakan campuran udara de
ngan bahan bakar relatif tinggi, mis. 16/1
> Menggunakan konverter katalitik :
CO CO
2
Pengaruh konsentrasi COHb di dalam darah
terhadap kesehatan manusia
Konsentrasi COHb
dalam darah (%)
Pengaruhnya terhadap kesehatan
< 1.0
1.0 2.0
2.0 5.0
> 5.0
10.0 80.0
Tidak ada pengaruh
Penampilan agak tidak normal
Pengaruhnya terhadap sistem saraf sentral,
reaksi panca indra tidak normal, benda
terlihat agak kabur.
Perubahan fungsi jantung dan pulmonari
Kepala pening, mual, berkunang-kunang,
pingsan, kesukaran bernafas, kematian
Pengaruh jenis aktivitas fisik dan waktu terhadap
konsentrasi COHb di dalam darah
Sulfur senyawa pencemar : SO
2
, H
2
S, se-
nyawa sulfit dan sulfat
> sumber SO
2
:
a. aktivitas mikroorganisme pada proses
aerobik : H
2
S SO
2
b. bahan bakar batu bara
c. di atmosfir melalui reaksi H
2
S dengan
radikal HO
*
dan HS
*
Penghilangan SO
2
:
> dengan proses desulfurisasi
contoh : pembakaran batu bara dengan
reaktor yang menggunakan batu kapur a-
tau dolomit yang akan menyerap SO
2
> dengan sistem penyaring pada alat peng-
hasil SO
2
menggunakan kapur / dolomit
Pengaruh SO2 terhadap manusia
Konsentrasi
(ppm)
Pengaruhnya
3 - 5 Jumlah terkecil yang dapat dideteksi dari baunya.
8 12 Jumlah terkecil yang segera mengakibatkan iritasi
tenggorokan
20 Jumlah terkecil yang segera mengakibatkan iritasi
mata
Jumlah terkecil yang segeera mengakibatkan batuk
Maksimum yang diperbolehkan untuk kontak dalam
waktu lama
50 100 Maksimum yang diperlukan untuk kontak dalam
waktu singkat (30 menit)
400 500 Berbahaya meskipun kontak secara singkat
Oksida nitrogen :
- di atmosfir sebagai N
2
O, NO dan NO
2
- N
2
O : dapat berfungsi sebagai anaestetik
dan tidak reaktif
- NO : terbentuk dari proses pembakaran
batu bara dan minyak bumi serta se-
cara alami pada temperatur tinggi da
ri N
2
dan O
2
- NO
2
: amat reaktif
- NO
x
: merupakan campuran dari N
2
O dan
NO
2
dalam atmosfir yang berasal da
ri pembakaran bahan bakar
Pengendalian senyawa NO
x
:
a. menggunakan udara berlebih pada pro-
ses pembakaran
b. proses katalitik , dengan resiko menghasilkan
senyawa COS yang toksik
Siklus NO
2
fotolitik
Senyawa gas klor dan fluor :
- Cl
2
: > pada industri sebagai desinfektan
dan untuk proses pemutihan
> toksik, reaktif, oksidator kuat
- F
2
: > dapat merusak tanaman (klorosis)
> toksisitas F
2
> HF
CFC (kloro fluoro karbon) ~ Freon
CFC 12 (Cl
2
CF
2
)
CFC 11 (Cl
3
CF)
Pada lapisan stratosfir terjadi proses foto-
deomposisi sbb.
Cl
2
CF
2
+ h Cl
*
+ ClCF
2
*
Cl
*
+ O
3
CLO
*
+ O
2
Senyawa pencemar organik :
Senyawa pencemar organik yang terbanyak adalah
senyawa hidrokarbon dari proses pembakaran. Senyawa
ini dapat mengakibatkan pembentukan kabut (smog).
Partikel
Komponen partikel dan bentuk yang umum terdapat di
udara:
Komponen Bentuk
Karbon
Besi
Magnesium
Kalsium
Aluminium
Sulfur
Titanium
Karbonat
Silikon
Fosfor
Kalium
Natrium
Lain-lain
Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
MgO
CaO
Al
2
O
3
SO
2
TiO
2
CO
3
SiO
2
P
2
O
5
K
2
O
Na
2
O
-
Pencemar udara :
1. Pencemar primer : bentuk tidak berubah
seperti saat dibebaskan mula-mula
Contoh : CO
2
, CO, NO
x
2. Pencemar sekunder : bentuk telah berubah karena
hasil reaksi di atmosfir (mis. reaksi fotokimia, reaksi
oksidasi katalitis)
Contoh : reaksi pembentukan ozon yang
merupakan reaksi fotokimia senyawa HC di udara
dengan NO
x
Pengaruh senyawa pencemar di udara terhadap
lingkungan :
1. Pengaruh terhadap benda mati
mis. SO
2
- karat pada logam
- perubahan warna gedung
2. Pengaruh terhadap kesehatan manusia
mis. CO berikatan dengan Hb membentuk se-
nyawa karboksi haemoglobin
NO
x
merusak sistem syaraf
HC - benzena C
6
H
6
pada 100 ppm : iritasi
pada 20.000 ppm : kematian
- toluena C
7
H
16
pada 600 ppm : kehilangan
koordinasi
Sumber pencemar udara :
1. Udara dalam ruangan
a. asbes kanker paru
Sumber pencemar udara :
1. Udara dalam ruangan
a. Asbes kanker paru
b. Radon sistem penafasan
c. Formaldehid kayu lapis, dll.
d. Senyawa organik menguap (VOC)
e. Pestisida, dll.
2. Udara di luar ruangan
Mis. CO, HC, SO
2
, H
2
S, dll.
3. Kabut asap
a. Kendaraan bermotor HC dan oksida
nitrogen
b. Pembentukan radikal organik bebas
O + RH R
*
+ senyawa lain
O
3
+ RH R
*
+ senyawa lain
c. Penyebaran rantai cabang
NO + ROO
-
NO
2
+ senyawa lain
NO
2
+ R
*
suatu produk mis. PAN
(Peroksi Asetil Nitrat)
Hubungan nilai PSI (Pollutant Standard
Index) dengan kesehatan :
Nilai PSI Berbahaya Efek Kesehatan Peringatan
>400 Berbahaya Kesehatan
menurun yang
mempengaruhi
aktivitas normal
Semua orang
harus tetap di
rumah
300 -399 Berbahaya Kesehatan
menurun, penyakit
tertentu terjadi
Penduduk
dilarang keluar
rumah
Nilai PSI Berbahaya Efek Kesehatan Peringatan
200 299 Sangat tidak
sehat
Menurunkan toleransi
penduduk berpenyakit
jantung, paru-paru
Orang tua dan
muda
berpenyakit
jantung, paru-
paru tetap di
rumah
100 -199 Tidak sehat Terjadi gejala
rangsangan pada orang
peka terhadap penyakit
tertentu
Penduduk
dengan
gangguan
saluran
pernafasan tetap
di rumah
50 99 Sedang
0 49 Baik
Nilai PSI Berbahaya Efek Kesehatan Peringatan
200 299 Sangat tidak
sehat
Menurunkan toleransi
penduduk berpenyakit
jantung, paru-paru
Orang tua dan
muda
berpenyakit
jantung, paru-
paru tetap di
rumah
100 -199 Tidak sehat Terjadi gejala
rangsangan pada orang
peka terhadap penyakit
tertentu
Penduduk
dengan
gangguan
saluran
pernafasan tetap
di rumah
50 99 Sedang
0 49 Baik
Beberapa isu penting :
1. Efek gas rumah kaca
akibat kenaikan kandungan CO
2
di atmosfir,
sehingga mengakibatkan temperatur permukaan
bumi meningkat.
Transformasi sinar radiasi yang terjadi pada
permukaan bumi
2. Pola inversi temperatur
adanya penumpukan senyawa pencemar pada lapisan
atmosfir tertentu mengakibatkan peningkatan aktivitas
fotokimia sehingga sirkulasi udara secara vertikal
terhambat
3. Penipisan lapisan ozon
secara alami ozon terbentuk pada lapisan
stratosfir
fungsi : menyerap radiasi sinar matahari
yang dapat membahayakan makhluk hidup
hasil penelitian :
1 atom klor dapat merusak > 100.00
molekul O
3
Penyebab utama penipisan lapisan ozon
adalah senyawa CFC (Chloro Fluoro Carbon)
yang sangat stabil, tidak mudah terbakar dan
digunakan sebagai refrigeran, aerosol, dll.
Senyawa lain yang bersifat merusak ozon :
- CCl
4
- CHCCl
3
- CF
2
Br
Dampak penipisan lapisan ozon :
a. Terhadap kesehatan manusia : kanker kulit,
katarak mata, penurunan ketahanan tubuh.
b. Terhadap tanaman : penurunan laju proses
fotosintesis
c. Terhadap bangunan : merusak warna/ cat
d. Terhadap lingkungan : peningkatan suhu
Senyawa alternatif pengganti CFC : senyawa
HGC ( Hidro Fluoro Carbon ) namun
penggunaannya dibatasi karena efek rumah
kaca
4. Hujan asam (Acid Rain)
karena senyawa pencemar
mengandung senyawa asam seperti SO
4
=
,
Cl
-
, dll. yang turun bersama hujan.
Akibat : kerusakan pada daun tanaman
Upaya pengendalian pencemaran udara :
1.Sumber bergerak
a. Penggunaan BBM tanpa Pb dan S rendah
b. Diversifikasi enersi sebagai BBM
c. Penggunaan alat kontrol emisi gas se
perti catalytic convertor
d. Monitoring kualitas udara secara teratur
dengan menerapkan sistem PSI
2. Sumber tidak bergerak
a. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih
dan pengendalian partikel pencemar udara
dengan alat seperti scrubber, precipitator, dll.
b. Pengendalian pencemar seperti SO
2
dan
NO
x
dengan cara penggunaan bahan bakar
dengan S rendah, meninggikan cerobong,
menggunakan alat desulfurisasi dan denitrifikasi
Penanggulangan :
1. Pendekatan teknologis
2. Pendekatan planologis, mis. Penataan
lingkungan fisik
3. Pendekatan administratif, mis. melalui
penegakan hukum (law enforcement)
4. Pendekatan edukatif, mis. Melalui
pembinaan masyarakat
You might also like
- Alat Transportasi FluidaDocument52 pagesAlat Transportasi FluidaSerbio GalihNo ratings yet
- Rawatan Air Mentah (Air Terawat)Document13 pagesRawatan Air Mentah (Air Terawat)palong5759No ratings yet
- Tinjauan Pustaka AirDocument3 pagesTinjauan Pustaka AirdesitanuramyNo ratings yet
- Mochamad Faizal AmirDocument4 pagesMochamad Faizal AmirHikmah Fatwa Nurodin100% (1)
- Laporan Koagulasi FlokulasiDocument24 pagesLaporan Koagulasi FlokulasiAfifah Nur AimanNo ratings yet
- Pemilihan ImpellerDocument20 pagesPemilihan ImpellerLaila SyafitriNo ratings yet
- AGITASIDocument26 pagesAGITASIEsterNo ratings yet
- Laporan Acara 1 (Pengomposan Bahan Organik)Document7 pagesLaporan Acara 1 (Pengomposan Bahan Organik)nopyarti dewiNo ratings yet
- Laporan Praktikum, Penetapan Kadar Zat OrganikDocument14 pagesLaporan Praktikum, Penetapan Kadar Zat OrganikHendro TonapaNo ratings yet
- CodDocument13 pagesCodbenevaness12No ratings yet
- Rekling Observasi Ipal BojongsoangDocument27 pagesRekling Observasi Ipal BojongsoangAji Muhammad NizarNo ratings yet
- Absorpsi Kujang 1BDocument18 pagesAbsorpsi Kujang 1Bb_dragonsNo ratings yet
- Efek Panas TermodinamikaDocument28 pagesEfek Panas TermodinamikaHabib Maulana Yasminto0% (1)
- Rawatan Air BoilerDocument7 pagesRawatan Air BoilerMahfuzah Mustapha100% (1)
- Pelunakan AirDocument19 pagesPelunakan AirDesi SulistyowatiNo ratings yet
- ACROLEINDocument28 pagesACROLEINRosaNo ratings yet
- Bab06KimiaDasar KesetimbanganKimiaDocument58 pagesBab06KimiaDasar KesetimbanganKimiaWildan NaufalNo ratings yet
- FiltrasiDocument23 pagesFiltrasilailillutfiaNo ratings yet
- Kelarutan CaO Dalam AirDocument1 pageKelarutan CaO Dalam AirPutriSekarAyuNo ratings yet
- Neraca MassaDocument30 pagesNeraca MassaSukmaning Syahri67% (3)
- Laporan SPAL Drainase TrisaktiDocument86 pagesLaporan SPAL Drainase Trisaktivansca ditria PribadiNo ratings yet
- Kuliah 4. SentrifugasiDocument21 pagesKuliah 4. Sentrifugasidedi saputraNo ratings yet
- Matlab Tugas 4Document11 pagesMatlab Tugas 4WisnuNo ratings yet
- Distilasi - McCabe Thiele-Mustain ZamhariDocument32 pagesDistilasi - McCabe Thiele-Mustain ZamhariamaliaNo ratings yet
- Definisi FlokulatorDocument4 pagesDefinisi FlokulatorAdinda Wijaya Hartanti PutriNo ratings yet
- BiodieselDocument4 pagesBiodieselmerry rachmawatiNo ratings yet
- Laporan KP Pt. Rapp Almost DonedocxDocument69 pagesLaporan KP Pt. Rapp Almost Donedocxraynanda pratamaNo ratings yet
- Proposal Penelitian Produksi Edible Film Berbahan Baku Pati Kulit Singkong Dalam Rangka Memperpanjang Umur Simpan Buah Sawo.Document44 pagesProposal Penelitian Produksi Edible Film Berbahan Baku Pati Kulit Singkong Dalam Rangka Memperpanjang Umur Simpan Buah Sawo.Renaldy RizkyNo ratings yet
- Absorpsi (Perhitungan)Document14 pagesAbsorpsi (Perhitungan)HettiHerliani100% (1)
- Laporan KP Detta RevisiDocument182 pagesLaporan KP Detta RevisiBernadetta Catelya ChristiantiNo ratings yet
- (#05) - Kuliah IV&v - Contoh Soal 4 & Packed ColumnDocument27 pages(#05) - Kuliah IV&v - Contoh Soal 4 & Packed ColumnMarcel MrcNo ratings yet
- Hubungan Parameter Air Limbah COD, BOD Dan TSSDocument1 pageHubungan Parameter Air Limbah COD, BOD Dan TSSMuhammad Faiz AdjitaNo ratings yet
- Penanganan Limbah GasDocument4 pagesPenanganan Limbah GasSonia WImarselaNo ratings yet
- Kriteria Disain KoagulasiDocument6 pagesKriteria Disain KoagulasiNadya Hermantika Sari100% (1)
- Laporan Kerja Praktek Petrokimia GresikDocument134 pagesLaporan Kerja Praktek Petrokimia GresikMuhammad NoorNo ratings yet
- Sedimentasi 8ADocument31 pagesSedimentasi 8Adiyah ayu sariNo ratings yet
- Laporan Observasi PdamDocument47 pagesLaporan Observasi PdamAzmi ZoumaNo ratings yet
- Materi KPR 1 Reaktor 1 2023Document40 pagesMateri KPR 1 Reaktor 1 2023Ridha RahmawatiNo ratings yet
- Diagram Alir Percobaan Pewarna MakananDocument4 pagesDiagram Alir Percobaan Pewarna MakananMuhamadNurmajidNo ratings yet
- Rancang Bangun Hot Press Pelepah Pinang Skla Rumah TanggaDocument68 pagesRancang Bangun Hot Press Pelepah Pinang Skla Rumah Tanggahengky.tm21No ratings yet
- Perancangan Alat HeaterDocument7 pagesPerancangan Alat HeaterMaria Kristiani PasaribuNo ratings yet
- Iwk Dza Dan ShaDocument12 pagesIwk Dza Dan ShaSharifah NajihaNo ratings yet
- Rawatan AirDocument7 pagesRawatan AiranaNo ratings yet
- Proses Rawatan AirDocument3 pagesProses Rawatan AirmrsifuNo ratings yet
- Kualiti AirDocument8 pagesKualiti AirTn FaizNo ratings yet
- Isu Persekitaran Krisis Bekalan Air BersihDocument11 pagesIsu Persekitaran Krisis Bekalan Air BersihMohd RaziNo ratings yet
- Building Services 1Document39 pagesBuilding Services 1Mohd Karafi Md SallehNo ratings yet
- Sistem Bekalan Air Sejuk 1Document72 pagesSistem Bekalan Air Sejuk 1Eitah Mahadi100% (2)
- Isu Persekitaran Krisis Bekalan Air BersihDocument11 pagesIsu Persekitaran Krisis Bekalan Air Bersihnuwa1050% (2)
- Buku Panduan Bekalan Air Ir ZulfakarDocument166 pagesBuku Panduan Bekalan Air Ir ZulfakarSaiful Lizan Mohd Lajis100% (1)
- Sema RangDocument20 pagesSema Rangmanusia biasaNo ratings yet
- Rawatan AirDocument29 pagesRawatan Airfarahazura100% (1)
- Sistem Buangan Air SisaDocument16 pagesSistem Buangan Air SisaYat KkbtNo ratings yet
- Bekalan AirDocument163 pagesBekalan Airtunperak1667% (3)
- Loji Rawatan Air Sungai TeripDocument7 pagesLoji Rawatan Air Sungai TeripDonovan DuranNo ratings yet
- Topik 5 - Rawatan Air Sisa (16 Nov) BHG 1Document16 pagesTopik 5 - Rawatan Air Sisa (16 Nov) BHG 1Princess FiejahNo ratings yet
- Folio Sains 2016Document32 pagesFolio Sains 2016nabilah100% (1)
- Sce 3114 Sains Teknologi Dan MasyarakatDocument19 pagesSce 3114 Sains Teknologi Dan MasyarakatMeor Muhammad HafizalNo ratings yet